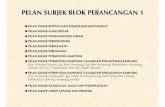Morphological, molecular and MALDI-TOF MS identification of ...
Makalah kel blok 19 tof
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Makalah kel blok 19 tof
Tetralogi Fallot pada AnakYudia Mahardika (102009028)
Sisilia Dina Mariana (102009147)
Lanny Ardianny(102011425)
Angelia Marchely Felicita (102012075)
Edison (102012106)
Tiffany Cindy Claudia A.P (102012197)
Calvin Affendy (102012262)
Elizabeth Angelina (102012354)
Erly Furhana Furny binti Saharudin (102012476)
Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta
Jln. Arjuna Utara No. 6 Jakarta 11510. Telephone : (021) 5694-2061, fax : (021) 563-1731
Kelo [email protected]
Pendahuluan
Latar Belakang
Jantung merupakan organ paling vital yang memegang peranan
penting pada kehidupan setiap manusia, termasuk anak-anak yang
sedang mengalami proses tumbuh kembang. Struktur dan fungsi jantung
normal sangat dibutuhkan untuk mempertahankan peredaran darah yang
stabil guna mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi seorang
anak. Namun, masih banyak sekali 7-8 bayi per 1000 kelahiran hidup
dilahirkan dengan penyakit jantung bawaan (PJB).
Anak dengan PJB memiliki kelainan struktur jantung yang dapat
berupa lubang atau defek pada sekat ruang-ruang jantung,
penyempitan atau sumbatan katup, atau pembuluh darah yang berasal
atau bermuara ke jantung, ataupun abnormalitas konfigurasi jantung
serta pembuluh darah. PJB sendiri digolongkan dalam 2 tipe, yaitu
PJB biru (sianotik), yaitu PJB yang menyebabkan warna kebiruan
(sianosis) pada kulit dan selaput lendir terutama di daerah
lidah/bibir dan ujung-ujung anggota gerak akibat kurangnya kadar
oksigen di dalam darah. Tipe yang kedua adalah PJB asianotik
umumnya menimbulkan gejala gagal jantung yang ditandai dengan sesak
memberat saat menetek/beraktivitas, bengkak pada wajah, anggota
gerak, serta abdomen, dan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan
kekurangan gizi.1
Dalam makalah ini, kami akan lebih membahas tentang PJB
sianotik, salah satunya adalah Tetralogi of Fallot. Angka
kejadiannya sekitar 5-7% dari seluruh penyakit jantung bawaan.
Kelainan Tetralogi Fallot mula-mula dilaporkan pada tahun 1672,
tetapi Fallot pada tahun 1888 menguraikan sekelompok penderita
dengan stenosis pulmonal; dekstro-posisi pangkal aorta; defek
septum ventrikel; hipertrofi ventrikel kanan. Kecuali selama umur
minggu-minggu pertama, Tetralogi Fallot merupakan bentuk penyakit
jantung utama yang menyebabkan sianosis. Sembilan persen bayi yang
ditemukan dengan penyakit jantung berat pada umur tahun pertama
menderita Tetralogi Fallot (0,196-0,258/1000 kelahiran hidup).
Skenario
Seorang anak laki-laki berusia 2½ tahun dibawa ibunya ke IGD
RS karena tiba-tiba bertambah biru setelah menangis. Keluhan
serupa pernah terjadi sebelumnya saat pasien habis BAB, kurang
lebih saat berusia 2 tahun. Saat itu ibu segera melarikan anaknya
ke puskesmas terdekat dan setelah diperiksa dokter mendiagnosis
anak menderita kebocoran jantung, namun sampai saat ini anak
belum pernah mendapat pemeriksaan lengkap. Keluhan sering batuk
pilek sejak kecil tidak ada, namun saat bayi bila menyusui hanya
sebentar-sebentar dan cepat lelah. Pasien lahir spontan, ditolong
oleh bidan, saat lahir langsung menangis dan tidak biru.
Pembahasan
Anamnesis
Anamnesis terbagi menjadi 2, yaitu auto-anamnesis dan allo-
anamnesis. Pada umumnya, anamnesis dilakukan secara auto-
anamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan secara langsung terhadap
pasiennya dan pasiennya sendirilah yang menjawab dan menceritakan
keluhannya kepada dokter. Inilah cara yang terbaik untuk
melakukan anamnesis karena pasien bisa secara langsung
menjelaskan apa yang sesungguhnya ia rasakan.
Tetapi ada kalanya dimana dilakukan allo-anamnesis, seperti
pada pasien yang tidak sadar, lemah, atau sangat kesakitan,
pasien anak-anak, dan manula, maka perlu orang lain untuk
menceritakan keluhan atau permasalahan pasien kepada dokter.
Tidak jarang juga dalam praktek, auto dan allo-anamnesis
dilakukan secara bersama-sama.
Tujuan utama anamnesis adalah untuk mengumpulkan semua
informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit pasien dan
adaptasi pasien terhadap penyakitnya. Kemudian dapat dibuat
penilaian keadaan pasien. Prioritasnya adalah memberitahukan
nama, jenis kelamin, dan usia pasien, menjelaskan secara rinci
keluhan utama, menjelaskan riwayat penyakit dahulu yang
signifikan, riwayat keluarga, pengobatan dan alergi, temuan
positif yang relevan dengan penyelidikan fungsional, dan
menempatkan keadaan sekarang dalam konteksi situasi sosial
pasien. Presentasi anamnesis harus mengarah pada keluhan atau
masalah. Saat melakukan anamnesis, hindari penggunaan kata-kata
medis yang tidak dimengerti oleh pasien.1
Allo-anamnesis yang dilakukan pada kasus ini, yaitu:
Identitas pasien: Anak laki-laki, 2½ tahun
Keluhan utama: mengalami biru setelah menangis
Riwayat penyakit sekarang: lama keluhan,
mendadak/terus-menerus/perlahan/hilang timbul/sesaat,
keluhan lokal (lokasi,menetap/berpindah,menyebar),
bertambah berat/berkurang saat apa, yang mendahului
keluhan apa
Obat-obatan: obat-obatan apa yang sedang dikonsumsi
pasien? adakah baru-baru ini terdapat perubahan
pemakaian obat? Bagaimana kepatuhannya mengikuti terapi
dan apakah dilakukan pengawasan terapi?
Riwayat penyakit dahulu: pernah terjadi sebelumnya saat
pasien habis BAB, kurang lebih saat berusia 2 tahun,
saat bayi bila menyusui hanya sebentar-sebentar dan
cepat lelah
Riwayat kehamilan dan kelahiran: pasien lahir spontan,
ditolong oleh bidan, saat lahir langsung menangis dan
tidak biru (ditanyakan yang sesuai dengan etiologi
yaitu faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi)
Riwayat keluarga: keluhan yang sama pada anggota
keluarga, orang serumah, dan sekelilingnya
Riwayat personal dan sosial terkait: gaya hidup, pola
makan, keadaan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.
Biasanya anak cenderung mengalami keterlambatan
pertumbuhan karena sulit untuk makan (ketika makan
terasa sesak) sehingga asupan kalorinya sangat sedikit.
Apakah saat beraktifitas mengalami dispneu atau
takipneu (karena inadekuat O2 ke jaringan). Ortopneu
biasanya diakibatkan kongesti vena pulmonary.
Berkeringat secara abnormal biasanya disebabkan oleh
gagal jantung kongesti. Nyeri pada dada yang disebabkan
karena iskemia pada otot jantung. Pernah mengalami
sincope atau tidak (karena stenosis aorta, hipertensi
pulmonal, heart rate yang sangat tinggi/sangat rendah). 2
Pemeriksaan Fisik3
Pemeriksaan fisik juga penting untuk mengarahkan evaluasi
selanjutnya. Sebelumnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan
tanda-tanda vital (TTV). Terdapat empat modus dasarnya, yaitu:
Keadaan umum dan TTV dapat dilakukan secara selintas
pandang dengan menilai keadaan fisik tiap bagian tubuh.
Selain itu, perlu dinilai secara umum tentang keadaan
pasien (compos mentis, apatis, somnolen, sopor, atau
koma). Hasil: kesadaran compos mentis, nadi 150x/menit
(N 75-120x/menit), pernapasan 52x/menit (N
20-30x/menit), dan suhu 36.3°C.
Inspeksi yang membutuhkan penggunaan mata pemeriksa
secara kritis, dimulai dengan pengamatan umum selama
wawancara medik (anamnesis) dan merupakan modus utama
pemeriksaan fisik.
Hasil: sianosis dan diaforetik, clubbing finger.
Palpasi yaitu mode meraba dan merasakan, dimana palpasi
ringan digunakan untuk menilai kulit dan struktur
permukaan, variasi dari suhu permukaan, kelembaban,
serta kekeringan. Palpasi dilakukan di organ-organ
visera, seperti pada abdomen.
Hasil: jantung secara klinis tidak membesar tetapi
aktivitas ventrikel kanan mudah teraba dan mungkin
dapat thrill sistolik pada daerah pulmonal.
perkusi yaitu menggunakan suara untuk menentukan
densitas dan isi struktur. Perkusi dilakukan dengan
mengetuk permukaan tubuh dan menimbulkan getaran,
mendengar, dan merasakan adanya perbedaan dalam
penghantaran gelombang suara.
auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop untuk
menilai pergerakan gas, cairan, atau organ di dalam
kompartemen tubuh.
Hasil: bunyi jantung 1 dan 2 murni regular, murmur
sistolik grade 2/6 di linea sternalis kiri ics 2.
Pemeriksaan Penunjang4,5
1. Pemeriksaan lab ditemukan adanya peningkatan Hb dan Ht akibat
saturasi oksigen yang rendah. Terdapat juga peningkatan
tekanan partial karbondioksida (PCO2), penurunan tekanan
parsial oksigen (PO2) dan penurunan pH. Pasien dengan Hb dan
Ht normal atau rendah mungkin menderita defisiensi besi.
Nilai juga faktor pembekuan darah (trombosit, protombin time)
2. Elektrokardiogram ditemukan deviasi sumbu QRS ke kanan,
hipertrofi ventrikel kanan, dan hipertrofi atrium kanan. Pada
anak mungkin gelombang T positif di V1, EKG sumbu QRS hampir
selalu berdeviasi ke kanan. Gelombang P di hantaran II tinggi
(P pulmonal). Pada penderita tetralogi asianosis, hipertrofi
biventrikuler kombinasi mula-mula dapat ditemukan, dengan
progresivitas menuju hipertrofi ventrikel kanan seiring
berkembangnya sianosis.
3. Foto rontgen toraks ditemukan gambaran jantung khas seperti
sepatu boot, segmen pulmonal yang cekung, apeks jantung
terangkat (hipertrofi ventrikel kanan), dan gambaran
vaskularisasi paru oligemi.
4.
Ekokardiogram digunakan untuk ekokardiogram 2-dimensi,
overriding aorta, tentukan tipe VSD (perimembranus subaortik
atau subarterial doubly committed), deviasi spetum
infundibular ke anterior, dimensi dan fungsi ventrikel kiri,
serta tentukan konfluensi dan diameter cabang-cabang arteri
pulmonalis,
5. Ekokardiografi berwarna dan Doppler digunakan untuk hitung
perbedaan tekanan ventrikel kanan dan arteri pulmonalis
(beratnya PS). Terdapat juga aliran ventrikel kanan ke aorta
melalui VSD.
6. Sedap jantung digunakan untuk menilai konfluensi dan ukuran
arteri pulmonalis serta cabang-cabangnya, mencari anomali
arteri koroner, melihat ada tidaknya VSD tambahan, dan
Gambar 1. Foto rontgen toraks dariTetralogi of Fallot
melihat ada tidaknya kolateral dari aorta langsung ke paru
(anak besar/dewasa).
7. Angiografi ventrikel kanan atau arteri pulmonalis digunakan
untuk menilai konfluensi dan diameter kedua arteri
pulmonalis, serta ada tidaknya stenosis pada percabangan
arteri pulmonalis atau di perifer.
8. Angiografi Aorta dilakukan bilar diperlukan untuk melihat
kelainan arteri koronaria atau bila diduga ada kolateral.
Diagnosis
Working diagnosis
Penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan sekumpulan
malformasi struktur jantung atau pembuluh darah besar yang telah
ada sejak lahir. Penyakit jantung bawaan yang kompleks terutama
ditemukan pada bayi dan anak. Penyebab terjadinya PJB belumdapat
diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor resiko atau
predisposisi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan
angka kejadian PJB, yaitu:
Tabel 1. Faktor Predisposisi Penyakit Jantung Bawaan.7
Faktor Prenatal A. Faktor Genetik Ibu menderita penyakit
infeksi : Rubela
Ibu alkoholisme
Umur Ibu lebih dari 40 tahun
Ibu menderita penyakit
Anak yang lahir sebelumnya
menderita PJB
Ayah/Ibu menderita PJB
Kelainan kromosom,
diabetes melitus yang
memerlukan insulin
Ibu meminum obat-obatan
penenang atau jamu
misalnya sindrom Down
Lahir dengan kelainan
bawaan yang lain
Penyakit Jantung bawaan dapat di bagi atas dua golongan
besar, yaitu penyakit jantung bawaan non sianotik, dan penyakit
jantung bawaan sianotik. PJB non sianotik, yaitu Atrial Septal
Defect (ASD), Ventricle Septal Defect (VSD), Persistent Ductus
Arteriosus (PDA), dan Arterioventricular Septal Defect (AVSD/AV
Canal Defect). Sedangkan yang termasuk PJB sianotik, yaitu
Tetralogy of Fallot (TOF), Double Outlet Right Ventricle (DORV),
Transposition of Great Arteries (TGA), serta Total Anomalous
Pulmonary Venous Return (TAPVR).
Tetralogi of Fallot (TOF)
Tetralogy of fallot (TOF) adalah kelainan jantung bawaan
dengan gangguan sianosis yang ditandai dengan kombinasi 4 hal
yang abnormal meliputi (1) defek septum ventrikel yaitu adanya
lubang pada sekat antara kedua rongga ventrikel, (2) stenosis
pulmonal yang terjadi karena penyempitan klep pembuluh darah yang
keluar dari bilik menuju paru, selain itu bagian otot dibawah
klep juga menebal dan menimbulkan penyempitan, (3) overriding
aorta dimana katup aorta membesar dan bergeser ke kanan, sehingga
terletak lebih kekanan, dan (4) hipertrofi ventrikel kanan atau
penebalan otot di ventrikel kanan karena adanya peningkatan
tekanan ventrikel kanan akibat dari stenosis pulmonal. Komponen
yang paling penting dalam menentukan derajat beratnya penyakit
adalah stenosis pulmonal dari sangat ringan sampai berat.
Stenosis pulmonal bersifat progresif, makin lama makin berat.
Derajat stenosis pulmonal sangat menentukan gambran kelainan;
pada obstruksi ringan tidak terdapat sianosis, sedangkan pada
obstruksi berat sianosis terlihat jelas. Pada pasien dengan TOF,
stenosis pulmonal menghalangi aliran darah ke paru-paru dan
mengakibatkan peningkatan ventrikel kanan sehingga terjadi
hipertrofi ventrikel kanan. Darah yang banyak mengandung CO2
seharusnya dipompakan ke paru-paru, namun malah berpindah ke
ventrikel kiri karena adanya celah antara ventrikel kanan akibat
VSD, akibatnya darah yang ada di ventrikel kiri yang kaya akan O2
dan akan dipompakan ke sirkulasi sistemik bercampur dengan darah
yang berasal dari ventrikel kanan yang kaya akan CO2. Hal
tersebut menyebabkan adanya penurunan kadar O2 dalam darah yang
akan dipompakan ke sirkulasi sistemik.8
Gambar 2. Tetralogy of Fallot.9
Differential diagnosis
Pulmonal Atresia (PA) dengan atau tanpa VSD10
Terdapat dua macam atresia pulmonal yaitu atresia pulmonal
dengan defek septum ventrikel dan atresia pulmonal tanpa defek
septum ventrikel. Atresia pulmonal dengan defek septum ventrikel
merupakan 20% dari pasien dengan gejala menyerupai Tetralogi of
Fallot, dan merupakan penyebab penting sianosis pada neonates.
Walaupun letak defek septum ventrikel sama dengan pada tetralogi,
kelainan ini berbeda dengan tetralogi Fallot. Darah dari
ventrikel tidak menuju ke arteri pulmonalis dan semua darah
ventrikel kanan akan masuk ke aorta. Atresia dapat mengenai katup
pulmonal, a.pulmonalis, atau infundibulum. Suplai darah ke paru
harus melalui duktis arteriosus atau melalui kolateral aorta-
pulmonal (pembuluh darah berasal dari arkus aorta atau aorta
descendens bagian atas). Pada umumnya vaskularisasi paru
berkurang, kecuali bila terdapat arteriosus atau kolateral yang
cukup besar.
Sianosis terlihat lebih dini dibandingkan dengan pada
Tetralogi of Fallot, yaitu dalam hari-hari pertama pasca lahir.
Pemeriksaan fisik tidak terdengar bising di daerah jalan keluar
ventrikel kanan, namun mungkin terdengan bising di daerah
anterior atau posterior, yang menunjukkan terdapatnya aliran
kolateral. Apabila kolateral banyak, maka pasien mungkin tidak
terlihat sianotik. Jantung dapat membesar dan hiperaktif dan
terjadi gagal jantung pada usia bayi. Terdapatnya hipertrofi
ventrikel kanan pada EKG serta adanya sianosis dapat
menyingkirkan diagnosis duktus arteriosus persisten.
Atresia pulmonal tanpa VSD merupakan kelainan yang jarang
ditemukan yakni kira-kira1% dari seluruh penyakit jantung bawaan.
Karena terdapat atresia pulmonal dan tidak terdapat defek septum
ventrikel, maka darah dari ventrikel kanan tidak dapat keluar.
Dari atrium kanan darah menuju ke atrium kiri melalui defek
septum atrium atau foramen ovale. Satu-satunya jalan darah ke
paru adalah melalui duktus arteriosus atau sirkulasi bronikal.
Biasanya ada terdapat insufiensi tricuspid.
Sianosis telah jelas tampak pada waktu bayi lahir dan terus
bertambah pada hari-hari pertama. Bayi sesak dengan gejala gagal
jantung. Pada pemeriksaan fisik biasanya tidak terdengar bising,
atau terdengar bising pansistolik insufisiensi tricuspid atau
terdengar bising arteriosus.
Double Outlet Right Ventricle (DORV)11
Sesuai dengan namanya, kelainan ini kedua arteri besar
keluar dari ventrikel kanan masing-masing dengan konusnya. Kedua
arteri besar tidak menunjukkan kontinuitas dengan katub mitral.
Hal inilah yang membedakan DORV dengan Tetralogi Fallot dengan
overidding aorta yang ekstrim.
Pada sebagian besar kasus, ventrikel kanan besar sedangkan
ventrikel kirinya normal. Secara keseluruhan DORV dapat terjadi:
1. Terdapat defek septum ventrikel besar subaortik, tanpa
stenosis pulmonal. Hal ini memberi gejala seperti pada
defek septum ventrikel besar, berupa gagal jantung
tanpa sianosis yang nyata.
2. Terdapat defek septum besar subpulmonik, tanpa diserta
stenosis pulmonal, yang disebut sebagai malformasi
TAUSSIG-Bing. Keadaan ini mirip dengan transposisi
dengan defek septum ventrikel besar, dengan gejala
utama gagal jantung dengan sianosis ringan.
3. Terdapat defek septum ventrikel besar serta stenosis
pulmonal. Gangguan hemodinamik yang mirip dengan TOF.
Manifestasi klinis adalah sianosis tanpa gagal jantung.
4. Defek septum ventrikel mengecil, hingga terjadi
obstruksi jantung kiri yang menyebabkan gagal jantung.
Transposition of Great Arteries (TGA)
Transposition of Great Arteries (TGA) merupakan abnormalitas
kongenital dimana arteri-arteri besar mengalami transposisi. Pada
kelainan jantung ini, aorta dan arteri pulmonal mengalami
transposisi sehingga aorta keluar dari ventrikel kanan dan arteri
pulmonalis keluar dari ventrikel kiri. Hal ini menandakan adanya
dua sirkulasi terpisah, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi
sistemik yang bekerja secara paralel. Hal ini bertolak belakang
dengan kehidupan, dimana seharusnya ada percampuran antara kedua
sirkulasi tersebut. Dalam kehidupan janin, bayi tersebut tidak
mengalami kesulitan karena aliran darah pulmonal sangat kecil.
Tetapi karena duktus arteriosus dan foramen ovale mulai menutup
setelah lahir, terjadilah sianosis yang progresif. Beratnya
gejala tergantung pada derajat percampuran kedua sirkulasi
melalui saluran fetal tersebut.8,12
Gejala klinis pada pasie TGA berupa sianosis progresif yang
timbul dalam beberapa jam pertama atau beberapa hari pertama
kehidupannya. Bayi yang menderita kelainan ini menjadi sangat
biru dan asidosis dan selanjutnya dapat terjadi gagal napas dan
gagal jantung. Pada pemeriksaan fisik selain ditemukan sianosis,
biasanya tidak terdapat bising jantung, tetapi bunyi jantung
kedua terdengar keras karena aorta yang mengalami transposisi
terletak di sebelah anterior, dekat dengan dinding dada. Pada
pemeriksaan penunjang dapat dilakukan rontgen toraks dengan
gambaran yang khas, yaitu jantung sedikit membesar dan dikatakan
tampak seperti sebuah telur yang berbaring pada satu sisinya.
Tatalaksana yang dapat dilakukan berupa pembuatan pintas antara
sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal yang dibuat dengan cara
ballon artrial septostomy (prosedur Rashkind). Sebuah kateter
khusus berlumen ganda dimasukkan lewat vena cava inferior, atrium
kanan, dan foramen ovale menuju ke dalam atrium kiri. Balon dekat
ujung akteter dikembungkan dengan medium kontras, kemudian
kateter dan balon ditarik kembali dengan keras melalui septum
atrium, sehingga merobek septum atrium dan membuat defek septum
yang besar. Hal ini memungkinkan percampuran darah dan mengurangi
sianosis. Selain itu, dapat pula dilakukan operasi koreksi
definitif yang merupakan suatu perbaikan anatomi, dimana
dilakukan dengan cara mengganti arteri pulmonalis dan aorta ke
ventrikel yang seharusnya. Hal ini biasanya dilakukan pada minggu
pertama atau minggu kedua kehidupan.8,12
Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR)11
Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR) adalah
penyakit jantung bawaan yang tidak diketahui penyebabnya dimana
tidak satu pun dari empat vena yang membawa darah dari paru-paru
ke jantung melekat ke atrium kiri. Pada TAPVR, oksigen dalam
darah kembali dari paru-paru ke ventrikel kanan dan tidak ke sisi
kiri jantung.
Gejala klinis yang dapat ditemukan dapat bervariasi dan
terkadang tidak gejala klinis tidak ditemukan pada anak yang
berusia sangat muda. Gejala klinis yang dapat ditemukan antara
lain sianosis, infeksi saluran pernapasan, lethargy, poor feeding,
dan poor growth.
Manifestasi klinis
Gejala klinis yang dapat ditimbulkan pada pasien dengan
tetralogi of fallot (TOF), diantaranya sebagai berikut:8
1. Pada auskultasi terdengar bunyi murmur pada batas kiri
sternum tengah sampai bawah.
2. Sianosis/kebiruan terutama pada bibir dan kuku : Sianosis
akan muncul saat anak beraktivitas, makan/menyusu, atau
menangis dimana vasodilatasi sistemik (pelebaran pembuluh
darah di seluruh tubuh) muncul dan menyebabkan peningkatan
aliran darah dari kanan ke kiri (right to left shunt). Darah
yang miskin oksigen akan bercampur dengan darah yang kaya
oksigen dimana percampuran darah tersebut dialirkan ke
seluruh tubuh. Akibatnya jaringan akan kekurangan oksigen
dan menimbulkan gejala kebiruan.
3. Bayi mengalami kesulitan untuk menyusu.
4. Sesak napas jika melakukan aktivitas dan kadang disertai
kejang atau pingsan.
5. Setelah melakukan aktivitas, anak selalu jongkok (squating)
untuk mengurangi hipoksi dengan posisi knee chest.
6. Jari tangan clubbing (seperti tabuh genderang karena kulit
atau tulang di sekitar kuku jari tangan membesar).
7. Pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung lambat.
8. Berat badan bayi sulit bertambah.
Serangan sianosis dan hipoksia atau yang disebut “hipoxic
spell” terjadi ketika kebutuhan oksigen otak melebihi suplainya.
Episode biasanya terjadi bila anak melakukan aktivitas (misalnya
menangis, setelah makan atau mengedan).
Etiologi
Tetralogi Fallot terjadi selama pertumbuhan janin, ketika
jantung bayi sedang berkembang. Pada umumnya penyebab Tetralogi
fallot tidak diketahui. Namun, Faktor-faktor seperti gizi ibu
yang buruk saat kehamilan, virus atau gangguan genetik dapat
meningkatkan risiko kondisi ini. Penyebab terjadinya Tetralogi
Fallot antara lain adalah:13
a. Faktor endogen
Berbagai jenis penyakit genetik :
1. Kelainan kromosom
2. Anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung
bawaan
3. Adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes
melitus, hipertensi, penyakit jantung atau kelainan
bawaan
b. Faktor eksogen
1. Riwayat kehamilan ibu: Riwayat mengikuti program KB oral
atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter
(thalidmide, dextroamphetamine, aminopterin,
amethopterin, jamu)
2. Ibu menderita penyakit infeksi Rubella (campak Jerman)
atau infeksi virus lainnya
3. Gizi yang buruk selama hamil
4. Ibu yang alkoholik
5. Usia ibu diatas 40 tahun
6. Ibu menderita diabetes.
7. Anak-anak yang menderita sindrom Down.
Epidemiologi
Tetralogi Fallot timbul pada 3-6 per 10.000 kelahiran dan
menempati urutan keempat penyakit jantung bawaan pada anak
setelah defek septum ventrikel, defek septum atrium dan duktus
arteriosus persisten, atau lebih kurang 10-15 % dari seluruh
penyakit jantung bawaan. Diantara penyakit jantung bawaan
sianotik, Tetralogi Fallot merupakan 2/3 nya.6 Tetralogi Fallot
merupakan penyakit jantung bawaan yang paling sering ditemukan
yang ditandai dengan sianosis sentral akibat adanya pirau kanan
ke kiri. Angka kejadian antara bayi laki-laki dan perempuan
sama.
Patofisiologi
Pada tetralogi fallot terdapat empat macam kelainan jantung
yang bersamaan, maka:
1. Darah dari aorta berasal dari ventrikel kanan bukan dari
kiri, atau dari sebuah lubang pada septum, sehingga menerima
darah dari kedua ventrikel.
2. Arteri pulmonal mengalami stenosis, sehingga darah yang
mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru jauh lebih
sedikit dari normal; malah darah masuk ke aorta.
3. Darah dari ventrikel kiri mengalir ke ventrikel kanan
melalui lubang septum ventrikel dan kemudian ke aorta atau
langsung ke aorta, mengabaikan lubang septum.
4. Karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar
darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi, otot-ototnya
akan sangat berkembang, sehingga terjadi pembesaran
ventrikel kanan.13
Kelainan fisiologis utama akibat Tetralogi of Fallot adalah
karena darah tidak melewati paru sehingga tidak mengalami
oksigenasi. Sebanyak 75% darah vena yang kembali ke jantung dapat
melintas langsung dari ventrikel kanan ke aorta tanpa mengalami
oksigenasi.
Komplikasi2
Penderita dengan tetralogi of fallot sebelum perbaikan
rentan terhadap beberapa komplikasi yang serius, diantarnya:
1. Trombosis otak biasanya terjadi pada vena serebralis atau
sinus dura dan kadang-kadang pada arteri serebralis, lebih
sering bila ada polistemia berat. Trombosis terjadi paling
sering pada penderita dibawah umur 2 tahun. Penderita ini
dapat menderita anemi defisiensi besi, seringkali dengan
kadar hemoglobin dan hematokrit dalam batas normal. Terapi
terdiri atas hidrasi yang cukup. Flebotomi dan penggantian
volume dengan plasma beku segar terindikasi pada penderita
polistemia berat. Heparin sedikit bermanfaat dan
terterkontraindikasi pada infark serebral hemoragik.
2. Abses otak kurang sering daripada kejadian vaskuler otak.
Penderita biasanya diatas usia 2 tahun. Mulanya sakit sering
tersembunyi dengan demam ringan dan atau perubahan dalam
perilaku sedikit demi sedikit. Pada beberapa penderita, ada
gejala yang mulainya akut, yang dapat berkembang sesudah
riwayat nyeri kepala, nausea, dan muntah. Serangan
epileptiform dapat terjadi ; tanda-tanda neurologis lokal
tergantung pada tempat dan ukuran abses, dan adanya kenaikan
tekanan intrkranial. Laju endap darah dan hitung sel darah
putih biasanya naik. Terapi antibiotik masif dapat membantu
menahan infeksi terlokalisasi, tetapi drainase bedah abses
hampir selalu diperlukan.
3. Endokarditis bakterial terjadi pada penderit yang tidak dioperasi
pada infundibulum ventrikel kanan atau pada katup pulmonal,
katup aorta atau jarang pada katup trikuspidal. Endokarditis
dapat menyulitkan shunt paliatif atau, pada penderita dengan
pembedahan korektif, setiap sisa stenosis pulmonal atau sisa
VSD. Profilaksis antibiotik sangat penting sebelum dan
sesudah prosedur bedah tertentu yang disertai dengan insiden
bakteremia yang tinggi.
4. Gagal jantung kongestif merupakan tanda biasa penderita dengan
tetralogy of fallot. Karena derajat penyumbatan pulmonal
semakin tua semakin buruk, gejala-gejala gagal jantung
mereda dan akhirnya pada penderita sianosis sering pada umur
6-12 bulan. Penderita pada saat ini beresiko untuk
bertambahnya serangan hipersianotik.
Tata Laksana2,7
Pada penderita TOF dapat diberikan terapi baik secara non-
medikamentosa ataupun secara medikamentosa untuk meringankan
gejala yang ditimbulkan. Terapi tersebut antara lain dengan cara:
1. Posisi lutut ke dada agar aliran darah ke paru bertambah
karena peningkatan afterload aorta akibat penekukan arteri
femoralis. Selain itu untuk mengurangi aliran darah balik
ke jantung (venous).
2. Morphine sulfat 0,1-0,2 mg/kgBB SC, IM, atau IV atau dapat
pula diberi Diazepam (Stesolid) per rektal untuk menekan
pusat pernafasan dan mengatasi takipneu.
3. Oksigen dapat diberikan, walaupun pemberian di sini tidak
begitu tepat karena permasalahan bukan kerena kekurangan
oksigen, tetapi karena aliran darah ke paru menurun. Dengan
usaha di atas diharapkan anak tidak lagi takipneu, sianosis
berkurang dan anak menjadi tenang. Bila hal ini tidak
terjadi dapat dilanjutkan dengan pemberian :
a. Propanolol 0,01-0,25 mg/kg IV perlahan-lahan untuk
menurunkan denyut jantung sehingga serangan dapat
diatasi. Dosis total dilarutkan dngan 10 ml cairan
dalam spuit, dosis awal/bolus diberikan separuhnya,
bila serangan belum teratasi sisanya diberikan
perlahan dalam 5-10 menit berikutnya.
b. Ketamin 1-3 mg/kg (rata-rata 2 mg/kg) IV perlahan.
Obat ini bekerja meningkatkan resistensi vaskuler
sistemik dan juga sedatif.
c. Penambahan volume cairan tubuh dengan infus cairan
dapat efektif dalam penanganan serangan sianotik.
Penambahan volume darah juga dapat meningkatkan
curah jantung, sehingga aliran darah ke paru
bertambah dan aliran darah sistemik membawa oksigen
ke seluruh tubuh juga meningkat.
Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan, yaitu:
1. Edukasi kepada keluarga pasien untuk mengenali dan
mengatasi serangan sianosis.
2. Propanolol oral 0,5-1,5 mg/kgBB po tiap 6 jam dapat
digunakan untuk mencegah serangan berulang sementara
menunggu tindakan operasi korektif.
3. Bila ada defisiensi zat besi segera diatasi untuk
mencegah komplikasi cerebrovaskular.
Tindakan operasi dianjurkan untuk semua pasien TOF. Tindakan
operasi yang dilakukan, yaitu:
1. Blalock-Taussig Shunt (BT-Shunt), yaitu merupakan posedur
shunt yang dianastomosis sisi sama sisi dari arteri
subklavia ke arteri pulmonal.
2. Waterson Shunt, yaitu membuat anantomosis intraperikardial
dari aorta asending ke arteri pulmonal kanan,hal ini
biasanya dilakukan pada bayi. Pada tipe ini ahli bedah harus
hati-hati untuk menentukan ukuran anastomosis yang dibuat
antara bagian aorta asending dengan bagian anterior arteri
pulmonal kanan. Jika anastomosis terlalu kecil maka akan
mengakibatkan hipoksia berat. Jika anastomosis terlalu besar
akan terjadi pletora dan edema pulmonal.
3. Potts Shunt, yaitu anastomosis antara aorta desenden dengan
arteri pulmonal yang kiri. Teknik ini jarang digunakan.
4. Total Korektif, terdiri atas penutupan VSD, valvotomi
pulmonal dan reseksi infundibulum yang mengalami hipertrofi.
Prognosis
Prognosis cukup baik pada yang dioperasi usia anak-anak.
Prognosis jangka panjang kurang baik bila dioperasi pada usia
dewasa yang sudah terjadi gangguan fungsi ventrikel kiri akibat
hipoksia yang lama ataupun pasca bedah dengan residual PI berat
sehingga terjadi gagal ventrikel kanan.5
Pencegahan
Pencegahan Tetralogi Fallot adalah antara lain dengan
menghindari penyebabnya. Meskipun untuk faktor endogen tidak
dapat dicegah, namun sedapat mungkin ibu menghindari faktor-
faktor eksogen yang dapat menyebabkan tetralogi fallot. Antara
lain dengan melakukan ante-natal health care secara teratur
selama masa kehamilan, tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa
persetujuan atau izin dokter karena dapat berpengaruh terhadap
kesehatan janin. Selain itu juga, tidak mengkonsumsi alkohol
maupun obat-obatan terlarang selama masa kehamilan.13
Penutup
Tetralogi of fallot adalah penyakit jantung kongentinal yang
merupakan suatu bentuk penyakit kardiovaskular yang ada sejak
lahir dan terjadi karena kelainan perkembangan dengan gejala
sianosis karena terdapat kelainan VSD, stenosispulmonal,
hipertrofiventrikel kanan, dan overiding aorta. Penyebab penyakit
jantung bawaan tidak diketahui secara pasti. diduga karena adanya
faktor endogen dan eksogen. Sianosis merupakan gejala tetralogi
fallot yang utama.Berat ringanya sianosis ini tergantung dari
severitas stenosis infindibuler yang terjadi pada tetralogi
fallot dan arah pirau interventrikuler. Tetralogi fallot hanya
bisa disembuhkan melalui operasi. Operasi direkomendasikan pada
usia 1 tahun keatas guna mencegah komplikasi kembali saat dewasa
nantinya. TF dengan absent pulmonary valve atau tanpa adanya
katup harus segera diatasi dengan operasi.
Daftar Pustaka
1. Gleadle J. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jakarta:
Penerbit Erlangga; 2005,h.155,191.
2. Behrman, Kliegman, Jenson. Ilmu Kesehatan Anak Nelson Edisi
15 Vol 2. Jakarta: EGC; 2003.h. 577-83.
3. Houghton AR. Gray D. Chamberlain’s gejala dan tanda dalam
kedokteran klinis. Jakarta: EGC; 2012,h.103-7.
4. Tempe DK. Anesthesia for the management of congenital heart
defect. In: Tempe DK, editor: Clinical Practice of Cardiac
Anesthesia. Delhi: modern Publishers; 2004.p.166-71.
5. Levin SK, Carlon VA. Tetralogy of fallot. In: Yao FSF,
editor: Yao & Artusio’s Anesthesiology Problem-Oriented
Patient Management. 5th Ed. Philadelphia: Lippincort
Williams & Walkins; 2003.p.233-48.
6. Kumar V, Abbas AK, Fausto A. Dalam : Pendit BU. Robbins &
Cotran Dasar Patologis Penyakit Ed 7. Jakarta: EGC; 2009.h.
587-88.
7. Hull D, Johnston DI. Dasar-dasar pediatri. Ed 3. Jakarta:
EGC; 2008. h. 143-6.
8. Muttaqin A. Pengantar : klien dengan gangguan sistem
kardiovaskular. Jakarta: Salemba Medika; 2009. h. 186-94.
9. Tetralogy of Fallot. Diunduh tanggal 18 September 2014 dari
http://commons.wikimedia.org.
10. Laizzo PA. Handbook of cardiac anatomy, physiology, and
devices. 2nd Edition. USA: Springer; 2009.p.142.
11. Berstein, Daniel. The cardiovascular system. Robert K.
Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Saunders; 2007.p.
1881-1900
12. Gray HH, Dawkins KD, Morgan JM, Simpson IA. Kardiologi.
Jakarta: Erlangga; 2005. h. 264-7.
13. Kliegman. Nelson Pediatric. 18th Edition, Cyanotic
congenital heart lesions: lesions associated with decreased
pulmonary blood flow; 2006.h.247-8.