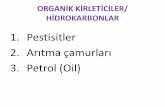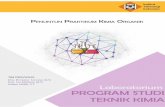KIMIA ORGANIK KEL 11
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of KIMIA ORGANIK KEL 11
MAKALAH KIMIA ORGANIK II
SABUN, DETERGEN CAIR, BIOETANOL, PENGUJIAN
ANGKA ASETIL, REICHERT MEISSL
DAN ANGKA POLENSKE
Disusun Oleh :
Ainoel Yaqin 1314012
Andri Heri 1314017
Ninis Rahayu 1314021
Ardi Riyanto 1314029
Khusnul Chotimah 1314066
i
JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2014
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah
yang berjudul SABUN, DETERGEN CAIR, BIOETANOL, PENGUJIAN
ANGKA ASETIL, REICHERT MEISSL DAN ANGKA POLENSKE dengan
baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dalam
Mata Kuliah Kimia Organik II.
Tersusunnya makalah ini karena ada dorongan dan
bantuan yang diberikan oleh banyak pihak, oleh karena
itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-
teman mahasiswa ITN Malang yang telah meluangkan
waktunya untuk membantu terselesainya makalah ini.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih terdapat
banyak kekurangannya, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari
pembaca.
ii
Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya Mahasiswa
Jurusan Teknik Kimia ITN Malang.
Malang, Oktober 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................
..................................................ii
DAFTAR ISI..........................................
.................................................iii
BAB I SABUN
iii
1.1..........................................Sejarah
................................................
...............................................1
1.2................................Klasifikasi Sabun
................................................
...............................................4
1.3....................Sifat Kimia dan Fisika Sabun
................................................
...............................................4
1.4...........................Proses Pembuatan Sabun
................................................
...............................................5
BAB II DETERGEN CAIR
2.1..........................................Sejarah
................................................
...............................................6
2.2........................Klasifikasi Deterjen Cair
................................................
...............................................7
2.3.............Sifat Kimia dan Fisika Deterjen Cair
................................................
...............................................7
2.4...................Proses Pembuatan Detergen Cair
...............................................8
BAB III PENGUJIAN ANGKA ASETIL, REICHERT MEISSL DAN
ANGKA POLENSKE
iv
3.1...........................Pengujian Angka Asetil
................................................
...............................................9
3.2........................Pengujian Reichert Meissl
................................................
..............................................10
3.3.........................Pengujian Angka Polenske
................................................
..............................................12
BAB IV BIOETANOL
4.1..........................................Sejarah
................................................
..............................................13
4.2...........................Sifat Fisika Dan Kimia
................................................
..............................................14
4.3.................................Standar Kualitas
................................................
..............................................16
4.4........................Proses Pembuatan Biodisel
................................................
..............................................17
DAFTAR PUSTAKA......................................
..................................................21
v
BAB I
SABUN
1.1. Sejarah
Berdasarkan ukiran yang terdapat di bejana gerabah
peninggalan Babilonia, bahan-bahan yang terkandung dalam
sabun diduga telah dimanfaatkan sejak 2.800 SM. Dalam
Papirus Eber, dokumen kesehatan Mesir Kuno tahun 1.500 SM,
masyarakat Mesir Kuno menggunakan kombinasi minyak hewani
atau nabati dengan garam alkali –dikenal dengan istilah
saponifikasi–untuk menyembuhkan penyakit kulit dan
membersihkan badan.
Istilah saponifikasi diambil dari bahasa latin “sapo”
yang artinya soap atau sabun. Sapo merupakan nama sebuah
gunung –ada juga yang menyebutnya bukit– dalam legenda
Romawi Kuno, yang biasa menjadi tempat pemotongan hewan
kurban dalam upacara. Ketika hujan, sisa-sisa lemak hewan
itu tercampur abu kayu pembakaran dan mengalir ke Sungai
Tiber di bawah gunung. Tak diduga, saat masyarakat sekitar
sungai mencuci, mereka mendapati air mengeluarkan busa dan
pakaian mereka menjadi lebih bersih.
Pada abad ke-1 masyarakat Romawi Kuno melakukan
saponifikasi dengan cara mereaksikan ammonium karbonat yang
terdapat dalam air seni (urine) dengan minyak tumbuhan dan
lemak hewan. Ada pekerja khusus yang mengumpulkan air seni
(fullones) untuk dijual ke para pembuat sabun. Tapi baru
1
pada abad ke-2 dokter Galen (130-200 SM) menyebutkan
penggunaan sabun untuk membersihkan tubuh.
Ahamad Y. al-Hassan dan Donald Hill dalam bukunya
Islamic Technology: An Illustrated History, menyebut Abu
Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, kimiawan Persia,
sebagai peracik pertama ramuan sabun modern. Orang Arab
membuat sabun dari minyak nabati atau minyak atsiri,
misalnya minyak thymus. Sentra industri sabun berada di
Kufah, Basrah, dan Nablus di Palestina. Sabunnya sudah
berbentuk padat dan cair.
Masyarakat di Eropa Utara, pada abad pertengahan,
baru mengenal sabun cair tapi baunya kurang enak. Pada abad
ke-13 jenis sabun keras mulai diekspor ke Eropa. Teknologi
pembuatan sabun juga ditransfer ke Italia dan Prancis
selatan selama Renaissance. Di Inggris, seperti ditulis
John A. Hunt dalam “A Short History Soap”, dimuat di
Pharmaceutical Journal, 1999, catatan Bristol Company of
Soapmakers untuk tahun 1562-1642 menunjukkan lebih dari 180
orang terlibat dalam bisnis sabun. Bisnis sabun mendapat
tempat yang istimewa di Inggris. Pada 1622 Raja James
memberikan hak monopoli kepada seorang pembuat sabun dengan
membayar imbalan $100.000 setahun.
Sekalipun sabun mulai dikenal, ia masih menjadi
barang asing bagi sebagian masyarakat di Eropa Tengah.
Menurut Alicia Alvrez dalam bukunya The Ladies′ Room
Reader: The Ultimate Women′s Trivia Book, Di Jerman,
Duchess of Juelich merasakan sensasi luar biasa ketika
2
mendapat hadiah sekotak sabun dari sahabatnya pada 1549.
Pada 1672, seorang Jerman bernama A. Leo harus menuliskan
keterangan rinci cara penggunaannya ketika mengirimkan
bingkisan hadiah berisi sabun kepada seorang puteri Prusia,
Lady von Schleinitz.
Berbeda dengan Inggris, penguasa Perancis Raja Louis
XIV justru bersikap keras kepada pembuat sabun. Sang raja
pernah menghukum mati dengan pisau guillotin terhadap tiga
orang pembuat sabun karena membuat kulit sang raja iritasi.
Takut ditimpa hukuman yang sama, beberapa pembuat sabun
berusaha lebih serius untuk menciptakan sabun berkualitas
baik.
Revolusi industri yang berkembang di negeri-negeri
Eropa pada abad ke-19 memperpesat industri sabun. Namun di
beberapa negara, sabun masih dikenai pajak tinggi karena
tergolong barang mewah. “Kombinasi monopoli dan pajak
khusus telah menghalangi pembangungan industri sabun” tulis
Patricia E. Malcolmson dalam English Laundresses: a Social
History, 1850-1930. Pada 1852 Inggris dan Prancis
menghilangkan pajak sabun untuk meningkatkan standar hidup
bersih dan sehat masyarakat. Sabun pun menjadi komoditas
sehari-hari yang bisa digunakan masyarakat biasa.
Sebelum mengenal sabun, masyarakat di Nusantara
biasanya mandi dengan menggosokan lempeng-lempeng batu
halus untuk menyingkirkan kotoran di tubuh. Agar kulit
harum dan halus, mereka menaburkan kuntum mawar, melati,
kenanga, sirih, dan minyak zaitun dalam wadah penampungan
3
air. Kebiasaan ini masih berlangsung hingga 1980-an,
terutama di desa-desa. Bahkan saat ini, sekalipun
menggunakan sabun, ada yang merasa belum bersih tanpa
menggosokkan batu ketika mandi.
Salah satu perusahaan yang memperkenalkan sabun
produksi industri adalah Unilever, merger antara perusahaan
asal Inggris, Lever Brothers, dan perusahaan asal Belanda,
Margarine Urine. Produk sabun Unilever adalah Lifebuoy,
Lux, Sweetmay, dan Capitol. Unilever membuka anak
perusahaan di Jakarta pada 1931. Pesaingnya, P&G, produksi
perusahaan Jerman, Dralle yang pada 1940-an berubah nama
menjadi Colibri dan diambil-alih Unilever.
Saat Perang Pasifik, Unilever diambil-alih militer
Jepang untuk kepentingan perang. Ini membuat sabun jadi
barang langka. Kalau pun ada, harganya melonjak. Untuk
mengatasinya, pada 1943 otoritas Jepang mengeluarkan izin
operasi kepada 94 perusahaan sabun: 11 untuk orang
Indonesia, dan selebihnya Tionghoa. Tak satu pun izin untuk
orang Eropa. Selain itu, militer Jepang memberikan latihan
cara membuat sabun agar rakyat bisa hidup mandiri. Latihan
itu diadakan di gudang Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di
Jalan Sunda 28 Jakarta. Selain untuk keperluan sehari-hari,
rakyat yang telah mahir membuat sabun biasanya menjual
sabun hasil buatan mereka.
“Sabun yang bahan dasarnya terbuat dari minyak
kelapa, abu, kapur, dan garam itu memiliki kualitas yang
4
baik dan membuka lapangan usaha baru bagi rakyat,” tulis
harian Borneo Shimboen, 22 Oktober 1943.
Setelah perang berakhir, Unilever mencoba bangkit.
Tapi Unilever kembali berada dalam posisi sulit ketika
terjadi gejolak politik pada 1950-an menyangkut Papua
Barat. Semua perusahaan Belanda dinasionalisasi. Staf
Unilever diusir dan diganti oleh tenaga-tenaga Inggris dan
Jerman. Operasinya di bawah pengawasan pemerintah tahun
1964. Produksi Unilever merosot.
Pada 1967 kendali Unilever dikembalikan. Sejak itu
produk-produk Unilever kembali merajai pasar penjualan
sabun di Indonesia. Pesaing bermunculan.
Kini, sabun sudah menjadi barang kebutuhan sehari-
hari. Mandi takkan terpisahkan dari sabun. Tinggal
bagaimana membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun.
Indonesia, berdasarkan survey Departemen Kesehatan tahun
lalu, termasuk negara yang malas cuci tangan pakai sabun.
Padahal, sejak 2008, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah
menetapkan 15 Oktober sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun
Sedunia.
1.2. Klasifikasi Sabun
Klasifikasi sabun menurut pH :
- pH 5 – 8: dianggap lembut untuk kulit
- pH 8 – 10: pH optimal untuk sabun badan
5
- pH 10 – 12: untuk laundry / mencuci baju
Sabun dapat dibedakan sesuai jenis dan fungsinya yaitu:
- Sabun keras atau sabun cuci.
Dibuat dari lemak dengan NaOH, misalnya Na – Palmitat dan
Na – Stearat.
- Sabun lunak atau sabun mandi.
Dibuat dari lemak dengan KOH, misalnya K-Palmitat dan K-
Stearat
1.3. Sifat Kimia dan Fisika Sabun
Sifat Fisika
Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air,
tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil,
melainkan larut dalam bentuk ion. Sabun dan detergen
merupakan agen pengemulsi yang paling efektif, khususunya
untuk emulsi minyak-air. Minyak dalam air merupakan emulsi
dengan minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase
pendispersi.
Sifat Kimia
a. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suku tinggi
sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu
larutan sabun dalam air bersifat basa.
CH3(CH2)16COONa + H2O CH3(CH2)16COOH + OH-
b. Jika larutan sabun dalam air diaduk maka akan
menghasilkan buih, peristiwa ini tidak akan terjadi pada
air sadah. Dalam hal ini sabun dapat menghasilkan buih
setelah garam-garam Mg atau Ca dalam air mengendap.
CH3(CH2)16COONa + CaSO4 Na2SO4 + Ca(CH3(CH2)16COO)2
6
c. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini
disebabkan proses kimia koloid, sabun (garam natrium dari
asam lemak) digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat
polar maupun non polar, karena sabun mempunyai gugus
polar dan non polar. Molekul sabun mempunyai rantai
hydrogen CH3(CH2)16 yang bertindak sebagai ekor yang
bersifat hidrofobik (tidak suka air) dan larut dalam zat
organik sedangkan COONa+ sebagai kepala yang bersifat
hidrofilik (suka air) dan larut dalam air.
d. Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk
mencuci dan membersihkan. Banyak sabun merupakan campuran
garam natrium atau kalium dari asam lemak yang dapat
diturunkan dari minyak atau lemak dengan direaksikan
dengan alkali (seperti natrium atau kalium hidroksida).
1.4. Proses Pembuatan Sabun
Sabun dibuat baik lewat proses batch maupun proses
sinambung. Pada proses batch, lemak atau minyak dipanaskan
dengan alkali (NaOH) sedikit berlebih dalam ketel terbuka.
Bila penyabunan selesai, garam ditambahkan untuk
mengendapkan sabun sebagai padatan. Lapisan air yang
mengandung garam, gliserol, dan kelebihan alkali
disingkirkan, dan gliserol dipulihkan lewat penyulingan.
Padatan sabun kasar, yang mengandung sedikit garam, alkali,
dan gliserol sebagai pengotor, dimurnikan lewat pendidihan
dengan air dan pengendapan kembali dengan garam beberapa
kali. Akhirnya, padatan dididihkan dengan air secukupnya
untuk membentuk campuran lembut, yang jika dibiarkan
7
menghasilkan lapisan sabun homogen di bagian atas. Sabun
ini dapat dijual tanpa pengolahan lebih lanjut, yaitu
sebagai sabun industri murahan. Berbagai bahan pengisi,
seperti pasir atau batu apung dapat ditambahkan untuk
membuat sabun gosok. Pengolahan lain mengubah sabun kasar
menjadi sabun mandi, sabun bubuk atau sabun serpih, sabun
obat atau sabun wangi, sabun cuci, sabun cair, atau sabun
apung (dengan mengembuskan udara ke dalamnya).
Dalam proses sinambung, yang lebih umum dikerjakan
sekarang, lemak atau minyak terhidrolisis oleh air pada
suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis, biasanya
suatu sabunk zink. Lemak atau minyak dan air dimasukkan
terus menerus dari arah berlawanan dari suatu reaktor yang
lebih besar, dan asam lemak dan gliserol diambil segera
setelah terbentuk lewat penyulingan. Asam kemudian
dinetralkan secara hati-hati dengan alkali yang jumlahnya
tepat untuk menjadi sabun.
BAB II
DETERGEN CAIR
8
2.1. Sejarah
Deterjen sintetik yang pertama dikembangkan oleh
Jerman pada waktu Perang Dunia II dengan tujuan agar lemak
dan minyak dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Pada
saat ini ada lebih 1000 macam deterjen sintetik yang ada di
pasaran. Fritz Gunther, ilmuwan Jerman, biasa disebut
sebagai penemu surfactant sintetis dalam deterjen tahun 1916.
Namun, baru tahun 1933 deterjen untuk rumah tangga
diluncurkan pertama kali di AS. Sebelum tahun 1965,
deterjen menghasilkan limbah busa di sungai dan danau. Ini
karena umumnya deterjen mengandung alkylbenzene sulphonate yang
sulit terurai.
Setelah 10 tahun dilakukan penelitian (1965),
ditemukan linear alkylbenzene sulphonate (LAS) yang lebih ramah
lingkungan. Bakteri dapat cepat menguraikan molekul LAS,
sehingga tidak menghasilkan limbah busa. Sepanjang sejarah
banyak usaha dilakukan untuk membantu kita mengerjakan
pekerjaan mencuci. Pencucian dengan air saja, bahkan dengan
penggosokan atau putaran mesin sekeras apapun, akan
menghilangkan sebagian saja bercak, kotoran dan
partikelpartikel tanah.
Air saja tidak dapat menghilangkan debu yang tak
larut dalam air. Air juga tak mampu menahan debu yang telah
lepas dari kain agar tetap tersuspensi (tetap berada di
air, jadi tidak kembali menempel ke kain). Jadi diperlukan
bahan yang dapat membantu mengangkat kotoran dari air dan
kemudian menahan agar kotoran yang telah terangkat tadi,
9
tetap tersuspensi. Sejak ratusan tahun lalu telah dikenal
sabun, yakni persenyawaan antara minyak atau lemak dan
basa. Awalnya orang-orang Arab secara tak sengaja menemukan
bahwa campuran abu dan lemak hewan dapat membantu proses
pencucian.
Walaupun berbagai usaha perbaikan pada kualitas dan
proses pembuatan sabun telah dilakukan, semua sabun hingga
kini mempunyai satu kekurangan utama yakni akan bergabung
dengan mineral-mineral yang terlarut dalam air membentuk
senyawa yang sering disebut lime soap (sabun-kapur),
membentuk bercak kekuningan di kain atau mesin pencuci.
Akibatnya kini orang mulai meninggalkan sabun untuk mencuci
seiring dengan meningkatnya popularitas deterjen.
2.2. Klasifikasi Deterjen Cair
Menurut kandungan gugus aktifnya maka detergen
diklasifikasikan sebagai berikut:
- Detergen jenis keras
Detergen jenis keras sukar dirusak oleh mikroorganisme
meskipun bahan tersebutdibuang akibatnya zat tersebut
masih aktif. Jenis inilah yang menyebabkan pencemaran
air. Contoh: Alkil Benzena Sulfonat (ABS). Proses
pembuatan ABS ini adalah dengan mereaksikan Alkil Benzena
dengan BelerangTrioksida, asam Sulfat pekat atau Oleum.
Reaksi ini menghasilkan Alkil BenzenaSulfonat.
Jika dipakai Dodekil Benzena maka persamaan reaksinya
adalah:
10
C6H5C12H25 + SO3C6H4C12H25SO3H (Dodekil Benzena Sulfonat)
Reaksi selanjutnya adalah netralisasi dengan NaOH
sehingga dihasilkan Natrium Dodekil Benzena Sulfonat
- Detergen jenis lunak
Detergen jenis lunak, bahan penurun tegangan permukaannya
mudah dirusak oleh mikroorganisme, sehingga tidak aktif
lagi setelah dipakai. Contoh: Lauril Sulfat atau Lauril
Alkil Sulfonat (LAS). Proses pembuatan (LAS) adalah
dengan mereaksikan Lauril Alkohol dengan asam Sulfat
pekat menghasilkan asam Lauril Sulfat dengan reaksi:
C12H25OH + H2SO4C12H25OSO3H + H2O.
Asam Lauril Sulfat yang terjadi dinetralisasikan dengan
larutan NaOH sehingga dihasilkan Natrium Lauril Sulfat.
2.3. Sifat Kimia dan Fisika Deterjen Cair
Sifat Fisika
- Kelarutan dan daya melarutkan, murray dan Hartly dalam
pernyataanya menunjukkan bahwa partikel-partikel tunggal
relatif tidak larut, sedangkan misel mempunyai kelarutan
tinggi. Makin panjang rantai hidrokarbonnya, makin tinggi
temperatur kritik larutan.
- Karakteristik deterjen cair adalah sebagai berikut yaitu
larutan agak kental, busanya sedikit. Warnanya putih
keruh jika tidak ditambahkan pewarna.
- Daya emulsi-emulsi adalah suspensi partikel cairan dalam
fasa cairan yang lain, yang tidak saling melarutkan. Sama
hanya dengan pembasahan, maka surfaktant akan menurunkan
tegangan antarmuka, sehingga terjadi emulsi yang stabil.
11
- Pembasahan perubahan dalam tegangan permukaan yang menyertai
proses pembasahan dinyatakan oleh Hukum Dupre.
Sifat kimia
Pada umumnya, deterjen mengandung bahan-bahan berikut:
- Surfactant
Surfactant (surface active agent) merupakan zat aktif
permukaan yang mempunyaiujung berbeda yaitu hidrofil
(suka air) dan hidrofob (suka lemak). Bahan aktif ini
berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga
dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan
bahan.
- Filler
Filler (pengisi) adalah bahan tambahan deterjen yang
tidak mempunyai kemampuanmeningkatkan daya cuci, tetapi
menambah kuantitas. Contoh Sodium sulfat.
- Additive
Additive adalah bahan suplemen/tambahan untuk membuat
produk lebih menarik,misalnya pewangi, pelarut, pemutih,
pewarna dst, tidak berhubungan langsung dengandaya cuci
deterjen. Additives ditambahkan lebih untuk maksud
komersialisasi produk. Contoh: Enzim,Boraks,Sodium
klorida, Carboxy Methyl Cellulose (CMC).
- Suds Regulator (pengatur busa)
Untuk membantu surfactant dalam proses pencucian. contoh:
asam lemak Abrasive.
- Water softener
12
Untuk menetralkan efek dari “kekerasan “ ion-ion pada
bahan lain.
- Oxidants
Untuk pemutihan dan disinfeksi
- Bahan Non-surfactant yang dapat mempertahankan kotoran di
skorsing Enzymes.
2.4. Proses Pembuatan Detergen Cair
Metode pembuatan deterjen cair adalah: Mencampur 10 %
SLS – DG, 20 % soda abu, CMC lokal 5 %, pewarna secukupnya
dan air 64.5% ke dalam reaktor, memanaskan campuran bahan
di atas kemudian diaduk, setelah tercampur homogen api
dimatikan, lalu didinginkan, setelah dingin ditambah parfum
sebanyak 1 %, mengalirkan larutan ke bak filter,
mengalirkan larutan ke bak penampung.
BAB III
PENGUJIAN ANGKA ASETIL, REICHERT MEISSL
DAN ANGKA POLENSKE
3.1. Pengujian Angka Asetil
Bilangan Asetil adalah sifat kimia minyak atau lemak
untuk menentukan gugusan hidroksil bebas yang sering
terdapat dalam minyak atau lemak, baik alam ataupun
sintesis (terutama pada minyak jarak, croton oil dan
monogliserida). Bilangan asetil ini dinyatakan sebagai
jumlah milligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam
asetat yang diperoleh dari penyabunan 1 gram minyak atau
13
lemak atau lilin yang telah di asetilasi. Serta dapat
dinyatakan dengan rumus :
KA (%) = [(D-C)Na + (A-B)Nb] × (F/W)
dimana:
A = volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi
contoh
B = volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi
blanko
C = volume HCl yang dibutuhkan untuk titrasi
contoh
D = volume HCl yang dibutuhkan untuk titrasi
blanko
Na = Normalitas HCl
Nb = Normalitas NaOH
F = 4.305 untuk kadar asetil
Peralatan
- Tabung Reaksi
- Stopper
- Labu Didih
- Termometer
- Stopwatch
- Ubin Porselen Atau Silica Kaca
- Pipet Tetes
- Pipet Volume
- Gelas Arlogi
- Gelas Ukur
- Beakerglass
14
- Erlenmeyar
- Statif Dan Klem
- Karet Penghisap
- Botol Aquadest
- Corong Kaca
- Waterbatch
Bahan
- Asam Format
- Nitrat Laktanum
- Iodium
- Ammonia
Prosedur Pengujian
1. Masukkan 10 sampai 20 mg sampel ke dalam tabung reaksi
(180 mm × 18 mm)
2. Tambahkan 0,15 ml asam format kemudian tutup tabung
reaksi dengan stopper.
3. Pasangkan tabung kecil (sekitar 100 mm × 10 mm) yang
berisi air. Alat ini bertindak sebagai kondensor,
sehingga larutan nitrat lantanum bisa mengalir dari luar
tabung reaksi kecil. Kecuali zat yang sukar
terhidrolisa, akan tetap dalam labu selama 5 menit.
4. Campurkan larutan dengan iodium 0,01 m sebanyak 0,05 ml
pada ubin porselen atau silica kaca dan kemudian
menambahkan 1 tetes ammonia 2m di tepi larutan.
5. Biarkan hingga berubah warna menjadi warna biru (sekitar
1-2 menit) di persimpangan larutan yang berlangsung
secara cepat.
15
6. Untuk zat yang terhidrolisa, panaskan dengan perlahan
larutan dengan cara membuka tutup kondensat.
3.2. Pengujian Reichert Meissl
Bilangan yang menyatakan berapa mL KOH 0,1 N untuk
menetralkan asam lemak yang dapat didestilasi dengan uap
H2O dan larutdalam H2O yang berasal dari 5 gram lemak.
Jumlah (mL) dari NaOH 0,1N yagn dipergunakan untuk
menetralkan asam lemak yang menguap dan larut dalam air
yang diperoleh dari penyulingan 5gr minyak atau lemak.
Perhitungan :
Bilangan Reichert-Meissl = 1,1 x (A-B)
A = jumlah ml NaOH 0,1N untuk titrasi contoh
B = jumlah ml NaOH 0,1N untuk titrasi blanko
Fungsi: mengukur jumlah asam lemak yang tersusun dari 2–6
atom C.
Prosedur
1. 5 gr minyak cair yang sudah disaring dimasukkan ke dalam
labu suling 300 mL
2. Tambahkan 20mL soda gliserol (dibuat dari 20 mL NaOH 50%
dalam180 mL gliserol pekat)
3. Campuran dipanaskan sampai jernih (tersabunkan). Dijaga
agar tidak berbusa dengan menggoyang-goyang labu secara
perlahan
4. Tambahkan 135 mL air mendidih setetes demi tetes untuk
menghindari terbentuknya busa
5. Tambahkan 5 mL H2SO4 20% dan batu didih
16
6. Lakukan penyulingan selama 30 menit dengan suhu tidak
terlalu tinggi sehingga asam lemak tidak mendidih. Maka
diperoleh 120 mL destilat yang suhunya tidak boleh lebih
dari 20°C
7. Setelah diperoleh 110 mL destilat api dimatikan.
Destilat yang masih keluar ditampung dengan tabung yang
berbeda
8. Destilat dari kedua tabung dicampur sambil dokocok
perlahan-lahan. Kemudian direndam dalam air 15°C selama
15 menit.
9. Saring dengan kertas saring 100 mL destilat, dititrasi
dengan larutan NaOH 1,0 N dengan indikator pp sampai
terbentuk warna merah jambu, kemudian catat volume NaOH
yangkeluar sebagai V1.
10. Sebagai pembanding buat titrasi blanko, dan catat
volume NaOH yangdigunakan pada saat titrasi sebagai V2.
Bilangan Reicht Meissl = 1,1 ( V1−V2)
3.3. Pengujian Angka Polenske
Bilangan yang menyatakan berapa mL KOH 0,1 N untuk
menetralkan asam lemak yang dapat didestilasi dengan uap
H2O dan tak larut dalam H2O yang berasal dari 5 g lemak
17
Fungsi: mengukur jumlah asam lemak yang tersusun dari6-12
atamC
1. Lemak yang tinggal dan tidak larut dalam air dari
penentuan bilangan Reichert Meissl dipisahkan dengan
kertas saring.
2. Cuci dengan 15 mL air di dalam botol penampung110 mL
sebanyak 3 kali
3. Bagian yang tidak larut diekstraksi dengan pencucian
seperti di atas dengan menambahkan 15 mL alkohol 95% yang
netral sebanyak 3 kali
4. Campuran yang larut dalam air diekstraksi dengan NaOH
0.1N dengan menggunakan 0.5 mL phenolphthalein sebagai
indikator
5. Titrasi larutan sampai berubah warna menjadi merah
jambu
6. Bilangan Polenske=jumlah mL NaOH 0.1 N untuk titrasi.
18
BAB IV
BIODIESEL
4.1. Sejarah
Biodiesel pertama kali dikenalkan di Afrika selatan
sebelum perang dunia II sebagai bahan bakar kenderaan
berat. Bahan bakar nabati bioetanol dan biodiesel merupakan
dua kandidat kuat pengganti bensin dan solar yang selama
ini digunakan sebagai bahan bakar mesin Otto dan Diesel.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan pengembangan dan
implementasi dua macam bahan bakar tersebut, bukan hanya
untuk menanggulangi krisis energi yang mendera bangsa namun
juga sebagai salah satu solusi kebangkitan ekonomi
masyarakat.
Biodiesel didefinisikan sebagai metil/etil ester yang
diproduksi dari minyak tumbuhan atau hewan dan memenuhi
kualitas untuk digunakan sebagai bahan bakar di dalam mesin
diesel. Sedangkan minyak yang didapatkan langsung dari
pemerahan atau pengempaan biji sumber minyak (oilseed), yang
19
kemudian disaring dan dikeringkan (untuk mengurangi kadar
air), disebut sebagai minyak lemak mentah. Minyak lemak
mentah yang diproses lanjut guna menghilangkan kadar fosfor
(degumming) dan asam-asam lemak bebas (dengan netralisasi
dan steam refining) disebut dengan refined fatty oil atau straight
vegetableoil (SVO). SVO didominasi oleh trigliserida sehingga
memiliki viskositas dinamik yang sangat tinggi dibandingkan
dengan solar (bisa mencapai 100 kali lipat, misalkan pada
Castor Oil. Oleh karena itu, penggunaan SVO secara langsung
di dalam mesin diesel umumnya memerlukan
modifikasi/tambahan peralatan khusus pada mesin, misalnya
penambahan pemanas bahan bakar sebelum sistem pompa dan
injektor bahan bakar untuk menurunkan harga viskositas.
Viskositas (atau kekentalan) bahan bakar yang sangat
tinggi akan menyulitkan pompa bahan bakar dalam mengalirkan
bahan bakar ke ruang bakar. Aliran bahan bakar yang rendah
akan menyulitkan terjadinya atomisasi bahan bakar yang
baik. Buruknya atomisasi berkorelasi langsung dengan
kualitas pembakaran, daya mesin, dan emisi gas buang.
Pemanasan bahan bakar sebelum memasuki sistem pompa
dan injeksi bahan bakar merupakan satu solusi yang paling
dominan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul
pada penggunaan SVO secara langsung pada mesin diesel. Pada
umumnya, orang lebih memilih untuk melakukan proses kimiawi
pada minyak mentah atau refined fatty oil/SVO untuk menghasilkan
metil ester asam lemak (fatty acid methyl ester - FAME)
yang memiliki 73 berat molekul lebih kecil dan viskositas
20
setara dengan solar sehingga bisa langsung digunakan dalam
mesin diesel konvensional.
Biodiesel umumnya diproduksi dari refined vegetable oil
menggunakan proses transesterifikasi. Proses ini pada
dasarnya bertujuan mengubah [tri, di, mono] gliserida
berberat molekul dan berviskositas tinggi yang mendominasi
komposisi refinedfatty oil menjadi asam lemak methil ester
(FAME).
Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat
diperbaharui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara
lain : jarak pagar, kelapa, sawit, kedele, jagung, rape
seed, kapas, kacang tanah. Selain itu ,biodiesel juga bisa
dihasilkan dari lemak hewan dan minyak ikan.
4.2. Sifat Fisika Dan Kimia
Biodiesel dihasilkan dari minyak nabati, seperti kelapa
sawit, jarak pagar, kacang tanah, kelapa, dan lain
sebagainya. Indonesia, sebagai negara agraria, mempunyai
peluangsangat besar untuk mengembangkanBiofuel sebagai
energi alternatif pengganti minyak diesel (solar).
Sifat fisika dan kimia biodiesel:
Sifat fisik / kimia BiodieselKomposisi Ester alkil
Densitas, g/ml 0,8624Viskositas, cst 5,55Titik kilat, oc 172Angka setana 62,4
Perbandingan sifat fisik dan kimia biodiesel dan solar
Sifat fisik / Biodiese Solar
21
kimia l
Komposisi Esteralkil
Hidrokarbon
Densitas, g/ml 0,8624 0,8750Viskositas, cSt 5,55 4,6Titik kilat, oC 172 98Angka setana 62,4 53Energi yangdihasilkan
40,1MJ/kg
45,3MJ/kg
Dibandingkan dengan minyak solar, biodiesel mempunyai
beberapa keunggulan. Keunggulan utamanya adalah emisi
pembakarannya yang ramah lingkungan karena mudah diserap
kembali oleh tumbuhan dan tidak mengandung SOx.
Perbandingan emisi pembakaran biodiesel dengan minyak solar
disajikan dalam Tabel 3.
Perbandingan emisi pembakaran biodiesel dengan solar
Senyawa emisi Biodiesel SolarSO2, ppm 0 78NO, ppm 37 64NO2, ppm 1 1CO, ppm 10 40
Partikulat, mg/Nm3 0,25 5,6Benzen, mg/Nm3 0,3 5,01Toluen, mg/Nm3 0,57 2,31Xilen, mg/Nm3 0,73 1,57
Etil benzen, mg/Nm3 0,3 0,73Bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan biodiesel
sebagai berikut:
1. Metanol.
22
Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol atau spritus.
Metanol adalah bentuk alkohol yang paling sederhana.
Metanol diproduksi secara alami oleh bekteri diudara.
Sifat fisika dan kimia metanol sebagai berikut:
Sifat kimia dan fisika
rumus molekul CH3OH
massa molar 32.04 g/mol
densitas 0.7918 g/cm³, liquid
2. Minyak jelantah
Minyak jelantah adalah minyak limbah yang berasal dari
jenis-jenis minyak seperti minya jagung, minyak sayur,
minyak samin dan sebagainya, yang telah dipakai
sebelumnya. Minyak jelantah yang digunakan berulang-ulang
dapat merusak kesehatan manusia yang menimbulkan penyakit
kangker, dan menguangi kecerdasan generasi berikutnya
karena terdapat senyawa-senyawa yang bersifat
karsinoginetik yang terjadi saat pengorengan. Minyak
jelantah yang digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah
minyak jelantah yang sekali pemakaian.
3. Katalis
Seperti reaksi kimia pada umumnya, pada reaksi
esterifikasi dan transesterifikasi ditambahkan katalis
untuk mempercepat laju reaksi dan meningkatkan perolehan.
Katalis dapat menurunkan energi aktifitasi pada suatu
zat. Zat yang memiliki energi aktifitasi akan sulit
meregangkan gugus senyawanya sehingga reaksi akan lama
23
terjadi dan untuk mempercepatnya dibutuhkan katalis untuk
mempercepat reaksi.
Untuk pembuatan biodiesel mengunakan katalis NaOH
(natrium hidroksida) juga dikenal sebagai soda kaustik
atau sodium hidroksida adalah sejenis basa logam basa
logam kaustik. Natrium hiroksida membentuk larutan
alkalin yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. NaOH
juga digunakn dalam pembuatan biodiesel dari minyak
jelantah sebagai katalis.
Adapun sifat fisika dan kimia NaOH sebagai berikut:
3.3. Standar Kualitas
Standard Eropa untuk
biodiesel adalah nomor
EN 14214, yang mana dapat
diartikan ke dalam standard
nasional masing-masing
negara yang dibentuk oleh
CEN area (Committee for European Standardization) sebagai
contoh, untuk United Kingdom, BS EN 14214 dan untuk Jerman
DIN EN 14214.Terdapat spesifikasi standard lain. ASTM
D6751 adalah referensi standard yang umum digunakan di
United States dan Kanada.Selain itu, terdapat juga penamaan
DIN standard untuk 3 jenis biodiesel, yang mana dibuat
sesuai dengan jenis sumber bahan baku:
- RME (rapeseed methyl ester, sesuai dengan DIN E 51606)
24
Sifat fisika dan fisikaNaOH
Massamolar
39,9971g/mol
Titikdidih 1390 0C
Titikleleh 3180C
Densitas 2,1 g/cm3
Kelarutan Larut dalamair
- PME (vegetable methyl ester, minyak sayur murni, sesuai
dengan DIN E 51606)
- FME (fat methyl ester, produk minyak sayur dan lemak,
sesuai dengan DIN V 51606)
Tabel persyaratan biodiesel yang ditetapkan oleh SNI
No. Parameter Satuan Nilai1. Massa jenis pada 40 ˚C kg/m3 840-890
2. Viskositas kinematik pada 40 ˚C mm2/s 2,3-6,0
3. Angka setana min. 51
4. Titik nyala (mangkok tertutup) (cSt) maks.
1005. Titik kabut ˚C maks.18
4.4. Proses Pembuatan Biodisel
Proses pembuatan biodiesel dari minyak dengan
kandungan FFA rendah secara keseluruhan terdiri dari reaksi
transesterifikasi, pemisahan gliserol dari metil ester,
pemurnian metil ester (netralisasi, pemisahan methanol,
pencucian dan pengeringan/dehidrasi), pengambilan gliserol
sebagai produk samping (asidulasi dan pemisahan metanol)
dan pemurnian metanol tak bereaksi secara
destilasi/rectification. Proses esterifikasi dengan katalis
asam diperlukan jika minyak nabati mengandung FFA di atas
5%. Jika minyak berkadar FFA tinggi (>5%) langsung
ditransesterifikasi dengan katalis basa maka FFA akan
25
bereaksi dengan katalis membentuk sabun. Terbentuknya sabun
dalam jumlah yang cukup besar dapat menghambat pemisahan
gliserol dari metil ester dan berakibat terbentuknya emulsi
selama proses pencucian. Jadi esterifikasi digunakan
sebagai proses pendahuluan untuk mengkonversikan FFA
menjadi metil ester sehingga mengurangi kadar FFA dalam
minyak nabati dan selanjutnya ditransesterifikasi dengan
katalis basa untuk mengkonversikan trigliserida menjadi
metil ester.
Pembuatan biodiesel dari minyak tanaman memiliki
kasus yang berbeda-beda sesuai dengan kandungan FFA. Pada
kasus minyak tanaman dengan kandungan asam lemak bebas
tinggi dilakukan dua jenis proses, yaitu esterifikasi dan
transesterifikasi, sedangkan untuk minyak tanaman yang
kandungan asam lemak rendah dilakukan proses
transesterifikasi. Proses esterifikasi dan
transesterifikasi bertujuan untuk mengubah asam lemak bebas
dan trigliserida dalam minyak menjadi metil ester
(biodiesel) dan gliserol.
Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak
bebas menjadi ester. Esterifikasi mereaksikan minyak lemak
dengan alkohol. Katalis-katalis yang cocok adalah zat
berkarakter asam kuat. biasanya asam sulfat (H2SO4) atau
asam fosfat (H2PO4) .
Proses esterifikasi dengan katalis asam diperlukan
jika minyak nabati mengandung FFA di atas 2%. Jika minyak
berkadar FFA tinggi (>2%) langsung ditransesterifikasi
26
dengan katalis basa maka FFA akan bereaksi dengan katalis
membentuk sabun. Terbentuknya sabun dalam jumlah yang cukup
besar dapat menghambat pemisahan gliserol dari metil ester
dan berakibat terbentuknya emulsi selama proses pencucian.
Jadi esterifikasi digunakan sebagai proses pendahuluan
untuk mengkonversikan FFA menjadi metil ester sehingga
mengurangi kadar FFA dalam minyak nabati dan selanjutnya
ditransesterifikasi dengan katalis basa untuk
mengkonversikan trigliserida menjadi metil ester.
Reaksi esterifikasi dari asam lemak menjadi metil ester
adalah :
Faktor-faktor yang berpengaruh pada reaksi esterifikasi
antara lain:
a. Waktu Reaksi
Semakin lama waktu reaksi maka kemungkinan kontak antar
zat semakin besar sehingga akan menghasilkan konversi
yang besar. Jika kesetimbangan reaksi sudah tercapai
maka dengan bertambahnya waktu reaksi tidak akan
menguntungkan karena tidak memperbesar hasil.
b. Pengadukan
Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara
molekul zat pereaksi dengan zat yang bereaksi sehingga
mempercepat reaksi dan reaksi terjadi sempurna. Sesuai
dengan persamaan Archenius. Dimana semakin besar tumbukan
maka semakin besar pula harga konstanta kecepatan reaksi.27
Sehingga dalam hal ini pengadukan sangat penting
mengingat larutan minyak-katalis metanol merupakan
larutan yang immiscible.
c. Katalisator
Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi
pada suatu reaksi sehingga pada suhu tertentu harga
konstanta kecepatan reaksi semakin besar.
d. Suhu Reaksi
Semakin tinggi suhu yang dioperasikan maka semakin banyak
konversi yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan persamaan
Archenius. Bila suhu naik maka harga k makin besar
sehingga reaksi berjalan cepat dan hasil konversi makin
besar.
Transesterifikasi (biasa disebut dengan alkoholisis)
adalah tahap konversi dari trigliserida (minyak nabati)
menjadi alkyl ester, melalui reaksi dengan alkohol, dan
menghasilkan produk samping yaitu gliserol. Di antara
alkohol-alkohol monohidrik yang menjadi kandidat
sumber/pemasok gugus alkil, metanol adalah yang paling umum
digunakan, karena harganya murah dan reaktifitasnya paling
tinggi (sehingga reaksi disebut metanolisis). Jadi, di
sebagian besar dunia ini, biodiesel praktis identik dengan
ester metil asam-asam lemak (Fatty Acids Metil Ester,
28
FAME). Reaksi transesterifikasi trigliserida menjadi metil
ester sebagai berikut:
Transesterifikasi juga menggunakan katalis dalam
reaksinya. Tanpa adanya katalis, konversi yang dihasilkan
maksimum namun reaksi berjalan dengan lambat. Katalis yang
biasa digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah
katalis basa, karena katalis ini dapat mempercepat reaksi.
Tahapan reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel
selalu menginginkan agar didapatkan produk biodiesel dengan
jumlah yang maksimum.
Faktor-faktor yang mempengaruhi transesterifikasi :
a. Pengaruh air dan asam lemak bebas
Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi harus
memiliki angka asam yang lebih kecil dari 1. Banyak
peneliti yang menyarankan agar kandungan asam lemak bebas
lebih kecil dari 0.5% (<0.5%). Selain itu, semua
bahan yang akan digunakan harus bebas dari air.
Karena air akan bereaksi dengan katalis, sehingga
jumlah katalis menjadi berkurang. Katalis harus
terhindar dari kontak dengan udara agar tidak mengalami
reaksi dengan uap air dan karbon dioksida.
29
b. Pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah
Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan
untuk reaksi adalah 3 mol untuk setiap 1 mol
trigliserida untuk memperoleh 3 mol alkil ester
dan 1 mol gliserol. Secara umum ditunjukkan bahwa
semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka
konversi yang diperoleh juga akan semakin
bertambah. Pada rasio molar 6:1, setelah 1 jam konversi
yang dihasilkan adalah 98-99%, sedangkan pada 3:1
adalah 74-89%. Nilai perbandingan yang terbaik
adalah 6:1 karena dapat memberikan konversi yang
maksimum.
c. Pengaruh jenis alkohol
Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan perolehan
ester yang tertinggi dibandingkan dengaan menggunakan
etanol atau butanol.
d. Pengaruh jenis katalis
Alkali katalis (katalis basa) akan mempercepat reaksi
transesterifikasi bila dibandingkan dengan katalis asam.
Katalis basa yang paling populer untuk reaksi
transesterifikasi adalah natrium hidroksida (NaOH),
kalium hidroksida (KOH), natrium metoksida (NaOCH3),
dan kalium metoksida (KOCH3).
e. Pengaruh temperatur
Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada temperatur
30 - 65° C (titik didih metanol sekitar 65° C). Semakin
30
tinggi temperatur, konversi yang diperoleh akan semakin
tinggi untuk waktu yang lebih singkat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Hart, Harold. 2013. Kimia Organik Suatu Kuliah Singkat.
Jakarta: Erlangga.
2. http://ocw.usu.ac.id/course/download/4140000062-
teknologi-oleokimia/tkk-322_handout_deterjen.pdf
3. https://www.scribd.com/doc/111411537/aaa
4. http://directory.umm.ac.id/penelitian/PKMI/pdf/INDUSTRI
%20KECIL%20DETERJEN%20CAIR.pdf
5. https://www.scribd.com/doc/67060407/Lipid-Dan-Deterjen#
6. https://www.scribd.com/doc/30631776/Makalah-Kimia-
Organik-tengik1
7. http://edukasi.kompasiana.com/2011/12/19/biodiesel-
423260.html
31