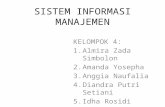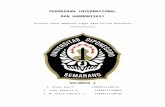LAPORAN TUGAS KELOMPOK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AKHLAK MANUSIA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
Tugas Kelompok
Transcript of Tugas Kelompok
Tugas Kelompok
Mata Kuliah : Issue dan Formulasi Kebijakan Publik
Nama Dosen : Rina Herlina Haryanti, M.Si
Anggota Kelompok: NIM.( S240908005)-Ferry Asmoro
NIM.( S241208005)-Ir. Sri Kusrini
Maruti
NIM.( S241208012)-Umi Raestyawati
NIM.( S241208013)-Anies Fortuna
NIM.( S241208016)-Muhama Lohmi
NIM.( S241208017)-Andy Arya Maulana W
Tugas Kelompok :
Diskusikan bagaimana proses sebuah issue berhasil mendapatkan
status sebagai masalah publik?
Menurut :
A. Perspektif administratif
B. Perspektif teknokratis
C. Perspektif governance
1
D. Perspektif democratic-governance
E. Perspektif konflik
F. Perspektif advokasi
Sebuah issue berhasil mendapatkan status sebagai masalah
publik, tentunya memerlukan proses. Dalam hal ini adalah tahapan
– tahapan alamiah maupun prosedural yang harus dilalui. Tahap-
tahap kebijakan publik menurut William Dunn, adalah sebagai
berikut:
1. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat
strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah,
ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan
prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah issue
berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan
mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka issue tersebut
berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih
daripada issue lain.
Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan
suatu issue publik yang akan diangkat dalam suatu agenda
pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga
sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues
biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara
para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh,
atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan
tersebut. Menurut William Dunn (1990), issue kebijakan merupakan
produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan,
rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah
2
tertentu. Namun tidak semua issue bisa masuk menjadi suatu
agenda kebijakan.
Ada beberapa Kriteria issue yang bisa dijadikan agenda
kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980;
Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:
1) Telah mencapai titik kritis tertentu à jika diabaikan, akan
menjadi ancaman yang serius;
2) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu à berdampak
dramatis;
3) Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak
(umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4) Menjangkau dampak yang amat luas ;
5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6) Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan,
tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak
disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang
lama.
Contoh : Legislatif negara ( DPR ) menyiapkan Rancangan
Undang-Undang, dan mengirimkannya kepada Komisi Kesehatan dan
Kesejahteraan untuk dipelajari terlebih dahulu dan kemudian
disetujui. Namun pada kenyataannya RUU berhenti di Komisi dan
tidak terpilih menjadi Agenda.
Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan
berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga
keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh
mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan
stakeholder.
3
2. Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan
perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan,
dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil
untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada
proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu
masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan
mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya
bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk
rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat
baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota
mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola
melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui
proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai
kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini,
evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya,
4
evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,
melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan
masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk
menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap
dampak kebijakan.
Kami berdiskusi dan bersama – sama mengkaji proses tersebut
sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami, dimulai dari
Perspektif A sampai dengan Perspektif F.
================================================================
=====
A. Perspektif administratif
Perspektif Administrasi tidak mungkin lepas dari Pemerintah
sebagai Penyelenggara pemerintahan yang seperti diketahui
bersama bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Administratif
cenderung bersifat Hierarki dan Prosedural. Dalam hal ini
Pemerintah dalam melaksanakan Fungsi Administratif melalui
Pelayanan Masyarakatnya / Publik biasa disebut Birokrasi.
Pemikiran Max Weber tentang birokrasi, oleh Jay M Shafritz
(1978) diklasifikan sebagai pemikiran Old Administration Paradigm
(Paradigma Administrasi Klasik). Hal ini disandarkan pada ciri
khas paradigma Administrasi Klasik, yang menekankan pada aspek
birokrasi di dalam analisis-analisis administrasi negara hingga
tahun 1970-an. Selain itu, analisis birokrasi yang
5
dikemukakannya sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran birokrasi
selanjutnya.
Di dalam analisis birokrasinya, Weber mempergunakan
pendekatan “ideal type”. Tipe ideal merupakan konstruksi abstrak
yang membantu kita memahami kehidupan sosial. Weber berpendapat
adalah tidak memungkinkan bagi kita memahami setiap gejala
kehidupan yang ada secara keseluruhan. Adapun yang mampu kita
lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu
hal yang amat penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa
diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu, dan apa yang
membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya.
Dengan demikian tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita
bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting dan
krusial yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu
dengan lainnya. Dengan cara semacam ini kita menciptakan tipe
ideal tersebut (Thoha, 2004)
Dalam keseluruhannya, karya Weber mendorong tumbuhnya paham
pesimisme. Sedikit sekali memberikan alternatif dari hak-hak
bagi manusia untuk melakukan pilihan. Berbagai tragedi
kemanusiaan akibat dari ajaran ini, merupakan sesuatu yang
berharga dimana manusia dalam masyarakat yang modern harus
memberikan perhatian guna menghindari terjadinya berbagai
kekacauan. Teknik-teknik demokrasi seperti referendum, pemilu,
dan lembaga perwakilan adalah teknik-teknik yang dipergunakan
untuk mengurangi jalur-jalur berlanjutnya dominasi birokrasi
(phenomena birokratik). Seperti diamati Daniel Bell: “Bagi Weber
sebuah nilai etik dan gaya hidup, mulai menguasai kehidupan
seluruh masyarakat” (Bell, 1973). Di dalamnya mencakup paham
universal tentang kesesuaian (conformity), ketidakmemihakkan
6
(impersonality), dan perhitungan secara rasional (rational calculation),
dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir manusia yaitu efisiensi,
ketepatan (preciseness) dan kepatuhan (obidience).
Menurut David Beentham (1975), Weber memperhitungkan tiga
elemen pokok dalam konsep birokrasinya. Tiga elemen itu antara
lain: pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis
(technical instrument). Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang
independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai
kecenderungan yang melekat (inherent tendency) pada penerapan fungsi
sebagai instrumen teknis tersebut. Ketiga, pengembangan dari sikap
ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka
dari kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang
partikular. Dengan demikian birokrasi bisa keluar dari fungsinya
yang tepat karena anggotanya cenderung datang dari klas sosial
yang partikular tersebut.
Contoh nyata dari Perspektif ini salah satunya adalah
adanya Agenda Pemerintah menggodok materi dan formulasi yang
tepat, yang pada akhirnya keluar Produk Kebijakan yaitu UU
Otonomi Daerah ( UU No 22 Tahun 1999 ) yang kemudian
disempurnakan pelaksanaanya dengan dikeluarkannnya UU No. 32
Tahun 2004. Sebelum keluarnya Produk Hukum ini, issue
Sentralisasi Wewenang dan Kebobrokan Birokrasi selama Masa Orde
Baru, membuat masing-masing pemerintah Daerah merasa terpasung
dan tidak dapat memberdayakan serta mengembangkan daerahnya
masing-masing, segala sesuatu bersifat sentralistik, kemudian
dengan melalui pergolakan panjang serta proses seiring
terjadinya perubahan masa Kepemimpinan menjadi Orde Reformasi
yang merubah paradigma Birokrasi baru, yang notabene menerapkan
sistem Desentralisasi, yaitu pelimpahan Wewenang Pemerintah
7
Pusat Kepada Daerah untuk mengelola dan memberdayakan Potensi
daerahnya masing-masing.
B. Perspektif Teknokrat
Proses sebuah issue berhasil mendapatkan status sebagai
masalah publik dipandang dari Perspektif Teknokratis. Sudut
pandang kali ini adalah dimana seluruh kebijakan pemerintah yang
ada, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran para aktor yang
berada di balik proses formulasi kebijakan. Peran sentral dalam
pembentukan sebuah kebijakan publik biasanya dipegang oleh para
pakar dan ahli yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Para
aktor tersebut bukan berasal dari birokrat namun biasanya
berasal dari profesional seperti analis, dosen, peneliti,
teknisi dan lain sebagainya yang ikut berkiprah dalam
pemerintahan, dan mereka disebut dengan teknokrat.
Telah diketahui bersama bahwa Publik dan Pemerintah, mereka
menaruh kepercayaan sangat tinggi kepada para Teknokrat.
Teknokrat adalah orang-orang yang dianggap mampu serta
profesional dalam mengamati dan menganalisa permasalahan publik.
Namun disisi lain kehadiran para Teknokrat dapat melahirkan
ketergantungan, yaitu ketika dalam setiap pengambilan kebijakan
Teknokrat menjadi aktor penentu utama. Bila hal ini diteruskan
maka akan menimbulkan kondisi Teknokratisme yaitu monopoli dalam
manajemen organisasi dan sumber daya negara oleh para teknokrat.
8
Jika dikaitkan dengan proses mengkaitkan masalah dengan
solusi, karena seringkali dalam perumusan kebijakan pemerintah
sering abai mengkaitkannya. Seharusnya dalam proses ini,
teknokrat dan akademisilah yang lebih dominan berupaya
meyakinkan pihak birokrat atau politisi, melalui alternatif-
alternatif solusi masalah. Teknokrat dan akademisi inilah yang
disebut dengan policy entrepreneur.
Selama ini para Teknokrat di negeri kita cenderung tertutup
dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Sifat eksklusif ini
terlihat manakala para teknokrat merasa tidak perlunya
berkoordinasi dengan para birokrat dan stakeholder untuk
menyelesaikan masalah publik, hal ini patut diwaspadai
dikarenakan dalam perumusan suatu kebijakan publik, tidak bisa
dihindari adanya kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak
yang turut mewarnai. Ada beberapa kelemahan dari sebuah
kebijakan yang dibuat oleh para teknokrat negeri ini, antara
lain :
Pertama, sifat eksklusivitas teknokrat membuat proses
pembentukan kebijakan menjadi tidak transparan sehingga
kebijakan yang dihasilkan terkesan kental dengan unsur politis
dan serta berpihak kepada kekuasaan yang lebih tinggi, contoh:
Kebijakan dalam masalah Blok Cepu yang jatuh ke tangan Exxon
Mobile USA dengan jalan menyelipkan pasal 103A kedalam Peraturan
Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi sehingga jalannya Exxon Mobile sebagai raksasa minyak
dunia untuk menguasai Blok Cepu dapat mulus tanpa hambatan.
Kedua, kebijakan yang dihasilkan dissuesun oleh para
teknokrat secara teoretis tidak memiliki basis teori yang solid
dan kohesif sebab sangat miskin aspek multidisiplinernya.
9
Padahal, pendekatan multidisipliner sangat diperlukan dalam
melihat aspek kehidupan masyarakat yang sangat beragam
persoalannya, contoh: Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Berdasarkan
peraturan tersebut, disebutkan adanya batas minimal perlindungan
Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung bervegetasi sebesar 45%
dari luas Pulau Kalimantan. Namun, peraturan ini menghilangkan
status Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada pada Kawasan
Hutan Negara. Kehilangan status ini ternyata berimplikasi pada
ancaman de-forestasi yang lebih serius di Provinsi Kalimantan
Tengah.
Ketiga, kebijakan yang didominasi oleh para pakar dan elite
membuat bahasa dan kebijakannya sangat sulit dimengerti rakyat
banyak. Masyarakat dalam proses kebijakan ini hanya menerima apa
yang diputuskan oleh para pakar dan elite. Sering terjadi dalam
kenyataan sosial bahwa bahasa dan pikiran para pakar tidak
sesuai dengan tuntutan dan pola pikir masyarakat. Sebagai contoh
kasus adalah Bailout Bank Century, rakyat dibohongi dengan
mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sangat stabil dan
percaya diri, namun hari berikutnya mereka mengadakan rapat KSSP
(Komite Stabilitas Sektor Keuangan) untuk memberikan FPJP
(Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek) kepada Bank Century yang
kalah kliring dengan alasan bahwa sekecil apa pun, sebuah bank
dalam keadaan krisis akan menimbulkan dampak sistemik karena
faktor psikologis pasar sudah terpengaruh suasana krisis.
Akibatnya, orang akan melakukan rush apabila ada bank yang gagal
dan ditutup.
10
Keempat, pada praktiknya seringkali kebijakan publik yang
dilakukan para teknokrat justru gagal mengantisipasi dampak-
dampak yang tidak diinginkan dan lemah dalam penerapannya.
================================================================
=====
C. Perspektif Governance
Governance dapat diartikan sebagai Tata pemerintahan yang
baik, dimana hal ini lebih melihat bagaimana sebuah pemerintahan
dijalankan dengan baik. Istilah governance mengacu pada proses
pemerintahan; atau kondisi yang berubah dari pelaksanaan aturan;
atau metode baru untuk memerintah masyarakat (Rhodes, 1996).
Sedangkan definisi lain dikemukakan oleh Minogue (1998), yang
mengungkapkan empat komponen utama yaitu legitimacy menyiratkan
kepedulian terhadap yang diperintah, Accountbility yang meliputi
adanya tanggung jawab dari pejabat publik dan pemimpin politik,
competence dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang
tepat dan memberikan pelayanan publik yang efisien, sementara
penghargaan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia
menjadi penopang seluruh sistem pemerintahan yang baik.
Secara ringkas Perspektif Governance saat ini adalah
Perspektif Good Governance atau Manajemen Publik Baru (MPB) memiliki
dua arti, yaitu : Manajerialisme dan Ekonomi Institusional baru.
Manajerialisme mengacu pada pengenalan metode-metode manajemen
sektor privat ke dalam sektor publik. Ini menekankan pada
penguasaan manajemen profesional; standar dan pengukuran kinerja
11
yang jelas; mengelola berorientasi hasil; nilai uang; dan yang
terbaru adalah kedekatan dengan pelanggan.
Ekonomi Institusional baru mengacu kepada pengenalan
struktur intensif (seperti persaingan pasar) ke dalam kebijakan
publik. Ini menekankan kepada pemecahan birokrasi; persaingan
yang lebih besar melalui sistem kontrak dan pasar semu dan
pilihan pelanggan.
MPB relevan dalam diskusi mengenai governance, karena
pengendalian (steering) merupakan pusat untuk analisis menajemen
publik dan pengendalian sinonim dengan governance. Contoh, Osborne
dan Gaebler (1992) yang membedakan antara “keputusan kebijakan”
(steering) dan “pengantaran pelayanan” (rowing), menyatakan
bahwa birokrasi merupakan alat yang bangkrut untuk pengantaran.
Secara jelas MPB, berarti Pemerintahan dan Wirausaha
memikul tanggung jawab bersama dalam hal kompetisi, pasar,
pelanggan dan hasil. Transformasi nilai sektor publik ini
berkaiatan dengan “pengurangan peran pemerintah” (berkurangnya
pendayung “rowing”). Sehingga memperkuat governance ( lebih kepada
pengendalian/ “steering”).
Pada intinya governance diartikan sebagai pelaksanaan
kekuasaan politik untuk mengelola masalah-masalah negara dan
good government”, meliputi : pelayanan publik yang diaudit dan
memiliki akuntabilitas terbuka dan efisien dengan birokrasi yang
berkompetensi untuk membantu merancang dan menerapkan kebijakan
dan pengelolaan yang tepat pada sektor publik yang ada. Dan
untuk memenuhi efisien dalam pelayanan publik, Bank Dunia
menuntut didorongnya keompetisi dan pasar; privatisasi
perusahaan publik; reformasi pelayanan sipil dengan mengurangi
staf yang terlalu banyak; memperkenalkan disiplin anggaran;
12
mendesentralisasikan administrasi; dan mendorong berkembangnya
organisasi non pemerintah. Pendeknya, good government mengawinkan
manajemen publik baru dengan kelebihan demokrasi liberal.
Secara ringkas fungsi pemerintah dalam governance
menempatkan posisi pemerintah sebagai pengarah (steering),
dimana pada prosesnya juga melibatkan 3 pihak yaitu pemerintah,
masyarakat dan pihak swasta. Dalam perspektif governance,
kebijakan publik dirumuskan oleh tiga pihak tersebut.
Contoh nyata perspektif ini, adalah Keberadaan PT.
Freeport yaitu pihak Swasta atau Organisasi Non Pemerintah yang
dirangkul Pemerintah untuk menangani Pengelolaan dan Pengolahan
Tambang Emas di Wilayah Papua, yang notabene masyarakatnya masih
belum sejahtera dengan latar belakang yang masih di bawah rata
– rata, dengan keinginan penghidupan yang layak, sejahtera dan
lebih maju, namun berjalannya waktu muncul Gap (masalah) dimana
masyarakat merasakan bahwa apa yang diharapkan tidak terwujud
dan timbul gejolak, mereka merasa dibohongi, miskin di tengah
kekayaan tanah airnya, dengan dibantu LSM, Walhi, dll, terutama
Pengamat Lingkungan, masyarakat Papua berpendapat dan berjuang
untuk mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang Kontrak
Freeport di Indonesia, yang pada akhirnya issue ini menjadi
Masalah Publik, dan bukan sekedar Masalah Publik namun juga
menjadi perhatian dan agenda pemerintah untuk menindaklanjutinya
dan meningkat pada tahapan untuk mengAgendakan pembahasan dan
Kebijakan apakah akan terus diadakan perpanjangan kontrak dengan
PT. Freeport, sebagai bentuk perhatian Pemerintah dalam
pemenuhan keinginan masyarakat Papua untuk hidup layak dan
sejahtera atas kekayaan di tanah mereka sendiri.
13
D. Perspektif Democratic Governance
Makna “Democratic Governance dan Hak Azasi Manusia” jika ditarik ke
permasalahan tingkat lokal dalam otonomi daerah, maka pada
hakikatnya di dalam lokalitas pengurusan kehidupan publik dengan
kebijakan publik (public policy) inilah, secara langsung pemerintah
berkaitan dengan hak azasi warga. Kebijakan publik sebagai
pengaturan kehidupan warga di ruang publik (public-sphere), dan
berada di dalam lingkup sistemik melalui berbagai ketentuan
administratif negara, yang berlangsung di ruang publik dalam
lingkup fisik (public-space) di wilayah otoritas negara. Bagian
terbesar dari pengaturan ini sepanjang berhubungan dengan public-
space berada di bawah otoritas lokal.
Karenanya pembicaraan tentang democratic governance dalam kaitan
dengan hak azasi manusia dilihat dari keberadaan media pers dan
civil society, dengan menempatkannya untuk menghadapi sosok “mutan”
yang tersebar, ini tidak kalah peliknya dibanding dengan upaya
memaksa turun penguasa Orde Baru. Sebab langkah yang harus
ditempuh adalah menumbuhkan tata nilai bersifat komprehensif
yang mencakup sistem dan prosedur atas aspek-aspek
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota dan propinsi; kerja
sama antar kabupaten/ kota dalam satu propinsi atau beda
propinsi, dan kerjasama antar propinsi; serta partisipasi warga
masyarakat sebagai pelaku yang harus mengambil bagian aktif
(stakeholders) di ruang publik.
14
Persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan pada
tingkat lokal adalah reformasi dalam sistem dan nilai yang
diwujudkan dengan good governance yang dilihat melalui prinsip
keterbukaan (disclosure) dan akuntabilitas publik (public
accountability). Berbarengan dengan proses otonomi daerah maka
setiap daerah otonomi diharapkan dapat menjadi suatu entitas
sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar good
governance di satu pihak, dan partisipasi warga di ruang publik
pada pihak lain.
Dalam entitas sosial, lingkup daerah secara empiris adalah
interaksi yang berlangsung antara warga masyarakat dengan
penyelenggara pemerintahan (eksekutif dan legislatif) dengan
titik temunya adalah melalui kebijakan publik (public policies) dan
pelayanan publik (public services).
Transformasi pemerintahan selayaknya pula diikuti dengan
reformasi sosial sehingga kehidupan di ruang publik lebih
kondusif untuk terwujudnya civil society. Membangun civil society pada
dasarnya adalah membalik arus utama proses kebijakan yang
tadinya bersifat top-down dari kekuasaan negara ke warga
masyarakat, ditransformasikan agar tercipta proses arus bersifat
sharing dari warga sebagai pelaku yang mengambil bagian aktif di
ruang publik ke kebijakan yang dikeluarkan kekuasaan negara.
Untuk itu diperlukan partisipasi warga dalam kehidupan di ruang
publik dengan acuan nilai bersama atas dasar kebebasan pers.
(Mengutip Materi yang disampaikan pada Workshop “Democratic
Governance in Theory: Sebuah Gugatan atas Konsep Good Governance”, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 16 – 18 September 2004).
15
Sebuah issue berhasil menjadi agenda kebijakan menurut
Perspektif Democratic Governance, penekanannya adalah pada
Partisipasi atau peran serta masyarakat. Partisipasi menjadi mutlak
dalam rangka menjalankan prinsip demokratisasi pemerintah.
Idealnya peran serta masyarakat dalam pemerintahan dilibatkan
sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan,
yang demikian dikenal sebagai makna etimologis dan idealis
Demokrasi yang berasal dari Kata Demos – Kratein, artinya “Dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perwujudan nyata dari
demokrasi ada pada tingkatan sejauh mana rakyat turut berperan
dalam perencanaan pemerintah menentukan kebijakan publik. Ini
berhubungan pula sejauh mana aspirasi masyarakat dapat
tertampung oleh pemerintah dan sampai dimana pengetahuan
masyarakat mengenai haknya sebagai warga negara untuk turut
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan
pemerintah.
Secara nyata Democratic Governance dapat dilihat secara
nyata adalah pada Era reformasi suasana kebebasan Pers sangat
nampak terlihat. Alasan normatif atas signifikansi kebebasan
pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada
kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan
pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara
untuk mengetahui (right to know) masalah-masalah publik, dan di
pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan
pendapatnya (right to express). Karenanya kebebasan pers dilihat
bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme (secara
berganti digunakan istilah media pers untuk pengertian yang
sama) yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak
boleh terputus dalam proses demokrasi.
16
Inilah yang mendasari pemikiran mengapa warga harus
dijamin haknya untuk mengetahui permasalahan di ruang publik,
dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan
pendapat, kesemuanya perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi
dan civil society.
Kebebasan pers bukan hanya menyangkut keberadaan media
pers, tetapi pada dasarnya mencakup suatu rantai dalam proses
demokrasi. Sekaligus melalui kebebasan pers dituntut
akuntabilitas sosial institusi pers dalam konteks proses ini.
Proses demokrasi dalam perspektif media mencakup: bermula dari
dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta
publik (public fact) yang memiliki signifikansi sebagai masalah
publik (public issue). Masalah (issue) publik dapat diartikan
sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat
terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya.
Issue publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan
independen) dalam kaidah obyektivitas oleh media pers sebagai
informasi jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme akan
menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik (public
opinion). (Gurevitch dan Blumler, 1990; Hennessy, 1981).
Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon
terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan publik.
Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai
dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat
diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat
terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro
dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik, baik
berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam
melayani warga masyarakat. Muara dari seluruh proses ini adalah
17
pelayanan publik dan akuntabilitas (accountability) atau
pertanggungjawaban, sebagai ciri dari birokrasi publik
(pemerintahan) dalam norma demokrasi (Coob, 1981).
Dengan begitu basis kehidupan warga dalam ruang publik
adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat
benar dan obyektif sehingga dapat membentuk pendapat publik
secara rasional, untuk kemudian dapat ambil bagian (sharing) dalam
kehidupan publik. Dengan demikian akuntablitas atau
pertanggungjawaban dari media jurnalisme dilihat dengan
parameter yang melekat dalam proses fungsinya keberadaan dan di
ruang publik.
Ruang publik dapat dilihat dari posisi warga masyarakat
sebagai warga yang bersentuhan atau merespon kekuasaan dari 3
ranah, yaitu di satu pihak dalam lingkup kekuasaan negara (state),
dalam pada pihak lain dalam lingkup kapitalisme pasar (market
capitalism) dan kolektivitas sosial (communalism). Dari dua yang
terakhir inilah muncul 3 stakeholders di ruang publik, berupa
kekuatan pasar melalui korporasi komersial dan organisasi
masyarakat sipil seperti partai politik, organisasi keagamaan,
serikat buruh, dan lainnya. Kedudukan warga dapat terdominasi
dalam sistem hegemonik manakala warga hanyalah sebagai konsumen
atau pengguna (users) kebijakan publik yang diproduksi kekuasaan
negara.
Begitu pula dalam menghadapi kekuasaan pasar, warga
masyarakat sebagai konsumen, yang dieksploitasi dari sisi nilai
ekonomis warga bagi kapitalis. Disini biasa dibedakan korporasi
komersial bersifat swasta (private), dengan korporasi yang
keberadaannya mengambil modal publik (go public), sebab masing-
masing membawa konsekuensi berbeda bagi warga. Sementara dalam
18
konteks kolektivitas sosial, warga masyarakat dapat menjadi
massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh
homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme di bawah
kepemimpinan bersifat elitis dan patrimonial.
Warga pada hakikatnya memang hanya menjadi konsumen (users),
tidak pernah dapat menjadi faktor produktif dalam proses
kebijakan publik. Karenanya membicarakan hak-hak publik dalam
kaitan dengan kebijakan publik adalah dari pandangan ersifat
normatif. Karenanya dari sisi warga, kedudukan idealistiknya
dilihat pada kekuatan pasar dan organisasi masyarakat sipil,
sejauh mana dapat menjadi representasi dari kepentingan warga di
satu pihak, sehingga lebih jauh kebijakan publik memenuhi
kepentingan warga di pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan
korporasi dalam kekuasaan pasar dan organisasi masyarakat sipil
dalam konteks civil society, didefinisikan sebagai stakeholders dalam
penyelenggaraan kehidupan publik, melalui peranannya dalam
menghadapi kebijakan dan pelayanan publik guna menjaga agar hak
dan kepentingan warga (public interest) di ruang publik senantiasa
terpenuhi.
Dari sini dikembangkan perspektif kultural, yaitu ruang
publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di
dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal,
yang terbebas dari dominasi kekuasaan negara, pasar dan
kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, idealisasi
kehidupan publik diwujudkan melalui realitas kehidupan warga
masyarakat, dilihat dalam proses interaksi personal atas dasar
kultural. Ciri dari interaksi semacam ini adalah dengan
keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi.
Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar
19
menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (public discussion)
atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar
kekerasan (kekuatan fisik maupun psikologis), baik secara
personal, atau institusional oleh negara maupun kolektivisme
dalam masyarakat. Dari ruang publik idealistik inilah lahir
fungsi imperatif media pers, sebagai perpanjangan/ekstensi dari
ruang publik tersebut (Blumler, 1990; Zukin, 1981).
Contoh kasus saat ini adalah adanya gerakan sosial
masyarakat, LSM dan berbagai pihak dalam “Gerakan Koin untuk
KPK”. Gerakan koin untuk KPK ini dimaksudkan untuk memberikan
dukungan bagi KPK dalam membangun Gedung dan kontribusinya dalam
memberantas Korupsi di Indonesia. Hal ini dilakukan karena usulan
anggaran untuk perbaikan Gedung KPK yang sudah cukup tua tidak
disetujui oleh Pemerintah (Eksekutif), padahal saat ini
keperluan untuk membangun atau merenovasi gedung KPK cukup
mendesak. Setelah dilakukannya gerakan sosial oleh masyarakat,
LSM dan berbagai pihak yang tak lepas dari peran pihak media
massa yang menyajikannya ke dalam topik utama berita, guna
mendukung eksistensi fungsi dan keberadaan KPK dalam memberantas
korupsi, maka hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah yang
semula bahwa Pemerintah akan melakukan penangguhan anggaran
gedung KPK. Peran serta dan partisipasi elemen masyarakat
tersebut menuai hasil dan dampak, bahwa apa yang dilakukan
menjadikan issue sebagai agenda setting kebijakan Pemerintah
yang seperti diberitakan oleh Media Massa tepatnya Hari Jum”at
tanggal 12/10/2012, akhirnya presiden SBY menyetujui untuk
pemberian anggaran pembangunan gedung KPK.
Begitupula dengan Kondisi Orde Reformasi yang memberikan
ruang pada Publik atau Masyarakat dan pihak Swasta untuk ikut
20
berperan dan berpartisipasi aktif. Berkembangnya Multi Partai
yang dahulunya hanya Partai Golkar yang berkuasa dalam beberapa
dekade Kurun Waktu pemerintahan Orde Baru, sehingga issu
Kekuasaan Otoriter membuat berbagai fihak berfikir, bereaksi
dan bergerak terutama Kaum Akademisi, Civitas Akademik, serta
Wartawan sebagai Pihak Pers untuk meliput dan memberikan
informasi secara lebih terbuka dibandingkan pada masa Orde Baru,
sehingga hal – hal yang mungkin tidak nampak menjadi nampak,
termasuk penyebab utama issue mampu diangkat menjadi agenda
Pemerintah, mendapatkan perhatian sehingga perlu ditindak
lanjuti untuk kemudian dibuat rancangan solusi atau jawaban dari
permasalahan yang muncul.
Tidak terkecuali Perubahan Amandemen UUD 1945 yang
dilakukan empat kali berturut – turut sebagai tindak lanjut dari
Legalitas dan Supremasi Hukum atas penyimpangan Kepemimpinan dan
pengejawantahan Kedaulatan Negara dan Kekuasaan pemerintah yang
kemudian diputuskan bahwa Pasal 1 sampai dengan Pasal 7,
menegaskan tentang Kedaulatan Negara, dan Pemerintahan serta
rinci sampai kepada Masa Jabatan Kepala pemerintahan dan Kepala
Daerah hanya bisa dua kali periode masa jabatan pada posisi yang
sama, dengan asumsi jika terpilih kembali.
Hal terpenting, Amandemen UUD 1945 menjelaskan bahwa
penegakkan demokrasi oleh Pemerintah ditandai dengan pemenuhan
Hak Azasi dan Perlindungan Warga Negara di dalam UUD 1945
Amandemen secara lebih rinci dan jelas, mulai dari kebebasan
berserikat, berpendapat, berkumpul, mengembangkan diri dan
berorganisasi, terutama pada Pasal28 A sampai dengan 28 J.
21
E. Perspektif konflik
Dalam kuliah issue dan formulasi kebijkan publik, telah
dijelaskan issue kebijakan yang muncul karena adanya konflik
atau adanya sebuah perbedaan persepsional terhadap sesuatu,
untuk itu issue juga bersifat subjektif karena berasal dari
persepsi tersebut. Sebuah issue bisa menjadi masalah publik
bilamana telah menyangkut pada wilayah yang lebih luas dari
issue tersebut, dan tentunya berdampak pada masyarakat atau
publik, untuk melihat issue sebagai masalah publik yang ditinjau
melalui perspektif konflik, maka kita perlu mengetahui terlebih
dahulu perspektif konflik.
Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial
(Weber dalam David L.Sills 1968:232), baik itu bersifat positif
atau negatif. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang
mana mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya
dibedakan secara analisis.
Menurut Gamble (1984:261) konflik merupakan bentrokan
sikap-sikap, pendapat-pendapat,perilaku-perilaku, tujuan-tujuan
dan kebutuhan yang bertentangan” (Verderber, 1978:123) termasuk
juga “perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai” (Hamidi, 1995: 25).
Sosiologi konflik berasumsi bahwa masyarakat selalu dalam
kondisi pertentangan, pertikaian dan perubahan, semua itu adalah
sebagai bagian dari ter1ibatnya kekuatan-kekuatan masyarakat
yang saling berebut sumberdaya dengan menggunakan nilai-nilai
22
dan ide (Ideologi) sebagai alat untuk meraihnya (Wallace &Wolf,
1986). Dalam pandangan sosiologi hal ini merupakan kenyataan
sosial yang bagi Dahrendorf, merupakan siklus tak berakhir dan
adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok
terkoordinasi dari sistem sosial.
Ringkasnya, ada sedikitnya empat hal yang penting dalam
memahami teori konfilk sosial, antara lain:
1. Kompetisi (atas kelangkaan sumber daya seperti makanan,
kesenangan, partner seksual, dan sebagainya. Yang menjadi
dasar interaksi manusia bukanlah konsensus seperi yang
ditawarkan fungsionalisme, namun lebih kepada kompetisi.
2. Ketidaksamaan struktural. Ketidaksamaan dalam hal kuasa,
perolehan yang ada dalam struktur sosial.
3. Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan
berjuang untuk mencapai revolusi.
4. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara
keinginan (interes) yang saling berkompetisi dan bukan
sekadar adaptasi. Perubahan sosial sering terjadi secara
cepat dan revolusioner daripada evolusioner.
Lalu bagaimana sebuah issue yang berasal dari perspektif
konflik yang terjadi pada individu atau masyarakat menjadi
sebuah masalah publik? atau suatu issue konflik antara individu,
individu dan kelompok atau antar kelompok bisa menjadi sebuah
masalah publik dan termasuk dalam agenda kebijakan publik?
pembentukan agenda terjadi sebagai akibat dari perluasan issue
yang menjadi perhatian kelompok tertentu ke perhatian publik
yang lebih luas. Dinamika perluasan ini akan tergantung kepada
karakteristik issue awal. Cobb dan Elgar (Parsons, 2005; 130-
131) berpendapat :
23
a. Semakin mendua suatu issue didefinisikan, semakin besar
kemungkinannya akan mencapai publik yang lebih luas (tingkat
spesifitas);
b. Definisi issue yang semakin signifikan secara sosial akan
semakin besar kemungkinan nya berkembang menjadi perhatian
publik yang lebih luas (lingkup signifikansi sosial);
c. Jika issue didefinisikan sebagai issue yang memiliki
relevansi jangka panjang, semakin besar pandangannya akan
terungkap ke hadapan audien yang lebih luas (relevansi temporal);
d. Semakin nonteknis issue itu didefinisikan, semakin besar
kemungkinannya akan semakin ke publik yang lebih luas (tingkat
kompleksitas);
e. Semakin banyak issue yang disefinisikan sebagai issue yang
sedikit memiliki preseden (precedent), semakin besar peluangnya
issue itu akan sampai ke populasi yang lebih besar (preseden
kategoris).
Jika dilihat secara keseluruhan, bahwa dalam perspektif
konflik yang ada, issue dapat dilihat sebagai masalah publik
jika issue yang terjadi memiliki dampak yang lebih luas dan
besar dari lingkup asal issue tersebut. Pada posisi ini, peran
media massa sangat penting dalam membangkitkan perhatian,
memprovokasi aksi, melemahkan pertentangan, menunjukkan kekuatan
komitmen dan dukungan. Terakhir, akses issue ke proses
pengambilan keputusan institusional formal akan tergantung
kepada sejauh mana konflik diperlihatkan pada berbagai publik.
Menurut Cobb dan Elder (Parsons, 2005; 132), semakin besar
audien, semakin besar peluangnya untuk masuk ke arena
pengambilan keputusan ;
24
a. Ketika konflik dibatasi pada kelompok identifikasi, status
agenda formal kemungkinan hanya akan diraih ketika
penentang mengancam akan mengganggu sistem.
b. Konflik yang dibatasi pada perhatian publik kemungkinan
besar akan dibawa ke agenda oleh ancaman sanksi langsung.
c. Konflik yang dibatasi pada publik yang attentive kemungkinan
akan mencapai agenda formal melalui saluran perantara
(issue dibawa oleh orang dan kelompok yang mengetahuinya
dengan baik).
Dari model Cobb dan Elder diatas bahwa, dalam memperhatikan
sebuah issue yang berasal dari adanya konflik yang terjadi dapat
dipakai secara empiris untuk menunjukkan bagaimana kepentingan
pihak-pihak yang punya posisi dominan untuk issue dapat dibatasi
dalam parameter yang ketat (Parsons, 2005:132). Untuk secara
jelas melihat hal ini akan kita lihat beberapa contoh kasus,
bagaimana sebuah issue yang kemudian menjadi sebuah masalah
publik dilihat melalui perspektif konflik tidak terlepas dengan
adanya media massa, atau yang kita pahami sebagai policy
enterpreneur.
Contoh kasus issue sebagai masalah publik yang ditinjau
dari perspektif konflik adalah, kasus Prita Mulya Sari – Pasien,
terhadap Rumah Sakit Omni Internasional, tempat Pasien Prita
dirawat. Termasuk pula contoh kasus tawuran pelajar, yang marak
saat ini hingga berujung kematian. Kasus bullying di kalangan
kampus, Kasus pembakaran dan pembunuhan Kelompok Aliran tertentu
di Jawa Timur oleh Kelompok Islam yang beraliran lainnya, serta
banyak lagi kasus konflik individu dengan individu, individu
dengan kelompok, atau kelompok dengan Kelompok yang akhirnya
konflik tersebut meluas menjadi masalah bagi semua pihak yang
25
merasa ikut merasakannya dan berempati, bahkan ikut merasakan
dampak dan kerugian dari konflik yang terjadi. Dari beberapa
kasus tersebut, diketahui bahwa awal konflik adalah antara
individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok
tertentu. Namun kemudian dengan semakin meluasnya issue
sederhana ke arah hal-hal yang menyangkut permasalahn SARA, HAM,
Kekerasan dan sebagainya, yang kemudian dibantu dengan
pemberitaan oleh media massa kepada masyarakat (Blow-Up),
kemudian membangkitkan solidaritas sosial yang kemudian
melahirkan sebuah masalah publik yang lebih luas. Maka hal ini,
yang awalnya berupa issue kemudian dibantu oleh Policy Entrepreneur
menjadi sebuah masalah publik yang butuh solusi / kebijakan dan
penanganan segera.
F. Perspektif Advokasi
Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi
sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi
dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan
mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Advokasi
pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan
publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan
dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok
masyarakat (public interest) - dalam hal ini dunia usaha.Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan
kebijakan public yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah
26
munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.” (Socorro
Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Development,
1997).
Dalam kedudukannya sebagai organisasi pengusaha, maka yang
dimaksud adalah advokasi kebijakan publik, yaitu tindakan-
tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik
tertentu, meliputi yaitu:
• Hukum dan perundang-undangan
• Peraturan
• Putusan pengadilan
• Keputusan dan Peraturan Presiden
• Platform Partai Politik
• Kebijakan-kebijakan institusional lainnya
Tujuan utama advokasi adalah memudahkan media mencari bahan
berita ataupun pandangan “bisnis” yang diperoleh dari anggota
yang berkompeten sebagai narasumber. Pendekatan kepada media
harus strategis. Pastikan para wartawan mengetahui kegiatan yang
dilakukan organisasi dan asosiasi bisnis, anggota organisasi,
permasalahan yang dihadapi dan tujuan agenda bisnis atau
advokasi. Ciptakan reputasi dengan membuat materi yang
berkualitas dan berguna untuk mereka. Lakukan siaran pers dan
berikan materi publikasi lainnya. Bersikap responsif ketika
menyampaikan informasi dan materi. Melalui pengelolaan hubungan
yang positif dan proaktif dengan pers, besar kemungkinan akan
berhasil menciptakan peliputan media yang mengesankan. Tidak
hanya itu, kemungkinan akan muncul kesempatan untuk menjadi
pihak pertama yang dihubungi manakala berita penting muncul.
Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal,
27
nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus
harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat
keputusan; bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana
cara menerapkan dan menegakkan keputusan.” (Lisa Vene Klassen and
Valerie Miller, The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C.:
The Asia Foundation, 2002).
Advokasi adalah aksi yang strategis dan terpadu, oleh
perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu
masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil
keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut
sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan
kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut.
(Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003)
Memperhatikan pengertian dan tujuan dari upaya advokasi
maka yang menjadi kekuatan upaya ini adalah kerangka analisis
dari suatu kebijakan publik. Hal ini dipahami bahwa sebelum
mengusulkan perubahan atau pencabutan atas kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah maka kebijakan tersebut harus
dianalisis dahulu. Salah satu kerangka analisis yang berguna
untuk melihat suatu kebijakan publik adalah dengan melihat
kebijakan tersebut sebagai suatu ”sistem hukum” (system of law)
yang terdiri dari :
Isi Hukum (content of law), yaitu uraian atau penjabaran
tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk
perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan
Pemerintah. Ada juga kebijakan yang lebih merupakan
kesepakatan umum (konvensi) tidak tertulis, tetapi dalam hal
ini kita lebih menitikberatkan perhatian pada naskah (text)
28
hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang
berlaku.
Tata Laksana Hukum (structure of law), yaitu semua perangkat
kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam
pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pegadilan,
penjara, birokrasi pemerintahan, parpol dan sebagainya) serta
para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi,
tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen dan lain-lain)
Budaya Hukum (culture of law), yaitu persepsi, pemahaman,
sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran
terhadap dua aspek sistem hukum di atas (isi dan tata laksana
hukum). Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk
tanggapan (reaksi atau respone), karena itu hal ini merupakan
aspek kontekstual dari sistem hukum yang berlaku.
Sebagai suatu kesatuan sistem, ketiga aspek hukum tersebut
saling terkait antara satu sama lain dan tidak bisa berdiri
sendiri-sendiri. Oleh karena itu dikatakan bahwa idealnya, suatu
kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran
perubahan ketiganya. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam
kenyataannya, perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja
tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya.
Perubahan suatu naskah undang-undang atau peraturan pemerintah,
tidak dengan sendirinya merubah mekanisme kerja lembaga atau
aparat pelaksananya. Banyak contoh selama ini dengan jelas
menunjukkan bahwa naskah undang-undang atau peraturan pemerintah
yang betapapun baiknya secara normatif apabila tidak didukung
oleh kesiapan perangkat kelembagaan atau aparat pelaksana yang
memadai maka pada akhirnya hanya akan tersisa sebagai retorika
murni belaka.
29
Begitu juga dengan budaya hukum. Suatu naskah hukum
katakanlah sudah ada dan memenuhi semua tuntutan normatif yang
diperlukan, tersedia juga perangkat kelembagaan dan aparat
pelaksana yang handal dan terpercaya. Tetapi sikap dan perilaku
masyarakat kadangkala justru tidak mendukung isi maupun tata
laksana hukum tersebut, akibatnya maka peraturan dalam bentuk
suatu kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia belaka.
Contoh dari kasus tersebut adalah adanya aturan tentang
larangan untuk merokok di sembarang tempat yang berlaku di
daerah Jakarta. Naskah aturan sudah ada dan memenuhi syarat
normatif sebagai suatu Peraturan Daerah (Perda) kemudian aparat
penegak Perda tersebut juga sudah siap, namun kembali lagi bahwa
sikap dan perilaku masyarakat tidak mendukung tegaknya aturan
yang menjadi kebijakan Pemeritah DKI Jakarta Tersebut. Akibatnya
kebijakan untuk tidak merokok di sembarang tempat cenderung
hanya menjadi slogan semata.
Sebaliknya juga demikian, tata laksana hukum yang berubah
tidak secara otomatis merubah isi hukum yang berlaku. Itu
sebabnya maka timbul pendapat bahwa UU atau peraturannya sudah
bagus, namun oknum pelaksananya yang tidak mampu menegakkan UU
tersebut. Sama halnya dengan budaya hukum yang berubah, tidak
secara otomatis merubah tata laksana maupun isi hukum yang sudah
ada. Dalam banyak kasus, para aparat pelaksana hukum yang
mencoba melakukan amanat hukum berdasarkan kata hati nurani dan
rasa keadilan umum (budaya hukum), dalam istilah baku ilmu hukum
disebut sebagai rechtmatigheid, melakukan suatu exclusion
(perkecualian hukum), meskipun terpaksa harus menentang isi atau
naskah hukum yang berlaku, justru sering atau bahkan selalu
30
akhirnya berhadapan dengan kekakuan naskah hukum dan kepentingan
politik kekuasaan dibaliknya.
Sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik
seharusnya mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut.
Ini sama artinya suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang
secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan
terjadinya suatu perubahan kebijakan baik dalam isi, tata
laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Namun perubahan bisa
saja terjadi tidak sekaligus pada ketiga aspek hukum tersebut,
bisa juga perubahan terjadi secara bertahap mulai dari salah
satu aspek hukum tersebut yang dianggap bisa sebagai titik tolak
paling krusial, kemudian berlanjut ke aspek-aspek hukum
selanjutnya. Intinya bahwa perubahan yang terjadi secara
bertahap dan menyeluruh. Tahapan yang dilalui agar Advokasi
kebijakan bisa berjalan dengan efektif, antara lain :
Pengorganisasian (Membentuk tim/komite)
Mengidentifikasikan masalah dan sasaran (Survey dan FGD)
Menetapkan prioritas advokasi
Merumuskan kelompok sasaran : ‘Orang Dalam’, menyelenggarakan
pertemuan-pertemuan dengan pembuat kebijakan (executif dan
legislatif). ‘Orang Luar’, mempengaruhi media massa,
mengembangkan aktivitas-aktivitas di tingkat Grass Root,
Membangun Koalisi.
Mengidentifikasi pendukung dan penentang
Menyusun Renstra dan merancang pesan ke publik
Menyusun Anggaran
Evaluasi
Contoh konkrit dari bentuk Advokasi ini antara lain
Gerakan Advokasi dari LSM peduli Lingkungan pada Kasus Korban
31
Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Diikuti gerakan masal bersama Korban
Lapindo untuk menuntut penyelesaikan tentang ganti rugi Korban
Lumpur oleh pihak Lapindo dan tentunya adalah besarnya peran
Media Massa yang secara tidak langsung mengusung dan melindungi
proses berlangsungnya perjuangan masyarakat sidoarjo untuk
sampai pada Agenda Pemerintah, dimana sudah seharusnya
Pemerintahlah yang mampu menjadi Pihak Advokasi bagi rakyat atau
masyarakatnya.
Contoh lainnya adalah ‘Kasus Sendal Jepit”, dimana terdapat
kasus yang diadvokasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI) terkait kasus seorang anak yang diperkarakan oleh pihak
kepolisian, karena mencuri sendal jepit salah seorang anggota
polisi. Permasalahan yang menjadi perhatian Publik dan Media
Massa disini adalah bahwa anak yang mencuri sendal jepit
tersebut masih dibawah umur, memang anak tersebut melakukan
kesalahn dan tindak pencurian, sehingga kemudian di perkarakan
secara hukum dan sempat melalui proses penahanan. Namun secara
logika kesalahan anak tersebut sangat jauh jika dibandingkan
dengan kesalahan besar para Koruptor yang justru tidak sampai
ke meja hijau dan bahkan tidak ditindak lanjuti oleh aparat
kepolisian. Maka akhirnya KPAI kemudian memberikan advokasi
kepada anak tersebut dan hal ini juga didukung oleh banyak pihak
dengan adanya gerakan “sandal jepit” oleh masyarakat. Hal ini
dapat dilihat sebagai issue yang kemudian menjadi masalah publik
karena sudah melibatkan KPAI, LSM, dan Masyarakat untuk menuntut
keadilan bagi anak tersebut untuk selanjutnya dari segi Advokasi
pastinya akan ditindaklaanjuti proses mediasi atau wujud tindak
lanjut lainnya oleh pihak Institusi Pemerintah dalam hal ini
Kepolisian dan Pengadilan atas Advokasi yang dilakukan oleh
32
KPAI sebagai Lembaga Resmi yang bergerak dalam Perlindungan Anak
Indonesia. Dari sini tidak menutup kemungkinan akan berdampak
pada evaluasi dan formulasi kebijakan terhadap perlakuan dan
prosedur pelanggaran oleh Anak di bawah umur secara lebih
manusiawi dan sesuai dengan pemenuhan Hak Azasi Manusia.
Demikianlah hasil diskusi, pemikiran dan pemaparan hasil
penelusuran literatur, serta pemahaman kami memandang realita
yang terjadi, dikaitkan dengan persoalan dan pertanyaan mengenai
Tugas Kelompok yang diajukan pada Mata Kuliah Issue dan
Formulasi Kebijakan Publik.
Dapat disimpulkan, bahwa enam perspektif yang ada dengan
sudut pandang dan konsentrasi serta fokus terhadap issue mampu
atau berhasil menjadi masalah publik, adalah tetap pada koridor
dimana issue yang hanya sebagai sesuatu hal yang tidak selalu
bisa dimaknai atau dibuktikan kebenarannya ( kabar burung ),
issue yang tidak selalu diperhatikan, mampu dan bisa dikatakan
berhasil menjadi Masalah Publik, dimana issu itu mencapai suatu
Kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan – kebutuhan atau
ketidakpuasan pada rakyat, dimana perlu dicarikan cara – cara penanggulangannya.
( James E. Anderson, 1979).
Issue yang berhasil menjadi Masalah Publik, yaitu jika issue
kemudian menjadi Kebutuhan- kebutuhan, Nilai-nilai, Kesempatan-kesempatan
yang tidak terealisir, dan hanya dapat dicapai melalui Tindakan Publik. ( Dunn,
1994. Edisi Indonesia, 1998 : 210 -213 ).
Bahasan Issue menjadi Masalah Publik telah kami sajikan
sesuai dengan kemampuan dan tentunya Kelompok kami tidak lepas
33
dari kekurangan, kesalahan dan kami adalah manusia yang memiliki
keterbatasan. Sehingga kami sangat berterima kasih atas saran,
kritik dan tanggapan yang diberikan selama itu positif dan
bersifat membangun.
Di luar Konteks Pertanyaan ( Tugas ) Kelompok, kami
berpendapat bahwa, pada perkembangannya issue mampu meningkat
bukan hanya sekedar menjadi Masalah Publik namun apabila
berkembang, serta berdampak nyata dan meluas, maka besar
peluangnya akan melalui Agenda Setting yang pada akhirnya
menjadi Agenda Kebijakan sampai kepada Titik Formulasi Kebijakan
dan menghasilkan Produk Kebijakan, adalah tahapan atau tingkatan
yang tidak terlepas dari kreativitas dan aktivitas berbagai
pihak.
Proses tersebut terjadi jika issue sudah meningkat
menjadi Agenda melalui Policy Windows, dimana proses diawali
dengan adanya suatu peluang, dimana ketiga aliran (problems, policies
dan politics) bisa bertemu bersamaan, sehingga issue-issue bisa
menjadi Agenda. Dilanjutkan dengan Proses policy windows , jendela
dibuka oleh kejadian-kejadian, baik dalam aliran masalah atau
dalam aliran politik. Dimana Policy entrepreneur s, begitu ada
kesempatan yang muncul (policy windows), maka issue dapat
diangkat menjadi agenda, jika ada pihak-pihak yang mampu
mempertemukan ketiga aliran yang oleh Kingdon disebut sbg policy
entrepreneurs. (Pejabat pemerintah, PNS karir, pelobi, akademisi
atau wartawan).
34
Sumber Referensi
1. Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, Rajawali
Press, Jakarta, 2003
2. William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998,
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal: 24
3. Budi Winarno, Kebijakan Publik: teori dan Proses. Jakarta: PT Buku
Kita. Hal: 33.
4. R Daniel. Lecture, Legitimation and Decision - Making, dalam
www.www.csub.edu /~rdaniels/ppa_503_lecture7a.pp.
5. Budi Winarno, Kebijakan Publik: teori dan Proses. Jakarta: PT Buku
Kita. Hal: 225.
6. Giddens, Anthony., Kapitalisme dan Teori Sosial Modern:
Suatu Analisis Karya Tulis Max Weber, UI Press, Jakarta,
1985
7. Bingham, Richard D, 1978., Innovation, Bureaucracy, and Public
Policy: A Study of Innovation Adoption by Local Government, The Western
Political Quarterly, Vol. 31, No. 2. (Jun), pp. 178-205.
8. Gurevitch, Michael dan Blumler, Jay G., (1990) “Political
Communication systems and democratic values”, dalam Lichtenberg,
Judith, ed., Democracy and the Mass Media, Cambridge University
Press, Cambridge
35
9. Pendapat Umum, edisi keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta
10. Materi Workshop “Democratic Governance in Theory: Sebuah
Gugatan atas Konsep Good Governance”, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 16 – 18
September 2004).
11. Nickel, James W., (1987) Hak Asasi Manusia, Refleksi
Filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terjemahan
Arini, (1996) Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
12. Zukin, Cliff, (1981) “Mass Communication and Public
Opinion”, dalam Nimmo dan Sanders, ed., Handbook of Political
Communication, Sage Publications, Beverly HillsGurevitch dan
Blumler, 1990; Hennessy, 1981
13. Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, The Action Guide for
Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C.: The Asia
Foundation, 2002
14. Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003
15. Socorro Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines:
The Center for Legislative Development, 1997
36