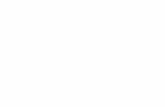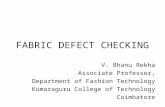MAKALAH CONGENITAL HEART DEFECT
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of MAKALAH CONGENITAL HEART DEFECT
A. ANATOMI DAN FISIOLOGI
- Sebelum lahir, sebagian besar darah dialihkan dari paru-paru
janin yang belum berfungsi melalui foramen ovale, suatu
pembukaan pada septum interatrium di antara atrium kanan an
atrium kiri. Saat lahir, paru-paru mulai berfungsi dan
foramen ovale tertutup. Sisi ini ditandai dengan adanya
lekukan pada septum interatrium yang disebut fossa ovalis.
Foramen ovale yang tidak tertutup disebut defek septum
interatrium ( Slonane, 2003).
- Aorta adalah arteri utama yang membawa darah yang mengandung
oksigen ke seluruh jaringan tubuh, kecuali paru-paru. Aorta
merupakan pembuluh nadi (arteri) yang terbesar.
Congenital Heart Defect Page 1
fossa ovalis
- Darah yang melalui aorta dipompa oleh ventrikel kiri
melewati valvula semilunaris aorta (katup) aorta.
- Arteri Pulmonalis merupakan pembuluh darah yang keluar dari
ventrikel kanan, bercabang menjadi dua yang masing- masing
menuju ke paru-paru kanan dan kiri.
- Arteri pulmonalis sinistra merupakan pembuluh nadi yang
hanya mengalirkan darah kaya akan karbondioksida (CO2) dari
ventrikel kanan ke paru-paru kiri.
- Arteri pulmonalis dextra merupakan pembuluh nadi yang hanya
mengalirkan darah kaya akan kerbondioksida (CO2) dari
ventrikel kanan ke paru-paru kanan.
- Vena pulmonalis :Terdapat empat vena pulmonalis yaitu; dua
vena pulmonalis dextra dan dua vena pulmonalis sinistra.
Keempat vena ini yang mengalirkan darah dari paru-paru yang
kaya akan oksigen (O2) masuk ke atrium kiri dan kemudian
masuk ke ventrikel kiri melewati valvula bicuspidalis (katup
jantung berkelopak dua) selanjutnya dialirkan ke seluruh
jaringan tubuh, kecuali paru-paru.
- Vena pulmonalis dextra : Membawa darah kaya akan O2 dari
paru-paru kanan menuju atrium kiri.
- Vena pulmonalis sinistra : Membawa darah kaya akan O2 dari
paru-paru kiri menuju atrium kiri.
- Vena Cava Inferior: Membawa darah yang berasal dari bagian
tubuh di bawah jantung ke atrium kanan, kemudian masuk ke
ventrikel kanan melewati valvula tricuspidalis (katup
jantung berkelopak tiga) menuju ke paru-paru kiri dan kanan
melalui arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis
dextra. Vena cava inferior termasuk vena yang berukuran
besar.
Congenital Heart Defect Page 2
- Vena Cava Superior: Membawa darah yang berasal dari bagian
tubuh diatas jantung ke atrium kanan, kemudian masuk ke
ventrikel kanan melewati valvula tricuspidalis (katup
jantung berkelopak tiga) menuju ke paru-paru kiri dan kanan
melalui arteri pulmonalis sinistra dan arteri pulmonalis
dextra. Vena cava inferior termasuk vena yang berukuran
besar. Vena cava superior termasuk vena yang berukuran
besar.
- Atrium dextra (kanan) terletak dalam bagian superior kanan
jantung, atrium kanan memiliki fungsi sebagai penerima darah
dari seluruh jaringan kecuali paru-paru.
- Atrium sinistra (kiri) menampung empat vena pulmonalis yang
mengembalikan darah teroksigenasi dari paru-paru menuju ke
seluruh tubuh.
- Valvula semilunaris aorta (katup aorta): Terletak diantara
ventrikel kiri dan aorta, katup ini berfungsi mengalirkan
darah dari ventrikel kiri ke aorta dan tidak sebaliknya,
katub ini terdiri dari tiga daun katup.
- Valvula semilunaris arteri pulmonalis (katup pulmonalis):
Terletak diantara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis,
katup ini berfungsi mengalirkan darah dari ventrikel kanan
ke arteri pulmonalis dan tidak sebaliknya, katup ini terdiri
dari tiga daun katup.
- Valvula bicuspidalis: berfungsi untuk mencegah kembalinya
darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri.
- Valvula tricuspidalis: berfungsi untuk mencegah kembalinya
darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan.
- Ventrikel sinistra (kiri): Ventrikel kiri mempunyai
miokardium (lapisan otot jantung) yang paling tebal karena
harus memompa darah ke seluruh tubuh,
Congenital Heart Defect Page 3
- Ventrikel dextra (kanan): memiliki fungsi sebagai penerima
darah dari atrium kanan yang kemudian dipompa ke seluruh
tubuh melewati arteri pulmonalis.
- Septum interventrikular: dinding yang memisahkan ventrikel
kanan dan kiri jantung. ( Smeltzer & Bare, 2001)
B. INSIDEN DAN ETIOLOGI
a. Insiden
Penyakit jantung kongenital terjadi pada sekitar 8 dari
1000 kelahiran hidup. Insiden lebih tinggi pada yang lahir
mati (2%), abortus (10-25%), dan bayi prematur (2% termasuk
defek sekat ventrikel [VSD], tetapi tidak termasuk duktus
arteriosus paten sementara [PDA]). Insiden menyeluruh ini
tidak termasuk prolaps katup mitral, PDA pada bayi preterm,
dan katup aorta biskupid (ada sekitar 0,9% seri dewasa).
Pada bayi dengan defek jantung kongenital, ada spectrum
keparahan yang lebar : sekitar 2-3 dari 1000 bayi neonatus
total akan bergejala penyakit jantung pada usia 1 tahun
pertama. Diagnosa ditegakkan pada umur 1 minggu pada 40-50%
penderita dengan penyakit jantung kongenital dan umur 1
bulan pada 50-60% penderita. Sejak pembedahan paliatif atau
korektif berkembang, jumlah anak yang hidup dengan penyakit
jantung congenital bertambah secara dramatis.
Kebanyakan defek kongenital ditoleransi dengan baik
selama kehidupan janin karena sifat parallel sirkulasi
janin. Bahwa defek jantung berat, misalnya, hipoplasi
ventrikel kiri berat, biasanya dapat dikompensasi dengan
baik oleh sirkulasi janin. Hanya sesudah sirkulasi ibu
dihilangkan, jalur janin (duktus arteriosus dan foramen
ovale) tertutup atau restriksi, dan sistem kardiovaskuler
Congenital Heart Defect Page 4
tidak tergantung dipertahankan sehingga pengaruh
hemodinamika sepenuhnya dari kelainan anatomi menjadi
tampak. Satu pengecualin utama adalah kasus lesi
regurgitasi, yang paling sering katup trikuspidal. Pada lesi
ini, misalnya, anomali Ebstein, sirkulasi janin parallel
tidak dapat mengkompensasi dengan cukup karena beban volume
yang dibebankan pada jantung kanan. Gagal jantung dalam
rahim seringkali dengan efusi pleura dan asites janin
(hydrops fetalis) dapat terjadi.
Walaupun dekat masa perinatal menandai waktu peralihan
yang paling berarti dalam sirkulasi, sirkulasi bayi terus
mengalami perubahan setelah lahir, dan perubahan ini
kemudian dapat juga mempunyai pengaruh hemodinamik yang kuat
pada lesi jantung dan insiden penampakannya. Misalnya ketika
tahanan vaskuler pulmonal turun sesudah usia beberapa minggu
pertama, shunt dari kiri ke kanan melalui defek intrakardial
bertambah dan gejala-gejala menjadi lebih nyata. Arti
relatif berbagai defek dapat juga berubah secara dramatis
pada pertumbuhan : beberapa defek sekat ventrikel dapat
menjadi jauh lebih kecil ketika anak bertambah umur.
Sebaiknya, stenosis katup aorta atau pulmonal, yang mungkin
ringan pada masa neonatus, dapat menjadi jelek jika
pertumbuhan lubang katup tidak mengimbangkan pertumbuhan
penderita. Dokter harus menyadari spectrum keparahan
berbagai malformasi jantung congenital dan evolusinya
bersama waktu dan selalu waspada pada malformasi congenital
yang menyertai, yang dapat sangat mempengaruhi prognosis
penderita. (Behrman, Kliegman, Arvin, 2000).
b. Etiologi
Congenital Heart Defect Page 5
Seperti pada hampir semua kelainan kongenital, etilogi
pasti belum diketahui tetapi telah diketahui adanya factor
genetic dan lingkungan yang berperan. Jika seorang ibu
mempunyai anak dengan kelainan jantung kongenital , risiko
anak kedua terkena adalah tiga kali lebih besar dibandingkan
bila anaknya tidak menderita kelainan jantung. Anak dengan
kelainan kromosom mempunyai angka kejadian penyakit jantung
congenital yang lebih besar. Hampir separuh anak dengan
sindrom down mempunyai kelainan jantung. Infeksi rubella
pada trimester pertama kehamilan, penyakit diabetes pada ibu
dan penggunaan obat dalam kehamilan (seperti thalidomide,
alcohol, fenitoin) merupakan factor lingkungan yang
berhubungan dengan peningkatan insiden penyakit jantung
congenital. (Hull & Johnston, 1995).
1. Congenital Heart Defect (Penyakit Jantung Kongenital)
1.1 Penyakit Jantung Kongenital Asianotik
Jenis penyakit jantung kongenital yang sering dijumpai
adalah adanya lubang antara dua sisi jantung, baik pada
atrium, ventrikel atau arteri besar. Pada kehidupan janin,
aliran darah paru sedikit dan tekanan dalam ventrikel kanan
dan arteri pulmonalis tinggi. Setelah mulai terbentuk
pernapasan teratur, resistensi pembuluh darah paru menurun
dengan akibat penurunan tekanan pada jantung kanan. Karena
tekanan jantung kiri melampaui tekanan jantung kanan, darah
akan mengalir dari kiri ke kanan melalui lubang tersebut.
Congenital Heart Defect Page 6
Resistensi pembuluh darah paru menurun cepat pada hari-
hari pertama setelah lahir kemudian penurunan ini menjadi
lebih lambat dalam beberapa minggu kemudian, hingga pada usia
3 bulan aliran darah dari kiri ke kanan mencapai puncaknya.
Dengan demikian, ada sirkulasi tambahan dari jantung kiri ke
jantung kanan, kemudian ke paru-paru dan kembali lagi ke
jantung kiri. Hal ini disebut pirau. Jika lubang kecil, pirau
mungkin ringan; tetapi bila lubang besar akan mengalirkan
sebagian besar curah jantung sehingga aliran darah melalui
arteri pulmonalis bertambah beberapa kali lebih besar daripada
aliran melalui aorta. Pirau besar menimbulkan beban tambahan
bagi jantung dengan akibat hipertrofi, dilatasi dan kadang
gagal jantung. Karena tingginya resistensi pembuluh darah paru
setelah lahir, bising sering tidak terdengar. Pada bayi dengan
pirau kiri ke kanan yang sederhana, gagal jantung jarang
terjadi pada minggu-minggu pertama kehidupan. (Hull &
Johnston, 1995).
1.1.1 Defek Septum Atrium (ASD)
a. Defek Ostium Sekundum
Defek ostium sekundum adalah lubang yang terletak
pada septum atrium pada daerah fosa ovalis, yaitu
lokasi foramen ovale. Ini terjadi karena atrium kanan
kurang berotot dan lebih mudah terisi darah dibanding
atrium kiri, darah akan mengalir dari atrium kiri ke
atrium kanan melalui defek, kemudian ke ventrikel
kanan dan ke paru-paru. Oleh karena itu jantung kanan
yang menanggung seluruh beban tambahan akibat adanya
pirau tersebut. (Hull & Johnston, 1995).
Congenital Heart Defect Page 7
Manifestasi klinis. Jarang timbul pada masa anak,
hampir semua anak yang mengalami defek septum atrium
menunjukkan adanya bising jantung. Bising sering
terdengar cukup halus dan seringkali tidak terdeteksi
hingga anak mencapai usia sekolah. Jika timbul gejala
klinis, biasanya adalah sesak napas atau kelelahan
setelah memeras tenaga atau infeksi saluran napas
berulang. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksan penunjang. Rontgen toraks
memperlihatkan adanya kardiomegali dengan pembesaran
atrium dan arteri pulmonali, serta plethora paru.
Elektrokardiogram menunjukan deviasi aksis ke kanan
(RAD), hipertrofi ventrikel kanan, dan right bundle
branch block (RBBB) pada hampir semua kasus. Diagnosis
dipastikan dengan ekokardiografi. (Hull & Johnston,
1995).
Pengobatan. Jika defek berukuran sedang atau
besar, dianjurkan penutupan dengan menggunakan
pintasan kardiopulmoner. Koreksi dilakukan dengan
penjahitan sederhana atau dengan insersi jaringan
perikardium. (Hull & Johnston, 1995).
b. Defek ostium primum
Meskipun lebih jarang dibandingkan ostium
sekundum, defek ostium primum merupakan masalah yang
lebih serius. Lubang terletak di bagian bawah septum
atrium dan merupakan akibat kegagalan perkembangan
septum primum pada kehidupan janin. Defek berada tepat
di atas katup atrioventrikel dan biasanya meluas ke
bagian insersi daun anterior katup mitral sehingga
Congenital Heart Defect Page 8
menimbulkan celah pada katup mitral dan sering terjadi
insufisiensi. Defek septum atrium ostium primum
merupakan akibat ringan dari berbagai kegagalan
perkembangan bagian sentral jantung, yaitu endocardial
cushion defect. Pada bentuk yang paling berat,defek
meluas dari septum atrium melalui katup
atrioventrikular dan menibulkan peningkatan terjadinya
pirau besar kiri ke kanan serta menyebabkan
insufisiensi mitral dan trikuspid. endocardial cushion
defect sangat sering dijumpai pada anak yang menderita
sindrom down. (Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Gagal jantung sering terjadi
pada masa bayi dan masa kanak-kanan. Tanpa tindakan
bedah, kelainan ini mempunyai angka kematian yang
tinggi. Sering timbul hipertensi pulmonal yang berat,
terutama pada sindrom down. Biasanya terdapat tanda-
tanda gagal jantung dengan kardiomegali yang nyata.
Anak yang menderita gagal jantung sering mengalami
sesak napas saat istirahat, dengan deformitas pada iga
bawah. Anak tersebut tampak kemerahan, dengan denyut
nadi normal. Secara klinis terdapat pembesaran jantung
disertai peningkatan aktivitas kedua ventrikel.
Sebagai tambahn tanda auskultasi pada defek septum
atrium, mungkin terdengar bising pansistolikapikal
yang menandakan regurgitasi mitral. (Hull & Johnston,
1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks menunjukkan
kardiomegali yang nyata, pembesaran arteri pulmonalis,
dan plethora paru. Elektrokardiogram sering menunjang
diagnotik, memperlihatkan deviasi aksis kekiri dan
Congenital Heart Defect Page 9
right bundle branch block. Kateterisasi dibutuhkan
untuk menilai ukuran pirau dan derajat insufisiensi
mitral. (Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Pembedahan dini biasanya dianjurkan
pada anak dengan defek ostium primum. Defek ditutup
dan celah pada katup mitral diperbaiki. Tindakan
pembedahan ini lebih sulit dan mempunyai risiko yang
lebih besar dibanding pembedahan pada defek ostium
sekundum. (Hull & Johnston, 1995).
1.1.2 Defek Septum Ventrikel (VSD)
Kelainan ini merupakan kelainan jantung bawaan yang
paling sering ditemukan. Sebuah defek biasanya terdapat
pada bagian membranosa septum ventrikel, berdekatan
dengan katup trikuspid, atau dibawah katup aorta. Pada
keadaan yang lebih jarang dapat ditemukan satu atau
multiple defek pada bagian muscular septum. Pada 25-30%
dari seluruh anak yang menderita defek septum ventrikel
ditemukan kelainan jantung lain. (Hull & Johnston, 1995).
a. Defek septum ventrikel kecil
Karena pirau melalui defek ini kecil, anak yang
menderita kelainan ini tidak memperlihatkan gejala
klinis. Bising jantung sering ditemukan pada
pemeriksaan rutin. Anak tampak sehat, kemerahan,
mempunyai nadi normal, dan jantung tidak membesar.
Biasanya terdapat thrill pada tepi kiri sternum bagian
bawah. Pada auskultasi terdengar bising pansistolik
yang keras pada lokasi yang sama akibat aliran darah
melalui defek. (Hull & Johnston, 1995).
Congenital Heart Defect Page 10
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks dan
elektrokardiogram biasanya normal. Kateterisasi
jantung tidak diperlukan.
Pengobatan. Pada kelainan ini terdapat risiko
terjadinya endokarditis bakterialis. Oleh karena itu,
antibiotic profilaksis perlu diberikan pada saat
ekstrasi gigi dan lain-lain. (Hull & Johnston, 1995).
b. Defek septum ventrikel sedang
Gejala biasanya timbul pada bayi, yaitu sesak
napas pada saat minum dan menangis, gagal tumbuh,
serta infeksi paru berulang. Ketika anak bertambah
usia, gejala cenderung berkurang dan mungkin hilang
sama sekali akibat penutupan defek secara relatif atau
nyata. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks
memperlihatkan kardiomegali, pembesaran arteri
pulmonalis dan plethora paru. Elektrokardiogram
menunjukkan hipertrofi biventricular karena kedua
ventrikel terlibat dalam pirau tersebut. Kateterisasi
jantung harus dilakukan jika anak tidak menunjukkan
perbaikan dengan bertambahnya usia atau jika ditemukan
hipertensi pulmonal. (Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Jika gejala menonjol, sebaiknya
diberikan diuretic. Pembesaran hendaknya dihindari
karena ada kecenderungan perbaikan spontan, kecuali
bila ada gejala yang terus menerus dan timbulnya
hipertensi pulmonal. (Hull & Johnston, 1995).
Congenital Heart Defect Page 11
c. Defek septum ventrikel besar
Jika resistensi pembuluh darah paru turun
mencapai minimal pada umur 3 bulan, pirau yang terjadi
melalui defek yang besar yang besar dan mengakibatkan
gagal jantung. Gejala sesak napas pada pemberian minum
biasanya mendahului keadaan tersebut, dan berkeringat
merupakan gejala yang sering ditemukan. Bayi mungkin
sakit berat disertai gagal jantung kongestif, dan
mempunyai kecenderungan tinggi untuk mengalami infeksi
paru yang sering mencetuskan episode gagal jantung.
(Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks menunjukkan
kardiomegali yang nyata, arteri pulmonalis yang besar,
dan plethora paru. Elektrokardiogram memperlihatkan
hipertrofi biventricular. Ekokardiografi akan
memperlihatkan defek sedangkan kateterisasi diperlukan
untuk mengukur besar pirau dan tekanan arteri
pulmonalis. (Hull & Johnston, 1995.
Pengobatan. Pengobatan awal adalah medikamentosa.
Bayi dengan gagal jantung dirawat dalam posisi
setengah duduk. Diuretic (biasanya furosemide atau
thiazide) diberikan bersama-sama dengan suplemen
kalium atau diberikan diuretic hemat kalium seperti
spironolakton. Keberhasilan terapi dinilai dengan
penimbangan berat badan secara berkala dan pencatatan
ukuran hati. Jika gagal jantung berespons terhadap
pengobatan berat badan akan menurun dengan cepat dan
ukuran hati akan mengecil. Jika bayi tidak berespons
terhadap pengobatan, diperlukan penutupan dengan
Congenital Heart Defect Page 12
pembedahan. Pembedahan paling baik dilakukan dalam
satu tahap dengan menggunakan pintasan kardiopulmoner.
Pembedahan seperti ini pada bayi yang sakit memerlukan
keterampilan medis dan bedah yang paling baik. Cara
pembedahan alternatif adalah menempatkan pita pengerut
disekitar basal arteri pulmonalis yang mengurangi
besar pirau. Pembedahan kedua diperlukan untuk
mengangkat pita dan menutup defek. (Hull & Johnston,
1995).
1.1.3 Duktus Arteriosus Persisten
Duktus arteriosus persisten merupakan kelainan
jantung bawaan yang sering dijumpai, baik sebagai
kelainan tunggal ataupun sebagai kombinasi jantung yang
lain. Kelainan ini terutama sering dijumpai pada
perempuan, pada anak dari ibu yang menderita rubella saat
kehamilan trimester pertama dan pada bayi yang dilahirkan
premature. Dalam kehidupan janin, duktus arteriosus yang
merupakan pembuluh darah besar berotot, mengalirkan darah
dari ventrikel kanan dan arteri pulmonalis ke aorta.
Dalam 24 jam pertama setelah lahir, duktus akan menutup
sebagai respons terhadap darah yang teroksigenisasi.
Duktus arteriosus persisten tidak mungkin menutup spontan
setelah beberapa hari kehidupan, namun pada bayi
premature penutupan spontan dalam 3bulan pertama
kehidupan masih mungkin terjadi. Saat resistensi pembuluh
darah pulmonalis menurun setelah lahir, terjadi pirau
kiri ke kanan dari aorta ke arteri pulmonalis melalui
Congenital Heart Defect Page 13
duktus (berlawanan arah dengan aliran darah pada
kehidupan janin). (Hull & Johnston, 1995).
a. Duktus arteriosus persisten kecil
Anak dengan kelainan ini bebas keluhan. Bising
jantung dapat dideteksi pada pemeriksaan rutin atau
sacara kebetulan. Bayi tampak kemerahan dengan nadi
normal. Pada auskultasi terdengar bising kontinu yang
keras dengan punktum maksimum di bawah klavikula kiri.
Bising menyebar dari fase sistolik ke diastolic karena
tekanan arteri pulmonalis lebih rendah dari pada di
aorta sepanjang siklus jantung. Bising tersebut
mempunyai kualitas machinery kasar. (Hull & Johnston,
1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen dada dan
elektrokardiogram normal. Ekokardiografi dengan
Doppler memperlihatkan duktus terebut.
Pengobatan. Tindakan ligasi dianjurkan karena
risiko endokarditis bakteriali. Pembedahan itu sendiri
mempunyai risiko yang amat kecil.
b. Duktus arteriosus persisten besar
Beratnya keluhan berhubungan dengan besarnya
pirau. Anak mungkin kurang gizi dengan penurunan
toleransi terhadap latihan dan peningktan risiko
infeksi paru. Pada keadaan ektrem lain, gagal jantung
yang berat dapat terjadi pada masa bayi. Pada
pemeriksaan anak tampak kecil dan kurus. Peningkatan
frekuensi pernapasan sering dijumpai. Tidak ada
sianosis tetapi nadi mudah diraba, bersifat penuh danCongenital Heart Defect Page 14
kolaps. Tekanan darah diastolik adalah rendah dan
tekanan nadi lebar. Jantung membesar secara klinis
dengan pembesaran ventrikel kiri secara menonjol dan
terdapat thrill sistolik pada daerah pulmonalis. Pada
auskultasi terdengar bising sistolik kasar yang meluas
melampaui bunyi jantung dua hingga fase diastolik
dini. Panjang bising tergantung pada tekanan arteri
pulmonalis. Tekanan ini tinggi bila terdapat pirau
yang besar sehingga darah hanya mengalir dari kiri ke
kanan selama fase sistolik. Bunyi jantung dua komponen
pulmonal terdengar keras. Bising mid-diastolik mitral
mungkin terdengar. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks menunjukkan
gambaran ke pirau kiri ke kanan. Elektrokardiogram
memperlihatkan hipertrofi ventrikel kiri. Diagnosis
dikonfirmasi dengan menggunakan ekokardiografi. (Hull
& Johnston, 1995).
Pengobatan Jika terjadi gagal jantung,
diperlukan terapi medikamentosa. Pembedahan harus
dilakukan segera setelah kondisi anak memungkinkan.
(Hull & Johnston, 1995).
1.1.4 Hipertensi Pulmonal
Suatu pirau kiri ke kanan yang besar dengan aliran
darah pulmonalis yang besar akan menimbulkan peningkatan
tekanan arteri pulmonali secara nyata karena peningkatan
aliran (hipertensi pulmonal hiperdinamis). Setelah
penutupan defek melalui pembedahan, tekanan arteri
pulmonali kembali normal. Aliran arteri pulmonalis yang
tetap tinggi dapat mengakibatkan kerusakan permanen
Congenital Heart Defect Page 15
pembuluh darah paru lebih kecil sehingga dapat terjadi
penyempitan dan hiperteni pulmonal ireveribel. Jika pada
keadaan tersebut defek ditutup, tekanan arteri
pulmoanalis tetap tinggi. Jika tekanan arteri pulmonalis
mencapai tekanan sistemis, pirau kiri ke kanan berhenti
dan mungkin akan berbalik. (Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Anak memperlihatkan sianosis
ringan dengan jari tabuh, tetapi dapat tampak normal.
Namun, toleransi latihan biasanya sangat menurun. Pada
pemeriksaan ditemukan pembesaran ventrikel kanan dan
heaving, dan bunyi jantung dua komponen pulmonal dapat
teraba. Pada aukultasi biasanya terdengar bising sistolik
ejeksi pada daerah pulmonal akibat aliran darah melalui
arteri pulmonalis yang besar, tidak melalui pirau, dan
kadang-kadang terdengar bising diastolic dini yang
menandakan adanya insufisiensi pulmonal. Komponen
pulmonal bunyi jantung dua terdengar amat keras. (Hull &
Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks menunjukkan
pembesaran jantung dengan pembesaran atrium kanan. Ukuran
arteri pulmonalis amat meningkat tetapi cabang yang lebih
kecil tidak terlihat. Elektrokardiogram memperlihatkan
deviasi akis ke kanan, hipertrofi atrium kanan, dan
hipertrofi ventrikel kanan. (Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Kateterisasi jantung dibutuhkan untuk
memperlihatkan lokasi pirau dan mengukur tekanan arteri
pulmonalis. Terjadinya hipertensi pulmonal yang berat dan
ireversibel merupakan akibat pirau kiri ke kanan yang
besar disebut sindrom eisenmenger. Meskipun pada mulanya
istilah tersebut dihubungkan dengan defek septum
Congenital Heart Defect Page 16
ventrikel, hal itu dapat terjadi pada pirau kiri ke kanan
pada setiap lokasi. Keadaan ini mungkin sekali untuk
terjadi pada kasus defek septum ventrikel yang besar,
defek kanal atrioventrikular dan transposisi arteri
dengan pirau yang besar. Tidak ada koreksi pembedahan
yang dapat dilakukan, dan harapan hidup angka yng
menderita berkurang. Transplantasi jantung paru mungkin
merupakan pilihan bagi penderita tersebut. (Hull &
Johnston, 1995).
1.1.5 Stenosis Aorta
Kelainan ini merupakan penyakit bawaan yang sering
dijumpai dapat merupakan kelainan tunggal ataupun dalam
kombinasi dengan kelainan jantung yang lain. Pada
sebagian besar kasus katup aorta itu sendiri menyempitan
akibat deformitas congenital. Katup yang mengalami
deformitas mungkin berbentuk bikuspid dari pada trikuspid
dan daun katup sering menempel pada tepinya. Derajat
stenosis mungkin memburuk saat anak bertambah usia yang
dikarenakan penebalan dan klasifikasi daun katup. Katup
aorta bikuspid mungkin dapat membuka secara normal pada
masa anak, tetapi akan menebal dan menyempitan pada masa
dewasa. Jika katup aorta sangat menyempit dan kaku,
sering dijumpai pula insufisiensi aorta. (Hull &
Johnston, 1995).
Kadangkala obstruksi aorta dapat terjadi di atas
ataupun di bawah katup aorta. Pada stenosis
supravalvular, aorta asendens di atas katup menyempit.
Hal ini sering dihubungkan dengan tampilan wajah yang
tidak biasa, cacat mental dan hiperkalsemia pada masa
Congenital Heart Defect Page 17
bayi (sindrom william). Pada stenosis aorta subvalvuler,
mungkin terdapat diafragma fibrosa di bawah katup yang
menghambat aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta,
atau mungkin terdapat hipertrofi ventrikel dan septum
interventrikuler yang berlebihan yang menghambat saluran
keluar ventrikel kiri selama sistolik yang disebut
kardiomiopati obstruktif hipertrofik. (Hull & Johnston,
1995).
Manifestasi klinis. Stenosis aorta berat menimbulkan
gagal jantung pada masa bayi. Pada sebagian besar kasus,
bising jantung ditemukan pada pemeriksaan rutin. Sebagian
kecil dari anak-anak besar yang mengalami stenosis aorta
berat dapat mengeluh pusing atau pening saat olahraga,
serta penurunan kesadaran. Hal ini merupakan indikasi
untuk pengobatan segera. Endokarditis, bakterialis
merupakan komplikasi stenosis aorta yang tidak tergantung
pada beratnya penyakit. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks mungkin
menunjukkan pembesaran ventrikel kiri dengan dilatasi
aorta desenden post-stenosis. Elektrokardiogram
memperlihatkan hipertrofi ventrikel kiri dalam derajat
yang bervariasi tergantung pada beratnya stenois.
Gradient katup aorta dapat diukur dengan ultrasonografi.
(Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Jika ekokardiografi memperlihatkan
gradient katup aorta lebih dari 40 mmHg, diperlukan
katerisasi jantung untuk mengonfirmasi temuan tersebut.
Tenoi dapat dihilangkan dengan valvuloplasti balon dengan
ujung kateter melewati katup aorta dari arteri femoralis,
balon dikembangkan untuk melebarkan katup yang stenosis.
Congenital Heart Defect Page 18
Jika hal ini tidak berhasil atau stenosis aorta berat,
diperlukan valvotomi aorta terbuka. Stenosis dan
insufisiensi residual sering dijumpai, tetapi penggantian
katup aorta harus dihindari sedapat mungkin sampai
pertumbuhan anak berhenti. Stenosis aorta merupakan suatu
kelainan jantung bawaan yang memerlukan pembatasan
aktivitas berat karena terdapat risiko kematian mendadak.
Pencegahan endokarditis bakterialis merupakan hal yang
penting. (Hull & Johnston, 1995).
1.1.6 Stenosis Pulmonal
Pada keadaan ini, katup pulmonal mengalami
deformitas bawaan. Katup mengalami penebalan dan
menyempit. Ventrikel kanan mengalami hipertrofi sebagai
kompensasi adanya obstruksi. Saluran keluar ventrikel
kanan yang muscular, yaitu infundibulum, juga mengalami
hipertrofi dan ini akan meningkatkan derajat obstruksi.
(Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Jika terdapat stenosis yang
berat, bayi akan memperlihatkan gagal jantung kanan.
Sianosis mungkin tampak, akibat pirau darah dari kanan ke
kiri melalui foramen ovale. Pada kasus ringan dan sedang,
bising jantung terdengar pada pemeriksaan rutin. Gejala
jarang dijumpai pada masa kanak-kanak. Namun pada kasus
stenosis sedang, disfungsi ventrikel kanan dan aritmia
mungkin terjadi pada masa dewasa. (Hull & Johnston,
1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks menunjukan
dilatasi arteri pulmonalis post-stenosis. Atrium kanan
dan ventrikel kanan membesar pada kasus yang berat.
Congenital Heart Defect Page 19
Elektrokardiogram memperlihatkan deviasi aksis ke kanan
(RAD), hipertrofi atrium kanan dan hipertrofi ventrikel
kanan dalam derajat yang bervariasi, tergantung pada
derajat stenosis. Gradient katup pulmonal diukur dengan
ultrasonografi Doppler. (Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Jika gradient Doppler melewati katup
lebih dari 40-50 mmHg, dilakukan kateterisasi jantung
dengan valvuloplasti balon. Tindakan ini mempunyai
keberhasilan yang tinggi penyempitan dikurangi sampai 75
persen atau lebih dan penyempitan biasanya tidak rekuren.
(Hull & Johnston, 1995).
1.1.7 Koarktasio Aorta
Koarktasio aorta merupakan penyempitan local aorta
desendens, dekat lokasi duktus arteriosus dan biasanya
sebelah distal arteri subklavia kiri. Darah arteri
memintas daerah obtruksi dan mencapai bagian bawah tubuh
melalui pembuluh darah kolateral yang sangat membesar.
Ventrikel kiri mengalami hipertrofi sebagai kompensasi
adanya obstruksi dan dapat terjadi gagal jantung. Tekanan
darah sistolik pada bagian atas tubuh biasanya meningkat.
(Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Jika terjadi penyempitan berat,
dapat timbul gagal jantung dalam beberapa hari atau
beberapa minggu pertama kehidupan. Namun pada sebagian
besar kasus, diagnosis dibuat pada pemeriksaan rutin
ataupun secara kebetulan, yaitu dengan terdengarnya
bising atau tidak terabanya nadi femoralis ataupun karena
ditemukannya hipertensi. Kadang-kadang dapat terjadi
Congenital Heart Defect Page 20
komplikasi seperti perdarahan subaraknoid akibat pecahnya
aneurisma intracranial atau endarteritis bakterialis pada
anak ataupun dewasa. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks mungkin
menunjukan pembesaran ventrikel kiri. Pada anak yang
lebih besar dapat terlihat lekukan iga tempat arteri
interkostal yang membesar telah mengerosi sisi bawah iga.
Elektrokardiogram mungkin memperlihatkan hipertrofi
ventrikel kiri (LVH). (Hull & Johnston, 1995).
Pengobatan. Pembedahan dianjurkan untuk semua kasus
kecuali kasus yang amat ringan. Pembedahan sebaiknya
dilakukan segera setelah diagnosis ditegakkan. Segmen
aorta yang menyempit direseksi dan kedua ujung disambung
kembali. Pada bayi, bagian proksimal arteri subklavia
kiri dapat digunakan memperbaiki aorta setelah eksisi
bagian yang menyempit. Pembedahan dini lebih efektif
dalam mengatasi hipertensi secara permanen, tetapi karena
anak bertumbuh, terdapat risiko penyempitan kembali pada
lokasi koartasio yang akan memerlukan pembedahan lanjut.
(Hull & Johnston, 1995).
1.2 Penyakit Jantung Kongenital Sianotik
1.2.1 Tetralogi Fallot
Dua gejala utama kelainan ini adalah defek septum
ventrikel yang besar dan biasanya berlokasi disebelah
atas pada bagian membranosa septum dibawah katup aorta,
serta stenosis katup pulmonal atau infundibulum. Oleh
karena itu terdapat resistensi terhadap aliran darah
melalui katup pulmonal sehingga terjadi pirau darah dari
ventrikel kanan ke ventrikel kiri kemudian ke aorta. Pada
Congenital Heart Defect Page 21
kenyataannya, karena defek septum berada tepat dibawah
katup aorta, aorta tampak meluas sehingga berhubungan
dengan ventrikel kanan dan terjadi pirau langsung dari
ventrikel kanan ke aorta. Stenosis pulmonal atau
infundibulum menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan.
Overriding aorta, hipertrofi ventrikel kanan, dalam
kombinasi dengan defek septum ventrikel dan stenosis
pulmonal membentuk tetralogi yang dilaporkan pertama kali
oleh fallot. Arteri pulmonalis utama berukuran kecil dan
arteri tersebut mungkin tidak paten pada kasus yang
paling berat (atresia pulmonal dengan defek septum
ventrikel). (Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Anak yang menderita tetralogi
fallot biasanya tampak kemerahan pada masa neonatus,
meskipun mungkin terdengar bising jantung akibat aliran
darah melalui infundibulum atau katup pulmonal yang
menyempit. Sianosis timbul dan bertambah berat setelah
beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Kadangkala
bayi mungkin terlihat kemerahan saat istirahat dan hanya
terlihat sianosis pada saat memeras tenaga seperti saat
menangis atau minum susu. Bayi yang menderita tetralogi
fallot hampir sepanjang waktu tampak relative sehat,
namun rentan terhadap serangan yaitu saat bayi menjadi
amat sianosis dan pucat serta seringkali disertai
penurunan kesadaran. Serangan demikian terjadi karena
penurunan resistensi pembuluh darah sistemik, sehingga
meningkatkan pirau kanan ke kiri dan mencegah darah
mengalir ke paru-paru. Gagal jantung amat jarang terjadi
pada tetralogi fallot tetapi komplikasi tromboemboli
Congenital Heart Defect Page 22
akibat polisitemia, endokarditis bakterialis dan abses
serebri dapat terjadi. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks memperlihatkan
besar jantung yang normal dengan apeks diatas diafragma
kiri, tetapi pinggir jantung kiri berbentuk konkaf karena
arteri pulmonalis utama berukuran kecil. Diagnosis
ditegakkan dengan ekokardiografi. (Hull & Johnston,
1995).
Pengobatan. Pengobatan pada semua kasus tetralogi
fallot yaitu dengan pembedahan. Pembedahan pirau adalah
pembuatan komunikasi antara sirkulasi sistemik dan
pulmonalis. Jenis yang paling sering dikerjakan adalah
modifikasi prosedur blalock. Dalam prosedur tersebut ,
suatu pipa goretex digunakan untuk menghubungkan arteri
subklavia dan arteri pulmonalis pada sisi kiri atau sisi
kanan. Setelah berumur satu tahun, koreksi total
dilakukan dengan menggunakan pintasan kasrdiopulmonar-
lubang ditutup dan katup pulmonalis serta infundibulum
dilebarkan. (Hull & Johnston, 1995).
1.2.2 Transposisi Arteri Besar
Pada kelainan jantung ini, aorta dan arteri pulmonal
mengalami transposisi sehingga aorta keluar dari
ventrikel kanan dan arteri pulmonalis keluar dari
ventrikel kiri. Hal ini berarti ada dua sirkulasi
terpisah yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik
yang bekerja secara parallel. Tentu saja hal ini tidak
cocok dengan kehidupan, karena tidak sesuai denga fakta
bahwa seharusnya ada percampuran antara kedua sirkulasi.
Dalam kehidupan janin, bayi tersebut tidak mengalami
Congenital Heart Defect Page 23
kesulitan karena aliran darah pulmonal sangat kecil.
Tetapi karena duktus arteriosus dan foramen ovale mulai
menutup setelah lahir, terjadilah sianosis yang
progresif. Beratnya gejala tergantung pada derajat
percampuran kedua sirkulasi melalui saluran fetal
tersebut. Pada beberapa kasus dapat timbul defek septum
ventrikel yang besar atau duktus arteriosus paten yang
besar. Pada kasus tersebut terdapat suatu aliran darah
pulmonal yang tinggi dan hanya terdapat sianosis yang
ringan. Tetapi pada bentuk yang ringan, sianosis
progresif timbul pada jam-jam pertama atau hari-hari
pertama setelah lahir. Tanpa pengobatan hanya sedikit
anak yang dapat bertahan hidup dalam tahun pertama
kehidupan. (Hull & Johnston, 1995).
Manifestasi klinis. Sianosis progresif timbul dalam
beberapa jam pertama atau beberapa hari pertama
kehidupan. Bayi yang menderita kelainan ini menjadi
sangat biru dan asidosis. Selanjutnya dapat terjadi gagal
napas dan gagal jantung. (Hull & Johnston, 1995).
Pemeriksaan penunjang. Rontgen toraks biasanya khas.
Jantung sedikit membesar dan dikatakan tampak seperti
sebuah telur yang berbaring pada satu sisinya. Diagnosis
ditegakkan berdasarkan ekokardiografi.
Pengobatan. Sebuah pintas antara sirkulasi sistemik
dan sirkulasi pulmonal diperlukan dengan segera. Pintas
tersebut dibuat dengan cara ballon atrial septostomy
(prosedur rashkind). Sebuah kateter khusus berlumen ganda
dimasukkan lewat vena cava inferior, atrium kanan dan
foramen ovale menuju ke dalam atrium kiri. Balon dekat
ujung kateter dikembungkan dengan medium kontras,
Congenital Heart Defect Page 24
kemudian kateter dan balon ditarik kembali dengan keras
melalui septum atrium, sehingga merobek septum atrium dan
membuat defek septum yang besar. Hal ini memungkinkan
percampuran darah dan mengurangi sianosis. Operasi
koreksi definitive merupakan suatu perbaikan anatomi,
yaitu dengan mengganti arteri pulmonalis dan aorta ke
ventrikel yang seharusnya. Hal ini biasanya dilakukan
pada minggu pertama atau minggu kedua kehidupan. (Hull &
Johnston,1995)
C. PATOFISIOLOGI1. Defek Septum Atrium (ASD)
Penyakit ini terjadi karena tekanan atrium kiri lebih
besar dari atrium kanan. Hal ini disebabkan karena atrium
kanan kurang berotot dan lebih mudah terisi darah dibanding
atrium kiri. Kemudian darah akan mengalir dari atrium kiri
ke atrium kanan melalui defek tersebut. Hal ini menyebabkan
2 hal yang berbeda yaitu pada ventrikel kanan terjadi
peningkatan volume sehingga aliran darah ke paru meningkat
dan terjadi peningkatan tekanan paru. Kemudian volume paru
menurun yang ditandai dengan bising jantung pada saat
dilakukan auskultasi dan juga bayi mengalami sesak napas
atau kelelahan setelah memeras tenaga untuk menangis atau
setelah melakukan aktivitas lainnya. (Behrman, Kliegman,
Arvin, 2000).
2. Defek Septum Ventrikel (VSD)
Penyakit ini terjadi karena tekanan ventrikel kiri
lebih besar dari ventrikel kanan. Kemudian terjadi pirau
ventrikel kiri ke kanan sehingga volume ventrikel kanan
Congenital Heart Defect Page 25
meningkat dan aliran darah ke paru meningkat sehingga
terjadi peningkatan tekanan paru. Kemudian volume paru
menurun yang ditandai dengan bising jantung pada saat
dilakukan auskultasi dan juga bayi mengalami sesak napas
atau kelelahan setelah memeras tenaga untuk menangis atau
setelah melakukan aktivitas lainnya. (Behrman, Kliegman,
Arvin, 2000).
3. Duktus Arterious Persisten
Penyakit ini terjadi pada anak dari ibu yang menderita
rubella saat kehamilan trimester pertama dan pada bayi yang
dilahirkan premature. duktus arteriosus yang merupakan
pembuluh darah besar berotot, mengalirkan darah dari
ventrikel kanan dan arteri pulmonalis ke aorta. Dalam 24 jam
pertama setelah lahir, duktus akan menutup sebagai respons
terhadap darah yang teroksigenisasi. Duktus arteriosus
persisten tidak mungkin menutup spontan setelah beberapa
hari kehidupan, namun pada bayi premature penutupan spontan
dalam 3 bulan pertama kehidupan masih mungkin terjadi. Saat
resistensi pembuluh darah pulmonalis menurun setelah lahir,
terjadi pirau kiri ke kanan dari aorta ke arteri pulmonalis
melalui duktus (berlawanan arah dengan aliran darah pada
kehidupan janin). Pada DAP kecil sering ditemukan gejala
bising jantung, bayi kemerahan, dan gangguan difusi paru.
(Behrman, Kliegman, Arvin, 2000).
4. Hipertensi pulmonal.
Penyakit ini terjadi karena pirau kiri ke kanan yang
besar dengan aliran darah arteri pulmonalis yang besar akan
menimbulkan peningkatan tekanan arteri pulmonali. Sehingga
Congenital Heart Defect Page 26
mengakibatkan terjadinya defek/ lubang. Hal ini mengharuskan
pembedahan penutupan defek. Setelah pembedahan tekanan
arteri pulmonali dapat kembali normal. Namun dapat juga
menyebabkan arteri pulmonalis tetap tinggi yang
mengakibatkan kerusakan permanen pembuluh darah paru lebih
kecil sehingga dapat terjadi penyempitan dan hiperteni
pulmonal ireveribel. Jika pada keadaan tersebut defek
ditutup lagi, tekanan arteri pulmoanalis tetap tinggi. Jika
tekanan arteri pulmonalis mencapai tekanan sistemis, pirau
kiri ke kanan berhenti dan mungkin akan berbalik. (Behrman,
Kliegman, Arvin, 2000).
5. Stenosis Aorta
Penyakit ini terjadi karena ventrikel kiri meningkat
sehingga kerja ventrikel kiri jadi meningkat. Sehingga
terjadi hipetrofi ventrikel kiri dan peningkatan volume
atrium kiri. Kemudian tekanan atrium meningkat sehingga
terjadi hipertrofi atrium kiri dan penutupan daya
kontraktilitas ventrikel kiri. Darah reflak ke vena pulmonal
kemudian terjadi peningkatan cairan diparu. Sehingga
menyebabkan anak sesak napas dan terdapat bising jantung
saat dilakukan auskultasi. Ini memngindikasikan terjadinya
gangguan difusi diparu. (Behrman, Kliegman, Arvin, 2000).
6. Stenosis Pulmonal
Penyakit ini terjadi karena volume ventrikel kanan
meningkat sehingga kerja jantung meningkat. Sehingga terjadi
hipetrofi ventrikel kanan dan peningkatan tekanan atrium
kiri. Kemudian terjadi peningkatan permeabilitas vena cava
sehingga cairan intravaskuler berkurang dan kardiak output
Congenital Heart Defect Page 27
turun. Sehingga menyebabkan anak sianosis dan terdapat
bising jantung saat dilakukan auskultasi. Dan anak terlihat
pucat pada ekstremitasnya. (Behrman, Kliegman, Arvin,
2000).
7. Koarktasio Aorta
Penyakit ini terjadi karena penyempitan lokal aorta
desendens, sehingga terjadi hipertrofi ventrikel kiri
sebagai kompensasi adanya obstruksi (penyempitan) dan dapat
terjadi gagal jantung dan peningkatan tekanan darah
sistolik. Sehingga terdapat bising jantung saat dilakukan
auskultasi, serta tidak terabanya nadi femoralis. (Behrman,
Kliegman, Arvin, 2000).
8. Tetralogi fallot
Penyakit ini disebabkan oleh paparan faktor endogen dan
eksogen selama kehamilan trimester I-II. Stenosis pulmonal
menyebabkan terjadinya obstruksi berat sehingga aliran darah
paru menurun dan obstruksi aliran darah keluar ventrikel
kanan. Selanjutnya terjadi penurunan oksigen dalam darah,
hipertrofi ventrikel kanan, dan peningkatan aliran darah
aorta. Defek septum ventrikel menyebabkan tekanan sistolik
puncak ventrikel kanan ke kiri dan pirau kanan ke kiri.
(Behrman, Kliegman, Arvin, 2000).
9. Transposisi arteri besar
Pada kelainan jantung ini, aorta dan arteri pulmonal
mengalami transposisi sehingga aorta keluar dari ventrikel
kanan dan arteri pulmonalis keluar dari ventrikel kiri.
Sehingga terjadi dua sirkulasi terpisah yaitu sirkulasi
Congenital Heart Defect Page 28
pulmonal dan sirkulasi sistemik yang bekerja secara
parallel. Hal ini menyebabkan aliran darah pulmonal menjadi
sangat kecil. Bayi mengalami sianosis ringan yang ditandai
dengan pucat pada ekstremitasnya. (Behrman, Kliegman, Arvin,
2000).
D. PATHWAY
1. Pathway Defek Septum Atrium
Congenital Heart Defect Page 29
Tekanan atrium kiri > atrium
Darah mengalir dari atriumkiri ke kanan melalui defek
Aliran darah ke paru
Volume atrium kiriVolume ventrikel kanan
Volume ventrikel kiri
Kardiak output menurun
Hipoksia
Peningkatan tekanan paru
Suplai darah ke jaringan
Sianosis
-Bising jantung- sesak napas/dispnea
Volume paru menurun
Pucat pada ekstremitas
- Rontgen toraks-
Pembedahan
Gangguan difusi diparu
gangguan pertukaran gasResiko penurunan perfusi
jaringan
Gangguan ventilasi-
2. Pathway Defek Septum Ventrikel
Congenital Heart Defect Page 30
Tekanan ventrikel kiri >
Pirau ventrikel kirikanan
Aliran darah ke paru
Volume ventrikel kanan
Peningkatan tekanan paru
Volume paru menurun
- Bising jantung- Sesak
3. Pathway Duktus Arterious Persisten
Congenital Heart Defect Page 31
Rubella saat kehamilantrimester 1
DAP mengalirkan darah dari ventrikelkanan dan arteri pulmonalis ke aorta
DAP tidak menutup setelah lahir
Resistensi pembuluhdarah pulmonalis menurun
Terjadi pirau kiri ke kanan dari aortake arteri pulmonalis melalui duktus
DAP kecil
Gangguan difusi paru
Gangguan pertukaran gas
DSV kecil-Rontgen toraks
DSV sedang-Katetensasi jantung
DSV besar- Rontgen toraks- EKG
Antibiotikprofilaksis
Diuretik-Medikamentosa-Diuretik-Pembedahan
Gangguan ventilasi-
4.Pathway Hipertensi pulmonal
Congenital Heart Defect Page 32
Hipertensi pulmonal
Pirau kiri ke kanan yangbesar
Aliran darah arteripulmonalis yang besar
Peningkatan tekanan
Kerusakan permanenpembuluh darah
Penyempitan dan
DAP kecil
DAP besar
- Rontgentoraks
Pembedahan
-Rontgen thoraks-
Elektrokardiogram
Gagal jantung
Gangguanpertukaran gas
Intoleransiaktivitas
Terapimedikamentosa
Pembedahan
Gangguanventilasi-
Suplai 02 ke jaringan tubuh terganggu
Congenital Heart Defect Page 33
Peningkatan tekanan Penyempitan dan
Pembesaran jantung
Resiko penurunanperfusi jaringan
- Rontgen thoraks- Elektrokardiogram
- Kateterisasi
Transplantasi jantung paru
Suplai O2 terganggu
Hipoksia
5.Pathway Stenosis Aorta 6. Pathway
Stenosis Pulmonal
6.
Congenital Heart Defect Page 34
Stenosisaorta
Volume ventrikel kirimeningkat
Kerja ventrikel kirimeningkat
Hipertrofi ventrikelkiri
Daerah reflak ke atriumkiri
Peningkatan volume atrium kiri
Tekanan atriummeningkat
hipertrofi atrium kiri
Penurunan dayakontraliktitas
Daerah reflak ke venapulmonal
Peningkatan cairan diparu
-sesak napas-bising jantung
Gangguan difusi paru
Hipertrofi ventrikelkanan
Kerja jantung meningkat
Volume ventrikel kananmeningkat
Stenosis pulmonal
Daerah reflak ke atriumkanan
Peningkatanpermeabilitas vena cava
Daerah reflak ke venacava
Peningkatan tekananatrium kanan
Cairan intravaskuler
Suplai darah ke jaringanmenurun
Kardiak output turun
hipoksia
sianosis
Kardiomegali
7. Pathway Koarktasio Aorta
Congenital Heart Defect Page 35
Koarktasio Aorta
Penyempitan lokalaorta desendens
Obsturksi
Hipertrofi ventrikelkiri
Gagal jantung
Peningkatan Tekanandarah sistolik
- Bising Jantung- Tidak terabanya nadi femoralis- Hipertensi
- Rontgen toraks- EKG
Pembedahan
gangguan pertukaran gas
- rontgen toraks-elektrokardiogram
Kateterisasi jantung
Resiko penurunan perfusijaringan
-Rontgen toraks-elektrokardiogram
- Kateterisasi jantung- Elektrokardiogram
Gangguan ventilasi-perfusi
Pucat pada ekstremitas
Keletihan
Pola nafas tidak efektif
8. Pathway Tetralogi Fallot
Congenital Heart Defect Page 36
Tetralogi
Terpapar faktor endogen &oksigen
selama kehamilan
Defek septumStenosis Overriding
Aliran darah paru
O2 dalam darah
Obstruksialiran darah
keluar
Hipertrofiventrikel
Alirandarah
Tekanan sistolikpuncak ventrikel
Pirau kanan-kiri
Percampuran darahkaya O2 dengan CO2
9. Pathway Transposisi Arteri Besar
Congenital Heart Defect Page 37
Transposisi
Transposisi aorta Arteri pulmonal
Keluar dariventrikel kanan
Keluar dariventrikel kiri
Hipoksemia
Sesak
Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
Resiko penurunan perfusijaringan
sianos
Pucat pada ekstremitas
Kelemahantubuh
Bayi cepatlelah jikamenyusui,
-Rontgen toraks -ekokardiografi
Pembedahan
Kebutuhanbiologis
Intoleransiaktivitas
E. Nursing Care Plan
1. Defek Septum Atrium
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: - Peningkatan tekanan paru Ganguan Ganguan
Congenital Heart Defect Page 38
Sirkulasisistemik
Sirkulasipulmonal
Aliran darahpulmonal sangat
Komplikasi
-Defek septum ventrikel besar-Duktus arterious
Hipoksemia
Siagnosis
Resiko penurunan perfusijaringan
-Rontgen toraks-ekokardiografi
Pembedahan
DO:- Sesak napas- Bising jantung
Vol. paru menurun
- bising jantung- sesak napas/dispnea
Gangguan difusi paru
Gangguan Ventilasi- perfusi
Gangguan pertukan gas
pertukaran gas pertukaran gasberhubungan dengan Ventilasi- perfusi
2 DS:-DO:- Hipoksia- Siagnosis- Pucat pada ektremitas
Suplai darah ke jaringan tubuhmenurun
Hipoksia
Siagnosis
Pucat pada ektremitas
Resiko Penurunan perfusi jaringan
Resiko penurunanperfusi jaringan
Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia.
2. Defek septum ventrikel
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- Sesak napas- Bising jantung
Peningkatan tekanan paru
Vol. paru menurun
- bising jantung- sesak napas/dispnea
Gangguan difusi paru
Gangguan Ventilasi- perfusi
Ganguan pertukaran gas
Ganguan pertukaran gasberhubungan dengan Ventilasi- perfusi
Congenital Heart Defect Page 39
Gangguan pertukaran gas
3. Duktus Arteriosus Persisten
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- bising jantung- bayi kemerahan
DAP kecil
- bising jantung- bayi kemerahan
Gangguan difusi
Gangguan Ventilasi- perfusi
Gangguan pertukan gas
Ganguan pertukaran gas
Ganguan pertukaran gasberhubungan dengan Ventilasi- perfusi
2 DS:-DO:- klien lemah- BB menurun
DAP besar
Gagal jantung
Suplai O2 ke jaringan tubuh terganggu
Intoleransi aktivitas
Intoleransi aktivitas
Intoleransi aktivitas berhubungan dengan Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
4. Hipertensi Pulmonal
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis
Congenital Heart Defect Page 40
1 DS: -DO:- Siagnosis
Tekanan arteri pulmonal tetaptinggi
Pirau kiri ke kanan berhenti
Pembesaran jantung
Suplai O2 terganggu
Hipoksia
Resiko penurunan perfusi jaringan
Resiko penurunanperfusi jaringan
Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia.
5. Stenosis Aorta
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- sesak napas- bising jantung
Peningkatan cairan di paru
- Sesak napas- Bising jantung
Gangguan difusiparu
Gangguan Ventilasi- perfusi
Gangguan pertukangas
Ganguan pertukaran gas
Ganguan pertukaran gasberhubungan dengan Ventilasi- perfusi
6. Stenosis pulmonal
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- sesak napas- bising jantung
Suplai darah ke jaringanmenurun
Hipoksia
Resiko penurunanperfusi jaringan
Resiko penurunan perfusi jaringan
Congenital Heart Defect Page 41
Siagnosis
Pucat pada ektremitas
Resiko Penurunan perfusijaringan
Gangguan pertukangas
berhubungan dengan hipoksia
7. Koarktasio Aorta
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:Hipertrofi ventrikel kiri
Gagal jantung
Keletihan
Pola nafas tidakefektif
Pola nafas tidakefektif
Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan keletihan
8. Tetralogy fallot
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- Sesak napas- klien tampak lemah
Hipoksemia
Sesak napas
Kelemahan tubuh
bayi cepat lelah jika menyusu
kebutuhan biologis terganggu
ketidakseimbangan nutrisikurang dari
kebutuhan tubuh
gangguan nutrisikurang darikebutuhan tubuh
Ketidakseimbangan nutrisi kurang darikebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis
Congenital Heart Defect Page 42
2 DS:-DO:- Sesak napas- klien tampak lemah
Hipoksemia
Sesak napas
Kelemahan tubuh
Intoleransi aktivitas
Intoleransi aktivitas
Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum
3 DS:DO:- siagnosis
Hipoksemia
Siagnosis
Pucat pada ektremitas
Resiko Penurunan perfusijaringan
Resiko Penurunanperfusi jaringan
Resiko Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksemia.
9. Transposisi arteri besar
No Data Etiology (pathway) Problem Diagnosis1 DS: -
DO:- siagnosis-
A liran darah pulmonal yang kecil
Hipoksemia
Siagnosis
Resiko Penurunan perfusi jaringan
Resiko Penurunanperfusi jaringan
Resiko Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksemia
Intervensi
1. Defek Septum Atrium
Diagnosis:
Congenital Heart Defect Page 43
1. Ganguan pertukaran gas berhubungan dengan Ventilasi- perfusi.
2. Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia
(Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Mendemontrasikan
peningkatan ventilasi
dan oksigenasi yang
adekuat.
Mendemonstrasikan batuk
efektif dan suara nafas
yang bersih, tidak ada
dyspnue (mampu
mengeluarkan sputum,
mampu bernafas dengan
mudah).
Tanda-tanda vital dalam
rentang normal.
Posisikan pasien
untuk
memaksimalkan
ventilasi.
Identifikasi
pasien perlunya
pemasangan alat
jalan nafas
buatan.
Auskultasi suara
nafas, catat
adanya suara
tambahan.
Monitor pola nafas
: bradipena,
takipenia,
hiperventilasi.
Auskultasi suaru
paru setelah
tindakan untuk
mengetahui
hasilnya.
Agar memudahkan
pernafasan
Memaksimalkan
bernafas pasien.
Bunyi nafas menurun
atau tidak bila
jalan nafas
obstruksi sekunder
terhadap
perdarahan.
Untuk mengetahui
gangguan yang
terjadi pada system
pernapasan pasien.
2 Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
Congenital Heart Defect Page 44
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
disritma jantung.
Monitor abdomen
sebagai indicator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
menandakan gagal
jantung.
tindakan
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
2. Defek septum ventrikel
Diagnosis:
1. Ganguan pertukaran gas berhubungan dengan Ventilasi- perfusi.
2. Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia
(Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Mendemontrasikan
peningkatan ventilasi
dan oksigenasi yang
adekuat.
Mendemonstrasikan batuk
efektif dan suara nafas
yang bersih, tidak ada
dyspnue (mampu
mengeluarkan sputum,
mampu bernafas dengan
mudah).
Tanda-tanda vital dalam
rentang normal.
Posisikan pasien
untuk
memaksimalkan
ventilasi.
Identifikasi
pasien perlunya
pemasangan alat
jalan nafas
buatan.
Auskultasi suara
nafas, catat
adanya suara
Agar memudahkan
pernafasan
Memaksimalkan
bernafas pasien.
Bunyi nafas menurun
atau tidak bila
jalan nafas
obstruksi sekunder
terhadap
perdarahan.
Untuk mengetahui
gangguan yang
terjadi pada systemCongenital Heart Defect Page 45
tambahan.
Monitor pola nafas
: bradipena,
takipenia,
hiperventilasi.
Auskultasi suaru
paru setelah
tindakan untuk
mengetahui
hasilnya.
pernapasan pasien.
2 Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
disritma jantung.
Monitor abdomen
sebagai indicator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
menandakan gagal
jantung.
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
3. Duktus Arteriosus Persisten
Diagnosis:
1. Ganguan pertukaran gas berhubungan dengan Ventilasi- perfusi.
2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan Ketidakseimbangan
antara suplai dan kebutuhan oksigen (Nanda, 2012).
Congenital Heart Defect Page 46
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Mendemontrasikan
peningkatan ventilasi
dan oksigenasi yang
adekuat.
Mendemonstrasikan batuk
efektif dan suara nafas
yang bersih, tidak ada
dyspnue (mampu
mengeluarkan sputum,
mampu bernafas dengan
mudah).
Tanda-tanda vital dalam
rentang normal.
Posisikan pasien
untuk
memaksimalkan
ventilasi.
Identifikasi
pasien perlunya
pemasangan alat
jalan nafas
buatan.
Auskultasi suara
nafas, catat
adanya suara
tambahan.
Monitor pola nafas
: bradipena,
takipenia,
hiperventilasi.
Auskultasi suaru
paru setelah
tindakan untuk
mengetahui
hasilnya.
Agar memudahkan
pernafasan
Memaksimalkan
bernafas pasien.
Bunyi nafas menurun
atau tidak bila
jalan nafas
obstruksi sekunder
terhadap
perdarahan.
Untuk mengetahui
gangguan yang
terjadi pada system
pernapasan pasien.
2 Berpartisipasi dalam
aktifitas fisik tanpa
di serta peningkatan
TD, nadi dan RR.
TTV normal.
Level kelemahan.
mengidentifikasi
aktivitas yang
mampu dilakukan.
Kolaborasi dengan
tenaga rehabilitas
medic dalam
Agar tindakan yang
diberikan sesuai
dengan kebuthan
pasien.
Mempercepat proses
pengambalian
Congenital Heart Defect Page 47
Status respirasi :
pertukaran gas dan
ventilasi adekuat.
merencanakan
program terapi
yang tepat
Bantu untuk
mengidentifikasi
aktivitas yang
disukai
Bantu
pasien/keluarga
untuk
mengidentifikasi
kekurangan dalam
beraktivitas
kemampuan
aktivitas.
Meningkatkan
kemampuan aktivitas
pasien.
4. Hipertensi Pulmonal
Diagnosis:
1. Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia
(Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
disritma jantung.
Monitor abdomen
sebagai indicator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
Congenital Heart Defect Page 48
menandakan gagal
jantung.
5. Stenosis Aorta
Diagnosis:
1. Ganguan pertukaran gas berhubungan dengan Ventilasi- perfusi
(Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Mendemontrasikan
peningkatan ventilasi
dan oksigenasi yang
adekuat.
Mendemonstrasikan batuk
efektif dan suara nafas
yang bersih, tidak ada
dyspnue (mampu
mengeluarkan sputum,
mampu bernafas dengan
mudah).
Tanda-tanda vital dalam
rentang normal.
Posisikan pasien
untuk
memaksimalkan
ventilasi.
Identifikasi
pasien perlunya
pemasangan alat
jalan nafas
buatan.
Auskultasi suara
nafas, catat
adanya suara
tambahan.
Monitor pola nafas
: bradipena,
takipenia,
hiperventilasi.
Auskultasi suaru
paru setelah
tindakan untuk
Agar memudahkan
pernafasan
Memaksimalkan
bernafas pasien.
Bunyi nafas menurun
atau tidak bila
jalan nafas
obstruksi sekunder
terhadap
perdarahan.
Untuk mengetahui
gangguan yang
terjadi pada system
pernapasan pasien.
Congenital Heart Defect Page 49
mengetahui
hasilnya.
6. Stenosis Pulmonal
Diagnosis:
1. Resiko penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia.
(Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
disritma jantung.
Monitor abdomen
sebagai indicator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
menandakan gagal
jantung.
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
7. Korktasio Aorta
Diagnosis:
1. Pola nafas tidak efektif berhubugnan dengan keletihan. (Nanda,
2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
Congenital Heart Defect Page 50
1. Mendemonstrasikan batuk
efektif dan suara nafas
yang bersih (mampu
bernafas dengan mudah)
Frekuensi pernafasan
dalam rentang normal.
TTV dalam rentang normal
(TD, Nadi, Pernafasan).
Posisikan pasien
untuk memaksimalkan
ventilasi
Auskultasi suara
napas, catat adanya
suara tambahan
Monitor respirasi
dan status O2 ,
(oxygen terapi)
Monitor TD, nadi,
suhu, dan RR
Monitor pola
pernapasan abnormal
Posisi semifowler
bisa membuat klien
mudah untuk
bernafas.
Untuk mengetahui
apakah suara nafas
klien normal.
Mengetahui apakah
kebutuhan O2
terpenuhi.
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
selanjutnya.
Mengetahui gangguan
pernafasan apa yang
dialami pasien.
8. Tetralogi Fallot
Diagnosis:
1. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis
2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum
Congenital Heart Defect Page 51
3. Resiko Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksemia. (Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Adanya peningkatan BB
sesuai tujuan.
BB ideal sesuai dengan
tinggi badan.
Tidak ada tanda
malnutrisi.
Tidak terjadi penurunan
berat badan yang
berarti.
Kaji adanya alergi
makanan.
Kolaborasi dengan
ahli gizi untuk
menentukan jumlah
kalori dan nutrisi
yang dibutuhkan
pasien.
Berikan makan yang
terpilih (sudah
dikonsultasikan
dengan ahli gizi).
Pasien tidak salah
dalam menerima
asupan makanan.
Kalori dan nutrisi
dibutuhkan untuk
memenuhi.
Agar nutrisi pasien
terpenuhi sesuai
dengan kebutuhan.
2 Berpartisipasi dalam
aktifitas fisik tanpa
di serta peningkatan
TD, nadi dan RR.
TTV normal.
Level kelemahan.
Status respirasi :
pertukaran gas dan
ventilasi adekuat.
Mengidentifikasi
aktivitas yang
mampu dilakukan.
Kolaborasi dengan
tenaga rehabilitas
medic dalam
merencanakan
program terapi
yang tepat
Bantu untuk
mengidentifikasi
aktivitas yang
disukai
Agar tindakan yang
diberikan sesuai
dengan kebuthan
pasien.
Mempercepat proses
pengambalian
kemampuan
aktivitas.
Meningkatkan
kemampuan aktivitas
pasien.
Congenital Heart Defect Page 52
Bantu
pasien/keluarga
untuk
mengidentifikasi
kekurangan dalam
beraktivitas3 Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
disritma jantung.
Monitor abdomen
sebagai indikator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
menandakan gagal
jantung.
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
9. Transposisi Arteri Besar
Diagnosis:
1. Resiko Penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan
hipoksemia. (Nanda, 2012).
No.
Dx
Goal/ out comes Intervention Rational
1. Tekanan systolic dan dan
diastole dalam rentang
yang diharapkan.
Bunyi jantung abnormal
tidak ada.
Monitor TD, nadi,
suhu dan RR.
Catat adanya
disritma jantung.
Monitor abdomen
Vital sign
merupakan indikasi
dalam menetukan
tindakan
Congenital Heart Defect Page 53
Kelahan yang ekstrim
tidak ada.
sebagai indikator
penurunan perfusi.
Monitor status
pernafasan yang
menandakan gagal
jantung.
selanjutnya.
untuk mengetahui
keadaan frekuensi
dan irama jantung.
Implementasi (Skip)
Evaluation
1. Defek Septum Atrium
DIAGNOSIS SOAP
1. Ganguan pertukaran gas
berhubungan dengan
Ventilasi- perfusi
S : keluarga klien mengatakan
bahwa klien masih sering
kesulitan ketika bernapas.
O : - klien sesak napas
- terdapat bising jantung
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi 2. Resiko penurunan
perfusi jaringan berhungan
dengan hipoksia,
S : -
O : - Hipoksia
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
Congenital Heart Defect Page 54
2. Defek septum ventrikel
DIAGNOSIS SOAP1. Ganguan pertukaran gas
berhubungan dengan
Ventilasi- perfusi
S : keluarga klien mengatakan
bahwa klien masih sering
kesulitan ketika bernapas.
O : - klien sesak napas
- terdapat bising jantung
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi 2. Resiko penurunan
perfusi jaringan berhungan
dengan hipoksia,
S : -
O : - Siagnosis
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
3. Duktus Arteriosus Persisten
DIAGNOSIS SOAP1. Ganguan pertukaran gas
berhubungan dengan
Ventilasi- perfusi
S : keluarga klien mengatakan
bahwa klien masih sering
kesulitan ketika bernapas.
O : - klien sesak napas
- terdapat bising jantung
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi2. Intoleransi aktivitas
berhubungan dengan
Ketidakseimbangan antara
suplai dan kebutuhan oksigen
S : -
O : - klien tampak lemah
- BB klien masih dibawah
normal
A : masalah belum teratasi
Congenital Heart Defect Page 55
P : lanjutkan intervensi
4. Hipertensi Pulmonal
DIAGNOSIS SOAP 1. Resiko penurunan
perfusi jaringan berhungan
dengan hipoksia,
S : -
O : - siagnosis
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
5. Stenosis Aorta
DIAGNOSIS SOAP1. Ganguan pertukaran gas
berhubungan dengan Ventilasi-
perfusi
S : keluarga klien mengatakan
bahwa klien masih sering
kesulitan ketika bernapas.
O : - klien sesak napas
- terdapat bising jantung
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
6. Stenosis Pulmonal
DIAGNOSIS SOAP 1. Resiko penurunan
perfusi jaringan berhungan
dengan hipoksia,
S : -
O : - Siagnosis
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
Congenital Heart Defect Page 56
7. Koarktasio Aorta
DIAGNOSIS SOAP 1. pola nafas tidak
efektif berhubungan
keletihan.
S : -
O : - Siagnosis
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
8. Tetralogi Fallot
DIAGNOSIS SOAP1. Ketidakseimbangan nutrisi
kurang dari kebutuhan tubuh
berhubungan dengan faktor
biologis
S : -
O : - klien terlihat lemah
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
2. Intoleransi aktivitas
berhubungan dengan kelemahan
umum
S : -
O : - klien masih tampak lemah
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
3. Resiko Penurunan perfusi
jaringan berhubungan dengan
hipoksemia
S : -
O : - siagnosis
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
9. Transposisi Arteri Besar
DIAGNOSIS SOAP1. Resiko Penurunan perfusi
jaringan berhubungan dengan
S : -
O : - siagnosis
Congenital Heart Defect Page 57
hipoksemia A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
E. Family Teaching
- Ajarkan kepada bapak dan ibu atau keluarga dari anak tentang
bagaimana cara memantau kecenderungan kenaikan dan penurunan
berat badan.
- Berikan pemahaman kepada bapak dan ibu atau keluarga tentang
pemberian makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan
nutrisi.
- Berikan penjelasan kepada orang tua tentang bagaimana cara
untuk mengidentifikasi kekurangan dalam beraktifitas.
F. Departement of Health (DOH) Policy ( terlampir I )
G. Evidence Based Reseach ( terlampir II )
Congenital Heart Defect Page 58
DAFTAR PUSTAKA
Berhman, Richard E; Kliegman, Robert M; Arvin, Ann M
(editor).2000. Ilmu Kesehatan Anak Nelson. Edisi 15. Jakarta:
EGC.
Herdman T. Heather. 2012. Diagnosis Keperawatan Definisi dan Klasifikasi 2012-
2014. Jakarta: EGC.
Hull, David., dan Johnston, Derek I. 1995. Dasar-dasar pediatri.
(Edisi 3). Jakarta: EGC.
Slonane, Ethel. 2003. Anatomi Dan Fisiologi untuk pemula. 2003. Jakarta:
EGC .
Smeltzer, Suzanne C., dan Bare, Brenda G. 2001. Keperawatan Medikal
Bedah Brunner & Suddarth (Volume dua). Edisi 8. Jakarta: EGC.
Congenital Heart Defect Page 59