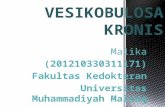Isi laporan fix
Transcript of Isi laporan fix
I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapang
Kubis atau kol merupakan salah satu jenis sayuran
daun yang berasal dari daerah subtropis yang telah lama
dikenal dan dibudidayakan di Indonesia. Produksi kubis
di Indonesia, selain untuk memenuhi keperluan dalam
negeri, juga merupakan komoditas ekspor. Kubis
termasuk kelompok enam besar sayur segar yang diekspor
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni
bersama-sama dengan kubis bunga, kentang, tomat, cabe
dan bawang merah (Rukmana, 1994).
Semua jenis kubis dapat tumbuh dan berkembang pada
berbagai jenis tanah. Kubis akan tumbuh optimum bila
ditanam pada tanah yang kaya akan bahan organik. Kubis
memerlukan air yang cukup tetapi tidak boleh
berlebihan. Artinya tanaman kubis akan mati bila
kekurangan atau kelebihan air. Realita yang ada, tidak
semua petani di sentra pertanaman kubis menanam kubis.
Keengganan petani menanam kubis dipicu oleh alasan
1
klasik yaitu takut terserang hama dan penyakit.
Tanaman kubis akan tumbuh baik pada kelembaban yang
cukup tinggi (60-69%) dan suhu cukup rendah. Keadaan
ini memang dapat memunculkan berbagai penyakit,
terutama bakteri dan cendawan. Kedua patogen inilah
yang merupakan patogen utama pada kubis (Pracaya,
2001).
Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyakit kubis
sangat besar nilainya. Terkadang serangannya sangat
hebat sehingga terjadi gagal panen. Oleh sebab itu,
pengetahuan mengenai penyakit-penyakit pada kubis,
gejala, dan cara pengendaliannya sangat penting.
Pengetahuan ini khususnya penting diketahui oleh petani
kubis atau petani yang tinggal di daerah yang cocok
untuk pertumbuhan kubis agar mereka tetap mau menanam
kubis dan paham cara pengendalian hama dan penyakitnya
(Pracaya, 2001).
Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan prinsip
Pengendalian Hama Penyakit Terpadu (PHT), yakni
pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan
2
menggunakan satu atau lebih dari beberapa teknik
pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan
untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan
kerusakan lingkungan hidup. PHT memadukan berbagai
metode pengelolaan tanaman budidaya dalam perpaduan
yang paling efektif dalam mencapai stabilitas produksi,
dengan seminimal mungkin bagi manusia dan lingkungan.
PHT dapat dilakukan dengan cara fisik, biologi, kultur
teknis, dengan cara kimiawi maupun dengan pengendalian
secara hayati (Anonim, 2007).
Pengendalian hama dan penyakit di Balitsa
menggunakan teknik pengendalian hama secara terpadu
yaitu teknik pengendalian dengan melihat terlebih
dahulu apakah ada serangan, jika terdapat serangan dan
sudah melebihi ambang kematian maka dilakukan
pengendalian dengan menyemprotkan pestisida pada
tanaman kubis. Pengantisipasian serangan penyakit
yaitu lebih diutamakan adalah kegiatan pencegahan
dengan perlakuan benih dan pemeliharaan bibit.
3
B. Tujuan Praktik Kerja Lapang
Tujuan praktik kerja lapang yang dilaksanakan di
Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang Bandung
antara lain:
1. Mengetahui budidaya tanaman kubis.
2. Mengetahui manajemen pengendalian hama dan penyakit
pada tanaman kubis.
3. Mengetahui analisis usaha tani dalam budidaya
tanaman kubis di Balai Penelitian Tanaman Sayuran,
Lembang Bandung.
C. Manfaat
Manfaat Praktik Kerja Lapang di Balai Penelitian
Tanaman Sayuran, Lembang Bandung antara lain:4
1. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang proses
budidaya tanaman kubis.
2. Mengetahui manajemen pengendalian hama dan penyakit
yang ada pada tanaman kubis.
3. Memperoleh pengalaman kerja di lapangan dan dapat
menerapkan teori yang telah diterima di bangku
kuliah dengan praktik yang sesungguhnya.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
Manajemen hama dan penyakit, mencakup kegiatan-
kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) yang dapat menyebabkan penurunan produksi dan
mutu, dengan memperhatikan aspek keamanan produk dan5
kelestarian lingkungan serta sumber daya alam.
Pengendalian OPT dilakukan dengan prinsip Pengendalian
Hama Penyakit Terpadu (PHT) (Anonim, 2007).
PHT memadukan berbagai metode pengelolaan tanaman
budidaya dalam perpaduan yang paling efektif dalam
mencapai stabilitas produksi, dengan seminimal mungkin
bagi manusia dan lingkungan. PHT dapat dilakukan
dengan cara:
1. Fisik, membunuh organisme pengganggu secara
manual
2. Biologi, memanfaatkan peranan agens hayati
seperti predator dan pathogen
3. Kultur teknis, dengan penanaman varietas toleran,
pengaturan jarak tanam, pengaturan drainase,
pemupukan berimbang, penjarangan buah, dll.
4. Kimiawi, merupakan alternatif terakhir, dengan
mempertimbangkan ambang ekonomi (Anonim, 2007).
Pengendalian juga dapat menggunakan pertisida
hayati yang akrab lingkungan, disebut demikian karena
bahan kimia nabati ini dapat mudah terurai, dapat
6
dibuat oleh petani karena bahan baku tersedia disekitar
lokasi, dan harga pembuatan yang terjangkau. Kelemahan
pestisida nabati adalah:
1. Daya tahan yang singkat (sangat mudah
berubah/terurai), oleh karena itu volume aplikasi
harus direncanakan dengan cermat agar efisien,
2. Konsentrasi larutan yang dihasilkan masih tidak
konsisten karena sangat tergantung pada tingkat
kesegaran bahan baku.
3. Diperlukan standar pengolahan untuk tiap tanaman dan
standar aplikasi penggunaan bagi pengendalian OPT
(Anonim, 2007).
PHT meliputi empat prinsip dasar, yaitu:
1. Tanaman budidaya yang sehat
Sasaran pengelolaan agro-ekosistem adalah
produktivitas tanaman budidaya. Pemilihan varietas,
tanaman yang memperoleh cukup pemupukan, pengairan,
penyiangan gulma dan disertai pengolahan tanah yang
baik sebelum masa tanam adalah dasar bagi pencapaian
7
hasil produksi yang tinggi. Budidaya yang sehat dan
kuat bagian program PHT.
2. Melestarikan dan Mendayagunakan fungsi musuh alami
Kekuatan unsur-unsur alami sebenarnya mampu
mengendalikan lebih dari 99% hama kebanyakan lahan
agar tetap berada pada jumlah yang tidak merugikan.
Tanpa disadari, sebenarnya semua petani bergantung
pada kekuatan alami yang sudah tersedia di lahannya
masing-masing. PHT secara sengaja mendayagunakan
dan memperkuat peranan musuh alami yang menjadi
jaminan pengendalian, serta memperkecil pemakaian
pestisida berarti mendatangkan keuntungan ekonomis
kesehatan dan lingkungan tidak tercemar.
3. Pemantauan Lahan Secara Mingguan
Masalah hama tidak timbul begitu saja. Masalah ini
timbul karena kombinasi faktor-faktor lingkungan
yang mendukung pertumbuhan populasi hama. Kondisi
lingkungan atau ekosistem sangat penting artinya
8
dalam kaitannya dengan timbulnya masalah HAM. PHT
menganjurkan pemantauan lahan secara mingguan oleh
petani sendiri untuk mengkaji masalah hama yang
timbul dari keadaan ekosistem lahan yang cenderung
berubah dan terus berkembang. Pengendalian Hama
Terpadu membantu petani untuk mempelajari dan
mempraktekkan keterampilan teknologi pengendalian
hama.
4. Petani Menjadi Ahli PHT di Lahannya Sendiri
Pada dasarnya petani adalah penanggung jawab,
pengelola dan penentu keputusan di lahannya sendiri.
Petugas dan orang-orang lain merupakan nara sumber,
pemberi informasi dan pemandu petani apabila
diperlukan, untuk itu petani dilatih untuk ahli PHT
dilahannya sendiri. Petani secara mandiri dan
percaya diri mampu untuk melaksanakan dan menerapkan
prinsip teknologi PHT di lahannya sendiri dengan
keahliannya itu. Petani harus mampu menjadi
pengamat, penganalisis ekosistem, pengambil
keputusan pengendalian dan sebagai pelaksana
9
teknologi pengendalian sesuai dengan prinsip-prinsip
PHT karena petani bertindak sebagai ahli PHT
(Harahap, 2010).
B. Botani dan Ekologi Tanaman Kubis
Berdasarkan klasifikasinya, kol/kubis termasuk
dalam:
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Klas : Dicotyledonae
Famili : Cruciferae
Genus : Brassica
Spesies : Brassica oleracea (Anonim, 2009).
Tanaman kubis yang dibudidayakan umumnya tumbuh
semusim (annual) ataupun dwi musim (biennua ) yang
berbentuk perdu. Sistem perakaran tanaman kubis relative
dangkal, yakni menembus pada kedalaman tanah antara 2010
– 30 cm. Batang tanaman kubis umumnya pendek dan
banyak mengandung air (Herbaceous), di sekeliling batang
hingga titik tumbuh, terdapat helai daun yang
bertangkai pendek. Daun – daun kubis bentuknya bulat
telur sampai lonjong dan lebar – lebar, berwarna hijau
(kubis putih) atau hijau – kemerahan (kubis merah).
Daun – daun atas pada fase generatif akan saling
menutupi satu sama lain membentuk krop. Bentuk krop
sangat bervariasi antara bulat – telur, gepeng dan
bentuk kerucut. Struktur bunga kubis terdiri atas 4
helai daun kelopak berwarna hijau, 4 helai daun mahkota
berwarna kuning muda, 4 helai benangsari bertangkai
panjang, 2 helai benangsari bertangkai pendek dan 1
buah putik yang beruang dua. Selama 1 – 2 bulan
tanaman kubis dapat berbunga terus dan jumlah bunga
yang dihasilkan mencapai lebih dari 500 kuntum.
Tanaman kubis termasuk mudah sekali kawin silang,
tetapi sukar untuk mengadakan penyerbukan sendiri.
Buah – buah kubis berbentuk polong, panjang dan ramping
berisi biji. Biji – bijinya bulat kecil
11
berwarna cokelat sampai kehitam – hitaman. Biji – biji
inilah yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman
kubis (Rukmana, 1994).
Varietas-varietas tanaman kol yang dibudidayakan,
antara lain:
1. Kubis putih (B.o. var. capitata L. f.alba DC.)
Kubis kepala bulat: krop bulat dan kompak, ukuran
daun kecil sampai sedang, mempunyai daun luar berwarna
hijau muda, memiliki teras atau hati kecil dan
mempunyai batang pendek. Beberapa varietas unggul
kubis putih kepala bulat:
a. Globe Master: umur panen 75 hari, produksi 2-2,5
kg/tanaman
b. Emerald Cross Hybrid: umur panen 45 hari, produksi 1,2
kg/tanaman
c. Copenhagen Market: umur panen 72 hari, produksi 1,8-
2 kg/tanaman
d. K-K Cros: umur panen 58 hari, produksi 1,6
kg/tanaman
12
e. Green Cup: umur panen 73 hari, produksi 1,5
kg/tanaman
f. Ecarliana: umur panen 60 hari, produksi 1
kg/tanaman.
2. Kubis merah (B.o. var. capitata L. f. rubra.)
Krop berbentuk bulat kompak berwarna merah keunguan
dan permukaan luar daun tertutup lapisan. Beberapa
varietas yang mempunyai nilai ekonomi:
a. Ruby perfection: warna krop merah cerah, umur panen
80 hari, produksi 1,6 kg/tanaman.
b. Mammoth Red Rock: warna krop merah tua keunguan dan
keras, umur panen 100 hari, produksi 3,4
kg/tanaman.
c. Rubby ball: warna krop merah tua, umur panen 65
hari, produksi 1,5 kg/tanaman.
d. Res Acre: warna krop merah tua, umur panen 76 hari,
produksi 1,8 kg/tanaman.
3. Kubis Savoy (B.o. var. sabauda L.)
Ciri-ciri memiliki daun keriting berbentuk
babad/perut daging sapi, berwarna hijau, krop berbentuk
13
bermacam-macam, bulat dan kerucut. Kubis ini biasa
disebut kubis keriting atau kubis babat. Contoh
beberapa varietas komersial:
Perfection Drumhead : umur panen 90 hari, produksi 2,7-3,2
kg/tanaman.
a. Vorbote: produksi 1-2 kg/tanaman.
b. Savoy King Hybrid: umur panen 80 hari, produksi 1,8
kg/tanaman.
c. Savoy Ace: umur panen 80 hari, produksi 1,6
kg/tanaman.
d. Langedijk Early Yellow: produksi 1,5-2 kg/tanaman.
e. Langedijk Storage Yellow: produksi 2-3 kg/tanaman
(Perdana, 2009).
Syarat Pertumbuhan:
1. Iklim
a. Pengaruh angin dirasakan pada evaporasi lahan dan
evapotranspirasi tanaman. Laju angin yang tinggi
dalam waktu lama (continue) mengakibatkan
keseimbangan kandungan air antara tanah dan udara
14
terganggu, tanah kering dan keras, penguraian
bahan-bahan organik terhambat, unsur hara
berkurang dan menimbulkan racun akibat tidak ada
oksidasi gas-gas beracun di dalam tanah.
b. Disebutkan jumlah curah hujan 80% dari jumlah
normal (30 cm) memberikan hasil rata-rata 12%
dibawah rata-rata normal.
c. Stadia pembibitan memerlukan intensitas cahaya
lemah sehingga memerlukan naungan untuk mencegah
cahaya matahari langsung yang membahayakan
pertumbuhan bibit. Sedangkan pada stadia
pertumbuhan diperlukan intensitas cahaya yang
kuat, sehingga tidak membutuhkan naungan.
d. Tanaman kubis dapat hidup pada suhu udara 10-240C
dengan suhu optimum 170C. Untuk waktu singkat,
kebanyakan varietas kubis tahan dingin (minus 6-
100C), tetapi untuk waktu lama, kubis akan rusak
kecuali kubis berdaun kecil
e. Kandungan air tanah yang baik adalah pada
kandungan air tersedia. Dengan demikian lahan
15
tanaman kol memerlukan pengairan yang cukup baik
(irigasi maupun drainase).
2. Ketinggian Tempat
Tanaman kubis dapat tumbuh optimal pada ketinggian
200-2000 m dpl. Untuk varietas dataran tinggi,
dapat tumbuh baik pada ketinggian 1000-2000 m dpl
(Perdana, 2009).
C. Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit
Manajemen adalah suatu rangkaian yang meliputi
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka
memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik
sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi
secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
Rangkaian kegiatan tersebut dikenal sebagai fungsi –
fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut diterapkan
dalam segala bentuk manajemen bisnis baik skala besar
maupun skala kecil (Sa’id, 2001).
16
Manajemen pengendalian hama dan penyakit kubis
dapat dilakukan dengan:
1. Sebelum Tanam
a.Varietas
Pemilihan varietas untuk pertanaman merupakan
langkah awal dalam pelaksanaan budidaya tanaman
sehingga dalam pemilihan ini benar-benar
dilaksanakan dan dipikirkan apa yang akan ditanam.
b.Waktu Tanam
1) Setiap saat, tetapi untuk musim kemarau,
serangan hama akan lebih banyak.
2) Bibit sudah berumur kira-kira 3 minggu
c.Persiapan lahan
1) 2 hari sebelum tanam, tanah yang sudah diolah
mulai di bedeng-bedeng dengan ukuran bedengan 1
m. Bagian yang akan dibuat timbunan ini berguna
untuk menutup pupuk kandang yang ditaburkan
diatas bedengan.
17
2) Tanah di atas bedengan harus benar-benar gembur.
Untuk itu tanah olah harus dicangkul kembali
sehingga bongkahan menjadi lebih kecil.
3) Pupuk kandang ditabur di atas tanah, kemudian
tutup dengan lapisan tanah setebal 10 cm.
d.Persemaian
1) Mencampur pupuk kandang yang benar-benar matang
ke dalam petakan yang sudah ada.
2) Biarkan 3-4 hari supaya tanah terkena sinar
matahari langsung.
3) Memasang naungan supaya tanaman tidak terkena
sinar matahari atau hujan secara langsung.
4) Pemeliharaan persemaian yang terpenting adalah
penyiraman. Penyiraman persemaian dilakukan
setiap pagi dan sore dengan menggunakan gembor
yang halus. Jika terlihat ada serangan jamur,
yaitu busuk pangkal batang, segera buang tanaman
yang terserang.
2. Waktu Tanam
18
a. Menanam bibit kubis yang sudah siap dari
persemaian (setelah berumur 3-4 minggu) dengan
jarak tanam 60 x 70 cm,dengan cara memasukkan
benih kubis ke dalam lubang yang sudah dibuat,
kemudian tutup dengan tanah.
b. Memberi pupuk dasar 5 gram TSP/SP 36 dan 5 gram
KCl per tanaman dengan cara ditugal di sebelah
lubang tanam (Lubis, 2004).
3. Setelah Tanam
a. Awal Pertumbuhan (0 – 15 hari)
1) Menyiram tanaman setelah bibit ditaman di
lapang, yaitu setiap sore sampai tanaman benar-
benar hidup.
2) Menyulam tanaman yang mati
3) Pemupukan susulan pada saat tanaman berumur 15
hari, 1 gram Urea pertanaman, dengan cara
ditugal 5 cm dari tanaman.
4) Pengendalian hama secraa mekanis “pithesan”,
yaitu mengambil hama yang ada kemudian dipencet
dngan jari.
19
b. Fase Pembentukan daun (15 – 35 hari)
1) Penyiangan pada saat tanaman berumur 34 hari
2) Penambahan 5 g urea/tanaman saat umur 35 hari.
3) Pertumbuhan tanaman pada fase ini sangat penting
karena akan mempengaruhi pertumbuhan
selanjutnya.
4) Pengendalian hama dengan cara “pithesan”
c. Fase Pembentukan telur (35 – panen)
1) Peka terhadap serangan penyakit dan ulat jantung
kubis
2) Pengendalian hama dengan cara “pithesan” , yaitu
dengan mengambil hama yang ada kemudian dibunuh.
Jika telur kubis sudah keras dan masif, siap untuk
dipanen (Lubis, 2004).
20
III. METODE PKL
A. Tempat dan Waktu PKL
1. Tempat
PKL dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman
Sayuran ( Balitsa), Jalan Tangkuban Parahu, Lembang
Bandung.
2. Waktu
PKL dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan
Februari – April. 21
B. Materi PKL
Materi yang dikaji dalam PKL adalah manajemen
pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kubis,
serta analisis usaha pengendaliaanya.
C. Metode Pelaksanaan PKL
Metode yang digunakan dalam PKL adalah:
1. Metode Partisipasi Aktif
Metode partisipasi aktif digunakan untuk melakukan
praktik kerja secara langsung di lapangan, yaitu
sesuai dengan aktifitas yang ada di Instansi yang
bersangkutan dan mengamati secara langsung yang
terjadi di lapangan.
2. Pengambilan Data
a. Data Primer22
Data primer diperoleh dari pengamatan secara
langsung mengenai pengendalian hama dan penyakit
pada tanaman kubis dan wawancara dengan petugas di
lokasi setempat
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari catatan – catatan,
buku – buku serta pustaka lain yang berhubungan
dengan topik yang diamati.
23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Balai Penelitian Tanaman Sayuran
(BALITSA)
1. Sejarah Singkat
Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA) Lembang
pada awal terbentuknya yaitu tahun 1940 berada di bawah
naungan Balai Penelitian Teknologi Pertanian Bogor.
Sejak tahun 1962 berkembang menjadi Kebun Percobaan
Hortikultura yang merupakan cabang dari Lembaga
Penelitian Hortikultura Pasar Minggu. Pada tahun 1995
berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Sayuran
(Balitsa) yang letaknya di Lembang Bandung Jawa Barat.
Setelah semakin maju dan berkembang balai hortikultura
ini terbagi atas 4 balai diantaranya ada Balai
24
Penelitian Tanaman Sayuran ( BALITSA ), Balai
Penelitian Tanaman Buah ( BALITBU ), Balai Penelitian
Tanaman Hias ( BALITHI ), di beberapa daerah di
Indonesia.
Balitsa Lembang terletak pada wilayah sentra
produksi sayuran dan lahan yang subur dan juga
merupakan daerah agrowisata. Ketinggian daerah kurang
lebih 1200 m dpl, dengan curah hujan 0 - 1000 mm/
bulan, serta rata – rata kelembaban nisbi 70 - 100 %
(sesuai tabel data curah hujan Balitsa). Luas lahannya
sendiri sebesar 40 Ha. Tanah di Balitsa merupakan
jenis andosol yang mempunyai ciri cokelat kehitaman,
remah, memiliki pori – pori makro dan mikro dengan pH
5,5 – 7.
2. Susunan dan Struktur Organisasi
a. Susunan Organisasi
25
Susunan organisasi di Balitsa yaitu seksi jasa
penelitian yang mempunyai tugas melakukan bahan
penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta
penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian
tanaman sayuran.
Kelompok pejabat fungsional sesuai SK Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari
beberapa kelompok peneliti ( kelti ) yang meliputi:
1) Kelti Hama dan Penyakit,
2) Kelti Pemuliaan dan Plasma Nutfah,
3) Kelti Ekotisiologi, dan
4) Kelti Fisiologi Hasil.
Kegiatan yang dilakukan di Balai Penelitian Tanaman
Sayuran (BALITSA) Lembang, berupa kegiatan penelitian
yang didukung oleh kelompok peneliti pemuliaan dan
plasma nutfah, hama dan penyakit, ekofisiologi dan
fisiologi hasil. Fasilitas penunjang utama yang
tersedia yaitu kebun percobaan seluas 40 Ha,
laboratorium (tanah, hama dan penyakit, kultur
jaringan, teknologi pasca panen) rumah kasa atau kaca,
26
gudang tempat penyimpanan benih dan ruang-ruang
lainnya. Jenis – jenis kegiatan yang dilakukan,
meliputi :
1) Kegiatan Peneliti Pemuliaan dan Plasma Nutfah
Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok peneliti
pemuliaan dan plasma nutfah dengan kegiatan melakukan
perbaikan tanaman yang merupakan salah satu upaya
peningkatan produksi dan keberlanjutannya usahatani
daerah. Balitsa berusaha meminimalkan kendala biotik
dan abiotik yang berpengaruh terhadap kuantitas dan
kualitas hasil melalui pendekatan konvensional dan
bioteknologi.
2) Kegiatan Peneliti Hama dan Penyakit
Kelompok ini menekankan pada suatu teknik
pengendalian hama dan penyakit yang menerapkan suatu
kombinasi dari strategi yang bersandar pada faktor
penyebab kematian alami dan strategi penggunaan
pestisida.
3) Kegiatan Peneliti Ekofisiologi
27
Kelompok ini merancang suatu paket teknologi untuk
menanggulangi masalah yang ada dalam budidaya antara
lain budidaya sayuran di luar musim, budidaya kentang
dataran medium, budidaya di lahan marginal dan
pemupukan berimbang.
4) Kegiatan Peneliti Fisiologi Hasil
Penanganan pra dan pasca panen merupakan rantai
terakhir yang dapat memberikan intensif terhadap
peningkatan kuantitas hasil dan nilai tambah komoditas
sayuran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain
penanganan tanaman segar serta mendapatkan hasil olahan
yang bermutu, teknik pengendalian berbagai komoditas
sayuran, penyimpanan kentang di ruang terang dan teknik
penyimpanan umbi bawang merah untuk memperlambat
pertunasan.
5) Desiminasi Hasil
Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA) dalam
memperkenalkan produk dalam bentuk benih varietas yang
baru dengan mengadakan pekan kentang nasional yang akan
dilakukan setiap 4 tahun sekali dan mengadakan open
28
house kentang yang dilakukan setiap ada penelitian
tentang varietas baru. Tujuan dari pekan kentang
nasional dan open house adalah desiminasi agar hasil –
hasil yang di Balitsa dapat diketahui oleh masyarakat
luas.
b. Struktur Organisasi
29
KEPALA BALAI
Sub Bagian TataUsaha
Seksi JasaSeksi Pelayanan
Kelompok Jabatan
HamaPustakawFisiologiEkofisio
TeknisiLitkayasa
PranataKomputer
Pemuliaan
Keterangan : Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan bahan penyiapan kerjasama, info dandokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman sayuran.
: Garis Wewenang: Garis Tanggung Jawab
Sumber : Balitsa , 2002
Gambar 1. Strukur Organisasi Balai Penelitian Tanaman
Sayuran (BALITSA)
3. Lokasi dan Karakteristik Lahan
Balitsa
Balai Penelitian Tanaman Sayuran beralamatkan di
Jl. Tangkuban Perahu No. 517, Kotak Pos 8413 Lembang -
Bandung 40391.
E-Mail : [email protected]
Telepon : 022-2786245
Fax : 022-2786416
Lokasi Balitsa berada di Desa Cikole, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (± 20
km di sebelah utara kota Bandung). Berdasarkan teori
30
Schmidt-Ferguson, Balitsa memiliki tipe iklim B yaitu
Iklim basah dan temperatur harian 19-24 ºC, temperatur
tanah pada kedalaman 10 cm berkisar 22-23 ºC. Rata-
rata curah hujan tahunan 2.274,41 mm/tahun dengan
jumlah penguapan 43,10 mm pada tahun 2001.
Balitsa memiliki 2 kebun percobaan, yaitu kebun
percobaan Margahayu, Lembang dan kebun percobaan
Subang.
a. Kebun Percobaan Margahayu Lembang
Kebun percobaan Margahayu Lembang mempunyai luas 30
Ha dengan ketinggian 1250 m dpl. Kebun percobaan
Lembang digunakan untuk kegiatan penelitian dan
kegiatan terkait lainnya. Kegiatan penelitian sayuran
tidak seluruhnya dilakukan di lahan kebun tersebut,
tetapi ada pula yang dilakukan di lahan petani,
khususnya untuk kegiatan penelitian sayuran dataran
medium dan dataran rendah.
31
b. Kebun Percobaan Subang
Kebun percobaan Subang mempunyai luas 146,94 Ha.
Tanah yang berjenis Latosol ini sebagian besar ditanami
dengan aneka tanaman tropis plasma nutfah buah-buahan.
Seluas 6 Ha dari luas total kebun percobaan Subang
digunakan untuk kegiatan penelitian sayuran, khususnya
untuk sayuran dataran rendah dan kegiatan penelitian
perbenihan.
Balitsa terbagi menjadi 6 blok yaitu blok A, B, C,
D, E dan F. Masing – masing blok dipimpin oleh mandor
blok yang ditunjuk oleh balai.
Tabel 1. Luas masing – masing blok kebun di BalitsaLembang
No.BlokKebun
Luas Petakan Jumlah Luas
Produktif(Ha)
Efektif
(Ha)
Ha Persen
(%)
1. A 2,650 1,497 4,147 19,522. B 1,150 3,525 4,675 22,023. C 1,424 0,370 1,794 8,454. D 0,150 3,372 3,522 16,595. E 1,150 2,943 4,093 19,286. F 3,000 0 3,000 14,13Total Luas 9,524 11,707 21,231 100,00
32
Sumber Data : Kantor Ka. Sub. Sie. Sarana Lapang Balitsa
Tabel 2. Data total luas Balitsa Lembang
No. Jenis Penggunaan Lahan Jumlah LuasHa Persen (%)
1. Blok kebun (A, B, C, D, dan
F)
21,231
49,98
2. Gedung, laboratorium, dan
rumah kaca
16,914
39,81
3. Jalan kebun dan jalan utama 2,150
5,86
4. Teras dan batas petak 2,188
5,15
Total Luas 42,483
100,00
Sumber Data : Kantor Ka. Sub. Sie. Sarana Lapang Balitsa
Wilayah Balitsa dapat ditempuh dengan perjalanan
kurang lebih satu jam dari kota Bandung, sedangkan dari
kota Lembang sekitar 15 menit. Jenis alat
transportasi yang digunakan yaitu angkutan kota,
angkutan pedesaan, bis, dan ojeg. Transportasi menuju
Balitsa tergolong lancar karena dilalui jalan Kabupaten
antara Bandung dan Subang. Lokasi Balitsa merupakan
tempat yang strategis dimana disamping sebagai lembaga
penelitian tanaman sayuran juga dapat dijadikan sebagai
33
objek wisata bagi pengunjung Gunung Tangkuban Perahu
dan Ciater.
Batas – batas wilayah Balitsa sebagai berikut :
Utara : Perumahan penduduk
Selatan : Desa Cibogo
Timur : Jalan Raya Tangkuban Perahu
Barat : Desa Cibogo dan Gunung Puteri
4. Visi dan Misi
a. Visi :
“Menjadi/menuju lembaga penelitian tanaman sayuran
kelas dunia dalam menciptakan, menghasilkan dan
mengembangkan IPTEK tanaman sayuran yang berorientasi
kepada kebutuhan pengguna.”
b. Misi :
1) Menciptakan, menghasilkan dan mengembangkan IPTEK
Strategis Sayuran sesuai kebutuhan pengguna.
2) Mengembangkan kerjasama Nasional dan
Internasional melalui pola kemitraan menuju
kemandirian Penelitian Tanaman Sayuran.
34
3) Mengembangkan kapasitas dan publisitas serta
pelayanan prima dalam penelitian sayuran.
5. Tugas
Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 74/Kpts/
OT.210/1/2002 tugas pokok dari Balitsa ini sendiri
adalah melaksanakan penelitian tanaman sayuran.
6. Fungsi
Fungsi Balai Penelitian Tanaman Sayuran antara
lain :
a. Pelaksanaan penelitian genetika,
pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah
tanaman sayuran;
b. Pelaksanaan penelitian morfologi,
fisiologis, ekologi, entomologi dan fitopatologi
tanaman sayuran;
c. Pelaksanaan penelitian komponen
teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman
sayuran;
d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan
penalitian tanaman sayuran;
35
e. Penyiapan kerjasama, informasi dan
dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan
hasil penelitian tanaman sayuran; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga balai.
7. Kebijakan dan Program Litbang untuk
Pembangunan Agribisnis Sayuran
a. Berorientasi agribisnis;
b. Menjawab, mengantisipasi dan
menciptakan kebutuhan pengguna;
c. Mengutamakan pelaku agribisnis
dengan posisi tawar paling lemah (petani);
d. Memanfaatkan sumberdaya alam
termasuk sumberdaya hayati Indonesia secara optimal
e. Memanfaatkan peta informasi
global;
f. Mengkomoditaskan kekuatan dan
kelemahan internal dalam memanfaatkan peluang dan
menghadapi ancaman eksternal; dan
36
g. Mengoptimalkan manfaat
jaringan kerjasama nasional dan internasional.
8. Sasaran Program dari Balai
Penelitian Tanaman Sayuran
Sasaran program dari Balitsa adalah :
a. Tersedianya
varietas baru yang produktif, adaptif dan tahan
terhadap hama/penyakit sebagai upaya untuk
mengurangi ketergantungan terhadap varietas impor
serta membuka peluang ekspor;
b. Tersedianya
teknologi produksi dan pengelolaan benih bermutu,
konsep jaminan dan standarisasi mutu sebagai langkah
awal untuk membangun industri benih sayuran
nasional;
c. Tersedianya
teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan efisien
dengan memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal
dan berkelanjutan;
37
d. Tersedianya
teknologi pengendalian hama / penyakit yang berbasis
pada penggunaan musuh alami dan penggunaan pestisida
sintesis seminimal mungkin;
e. Tersedianya
teknologi penanganan segar yang dapat mempertahankan
mutu dan mengembangkan diversifikasi produk untuk
meningkatkan nilai tambah sayuran; dan
f. Tersedianya
data base dan informasi mutakhir sistem dan usaha
sayuran sebagai dasar pengambilan kebijakan
penelitian, perumusan / pemecahan masalah,
penyediaan teknologi secara akurat sesuai kebutuhan
masyarakat.
9. Laboratorium Penguji Balitsa
Balitsa terdapat beberapa laboratorium terakreditas
dan rumah kaca / kasa yang ditetapkan pada tanggal 28
Februari 2004 dan tercatat pada SNI 19 – 17025 – 2000.
Laboratorium ini terbagi atas :
38
a. Ruang Lingkup :
1) Laboratorium Hama dan Penyakit
2) Laboratorium Virologi
3) Laboratorium Tanah
4) Laboratorium Fisiologi Hasil
b. Perluasan Ruang Lingkup :
1) Laboratorium Benih
2) Laboratorium Ekofisiologis
3) Laboratorium Hama dan Penyakit
4) Laboratorium Virologi
Selain itu sarana penelitian lain ada kebun
percobaan milik Balitsa yang berada di tiga tempat
yaitu Lembang yang memiliki luas 40,5 Ha berada di 1250
m dpl, Subang dengan luas 109,7 Ha berada di 100 m dpl,
dan di wilayah Tegal luas 0,5 Ha berada di 1 m dpl.
Sarana penunjang yang ada di Balitsa berupa rumah kasa,
rumah kaca serta perpustakaan dan jaringan informasi.
39
B. Kegiatan Utama Balitsa
Balitsa merupakan lembaga penelitian di bidang
pertanian yang berorientasi agribisnis, sehingga dalam
melakukan kegiatan budidaya tanaman sayuran Balitsa
mempertimbangkan komoditas sayuran yang memiliki
prospek yang baik.
Kegiatan utama di Balitsa adalah kegiatan
penelitian dan usahatani. Kegiatan penelitian ini
meliputi kegiatan penelitian yang didukung oleh
kelompok peneliti pemuliaan dan plasma nutfah, hama dan
penyakit, ekofisiologi dan fisiologi hasil.
Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan utama
yaitu untuk perbaikan tanaman. Perbaikan tanaman ini
dapat meliputi kegiatan menemukan varietas – varietas
baru yang unggul , menemukan teknik pengendalian hama
dan penyakit yang efektif dan ramah lingkungan ,
menemukan suatu teknik budidaya baru serta penanganan
pra dan pasca panen.
40
Kegiatan usahatani yang dilakukan adalah usahatani
tanaman sayuran , antara lain kubis, tomat, kentang,
selada, cabai, paprika, dll. Teknik budidaya
diterapkan pada lahan penanaman sayuran di areal
Balitsa adalah budidaya konvensional dan budidaya ramah
lingkungan seperti LEISA (Low Eksternal Input and Sustainable
Agriculture) dan organik, ada juga teknologi budidaya
sayuran di rumah plastik khususnya untuk tanaman
sayuran paprika dan tomat. Hasil panen ini biasanya
dibeli dengan cara borongan.
C. Budidaya Tanaman Kubis
Budidaya tanaman kubis meliputi kegiatan-kegiatan
pokok : penyiapan bibit di pesemaian, pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan serta kegiatan panen dan pasca
panen:
41
1. Penyiapan bibit di
persemaian
Benih yang digunakan di Balitsa adalah benih kubis
varietas Green Coronet. Benih tanaman kubis varietas ini
berbentuk granule dan berwarna merah kehitaman. Jenis
varietas ini mempunyai bentuk kepala atau krop bulat
dan kompak, teras atau hatinya kecil, daun berukuran
kecil sampai sedang, warna daun hijau muda, mempunyai
beberapa daun luar dan batangnya pendek, umur panen
antara 60 – 120 hari dengan berat antara 1,5 – 5 kg per
krop.
Sebelum disemai, benih kubis direndam dalam air
hangat ( ± 50 ºC ) selama 0,5 jam atau direndam dalam
larutan Previcur N (1 ml/l) selama kira-kira 3 jam.
Perendaman (seed threatment) bertujuan untuk mempercepat
perkecambahan benih dan membebaskan dari serangan
penyakit. Benih kubis di angin - anginkan setelah
direndam lalu disebar rata di tempat persemaian.
Tempat persemaian permanen dibuat dari semen dengan
naungan berupa fiber menghadap arah timur barat dan
42
penegak berupa besi supaya kuat. Ukuran untuk naungan
untuk sendiri sebesar 85 cm sampai 100 cm dan untuk
bedengannya adalah 1 m x 10 m. Media persemaian adalah
campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan
1:1.
Benih yang telah disiapkan disebar lalu ditutup
tipis dalam media persemaian selama kurang lebih 2 – 3
hari. Setelah berumur 7 - 8 hari atau benih telah
berkecambah dipindahkan ke bumbunan daun pisang dengan
media yang sama dan dipelihara di persemaian. Daun
yang digunakan di Balitsa untuk membumbun adalah daun
pisang dan daun kayu besi. Pembumbunan di Balitsa
umumnya menggunakan daun pisang karena harganya lebih
terjangkau dan lebih cepat membusuk. Daun kayu besi
lebih lama dalam pembusukan. Cara pembumbunan
dilakukan dengan memberi media pada cetakan daun pisang
yang dibentuk kecil-kecil, media yang digunakan sama
seperti pada proses persemaian. Bibit yang sudah cukup
umur (tingginya sekitar 4 cm sampai 6 cm) ditanam pada
bumbunan daun pisang atau daun kayu besi dan kemudian
43
ditutup dengan tanah. Media agak ditekan agar tanaman
tidak lepas tetapi juga jangan terlalu kuat karena
dapat merusak akar tanaman. Penyiraman pada persemaian
dilakukan setiap hari di pagi hari. Pembumbunan
bertujuan untuk menjaga agar bibit tidak stres atau
agar tahan terhadap cekaman lingkungan, mengetahui
apakah bibit tersebut terkena hama atau penyakit serta
memudahkan dalam penanaman.
Bibit siap ditanam atau dipindahkan ke lahan
setelah bibit berumur kira - kira 3-4 minggu atau sudah
memiliki 4-5 helai daun. Bibit kubis dipelihara secara
intensif selama di persemaian. Hal ini dilakukan
karena bibit yang sehat selama dipersemaian turut
menentukan keberhasilan pertanaman di lahan. Bibit
yang dibutuhkan dalam sekali tanam ± 25.000 - 35.000
tanaman/Ha.
Penanaman bibit kubis dapat dilakukan pada pagi
atau sore dengan persyaratan bibit tersebut telah
melalui proses pembumbunan dengan kondisi daerah yang
cukup lembab. Penanaman kubis di Balitsa biasanya
44
dilakukan pada pagi hari. Bibit kubis dapat ditanam
dengan jarak 50 x 40 cm atau 60 x 50 cm dan 70 x 50 cm,
namun jarak yang dianjurkan adalah 70 x 50 cm.
Penanaman dengan tumpang sari antara kubis dan tomat
sangat dianjurkan karena dapat mengusir hama Plutella
xylosella pada kubis namun di Balitsa, penanaman dengan
tumpang sari jarang dilakukan karena penanaman dengan
tumpang sari dianggap akan lebih banyak memerlukan
biaya perawatan, sehingga kebanyakan penanaman kubis
dilakukan secara monokultur.
2. Pengolahan Lahan
Pengolahan lahan tanaman kubis di Balitsa
menggunakan 2 macam cara pengolahan lahan, yaitu :
a. Sistem Cangkul
(Maximum Tillage)
Yaitu dengan mengolah secara keseluruhan dengan cara
membalik posisi tanah, tanah di bagian bawah dibalik
menjadi di atas, sebaliknya tanah yang berada di
permukaan menjadi di bawah. Gulma – gulma yang ada
dicangkul dan dibuang sampai ke perakarannya.
45
Keuntungan sistem ini adalah gulma tidak akan cepat
tumbuh lagi dan tanahnya lebih gembur, sedangkan
kerugiannya yaitu lebih banyak memerlukan tenaga
kerja untuk mengolah tanah dan memerlukan waktu yang
lebih lama.
b. Sistem Garit
Laci (Minimum Tillage)
Yaitu tanah di cangkul dengan cara membalik posisi
tanah, tanah bagian atas di benamkan ke dalam tanah.
Hal ini bertujuan agar rumput-rumput yang berada di
permukaan ikut masuk kedalam tanah. Keuntungan
sistem ini adalah menghemat waktu dan tenaga kerja,
sedangkan kerugiannya adalah gulma dapat tumbuh
lebih cepat.
Sistem pengolahan yang lebih banyak dilakukan di
Balitsa adalah dengan menggunakan sistem garit laci
karena sistem ini lebih menghemat waktu dan jumlah
tenaga kerja.
Lahan yang telah diolah perlu diberikan pupuk dasar
baik dengan pupuk kandang maupun pupuk kimia. Pupuk
46
kandang yang diberikan yaitu pupuk kandang kuda dengan
dosis 30 - 40 ton/Ha. Pupuk kandang kuda diberikan
pada setiap lubang tanam dengan dosis 1 kg. Pupuk
kimia diberikan setelah pengaplikasian pupuk kandang.
Pupuk kimia yang dibutuhkan kubis adalah Urea sebanyak
100 kg/Ha, ZA 250 kg/Ha, SP-36 250 kg/Ha dan KCl 200
kg/Ha. Pemupukan dasar dengan pupuk kimia diberikan
dengan dosis 15 gr per tanaman. Lahan yang tercampur
dengan pupuk kandang dibiarkan kurang lebih satu minggu
agar pupuk kandang lebih matang. Kapur pertanian
dolomit diberikan jika kondisi pH tanah masam yaitu
dengan dosis 1,5 ton/Ha. Lahan dibiarkan selama 2
minggu sebelum penanaman.
Pemasangan mulsa dilakukan setelah pengolahan tanah
dan pemberian pupuk dasar selesai. Pemasangan mulsa
sebaiknya dilakukan pada siang hari karena lebih mudah
dalam merentangkan dan memasangnya. Pemasangan mulsa
hitam perak dilakukan supaya pertumbuhan gulma dapat
terhambat, mempermudahkan penyiraman dan menjaga
kelembaban tanah. Setelah pemasangan mulsa dilakukan
47
pelubangan mulsa dengan jarak tanam yang telah
ditentukan.
Pelubangan mulsa ini digunakan alat pelubang mulsa
yang terbuat dari besi berbentuk tabung dengan tuas
untuk memegang alat tersebut. Cara penggunaannya
adalah dengan menekan alat ke dalam mulsa, memutar
pegangan/tuas ke kiri lalu mengangkat tuas, dapat juga
dengan memanfaatkan kaleng susu bekas atau menggunakan
arang.
3. Penanaman
Bibit kubis yang telah berumur 3 – 4 minggu atau
sudah mempunyai 4 – 5 daun dan merupakan bibit yang
siap ditanam di lahan. Bibit ditanam pada tanah yang
sebelumnya telah dilubangi sesuai dengan jarak tanam
yang dikehendaki. Bibit agak ditekan lalu ditutup
dengan tanah. Bibit yang dibumbun dengan daun pisang
dapat langsung ditanam, namun bibit yang dibumbun
dengan daun kayu besi daunnya harus dilepas terlebih
48
dahulu karena daun kayu besi susah membusuk sehingga
kalau tidak dilepas akan menghambat proses pertumbuhan.
4. Pemeliharaan tanaman
kubis
Pemeliharaan tanaman yang paling penting adalah
penyulaman, penyiraman, pemupukan susulan, penyiangan
gulma dan pengendalian hama dan penyakit.
a. Penyulaman
Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit
kubis yang layu atau mati yang dilakukan sampai kubis
berumur 2 minggu. Kematian tanaman mungkin disebabkan
oleh :
1) Kekeringan hingga layu atau mati.
2) Terserang OPT, yaitu terpotongnya batang oleh ulat
tanah.
b. Penyiraman
Kegiatan penyiraman pada tanaman kubis sebaiknya
dilakukan setiap sore hari, akan tetapi apabila
temperatur udara tinggi dan matahari bersinar terik
maka penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi
49
dan sore hari. Hal ini disebabkan karena tanaman kubis
merupakan tanaman yang memerlukan tingkat kelembaban
tinggi. Penyiraman dilakukan dengan cara menyiram
tanaman kubis tersebut sampai benar-benar lembab atau
basah. Daun yang tertutup tanah segera disiram agar
tidak mengganggu proses fotosintesis. Penyiraman ini
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman kubis.
Penyiraman dilakukan tiap hari kira-kira sampai umur
dua minggu, sedangkan di musim kemarau penyiraman
diperjarang dan dihentikan setelah kubis tumbuh normal,
kira-kira berumur tiga minggu.
c. Pemupukan susulan
Kubis merupakan tanaman sayuran yang dianggap
sensitif terhadap kondisi kesuburan tanah dan pemberian
pupuk. Peranan unsur hara untuk tanaman menunjukan
manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan
pertumbuhan, kualitas dan hasil tanaman kubis.
Pemupukan dilakukan melalui tanah dan diberikan
secara bertahap sebanyak 3 kali. Pemupukan pertama
dilakukan ketika tanaman kubis berumur 15 hari setelah
50
tanam. Tujuan pemupukan susulan pertama untuk memacu
pertumbuhan tanaman. Pemupukan kedua dilakukan setelah
kubis berumur 1,5 bulan setelah tanam. Tujuan
pemupukan susulan kedua adalah untuk merangsang
pertumbuhan daun. Pemupukan ketiga dilakukan pada saat
tanaman berumur 70 hari setelah tanam. Tujuan
pemupukan susulan ketiga adalah untuk pembentukan krop.
Pemupukan susulan dapat diberikan pupuk majemuk
atau pupuk tunggal. Pupuk majemuk lebih baik diberikan
pada lahan yang diberi mulsa atau dengan sistem cor, hal
ini karena pupuk majemuk lebih larut dalam air dan
unsur hara makro dan mikro lebih tersedia.
Misalnya untuk melakukan pemupukan susulan dengan
sistem cor dapat dilakukan dengan pemberian pupuk NPK
25 : 7 : 7 sebanyak 2 kg dan ditambahkan pupuk Urea
sebanyak 1 kg dan dihomogenkan dalam 60 liter air.
Pemberian pupuk cor dilakukan dengan satu gelas plastik
akua per tanaman. Setiap 60 liter pupuk dapat memupuk
sebanyak 650 – 700 tanaman kubis.
51
Pupuk majemuk yang digunakan bisasanya pupuk NPK,
Ponska. Sedangkan pupuk tunggal lebih keras atau lebih
lama larut dalam air. Pupuk tunggal yang diberikan
adalah pupuk urea, ZA, SP-36 dan KCl. Jenis pupuk yang
dipakai NPK Mutiara 25, 7, 7 dengan dosis yang
digunakan 20 gr per tanaman. Setiap pemupukan susulan
dosisnya sama, yaitu 20 gr per tanaman. Pupuk
dibenamkan diantara tanaman kubis, lalu tanaman segera
disiram.
d. Penyiangan
Penyiangan dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan
gulma yang ada di sekitar tanaman kubis. Gulma yang
tumbuh disekitar kubis sangat merugikan bagi tanaman
tersebut bila tidak disiangi karena menjadi pesaing
tanaman pokok dalam memperoleh unsur hara yang
dibutuhkan tanaman, pesaing air, pesaing sinar
matahari, menjadi inang bagi hama dan penyakit.
Penyiangan dilakukan selama 2 minggu sekali dengan cara
mencabut langsung gulma yang ada dengan tangan.
e. Pengendalian hama dan penyakit
52
Pestisida terdiri dari insektisida dan fungisida
selain itu juga digunakan perekat yang berfungsi
sebagai perekat pestisida pada tanaman kubis.
Insektisida yang digunakan antara lain adalah Sherpa
dan Curracorn sedangkan fungisida yang digunakan adalah
Antracol. PPC ( Pupuk Pelengkap Cair ) yang digunakan
Supergrow sebagai pupuk daun. Interval penyemprotan 1-2
kali seminggu dan disesuaikan dengan kondisi tanaman
yang terserang hama dan penyakit, selain itu musim juga
mempengaruhi penyemprotan pestisida. Pada musim
kemarau penyemprotan pestisida dilakukan 1 kali dalam
seminggu, sedangkan pada musim hujan penyemprotan
pestisida dilakukan 2 minggu sekali.
5. Kegiatan Panen dan
Pasca Panen
Panen adalah suatu tindakan pengambilan hasil dari
tanaman dengan waktu tertentu dan setiap tanaman
berbeda-beda baik waktu maupun cara panennya. Kubis
dapat dipanen setelah kropnya besar, penuh dan padat.
Krop akan pecah dan kadang-kadang busuk apabila panen
53
terlambat. Panen kubis biasanya dilakukan 75-90 hari
atau sesuai varietas tanaman kubis. Berat dari kubis
juga berbeda-beda sesuai varietasnya. Panen terbaik
kubis untuk luas lahan sebesar 1 Ha dapat mencapai 40-
50 ton/Ha. Umumnya, di Balitsa menggunakan sistem
borongan untuk penjualan ke bandar atau pedagang
pengumpul karena sistem ini lebih mudah dan lebih
menguntungkan dari pada dengan menimbang hasil kubis
per kilogramnya.
Ciri-ciri kemasakan kubis adalah:
a. Krop kubis mengeras, diketahui dengan cara menekan
krop kubis.
b. Daun berwarna hijau mengkilap.
c. Daun paling luar sudah layu.
d. Krop kubis telah terlihat besar.
Pemetikan yang kurang baik akan menimbulkan
kerusakan mekanis yang menyebabkan krop kubis
terinfeksi patogen sehingga mudah pembusukan.
Langkah-langkah dalam panen kubis adalah :
54
a. Memotong batang kubis dengan menggunakan pisau
yang tajam dan bersih. Pemotongan dilakukan pada
bagian pangkal batang kubis dengan disertakan 4-5
lembar daun luar agar krop tidak mudah rusak.
b. Daun yang rusak dibuang sampai krop benar – benar
terlihat bagus.
c. Pemetikan dimulai dengan kubis yang sehat baru
kemudian dilakukan pemetikan pada kubis yang telah
terkena infeksi patogen.
Pasca panen adalah penanganan produk pertanian
dari setelah panen sampai ke konsumen, sehingga
kualitasnya tetap bermutu tinggi. Dua hal penting
dalam penanganan pasca panen, yaitu:
a. Sortasi (Pemilihan Mutu ) dan Gradding
(Penggolongan)
Sortasi bertujuan untuk memisahkan krop kubis yang
baik dan bermutu dari kubis yang kurang baik atau
rusak seperti retak, lecet dan kerusakan lainnya.
Sortasi di Balitsa dilakukan dengan cara
memisahkan kubis yang kualitasnya bagus dengan
55
kubis yang kurang bagus. Kubis yang
kualitasnya bagus di jual ke supermarket
sementara kubis yang kualitasnya kurang bagus
dijual ke pasar lokal.
Setelah dilakukan sortasi yaitu dilakukan gradding
(penggolongan). Gradding bertujuan untuk
menggolongkan kubis ke dalam mutu sesuai kelasnya
dan juga memudahkan dalam distribusi pemasaran.
Kubis kelas I yaitu kubis yang benar – benar
bagus, tidak lecet dan tidak terserang patogen serta
memiliki ukuran yang seragam. Kubis kelas ini akan
dipasarkan ke Supermarket dan dikirim ke luar
daerah.
Kubis kelas II yaitu kubis yang ukurannya tidak
seragam. Kubis kelas II ini dipasarkan ke pasar
tradisional.
b. Pengemasan
Pengemasan dilakukan dengan plastik Polyethylen dan
dalam pengangkutan, kemasan perlu dimasukkan dalam
kotak atau peti kayu dengan kapasitas 25-30 kg per
56
peti. Pengemasan bertujuan untuk memperkecil resiko
kerusakan akibat gesekan atau benturan selama
transportasi. Hal yang harus diperhatikan dalam
pengemasan adalah kapasitas kemasan dan kubis
disusun dalam kemasan dengan cara ditumpuk dengan
rapi.
Pemasaran kubis di Balitsa dapat melalui beberapa
tipe rantai pemasaran, yaitu:
1. Petani produsen – konsumen
2. Petani produsen – pengecer – konsumen.
3. Petani produsen – tengkulak – pengecer – konsumen.
4. Petani produsen – tengkulak – pedagang besar –
pengecer – konsumen.
Saluran rantai 1, 2 dan 3 merupakan saluran
pemasaran lokal, yaitu pemasaran di pasar-pasar lokal
yang ada di daerah pusat produksi atau untuk memenuhi
permintaan konsumen sekitar daerah produksi, sedangkan
saluran 4 merupakan saluran pemasaran untuk memenuhi
permintaan konsumen di luar daerah produksi. Kegiatan
57
masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam
pemasaran kubis di antaranya:
1. Tengkulak/pedagang desa
Lembaga pemasaran ini melakukan pembelian hasil
panen dari petani dan menjualnya kembali ke pedagang,
pengumpul atau pedagang pengecer, apabila jual beli
dengan sistem borongan atau timbangan maka kegiatan
panen menjadi tanggungan petani.
2. Pedagang besar
Pedagang besar melakukan pembelian kubis dalam
jumlah yang banyak dari tengkulak dan menjualnya
kembali ke pedagang pengecer dalam jumlah yang lebih
sedikit.
3. Pengecer
Pengecer melakukan pembelian kubis dari pedagang
besar dan menjualnya kembali kepada konsumen.
Penanganan pasca panen meningkatkan mutu dan harga
jual kubis di pasar. Untuk itu kegiatan pasca panen58
harus dilakukan dengan baik agar kualitas kubis tetap
segar sampai ke tangan konsumen.
D. Hama dan Penyakit Tanaman Kubis
1. Hama Tanaman Kubis
a. Hama – hama utama yang menyerang tanaman kubis
antara lain:
1) Ulat daun kubis ( Plutella xylostella L. )
Hama ulat daun kubis dilaporkan berasal dari
daerah Mediterranean di Eropa Selatan, yang merupakan
sumber berbagai jenis brasica. Hama ini tersebar luas
di areal yang ditanami brasica, mulai dari daerah
Amerika Utara dan Selatan, Afrika, China, India,
Jepang, Asia Tenggara termasuk Indonesia, Selandia
Baru, dan Australia. Telur Plutella kecil berukuran
kira-kira panjang 0,49 cm dan lebar 0,26 cm, warnanya
kuning atau putih kehijauan dan berbentuk oval. Di
lapangan, serangga betina meletakkan telur di
permukaan bawah daun tanaman inang secara tunggal
atau berkelompok. Tetapi, di laboratorium bila
59
ngengat (dewasa) betina dihadapkan pada tanaman muda
maka mereka bertelur pada bagian batang.
Stadium telur antara 3-6 hari. Larva atau ulat
mempunyai pertumbuhan maksimum dengan ukuran panjang
tubuh mencapai 10-12 mm. Prepupa berlangsung selama
lebih kurang 24 jam, setelah itu memasuki stadium
pupa. Panjang pupa bervariasi sekitar 4,5-7,0 mm dan
lama umur pupa 5-15 hari. Serangga dewasa atau
ngengat berbentuk ramping, berwarna coklat-kelabu.
Sayap depan bagian dorsal memiliki corak khas seperti
berlian, sehingga hama ini terkenal dengan nama
ngengat punggung berlian (diamondback moth). Nama
lain dari serangga tersebut adalah ngengat tritip dan
ngengat kubis (cabbage moth).
Ulat Plutella menyerang daun sehingga daun
berlubang-lubang dan terdapat bercak-bercak putih
seperti jendela yang menerawang dan tinggal urat-urat
daunnya saja, umumnya menyerang tanaman kubis yang
masih muda, tetapi kadang-kadang merusak tanaman yang
sedang membentuk krop.
60
Hama P. xylostella juga dapat menyerang tanaman kubis
yang sedang membentuk krop sampai panen. Keadaan ini
dapat terjadi jika :
a) Populasi musuh alaminya, yaitu parasitoid D.
semiclausum rendah.
b) Tidak ada hama pesaing yang penting, yaitu ulat
krop kubis (C. binotalis).
c) Hama P. xylostella telah resisten terhadap
insektisida yang digunakan.
d) Populasi larva P. xylostella sangat tinggi.
Pengendaliannya bisa dengan mekanik, kultur
teknik, pengendalian biologi dan pengendalian kimia.
Pengendalian yang sering dilakukan adalah
pengendalian dengan cara kimia. Pestisida yang
digunakan adalah Agrimec 18 EC dengan dosis 0,5-1
ml/liter air dan perekat seperti ABSH sebanyak 2
ml / liter air. Insektisida berperan sebagai
pemberantas ulat dan perekat sebagai perekat
pestisida dengan daun. Penyemprotan dilakukan
61
seminggu sekali apabila tanaman terserang hama sangat
berat dan tanaman sudah dewasa.
2) Ulat krop kubis ( Crocidolomia binotalis Zell. )
Ulat jantung (Crocidolomia binotalis) merupakan hama
yang penting pada tanaman kubis. Hama ini
merupakan ancaman yang serius bagi petani.
Serangan C. binotalis pada tanaman kubis sampai
sekarang belum dapat diatasi secara memuaskan,
meskipun pengendalian kimia telah dilakukan secara
intensif. Salah satu agen pengendali hayati
yang mempunyai potensi tinggi untuk mengendalikan
hama ulat jantung kubis adalah nematoda
entomopatogen Steinernema carpocapsae.
Ulat krop / jantung (Crocidolomia binotalis) sering
menyerang titik tumbuh sehingga disebut sebagai ulat
jantung kubis. Ulatnya kecil, berwarna hijau, lebih
besar dari ulat trip, jika sudah besar ada garis –
garis coklat, jika diganggu agak malas untuk
bergerak. Berbeda dengan ulat trip yang telurnya
diletakkan secara menyebar, ulat jantung kubis
62
meletakkan telurnya dalam satu kelompok. Kerusakan
ringan yang disebabkan ulat krop akan berakibat
menurunkan kualitas tanaman kubis, sedangkan
kerusakan berat dapat menggagalkan panen sehingga
kubis tidak laku terjual.
Pengendaliannya dengan menggunakan Sherpa yang
berbahan aktif Sipermetrin 50g/l dengan dosis 1,5-
2 cc/liter air dan bisa juga menggunakan Curracron
yang berbahan aktif Propenofos dengan konsentrasi 1,5-
2 cc/liter air.
b. Hama – hama sekunder tanaman kubis , meliputi :
1) Ulat grayak ( Spodoptera litura F. )
Ulat grayak muncul pada malam hari dan memakan
daun-daun muda. Hal ini menyebabkan daun menjadi
berlubang dan rusak. Pada siang hari ulat ini
bersembunyi di dalam tanah yang dangkal untuk
menghindari kekeringan. Ulat grayak dapat
dikendalikan dengan menggunakan Curracron yang
berbahan aktif Propenofos dengan konsentrasi 1,5-2
cc/liter air.
63
2) Ulat tanah (Agrotis ipsilon Hufn)
Ulat tanah membuat lubang kecil dengan jalan
memakan jaringan daun. Pada siang hari bersembunyi
dipermukaan tanah. Pada senja dan malam hari ulat
tanah muncul ke permukaan tanah dan memotong pangkal
batang dan titik tumbuh sehingga tanaman muda rebah
dan pada siang hari tampak layu. Daur hidup A. ipsilon
dari telur sampai dewasa sekitar 36-42 hari. Lamanya
daur hidup A. ipsilon tergantung pada tinggi rendahnya
suhu udara, semakin rendah suhu udara semakin lama
daur hidupnya dan sebaliknya. Pengendalian :
menyemprotkan insektisida Regent 1-1,5 ml/liter air.
3) Kutu daun (Aphis brassicae)
Kutu daun hidup berkelompok dibawah daun berwarna
hijau diliputi semacam tepung berlilin. Kutu daun
menyerang tanaman dengan menghisap cairan selnya,
sehingga menyebabkan daun menguning dan berbintik-
bintik tampak kotor. Menyerang hebat dimusim
kemarau. Pengendalian: menyemprotkan insektisida
Orthene 75 SP atau Hostathion 40 EC 1-2 cc/liter air.
64
4) Bangsa siput
Bangsa siput banyak jenisnya, yang menjadi hama
tanaman kubis yaitu:
a) Achatina fulica Fer. yaitu siput yang mempunyai
cangkang atau rumah, dikenal dengan bekicot.
b) Vaginula bleekeri Keferst. yaitu siput yang tidak
bercangkang, warna tubuhnya kecoklatan.
c) Parmarion pupillarist Humb. yaitu siput yang tidak
bercangkang akan tetapi dicirikan adanya chitine
yang mendatar pada bagian punggungnya. Tubuh
mempunyai warna coklat kekuningan.
Hama siput banyak merusak tanaman kubis di
persemaian dan dilahan penanaman, terutama terhadap
tanaman baru yang dipindah tanam. Hama siput
menyerang bagian daun. Pengendalian hama siput yaitu
dengan menyemprotkan helisida atau aplikasi siputox
dan secara mekanis dengan cara mengambil dan
dikumpulkan untuk dimusnahkan atau untuk pakan
ternak.
65
2. Penyakit Tanaman Kubis
Penyakit yang menyerang tanaman kubis, antara lain :
a. Penyakit akar bengkak ( Plasmodiophora brassicae Wor. )
Penyakit akar bengkak ( akar gada atau dalam
bahasa Inggris clubroot ) untuk pertama kali diketahui di
Indonesia pada tahun 1975. Penyakit bengkak akar
disebabkan infeksi dari cendawan Plasmodiophora brassicae.
Penyakit didukung oleh tanah yang masam, temperatur
tinggi dan tanah yang selalu basah dapat mempercepat
berkembangnya spora. Pembengkakan timbul pada akar
tanaman kubis menyerupai bisul-bisul dan dapat
menyebabkan akar membusuk. Pertumbuhan menjadi
terhambat karena akar tidak dapat menyerap unsur hara
secara sempurna dan akhirnya tanaman tumbuh kerdil,
ukuran krop kecil, tanaman cepat layu dan menyebabkan
tanaman menjadi mati.
Penyebab penyakit ini dapat tersebar setempat oleh
air drainase, alat-alat pertanian, tanah yang tertiup
angin, hewan, dan bibit-bibit. Menurut Suryaningsih
(1981), pupuk kandang dapat menyebarkan penyakit ini,
66
karena sisa-sisa kubis biasanya dipakai petani untuk
makanan ternak. Jamur ini dapat bertahan hidup dalam
saluran pencernaan ternak, sehingga pupuk kandang
terinfeksi. Pupuk Urea, SP-36, dan KCl yang diberikan
bersama-sama akan menekan penyakit, sebaliknya
pemberian Boron akan meningkatkan serangan penyakit
ini. Penanaman kubis secara terus menerus pada lahan
yang sama juga akan meningkatkan populasi Plasmodiophora
sp.
Pengendalian penyakit ini yaitu pemberian kapur
dolomit sebanyak 1,5 ton/Ha dan juga dapat diatasi
dengan pemberian pupuk kandang dengan dosis yang lebih
banyak. Tanaman segera dicabut dan dimusnahkan apabila
terdapat serangan bengkak akar yang parah pada tanaman
muda,
b. Busuk hitam (Xantomonas campestris)
Penyakit busuk hitam disebabkan oleh bakteri
Xantomonas campestris. Penyakit busuk hitam berjangkit
pada tanaman kubis dengan kondisi lingkungan hangat dan
kelembaban udara tinggi. Gejala khas pada kubis dewasa
67
yang terserang X.campestris adalah adanya bercak kuning
yang menyerupai huruf V di sepanjang pinggir daun
mengarah ke tulang daun. Penyaluran air yang melewati
bagian yang bergejala terhambat, sehingga tulang daun
busuk dan berwarna hitam. Penyakit ini dapat
menyebabkan busuk kering, yang dalam keadaan lembab
karena serangan jasad sekunder, dapat berubah menjadi
busuk basah yang mengeluarkan bau tidak enak.
Penanggulangan penyakit busuk hitam dimulai dari
benih. Perawatan benih dapat dilakukan dengan cara
merendam biji dalam air hangat selama 3 jam.
c. Busuk basah/busuk lunak
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia carotovora
pv. tanaman kubis yang terserang E. carotovora
memperlihatkan gejala busuk berwarna hitam pada daun-
daun pembungkus krop. Pembusukan juga terjadi pada
pangkal krop, sehingga krop mudah dilepas dari batang
kubis. Bagian yang terinfeksi mula-mula terjadi bercak
kebasahan. bercak membesar dan mengendap (melekuk),
bentuknya tidak teratur, berwarna coklat tua kehitaman.
68
Kelembaban yang tinggi menyebabkan jaringan yang sakit
tampak kebasahan, berwarna krem atau kecoklatan dan
tampak agar berbutir-butir halus dan di sekitar bagian
yang sakit terjadi pembentukan pigmen coklat tua atau
hitam.
Cara penanggulangan yang efektif adalah mencegah
terjadinya pelukaan dan mencegah serangan hama. Krop
yang terserang, daun – daun yang terinfeksi dibuang dan
dimusnahkan serta batang bekas potongan diolesi Kloroks.
Tempat penyimpanan yang bersuhu rendah sangat baik
untuk mencegah terjadinya perkembangan penyakit.
Kegiatan pemeliharaan tanaman kubis di Balitsa
dilakukan sangat intensif. Penyulaman, penyiraman,
penyiangan, pemupukan susulan dan pengendalian hama dan
penyakit dilakukan dengan rutin sesuai dengan
literatur. Kegiatan pemupukan susulan diberikan dengan
jenis pupuk yang berbeda tiap petani. Perbedaan ini
karena petani mempunyai pupuk andalan masing-masing dan
juga faktor ekonomi juga mempengaruhi pemakaian jenis
pupuk. Dosis pupuk yang diberikan pun kadang berbeda,
69
namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh dan masih
dalam lingkup yang wajar, maksudnya aplikasi pemupukan
tidak berbeda jauh dengan literatur.
Pengantisipasian resiko gagal panen di Balitsa
dilakukan dengan teknik pengendalian hama secara
terpadu yaitu teknik pengendalian dengan melihat
terlebih dahulu apakah ada serangan, jika terdapat
serangan dan sudah melebihi ambang kematian maka
dilakukan pengendalian dengan menyemprotkan pestisida
pada tanaman kubis. Pengantisipasian serangan penyakit
yaitu lebih diutamakan adalah kegiatan pencegahan
dengan perlakuan benih dan pemeliharaan bibit.
E. Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Kubis
Pengendalian hama dan penyakit tanaman erat
kaitannya dengan penggunaan pestisida. Manajemen
pengendalian hama dan penyakit yang dijalankan di Balai
Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, Bandung meliputi:
1. Perencanaan70
Perencanaan yaitu tindakan menentukan sasaran dan
arah tindakan yang akan dilaksanakan. Pada lahan
percobaan dan usaha budidaya di Balai Penelitian
Tanaman Sayuran Lembang, perencanaan dalam manajemen
pengendalian hama dan penyakit kubis meliputi
kegiatan :
a. Pemilihan Varietas
Pemilihan varietas merupakan kegiatan perencanaan
yang penting. Kesalahan dalam pemilihan varietas
sangat berakibat fatal. Komoditas sayuran yang dipilih
untuk diusahakan adalah sayuran dengan varietas unggul
yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit.
Kubis yang dibudidayakan di Balitsa adalah kubis
varietas Green coronet karena jenis kubis ini yang paling
cocok ditanam di dataran tinggi serta lebih tahan
terhadap serangan hama dan penyakit.
b. Pengadaan Benih
Benih yang digunakan di Balitsa yaitu benih impor
dari Taiwan karena Indonesia belum dapat menghasilkan
benih yang unggul. Iklim di Indonesia kurang cocok
71
untuk pengadaan benih. Iklim yang cocok untuk
pengadaan benih kubis yaitu negara dengan iklim Sub-
Tropis dengan pemanasan yang tidak terus –
menerus.
c. Pemilihan Lokasi dan Waktu Tanam
Pemilihan lokasi untuk usaha budidaya kubis
terutama didasarkan pada lingkungan yang cocok
(agroklimat). Varietas dataran tinggi dapat tumbuh
baik pada ketinggian 1000-2000 m dpl, suhu udara 10-
240C dengan suhu optimum 170C, kelembaban 80%.
Berdasarkan data iklim di Balai Penelitian Tanaman
Sayuran Lembang, suhu dan ketinggian Balitsa menunjang
bagi pertumbuhan tanaman kubis dan sayuran lainnya.
Ketinggian daerah Balitsa kurang lebih 1200 m dpl,
dengan curah hujan 0 - 1000 mm/ bulan, serta rata –
rata kelembaban nisbi 70 - 100 %.
Waktu tanam kubis sangat berpengaruh terhadap
intensitas serangan hama dan penyakit. Tanaman kubis
lebih baik ditanam pada saat musim hujan karena pada
72
musim hujan intensitas serangan hama dan penyakit
cenderung menurun karena terhambat oleh air hujan.
2. Pengorganisasian
Pembagian kerja adalah hal yang paling mutlak dalam
suatu organisasi. Balai Penelitian Tanaman Sayuran
memiliki struktur organisasi kebun percobaan yang
dipimpin oleh kepala kebun atau kepala mandor yang
dibantu oleh beberapa seksi yang ada dibawahnya.
Kepala kebun atau kepala mandor membawahi tujuh blok
kebun percobaan, yang masing – masing blok dipimpin
oleh mandor.
Tiap bagian atau seksi yang ada di kebun percobaan
Balitsa harus dikoordinasikan dengan kepala kebun.
Koordinasi dilakukan agar tiap bagian tidak berjalan
sendiri. Berjalannya organisasi di Balai Penelitian
Tanaman Sayuran tidak dapat tercapai jika tidak ada
pengorganisasian dan pengawasan yang baik.
73
Gambar 2. Struktur organisasi kebun percobaan Balitsa
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit kubis
dimulai dari awal tanam sampai setelah tanam yaitu
mulai dari penyiapan bibit dan lahan, penanaman,
pemeliharaan dan kegiatan panen dan pasca panen.
Bibit yang akan digunakan terlebih dahulu direndam
dengan larutan Previcur N. untuk mencegah serangan
penyakit. Media pesemaian juga harus steril dan tidak
masam karena kondisi media yang masam dapat memicu
74
timbulnya penyakit bengkak akar. Penyemprotan
insektisida segera dilakukan apabila terlihat gejala
serangan hama agar serangan hama tidak meluas dan
apabila terlihat gejala serangan penyakit maka tanaman
yang terserang penyakit segera dicabut dan dimusnahkan.
Hal ini dikarenakan cendawan penyebab penyakit dapat
bertahan lebih lama dalam tanaman meskipun gejala
serangannya sudah tidak terlihat, sehingga kalau tidak
dicabut dan dimusnahkan maka dapat terbawa ke lapang.
Pengolahan lahan dilakukan dengan membuang rumput
dan tanaman sebelumnya sampai bersih karena rumput –
rumput dan tanaman tua merupakan sarang hama. Pemberian
kapur pada tanah yang masam untuk mencegah penyakit
bengkak akar.
Kegiatan penanaman kubis dilakukan saat kubis telah
mencapai umur tanam yang pas, yaitu berumur 3 – 4
minggu. Hal ini dilakukan agar tanaman cukup kuat
dalam menghadapi kondisi lingkungan yang kurang baik
dan terutama dalam menahan serangan hama dan penyakit
yang menyerang.
75
Pemberian pupuk susulan dalam penanaman kubis juga
dapat menghambat serangan hama dan penyakit. Pupuk
susulan ini diberikan sebanyak 3 kali yaitu pada saat
tanaman berumur 15 hari setelah tanam, 1,5 bulan
setelah tanam dan 70 hari setelah tanam.
Panen dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi
luka pada kubis yang dapat memicu penyakit busuk lunak.
Pasca panen dilakukan dengan mengemas kubis dengan rapi
agar tidak terjadi benturan dan pelukaan.
4. Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan di Balai Peneitian
Tanaman Sayuran Lembang Bandung yaitu pangawasan yang
dilakukan di lapang. Pelaksanaan pengawasan di lapang
dilakukan dengan cara mengamati secara berkala kondisi
pertanaman kubis. Apabila terlihat ada serangan hama
dan penyakit serta sudah melewati batas amabang, maka
segera dilakukan tindakan pengendalian. Pengawasan ini
dilakukan oleh mandor dan pekerja – pekerja yang ada di
Balitsa. Mandor mengawasi setiap kegiatan petani di
76
kebun yang ada di bawah binaan Balai Penelitian Tanaman
Sayuran.
5. Evaluasi
Kegiatan evaluasi yang dilakukan di Balitsa yaitu
dengan membandingkan kualitas dan kuantitas hasil yang
diperoleh dari hasil usahatani musim sekarang dengan
hasil usahatani musim sebelumnya. Apabila terdapat
penurunan kualitas dan kuantitas hasil, maka dilakukan
pengevaluasian terhadap kegiatan usahatani yang sudah
dilakukan dengan cara mengevaluasi penyimpangan-
penyimpangan yang tejadi yang menyebabkan penurunan
kualitas dan kuantitas hasil untuk perbaikan usahatani
di musim selanjutnya.
Mandor berkoordinasi dengan pekerja lapang dan
kepala Litbang untuk mendata penyimpangan – penyimpang
yang terjadi agar penyimpangan tersebut tidak terjadi
di masa mendatang.
1. Manajemen Pengendalian Hama Kubis
Petani pada umumnya mengatasi gangguan ulat kubis
dengan menggunakan insektisida kimia sintetik.
77
Ditinjau dari segi penekanan populasi hama,
pengendalian secara kimiawi dengan insektisida memang
cepat dirasakan hasilnya, terutama pada areal yang
luas. Tetapi, selain memberikan keuntungan ternyata
penggunaan insektisida yang serampangan atau tidak
bijaksana dapat menimbulkan dampak yang tidak
diinginkan. Hasil survai pada petani sayuran
menyebutkan bahwa petani mengeluarkan 50% biaya
produksi untuk pengendalian secara kimiawi dengan
mencampur berbagai macam pestisida, karena belum
diketahui bagaimana penggunaan pestisida yang tepat.
a. Hama Pluttela xylostella sp.
Pengendalian ulat kubis dapat dilakukan dengan cara
mekanis, kimiawi dengan insektisida kimia sintetik
selektif maupun insektisida nabati, pola bercocok tanam
(tumpangsari, rotasi, irigasi, penanaman yang bersih),
penggunaan tanaman tahan, pengendalian hayati
menggunakan predator, parasitoid (misalnya dengan
Diadegma semiclausum Helen, Cotesia plutellae Kurdj., dll.),
78
patogen (misalnya pemakaian bakteri B. thuringiensis, jamur
Beauveria bassiana, dsb.) serta aplikasi program PHT.
Manajemen pengendalian yang dapat dilakukan antara
lain:
1) Saat awal tanam
a) Perencanaan musim tanam.
Lebih baik untuk menanam kubis dan brasica lain
pada musim hujan, karena populasi hama tersebut
dapat dihambat oleh curah hujan.
Apabila tersedia, dapat digunakan irigasi untuk
mengurangi populasi ulat daun kubis, apabila
pengairan dilaksanakan pada petang hari, dapat
membatasi aktivitas ngengat.
b) Pesemaian.
Tempat pembibitan harus jauh dari areal tanaman
yang sudah tumbuh besar. Sebaiknya pesemaian
atau bibit harus bebas dari hama ini sebelum
79
dipindah ke lapangan. Serangan ulat daun kubis
di lapangan diawali dari pesemaian yang
terinfestasi dengan hama tersebut.
2) Saat tanam
a) Penanaman
Sebaiknya tidak melakukan penanaman berkali-kali
pada areal sama, karena tanaman yang lebih tua
dapat menjadi sarang hama bagi tanaman baru.
c) Tanaman perangkap.
Tanaman brasica tertentu seperti caisin lebih
peka dapat ditanam sebagai border untuk dijadikan
tanaman perangkap, dengan maksud agar hama ulat
daun kubis terfokus pada tanaman perangkap.
d) Tumpang sari.
Penanaman kubis secara tumpang sari bersamaan
dengan tanaman yang tidak disukai hama ulat daun
kubis dapat mengurangi serangannya. Misalnya
80
tumpang sari kubis kubis dengan tanaman tomat
atau bawang daun.
3) Setelah tanam
a) Monitoring
Selama menanam kubis petani perlu melakukan
pemantauan atau monitoring hama dengan melakukan
pengamatan mingguan. Apabila hama mencapai 5
larva per 10 tanaman (Ambang Ekonomi = AE) atau
lebih, maka dapat dilakukan dengan menyemprot
tanaman menggunakan insektisida kimia atau
bioinsektisida, untuk menekan agar hama kembali
berada di bawah AE yang tidak merugikan secara
ekonomi.
b) Penggunaan agen hayati dan pengendalian secara
mekanis
Hama tersebut memiliki musuh alami berupa
predator (Paederus sp., Harpalus sp.), parasitoid
(Diadegma semiclausum, Cotesia plutellae), dan patogen
(Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana) yang bila
diaplikasikan dapat menekan populasi dan
81
serangannya. Pengendalain secara mekanis dapat
dilakukan dengan mengumpulkan hama yang
bersangkutan, memasukkan ke dalam kantung
plastik, dan memusnahkannya. Namun untuk areal
luas perlu pertimbangan tenaga kerja dan waktu.
c) Penggunaan insektisida
Aplikasi ini dilaksanakan setelah hama tersebut
mencapai atau melewati ambang ekonomi, dengan
memilih insektisida kimia selektif yang efektif
tetapi mudah terurai, atau penggunaan
insektisida biologi seperti pengguanaan lengkuas
dan sereh wangi.
b. Hama Croccidolomia binotalis
Pengendalian dapat dilakukan dengan :
1) Awal tanam
a) Melakukan perencanaan penanaman. Menanam kubis
pada saat musim hujan, karena pada musim hujan
populasi hama dapat terhambat.
b) Membuat draenase atau saluran air.
82
2) Saat tanam
a) Menanam kubis yang telah cukup umur
b) Tumpang sari caisin dan kubis, sawi dan kubis
atau kubis dengan tomat.
3) Setelah tanam
a) Pengamatan mingguan (Monitoring).
b) Melakukan pemupukan susulan.
c) Pemanfaatan dan pelestarian musuh alami, yaitu
nematoda entomopatogen Steinernema carpocapsae.
d) Pengendalian dengan menggunakan pestisida
nabati dengan pemanfaatan sumber daya alam di
sekitar.
e) Aplikasi insektisida sintetik yang diizinkan,
bila dijumpai populasi kelompok telur 3
kelompok telur / 10 tanaman.
2. Manajemen Pengendalian Penyakit Kubis
a. Pengendalian Plasmodiophora brassicae meliputi :
1) Awal tanam
a) Menanam varietas unggul
83
b) Perendaman benih dengan air hangat selama 3 jam
dan dengan Previcur N. selama 0,5 jam.
c) Sterilisasi media tanam.
d) Tanah persemaian harus bebas pathogen penyebab
penyakit akar bengkak. Hal ini dapat dilakukan
dengan menggunakan tanah lapisan bawah (minimal
40 cm).
2) Saat tanam
1) Menanan kubis yang telah cukup umur.
2) Pemberian pupuk.
3) Setelah tanam
1) Pengamatan rutin
2) Pemanfaatan Agens Hayati Trichoderma sp. dan
Gliocladium sp. pada persemaian dan pertanaman.
3) Penyiraman tanaman di persemaian dengan
menggunakan air bebas pathogen misalnya air air
sumur, atau air hujan yang belum jatuh ke tanah
pertanian
4) Pemberian pupuk susulan.
84
5) Pengapuran tanah dengan kapur pertanian atau
Dolomit di lahan kubis sebanyak 1,5 ton/ha.
2. Pengendalian Penyakit Busuk Hitam (Xantomonas
campestris)
Taktik manajemen utama yang bisa digunakan untuk
mengendalikan penyakit busuk hitam ada 2 macam,
yaitu :
a. Memperlakukan bibit dengan air panas sehingga anda
memiliki bibit bebas penyakit
Perlakuan dengan air panas adalah teknik yang
dirancang untuk menghasilkan benih yang bebas dari
penyakit sebelum ditanam. Perlakuan ini efektif
karena penyakit penyakit busuk hitam lebih
sensitif terhadap air panas dibandingkan dengan
benihnya, karena itu mati sedangkan benih tetap
produktif.
b. Tanam bibit yang bebas penyakit melalui isolasi
dari tanaman yang terinfeksi.
Pengendalian tanaman kubis dari penyakit busuk
hitam ini, dapat dilakukan dengan :
85
a. Awal tanam
1) Menanam varietas unggul
2) Perendaman benih dengan air hangat selama 3 jam
dan dengan Previcur N. selama 0,5 jam.
3) Menanam tanaman pada tempat-tempat yang
tanahnya bebas dari genangan.
b. Saat tanam
1) Menanam kubis yang telah cukup umur
2) Rotasi atau selang-seling dengan tanaman yang
bukan brassica selama mungkin.
c. Setelah tanam
1) Pengamatan mingguan
2) Menyirami tanaman dengan secukupnya saja, tidak
perlu terlalu banyak.
3) Menghindari bekerja di lahan pada saat tanaman
basah agar kerusakan yang membantu infeksi
penyakit busuk hitam tidak terjadi.
4) Melakukan manajemen pengendalian hama serangga
terpadu untuk pengendalian serangga yang baik
untuk mengurangi penyebaran penyakit busuk
86
hitam. Serangga menghasilkan luka yang
memungkinkan bakteri menyerang tanaman.
F. Analisis Usahatani Kubis
Analisis ekonomi dihitung untuk mengetahui
kedudukan usaha yang dijalankan. Analisis usaha dapat
digunakan untuk perhitungan dan penentuan tindakan
untuk memperbaiki dan meningkatkan keuntungan yang
maksimal dan meminimalkan tingkat kerugian yang
dihadapi.
Usaha agribisnis dikatakan layak apabila secara
ekonomis menguntungkan. Penilaian kelayakan usaha
biasanya dilakukan dengan analisis agribisnis. Ada dua
tujuan analisis agribisnis yaitu untuk mengetahui
tingkat efisiensi penegelolaaan agribisnis dan untuk
dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan
agribisnis. Analisis rendabilitas agribisnis terdiri
dari analisis input, analisis output dan analisis
income.
87
Hasil analisis usahatani kubis di Balai Penelitian
Tanaman Sayuran Lembang, Bandung untuk luasan 1000 m2
per musim tanam yaitu :
1. Penerimaan = Rp5.040.000,00
2. Pendapatan = Rp2.454.369,00
3. Produksi per 1000 m2 = 4200 kg
4. BEP
a. BEP volume produksi = 381 unit
b. BEP harga produksi = Rp616,00 per Unit
c. BEP penerimaan = Rp 453.622,00
5. R/C Ratio = 1,94
6. ROI = %
Usahatani di Balai Penelitian Tanaman Sayuran
Lembang, Bandung layak untuk diteruskan karena :
1. Ratio penerimaan dengan biaya (R/C Ratio) > 1
2. Produksi (unit) > BEP produksi (unit)
3. Penerimaan (Rp) > BEP penerimaan (Rp)
4. Harga (Rp/unit) > BEP harga (Rp/unit)
5. ROI > bunga bank yang berlaku
88
Kurva BEP
TR/TC
5.040.000 TR
2.454.369 TC
DL 2.340.675
TVC BEP
453.622
244.956 DR TFC
Q (unit)
0 381 4.200
89
Gambar 3. Kurva BEP
KeteranganTFC = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap)TVC = Total Variable Cost (Total Biaya Variabel)TC = Total Cost (Total Biaya)TR = Total Revenue (Total Penerimaan ) BEP = Break Event Point (titik impas)DR = Daerah RugiDL = Daerah Laba
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Budidaya tanaman kubis meliputi kegiatan-kegiatan
pokok : penyiapan bibit dan lahan, penanaman,
pemeliharaan dan kegiatan panen dan pasca panen
2. Manajemen pengendalian hama dan penyakit kubis
meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan dari
90
awal tanam, saat tanam sampai setelah tanam.
Sedangkan pengendalian hama dan penyakit kubis
dapat dilakukan dengan cara fisik, biologi,
kultur teknis dan kimiawi.
3. Hasil analisis Usahatani kubis 1000 m2 per musim
tanam:
a. Penerimaan = Rp5.040.000,00
b. Pendapatan = Rp2.454.369,00
c. Produksi per 1000 m2 = 4.200 kg
d. BEP produksi untuk budidaya kubis yaitu 381
unit, harga per unitnya Rp616,00 dan
penerimaannya Rp 453.622,00
d. R/C Ratio = 1,94
e. ROI = ???
B. Saran
91
1. Balitsa lebih banyak lagi bekerja sama dengan
produsen benih (kemitraan) agar dapat mensukseskan
penyediaan benih bermutu untuk petani.
2. Lebih banyak lagi melakukan penelitian –
penelitian tentang hama dan penyakit kubis,
sehingga dapat menemukan alternatif – alternatif
untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut.
3. Pensosialisasian kepada petani mengenai hasil
penelitian yang ada ke petani sekitar lebih di
intensifkan lagi.
92
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007. Manajemen Hama dan Penyakit. (On Line).http://www.organicindonesia.org/02produsen-artikel.php?id=104. Akses 17 Januari 2011.
Anonim. 2009. Kol atau Kubis. (On Line).http://gerbangpertanian.com. Akses 9 Maret 2010
Anonim. 2010. Mengenal Pestisida. (On Line).http://www.pupukcair.co.cc. Akses 15 Februari 2011.
Anonim. 2010. Pengenalan Pestisida. (On Line).www.a3roses.com. Akses 9 Maret 2011.
Departement of Agriculture and Food. 2010. Penyakit BusukHitam pada Keluarga Kubis. (On Line).http://www.indopetani.com. Akses 9 Maret 2011.
Harahap, Lenny H., 2010. Peranan Karantina Pertanian dalamPengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Tanaman Kubis. (OnLine). http://www.bbkpbelawan.deptan.go.id. Akses 17Januari 2011.
Herminanto. 2010. Hama Ulat Daun Kubis Pluttela xylostella danUpaya Pengendaliannya. (On Line).http://gerbangpertanian.com. Akses 9 Maret 2010.
93
Lubis H. 2004. Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Kubis(Brassica oleracea) dan Kentang (Solanum tuberasum). ProgramStudi Hama dan Penyakit Tanmaan Fakultas PertanianUniversitas Sumatera Utara.
Lubis, Lahmuddin 2004. Pengendalian Hama Terpadu PadaTanaman Kubis (Brassica Oleracca) Dan Kentang (SolanumTuberosum. Program Studi Hama dan Penyakit TanamanFakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. (On-Line). http://hpt-lahmuddin.com. Akses 17 Januari2011.
Perdana Dimas A. 2009. Budidaya Kol / Kubis. (On Line).http://dimasadityaperdana.blogspot.com/2009/06/budidaya-kol-kubis.html. Akses 19 Oktober 2010.
Permadi, Anggodo. 1993. Kubis. Balai PenelitianHortikultura Lembang. Bandung. 154 hal.
Pracaya. 2001. Kol Alias Kubis. Panebar Swadaya. Jakarta. 96hal.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. SistemPengendalian Manajemen. (On Line).http://www.pusdiklatwabpkp.com. Akses 17 Januari2011.
Rukmana, Rahmat. 1994. Bertanam Kubis. Kanisius.Yogyakarta. 68 hal.
Sa’id, E.G. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalila Indonesia.Jakarta. 150 hal.
Suhartono, 2009. Kelayakan Usaha Agribisnis. FakultasPertanian Universitan Jenderal Sodirman. Purwokerto.
Supriyono, R. A. 1993. Perencanaan dan Pengendalian BiayaSerta Pembuatan Keputusan. BPFE UGM. Yogyakarta.
94