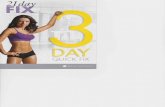Toksik fix
Transcript of Toksik fix
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di sepanjang jalan raya Rancaekek-Cicalengka, telah
berkembang kawasan industri tekstil sejak tahun 1978. Kawasan
yang merupakan bagian dari sub-DAS Citarik tersebut sebenarnya
merupakan daerah persawahan yang subur. Akan tetapi,
industrialisasi menyebabkan lahan sawah semakin berkurang.
Menurut Wahyunto dkk. (2001), antara tahun 1969 sampai 2000,
lahan sawah di Sub DAS Citarik menyusut dari 9.675 ha (36,7%)
menjadi 9.240 ha (35,4%). Lahan sawah ini telah dikonversi ke
penggunaan non-pertanian seperti perkotaan dan kawasan industri.
Salah satu dampak negatif alih fungsi lahan sawah untuk kawasan
industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan
oleh limbah industri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Suganda dkk. (2002), di Sub-DAS Citarik, khususnya sentra
produksi padi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, total
area persawahan yang tercemar aliran limbah pabrik tekstil
langsung seluas ± 1.215 ha; terkena limbah saat banjir lebih dari
satu minggu seluas 254 ha; terkena limbah saat banjir kurang dari
satu minggu seluas 474 ha; dan lahan tergenang banjir bulanan
(Desember sampai Mei) seluas 520 ha. Hal ini mengakibatkan hasil
gabah pada lahan sawah yang terkena limbah pabrik tekstil
berkurang antara 1 sampai 1,5 t/ha/panen dan kerugian di daerah
1
ini dapat mencapai Rp. 2.43 sampai Rp. 3.65 milyar/tahun (Suganda
dkk., 2002).
Kebijakan pemerintah dalam menempatkan kawasan industri di
daerah persawahan yang subur merupakan langkah yang kurang tepat,
karena terjadi pengalihan fungsi lahan sawah ke penggunaan lain.
Hasil penelitian Wahyunto et al. (2001) di Sub DAS Citarik,
menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan lahan sawah seluas 787
ha terhitung dari tahun 1991 sampai 2000.
Sejauh ini pengkajian dampak negatif dari konversi lahan
sawah lebih banyak dipandang dari nilai ekonomi komoditas yang
hilang. Padahal semestinya dilakukan pula kajian secara mendalam
dari aspek lainnya, seperti penurunan kualitas sumber daya tanah,
air, udara, dan keragaman hayati. Alihfungsi tersebut menyebabkan
hilangnya beberapa keuntungan ekternal (externalities) yang bisa
didapatkan dari keberadaan lahan sawah. Oleh karena itu, penting
artinya untuk melakukan kuantifikasi berbagai peranan lahan sawah
(multifungsi), sehingga didapatkan justifikasi kuat dalam
melakukan advokasi untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah
(Irianto et al., 2001; Tala’ohu et al., 2001).
Salah satu dampak negatif alih fungsi lahan sawah untuk
kawasan industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh buangan limbah industri tersebut. Menurut
ketentuan, limbah yang akan dibuang ke lingkungan harus aman bagi
lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia
atau hewan. Limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu dalam
instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan mengalami pemrosesan2
fisik, kimia, dan biologi sebelum dibuang ke lingkungan atau
badan air/sungai. Namun kenyataannya limbah buangan tersebut
masih sering dikeluhkan masyarakat, karena dampak negatif yang
ditimbulkannya seperti bau, warna, dan gangguan kesehatan.
Sungai terkadang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah,
namun sering dimanfaatkan sebagai air irigasi bagi persawahan di
bagian hilirnya. Seperti terjadi di Sub DAS Citarik, pihak
industri atau pabrik di wilayah Kabupaten Sumedang membuang
limbahnya ke S. Cihideung dan S. Cikijing yang merupakan sumber
air irigasi bagi persawahan di Kabupaten Bandung. Para petani di
kawasan tersebut melaporkan beberapa kali menanam padi dalam
setahun tanpa mendapatkan hasil atau hasilnya sangat minim
(Abdurachman et al., 2000).
Tanah yang terkena limbah zat kimia dalam konsentrasi di atas
ambang batas, mungkin tidak sakit meskipun mengandung
unsur/senyawa kimia atau logam berat yang berbahaya. Namun bila
tanah tersebut ditanami, maka tanaman tersebut akan mengakumulasi
unsur/senyawa yang berbahaya, sehingga dapat menimbulkan dampak
negatif bagi kesehatan manusia dan hewan yang mengkonsumsi produk
tersebut.
Penelitian tentang dampak dan pergerakan jenis-jenis
unsur/senyawa yang terkandung dalam limbah dan kadar
unsur/senyawa kimia dalam limbah tersebut perlu diketahui mulai
dari pusat industri sampai ke bagian hilirnya, karena pengaruh
limbahnya akan mempengaruhi luas tanam dan kualitas hasil
3
tanaman, sehingga pada akhirnya akan menurunkan ketahanan pangan
di suatu daerah. Ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan
ketersediaan komoditas pokok karbohidrat dalam jumlah yang cukup,
terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi oleh
masyarakat sepanjang waktu (Karama, 1999).
Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan bagi produksi
pertanian, maka lahan pertanian tersebut harus dicadangkan atau
dilindungi dari konversi lahan. Adanya konversi lahan, tidak
hanya menurunkan produksi tanaman, tetapi juga dapat menyebabkan
menurunnya pendapatan petani dan menurunannya penyerapan tenaga
kerja/buruh tani, serta kehilangan peluang untuk memperoleh
pendapatan dari penyewaan traktor dan penggilingan padi bagi
masyarakat sekitar (Sumaryanto dan Nur Suhaeti, 1997). Diduga
pencemaran yang terjadi pada lahan sawah di Sub DAS Citarik hulu
mengganggu stabilitas ketahanan pangan di daerah tersebut.
1.2 Tujuan
Mengidentifikasi penyebab matinya tanaman mentimun dan padi
akibat diberi irigasi dari sungai Citarik (Studi kasus di
Rancaekek)
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang
yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat
umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-
zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, menggangu
lingkungan hidup serta kehadirannya pada suatu saat dan tempat
tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai
ekonomis(Anonim, 2009). Meskipun merupakan air sisa namun
volumenya besar karena lebih kurang 80% dari air yang digunakan
bagi kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari tersebut dibuang lagi
5
dalam bentuk yang sudah kotor (tercemar). Selanjutnya air limbah
ini akhirnya akan mengalir ke sungai dan laut dan akan digunakan
oleh manusia lagi. Oleh sebab itu, air buangan ini harus dikelola
dan atau diolah secara baik.
Berdasarkan sumbernya air limbah dapat dikelompokkan menjadi
air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes
water), air buangan industri (industrial wastes water) yang
berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi dan
air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan,
hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan
sebagainya. Pada umumnya air limbah memiliki karakteristik
tertentu dan perlu utnuk diketahui karena menentukan cara
pengolahan yang tepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Secara
garis besar karakteristik air limbah ini digolongkan sebagai
berikut.
a. Karakteristik Fisik
Sebagian besar terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri
dari bahan-bahan padat dan suspensi. Terutama air limbah rumah
tangga, biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit
berbau. Kadang-kadang mengandung sisa-sisa kertas, berwarna bekas
cucian beras dan sayur, bagian-bagian tinja, dan sebagainya.
b. Karakteristik Kimiawi
6
Biasanya air buangan ini mengandung campuran zat-zat kimia
anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat
organik berasal dari penguraian tinja, urine dan sampah-sampah
lainnya. Oleh sebab itu pada umumnya bersifat basa pada waktu
masih baru dan cenderung ke asam apabila sudah mulai membusuk.
c. Karakteristik Bakteriologis
Kandungan bakteri patogen serta organisme golongan coli
terdapat juga dalam air limbah tergantung darimana sumbernya
namun keduanya tidak berperan dalam proses pengolahan air
buangan.
Keberadaan air limbah dapat memberikan dampak terhadap
makhluk hidup disekitar serta lingkungan. Hal ini terjadi karena
air limbah dapat bertindak sebagai menjadi transmisi atau media
penyebaran berbagai penyakit, menjadi media berkembangbiaknya
mikroorganisme patogen, menjadi tempat-tempat berkembangbiaknya
nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk, menimbulkan bau yang tidak
enak serta pandangan yang tidak sedap, merupakan sumber
pencemaran air permukaan, tanah dan lingkungan hidup lainnya dan
mengurangi produktivitas manusia karena orang bekerja dengan
tindak nyaman dan sebagainya. Mengingat bahaya yang diberikan
oleh air limbah maka, upaya untuk menanggulangi air limbah sangat
perlu utnuk dilakukan.
7
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pencemaran Air
Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau
dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke
dalam lingkungan. Dapat juga diartikan sebagai perubahan tatanan
lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga
kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sesuai dengan UU Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982.
Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari, yang
dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan
8
pencemaran dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat
terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.
Soemarwoto (1991) dalam Kurnia, et al. (2009) mengatakan pencemaran
terjadi pada tanah, air tanah, badan air atau sungai, udara,
bahkan terputusnya rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup
atau penghancuran suatu jenis organisme yang pada akhirnya akan
menghancurkan ekosistem.
Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran di sebut
polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila
keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makluk hidup.
Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah
bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat
memberikan efek merusak.
Selanjutnya Kurnia, et al. (2009 ) mengatakan bahwa penyebab
pencemaran pada lahan pertanian dapat digolongkan ke dalam
kegiatan non pertanian (industri, pertambangan) dan kegiatan
pertanian (penggunaan bahan-bahan agrokimia). Pencemaran pada
lahan sawah umumnya disebabkan oleh limbah industri dan aktivitas
budi daya yang menggunakan bahan-bahan agrokimia seperti pupuk
dan pestisida yang kurang terkendali. Banyaknya pabrik atau
industri tekstil yang dibangun di sekitar lahan pertanian telah
menyebabkan tercemarnya lahan sawah sehingga hasil gabah menjadi
berkurang atau sama sekali tidak menghasilkan.
Pencemaran yang terjadi ini disebabkan oleh limbah industri
tekstil yang dibuang ke badan air atau sungai, sementara sungai 9
merupakan sumber pengairan lahan sawah yang ada di bagian hilir
pabrik atau industri. Seperti aliran sungai Cikijing (anak sungai
Citarik) yang telah tercemar limbah industri tekstil dan
digunakan untuk pengairan persawahan disekitar Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung. Akibatnya unsur-unsur kimia yang
terbawa limbah, selanjutnya mengendap di dalam tanah. Proses ini
terus berlanjut sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya dan
beracun (B3) serta logam berat di dalam tanah. Oleh karena itu
diperlukan teknologi untuk mengendalikan pencemaran yang terjadi
pada tanah sawah.
Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Pengembangan Tanah
dan Agroklimat sejak 2001, yang dipaparkan tim dari BPLHD maupun
PSDA, tanah di persawahan Rancaekek mengandung natrium (Na)
dengan konsentrasi tinggi yaitu 2,03-12,97 me/100g tanah. Sebagai
perbandingan, kadar Na dalam tanah yang tidak tercemar limbah
industri tekstil hanya 0,42 me/100g tanah. Selain Na, unsur logam
berat pencemar lainnya yang terdeteksi adalah Hg, Cd, Cr, Cu, Co,
dan Zn. Ratusan hektare sawah di empat desa di Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung terindikasi mengandung bahan-bahan
kimia beracun dan logam berat (B3), sehingga menurunkan produksi
dan kualitas padi. Pencemaran terjadi karena para petani
menggunakan Sungai Cikijing (anak Sungai Citarik) yang telah
tercemar limbah industri tekstil sebagai sumber pengairan bagi
pertanian mereka . Begitu pula dengan lahan budidaya mentimun,
mereka menggunakan air yang bersumber dari Sungai Cikijing yang
sudah trcemar limbah tekstil tersebut.
10
3.2. Kapasitas Asimilasi
Sebenarnya, secara alami sungai mampu menetralisir bahan
pencemar yang masuk. Artinya, ia memiliki daya asimilasi untuk
memroses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar yang masuk.
Namun, dengan semakin tingginya konsentrasi akumulasi bahan
pencemar ke dalam perairan sehingga berakibat daya asimilatif
sungai sebagai gudang sampah menjadi menurun dan menimbulkan
masalah lingkungan.
Pendugaan kapasitas asimilasi perairan dalam menampung
limbah menggunakan metode hubungan antara konsentrasi limbah dan
beban limbah (Dahuri, 1999). Pola hubungan tersebut konsentrasi
limbah dan beban limbah disajikan pada Gambar 1.
11
3.3. Sumber-sumber dan Jenis Bahan Pencemar yang Masuk ke Sungai
Citarik
PT. ITM adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi
texstil dan dalam memproduksi texstil khususnya di bidang
persiapan kain Filamen, persiapan kain katun / SPUN menggunakan
bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu bahan kimia berupa Caustic
Soda / NaOh, Desizing / penghilang kanji dan zat pewarna Dispers
sehingga sebagai akibat dari proses produksi PT. ITM tersebut
mengeluarkan limbah cair. Selain PT.ITM, PT Kahatex dan PT
Polyfin Canggih juga merupakan penyumbang limbah sungai Citarik.
Larutan penghilang kanji biasanya langsung dibuang dan ini
mengandung zat kimia pengkanji dan penghilang kanji pati, PVA,
CMC, enzim, asam. Penghilangan kanji biasanya memberi kan BOD
paling banyak dibanding dengan proses-proses lain. Pemasakan dan
merserisasi kapas serta pemucatan semua kain adalah sumber limbah
cair yang penting, yang menghasilkan asam, basa, COD, BOD,
padatan tersuspensi dan zat-zat kimia. Proses-proses ini
menghasilkan limbah cair dengan volume besar, pH yang sangat
bervariasi dan beban pencemaran yang tergantung pada proses dan
zat kimia yang digunakan. Pewarnaan dan pembilasan menghasilkan
air limbah yang berwarna dengan COD tinggi dan bahan-bahan lain
dari zat warna yang dipakai, seperti fenol dan logam. Di
Indonesia zat warna berdasar logam (krom) tidak banyak dipakai.
12
Proses pencetakan menghasilkan limbah yang lebih sedikit daripada
pewarnaan.
Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Pengembangan Tanah
dan Agroklimat sejak 2001, yang dipaparkan tim dari BPLHD maupun
PSDA, tanah di persawahan Rancaekek mengandung natrium (Na)
dengan konsentrasi tinggi yaitu 2,03-12,97 me/100g tanah. Sebagai
perbandingan, kadar Na dalam tanah yang tidak tercemar limbah
industri tekstil hanya 0,42 me/100g tanah. Selain Na, unsur logam
berat pencemar lainnya yang terdeteksi adalah Hg, Cd, Cr, Cu, Co,
dan Zn. Ratusan hektar sawah di empat desa di Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung terindikasi mengandung bahan-bahan
kimia beracun dan logam berat (B3), sehingga menurunkan produksi
dan kualitas padi. Hal ini pun terjadi pada pertanaman mentimun,
sehingga tanaman menitumn banyak yang mati. Pencemaran terjadi
karena para petani menggunakan Sungai Cikijing (anak sungai
Citarik) yang telah tercemar limbah industri tekstil sebagai
sumber pengairan bagi pertanian mereka.
3.4. Proses toksik bahan pencemar terhadap tanaman padi dan
mentimun (fase eksposure, kinetic dan dinamik)
Fase Eksposure
Limbah berasal dari perusahaan bergerak di bidang produksi
texstil di bantaran sungai Citarik dan dalam memproduksi texstil
khususnya di bidang persiapan kain Filamen, persiapan kain
13
katun / SPUN menggunakan bahan Berbahaya Beracun (B3) yaitu bahan
kimia berupa Caustic Soda / NaOH, Desizing / penghilang kanji dan
zat pewarna Dispers. Unsur logam berat pencemar lainnya yang
terdapat di sungai Citarik adalah Hg, Cd, Cr, Cu, Co, dan Zn. Dan
limbah industri tekstil tersebut dibuang ke sungai Citarik, di
mana air sungai Citarik tersebut digunakan untuk pengairan lahan
pertanian.
Fase Kinetik
Pencemaran yang terjadi ini disebabkan oleh limbah industri
tekstil yang dibuang ke badan air atau sungai, sementara sungai
merupakan sumber pengairan lahan sawah yang ada di bagian hilir
pabrik atau industri. Akibatnya unsur-unsur kimia yang terbawa
limbah, selanjutnya mengendap di dalam tanah. Proses ini terus
berlanjut sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya dan beracun
(B3) serta logam berat di dalam tanah.
Fase Dinamik
Pencemaran ini mengakibatkan tanaman padi tidak dapat tumbuh
dengan baik, kalaupun tumbuh, bulir-bulir padinya lebih banyak
yang tak berisi. Selain tanaman padi, tanaman mentimun mengalami
hal yang sama. Tanaman-tanaman tersebut mati setelah diberi
pengairan yang airnya bersumber dari sungai Citarik.
14
3.5. Pencegahan dan pengendalian pencemaran sungai Citarik
Pengendalian pada Limbah Tekstil
Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
industri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan KepMen
LH No. 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah industri cair
bagi kegiatan industri dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pemcemaran air. Kedua
perundang-undangan tersebut pada intinya mewajibkan setiap usaha
dan atau kegiatan melakukan pengolahan limbah sampai memenuhi
persyaratan baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
1. Langkah pertama untuk memperkecil beban pencemaran dari
operasi tekstil adalah program pengelolaan air yang efektif
dalam pabrik, menggunakan :
o Pengukur dan pengatur laju alir
o Pengendalian permukaan cairan untuk mengurangi tumpahan
o Pemeliharaan alat dan pengendalian kebocoran
o Pengurangan pemakaian air masing-masing proses
o Otomatisasi proses atau pengendalian proses operasi
secara cermat
o Penggunaan kembali alir limbah proses yang satu untuk
penambahan (make-up) dalam proses lain (misalnya limbah
15
merserisasi untuk membuat penangas pemasakan atau
penggelantangan)
o Proses kontinyu lebih baik dari pada proses batch
(tidak kontinyu)
o Pembilasan dengan aliran berlawanan
2. Penggantian dan pengurangan pemakaian zat kimia dalam proses
harus diperiksa pula :
o Penggantian kanji dengan kanji buatan untuk mengurangi
BOD
o Penggelantangan dengan peroksi da menghasilkan limbah
yang kadarnya kurang kuat daripada penggelantangan
pemasakan hipoklorit
o Penggantian zat-zat pendispersi, pengemulsi dan perata
yang menghasilkan BOD tinggi dengan yang BOD-nya lebih
rendah.
3. Zat pewarna yang sedang dipakai akan menentukan sifat dan
kadar limbah proses pewarnaan. Pewarna dengan dasar pelarut
harus diganti pewarna dengan dasar air untuk mengurangi
banyaknya fenol dalam limbah. Bila digunakan pewarna yang
mengandung logam seperti krom, mungkin diperlukan reduksi
kimia dan pengendapan dalam pengolahan limbahnya. Proses
penghilangan logam menghasilkan lumpur yang sukar diolah dan
sukar dibuang. Pewarnaan dengan permukaan kain yang terbuka
16
dapat mengurangi jumlah kehilangan pewarna yang tidak
berarti.
4. Pengolahan limbah cair dilakukan apabila limbah pabrik
mengandung zat warna, maka aliran limbah dari proses
pencelupan harus dipisahkan dan diolah tersendiri. Limbah
operasi pencelupan dapat diolah dengan efektif untuk
menghilangkan logam dan warna, jika menggunakan flokulasi
kimia, koagulasi dan penjernihan (dengan tawas, garam feri
atau poli-elektrolit). Limbah dari pengolahan kimia dapat
dicampur dengan semua aliran limbah yang lain untuk
dilanjutkan ke pengolahan biologi.
Jika pabrik menggunakan pewarnaan secara terbatas dan
menggunakan pewarna tanpa krom atau logam lain, maka gabungan
limbah sering diolah dengan pengolahan biologi saja, sesudah
penetralan dan ekualisasi. Cara-cara biologi yang telah terbukti
efektif ialah laguna aerob, parit oksidasi dan lumpur aktif.
Sistem dengan laju alir rendah dan penggunaan energi yang rendah
lebih disukai karena biaya operasi dan pemeliharaan lebih rendah.
Kolom percik adalah cara yang murah akan tetapi efisiensi untuk
menghilangkan BOD dan COD sangat rendah, diperlukan lagi
pengolahan kimia atau pengolahan fisik untuk memperbaiki daya
kerjanya.
Untuk memperoleh BOD, COD, padatan tersuspensi, warna dan
parameter lain dengan kadar yang sangat rendah, telah digunakan
17
pengolahan yang lebih unggul yaitu dengan menggunakan karbon
aktif, saringan pasir, penukar ion dan penjernihan kimia.
Pengendalian pada Perairan
Selain dilakukan pada limbah tekstil, pengendalian juga
dapat dilakukan pada perairan. Secara garis besar sebenarnya ada
dua cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi
pencemaran perairan oleh logam berat, yaitu cara kimia dan
biologi.
Cara kimia, antara lain dengan reaksi chelating, yaitu
memberikan senyawa asam yang bisa mengikat logam berat sehingga
terbentuk garam dan mengendap. Namun, cara ini mahal dan logam
berat masih tetap berada di perairan meski dalam keadaan terikat.
Untunglah ada penanggulangan secara biologi yang bisa menjadi
alternatif terhadap mahalnya penanggulangan dengan cara kimia.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan eceng gondok (Eichornia
crassipes).
Eceng gondok selama ini lebih dikenal sebagai gulma.
Padahal, eceng gondok sebenarnya punya kemampuan menyerap logam
berat. Kemampuan ini telah diteliti di laboratorium Biokimia,
Institut Pertanian Bogor, dengan hasil yang sangat luar biasa.
Eceng gondok terbukti mampu menurunkan kadar polutan Pb dan
Fe. Oleh karena itu, diyakini eceng gondok juga mampu menurunkan
kadar polutan Hg, Zn, dan Cu. Sebab, secara struktur kimia, atom
18
Hg, Zn, dan Cu termasuk dalam golongan logam berat bersama Pb dan
Fe. Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan
juga mampu menyerap residu pestisida, contohnya residu 2.4-D dan
paraquat.
Memang dilaporkan eceng gondok dapat tumbuh sangat cepat
pada danau maupun waduk sehingga dalam waktu yang singkat dapat
mengurangi oksigen perairan, mengurangi fitoplankton dan
zooplankton serta menyerap air sehingga terjadi proses
pendangkalan, bahkan dapat menghambat kapal yang berlayar pada
waduk. Namun, apa arti sebuah danau yang bersih dari eceng gondok
jika ternyata air dan ikan yang ada di dalamnya tercemari
polutan? Bahkan, bila suatu danau polutan sangat tinggi dan tidak
ada tanaman yang menyerapnya, pencemaran dapat merembes ke air
sumur dan air tanah di sekitar danau.
Agar perairan bebas polusi namun pertumbuhan eceng gondoknya
terkendali, tentu saja diperlukan pengelolaan secara benar. Untuk
mengeliminasi gangguan eceng gondok, misalnya, caranya bisa
dengan membatasi populasinya. Pembatasan dapat dilakukan dengan
membatasi penutupan permukaan oleh eceng gondok tidak lebih dari
50 persen permukaannya.
Akan jauh lebih baik lagi bila pembatasan populasi ini
dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Sebab, dahan
eceng gondok adalah serat selulosa yang dapat diolah untuk
berbagai keperluan, seperti barang kerajinan maupun bahan bakar
pembangkit tenaga listrik. Namun, masyarakat tidak disarankan
19
untuk memberikan eceng gondok sebagai pakan pada ternak karena
polutan yang diserapnya bisa terakumulasi dalam dagingnya.
Masyarakat sekitar bisa diberi pelatihan mengenai pengolahan
eceng gondok menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi, mulai
dari anyaman dompet, tas sekolah, topi, bahkan juga mebeul.
BAB III
KESIMPULAN
Banyaknya pabrik atau industri tekstil yang dibangun di
sekitar lahan pertanian telah menyebabkan tercemarnya lahan sawah
sehingga hasil gabah menjadi berkurang atau sama sekali tidak
menghasilkan. Selain itu, tanaman mentimun juga banyak yang mati.
Tanaman-tanaman tersebut mati setelah diberi pengairan yang
airnya bersumber dari sungai Citarik.
Pencemaran yang terjadi ini disebabkan oleh limbah industri
tekstil yang dibuang ke badan air atau sungai, sementara sungai
merupakan sumber pengairan lahan sawah yang ada di bagian hilir
pabrik atau industri. Seperti aliran sungai Cikijing (anak sungai
Citarik) yang telah tercemar limbah industri tekstil dan
digunakan untuk pengairan persawahan disekitar Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung. Akibatnya unsur-unsur kimia yang
20
terbawa limbah, selanjutnya mengendap di dalam tanah. Proses ini
terus berlanjut sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya dan
beracun (B3) serta logam berat di dalam tanah. Unsur logam berat
pencemar yang terdapat di sungai Citarik antara lain Na, Hg, Cd,
Cr, Cu, Co, dan Zn.
Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
industri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan KepMen
LH No. 51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah industri cair
bagi kegiatan industri dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pemcemaran air. Kedua
perundang-undangan tersebut pada intinya mewajibkan setiap usaha
dan atau kegiatan melakukan pengolahan limbah sampai memenuhi
persyaratan baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
Selain dilakukan pada limbah tekstil, pengendalian juga
dapat dilakukan pada perairan. Secara garis besar sebenarnya ada
dua cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi
pencemaran perairan oleh logam berat, yaitu cara kimia dan
biologi. Cara kimia adalah dengan reaksi chelating dan cara
biologi misalnya dengan menggunakan tanaman eceng gondok.S
DAFTAR PUSTAKA
21
Andarani, Pertiwi, Dwina Roosmini. Profil Pencemaran Logam Berat (Cu, Cr,
Dan Zn) pada Air Permukaan Dan Sedimen Di Sekitar Industri Tekstil PT X
(Sungai Cikijing). Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan :
Institut Teknologi Bandung
Anonim. 2009. Pengelolaan Lahan Sawah Tercemar Limbah Tekstil. (diakses
dari : http://reensaikoe.wordpress.com/pengelolaan-lahan-
spesifik-lingkungan-plsl/pengelolaan-lahan-sawah-tercemar-
limbah-tekstil/ tanggal 3 Maret 2011)
Destawibowo, Bayu. 2009. Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Tekstil.
(diakses dari :
http://limbahlingkungan.blogspot.com/2009/04/pengolahan-dan-
pemanfaatan-limbah.html tanggal 6 Maret 2011)
Dinata, Arda. 2008. Menyelamatkan Laut dari Pencemaran. (diakses
dari :
http://arda-dinata-pplf.blogspot.com/2008_04_01 _archive.html
tanggal 6 Maret 2011)
22
Hasim, 2007. Eceng Gondok Pemersih Polutan Logam Berat. (diakses dari
http://petanidesa.wordpress.com/2007/03/11/eceng-gondok-
pemersih-polutan-logam-berat/ tanggal 6 Maret 2011)
Samawi, Farid. 2007. Desain Sistem Pengendalian Pencemaran Perairan Pantai
Kota. Sekolah Pascasarjana : Institut Pertanian Bogor
Suganda, Husein, Diah Setyorini, Harry Kusnadi, Ipin Saripin,
Undang Kurnia. 2002. Evaluasi Pencemaran Limbah Industri Tekstil Untuk
Kelestarian Lahan Sawah. Balai penelitian Tanah : Bogor
Toluena, Yanti. 2010. Biosorpsi Logam Berat pada Air Limbah Tekstil
Menggunakan Biomassa Jamur Lapuk Putih Isolat Lokal Singaraja. (diakses
dari :
http://wwwyantitoluena.blogspot.com/2010/09/biosorpsi-logam-
berat-pada-air-limbah.html tanggal 3 Maret 2011)
23