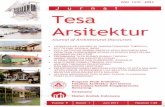STUDI PROSES GEOMORFOLOGI PADA LEMBAH FLUVIAL SUNGAI CODE ANTARA POGUNG LOR DAN POGUNG KIDUL...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of STUDI PROSES GEOMORFOLOGI PADA LEMBAH FLUVIAL SUNGAI CODE ANTARA POGUNG LOR DAN POGUNG KIDUL...
STUDI PROSES GEOMORFOLOGI PADA LEMBAH FLUVIAL SUNGAI CODE
ANTARA POGUNG LOR DAN POGUNG KIDUL KECAMATAN MLATI KABUPATEN
SLEMAN PADA PUNCAK MUSIM PENGHUJAN
Febriana Anita Yustinawati
14405244011
Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRAK
Sebagai planet yang dinamis, permukaan bumi senantiasamengalami perubahan bentuk sepanjang waktu. Perubahantersebut disebabkan oleh bekerjanya proses geomorfologiantara lain proses endogen, eksogen, dan ekstra terestrial.Salah satu proses eksogen adalah kerja aliran sungai, ataudikenal sebagai proses fluvial. Dalam proses fluvial terdapattiga rangkaian proses yang saling berkaitan yaitu erosi,transportasi, dan deposisi. Erosi banyak terjadi pada bagianhulu, transportasi di bagian tengah, dan deposisi di bagianhilir. Masing-masing proses memiliki wilayah yang dapatdiidentifikasi dengan jelas cakupan dan batasnya sehinggasering disebut zona erosi, zona transportasi, dan zonadeposisi atau diistilahkan pula dengan tingkat perkembangansungai muda, dewasa, dan tua. Pada zona transportasi lajuerosi telah dapat diimbangi oleh proses deposisi. Wilayah inidicirikan oleh pengangkutan material sedimen dari zona erosimenuju zona deposisi. Sungai Code pada wilayah antara PogungLor dan Pogung Kidul memiliki ciri tingkat perkembangandewasa ditandai oleh adanya proses transportasi sedimen sertakenampakan hasil erosi dan deposisi pada satu lembah sungaiyang sama. Dalam tulisan ini akan dideskripsikan hasilpengamatan proses fluvial mengenai karakteristik transportasisedimen yang terjadi di Sungai Code antara Pogung Lor danPogung Kidul. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa
1
Sungai Code pada musim hujan memiliki kecepatan arus yangbesar sehingga dapat mengangkut sedimen-sedimen dengan baik,pada sungai ini juga dijumpai kenampakan bentuklahan fluvialhasil deposisi seperti gosong pasir dan kenampakan hasilproses erosi.
PENDAHULUAN
Sejak bumi terbentuk dengan perkiraan waktu pada 4,56
miliar tahun yang lalu, permukaan bumi terus mengalami
perubahan bentuk oleh karena bekerjanya berbagai proses
geomorfologi baik proses endogen, eksogen, maupun ekstra
terestrial. Proses endogen terjadi karena adanya pengaruh
tenaga dari dalam bumi, proses eksogen dipengaruhi oleh
tenaga dari luar permukaan bumi, sedangkan proses ekstra
terestrial dipengaruhi oleh benda luar angkasa yang mencapai
permukaan bumi. Proses eksogen memiliki karakteristik yang
unik karena bekerjanya proses ini tidak terlepas dari
interaksi antara komponen atmosfer, hidrosfer, dan litosfer.
Dalam proses eksogen terdapat agen geomorfik yang mampu
mengikis dan mengangkut material bumi kemudian
mengendapkannya. Secara keseluruhan proses eksogen memiliki
sifat sebagai three phases of single activity yang terdiri dari erosi,
transportasi, dan deposisi (Pramono dan Ashari, 2014).
Pada daerah dengan iklim tropis basah seperti di
Indonesia salah satu proses eksogen yang paling dominan
adalah proses fluvial. Proses ini telah menghasilkan berbagai
kenampakan khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan
deposisi. Bentanglahan fluvial merupakan wilayah yang telah
lama ditempati oleh masyarakat di Indonesia. Dengan demikian
pemahaman mengenai proses fluvial dan bentuklahan yang
2
dihasilkan sangat penting terutama berkaitan dengan terapan
studi geomorfologi antara lain dalam bidang survei dan
pemetaan, survei hidrologis, survei sumberdaya dan mitigasi
bencana, serta dalam mendukung proyek-proyek pembangunan
(Verstappen, 1983; Huggett, 2007).
Sungai Code merupakan salah satu sungai yang terdapat
dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak. Sungai ini berhulu
dari wilayah Gunungapi Merapi, kemudian bergabung dengan
Sungai Opak sebagai sungai utama di sekitar escarpment
Pegunungan Baturagung (Ashari, 2010). Sungai ini memiliki
kedudukan penting karena melalui wilayah Kota Yogyakarta yang
memiliki kepadatan penduduk tinggi. Aktivitas Sungai Code
sepanjang waktu banyak berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat sehingga perlu adanya kajian mengenai
karakteristik geomorfologi sungai ini khususnya mengenai
proses yang masih berlangsung. Daerah pengamatan dibatasi
pada wilayah antara Pogung Lor dengan Pogung Kidul, yaitu
sebelum memasuki wilayah Kota Yogyakarta, yang dicirikan oleh
proses transportasi sedimen.
Proses transportasi sedimen sangat berkaitan dengan
ukuran butir material terangkut dan laju aliran sebagai
tenaga pengangkut (Huggett, 2007; Morisawa, 1979) sehingga
kondisinya tidak tetap sepanjang waktu. Apabila aliran
berkurang dan sedimen bertambah maka proses transportasi akan
cenderung mengarah kepada deposisi, sebaliknya apabila aliran
bertambah dan sedimen berkurang maka akan mengarah pada
proses redistribusi sedimen. Kondisi ini selanjutnya akan
mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar lembah sungai,
3
sehingga perlu ada kajian yang lebih rinci mengenai
karakteristik proses transportasi yang terjadi sebagai bentuk
monitoring perkembangan bentuklahan dan perubahan lingkungan
pada lembah Sungai Code.
KAJIAN PUSTAKA
Geomorfologi Fluvial
Definisi bentuklahan proses fluvial menurut Suharsono
(1988) dalam Pramono dan Ashari (2014:118) adalah bentuklahan
asal proses fluvial merupakan bentuklahan yang dihasilkan
oleh kerja aliran sungai, dalam hal ini terutama pada daerah-
daerah deposisi seperti lembah sungai besar dan dataran
alluvial. Proses kerja aliran sungai yang menghasilkan
bentuklahan fluvial meliputi tiga bagian, yaitu erosi,
transportasi dan sedimentasi. Karena saling berkaitan maka
ketiga proses ini sering disebut tiga tahap dari aktivitas
tunggal. Tahap dalam proses ini diawali oleh erosi, kemudian
pengangkutan, dan sedimentasi. Apabila lereng atau debit
aliran permukaan menjadi kecil, kecepatan dan energi aliran
juga menjadi kecil. Maka pada tahap ini terjadi sedimentasi
karena tenaga untuk mengangkut material hasil erosi juga
berkurang.
Proses deposisi pada awalnya berupa material berukuran
besar seperti bongkah, kerakal, dan kerikil. Kemudian disusul
pengendapan material yang lebih halus seperti pasir dan
lempung. Bentuk-bentuk fluvial pada daerah hulu biasanya
dikategorikan sebagai bentuklahan denudasional kecuali
apabila dijumpai pada sungai-sungai yang besar. Bila sungai
4
mencapai laut/danau terjadi peralihan ke bentuklahan asal
proses marin/lacustrine.
Menurut Van Sleen dkk (1974) dalam Pramono dan Ashari
(2014:118) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kondisi
alami dari sedimen fluvial yaitu: (1) muatan sedimen pada
tubuh perairan yang dikontrol oleh kecepatan aliran, gradien
dan pasokan (supply) dari muatan sedimen itu sendiri, (2) luas
dan kondisi alami daerah aliran sungai, mencakup kondisi
geologi, iklim, relief, tanah, vegetasi penutup, dan bentuk
DAS, dan (3) kondisi aliran air yang meliputi kecepatan,
kuantitas, dan arah aliran air serta variasinya.
Sedangkan menurut Charlton (2008) dalam Pramono dan
Ashari (2014:119) mengatakan bahwa sistem fluvial terdiri
atas tiga bagian yaitu zona erosi, zona transportasi dan zona
deposisi. Zona erosi merupakan bagian hulu daerah aliran
sungai, pada bagian ini kenampakan yang terbentuk adalah
kenampakan-kenampakan yang bersifat destruktif. Zona erosi
merupakan wilayah sungai berstadium muda. Zona transportasi
merupakan wilayah sungai berstadium dewasa, adapun zona
deposisi merupakan wilayah sungai berstadium tua yang banyak
dijumpai kenampakan hasil deposisi. Setelah erosi dan
transportasi, selanjutnya sedimen dari hasil proses fluvial
mengalami deposisi dalam berbagai bentuk dan ukuran.
Besarnya ukuran sedimen yang terangkut aliran air
ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sebagai berikut:
ukuran butir sedimen yang masuk ke badan sungai/saluran air,
karakteristik saluran, debit, dan karakteristik fisik
5
partikel sedimen. Besarnya sedimen yang masuk sungai dan
besarnya debit dipengaruhi oleh:
a. Kondisi klimatologi dan hidrologi seperti hujan dan
debit aliran sungai.
b. Kondisi DAS dan perubahan penggunaan lahan seperti
topografi, vegetasi.
c. Faktor yang relatif tetap dari DAS sepajang waktu,
seperti batuan dan topografi.
Interaksi dari masing-masing faktor tersebut di atas akan
menentukan besarnya jumlah dan tipe sedimen serta kecepatan
pengangkutan sedimen. Pengangkutan sedimen dari tempat yang
lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah hilir dapat
menyebabkan pendangkalan waduk, sungai, saluran irigasi, dan
pembentukan delta-delta sungai. Dengan demikian, proses
sedimentasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan
dampak yang merugikan. Dampak menguntungkan karena tingkat
tertentu adanya aliran sedimen kedaerah hilir dapat menambah
kesuburan tanah serta terbentuknya tanah garapan baru di
daerah hilir. Tetapi, pada saat bersamaan aliran sedimen juga
dapat menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan badan
perairan.
Sungai merupakan alur air alami, mengalir menuju
samudera, danau, laut, maupun ke sungai yang lain, menjadi
satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya
terkumpul dari hasil presipitasi. Pada beberapa wilayah
tertentu, air sungai juga dapat berasal dari lelehan es atau
salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan
polutan. Sungai adalah sistem yang kompleks, terdiri dari
6
banyak komponen yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam
suatu sistem yang sinergis dan mampu menghasilkan sistem
kerja yang efisien. Kompleksitas sungai dapat diketahui dari
bentuk alur dan percabangan sungai, formasi dasar sungai,
morfologi sungai, dan ekosistem sungai (Maryono, 2003).
Bagian terpenting pada proses geomorfologi di suatu alur
sungai adalah aliran air. Sungai memiliki peranan yang
penting, tidak hanya dalam dinamika permukaan bumi, akan
tetapi berpengaruh terhadap manusia di bumi (Morisawa,
1968). Beberapa bentuklahan asal proses fluvial sebagai
berikut:
1. Dataran Banjir
Dataran banjir (flood plain) terbentuk melalui pengendapan
muatan sungai berstadium dewasa.
2. Teras Aluvial
Merupakan bentuklahan yang dicirikan oleh dinding
berlereng curam pada satu sisi dan lereng datar/landai
pada sisi lainnya. Pembentukan teras diawali oleh
terjadinya pemotongan ke bawah (downcutting) atau
fegradasi pada dasar lembah yang lebar.
3. Point Bar
Point bar banyak dijumpai pada sungai yang sedang
mengalami meandering, yaitu kenampakan yang terbentuk
oleh pengendapan material di dalam alur sungai dan
berlangsung pada saat yang bersamaan dengan erosi ke
arah samping pada sisi yang berlawanan.
Muatan Sungai
7
Hubungan berlangsungnya erosi oleh air hujan di daerah
tangkapan air dan besarnya sedimentasi yang terpantau di
aliran sungai di bagian bawah daerah tangkapan air tersebut
erat kaitannya dengan sistem hidrologi DAS. Hujan sebagai
masukan dalam sistem hidrologi DAS setelah mengalami proses
akan menghasilkan keluaran berupa debit aliran dan muatan
sedimen. Komponen-komponen masukan, proses, dan keluaran
dalam sistem hidrologi DAS terkait satu sama lain dimana
keluaran yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh masukan dan
proses yang terjadi. Dengan demikian maka keluaran berupa
muatan suspensi selain dipengaruhi oleh karakteristik fisik
DAS sebagai komponen sistem proses, juga dipengaruhi oleh
hujan yang merupakan komponen masukan. Secara lebih lanjut
karakteristik aliran sungai juga berperan dalam transpor
muatan suspensi yang merupakan material hasil erosi. Dengan
demikian maka hujan dan karakteristik aliran memiliki
pengaruh nyata dalam proses erosi hingga transportasi muatan
suspensi sebagai material hasil erosi.
Muatan sedimen terbentuk dimulai dari pengaruh pukulan
tetesan hujan pada tanah sehingga memecah agregat tanah
menjadi butir-butir tanah yang telepas. Hujan sebagai faktor
masukan yang memasuki DAS sebagian terinfiltrasi dan sebagian
lagi menjadi aliran permukaan (overland flow) dipengaruhi oleh
faktor fisik DAS meliputi faktor lereng, tanah, vegetasi, dan
penggunaan lahan. Air hujan yang menjadi aliran permukaan
(overland flow) mengikis dan mengangkut butir-butir tanah
tersebut menuju sistem aliran. Aliran sungai selain berperan
dalam transportasi muatan sedimen juga berpengaruh pada
8
terjadinya erosi tebing sungai sehingga menambah jumlah
muatan sedimen yang terangkut. Pada proses akhirnya
dihasilkan keluaran berupa debit aliran, muatan sedimen, dan
unsur hara. Berdasarkan mekanisme pengangkutan sedimen
menurut Burgh (1972:238), muatan sedimen dibagi menjadi dua
yaitu: sedimen melayang (muatan suspensi) dan sedimen dasar
(muatan dasar). Sedimen melayang merupakan material tercampur
yang gerakannya dipengaruhi oleh aliran turbulensi sungai dan
terbawa secara tersuspensi. Muatan suspensi merupakan hasil
erosi permukaan atau erosi tebing sungai yang terbawa oleh
aliran dengan cara tersuspensi. Muatan suspensi tersusun oleh
partikel halus seperti debu dan tanah yang terangkut oleh
aliran sungai dalam bentuk terlarut. Sedangkan sedimen dasar
merupakan material yang meloncat, menggelinding, atau
menggeser pada dasar sungai. Muatan suspensi (suspended load)
merupakan material yang melayang dalam aliran sungai, sedikit
sekali interaksi dengan dasar sungai karena didorong ke atas
oleh turbulensi aliran (Soewarno, 1991), namun muatan sedimen
melayang (suspensi) pada saat tertentu sebagai muatan dasar yang
berada pada bagian dasar sungai. Muatan sedimen melayang
umumnya hanyut terbawa aliran, semakin kedasar sungai
kosentrasinya semakin besar. Penentuan muatan suspensi
meliputi tahapan pengambilan sampel, penyaringan,
penimbangan, perhitungan kadar suspensi, dan perhitungan
debit suspensi. Metode pengambilan sampel diantaranya dapat
dilakukan dengan cara depth integrating pada saat debit aliran
normal maupun point integrating pada saat debit puncak/banjir.
9
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksploratif survei
dengan pendekatan keruangan. Survei geomorfologi digunakan
dengan memperhatikan aspek morfologi, morfogenesa dan
morfometri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,
interpretasi citra penginderaan jauh dan studi pustaka,
pengambilan sampel sedimen dilakukan di bantaran sungai
dengan metode point integrating karena penelitian dilakukan pada
saat hujan sehingga sungai banjir. Data yang dikumpulkan
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berupa
hasil pengukuran dan pengamatan lapangan mengenai morfologi
Kali Code meliputi: (1) debit air, lebar, sedimen, dan
kedalaman sungai, (2) bentuklahan fluvial. Data sekunder
meliputi kondisi geomorfologi wilayah sekitar Sungai Code,
Sinduadi, Mlati, Sleman yang diperoleh dari citra astrium
2014 google maps, (3) informasi geomorfologi yang diperoleh
dari sumber pustaka.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan kombinasi antara analisis geomorfologi dengan
analisis deskriptif. Analisis geomorfologi digunakan untuk
mengidentifikasi morfometri sungai berdasarkan hasil
pengukuran lapangan, serta mengenali bentuklahan fluvial yang
dijumpai berkaitan dengan proses pembentukannya. Dalam
konteks ini, analisis geomorfologi memperhatikan tiga aspek
yaitu aspek morfologi dalam hal mengenali bentuk yang
dijumpai, serta aspek morfogenesa dalam hal pendugaan proses
yang telah bekerja sehingga menghasikan bentuk tersebut.
10
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Daerah Penelitian
Sungai Code yang membentang melintasi kota Yogyakarta
sepanjang 6,5 kilometer merupakan salah satu anak Sungai Opak
yang berhulu di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 1125
mdpal, dan merupakan lanjutan dari Sungai Boyong yang berada
di kaki Gunung Merapi di utara kota Yogyakarta, membentang
dari Kabupaten Sleman di sisi utara, melintas kota Yogyakarta
di tengah, hingga terus ke selatan hingga Kabupaten Bantul.
Sungai Code, adalah salah satu ikon utama kota Yogyakarta,
karena keunikan dan fungsinya yang lengkap, mulai dari
lintasan air, sebagai wilayah pemukiman dan salah satu
indikator lingkungan utama di Yogyakarta. Penelitian
dilakukan pada Sungai Code wilayah antara Pogung Lor dan
Pogung Kidul tepatnya pada Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati,
Kabupaten Sleman (Gambar 1).
11
Gambar 1. Peta Daerah Penelitian
Proses geomorfologi Sungai Code tidak dapat terlepas
dari kegiatan vulkanisme, mengingat Sungai Code merupakan
salah satu anak Sungai Opak yang merupakan jalur utama aliran
material piroklastis yang berasal dari Gunungapi Merapi
setelah melewati Sungai Gendol. Kestabilan dasar alur Sungai
Code dipengaruhi oleh material Gunungapi Merapi berupa
batuan, pasir, dan lumpur. Dinamika Sungai Code dipengaruhi
oleh kondisi fisik wilayah, juga dipengaruhi oleh aktivitas
Gunungapi Merapi. Sedimen yang terangkut aliran Sungai Code
berasal dari agregat material hasil erupsi yang tererosi di
wilayah yang lebih tinggi yang dialirkan melalui sungai-
sungai sebelumnya dan berasal dari selokan mataram. Volume
aliran sedimen dari hasil erosi maupun reruntuhan tebing
sungai dimulai dari sumber mata air di daerah gunungapi
kemudian terangkut ke tempat yang lebih rendah. Sumber
sedimen lainnya yaitu aliran lahar yang membawa banyak
12
material piroklastis, dan mempunyai kemungkinan prosentase
volume sedimen pada saluran yang dilaluinya. Proses aliran
sedimen akan berbeda dari hulu ke hilir, hal tersebut
dipengaruhi oleh tenaga pengangkut. Tenaga tersebut adalah
kecepatan aliran yang merupakan fungsi dari intensitas dan
tebal hujan, gradien sungai, dan keseragaman dasar saluran.
Debit Aliran Sungai
Untuk mengetahui debit aliran Sungai Code, dilakukan
pengukuran tidak langsung menggunakan Area Velocity Method dengan
pelampung. Prinsip pengukuran dengan metode ini adalah
kecepatan aliran diukur dengan menggunakan pelampung, luas
penampang basah (A) ditetapkan berdasarkan pengukuran lebar
permukaan air dan kedalaman air.
Persamaan debit yang diperoleh adalah: Q=A×k×V dengan A=KedalamanAir×LebarSungai
V=JarakWaktu
Nilai k tergantung dari jenis pelampung yang digunakan,
nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y.B
Francis sebagai berikut:
k=1−0,116 ¿
Dengan
α=kedalamantangkai (h ),yaitukedalamanpelampungyangtenggelam
kedalamanair(d)
Keterangan:
Q = debit aliran (m3dt)
A = luas penampang basah (m2)
13
V = kecepatan pelampung ( mdt )k = koefisien pelampung
Pengukuran untuk pengambilan data dilakukan di dua
bagian tempat, yaitu di bagian sungai dengan lembah yang
lurus (Gambar 2) dan bagian sungai dengan lembah yang
berkelok (Gambar 3).
Gambar 2. Sungai dengan lembah lurus
Pengambilan data untuk pengukuran debit aliran pada sungai di
Gambar 2 dilakukan pada pukul 15.35 WIB, saat itu hujan dan
terjadi kenaikan volume air, dari pengukuran didapatkan data
dan hasil sebagai berikut:
Tabel 1.1 Hasil Pengukuran pada Lembah Sungai Lurus
Lebar
sungai (m)
Kedalaman
tangkai (cm)
Kedalaman air
(cm)
Waktu
(detik)
14
8 20 150 28.726.227.526.7
Dari data di atas jika dimasukan ke persamaan debit area
velocity method , maka:
Luas penampang basah A=KedalamanAir×LebarSungaiA=1,5m×8m=12m2
Kecepatan pelampung V=JarakWaktu,
Vi=20
28,7=0,7 m
dt
Vii=20
26,2=0,8 m
dt
Viii= 2027,5
=0,7 mdt
Viv=20
26,7=0,7 m
dt
Jadi kecepatan pelampung (V) adalah 0,725 mdt
α=kedalamantangkai (h ),yaitukedalamanpelampungyangtenggelam
kedalamanair (d )
α= 20150
=0,13
Koefisien k=1−0,116 ¿
Maka debit aliran air yang diperoleh menggunakan area velocity
method pada lembah Sungai Code yang lurus adalah:
Q ¿A×k×V
15
Q ¿12×0,8×0,72
Q=7 m3dt
Gambar 3. Sungai dengan lembah berkelok
Pengambilan data untuk pengukuran debit aliran pada sungai di
Gambar 3 dilakukan pada pukul 15.02 WIB, disaat hujan, dan
didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1.2. Hasil Pengukuran pada Lembah Sungai Berkelok
Lebar
sungai (m)
Kedalaman
tangkai (cm)
Kedalaman air
(cm)
Waktu
(detik)10 20 150 16.5
16.518
15.7
16
Dari data pengukuran di atas jika dimasukan ke persamaan
debit, maka:
Luas penampang basah A=KedalamanAir×LebarSungaiA=1,5m×10m=15m2
Kecepatan pelampung (V)=JarakWaktu,
Vi=1016.5
=0,6 mdt
Vii=10
16.5=0.6 m
dt
Viii=1018
=0.6 mdt
Viv=10
15.7=0.6 m
dt
Jadi kecepatan pelampung (V) adalah 0.6 mdt
α=kedalamantangkai (h ),yaitukedalamanpelampungyangtenggelam
kedalamanair (d )
α=20150
=0,13
Koefisien k=1−0,116 ¿
Maka debit aliran air yang diperoleh menggunakan area velocity
method pada lembah Sungai Code yang lurus adalah:
Q ¿A×k×VQ=15×0,8×0,6
Q=7,2 m3dt
17
Dari kedua hasil pengukuran dan penghitungan debit
aliran air menggunakan area velocity method tersebut di dapatkan
selisih angka sebesar 0,2 m3dt dengan debit aliran pada lembah
sungai yang berkelok lebih besar dibandingkan dengan debit
aliran pada sungai yang berlembah lurus. Perbedaan ini dapat
disebabkan oleh perbedaan lebar sungai. Selain lebar sungai
data yang lain relatif sama.
Gambar 3.1 Pengukuran pada Lembah Sungai yang Berkelok
Muatan Suspensi
Muatan suspensi yang menjadi sampel, diambil pada
pinggiran point bar (gosong sungai) Sungai Code dengan metode
point integrating, karena pada saat dilakukan pengambilan data
untuk pengukuran Sungai Code sedang mengalami debit puncak
(banjir) karena hujan. Sedimen yang sudah diambil kemudian
diukur besar butirannya menggunakan ayakan khusus, setiap
18
ayakan memiliki kode angka pada masing-masing rantangnya,
angka-angka ini kemudian dikonversikan menggunakan rumus:
φ= 110
inch
Gambar 4. Sample Sedimen (Suspensi)
Gambar 5. Ayakan sample sedimen
Setelah sampel muatan suspensi diayak, didapatkan hasil
konversi sebagai berikut:
Tabel 1.3 Ukuran Butir Sedimen
19
KODE UKURAN BUTIR
(inch)
UKURAN BUTIR
(cm)
UKURAN BUTIR
(mm)10 0,1 0,254 2.5420 0,5 0,127 1.2740 0,025 0,0635 0,63560 0,016 0,04064 0,406480 0,0125 0,03175 0,3175100 0,01 0,0254 0,254
Dari ukuran butir yang telah dikonversikan di atas lalu
kita cocokan dengan kurva Hjulstorm (1935) di bawah ini:
Gambar 6. Kurva Hjulstorm (1935)
Untuk sedimen yang berada pada rantang ayakan dengan
kode 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 berkekuatan pelampung 0,6 mdt
berada pada zona erosi dengan material yang berbentuk pasir.
20
Gambar 7. Hasil Ayakan Pasir dan Sampel Batu Andesit
Bentuklahan Fluvial Sungai
Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari tentang
geometri (bentuk dan ukuran), jenis, sifat dan perilaku
sungai dengan segala aspek dan perubahannya dalam dimensi
ruang dan waktu. Sungai akan terbentuk sesuai dengan kondisi
geografi, ekologi, dan hidrologi daerah setempat, serta dalam
perkembangannnya akan mencapai kondisi keseimbangan
dinamiknya (Kern, 1994 dalam Maryono, 2005). Kondisi
geografi menentukan letak dan bentuk alur sungai memanjang
dan melintang. Ekologi menentukan tampang melintang dan
keragaman hayati serta faktor resistensi sungai, sedangkan
hidrologi menentukan besar kecil dan frekuensi aliran sungai.
Disamping ketiga faktor tersebut, aktivitas manusia di sungai
turut mempengaruhi perubahan morfologi sungai, baik dalam
skala kecil, seperti akibat dari adanya penambang pasir
sungai secara tradisional, maupun dalam skala besar seperti
pembangunan Sabo DAM dan pelurusan alur sungai. Dengan
demikian, morfologi sungai akan menyangkut juga sifat dinamik21
sungai dan lingkungannya yang saling terkait. Morfologi
sungai akan mengalami perkembangan baik secara memanjang
ataupun melintang. Suatu aktivitas atau kejadian di wilayah
sungai akan menyebabkan perubahan baik fisik maupun biotik
dengan waktu yang lebih cepat dari perubahan secara alamiah.
Pada Sungai Code ini, bentuklahan yang teramati adalah
bentuklahan deposisi berupa gosong pasir dan gosong lengkung
dalam. Teramati juga bekas-bekas erosi pada bibir lembah
sungai. Hasil bentukan lahan seperti ini bisa terjadi karena
material sedimen yang diterima oleh Sungai Code pada musim
penghujan memiliki jumlah yang banyak, begitupun dengan
kecepatan aliran airnya yang deras.
Gambar 8. Gosong Pasir dan Gosong Lengkung Dalam
22
Gambar 8. Bekas-bekas Erosi
KESIMPULAN
Sungai Code merupakan salah satu sungai yang terdapat
dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak. Sungai ini berhulu
dari wilayah Gunungapi Merapi, kemudian bergabung dengan
Sungai Opak sebagai sungai utama di sekitar escarpment
Pegunungan Baturagung (Ashari, 2010). Sungai ini memiliki
kedudukan penting karena melalui wilayah Kota Yogyakarta yang
memiliki kepadatan penduduk tinggi. Aktivitas Sungai Code
sepanjang waktu banyak berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat sehingga perlu adanya kajian mengenai
karakteristik geomorfologi sungai ini khususnya mengenai
proses yang masih berlangsung. Kestabilan dasar alur Sungai
Code dipengaruhi oleh material Gunungapi Merapi berupa
batuan, pasir, dan lumpur. Dinamika Sungai Code dipengaruhi
oleh kondisi fisik wilayah, juga dipengaruhi oleh aktivitas
Gunungapi Merapi. Sedimen yang terangkut aliran Sungai Code
berasal dari agregat material hasil erupsi yang tererosi di
23
wilayah yang lebih tinggi yang dialirkan melalui sungai-
sungai sebelumnya dan berasal dari selokan mataram. Dari
sedimen yang diambil sampel, sedimen yang berada pada rantang
ayakan kode 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 dengan kekuatan
pelampung 0,6 mdt berada pada zona erosi dengan material yang
berbentuk pasir. Pada Sungai Code ini, bentuklahan yang
teramati adalah bentuklahan deposisi berupa gosong pasir dan
gosong lengkung dalam. Teramati juga bekas-bekas erosi pada
bibir lembah sungai. Hasil bentukan lahan seperti ini bisa
terjadi karena material sedimen yang diterima oleh Sungai
Code pada musim penghujan memiliki jumlah yang banyak,
begitupun dengan kecepatan aliran airnya.
24
Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa bentuk pola
aliran Sungai Code yang cocok dengan gambar di atas ini
adalah suspended load dengan sungai yang berkelok dengan
adanya beberapa bentuklahan fluvial berupa beberapa gosong di
pinggirannya.
25
DAFTAR PUSTAKA
Asdak, C. 1995. Hidrologi Dan Pengelolaan DAS. Bandung: Fakultas
Pertanian
Universitas Padjajaran.1989.
Burgh, P. V. D. 1972. Veld Book of Apllied Hydrology. New York :
Mc
Graw-Hill Book Company.
Pramono, Heru dan Arif Ashari. 2014. Geomorfologi Dasar.
Yogyakarta: UNY Press.
Seyhan, Ersin. 1979. Application of Statistical Methodes to Hidrology.
Amsterdam :Intitute of Earth Science Free University.
Soewarno. 1991. Hidrologi Pengukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai
(Hidrometri). Nova: Bandung.
26