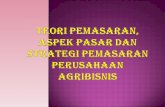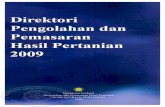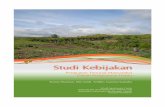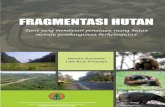TUGAS PEMASARAN HASIL HUTAN ANALISIS PEMASARAN HASIL HUTAN DUSUN PRINGSURAT DESA KEDUNGKRIS GUNUNG...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of TUGAS PEMASARAN HASIL HUTAN ANALISIS PEMASARAN HASIL HUTAN DUSUN PRINGSURAT DESA KEDUNGKRIS GUNUNG...
TUGAS PEMASARAN HASIL HUTAN
ANALISIS PEMASARAN HASIL HUTAN DUSUN PRINGSURAT DESA
KEDUNGKRIS GUNUNG KIDUL
Disusun Oleh:
Benedictte Putri Wikandari
10/300969/KT/06709
LABORATORIUM EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN
BAGIAN MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
2013BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Keberadaan hutan merupakan sumber mata pencaharian bagi
masyarakat yang tingkat perekonomiannya masih rendah karena
memanfaatkan sumberdaya hutan secara tradisional. Seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula permintaan
kebutuhan masyarakat akan hasil hutan baik kayu maupun non kayu
sesuai dengan kebutuhan. Mengingat hal tersebut sebagian besar
penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan hasil
hutan dan jasa hutan (DEPHUTBUN, 1998).
Pemasaran Hasil Hutan adalah konsep atau teori yang terkait
dengan analisis efisiensi dan strategi pengembangan pemasaran
komoditi hasil hutan dengan menggunakan variabel ekonomi, antara
lain: elastisitas, marjin pemasaran, marjin keuntungan, koefisien
korelasi, dan regresi pada marketing mix pemasaran hasil hutan
baik regional maupun internasional (Wahyu, 2009)
Sejarah terbentuknya pengelolaan hutan rakyat di sini, dari
Sumber Gedhe, bagian kanan, kiri, timur, selatan desa Kedungkris,
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul ini dikelilingi hutan
negara. Oleh Belanda karena tanahnya gundul kemudian ditanami
tanaman Jati.Ditetapkan dalam kesepakatan bila pohon dapat
ditebang setelah etat volume 50 m3 dijual tadinya di koperasi
diameter dibatasi khususnya 20 cm dengan syarat kayu bersertifikat
tetapi belum mencakup semua jenis kayu. Kayu kebanyakan dijual ke
tengkulak atau pengepul tidak dikoperasi. Apabila tebang butuh
saat butuh sekali uang tetapi diameter masih 15 cm maka dipinjami
dulu dari koperasi lalu diganti jaminan pohon yang mau ditebang
milik koperasi.
II. Tinjauan Pustaka
Usahatani adalah etiap organisasi dari alam, tenaga kerja, dan
modal yang ditunjukkan kepada produksi di lapangan pertanian.
Ketatalaksanaan organisasi ini dapat diusahakan oleh seorang
ataupun sekumpulan orang. Dalam hal ini istilah usahatani
mencangkup pengertian luas mulai dari bentuk sederhana yaitu hanya
untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai pada bentuk yang paling
modern yaitu mencari keuntungan atau laba (Bakhtiar Rifai dalam
Tjakrawiralaksana, 1987).
Menurut Tjakrawiralaksana (1987), organisasi usaha tani terdiri
dari 4 unsur pokok, yaitu lahan, kerja, modal, dan pengelolaan.
Keempat unsur ini dalam usaha tani kedudukannya sama pentingnya.
Lahan dan kerja seringkali disebut sebagai unsur produksi asli,
kedua unsur ini adalah yang pertama-tama digunakan oleh manusia
dalam kegiatan bertani. Sedangkan modal disebut sebagai unsur
produksi yang diturunkan dari kedua unsur yang pertama.
Pengelolaan adalah unsur produksi yang berlainan sifatnya dari
ketiga unsur sebelumnya, namun berperan sebagai dirigen untuk
menggerakkan ketiga unsur tersebut.
Secara sederhana agroforestry adalah kegiatan pengkombinasian
antara tanaman pertanian dengan tumbuhan berkayu (pohon). Definisi
yang lebih luas dikemukakan oleh para ilmuwan yang mengakibatkan
definisi agroforestry ini beragam tergantung dari sudut pandang
pembuat definisi dan latar belakang budaya tempat agroforestry
diterapkan. Menurut Hairiah dkk (2003)
Sistem pengelolaan yang berbeda-beda itu dapat disebabkan oleh
perbedaan kondisi biofisik (tanah dan iklim), perbedaan
ketersediaan modal dan tenaga kerja, serta perbedaan latar
belakang sosial- budaya. Oleh karena itu produksi yang dihasilkan
dari sistem agroforestri juga bermacam-macam, misalnya buah-
buahan, kayu bangunan, kayu bakar, getah, pakan, sayur-sayuran,
umbi-umbian, dan biji-bijian (Widianto dkk, 2003).
Beberapa kegiatan yang dikerjakan dan/atau diatur secara bersama-
sama akan lebih produktif dan efisien, antara lain:
a. Pengelolaan produksi, misalnya (a) penyediaan bibit tanaman
berkualitas, (b) pekerjaan pemangkasan/prunning, (c) pemanenan
kayu dan buah-buahan, serta (d) penanganan dan pengolahan pasca
panen.
b. Pengelolaan pemasaran, misalnya (a) pengaturan panen dan
pemasaran, yakni memenuhi kuantitas, kualitas dan pengiriman yang
sesuai dengan permintaan pasar, (b) pengaturan alat angkutan yang
murah dan lancar, serta (c) pemilahan ukuran dan kualitas.
c. Pengelolaan keuangan, misalnya tabungan dan simpan-pinjam antar
petani atau dengan pihak perbankan.
Menurut Irwanto (2008), ada beberapa keunggulan agroforestry
dibandingkan sistem penggunaan lahan lainnya, yaitu dalam hal:
1. Produktivitas (Productivity)
Dari hasil penelitian dibuktikan bahwa produk total sistem
campuran dalam agroforestry jauh lebih tinggi dibandingkan pada
monokultur (penanaman satu jenis). Adanya tanaman campuran
memberikan keuntungan, karena kegagalan satu komponen/jenis
tanaman akan dapat ditutup oleh keberhasilan komponen/jenis
tanaman lainnya.
2. Diversitas (Diversity)
Adanya pengkombinasian dua komponen atau lebih daripada sistem
agroforestry menghasilkan diversitas (keragaman) yang tinggi, baik
menyangkut produk maupun jasa. Dengan demikian dari segi ekonomi
dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.
Sedangkan dari segi ekologi dapat menghindarkan kegagalan fatal
pemanen sebagaimana dapat terjadi pada penanaman satu jenis
(monokultur).
3. Kemandirian (Self-regulation)
Diversifikasi yang tinggi dalam agroforestry diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan petani kecil dan
sekaligus melepaskannya dari ketergantungan terhadap produk produk
luar. Kemandirian sistem untuk berfungsi akan lebih baik dalam
arti tidak memerlukan banyak input dari luar antara lain pupuk dan
pestisida, dengan diversitas yang lebih tinggi daripada sistem
monokultur.
4. Stabilitas (Stability)
Praktek agroforestry yang memiliki diversitas dan produktivitas
yang optimal mampu memberikan hasil yang seimbang sepanjang
pengusahaan lahan, sehingga dapat menjamin stabilitas (dan
kesinambungan) pendapatan petani
Menurut Sardjono dkk (2003), ada beberapa klasifikasi agroforestry
antara lain: Agrisilvikultur (Agrisilvicultural Systems),
Silvopastura (Silvopastural Systems), Agrosilvopastura
(Agrosilvopastural Systems)
Peran dan Fungsi Agroforestry Terhadap Aspek Ekonomi
Menurut Widianto dkk (2003), ada beberapa peran dan fungsi
agroforestry terhadap aspek ekonomi, antara lain:
1. Aspek Ekonomi Agroforestry Pada Tingkat Kawasan
Sistem agroforestry memiliki beberapa komponen berbeda yang saling
berinteraksi dalam satu sistem (pohon, tanaman dan/atau ternak)
membuat sistem ini memiliki karakteristik yang unik, dalam hal
jenis produk, waktu untuk memperoleh produk dan orientasi
penggunaan produk. Jenis produk yang dihasilkan sistem
agroforestry sangat beragam, yang bisa dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu:
a. Produk untuk komersial misalnya bahan pangan, buah-buahan,
hijauan makanan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, daun, kulit,
getah, dan lain-lain.
b. Pelayanan jasa lingkungan, misalnya konservasi sumber daya alam
(tanah, air, dan keanekaragaman hayati)
Pola tanam itu dapat dilakukan dalam suatu unit lahan pada waktu
bersamaan (simultan) atau pada waktu yang berbeda/berurutan
(sekuensial), melibatkan beraneka jenis tanaman tahunan maupun
musiman. Pola tanam dalam sistem agroforestry memungkinkan
terjadinya penyebaran kegiatan sepanjang tahun dan waktu panen
yang berbeda-beda, mulai dari harian, mingguan, musiman, tahunan,
atau sewaktu-waktu.
Keragaman jenis produk dan waktu panen memungkinkan penggunaan
produk yang sangat beragam pula. Tidak semua produk yang
dihasilkan oleh sistem agroforestry digunakan untuk satu tujuan
saja. Ada sebagian produk yang digunakan untuk kepentingan
subsisten, sosial atau komunal dan komersial maupun untuk jasa
lingkungan.
2. Agroforestry dan Penyediaan Lapangan Kerja
Sistem agroforestry membutuhkan tenaga kerja yang tersebar merata
sepanjang tahun selama bertahun-tahun. Hal ini mungkin terjadi
karena kegiatan berkaitan dengan berbagai komponen dalam sistem
agroforestry yang memerlukan tenaga kerja terjadi pada waktu yang
berbeda-beda dalam satu tahun.
Kebutuhan tenaga kerja dalam sistem pertanian monokultur bersifat
musiman: ada periode di mana kebutuhan tenaga sangat besar
(misalnya musim hujan) dan periode di mana tidak ada kegiatan
(musim kemarau). Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan
kebutuhan tenaga kerja pada sistem agroforestry justru lebih
rendah dibandingkan sistem pertanian monokultur, baik tanaman
semusim
maupun tanaman tahunan.
Dalam perkembangan praktek agroforestry terdapat dua periode yang
perlu diperhatikan, yaitu:
a. Periode pengembangan, mulai saat persiapan sampai dengan mulai
memberikan keuntungan
b. Periode operasi, mulai memberikan keuntungan (cash flow
positif).
Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi pemasaran serta
memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Lembaga pemasaran
sangat beragam tergantung jenis produk yang dipasarkan. Beberapa
contoh lembaga pemasaran adalah sebagai berikut: produsen,
tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, agen penjualan,
pengecer, broker, eksportir serta importir. Pola-pola pemasaran
yang terbentuk selama pergerakan arus komoditi pertanian dari
petani produsen ke konsumen akhir disebut sistem pemasaran
(Sudiyono, 2004).
Secara umum, pola saluran tataniaga pertanian dapat dilihat pada
Gambar:
Margin Tataniaga
Ada dua pengertian margin tataniaga. Pertama, margin tataniaga
adalah perbedaan harga yang dibayar konsumen dengan harga yang
diterima petani. Kedua, margin tataniaga adalah imbalan yang
diberikan konsumen kepada lembaga tataniaga. Komponen margin
tataniaga terdiri dari biaya tataniaga atau biaya fungsional
(functional cost) yaitu biaya-biaya yang diperlukan lembaga-
lembaga tataniaga untuk melakukan fungsi-fungsi tataniaga dan
keuntungan (profit) lembaga tataniaga.
Selain itu, margin tataniaga juga dapat diketahui dengan
menghitung selisih harga antara yang dibayar konsumen dengan yang
diterima petani, yaitu dihitung dengan rumus:
M = Pr – Pf
Keterangan:
produsen konsumen
pengecerprodusen konsumen
produsen pengepul pengecer konsumen
M = margin pemasaran
Pr = harga di tingkat konsumen
Pf = harga di tingkat petani
Besarnya persentase yang diterima petani (farmer share) dari harga
tingkat konsumen
dihitung menggunakan rumus:
Sp = Pf/ Pr x 100%
Keterangan:
Sp = farmer share
Pf = harga di tingkat petani
Pr = harga di tingkat konsumen
Menurut Soekartawi (2002), besarnya biaya pemasaran berbeda-beda
tergantung faktor: macam komoditi pertanian, lokasi pengusahaan,
macam dan peranan lembaga pemasaran dan efektifitas pemasaran.
Semakin pendek rantai tataniaga, maka biaya tataniaga semakin
rendah, margin tataniaga juga semakin rendah dan harga yang harus
dibayar konsumen juga rendah serta harga yang diterima produsen
tinggi.
III. Rumusan Masalah:
1. Bagaimana sistem pemasaran yang ada di Desa KedungKris,
Gunung kidul?
2.
Bagaimana kaitan keunggulan aspek ekonomi pada penanaman
agroforestry di Desa Kedung Kris?
3. Bagaimana sistem tataniaga di Desa Kedung Kris, Gunung Kidul?
IV. Tujuan
1. Mengetahui sistem pemasaran yang ada di Desa KedungKris,
Gunung Kidul.
2. Mengetahui kaitan keunggulan aspek ekonomi pada penanaman
agroforestry di Desa KedungKris.
3. Mengetahui sistem tataniaga di Desa KedungKris, Gunung Kidul.
BAB II
METODE PENELITIAN
I. Metode Penelitian:
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi di Desa KedungKris, Kecamatan Nglipar, BDH Playen. Data ini
di ambil pada 25-26 Mei 2013
Alat dan Bahan
Pengambilan data menggunakan kalkulator, kuisioner, peralatan
inven.
Metode Pengumpulan data
Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer
berupa pengamatan langsung dan observasi. Juga dilakukan wawancara
dengan metode simple random sampling.
BAB III
ISI
Hasil dan Pembahasan:
No Jenis Ternak Kuantitas Satuan Harga /satuan
Jumlah Jenis lahan
1 Kayu Tebang butuh
HR
Krencek-kayubakarEmpon-empon 10 kilo 1 kilo 8000 80
ribuPekarangan
garut 40 kilo 1 kilo 2000 80 ribu
pekarangan
NoJenis Pohon
Keliling diameter t
Keterangan
1 jati 48 15.28662 1 2 jati 39 12.42038 1 3 jati 60 19.10828 1 4 jati 41 13.05732 7 5 jati 52 16.56051 8 6 jati 43 13.69427 8 7 jati 59 18.78981 1 8 jati 53 16.87898 1 9 jati 55 17.51592 1
10 jati 38 12.10191 1 11 mahoni 32 10.19108 8 12 mahoni 42 13.3758 1 13 mahoni 32 10.19108 1
14 mahoni 42 13.3758 9 15 mahoni 52 16.56051 1 16 mahoni 33 10.50955 9 17 akasia 34 10.82803 1 18 mahoni 66 21.01911 1 19 mahoni 37 11.78344 1 20 mahoni 33 10.50955 1 21 mahoni 40 12.73885 1 22 mahoni 32 10.19108 1 23 akasia 64 20.38217 1 24 mahoni 53 16.87898 1 25 akasia 51 16.24204 1 26 mahoni 33 10.50955 1 27 mahoni 47 14.96815 1 28 sengon 112 35.66879 1 29 30
JenisKeliling
Diameter
Tinggi
Jumlah pohon Volume
Produksibuah
cm cm m m3 Belum sudah
Kelapa 8025.4777
1 14 10.71337579
6 √
Kelapa 7523.8853
5 15 10.67177547
8 √
Kelapa 6019.1082
8 10 10.28662420
4 √Bambu
Analisis Marjin Pemasaran Empon-Empon:
Analisis Marjin Pemasaran Jati
Analisis Marjin Pemasaran Kayu Mahoni
Diversifikasi Produk
Diversitas produk karena ditanam dengan cara agroforestry
mendapat keuntungan maksimal. Diversifikasi yang tinggi dalam
agroforestry diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,
dan petani kecil dan sekaligus melepaskannya dari ketergantungan
terhadap produk produk luar. Kemandirian sistem untuk berfungsi
akan lebih baik dalam arti tidak memerlukan banyak input dari luar
antara lain pupuk dan pestisida, dengan diversitas yang lebih
tinggi daripada sistem monokultur. Selain itu produk yang
komersial dan dapat dijual termasuk hijauan pakan ternak, kulit,
getah, bahkan kayu bakar.
Lembaga Pemasaran
Lembaga pemasaran yang terkait adalah Produsen dan Konsumen
dengan perbedaan tingkat harga di kedua subjek ini. Dengan saluran
pemasaran Produsen-Pengepul-Pengecer-Konsumen.
Pada tingkat Petani, biasanya petani mendapat keuntungan sedikit
dikarenakan harga jual atau harga tingkat konsumen lebih rendah
seperti contoh mahoni dalam bentuk kayu gelondongan dijual dengan
harga 1 juta dengan marjin 0,5 juta karena harga pasar atau harga
konsumen sebenarnya 1,5 juta. Sedang keuntungan yang didapat juga
0,5 juta juga.
Pada tingkat Pengepul, harga lebih mahal karena dikenai harga
beli dan transportasi dan tawar menawar.
Pada tingkat Pengecer, sama terjadi tawar-menawar tapi biasanya
harga melunjak karena pengecer semena-mena. Pada kayu jati harga
pasar 6 juta, dengan itu produsen mendapat keuntungan 2 juta dari
harga beli dan marjin 2 juta dari harga beli harga di tingkat
konsumen dikurangi harga di tingkat petani.
Semua melalui satu saluran yaitu koperasi, koperasi berdiri
setelah penetapan kayu komersial boleh di tebang dengan keliling
tertentu yaitu 32 ke atas, tetapi masih ada lembaga sertivikasi
yaitu SLVK yang menangani soal legalitas kayu, dengan masuknya
SVLK ke koperasi maka kayu komersial yang legal 40-50 cm untuk
keliling untuk diperdagangkan.
Dari Hutan Rakyat tersebut yang telah diinven dan didapatkan
perhitungannya dalam presentase dan marjinnya dan tentunya dalam
aspek tataniaga atau distribusi, sebaiknya untuk melalui koperasi
dengan kisaran harga di tingkat konsumen untuk empon-empon 8000
per kilogramnya, 4 juta per m3 untuk log jati dan 1,5 juta untuk
log mahoni.
Terbukti bahwa menurut Soekartawi (2002), besarnya biaya
pemasaran berbeda-beda tergantung faktor: macam komoditi
pertanian, lokasi pengusahaan, macam dan peranan lembaga pemasaran
dan efektifitas pemasaran. Semakin pendek rantai tataniaga, maka
biaya tataniaga semakin rendah, margin tataniaga juga semakin
rendah dan harga yang harus dibayar konsumen juga rendah serta
harga yang diterima produsen tinggi.
n
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan:
1. Sistem pemasaran di Dusun Pringsurat, Desa KedungKris bahwa
dilakukan di koperasi, warga mereka menanam dan menjual kayu
dengan syarat pelestarian alam dan dilakukan sertifikasi terhadap
legalitas kayu.
2. Kaitan keunggulan aspek ekonomi pada penanaman agroforestry
di Desa KedungKris adalah pada diversifikasi produk, karena produk
hasil hutan yang komersial dan pengurangan sifat monokultur
sehingga fungsi lahan dapat dimaksimalkan untuk aspek ekonomi.
3. Sistem tataniaga di Desa KedungKris, Gunung Kidul terdiri
produsen, pengepul, pengecer, dan konsumen. Lembaga pemasaran yang
terkait adalah Produsen dan Konsumen dengan perbedaan tingkat
harga di kedua subjek yang disebut marjin yaitu tingkat harga
konsumen dikurangi tingkat harga konsumen. Marjin terbesar adalah
di tingkat Pengecer karena biasanya harga melonjak dan keuntungan
masuk ke produsen lebih banyak.
Daftar Pustaka:
Andayani, Wahyu. 2009. Buku Ajar Pemasaran Hasil Hutan.
Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
Anonim. Jurnal Tata Niaga Pertanian. Diakses 21 Desember 2013.
Cahyono, Eko Agung. 2002. Jurnal Analisis Pemasaran Hasil Hutan