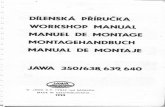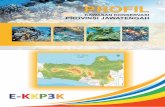Kasus Wisata dan “Ekonomi Kentang” di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah : Lesson Learned untuk...
Transcript of Kasus Wisata dan “Ekonomi Kentang” di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah : Lesson Learned untuk...
6 Januari 2015
Kasus Wisata dan “Ekonomi Kentang” di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah : Lesson Learned untuk Cibulao, Tugu Utara Puncak, Jawa Barat
Unggul Sagena NRP H152130191 Mandala Eka Putra NRP H152120161
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Institut Pertanian Bogor
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e2
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Daftar Isi Daftar Tabel ............................................................................................................................................ 3
Daftar Gambar ........................................................................................................................................ 3
Kasus Wisata dan “Ekonomi Kentang” di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah : Lesson Learned ........... 4
Latar Belakang ..................................................................................................................................... 4
Struktur Bab ........................................................................................................................................ 4
Dataran Tinggi Dieng ........................................................................................................................... 4
Dieng : Potensi dan Kondisi ................................................................................................................. 4
Penurunan Kualitas Wisata dan “Ekonomi Kentang” ..................................................................... 5
Kondisi Sosial Ekonomi di Sekitar Kawasan Dieng .......................................................................... 6
Permasalahan dan Dampak ................................................................................................................ 7
Analisis dan Rekomendasi ................................................................................................................. 13
Lesson Learned dan Rekomendasi .................................................................................................... 17
Antara Kawasan Dieng dan Kawasan Puncak (Cibulao) ................................................................ 19
Referensi ........................................................................................................................................... 24
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e3
Daftar Tabel
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng 5
Tabel 2 Data Penyimpangan penggunaan lahan kawasan Dieng Kabupaten Wonosobo
6
Tabel 3. Sejarah perkembangan lingkungan kawasan Dieng 7
Tabel 4. Permasalahan dan Penyebab : Dieng 12
Tabel 5 Upaya Instansi Dalam Kegiatan Konservasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng 15
Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi 19
Tabel 7 Lokus Kawasan dan Karakteristiknya 20
Tabel 8. Matriks Permasalahan Desa di Dieng dan Puncak 20
Tabel 9. Aspek Rekomendasi Solusi di Dieng dan Puncak (Cibulao) 22
Daftar Gambar
Gambar 1 Potensi Wisata Dieng 5
Gambar 2. Longsor di Banjarnegara, Desember 2014 9
Gambar 3. Peta Batas DAS 9
Gambar 4. Peta Kerusakan Lahan dan Lereng 9
Gambar 5. Peta Kerusakan Lahan 10
Gambar 6. Peta Tingkat Bahaya Erosi 10
Gambar 7. Kawasan Lindung dengan kondisi tutupan lahan di Desa Sembungan Kabupaten Wonosobo
11
Gambar 8. Alih fungsi Lahan yang dilakukan masyarakat desa sekitar lereng Dieng dengan olahan hasil tanaman kentang
11
Gambar 9 Pemukiman penduduk yang merambah kawasan lindung di Desa Dieng 12
Gambar 10 Lahan dengan teknik pengolahan tanpa kaidah konservasi di Desa Sembungan 12
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e4
Kasus Wisata dan “Ekonomi Kentang” di Dataran Tinggi Dieng, Jawa
Tengah : Lesson Learned
Latar Belakang Sebagai bagian dari buku kecil untuk rekomendasi pengelolaan Hutan warga Dusun Cibulao, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bagian ini membahas kasus Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah yang memiliki beberapa karakteristik masalah yang serupa. Dalam tulisan ini, diharapkan didapat pembelajaran (lesson learned) dari kasus Dieng untuk menjadi masukan bagi Kawasan Puncak, Bogor, khususnya Dusun Cibulao yang menjadi target buku ringkas.
Struktur Bab Bab yang berisi tentang kasus pengelolaan hutan wisata di Dieng, Jawa Tengah ini disusun sebagai berikut :
1. Introduksi ke Kasus Dataran Tinggi Dieng beserta identifikasi berbagai masalah dan upaya saat ini yang dapat dianalisa dan menjadi pengetahuan tambahan dan “pembelajaran” (lesson learned) untuk pengelolaan di “Dataran Tinggi” Puncak, Jawa Barat pada umumnya dan Kampung Cibulao pada khususnya.
2. Analisa, Lesson Learned, Rekomendasi.
Dataran Tinggi Dieng
Dataran Tinggi Dieng, yang terbentang di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara merupakan kasus yang menarik sebagai salah satu contoh pengelolaan yang dapat juga diterapkan di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, maupun untuk kasus di dusun Cibulao sebagai referensi dikarenakan karakteristik masalah dan lanskap geografis yang hampir sama.
Untuk itu, berikut dipaparkan mengenai state-of-affairs Dataran Tinggi Dieng untuk kemudian memetakan rekomendasi untuk lesson learned masyarakat Cibulao dalam bentuk pointers maupun tabel matriks yang mudah dipahami.
Dieng : Potensi dan Kondisi
Dataran Tinggi Dieng menjadi wilayah yang menarik karena merupakan dataran tinggi terluas kedua di dunia setelah Nepal. Terletak di ketinggian sekitar 2.063 m diatas permukaan air laut dengan dikelilingi oleh bukit dan pegunungan membuat Dieng memiliki kondisi udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Ditinjau dari sejarah terbentuknya, kawasan ini dulunya merupakan kepundan gunung berapi yang sangat luas yang kemudian berubah menjadi rawa-rawa dan danau dan pada akhirnya berubah menjadi daratan.
Selain itu pada awal abad ke-19 ditemukan bangunan candi di sekitar Dataran Tinggi Dieng dan 13 buah enkripsi diantara reruntuhan candi yang salah satunya menyebut nama Dihyang, yang diyakini sebagai asal nama Dieng, yang berarti tempat tinggi yang suci. Akses utama menuju Dataran Tinggi Dieng yang paling populer, mudah dan sering dilalui adalah dari arah pusat kota Wonosobo menuju ke arah utara dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit. Kondisi ini menyebabkan Dieng lebih identik sebagai bagian dari Kabupaten Wonosobo, walaupun sebenarnya
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e5
wilayah Dataran Tinggi Dieng dan kawasan wisatanya merupakan gabungan wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
Objek wisata yang menjadi daya tarik wisata di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng adalah Objek wisata alam dan Objek wisata budaya. Potensi Wisata yang ada di Dataran Tinggi Dieng dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1. Potensi Wisata Dieng
Penurunan Kualitas Wisata dan “Ekonomi Kentang”
Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng mengalami masa jayanya pada tahun 1990-an ketika jumlah wisatawan mancanegara mencapai 20-40 ribu pengunjung. Sektor wisata telah mampu membawa manfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat, ditandai dengan berkembangnya bisnis di bidang jasa yaitu hotel, restoran dan penjualan oleh-oleh dan cindera mata. Namun kondisi ini tidak bisa bertahan lama, karena sejak tahun 1998 jumlah pengunjung terutama wisatawan mancanegara menurun drastis. Kondisi ini terutama disebabkan krisis sosial konomi dan politik Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan karena terjadinya penurunan kualitas objek wisata dan lingkungan di sekitarnya.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
No. Tahun Jumlah Wisatawan
Domestik Mancanegara
1. 1990 81.674 42.987
2. 1991 80.067 39.758
3. 1992 81846 32.761
4. 1993 79.169 30.961
5. 1994 82.198 28.647
6. 1995 76.398 26.197
7. 1996 74.398 24.579
8. 1997 71.864 22.757
9. 1998 54.923 11.440
10. 1999 69.054 10.993
11. 2000 61.162 11.338
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e6
12. 2001 57.970 5.824
13. 2002 61.398 7.338
14. 2003 55.516 4.716
15. 2004 61.380 6.676
16. 2005 57.763 6.838
17. 2006 57.048 4.728
18. 2007 77.169 5.231
Sumber : BPS Banjarnegara dan Wonosobo (2006)
Masyarakat di sekitar kawasan wisata sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan komoditas utama kentang dan dengan pola bertanam yang mengakibatkan erosi tanah yang cukup tinggi. Pertanian tanaman kentang yang membawa dampak erosi tanah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga akibatnya diantaranya adalah menurunya kualitas objek wisata air (Telaga Warna dan Telaga Pengilon) akibat erosi tanah yang masuk ke telaga, pemandangan di wilayah Dieng tidak lagi dipenuhi oleh pemandangan pohon-pohon cemara, erosi menyebabkan banjir lumpur di banyak tempat, dan terganggunya pemandangan akibat pembongkaran pupuk kandang di sepanjang pinggir jalan raya.
Penduduk memang mengakui bahwa terjadi penurunan kualitas tanah dan seringnya longsor, namun daya tarik peningkatan ekonomi, seperti yang disebut Arbangiyah (2012) sebagai “ekonomi kentang” dimana menurut studi di salah satu desa yaitu Desa Sembungan, banyaknya kontribusi ekonomi peningkatan kesejahteraan dari penduduk sebagai petani kentang menjadikan banyak “haji kentang”, bahkan di lapangan, penduduk yang secara profesi di dalam data statistik bukan petani pun memiliki usaha sampingan sebagai petani kentang.
Kondisi Sosial Ekonomi di Sekitar Kawasan Dieng
Kawasan Dataran Tinggi Dieng (± 2.095 meter dpl) yang terletak di dua kabupaten yaitu Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah tengah menghadapi ancaman akan degradasi lahan lingkungan yang parah. Timbulnya degradasi lahan tersebut disebakan rasio kepadatan penduduk yang tinggi (rata-rata 100 jiwa/km2 ) dengan kepemilikan lahan yaitu rata-rata sebesar 0,1 ha mengakibatkan besarnya tekanan sumberdaya alam yang ada, berupa pengalihan fungsi lahan kawasan lindungan menjadi lahan budidaya pertanian intensif khususnya pada pengembangan budidadaya tanaman kentang. Desakan akan pengalih fungsi lahan kawasan lindung menjadi lahan budidaya disebabkan rendahnya parameter ekonomi dan tingkat pendidikan serta ketergantungan yang tinggi atas keberadaan hutan disekitarnya. Besarnya rasio desakan pemanfaatan lahan dibandingkan dengan tataguna lahan yang didorong oleh motif ekonomi menyebabkan terjadinya penyimpangan(degradasi) alih fungsi lahan. Hal ini dapat kita ambil contoh pada table dibawah tentang rasio penyimpangan lahan Kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo.
Tabel 2. Data Penyimpangan penggunaan lahan kawasan Dieng Kabupaten Wonosobo
Desa Luas Kawasan Lindung (Ha)
Tata Guna Lahan Pemanfaatan Lahan (Ha)
Penyimpangan (%)
Sembungan 530,5 Hutan Lindung Ladang : 218 41,1
Jojogan 81,11 Hutan Lindung Ladang : 73,98 91,2
Dieng 359,6 Hutan Lindung, Cagar budaya
Ladang : 205 Pemukiman : 2
57,8
Sikunang 608,6 Hutan Lindung Ladang : 204,2 33,6
Sumber : Bapeda Kab. Wonosobo (2007), BPS Kabupaten Wonososo (2006)
Oleh karena itu diperlukan penyusunan rencana penataan Kawasan Dieng agar produktivitas dan
jasa lingkungan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal. Sudah barang tentu rencana
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e7
tersebut perlu disusun atas dasar kaidah ekosistem dan konservasi, agar terjadi keseimbangan
antara produktivitas, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam beberapa
tahun terakhir, di kawasan Dieng banyak terjadi pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung.
menjadi kawasan budidaya. Konversi lahan ini yang menyebabkan degradasi lahan dan makin
meluasnya lahan kritis yang menyebar hampir menyeluruh di kawasan Dieng akibat eksploitasi lahan
hutan/pegunungan secara besar-besaran untuk tanaman kentang dan sayuran. Perkembangan
sejarah lingkungan kawasan Dieng terutama yang berkaitan dengan hutan dapat kita lihat pada table
dibawah ini.
Tabel 3. Sejarah perkembangan lingkungan kawasan Dieng
Sumber: Program Studi Perencanaan Wilayah Pedesaan PPS IPB, 2003
Permasalahan dan Dampak
Berdasarkan kondisi state-of-affairs Dieng diatas dan mengacu Purwanto (2004) dan Tim Kerja Pemulihan Kawasan Dieng (TKPKD) Kabupaten Banjarnegara (2012), maka masalah-masalah yang terjadi pada kawasan Dieng dan dampaknya, antara lain:
1. Tingginya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Penggunaan Tanah secara intensif untuk budiaya kentang dengan berbagai macam pupuk berpengaruh pada rrusaknya struktur tanah di kawasan Dieng bertambahnya luas lahan pertanian kentang (ekstensifikasi) yang merambah kawasan hutan lindung dan budaya mengakibatkan rusaknya obyek atraksi ekowisata Dieng. Hal ini berdampak kepada : 1. Turunnya minat wisatawan khususnya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke
Kawasan Dieng sehingga menurunkan kesejahteraan.
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e8
2. Pengolahan lahan pada lahan dengan tingkat kemiringan tinggi tanpa terassering yang memadai dan pembuatan saluran pembuangan air yang memotong kontur, menjadi penyebab utama tingginya tingkat erosi di kawasan ini yang memberikan ekternalitas negatif bagi wilayah di bawahnya.
3. Penggunaan pestisida dan insektisida kimia dalam dosis tinggi juga menyebabkan pencemaran air dan tanah yang menjadikan semakin menurunnya ketersediaan air bersih di wilayah ini.
Beberapa penyebab sehingga masyarakat tetap melakukan budidaya tanaman kentang meskipun tidak lagi memberikan keuntungan yang tinggi antara lain adalah: Masyarakat terlanjur terikat perjanjian/utang dengan lembaga perbankan atau dengan pemodal. Faktor sosial budaya bahwa seseorang dalam pergaulan sosial akan “diorangkan” jika masih melakukan budidaya kentang (TKPKD, 2012). Masyarakat juga belum memiliki kemampuan untuk berpindah pada budidaya komoditas-komoditas yang lebih ramah lingkungan.
2. Penyerobotan tanah milik Perhutani. Kondisi ini terjadi akibat dari kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan “lahan tidur” bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga masyakat menganggap tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Keadaan tersebut diperparah dengan penurunan kualitas kondisi sarana dan prasarana pendukung pariwisata di kawasan Dieng. Penyebab terjadinya masalah internal ini antara lain dikarenakan adanya penduduk pemilik lahan maupun penguasa atas lahan yang melakukan intensifikasi pertanian kentang yang menguntungkan dalam jangka pendek. Perkembangan kemudian petani yang tidak mempunyai lahan kemudian memanfaatkan lahan sebagai “the commons” dan sumber daya bersama. Sehingga masyarakat setempat “mengelola”nya sebagai ladang kentang yang eksensif hingga menimbulkan kentang sebagai komoditi umum masyarakat Dieng, bukan menggantungkan dari pariwisata yang ada, yang selama ini juga tidak berdampak kepada masyarakat lokal. Dampaknya adalah kerusakan lahan akibat over-use dan degradasi lahan yang semakin kritis, menyebabkan longsor dan dalam jangka panjang juga menurunkan kualitas air bersih.
3. Lemahnya peran aparat. Lemahnya peran aparat dalam penindakan kasus perusakan lingkungan dan ekositem Kawasan Dieng disebabkan minimnya jumlah aparat dalam mengawasi kegiatan dengan Luas kawasan Dieng.
4. Faktor Pasar. faktor “eksternal” yang memacu peningkatan kerusakan lingkungan di kawsan
Dieng, yaitu semakin meningkatnya permintaaan kentang di pasaran. Tingginya permintaaan kentang dan mudahnya system pemasaran kentang merupakan pemicu eksternal secara langsung dan tidak langsung keberadaan ekosistem Kawasan Dieng. Hal ini menjadi masalah karena belum adanya kepastian pasar untuk komoditas lain sebagai alternatif pengganti tanaman kentang. Tanpa adanya kepastian pasar dan keuntungan yang lebih menjanjikan dari komoditas kentang yang saat ini telah dibudidayakan oleh masyarakat, berbagai intervensi yang dilakukan baik melalui program pemerintah maupun para pihak lainnya seolah membentur batu karang.
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e9
Gambar 2. Longsor di Banjarnegara, Desember 2014
Gambar 3. Peta Batas DAS
Gambar 4. Peta Kerusakan Lahan dan Lereng
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e10
Gambar 5. Peta Kerusakan Lahan
Gambar 6. Peta Tingkat Bahaya Erosi
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e11
Gambar 7. Kawasan Lindung dengan kondisi tutupan lahan di Desa Sembungan Kabupaten
Wonosobo
Gambar 8. Alih fungsi Lahan yang dilakukan masyarakat desa sekitar lereng Dieng dengan olahan
hasil tanaman kentang
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e12
Gambar 9. Pemukiman penduduk yang merambah kawasan lindung di Desa Dieng
Gambar 10. Lahan dengan teknik pengolahan tanpa kaidah konservasi di Desa Sembungan
Berdasarkan identifikasi diatas, maka dapat dipetakan matriks permasalahan sebagai berikut :
Tabel 4. Permasalahan dan Penyebab : Dieng
Permasalahan Penyebab
Permasalahan yang terkait dengan laju degradasi lahan dan Kerusakan lingkungan
1. Tingginya sedimentasi dan erosi tanah di Kawasan Dieng
2. Pencemaran air di kawasan Dieng yang cukup tinggi.
3. Menurunnya tingkat kesuburan tanah di kawasan Dieng
Permasalahan yang terkait dengan sosial ekonomi masyarakat
1. Pada umumnya petani peduli lingkungan berpendapatan rendah.
2. Pola pikir bahwa budidaya kentang dan sayuran adalah satu-satunya sumber
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e13
pendapatan yang utama 3. Belum berkembangnya alternatif-alternatif
pendapatan bagi masyarakat dieng sebagai pengganti tanaman kentang
4. Tingginya resiko budidaya tanaman sayur 5. Belum mampunya kapasitas petani untuk
mengembangkan ketrampilan dalam pengembangan komoditas alternative
Permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat:
1. Kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan masih rendah
2. Kelembagaan masyarakat peduli lingkungan yang belum optimal, terutama terkait dengan pengelolaan lahan, manajemen organisasi, keuangan dan perencanaan
3. Belum berkembangnya unit-unit usaha ekonomi masyarakat berbasis kelompok
Permasalahan terkait dengan dukungan kebijakan dan regulasi dalam pemulihan kawasan Dieng
1. Belum adanya regulasi pada level desa dan kabupaten sebagai bentuk komitmen untuk mendukung upaya-upaya pemulihan Kawasan Dieng
2. Belum adanya integrasi kegiatan antar sektor pada sasaran yang sama dalam bentuk peraturan pada level kabupaten yang mengikat semua stakeholder yang terlibat, untuk mewujudkan koordinasi dalam perencanaan program.
Sumber : Diolah, berdasarkan TKPKD (2012)
Analisis dan Rekomendasi Andriana (2007) dalam penelitiannya menuturkan dalam pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang juga dihadapkan pada berbagai masalah antara lain;
1. Rencana tata ruang yang saat ini ada masih berorientasi pada batasan wilayah administrasi 2. Perangkat hukum yang masih terbatas dalam pengendalian pemanfaatan ruang 3. Belum adanya kesamaan pandangan dari berbagai instansi mengenai pentingnya
pembangunan yang berlandaskan pola tata ruang 4. Terbatasnya ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dalam penyusunan pola tata
ruang, 5. Kemampuan kelembagaan penataan ruang yang masih terbatas.
Penyebab utama ketidakberhasilan penanganan masalah atau tidak optimalnya penanganan adalah karena tidak adanya rujukan RTRW yang dapat menyerasikan dan mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan atau program. Selain itu belum adanya pelibatan masyarakat dalam langkah–langkah tersebut juga merupakan salah satu faktor mengapa permasalahan RTRW sulit ditangani. Sebagai warisan orde baru, perencanaan yang sentralistik selama ini sering tidak menemui hasil yang memuaskan. Data di lapangan, contohnya kasus Dieng menunjukkan penurunan wisata di Dieng karena adanya pola homo economicus masyarakat yang menanam Kentang tanpa perduli dampak
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e14
lingkungan yang akan terjadi kemudian. Secara top-down, lemahnya pengelolaan kawasan wisata Dieng yang hanya melibatkan faktor kapitalisme sumberdaya mengakibatkan penurunan daya dukung lahan dan masyarakat yang terkena krisis kemudian beramai-ramai menanam Kentang. Model perencanaan demikian sebagaimana dianalisa oleh Almendinger (2002) termasuk dalam konteks perencanaan “Positivisme” dimana penekanan perencanaan masih berkutat pada eksploitasi sumber daya dengan perhitungan “kapitalistik” yang diwujudkan melalui perencanaan rasional yang melihat output dan input terhadap kesejahteraan secara hitam diatas putih. Pada periode selanjutnya pun, teori perencanaan ala marxisme dan kritik nya juga tak mampu menjawab alternatif perencanaan, hanya sebagai anti-tesis semata. Alam, hutan dan sumberdaya yang ada seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai sumberdaya bersama. Pengenalan sumberdaya ini sebagaimana Ostrom dalam Rustiadi (2011) menyebutnya sebagai ‘common pool resources’ (CPRs). Pada perkembangannya, Dieng mengalami perubahan pola pertanian menjadi pertanian kentang yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Terjadilah kemudian penggunaan sumberdaya oleh sebagian pihak untuk menanam kentang, dikarenakan pasar yang juga merespons positif produksi kentang ini. Selain itu, dukungan pembiayaan begitu mudah diperoleh dari lembaga keuangan serta adanya banyak contoh “haji” yang kaya dari bisnis produksi kentang sehingga mekanisme ini bekerja tanpa terkendali. Program yang dilaksanakan akan menjadi proyek‖ semata tanpa adanya adopsi dan rasa memiliki dari masyarakat. Akibatnya, program tidak akan berkelanjutan dan hanya memiliki dampak yang rendah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat jenis lahan yang akan diintervensi sebagian besar adalah lahan milik, sehingga penggunaan apapun akan menjadi hak sepenuhnya dari pemilik lahan. Selain itu, petani juga merambah lahan-lahan milik Perhutani yang diyakini sebagai lahan bersama dan menanam kentang untuk meningkatkan perekonomian. Pola perilaku oportunis (opportunistic behavior) ini dipicu oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki tanah pribadi ternyata mmapu meningkatkan perekonomin dengan berladang kentang, ketimbang memanfaatkan wisata Dieng yang selama ini hanya dikelola oleh Pemerintah. Perilaku over-use lahan dengan menanami kentang kemudian dicontoh oleh rata-rata penduduk desa lainnya, dengan cara menyerobot lahan milik Perhutani di sekitar tempat tinggal mereka dan melakukan cocok tanam kentang. Penggunaan yang berlebihan ini sangat mengganggu potensi orang lain untuk memanfaatkannya dan menyebabkan terjadinya congestion yang akan mengarah kepada degradasi (kerusakan). Kecenderungan overuse dan adanya free rider merupakan masalah sekaligus penciri dari sumberdaya-sumberdaya CPRs sehingga menurut Rustiadi (2011) diperlukan mekanisme, sistem kelembagaan dan tatakelola (governance) yang dapat mencegah atau menghindarinya. Upaya konservasi bukan tidak ada, bahkan terlihat masif dan komprehensif. Namun pada kenyataannya, roadmap pemerintah daerah untuk penanggulangan berbagai degradasi lahan melalui pendekatan sentralistik (dan dengan perencanaan yang masih pada paradigma lama yaitu rasional planning saja) tidak berdampak cepat dalam prosesnya. Terutama timbul masalah yang tidak terpecahkan yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa kegiatan konservasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng oleh Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5. Upaya Instansi Dalam Kegiatan Konservasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng
Instansi Jenis Kegiatan
Kantor Lingkungan Hidup
Pengendalian limpasan dan erosi tanah di Ds. Jojogan, Sikunang, Sembungan dan Patakbanteng th. 2002
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e15
Penyusunan Buku Rencana Kampanye LH th. 2003 Penghentian budidaya kentang dan penghijauan kembali Telaga
Warna dan Telaga Pengilon th. 2003 Penerbitan SE Bupati Wonosobo tgl. 2 -Jan- 2004, No.660/148
tentang Larangan Penanaman Tanaman Semusim di Kawasan Lindung th. 2004
Penyusunan Grand Design Pengelolaan Lingkungan Hidup DAS Serayu, th. 2004
Demplot budidaya tanaman strawberi di Desa Campursari th. 2004 Demplot budidaya bunga potong di Ds. Patakbanteng th. 2004 Inventarisasi Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan yang
mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung th. 2004 Pengendalian Kerusakan lingkungan Dataran Tinggi Dieng di Ds.
Sembungan th.2005 Pengadaan tanah dan pembangunan gedung pengolah kompos di
Desa Sikunang th. 2005 Pembangunan gedung pengolah kompos (2 unit) di Ds. Sikunang th.
2006
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pengaman tebing sepanjang 1.964 m di Ds. Dieng, Parikesit dan Patak beanteng
Gully Plug sebanyak 10 unit di Ds. Dieng, Patakbanteng, Igirmranak dan Parikesit
Sumur resapan sebanyak 12 unit di Ds. Dieng, Patakbanteng, Igirmranak dan Parikesit
Dam penahan sebanyak 3 unit di Ds. Igirmranak Bantuan bibit kayu putih di Ds Sikunang th. 2003 Ujicoba penanaman kina di Ds. Sembungan dan Sikunang sebanyak
6000 btg th. 2003 Demplot purwaceng di Ds. Sikunang th. 2003 Mini UPSA di Ds. Sikunang seluas 10 ha th. 2004 Demplot konservasi pada lahan kentang di Ds.Patakbanteng
th.2004 Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam Th. 2002
seluas 15 ha di Ds. Dieng dan Patakbanteng
Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan kelembagaan dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Memberikan bantuan permodalan dan peralatan untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan di Desa Sikunang, Sembungan Dieng dan Patakbanteng masing-masing Rp. 10 juta
Mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan berupa alat-alat untuk pengepakan dan pengolahan carica sebagai upaya peningkatan ketrampilan usaha bersama secara partisipatif dan peningkatan pemberdayaan masyarakat
Dinas Peternakan dan Perikanan
Peternakan Pengadaan Domba di Ds. Jojogan sebanyak 45 ekor th. 2004’ Bantuan dana bergulir di Ds. Sembungan dan Igirmranak masing
masing Rp. 5 juta th. 2006 Perikanan Penebaran benih ikan di Telaga Warna sebanyak 200 ekor th. 2004
dan di Telaga Cebong sebanyak 2.750 ekor th. 2006
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e16
Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 12 Th. 1992 ttg. Izin Penebangan Kayu No. 1 Th. 1996 ttg. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.
Wonosobo No. 2 Th. 1996 ttg. Pola Tanam dan Konservasi Tanah dalam
Wilayah Kabupaten Dati II Wonosobo No. 25 Th. 1999 ttg. Rencana Umum Tata Ruang Pola Ibu Kota
Kecamatan Kejajar Kabupaten DaTi II Wonosobo No. 7 Th. 2002 ttg. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian
ke Non Pertanian No. 28 Th. 2002 ttg Perlindungan Terhadap Ikan No. 29 Th. 2002 ttg Ayoman Jalan
Peraturan Bupati Wonosobo No. 6 Th. 1994 ttg. Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran No. 4 Th. 1995 ttg. Keputusan Bersama Bupati KDH Tk. I II dg Bupati
Banjarnegara tentang Gelar Bersih Obyek Wisata Dieng No. 11 Th. 1995 ttg. Pengelolaan Obyek Wisata Pendakian Gunung
Sindoro No. 20 Th. 1995 ttg. Keputusan Bersama Bupati Wonosobo dg Bupati
Banjarnegara tentang Pengelolaan Obyek Wisata Dieng No. 25 Th. 1998 ttg. Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Dati II
Wonosobo No. 2 ttg Pola Tanam dan Konservasi Tanah Dalam Wilayah
Kabupaten Dati Wonosobo No. 17 Th. 2002 ttg. Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan
Kawasan Dataran Tinggi Dieng No. 6 Th. 2005 ttg. Pola Tanam dan Rencana Tanam di Kab.
Wonosobo
Perhutani KPH Kedu Utara BKPH Wonosobo
Penanaman Tanaman Kehutanan (Bintami, Keningar dan Ekaliptus) Tahun 2005 - Desa Dieng seluas 43,9 Ha - Desa Sikunang seluas 53,5 Ha - Desa Jojogan seluas 22 Ha Th. 2006 - Desa Dieng seluas 44,9 Ha
Sumber: Dinas Instansi di Lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo
Berdasarkan data kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo nampak bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam suatu bentuk pengelolaan yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan yang dilakukan hanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, dan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, serta beberapa kegiatan yang dilakukan tidak saling mendukung antara unit kerja yang satu dengan lainnya, sehingga sasaran yang di capai dan indikator keberhasilannya hanya berkisar pada ruang lingkup yang sangat parsial. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antar penyelenggara kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan kadang tidak saling terkait, dan saling tumpang tindih antara unit kerja yang satu dengan lainnya. Kegiatan tersebut juga berjalan sendiri-sendiri, dengan bentuk, volume dan sasaran yang berbeda. Kurangnya koordinasi antar instansi menjadi bagian yang sangat berperan dalam penyimpangan implementasi rencana tata ruang. Sehingga penyimpangan pemanfaatan kawasan lindung menjadi tanggung jawab institusi yang membidangi lingkungan saja. Hal ini dipengaruhi pula oleh kekuatan hukum dari kebijakan tersebut dimana aturan-aturan yang berkaitan dengan
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e17
pelaksanaannya seharusnya lebih dipertegas lagi tentang pihak-pihak yang harus berperan di dalamnya dan konsekuensi apa yang akan diberikan bila terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Selain secara internal masih sektoral, secara eksternal pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat minim. Untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih modern, berbasis advokasi dan kolaborasi dengan masyarakat (perencanaan kolaboratif) yang menjadi bagian dalam paradigma perencanaan yang “post-positivisme”. Menurut Sambroek & Eger (Indrawati et al., 2003) partisipasi merupakan suatu proses di mana seluruh pihak terkait secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Hal ini diwujudkan melalui suatu kebijakan pembangunan kehutanan yang tidak lagi bersifat sentralistik (terpusat dan dikelola oleh negara) yang dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif dalam menjaga kawasan hutan (Jatminingsih, 2009) dan hanya mengeksploitasi hasil hutan tanpa memperhatikan faktor sosial yang diakibatkannya. Dengan sistem sentralistik tersebut, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Untuk itu, sudah seharusnya jika masyarakat dijadikan kunci utama dalam pengelolaan hutan, dan diharapkan masyarakat akan secara aktif mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara optimum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan, dalam konteks ini, masyarakat di Dataran Tinggi Dieng harus mengelola wisata bersama pemerintah dengan konsep kolaboratif dengan bendera “eko-wisata” sehingga masyarakat menjadi sadar tentang daya dukung lingkungan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Perencanaan advokatif dan kolaboratif menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan agar semua upaya pemerintah (daerah) dapat terlaksana dengan baik.
Lesson Learned dan Rekomendasi Dua permasalahan mendasar yang dihadapi Kawasan Dieng adalah degradasi hutan dan lahan akibat tekanan dari konversi hutan menjadi lahan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi problem tersebut. Apabila digali lebih dalam, beberapa isu strategis yang terkait dengan kompleksitas permasalahan di Kawasan Dieng sekaligus usulan solusinya adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan pola pemanfaatan hutan dan lahan yang ramah lingkungan
Berdasar pada uraian tersebut, untuk dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kawasan Dieng, diperlukan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang lebih ramah lingkungan, yang memiliki nilai ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk pengelolaan lahan yang ada saat ini serta mampu menghasilkan nilai finansial yang minimum sama dengan jenis komoditas yang ada sekarang. Solusinya melalui : Reboisasi pada lahan perhutani, Penanaman tanaman keras pada lahan masyarakat, Perlunya sumur resapan dan biopori, Perlunya bangunan civil teknis untuk mengurangi sedimentasi dan erosi, Penggunaan pupuk dan pestisida yg sesuai aturan erosi, Penggunaan pupuk organik, Perbaikan terasering, Menerapkan pola tanam sesuai aturan/ketentuan.
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e18
2. Pengembangan sumber-sumber ekonomi alternatif yang berbasis lahan dan non berbasis lahan (on farm dan off farm) dan juga non farm
Perlu dilakukan fasilitasi dan didorong didorong agar ada pengalihan/pergeseran proporsi mata pencaharian masyarakat, dari sektor pertanian holtikultura (kentang) ke sektor atau komoditas lain. Hal ini penting dilakukan sebagai alternative ekonomi bagi masyarakat untuk mengurangi tekanan terhadap lahan. Solusinya melalui : Intensifikasi dan Diversifikasi pertanian ke selain Kentang, dengan demikian diperlukan peningkatan kapasitas SDM petani sehingga diperlukan advokasi dan pendampingan. Misalnya peternakan Domba dan tanaman lain. Membuka akses informasi dan mengembangkan komoditas pertanian yang punya nilai ekonomi sebanding dengan kentang dan sayuran juga penting. Mengelola ekowisata merupakan salah satu konsep yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Mendukung wisata Dieng melalui berbagai jasa-jasa dan produk berupa kerajinan, makanan dan minuman, tour guide dan sejenisnya merupakan alternatif selain budidaya kentang. Fasilitasi pembentukan dan penguatan unit-unit usaha ekonomi berbasis potensi lokal sangat diperlukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat Untuk mendukung bentuk pengelolaan hutan dan lahan yang lebih ramah lingkungan, dan mampu memberikan alternatif pendapatan maksimal, diperlukan peningkatan ketrampilan bagi petani. Hal ini disebabkan karena secara umum, sampai saat ini petani masih melakukan pengelolaan hutan dan lahan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman secara tradisional yang biasanya diperoleh secara turun temurun. Introduksi teknologi dan inovasi hampir belum terjadi di tingkat petani sehingga membutuhkan rencana peningkatan kapasitas SDM secara intensif dan mengenalkan teknologi-teknologi tepat guna.
4. Penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
Peningkatan Koordinasi antar institusi pemerintah dalam konteks pemulihan Kawasan Dieng, diperlukan dan menjadi tantangan tersendiri karena koordinasi adalah hal yang sulit. Namun demikian, menangani permasalahan yang kompleks seperti Kawasan Dieng, hampir tidak mungkin dilakukan secara parsial, dimana hal itu berarti bahwa keterpaduan gerak dengan didukung para pihak lainnya yaitu komponen masyarakat, sangat diperlukan.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
Kebutuhan adanya kelompok masyarakat yang solid dan mempunyai kapabilitas menjadi salah satu prakondisi yang diperlukan untuk keberhasilan suatu program, terutama untuk pemulihan Kawasan Dieng. Kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan ini masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan manajemen organisasi, keuangan dan perencanaan. Sehingga Pelatihan kelembagaan organisasi peduli lingkungan,selain peningkatan jumlahnya, sangat diperlukan.
6. Dukungan kebijakan (dan Kepemimpinan)
Berbagai program pemerintah dan para pihak lainnya nampaknya belum mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan kebijakan yg merupakan enabling factor untuk keberhasilan pemulihan kawasan yang telah terdegradasi tersebut. Regulasi dan kebijakan yang ada belum memadahi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan kompleks kawasan dieng. Dengan demikian, diperlukan perbaikan kebijakan (regulasi, harmonisasi perencanaan, penganggaran, keuangan) sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mendukung program pemulihan Kawasan Dieng. Selain itu, diperlukan pemimpin instansi pemerintahan yang
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e19
mau bekerja keras dan cerdas serta memiliki ide-ide dalam pengelolaan kawasan dan menyejahterakan rakyat dengan berbagai kebijakan yang out of the box dan berani keluar dari zona nyaman pendapatan yang diperoleh dari berfungsinya lokasi wisata saja namun tidak memberdayakan masyarakat lokal secara langsung.
Antara Kawasan Dieng dan Kawasan Puncak (Cibulao)
Terdapat beberapa kesamaan antara kawasan puncak dan kawasan dieng di dua provinsi yang
berbeda ini dalam hal permasalahan pengelolaan hutan.
Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi
No Unit Pengelolaan Hutan Lindung Hutan Produksi Jumlah
1 Unit I Jawa Tengah
573.241,63 877,30 574.118,93
2 Unit II Jawa Timur
812.950,40 315.505,30 128.455,70
3 Unit III Jawa Barat
552.065,80 240.402,01 792.467,70
J u m l a h
1.938.257,80 556.784,61 2.495.042,44
Sumber: Perum Perhutani ( 2007)
Luas keseluruhan hutan di unit I ini adalah; 574.118,93 Ha (23%) dari seluruh luas kawasan hutan Perhutani dan luas tersebut terdiri dari hutan produksi seluas 573.241,63 Ha hutan lindung seluas 877,30 ha dan hutan suaka. Hutan pada Unit I Jawa Tengah lebih banyak terdapat hutan kayu jati (46,45 %) dan selebihnya terdiri dari hutan damar, pinus, sono keling, kayu putih dan sisanya adalah hutan wisata (Soetadi & Sastraprawira, 2007) Jawa tengah memiliki potensi yang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan kawasan hutan rakyat (hutan hak) yaitu daerah Kabupaten Wonosobo, tepatnya di daerah kawasan hutan pegunungan, Dieng, Sindoro, dan Tleret. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo kurang/lebih 98.467,96 Ha, dari luas tersebut terdapat kurang/lebih 19.472 Ha merupakan kawasan hutan rakyat (hutan hak)39 dan kurang/lebih seluas 18.896 Ha adalah hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan. Luas keseluruhan tanah kawasan hutan Perhutani di Unit III adalah kurang/lebih 792.467,70 Ha, hutan produksi seluas 552.065,80 Ha sedangkan hutan lindung seluas 240.402,01 Ha. Kawasan hutan Jawa Barat atau Unit III ini, memiliki latar belakang yang agak berbeda dengan unit-unit yang lain. Hal ini disebabkan karena Unit III ini dulunya belum dikelola oleh Perum Perhutani akan tetapi dikelola oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat dan baru kemudian dilimpahkan kepada Perum Perhutani Unit III. Kawasan hutan Jawa Barat telah banyak mengalami kerusakan paling parah dan kawasan hutan tersebut banyak yang dikuasai masyarakat. Dalam perkembangan terbaru Perum Perhutani telah berusaha keras untuk memperoleh kembali hak penguasaan dan pengelolaan yang sekarang banyak berada di tangan masyarakat dan bahkan sebagian laba/pendapatan dari Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur banyak digunakan untuk membiayai pemulihan kembali kawasan hutan di Jawa Barat Banten yang rusak paling parah.
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e20
Sebagai lesson learned, maka karena karakteristik dua wilayah yang hampir sama maka beberapa
aspek solusi yang dilakukan untuk Dieng seharusnya dapat pula diterapkan di kawasan Puncak,
dalam hal ini Cibulao. Berikut ini tiga tabel yang berisi karakteristik, permasalahan, dan rekomendasi
yang dapat diterapkan di Cibulao.
Tabel 7. Lokus Kawasan dan Karakteristiknya
Lokus Kawasan Karakteristik
Kawasan Dataran Tinggi Dieng Permasalahan : Konversi Lahan Untuk Ladang Kentang, Degradasi Lingkungan Sumberdaya alam : Mata Air, Telaga, Hutan, Sungai, Kebun Tanaman kentang/umbi, Sayuran Sumberdaya manusia : buruh tani kentang, pengusaha kentang, pedagang, warung, PNS, guru Potensi : Pariwisata Candi, Telaga, Pemandangan Alam, Hiking
Kampung Cibulao, Kawasan Puncak Bogor
Permasalahan : Sampah, Konversi Lahan : Untuk Hunian Villa dan Kebun Teh, Degradasi Lingkungan Sumberdaya alam : Mata Air, Telaga, Kebun Teh, Hutan, Sungai, Kebun Tanaman, Sayuran Sumberdaya manusia : Memetik teh, ngored, ngupas, nanam bibit, memupuk, menyemprot, mandor, asisten, ternak, tani sayur, warung, guru, paraji, kader posyandu Potensi : Pariwisata Perkebunan Teh, Pemandangan Alam, Track Sepeda, Hiking
Masalah yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng dapat pula disandingkan dengan masalah yang
terjadi di Cibulao maupun Puncak pada umumnya sehingga dapat lebih mudah dipetakan dan dilihat
penyebab serta alternatif solusinya di tabel berikutnya.
Tabel 8. Matriks Permasalahan Desa di Dieng dan Puncak
Masalah
Desa-desa di Dieng (Desa Sembungan dst) Dusun/Kampung Cibulao di Puncak
Permasalahan yang terkait dengan laju degradasi lahan dan Kerusakan lingkungan
4. Tingginya sedimentasi dan erosi tanah di Kawasan Dieng
5. Pencemaran air di kawasan Dieng yang cukup tinggi.
6. Menurunnya tingkat kesuburan tanah di kawasan Dieng
1. Ketergantungan masyarakat
yang sangat tinggi terhadap
perusahaan yang sedang
dalam konflik membuat
kehidupan masyarakat tidak
sejahtera.
2. Tidak ada sumberdaya yang
dapat diakses oleh
masyarakat untuk menjadi Permasalahan yang terkait 6. Pada umumnya petani
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e21
dengan sosial ekonomi masyarakat
peduli lingkungan berpendapatan rendah.
7. Pola pikir bahwa budidaya kentang dan sayuran adalah satu-satunya sumber pendapatan yang utama
8. Belum berkembangnya alternatif-alternatif pendapatan bagi masyarakat dieng sebagai pengganti tanaman kentang
9. Tingginya resiko budidaya tanaman sayur
10. Belum mampunya kapasitas petani untuk mengembangkan ketrampilan dalam pengembangan komoditas alternative
penghidupan lain di luar
perkebunan, baik akses
terhadap sumberdaya alam
(lahan garapan –hutan dan
perkebunan, hak milik rumah
dan pekarangan) juga
sumberdaya financial (tidak
ada dana yang bisa diakses)
3. Tidak diperhatikannya
kesejahteraab karyawan oleh
perusahaan (14 tahun kondisi
rumah rusak, tidak
diperbaiki)
4. Tiap tahun naik upah tapi
hanya 40 rupiah
5. Akses pasar jauh
(Cipanas/Cisarua), sehingga
kebutuhan akan pangan
dapat diperoleh dari warung
(terdekat)
6. Tidak adanya program
perhutani dalam
memberdayakan masyarakat
pinggir hutan untuk
mengelola hutan dan
memanfaatkan hutan non
kayu
7. Jauhnya akses pendidikan
dan kesehatan (hanya
tersedia satu bidan pada satu
desa)
Permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat:
4. Kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan masih rendah
5. Kelembagaan masyarakat peduli lingkungan yang belum optimal, terutama terkait dengan pengelolaan lahan, manajemen organisasi, keuangan dan perencanaan
6. Belum berkembangnya unit-unit usaha ekonomi masyarakat berbasis kelompok
Permasalahan terkait dengan dukungan kebijakan dan regulasi dalam pemulihan kawasan Dieng
3. Belum adanya regulasi pada level desa dan kabupaten sebagai bentuk komitmen untuk mendukung upaya-upaya pemulihan Kawasan Dieng
4. Belum adanya integrasi kegiatan antar sektor pada sasaran yang sama dalam bentuk peraturan pada level kabupaten yang mengikat semua stakeholder yang terlibat, untuk mewujudkan koordinasi dalam
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e22
perencanaan program.
Sedangkan hal-hal yang dapat dilakukan di dua kawasan ini oleh semua aktor terutama pemerintah
daerah dan masyarakat sipil (civil society) adalah :
Tabel 9. Aspek Rekomendasi Solusi di Dieng dan Puncak (Cibulao)
Aspek Dieng Puncak (Cibulao dsk)
Pengaturan pola pemanfaatan hutan dan lahan yang ramah lingkungan
Penyuluhan mengenai dampak lingkungan dan melatih penggunaan pestisida yang benar, memberikan pengetahuan alternatif peningkatan kesejahteraan non farm dan off farm. Juga non farm.
Penyuluhan mengenai dampak lingkungan akibat penanaman tanaman yang merusak daya dukung lahan, memberikan pengetahuan alternatif peningkatan kesejahteraan non farm dan off farm. Juga non farm.
Pengembangan sumber-sumber ekonomi alternatif yang berbasis lahan dan non berbasis lahan (on farm dan off farm) dan non farm
Riset dan pengembangan berbagai alternatif dan memberikan solusi alternatif tersebut ke masyarakat. Misalnya on farm yang tidak merusak lingkungan, off farm yang lebih mobilitas dan non farm di kawasan ekowisata dieng
Riset dan pengembangan berbagai alternatif dan memberikan solusi alternatif tersebut ke masyarakat. Misalnya on farm yang tidak merusak lingkungan, off farm yang lebih mobilitas dan non farm di kawasan ekowisata puncak, terutama di sekitar Cibulao misalnya track sepeda gunung, hiking.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat
Program-program pendampingan, advokasi dan melibatkan masy dalam perencanaan kawasan ekowisata, pelatihan dan inkubasi pertanian alternatif selain kentang, difusi pengetahuan dan teknologi tepat guna ke masyarakat, pelatihan teknis ekowisata
Program-program pendampingan, advokasi dan melibatkan masy dalam perencanaan kawasan ekowisata, pelatihan teknis penanaman pohon keras, pemupukan dan tatakelola lingkungan
Penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah
Kelembagaan pemerintah yaitu instansi terkait ditingkatkan dengan koordinasi, melepaskan ego sektoral dan merencanakan pembangunan yang terpadu, melibatkan masyarakat (collaborative dan participative planning). Selain Pemda, Pemerintah pusat perlu pula turun tangan misalnya di Kementerian Desa dan PDT
Kelembagaan pemerintah yaitu instansi terkait ditingkatkan dengan koordinasi, melepaskan ego sektoral dan merencanakan pembangunan yang terpadu, melibatkan masyarakat (collaborative dan participative planning). Selain Pemda dan instansi administratif lokal, Pemerintah pusat perlu pula turun tangan misalnya di
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e23
harus memulai langkah perencanaan dan pembangunan di desa.
Kementerian Desa dan PDT harus memulai langkah perencanaan pembangunan desa.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
Investasi modal sosial melalui forum jejaring kelompok tani sadar lingkungan
Investasi modal sosial melalui forum-forum jejaring kelompok KTH
Dukungan kebijakan (dan Kepemimpinan)
Membuat peraturan kebijakan yang komprehensif bukan hanya melarang tapi memberikan alternatif. Dibarengi contoh kepemimpinan yang out of the box dalam mengelola kawasan wisata sebagai ekowisata
Membuat peraturan kebijakan yang melibatkan masyarakat sehingga dapat memanfaatkan lahan untuk mengelola kawasan wisata sebagai ekowisata misalnya track sepeda, hiking dan sight seeing wisata kebun teh yang dikelola masyarakat
Kata kunci dari kasus wisata dan “ekonomi kentang” di Dieng yang dapat dijadikan pembelajaran
oleh Kampung Cibulao di Desa Tugu Utara, Kawasan Puncak, Jawa Barat adalah :
1. Peningkatan Kesadaran individual dan kolektif
Dalam hal ini mengenai lingkungan, alternatif perekonomian dan dampak tindakan yang
menyebabkan tragedy of the commons dan mengganti budaya (revolusi mental)
“mengorangi” jika sudah jadi juragan kentang dan naik Haji dari itu. Selain individual,
kesadaran kolektif harus terbangun.
2. Peningkatan Kapasitas SDM
Dalam hal ini peningkatan kemampuan, pengetahuan dalam bercocok tanam dan
berwirausaha dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dengan memikirkan juga
keberlanjutan (sustainability).
Untuk mencapai itu, maka diperlukan dukungan dua hal :
3. Dukungan Kelembagaan
Penguatan kapasitas secara kelembagaan dengan melibatkan dan melakukan investasi sosial
capital bersama masyarakat membuat forum-forum petani sadar lingkungan, komunitas
atau kelompok Tani Hutan, pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan sejenisnya
diwujudkan dengan mendukung peningkatan aktivitas dan program lembaga masyarakat di
desa kawasan ini.
4. Dukungan Kebijakan dan Kepemimpinan
Kebijakan berupa regulasi dan peraturan tertulis harus mendorong berkurangnya kerusakan
lingkungn namun seiring itu harus juga mendorong peningkatan perekonomian masyarakat
sehingga diperlukan kebijakan yang tepat guna dan dengan demikian, perlu juga teladan
kepemimpinan dari pemerintah agar masyarakat dapat mengikuti arahan pemerintah
dengan sukarela karena adanya kepemimpinan yang profetik.
Unggul Sagena & Mandala Eka Putra (2015)
Pag
e24
Referensi
Arbangiyah, R. 2012. Perubahan Pola Pertanian Rakyat di Desa Sembungan Dataran Tinggi Dieng (1985-1995). Skripsi. Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.
Almendinger. P. 2002. Planning Theory. Palgrave. McMillan. Anonim. 2011.Vulcanological Survey Indonesia. http://rovicky.wordpress.com/2011/05/30/ Andayani, W. 2005. Ekonomi agroforestri. Yogyakarta: Debut Press. Andriana, R. 2007. Evaluasi Kawasan Lindung Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Program
Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Semarang. Jatminingsih,T. 2009. Karakteristik lingkungan, karakteristik petani pesanggem, dan peran
masyarakat lokal dalam PHBM KPH Kendal. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang: Universitas Diponegoro
Puspita, I. 2005. Zonasi Kondisi Kawasan Hutan Negara Di Dieng Dan Arah Pengelolaan Yang Berwawasan Lingkungan. Fakultas Teknik, UNDIP. Semarang. Tidak Diterbitkan.
Purwanto, N.G. 2004. Strategi Pengembangan Ekowisata Kawasan Dieng. Thesis. Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. Tidak diterbitkan.
Rustiadi, E., Saeful Hakim S., Panuju D. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespent Press.
Soetadi, R., Sastraprawira, S et. al, 1978, Mengenal Hutan Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang
TKPD, 2012. Roadmap Pemulihan Kawasan Dieng Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 -2016. Tim Kerja Pemulihan Kawasan Dieng, Kabupaten Banjarnegara.