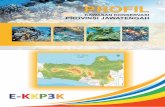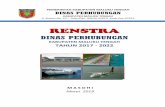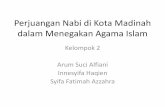Perjuangan Agraria_Pelajaran dari Batang, Jawa Tengah
Transcript of Perjuangan Agraria_Pelajaran dari Batang, Jawa Tengah
Kiprah PEWARTA dalam Perjuangan Agraria
Pelajaran dari Batang, Jawa Tengah
Sofian Munawar Asgart
Pendahuluan
Persoalan agraria merupakan salah satu masalah fundamental bagi suatu bangsa.
Mochammad Tauchid (2007) menggambarkan urgensi persoalan ini dengan
menyebutkan bahwa soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan
manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup,
soal darah yang menghidupi segenap manusia. Perebutan tanah berarti perebutan
makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah,
mengorbankan segala yang ada untuk mempertahankan hidup selanjutnya.1
Namun sayangnya, sepanjang sejarah kekuasaan formal Orde Baru, Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang secara hakiki bertujuan mewujudkan keseimbangan
distribusi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria untuk mencapai keadilan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia justru seringkali didiskreditkan dan
didelegitimasikan sebagai produk PKI. Padahal, jika ditelusuri secara jernih ide-ide
pokok yang mendasarinya, dan sejarah pembentukkannya, UUPA 1960 merupakan
kebijakan nasional yang lahir dari kesepakatan semua unsur kekuatan politik yang
hidup waktu itu, baik itu golongan nasionalis, Islam, sosialis maupun
komunis. Menurut Sadikin Gani (2006) masalah ketimpangan dan konflik agraria yang
terus mengemuka hingga kini merupakan warisan dari serangkaian politik agraria yang
pernah diterapkan di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga Indonesia merdeka di
bawah Orde Baru. Ketika Orde Baru berkuasa, rezim yang mengklaim dirinya sebagai
antitesis Orde Lama ini menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, di mana investasi modal menjadi motor penggerak utamanya.2
Karena berbagai stigmatisasi itulah maka gerakan-gerakan advokasi atas tanah
seringkali menghadapi sejumlah kendala dan bahkan menjadi tidak begitu populis di
tengah masyarakat. Namun demikian, bukan berarti gerakan-gerakan semacam ini tidak
ada. Pasca runtuhnya otoritarianisme Orde Baru bahkan gerakan-gerakan advokasi
agraria mulai bangkit kembali di sejumlah tempat. Tulisan ini ingin memotret salah
satu gerakan agraria yang dilakukan oleh Persaudaraan Warga Tani (PEWARTA),
sebuah lembaga dimana penulis melakukan kegiatan magang akademik sebagai bagian
dari salah satu tugas kuliah pada Program Konsentrasi HAM dan Demokrasi,
Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Kelahiran PEWARTA dalam Konteks Sejarah Agraria
Cerita-cerita adiluhung tentang masa keemasan kerajaan di Nusantara ternyata
menyimpan banyak ironi. Salah satu ironi itu adalah persoalan agraria dimana hukum
1 Tauchid, Mochammad (2007). Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran
Rakyat Indonesia, PEWARTA, Yogyakarta. 2 Sadikin Gani, ―Tantangan Reforma Agraria‖ dalam situs http://rumakiri.net dengan link berikut:
http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=97
1
pertanahan saat itu sepenuhnya didasarkan atas feodalisme yang begitu memberatkan
rakyat. Dalam sistem feodalisme yang nyaris berlaku di seluruh Nusantara saat itu
tanah adalah milik raja secara mutlak. Bahkan bukan hanya tanah saja, rakyat adalah
milik raja juga. Rakyat laksana benda sehingga ia menjadi hamba yang dapat
digunakan untuk apa saja demi kepentingan dan kehormatan raja.
Sebagai illustrasi, misalnya, di Kerajaan Mataram baik di Yogyakarta maupun di
Surakarta dulu dinyatakan bahwa tanah itu ‖kagungan dalem‖. Artinya, tanah adalah
milik Sultan dan Sunan. Rakyat hanya sebagai deelbouwer (pemaro) dan hanya berhak
meminjam (wewenang anggaduh) atas tanah. Hal serupa juga terjadi di Gorontalo.
Pada hari penobatan raja, para kepala adat (bete-bete) menyerukan ucapan di hadapan
raja, yang artinya kira-kira: ‖Angin, api, air, tanah, dan semua orang yang ada di sini
adalah kepunyaan seri paduka‖. Begitu juga di daerah-daerah lainnya hampir di
seantero Nusantara dimana raja memerintah, menganggap bahwa segala isi negerinya
–termasuk dan terutama tanah– adalah hak mutlak dari raja.
Pada kurun berikutnya, kedatangan VOC dan kolonialisme Belanda telah mengubah
pola pemilikan tanah. Penaklukan raja-raja Nusantara oleh Belanda sekaligus juga
berarti perampasan atas kekuasaan raja. Hak raja atas tanah dan tenaga rakyat dengan
beragam pengaturannya secara otomatis juga berpindah ke tangan pemerintah kolonial
Belanda. Pada tahun 1811, Raffles, salah seorang Gubernur Jenderal Belanda berkata:
‖Raja-raja sudah hilang. Gubernurmen yang menggantikannya. Karena itulah
Gubernurmenlah yang menerima hak-hak yang dulu ada pada raja, yaitu hak memiliki
semua tanah, juga tenaga rakyat bilamana diperlukan‖. Pada saat itulah muncul
beragam pengaturan atas tanah yang didasarkan atas Ordonansi Belanda, seperti: Hak
Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht, serta Hak Pakai dengan segala implikasi dan
beban sosial-politik yang menyertainya.
Arah politik agraria kolonial dapat dilihat dari aneka produk hukum yang
dilahirkannya. Ciri terpenting dari politik agraria kolonial adalah pengalokasian
sumber-sumber agraria khususnya tanah dan tenaga kerja demi akumulasi modal oleh
perusahaan. Untuk melegalkan usaha ini, Agrarische Wet 1870 diundangkan di Hindia
Belanda. Agrarische Wet telah membuka peluang luas bagi investasi perkebunan dan
pertanian yang sekalgus menggusur areal pertanian rakyat. Sementara itu, hak-hak adat
masyarakat atas tanah diletakkan sedemikian rupa kepada kelompok feodal melalui
azas domeinverklaring. Kondisi ini menjadikan rakyat hidup dalam dua kewajiban yang
menghisap dan memberatkan.
Secara detil, Tauchid mendeskripsikan bahwa selama masa kolonialisme Belanda tanah
dan rakyat Indonesia diperas-habis untuk kepentingan Belanda. Produksi tani Indonesia
menurutnya merupakan andalan pemerintah Belanda dalam perdagangan dunia saat itu.
Bagi Belanda dan kaum modal asing lainnya, Indonesia merupakan sumber kekayaan,
hingga 15% dari penghasilan nasional negeri Belanda saat itu. Indonesia sungguh
menjadi gantungan hidup negeri Belanda sebagaimana diakui sendiri oleh Baud, salah
seorang menteri Belanda yang mengatakan bahwa ‖Java was de kruk, waarop
Nederland dreef‖.3 Di mata kolonialisme Belanda, Indonesia merupakan negeri agraris
yang penting. Namun justru karena itulah Indonesia menjadi menarik untuk dikuasai
dan diperebutkan. Kekayaan Indonesia dari beragam produk pertaniannya tidak
3 Ibid.
2
menjadi sumber kekayaan rakyat, karena politik pertanahan dipegang oleh kaum
penjajah.
Kehadiran Jepang di Indonesia juga telah menambah malapetaka dan penderitaan
rakyat. Obsesi Jepang menjadikan Indonesia sebagai benteng pertahanan menghadapi
Sekutu memaksa rakyat Indonesia untuk melipatgandakan hasil bumi agar Indonesia
–terutama Jawa– menjadi gudang dan sumber perbekalan perang. Untuk itu penanaman
bahan makanan digiatkan dengan mengerahkan rakyat secara massif. Rakyat bukan
hanya dipaksa menjadi romusha, tapi juga diwajibkan menyerahkan bakti berupa hasil
bumi dengan pungutan yang besar.
Riwayat kekejaman culturstelsel terulang kembali saat masa Jepang. Bahkan, tanah-
tanah partikelir oleh pemerintah Jepang dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan
mengadakan Syiichi Kanri Kosha (Kantor Urusan Tanah Partikelir). Uang kumpenian
saat itu memang dihapuskan. Seolah-olah tanah partikelir itu semuanya dikuasai oleh
pemerintah dan tuan tanah seolah tak berkuasa lagi. Namun ternyata semua itu hanya
siasat untuk mengambil hati rakyat. Upaya ini ternyata hanya akal bulus Jepang untuk
memudahkan pengumpulan padi bagi keperluan cadangan perang menghadapi sekutu.
Kungkungan penjajahan fasis Jepang sebagai pengganti penjajahan Belanda
meninggalkan bekas-bekas kehancuran dan kelaparan serta malapetaka yang tiada tara.
Namun, di satu sisi, kehadiran Jepang telah memberi inspirasi tersendiri bagi bangsa
Indonesia. Belanda yang pada mulanya dianggap rakyat tidak dapat diganggu
kedaulatannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jepang. Hal ini telah
membuka pikiran dan menimbulkan perasaan harga diri bahwa Belanda bisa dikalahkan
dan begitu juga Jepang hingga bangsa Indonesia mampu melucuti Jepang beberapa
tahun kemudian.
Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 persoalan agraria
tidak serta-merta terselesaikan secara menggembirakan. Kemerdekaan politik itu tidak
membawa dampak riil bagi masyarakat dalam mengakses tanah secara adil. Dalam
salah satu klausul perjanjian Konferensi Meja Mundar (KMB) Belanda bahkan
meminta jaminan atas tanah-tanah perkebunan (onderneming) yang masih dikuasainya
sebagai salah satu ‖kompensasi‖ penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia. Tanah-
tanah onderneming itu sebagian telah dinasionalisasi dan diberikan hak penguasaannya
kepada perusahaan-perusahaan besar. Sebagian lagi ada yang masih terlantar dan tidak
jelas penguasaannya meski telah dikapling-kapling oleh negara, kapital, maupun
masyarakat. Karena itulah pasca kemerdekaan Indonesia, tanah-tanah onderneming ini
banyak melahirkan persoalan sengketa tanah yang hingga kini belum kunjung jua
penyelesaiannya.
Direktur CSDS, Imam Yudotomo, menyebutkan bahwa rangkaian sejarah pertanahan di
Indonesia tersebut menunjukkan bahwa tanah sejatinya pada awalnya adalah milik
rakyat. Karena itu menurutnya penting untuk ‘memprovokasi‘ rakyat agar mereka
punya kepercayaan diri untuk melakukan perjuangan mendapatkan hak atas tanah.
Menurut Imam, melalui informasi seperti inilah CSDS bersama PEWARTA
memberikan bekal informasi agar para petani memiliki argumen dalam melakukan
perjuangan menuntut hak atas tanah. ‖Dengan informasi itu, petani bisa lebih
bersemangat dan punya argumen untuk melakukan tuntutan klaim tanah. Ini antara lain
dasar-dasar yang kita sampaikan ke kelompok petani,‖ ujarnya.4
4 Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta: 22 Mei 2010.
3
Senada dengan itu, Manajer Program PEWARTA, Rudi Casrudi menyebutkan bahwa
perjuangan gerakan reforma agraria semakin berat tantangannya. Oleh karena itu para
petani menyadari bahwa perjuangan untuk itu tidak bisa dilakukan secara sendirian.
Karena itu, mereka berupaya membangun kekuatan dengan mendirikan organisasi
petani. Inilah awal berdirinya PEWARTA (Persaudaraan Warga Tani). Menurut Rudi,
tujuan utama didirikannya PEWARTA adalah untuk menyejahterakan petani dengan
membangun organisasi kaum tani yang kuat. Menurutnya, dengan kehadiran organisasi
PEWARTA ini diharapkan dapat ikut mengawal petani dalam rangka memperjuangkan
kepastian hak atas tanah.5
Ihwal kelahiran PEWARTA sebagai organisasi petani yang berorientasi pada
perjuangan agraria ini Rudi Casrudi menjelaskan bahwa kehadiran PEWARTA di
pertengahan tahun 1998 tak lepas dari kiprah gerakan petani dan gerakan mahasiswa
saat itu. Menurut Rudi, selain aksi-aksi di jalan, sejumlah aktivis mahasiswa ada juga
yang live-in di tengah masyarakat petani, sekaligus belajar bersama petani terutama
terkait beberapa persoalan pertanahan yang muncul saat itu, baik di Yogyakarta
maupun di beberapa tempat lain di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Batang.
Berkat dukungan banyak pihak maka organisasi PEWARTA sudah berdiri, tapi
ternyata tidak cukup hanya berdiri. Organisasi harus difungsikan agar benar-benar
berjalan secara efektif. Harus ada pembagian tugas yang jelas, apalagi mengingat
bahwa dampingan saat itu lebih banyak di Batang sementara PEWARTA sendiri
memilih Yogyakarta sebagai basecamp-nya. ‖Yogya menurut pandangan teman-teman
lebih starategis untuk membangun organisasi dan bersolidaritas dengan
kelompok/organisasi lain. Ini penting dilakukan juga dalam rangka konsolidai dan
networing sehingga kita tidak seperti memakai kacamata kuda. Tapi kita juga ada
pembagian tugas, siapa yang bekerja di lapangan (Batang) siapa yang melakukan
kampanye lebih luas (di Yogya) karena di Yogya lebih terbantu dengan adanya LSM,
gerakan mahasiswa, para akademisi yang bisa memberi masukan kepada PEWARTA
sebagai organisasi petani. Ini antara lain keberuntungan bagi PEWARTA yang memilih
tinggal di Yogya,‖ ucap Rudi ketika menjelaskan kenapa PEWARTA memilih
kantornya di Yogyakarta.6
Keadilan Agraria dan Epistemologi Kekuasaan
Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (1963) merumuskan kekuasaan sebagai
‖kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa,
sehingga tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai
kekuasaan”.7 Sementara Van Doorn (1957) melihat kekuasaan sebagai “kemampuan
pelaku untuk menetapkan secara mutlak alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-
alternatif memilih pelaku lain”.8 Hal ini menunjukkan bahwa konsepsi kekuasaan
memperlihatkan suatu hubungan yang bersifat tidak seimbang, dalam arti bahwa satu
pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain.
5 Wawancara dengan Rudi Casrudi, Yogyakarta: 15 Mei 2010.
6 Ibid.
7 Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan (1963). Power and Society: A Framework for Political Inquiry,
Paperback, Yale University Press. 8 Van Doorn, J.A.A, (1957). ―De laatste eeuw van Indie. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal
project‖ dalam AAGN Ari Dwipayana, Kuliah Teori Politik: Konsep Kekuasaan, Bahan Presentasi
Perkuliahan Semester I 2009, Magister Ilmu Politik, Fisipol-UGM, Yogyakarta.
4
Dalam konteks masalah agraria, epistemologi kekuasaan tampak nyata bahwa rakyat
merupakan objek yang tuna-kuasa, baik di hadapan raja maupun di hadapan pemerintah
kolonial Belanda. Potret inilah yang antara lain dilukiskan Tauchid dalam bagian
pertama buku ini. Awalnya, semua tanah dikuasai raja, sementara rakyat yang
mengerjakan tanah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian besar hasilnya.
Rakyat dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan dan kehormatan raja karena segala
peraturan dan hukum-hukum juga dikendalikan seluruhnya oleh raja sebagai pemegang
kuasa. Proses ‘penaklukan‘ rakyat oleh raja bisa dijelaskan dari ragam epistemologi
kekuasaan.
Max Weber, misalnya melihat otoritas kuasa bersumber dari tiga hal, yaitu: tradisional,
kharismatik, dan legal rasional. Sementara Gramsci menitikberatkan pada legitimasi
dan dominasi. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa
wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan
memang sudah sepatutnya. Secara timbal balik, legitimasi juga merupakan produk dari
hegemoni kekuasaan. Dengan mengutip beberapa ahli politik, Haryanto (2005)
membuat kategori teoretik kekuasaan sebagai berikut9:
Tokoh Teori Keterangan
Max Weber Legitimate
Domination Traditional, Charismatik, dan Legal Rational
Charles F.
Andrain
Legitimate
Teory
Traditional Legitimate, Ideologis Legitimate,
Personal Legitimate, Prosedural Legitimate,
Instruental Legitimate
Eksposisi konsep kekuasaan dalam konteks persoalan agrarian memang menempatkan
rakyat sebagai objek yang tuna-kuasa. Dalam ruang politik yang diktator-feodalistik,
misalnya, raja sebagai pihak yang berkuasa seringkali mengendalikan rakyat yang
dikuasainya lewat kekerasan fisik. Namun begitu, pelanggengan kekuasaan juga
dilakukan dengan modal simbolik. Jurgen Habermas salah seorang tokoh teori kritis
mengatakan bahwa bahasa merupakan medium dominasi dan kekuasaan. Artinya,
kekuasaan beroperasi efektif lewat kegiataan berbahasa, yakni lewat proses komunikasi
simbolik.10
Idiom-idiom simbolik seperti ‖manunggaling kawula gusti‖ merupakan
contoh penaklukan rakyat oleh raja. Dalam bahasa lain, Michel Foucault menyebutkan
bahwa arena kuasa tidak berakhir pada represi dari struktur politis, pemerintah, kelas
sosial yang dominan, melainkan menaruh perhatian pada mekanisme dan strategi kuasa,
bagaimana kekuasaan dipraktekkan, diterima dan dilihat sebagai kebenaran, bahkan
menjadi ritual kebenaran yang terus direproduksi.11
Konsepsi kekuasaan itu pula yang dapat menjelaskan mengapa ―reproduksi‖
penderitaan rakyat begitu mudah dipindahkan dari tangan raja-raja ke pemerintah
kolonial Belanda saat VOC berhasil merebut kedaulatan agrarian dari tangan raja-raja
di seantero Nusantara. Tampaknya, pemerintah kolonial Belanda sangat paham
psikologi rakyat Indonesia dalam konteks penguasaan tanah. Mitologi ‖manunggaling
kawula gusti‖, ―raja tak pernah salah‖, dan idiom-idiom simbolik-mitologis kuasa Jawa
9 Haryanto (2005). Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar, S2 PLOD UGM-JIP UGM, Yogyakarta. 10
Jurgen Habermas (1962). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a
Category of Bourgeois Society. The MIT Press, Germany. 11
Michel Foucault (1982). ―The Subject and Power‖ in Beyond Structuralism and Hermeneutics,
University of Chicago Press.
5
lainnya yang lebih memposisikan rakyat sebagai abdi telah mendorong langgengnya
cengkeraman pemerintah kolonial Belanda hingga ratusan tahun lamanya. Konsolidasi
kekuasaan kolonial bahkan dikuatkan lagi dengan dibuatnya ragam aturan (staatsblad)
agraria yang ‗komprehensif‘. Pada masa kolonial Belanda itulah kita menyaksikan
ragam peraturan agraria yang komplit, namun tentu saja semuanya menguntungkan
pemerintah kolonial Belanda sebagai pembuat kebijakan tunggal.12
Fenomena itu seolah menjustifikasi ―model strukturasi‖ sebagaimana diungkapkan
Anthony Giddens. Menurut Giddens, hubungan antara pelaku dan struktur berupa relasi
dualitas terjadi pada praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan
waktu yang mengarahkan kontinuitas dan transmutasi dari struktur untuk mereproduksi
sistem sosial. Dalam konteks ini, Giddens melihat tiga gugus besar struktur, yaitu:
1. Signifikansi menyangkut skemata simbolik, penyebutan dan wacana.
2. Struktur dominasi yang menyangkut skema penguasaan atas orang (politik) dan
barang (ekonomi).
3. Struktur legitimasi menyangkut skema peraturan normatif yang terungkap
dalam tata aturan hukum positif.
Eksposisi konsep strukturasi akan tampak dalam dimensi struktur sosial yang
mempertalikan struktur dengan domain teoretik dan implementasinya dalam tata aturan
yang terinstitusionalisasi. Secara sederhana, hal ini dapat disimak pada tabel berikut:
Struktur Domain Teoretik Aturan Institusi
Signifikansi Teori interpretasi nilai Peraturan simbolik
Dominasi Teori kekuasaan otoritatif Institusi politik dan ekonomi
Legitimasi Teori legitimasi normative Institusi legal/aturan hokum
Secara illustratif, Giddens membuat visualisasi diagram konsep strukturasi sebagai
berikut:
Kuatnya struktur dominasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda antara lain
tampak pada sejumlah aturan agraria yang masih langgeng.13
Bahkan, ketika Indonesia
memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 persoalan agraria tidak serta-merta
terselesaikan secara signifikan Kemerdekaan politik itu tampaknya tidak membawa
dampak nyata bagi masyarakat dalam penuntasan kasus-kasus pertanahan. Malahan
yang terjadi justru makin banyaknya sengketa tanah yang belum terselesaikan dari
12
Penjelasan lebih detil mengenai hal ini dapat disimak dalam Wignjosoebroto, Soetandjo (1994). Dari
Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di
Indonesia (1840-1870). Rajawali Press, Jakarta. 13
Peraturan Agraria pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nr.6 tahun 1952. Undang-undang ini
hanya menetapkan peraturan kolonial Belanda, yaitu ―Undang-undang Darurat Nr.6 tahun 1951 yang
berasal dari ―Grondhuur Ordonnantie‖ (Stbl.1981 Nr88) sebagai Undang-undang.
6
waktu ke waktu. Warisan kolonial dalam persoalan agraria bukan saja tampak dari
peraturan agraria yang masih berbau hukum kolonial, tapi juga dalam cara-cara
kolonial yang sudah terlanjur terstrukturasi dalam penanganan persoalan pertanahan
hingga kini.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), misalnya, mencatat bahwa pendekatan
kekerasan dan teror masih sering dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik
agraria.14
Untuk tahun ini saja, misalnya, KPA telah merekam 89 laporan kasus konflik
agraria dengan luas sengketa 133.278,79 Ha dan korban langsung dari sengketa ini
tidak kurang dari 7.585 KK. Ini tetap saja angka minimal, sebab metode yang dipakai
dalam pendataan ini berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPA
dan direkam oleh KPA melalui pemberitaan media massa.15
Menyeruaknya beragam kasus dan konflik agraria memang perlu segera diantisipasi
dan diselesaikan secara serius. Ahli hukum pertanahan UGM, Maria SW Sumardjono
menilai bahwa permasalahan tanah selalu saja timbul karena kompleksitasnya
persoalan tanah selalu terkait banyak aspek. Tanah sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan dasar manusia akan papan dan pangan serta merupakan sumber daya alam
yang langka itu menjadi rentan diperebutkan oleh banyak pihak.16
Menurut Maria,
persoalan ini selalu timbul karena kita belum memiliki disain reforma agraria yang baik
yang bisa menuntun kita menemukan jalan keluar yang adil bagi para pihak. Lalu
bagaimana persoalan agraria yang terjadi di Batang, Jawa Tengah dan bagaimana
PEWARTA memerankan dirinya sebagai organisasi petani yang punya konsen
terhadap persoalan agraria. Ulasan berikutnya akan membahas peran PEWARTA
dalam melakukan advokasi dan perjuangan hak atas tanah.
Kiprah PEWARTA dan Petani Batang
Batang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di jalur pantura 84
km sebelah barat kota Semarang. Terletak antara 6º 51' 46" dan 7º 11' 47" Lintang
Selatan dan antara 109º 40' 19" dan 110º 03' 06" Bujur Timur. Luas wilayah 78.864,16
Ha berpenduduk sekitar 694.453 jiwa atau dengan kepadatan 879 jiwa per km persegi.
Kabupaten Batang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya karena memiliki
wilayah pantai, dataran rendah maupun pegunungan dengan ketinggian 0-2000m dpl,
menghasilkan komoditi perikanan, perkebunan seperti teh dan karet serta komoditi
perhutanan, terutama berupa kayu jati dan gondorukem.17
Meskipun petani menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk, namun hal ini tidak
diikuti dengan baiknya kualitas hidup para petani. Ini antara lain ditunjukkan oleh
timpangnya kepemilikan tanah di Kabupaten Batang. Rizza Kamajaya (2007) misalnya
14
Dalam laporan tahunannya, misalnya KPA mencatat tertembaknya 12 petani di Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan oleh pihakkepolisian Desember 2009, sebelumnya 10 petani Takalar di Sulawesi
Selatan juga dilaporkan tertembak pada Agustus 2009, dan dua orang Petani Ujung Kulon, Banten pada
Mei 2009. Tahun ini dilaporkan 3 orang petani Bangun Purba, Rokan Hulu, tewas akibat penganiayaan
security (pamswakarsa) PT.SSL. Ini adalah bukti masih dipakainya cara-cara primitif oleh pemerintah
seperti penembakan, pembakaran, penganiayaan, penculikan dan bentuk intimidasi lainnya untuk
menakut-nakuti rakyat ketika memperjuangkan hak-haknya dalam menyelesaikan sengketa agraria 15
Laporan Akhir Tahun 2009, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dapat disimak pada link berikut: http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=1 16
Maria SW Sumardjono (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit
Buku Kompas, Jakarta. 17
http://www.batangkab.go.id/index.php?nav=com_menu&id=2
7
mengungkapkan bahwa peta pertanahan diKabupaten Batang lebih merupakan warisan
kepemilikan dari paea land lord dengan tradisi feodal yang masih kuat. Ironisnya,
meskipun Indonesia telah merdeka, penguasaan tanah itu bukan kembali kepada rakyat,
namun justru jatuh ke tangan pemilik modal serta korporasi negara yang dibackup oleh
aparat militer.18
Tak heran jika kemudian persoalan agraria di Kabupaten Batang sejak
lama telah memunculkan perlawanan petani yang cukup massif.
Muhammad Qodari (2003) menyebutkan bahwa gerakan reclaiming tanah petani di
Kabupaten Batang semula bersifat sporadis, dalam artian tidak atau belum terorganisir
dan berlangsung secara terpisah di sejumlah desa atau kumpulan desa. Namun
selanjutnya gerakan ini menjadi terorganisir dengan dibentuknya Organisasi Tani Lokal
(OTL) sebagai wahana perjuangan petani. Satu OTL dapat terdiri dari satu desa atau
gabungan beberapa desa sekaligus. Untuk memperkuat gerakan bersama, pada 2 Juni
2000 empat OTL bersepakat membentuk sebuah organisasi payung yang dinamakan
Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). Kini, anggota FPPB berjumlah 7 OTL.19
Nama OTL Jumlah Anggota Lawan
Pesedeluran Petani Penggarap
Perkebunan Tratak (P4T)
521 KK PT. Tratak
Paguyuban Patani Sido Dadi
(P2SD)
1.113 KK PT.Segayung
Petani Kebumen dan Simbang
(Kembang Tani)
853 KK PT. Ambarawa Maju
Paguyuban Petani Korban PT.
Pagilaran (P2KPP)
1.516 KK PT. Pagilaran
Petani Sido Makmur (PSM) 437 KK PT. Estu Subur
Petani Maju Kurang Tanah
(PMKT)
435 KK PT. Estu Subur
Paguyuban Patani Sido Mulyo
(P2SM)
475 KK Haji Suwardjo
Sumber: diolah dari data dokumen FPPB
Seiring bertambah kompleksnya persoalan petani di Kabupaten Batang, jumlah OTL
pun terus bertambah. Selain ketujuh OTL di atas, belakangan juga muncul OTL baru
yang juga memiliki persoalan agraria. Beberapa OTL yang muncul kemudian adalah
Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK), Paguyuban Petani Jati Rejo
(P2JR) di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, dan Paguyuban Petani Gringging Sari
Maju (P2GSM). Sebagaimana OTL yang lahir sebelumya, OTL ini pun memiliki
persoalan tanah, baik dengan pihak perusahaan perkebunan maupun dengan Perhutani
Kabupaten Batang. Dalam konteks perjuangan agraria itu pula, selain FPPB sebagai
organisasi payung OTL hadir pula organisasi Persaudaraan Warga Tani (PEWARTA)
yang juga turut membantu perjuangan petani di Kabupaten Batang.
Kehadiran PEWARTA –yang secara formal berdomisili di Yogyakarta— awalnya
diinisiasi oleh para aktifis mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang
bernama KAM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tergabung dalam
SEKAM. Para aktifis mahasiswa ini sering tinggal (live-in) di Batang terutama di
18 Kamajaya, Rizza (2007). Transformasi Strategi Gerakan Petani: Dari Gerakan Bawah Tanah
Menuju Gerakan Politik Formal Studi Kasus Gerakan Petani Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah,
Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
19 Qodari, Muhammad (2003). ―Sebuah Figur dalam Gerakan Petani Batang: Pengalaman dari Jawa
Tengah‖ dalam AE. Priyono et all (2003) Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto, Demos,
Jakarta.
8
rumah para warga yang ada OTL-nya. Dari persinggungan aktifisme inilah kemudian
PEWARTA lahir dan hadir bersama para petani dengan OTL-nya dan turut mengawal
perjuangan petani dengan segala persoalannya.
Ketua Badan Pelaksana PEWARTA, Dodi Uji Haryono, mengungkapkan bahwa
persoalan petani sejatinya sangat klasik. Persoalannya dari dulu hingga kini sebetulnya
tidak jauh bergeser yaitu soal lahan garapan. Persoalannya adalah keterbatasan lahan
bagi yang mempunyai lahan. Bahkan ada juga yang benar-benar tidak memiliki lahan.
Persoalan kedua, menurutnya adalah soal produksi tani mulai dari pengolahan tanah,
pupuk, hama, dan lain-lain. Dalam konteks ini petani sekarang menjadi sangat
tergantung pada obat-obat kimia yang bahkan dapat mengundang persoalan lain yaitu
kondisi tanah yang rusak. Persoalan kemudian soal distribusi hasil, karena akses
transportasi yang minim sehingga petani kesulitan menjual produksi hasil taninya
karena terkendala transportasi yang sulit. Karena itu, menurut Dodi, dari sisi harga
produk tani mereka tidak punya posisi tawar karena kalau lama menahan barang
akhirnya akan rugi. Persoalan lain soal budaya organisasi dimana petani belum terbiasa
berorganisasi, kalupun ada organisasi tani itu pun sangat monolitik seperti HKTI.
‖Iklim demokrasi belum sepenuhnya membuka cakrawala petani untuk berpikir keluar
dari tantangannya,‖ ujarnya.20
Senada dengan itu, Ketua Divisi Organisasi PEWARTA, M. Asari menyebutkan dua
tantangan utama yang dihadapi petani di kabupaten batang. Pertama, di level intern,
kurun waktu perjuangan pasca reformasi, gerakan petani mengalami kelelahan. Karena
kasus-kasus tanah tidak serta merta selesai pasca reformasi. Gerakan mereka lebih
reaksioner tanpa didasari pemahaman yang baik mengenai reorma agraria. Mereka
berharap setelah berhasil melakukan reklaiming persoalan tanah selesai, tapi ternyata
tidak. Dalam hal inilah kita harus memberi penyadaran kepda petani untuk memahami
persoalan reforma agraria secara lebih tepat. Kedua, di level ekstern, tidak ada
dukungan dari pemerintah terhadap gerakan petani, baik dari para eksekutif maupun
dari kalangan legislatif.21
Ketua OTL Subah, Batang Samsudin mengungkapkan bahwa selama menjadi petani
dirinya belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, entah dari bupati maupun dari
DPRD. Ia bahkan menuturkan bahwa hingga kini pemerintah tidak punya perhatian
sama sekali terhadap penderitaan petani. Dalam banyak kasus pertanahan, pemerintah
baik di level eksekutif maupun legislatif tidak berpihak kepada petani, tapi lebih
berpihak kepada pemodal. Menurut samsudin, bukan saja dalam soal koflik pertanahan,
tapi dalam soal pendidikan untuk petani pun lembaga-lembaga pemerintah seperti
departemen pertanian, bahkan, tidak pernah memberikan penyuluhan bagi petani.
‖BPN, Departemen Pertanian, Perhutani, dan lain-lain itu tak ada gunanya bagi petani.
Justru organisasi seperti PEWARTA inilah yang seringkali membantu kami,‖ ujarnya.22
Ketua FPPB, Sugandhi, mengamini pernyataan itu. Menurut Sugandhi, pemerintah
bahkan seakan membiarkan para petani dikriminalisasi entah oleh pihak pengusaha
maupun oleh aparat pemerintah seperti kepolisian. Berbagai pelanggaran HAM,
menurutnya, sering dilakukan aparat pemerintah terhadap petani. ‖Kita sering dituduh
sebagai PKI, dirampas dan diusir dari tanah garapan, pengambilan tanah masyarakat
20
Wawancara dengan Dodi Uji Haryono, Batang: 5 Juni 2010. 21
Wawancara dengan M.Asari, Batang: 5 Juni 2010. 22
Wawancara dengan Samsudin, Batang: 6 Juni 2010.
9
oleh petani, dan lain-lain,‖ ujarnya.23
Dalam menghadapi berbagai persoalan seperti
itulah menurut Sugandhi, PEWARTA banyak membantu perjuangan petani. Oleh
karena itu, kiprah PEWARTA memang sangat banyak diharapkan oleh para petani di
Kabupaten Batang.
Ketua Badan Pengurus PEWARTA, Dodi Uji Haryono menyadari bahwa harapan
masyarakat, terutama kelompok petani di Kabupaten Batang berharap begitu banyak
atas kiprah PEWARTA. Mulai dari pendataan kasus, pelatihan pendidikan politik bagi
para petani, hingga pendampingan kasus-kasus atas pelanggaran HAM24
terhadap
petani menjadi rentetan agenda PEWARTA. Namun demikian, para pengurus
PEWARTA juga menyadari berbagai keterbatasan yang dimilikinya.‖Terus terang,
kami merasa berat untuk melakukan semua hal, karena itu PEWARTA mencoba
melakukan apa yang mampu kita lakukan, terutama menyangkut pendidikan petani,
baik formal maupun informal,‖ ujarnya.
Dodi kemudian menguraikan bahwa pendidikan formal yang dimaksudkan adalah
bentuk traning-traning advokatif soal keorganisasian, kepemimpinan. Model
pendidikan ini diberikan kepada petani dengan harapan agar ke depan para petani
mampu melakukan advokasi secara mandiri. Sementara pendidikan informal biasanya
dilakukan dalam pertemuan-pertemuan sosial yang intinya memberikan penyadaran.
Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan pertemuan informal seperti
selapanan, yasinan yang sekaligus dimanfaatkan untuk menyusun agenda atau paling
tidak informasi seputar kasus maupun problem produksi petani. ‖Kenyataannya,
pendidikan formal itu kalau tidak ditinjklanjuti dengan yang informal agak sia-sia. Para
petani justru lebih banyak memahami pada saat acara-acara yang bersifat informal.
Karena itu perlu disinegikan,‖ tambah Dodi.25
Dari berbagai upaya yang dilakukan PEWARTA, secara umum kiprah yang diperankan
PEWARTA bersama para petani di Kabupaten Batang dapat dikategorkan dalam empat
agenda utama, yaitu: 1) beragam pendampingan kasus, 2) upaya penyebaran informasi,
3) pendidikan para legal bagi para aktifis petani, dan 4) inisiasi transformasi gerakan
petani dari gerakan sosial ke gerakan politik formal.26
1. Pendampingan Kasus
Hingga saat ini sudah ada belasan kasus tanah yang terjadi di wilayah Kabupaten
Batang di mana PEWARTA turut ambil bagian dalam upaya penyelesaiannya.
Langkah pertama yang dilakukan PEWARTA dalam membantu upaya ini adalah
dengan melakukan identifikasi terhadap sumber konflik. Mulai dengan memetakan
posisi kasus, siapa saja pihak-pihak yang bersengketa, memantau perkembangan
atau progres yang dihasilkan hingga solusi yang dikehendaki para pihak. Kemudian,
PEWARTA juga berupaya menentukan bentuk pilihan advokasinya, apakah
misalnya melalui litigasi ke pengadilan atau pendampingan di luar hukum acara
pengadilan (non-litigasi). Ketua Divisi Organisasi, M. Asari mengungkapkan
bahwa pola pendampingan yang dilakukan PEWARTA biasanya bersifat dua arah.
‖Artinya, pengurus PEWARTA bisa proaktif turun ke bawah melakukan
anjangsana ke petani untuk menanyakan kasus atau bisa juga sebaliknya, petani
23
Wawancara dengan Sugandhi, Batang: 5 Juni 2010. 24
Beberapa kasus pelanggaran HAM terhadap petani di Kabupaten Batang yang mendapat pengawalan
PEWARTA dapat disimak pada table di bagian lampiran. 25
Ibid. 26
Dokumentasi berbagai kegiatan PEWARTA dapat disimak dalam lampiran.
10
yang datang biasanya ke Ketua PEWARTA untuk melaporkan kasus yang menimpa
dirinya atau kelompoknya,‖ ujar Asari.27
Asari juga menyebutkan bahwa berbagai upaya pendampingan kasus yang telah
dilakukan PEWARTA di satu sisi memang masih jauh dari harapan karena masih
banyaknya kasus yang belum tertangani secara tuntas. Namun demikian,
menurutnya, ada pula kasus-kasus yang pencapaian targetnya sudah lumayan sesuai
dengan yang diharapkan. ‖Dari segi pengetahuan, sudah mulai muncul pemahaman
mengenai reforma agraria terutama dari para pegiat dan pengurus organisasi tani.
Kedua, dari segi penguasaan tanah, ada beberapa keberhasilan misalnya di
Kecamatan Tulis dan Subah dimana sebagian petani sudah berhasil mendapatkan
hak atas tanah bahkan dengan sertifikasinya,‖ tambahnya.
2. Penyebaran Informasi
Dalam abad teknologi informasi sekarang ini, informasi menjadi senjata paling
penting yang dapat dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk juga oleh gerakan tani.
Oleh karena itu, dalam mengawal perjuangan petani, PEWARTA juga menjadikan
informasi sebagai salah satu andalan kekuatannya. Pemilihan Kota Yogyakarta
sebagai basis kantornya merupakan salah satu pilihan sadar PEWARTA bahwa
Kota Pendidikan ini dapat menjadi andalan tersendiri dalam menjaring informasi
dalam rangka membuat dan memperkuat strategi kegiatan untuk penguatan petani.
Dalam tataran lebih praksis lagi, upaya konkret yang dilakukan PEWARTA dalam
rangka penyebaran informasi ke petani adalah dengan membangun ‖Radio Puspita‖
bersama para aktifis petani di Kabupaten Batang. Nama ‖Puspita‖ sendiri dipilih
secara sengaja yang merupakan kepanjangan dari ‖pusat penyebaran informasi
tani‖. Ketua Radio Puspita, Sujono mengungkapkan bahwa pertimbangan
dibangunnya radio ini adalah adanya kebutuhan para petani atas informasi yang
cepat dan murah. ‖Kami para petani juga perlu informasi, karena itu ketika
PEWARTA menawarkan untuk membantu membuat radio kami sangat tertarik
karena kami anggap ini akan sangat membantu,‖ ujarnya.28
Mengenai bentuk acara radionya, Sujono mengakui bahwa Puspita tidak punya
acara yang muluk-muluk. Namun begitu ia yakin informasi yang disampaikan radio
Puspita yang on-air delapan jam sehari mulai pukul 14.00 – 22.00 itu sangat
bermanfaat bagi para petani. ‖Ada dialog dan tanya jawab soal kasus-kasus petani
yang biasanya diisi orang PEWARTA. Ada juga informasi lainnya soal pertanian,
seperti soal musim, pupuk, soal penanganan hama, dan lain-lain. Acara pokoknya
sebetulnya cuman hiburan, seperti wayangan dan musik, namun informasi-
informasi pertanian seringkali diselipkan dalam acara itu,‖ tambah Sujono.
3. Pendidikan Paralegal
Pendidikan paralegal yang dicanangkan PEWARTA berangkat dari suatu kesadaran
bahwa persoalan agraria yang dihadapi petani seringkali muncul dalam konteks
ranah hukum yang pelik. Paralegal kemudian diasumsikan sebagai pekerjaan
semilegal untuk membantu pekerja hukum (pengacara atau advokat) dalam
melakukan tindakan legal. Menurut Gunawan (2010) dalam medan perjuangan
kaum tani di lapangan agraria, paralegal diperlukan untuk menjawab minimnya
27
Wawancara dengan M.Asari, Batang: 5 Juni 2010. 28
Wawancara dengan Sujono, Batang: 6 Juni 2010.
11
tenaga advokat guna membela petani dalam konflik agraria.Oleh karenanya,
petugas paralegal yang dilahirkan dari kalangan petani sendiri diharapkan tidak saja
mumpuni menjadi asisten pengacara, tetapi juga mampu memberikan pendidikan
hukum kepada dampingannya (dalam hal ini petani) tentang apa saja hak-haknya,
baik hak konstitusional, hak asasi manusia, maupun hal legal.29
Dalam ulasannya, Riando Tambunan, menyebutkan bahwa pendidikan hukum
dengan tema ―Pendidikan dan Pelatihan Para Legal Untuk Petani‖ ini bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tani terhadap hak-hak
mereka secara hukum atas tanah, dengan harapan bahwa peserta pelatihan akan
dapat melakukan kerja-kerja paralegal dalam rangka memperjuangkan hak atas
tanah sekaligus membela diri mereka dalam hal terjadi kriminalisasi terhadap
anggota organisasi. Meski demikian patut disadari bahwa pelatihan ini hanyalah
merupakan salah satu bekal tambahan bagi petani, karena utamanya perjuangan hak
atas tanah membutuhkan semangat, keberanian dan militansi dari kawan-kawan
petani itu sendiri. ―Materi-materi yang diberikan cukup bervariasi mulai dari materi
hukum sampai dengan politik agraria yang akhirnya ditutup dengan simulasi dan
praktek (mootcourt) seperti simulasi penangkapan, tehnik menjawab interogasi
pihak kepolisian serta proses pengadilan,‖ ujar Riando Tambunan.30
4. Transformasi Gerakan
Meskipun OTL baru terus bermunculan di Kabupaten Batang dengan beragam
tuntutannya, namun tidak serta persoalan agraria yang dihadapi para petani kunjung
berhasil. Malahan beberapa kasus yang telah ditangani dalam waktu yang cukup
lama mengalami kemunduran. Muisin, anggota FPPB di Desa Sengon, Kecamatan
Subah, Kabupaten Batang, misalnya menceritakan bahwa tanah garapannya yang
semula merupakan hasil reklaiming kini harus ia lepaskan kembali karena ia kerap
menghadapi teror. ―Kita sering diancam preman untuk meninggalkan lahan, ya …
akhirnya kita mundur,‖ ucapnya.31
Dalam banyak kasus di beberpa tempat di Kabupaten Batang, para petani yang
awalnya telah berhasil melakukan reklaiming masih harus menghadapi teror dari
preman, mandor, tokoh masyarakat, aparat desa, polisi bahkan tentara. Artinya
petani menggarap lahan dengan tidak tenang dan sewaktu-waktu bisa diusir tanpa
ganti kerugian. Karena itulah para aktifis PEWARTA memandang perlunya
melakukan terobosan cara melalui transformasi gerakan. Bahwa perjuangan
merebut hak atas tanah tidaklah cukup sebatas reklaiming, tapi juga membutuhkan
sebuah saluran/kanalisasi kebijakan politik sebagai penyelesaiaan lainnya. Salah
seorang inisiator PEWARTA, Seno Sudarsono memberi contoh bahwa dalam
penyelesaian konflik agraria perlu dukungan dan tekanan dari pihak legislatif dan
eksekutif.
Menurut Seno, gerakan sosial yang kuat dalam melakukan aksi-aksi massa
membutuhkan penyelesaian yang bersifat politik, mengingat sumber agraria adalah
bagian dari kekuasaan politik. Ia menambahkan bahwa konflik agraria di
Kabupaten Batang sebagai perebutan sumber daya alam akan mengalami kebuntuan
29
Gunawan (2010). Panduan Pendidikan Paralegal untuk Perjuangan Kaum Tani, Penerbitan bersama
CSDS, PEWARTA, IHCS, dan FES, Jakarta. 30
Simak: http://ihcs.or.id/s2/index.php?option=com_content&view=article&id=34:pelatihan-parelegal-
bagi-perjuangan-petani&catid=10:berita-ihcs&Itemid=6 31
Wawancara dengan Muisin, Batang: 6 Juni 2010.
12
jika hanya mengandalkan pada penyelesaiaan kasus lewat proses hukum legal
formal. Untuk itulah dibutuhkan perubahan pola gerakan dengan inisiasi
transformasi gerakan petani dari gerakan sosial ke gerakan politik formal. ‖Artinya,
organisasi tani tidak sebatas melakukan perluasan pendudukan/reklaiming tapi juga
melakukan lobby, negoisasi dan membuka komunikasi politik dengan para
pengambil kebijakan, seperti dengan kepala desa, anggota DPRD dan Kepala
Daerah/Bupati, dan bahkan kalau mampu mendudukkan kader-kadernya di jabatan
tersebut,‖ ujarnya.32
Tak heran jika pada perkembangan berikutnya para aktifis
organisasi petani di Kabupaten Batang kemudian terlibat dalam kontestasi politik
formal-elektoral, baik dalam perebutan Kepala Desa maupun turut terlibat dalam
pemenangan Pilkada.
Berbagai agenda dan ragam kegiatan yang telah dilakukan PEWARTA tentu tidak
serta-merta menuntaskan segenap persoalan yang dihadapi petani di Kabupaten Batang.
Ketua Badan Pengurus PEWARTA, Dodi Uji Haryono bahkan mengakui bahwa upaya
kiprah yang diperankan PEWARTA hanyalah satu segmen awal bagi upaya perjuangan
petani yang sesungguhnya. Menurutnya, kalaulah upaya seperti reklaiming itu mau
dianggap suatu ‘keberhasilan‘, maka itu sebenarnya adalah keberhasilan yang masih
bersifat sementara, karena kenyataannya masih banyak petani yang belum mampu
memanfaatkan tanahnnya. Mereka berpikir yang penting sudah dapat tanah tapi lalu
kemudian bagaimana. ‖Kita terus berupaya menyadarkan petani bahwa perjuangan
reforma agraria itu bukan hanya sekadar bagaimana mendapatkan hak atas tanah, tapi
bagaimana mendapatkan akses-akses yang lebih luas,‖ ujarnya.33
Dodi juga menyebutkan pentingnya menanamkan sikap-sikap yang lebih ‘politis‘
kepada para petani, karena sebenarnya muara persoalan tanah itu ada di situ. Pekerjaan
rumah lainnya yang harus menjadi agenda gerakan petani di Kabupaten Batang,
menurut Dodi adalah membangun kebersamaan diantara semua gerakan petani yang
ada sehingga kekuatannya tidak terpecah-pecah. ‖ini persoalan bagaimana membangun
dan membina organisasi tani agar kuat dan fungsional,‖ tambahnya.
Senada dengan itu, Imam Yudotomo, Direktur CSDS yang juga pendiri PEWARTA
memberikan otokriktiknya terhadap gerakan petani. Menurutnya, budaya organisasi
dalam gerakan petani masih masih lemah, termasuk di PEWARTA. Kelemahan
lainnya, menurut Imam adalah organisasi tani mudah terpecah-pecah karena rapuhnya
persatuan diantara mereka, termasuk kurangnya persatuan dalam kerja-kerja kolektif.
Padahal, menurut Iman hal ini penting untuk dimiliki petani. ‖Ini terbukti, misalnya
mekanisme kerja kolektif bisa menjadi jawaban. Contoh, transmigran Bali lebih banyak
berhasil karena mereka terbiasa dengan model kerja kolektif,‖ ujarnya.34
Selain itu,
kekurangan lainnya menurut Imam adalah petani kita cenderung cepat puas. ‖Setelah
mendapatkan tanah, mereka lupa tujuan dan ia malah menjual tanahnya. Beberapa hal
ini perlu menjadi bahan refleksi sekaligus dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan
gerakan petani ke depan ‖ tambah Imam.
32
Wawancara dengan Seno Sudarsono, Yogyakarta: 10 Juni 2010. 33
Wawancara dengan Dodi Uji Haryono, Batang: 5 Juni 2010. 34
Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta: 22 Mei 2010.
13
Daftar Pustaka
Foucault, Michel (1982). ―The Subject and Power‖ in Beyond Structuralism and
Hermeneutics, University of Chicago Press.
Gani, Sadikin (2006) ―Tantangan Reforma Agraria‖ dalam situs: http://rumakiri.net
Gunawan (2010). Panduan Pendidikan Paralegal untuk Perjuangan Kaum Tani,
Penerbitan bersama CSDS, PEWARTA, IHCS, dan FES, Jakarta.
Habermas, Jurgen (1962). The Structural Transformation of the Public Sphere: An
Inquiry into a Category of Bourgeois Society. The MIT Press, Germany.
Haryanto (2005). Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar, S2 PLOD UGM-JIP
UGM, Yogyakarta.
Kamajaya, Rizza (2007). Transformasi Strategi Gerakan Petani: Dari Gerakan Bawah
Tanah Menuju Gerakan Politik Formal Studi Kasus Gerakan Petani Kabupaten
Batang, Provinsi Jawa Tengah, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Konsorsium Pembaruan Agraria (2009). Laporan Akhir Tahun 2009, KPA, Jakarta.
dalam situs: http://www.kpa.or.id/
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan (1963). Power and Society: A Framework
for Political Inquiry, Paperback, Yale University Press.
Qodari, Muhammad (2003). ―Sebuah Figur dalam Gerakan Petani Batang: Pengalaman
dari Jawa Tengah‖ dalam AE. Priyono et all (2003) Gerakan Demokrasi di Indonesia
Pasca-Soeharto, Demos, Jakarta.
Setiawan, Usep ―Menjaring Komitmen Demi Keadilan Agraria‖, dalam Kompas: Edisi
17 November 2003.
Sumardjono, Maria SW (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
---------------- (1982). Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Jurusan Hukum
Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tauchid, Mochammad (2007) Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia, PEWARTA, Yogyakarta.
Wignjosoebroto, Soetandjo (1994). Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional:
Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (1840-1870).
Rajawali Press, Jakarta.
Wiradi, Gunawan (2009). Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa, IPB Press,
Bogor.
Wiradiputra, RA (1952). Agraria (Hukum Tanah), Penerbit Jambatan, Jakarta.
14
http://ihcs.or.id/s2/index.php?option=com_content&view=article&id=34:pelatihan-
parelegal-bagi-perjuangan-petani&catid=10:berita-ihcs&Itemid=6
http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=97
http://www.batangkab.go.id/index.php?nav=com_menu&id=2
http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=1
Undang-undang Darurat Nr.6 tahun 1951
Undang-Undang Nr.6 tahun 1952
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960
Wawancara
Wawancara dengan Rudi Casrudi, Yogyakarta: 15 Mei 2010.
Wawancara dengan Imam Yudotomo, Yogyakarta: 22 Mei 2010.
Wawancara dengan Dodi Uji Haryono, Batang: 5 Juni 2010.
Wawancara dengan M.Asari, Batang: 5 Juni 2010.
Wawancara dengan Sugandhi, Batang: 5 Juni 2010.
Wawancara dengan Samsudin, Batang: 6 Juni 2010.
Wawancara dengan Muisin, Batang: 6 Juni 2010.
Wawancara dengan Sujono, Batang: 6 Juni 2010.
Wawancara dengan Seno Sudarsono, Yogyakarta: 10 Juni 2010.