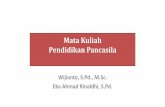BAB II - Digital Library UNS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of BAB II - Digital Library UNS
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Hukum Pidana Internasional
a. Pengertian Hukum Pidana Internasional
Bassiouni menyatakan bahwa hukum pidana internasional adalah
disiplin hukum yang kompleks, yang komponennya lebih dari satu disiplin
hukum dan memiliki hubungan fungsional diantaranya (Eddy O.S Hiariej,
2009: 8).
Pidana internasional menurut Bantekas dan Nash adalah perpaduan
antaran dua disiplin hukum, yaitu hukum internasional dan hukum pidana
nasional (Eddy O.S Hiariej, 2009: 1).
Sehingga untuk mengetahui definisi hukum pidana internasional
harus mengetahui dulu definisi dari hukum pidana dan hukum
internasional.
1) Pengertian Hukum Pidana
Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagai bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh
dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa
yang melakukan. Juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang
telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dengan
cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno,
2008: 1).
Menurut Sudarto memberikan definisi hukum pidana, yaitu
penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang-orang yang
melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan
Badra Namawi, 1998: 2)
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 13
2) Pengertian Hukum Internasional
Menurut Sugeng Istanto hukum internasional adalah sebagai
kumpulan ketentuan hukum yang berlakuknya dipertahankan oleh
masyarakat internasional (Sugeng Istanto,1998: 2).
Starke memberi definisi hukum internasional publik sebagai
keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah
yang mengikat negara-negara untuk mentaatinya dalam hubungan
antar negara-negara itu sendiri (J.G. Starke,2001: 1).
3) Pengertian Pidana Internasional
Menurut Bassiouni hukum pidana internasional adalah
perpaduan dari dua disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling
melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan
aspek-aspek internasional dari hukum pidana (Eddy O.S Hiariej,
2009:8).
b. Sumber-Sumber Hukum Pidana Internasional
Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan dan
menggali suatu hukum.
Sugeng Istanto berpendapat bahwa sumber hukum formil ialah
faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum
yang berlaku umum. Tegasnya, sumber hukum formil adalah yang
membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif yakni
proses perundang-undangan dan kebiasaan. Di sisi lain, hukum
materiil ialah faktor yang menetukan isi ketentuan hukum yang
berlaku (Sugeng Istanto, 1998: 10-11).
Dalam hukum pidana internasional sendiri terdapat perpaduan sumber
hukum yaitu hukum internasional tentang kejahatan dan hukum pidana
yang mengandung dimensi nasional.
Sumber hukum dalam konteks hukum internasional mengacu pada
Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, dalam memutus
sengketa internasional yang diserahkan padanya, hakim mahkamah
internasional dapat menggunakan:
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 14
1) Perjanjian internasional (International Conventions);
2) Kebiasaan internasional (Internastional Custom), sebagai bukti praktik
umum yang dierima sebagai hukum;
3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang
beradab (General Principles of Law Recognized by Civilized Nations);
4) Putusan pengadilan dan doktin atau karya hukum sebagai sumber
hukum tambahan (subsidiary).
Selain sumber hukum pidana internasional yang diutarakan di atas,
ada juga apa yang disebut dengan istilah jus cogens. Jus cogens adalah
hukum pemaksa tertinggi dan harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab di
dunia sebagai prinsip dasar yang umum dalam hukum internasional yang
berkaitan dengan moral. Dalam konteks hukum pidana internasional,
perlindungan terhadap perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai
kemanusiaan yang fundamental seperti hak hidup merupakan jus cogens,
sehingga kejahatan yang merupakan pengikaran terhadap jus cogens tidak
dapat disampingi oleh aturan hukum manapun (Eddy O.S Hiariej, 2009:8).
Sedangkan sumber hukum pidana internasional dalam konteks hukum
nasional negara-negara seperti:
1) Peraturan perundang-undangan;
2) Asas-asas hukum pidana nasional;
3) Putusan badan peradilan nasional.
Jadi sumber hukum pidana internasioal terdiri dari hukum
internasional yaitu: perjanjian internasional, kebiasaan internasional,
prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang
beradab, putusan pengadilan dan doktrin, dan dari hukum pidana nasional
yaitu: peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana nasional,
putusan badan peradilan nasional.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 15
c. Asas-Asas Hukum Pidana Internasional
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum atau prinsip
hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan pikiran dasar
yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang
konkret yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang
terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang
merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat
umum dalam peraturan hukum konkret tersebut. Ditegaskan lagi oleh
Sudikno, bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret,
melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat
umum dan abstrak (Sudikno Mertokusumo, 2003: 34-35).
Sebagaimana sumber hukum pidana internasional, asas hukum
internasional juga terdiri 2 (dua) aspek yaitu, asas hukum pidana
internasional yang berasal dari hukum internasional secara garis besar
dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus.
Asas-asas hukum pidana internasional yang bersifat umum:
1) Pacta sunt servanda: setiap Perjanjian menjadi hukum yang mengikat
para pihak yang melakukan perjanjian.Bila dihubungkan dengan
sumber hukum pidana internasional, dapat dipahami bahwa perjanjian
internasional merupakan urutan paling atas dalam sumber hukum
pidana internasional;
2) Good faith: bahwa semua kewajiban yang diembani oleh hukum
internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya;
3) Civitas maxima: bahwa ada sistem hukum universal yang dianut semua
bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan;
4) Resiprokal: bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan
baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga
harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara lain;
5) Kemerdekaan, berdaulat, dan sederajat.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 16
Sedangkan asas-asas hukum pidana internasional yang bersifat khusus:
1) Aut dedere aut punere: bahwa pelaku kejahatan internasional diadili
menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan;
2) Aut dedere aut judicare: bahwa setiap negara berkewajiban menuntut
dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban
melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan,
menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional;
3) Par in parem in hebet imperium: bahwa kepala negara tidak dapat
dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas par in parem
in hebet imperium dikecualikan dari kejahatan-kejahatan serius
terhadap masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan
kemanusiaan, keajahatan perang (Eddy O.S Hiariej, 2009: 26-27).
Asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana
nasional:
1) Legalitas: tidak ada kejahatan yang dapat dipidana, sebelum aturan
hukum dibuat terlebih dahulu;
2) Territorial: Perundangan suatu negara berlaku bagi semua orang yang
melakukan kejahatan di negara tersebut;
3) Ne bis in idem: seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di
depan pengadilan atas perkara yang sama. Dikecualikan terhadap
kejahatan-kejahatan berat seperti: genosida, kejahatan perang,
kejahatan terhadap kemanusiaan;
4) Praduga tak bersalah: seseorang yang diduga melakukan kejahatan
wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan dipengadilan.
d. Karakteristik Kejahatan Internasional
Menurut Bassiouni terdapat 10 (sepuluh) karakteristik kejahatan
internasional, meliputi:
1) Explicit recognition of prescribed conduct as constuting an
international crime or a crime or under international law, or a crime
(pengakuan secara ekspisit tindakan-tindakan sebagai kejahatan
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 17
internasional atau kejahatan di bawah hukum internasional atau
kejahatan);
2) Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a
duty to prohibit, prevent, punish, or like (pengakuan secara implisit
dari sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan
menetapkan suatu kewajiban untuk melarang, mencegah, menuntut,
menjatuhkan pidana);
3) Criminalization of the proscribed conduct (kriminalisasi tindakan-
tindakan tertentu);
4) Duty of right to prosecute (kewajiban atau hak untuk menuntut);
5) Duty or right to punish the proscribed conduct (kewajiban atau hak
untuk menjatuhkan pidana atas tindakan tertentu);
6) Duty or right to extradite (kewajiban atau hak mengekstradisi);
7) Duty or right to coorporerate to prosecution, punishment, including,
judicial assistance in penal proceeding (kewajiban atau hak untuk
bekerjasama dalam penuntutan, pemidanaan, termasuk bantuan
yudisial dalam proses pemidanaan);
8) Establishment of criminal jurisdictional basis (penetapan suatu dasar-
dasar yuridkisi kriminal);
9) Reference to the establishment of an international criminal court or an
international tribunal with penal characteristics (referensi
pembentukan pidana internasional atau tribunal internaasional dengan
karakter-karakter pidana);
10) Elimination of the defense of superior orders (penghapusan alasan-
alasan perintah atasan) (Romli Atmasasmita, 2000: 38).
e. Internasionalisasi Kejahatan
Internasionaslisasi kejahatan adalah proses penetapan tindakan-
tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional. Tindakan-tindakan
tertentu yang dapat dinyatakan sebagai kejahatan internasional dapat
melalui doktrin, kebiasaan, atau praktik hukum internasional (Eddy O.S
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 18
Hiariej, 2009:51). Sedangkan proses penetapannya dibahas oleh suatu
komite atau badan bersifat ad-hoc kemudian memperoleh persetujuan dari
suatu konvensi yang diadakan khusus untuk itu.
Terkait dengan internasionalisasi kejahatan, menurut Bassiouni ada 5
(lima) unsur tingkah laku tertentu yang jika salah satu unsurnya terpenuhi,
maka tingkah laku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan.
Kelima unsur tersebut:
1) Tingkah laku yang dilarang berakibat signifikan terhadap kepentingan
internasional, khususnya perdamaian dan keamanan internasional
(contoh: kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida);
2) Tingkah laku yang dilarang merupakan perbuatan buruk dan dianggap
mengancam nilai-nilai yang dianut bersama oleh maasyarakat dunia,
termasuk apa yang dianggap oleh sejarah sebagai tingkah laku yang
menyentuh nurani kemanusian (contoh: kejahatan perang dan bajak
laut);
3) Tingkah laku yang dilarang memiliki implikasi transnasional yang
melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara dalam
perencanaan, persiapan, perbuatannya, baik melalui keragaman
kewarganegaraan para pelaku kejahatan atau korban atau perlengkapan
yang digunakan melebihi batas-batas negara. (contoh: pembajakan
pesawat udara);
4) Tingkah laku yang membahayakan perlindungan terhadap kepentingan
internasional atau terhadap orang yang dilindungi secara internasional
(contoh: kejahatan terhadap diplomat, kepala negara asing dan konsul);
5) Tingkah laku tersebut melanggar kepentingan internasional yang
dilindungi namun tidak sampai pada poin pertama dan kedua, namun
tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi
internasional. (contoh: pemalsuan uang dan peredaran uang palsu)
(Eddy O.S Hiariej, 2009: 50-52).
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 19
f. Hirarki Kejahatan Internasional
Berdasarkan internasionalisasi kejahatan dan karakteristik kejahatan
internasional, kejahatan internasional memiliki hirarki atau tingkatan.
Sampai dengan tahun 2003 atas dasar 281 konvensi internasional sejak
tahun 1812, ada 28 kategori kejahatan internasional dan berdasarkan 28
kategori tersebut Basiiouni membagi tingkat kejahatan internasional
menjadi 3 (tiga) ,yaitu:
1) International crime
International crime adalah bagian dari jus cogens. Tipikal dan
karakteristik dari international crime berkaitan dengan perdamaian dan
keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.
Kejahatan tersebut meliputi:
a) Aggresion (agresi);
b) Genocide (genosida);
c) Crimes againts humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan);
d) Unlawful possession or use or emplacement of weapons
(penyalahgunaan senjata api);
e) Theft of nuclear materials (pencurian material nuklir);
f) Mercanarism (tentara bayaran);
g) Apartheid;
h) Slavery and slave-related practices (perbudakan);
i) Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment
(penyiksaan dan segala bentuk kekejaman yang tidak manusiawi);
j) Unlawful human experimentation (percobaan yang tidak
manusiawi).
2) International delicts
Tipikal dan karakter international delicts berkaitan dengan
kepantingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu
negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal dari satu negara.
Kejahatan tersebut meliputi:
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 20
a) Piracy (bajak laut);
b) Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety
(pembajakan pesawat terbang dengan cara melawan hukum
internasional tentang keamanan penerbangan);
c) Threat and use of force against internationally protected persons
(mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap orang yang
dilindungi hukum internasional);
d) Threat and use of force against internationally protected persons
(mengancam dan menggunakan kekerasan terhadap orang yang
dilindungi hukum internasional);
e) Crime against united nationas and associated personnel (kejahatan
melawan personel PBB);
f) Taking of civilian hostages (membawa penduduk sipil sebagai
sandera);
g) Unlawful use of the mail (pelanggaran hukum dalam penggunaan
surat);
h) Attacks with exsplosives (serangan dengan menggunakan ledakan);
i) Financing of terrorism (pembiayaan terorisme);
j) Unlawful traffic in drugs and related drugs offenses (pelanggaran
hukum terhadap penjualan obat-obat terlarang);
k) Organized crime (organisasi criminal);
l) Destruction and/or theft of national treasures (menghancurkan atau
mencuri peninggalan bersejarah);
m) Unlawful acts against certain internationally protected elements of
the environment (kejahatan terhadap lingkungan).
3) International infractions
Dalam hukum pidana internasional secara normatif, international
infraction tidak termasuk dalam kategori international crime dan
international delicts. Kejahatan tersebut meliputi:
a) International traffic in obscene materials (menjual-belikan alat-alat
cabul);
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 21
b) Falsification and counterfeiting (pemalsuan mata uang asing dan
materai);
c) Unlawful interferece with submarine cables, and (pelanggaran
hukum dengan mencampuri kabel pada kapal selam);
d) Bribery of foreign public officials (menyuap pejabat publik) (Eddy
O.S Hiariej, 2009: 55-58).
g. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat
1) Melalui Hukum Nasional:
Penegakan hukum pidana internasional yang menggunakan
hukum nasional masing-masing negara di mana kejahatan
internasional tersebut terjadi.Penegakan hukum pidana
internasional menggunakan hukum nasional sering disebut indirect
enforcement system atau penegakan hukum pidana internasional
secara tidak langsung.
2) Melalui Pengadilan ad hoc
Dalam hukum pidana terdapat prinsip yang dianggap
fundamental yaitu asas legalitas yang tertuang dalam adagium
nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.
Berdasarkan prinsip ini seseorang tidak dapat dianggap melakukan
tindak pidana dan dijatuhi pidana apabila sebelumnya tidak ada
kriminalisasi formal terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan
kata lain seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum apabila pada
waktu melakukan perbuatan tersebut belum dinyatakan sebagai
tindak pidana. Pasal 11 Statuta Roma juga mencerminkan hal yang
sama mengenai asas legalitas. Dalam pasal 11 Statuta Roma
menegaskan bahwa yurisdiksi ICC hanya mencakup kejahatan
yang dilakukan setelah Statuta Roma 1998 berlaku yaitu tanggal 1
Juli 2002, jadi berdasarkan pasal 11 tersebut ICC tidak memiliki
kewenangan utuk mengadili kejahatan yang dilakukan sebelum
tanggal 1 Juli 2002. Hal ini juga dikuatkan pada Pasal 24 ayat (1)
Statuta Roma 1998. Sehingga untuk mengadili sutu pelanggaran
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 22
HAM berat yang terjadi sebelum Statuta Roma 1998 berlaku, maka
pelanggaran HAM berat tersebut merupakan yurisdiksi pengadilan
ad hoc. Dibawah ini akan dibahas beberapa mahkamah ad hoc
yang mengadili pelanggaran HAM berat:
a) Mahkamah Nuremberg
Mahkamah Nuremberg dibentuk untuk mengadili
penjahat perang Nazi. Mahkamah Nuremberg dibentuk tahun
1945 berdasarkan Piagam London (London Charter).
Mahkamah Nuremberg terdiri dari empat (4) orang hakim
ditambah dengan empat (4) hakim pengganti berasal dari
keempat negara penyusun Statuta Mahkamah yaitu Amerika
Serikat, Inggris, Prancis dan Uni Sovyet. Mahkamah Nuremberg
memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan terhadap perdamaian
(crimes against peace), keajahatan perang (crimes war),
kejahatan terhadap kemanusian (crimes against humanity).
Dalam mahkamah ini kedudukan resmi pelaku tidak dapat
dijadikan alasan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.
Kejahatan yang dilakukan atas perinstah pemerintah atau atasan,
tidak dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab dan
dijadikan dasar untuk mengurangi hukuman (Eddy O.S Hiariej,
2009: 76).
b) Mahkamah Tokyo
Mahkamah Tokyo dibentuk pada 19 Januari 1946.
Mahkamah Tokyo dibentuk bertujuan untuk mengadili para
penjahat perang Jepang. Berbeda dengan Mahkamah
Nuremberg yang dibentuk oleh para negara pemenang perang
dunia II, Mahkamah Tokyo dibentuk melalui proklamasi
komandan tertinggi sekutu di Timur Jauh, Jendral Douglas Mac
Arthur. Mahkamah Tokyo terdiri 11 hakim yang semuanya
dibentuk oleh Jendral Douglas Mac Arthur. Yurisdiksi
Mahkamah Tokyo hampir sama dengan Mahkamah Nuremberg
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 23
yaitu kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace),
keajahatan perang (crimes war), kejahatan terhadap kemanusian
(crimes against humanity). Mahkamah Tokyo mengatakan
bahwa alasan tindakan negara (act of state) dan perintah atasan
tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab
pelaku, tetapi dapat dijadikan dasar untuk mengurangi
hukumannya. Hal yang sama juga diterapkan jika pelaku
melakukan tindakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai
pejabat resmi (Eddy O.S Hiariej, 2009: 78).
c) International Criminal Trbunal for the Former Yugoslavia
(ICTY)
Dalam rangka merespons konflik bersenjata yang terjadi
di Yugoslavia awal dekade 1992. DK PBB membentuk komisi
ahli pada tanggal 6 Oktober 1992 untuk meneliti pelanggaran
hukum internasional yang terjadi di sana, dari penelitian komisi
ahli tersebut kemudian DK PBB dengan Resolusi Nomor 827
tahun 1993 membentuk ICTY dengan yurisdiksi genosida,
Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, Pelanggaran
berat sebagaimana yang diatur dalam Konvesi Jenewa 1949,
Pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, dan kejahatan
terhadap kemanusiaan yang dilakuakan di dalam wilayah bekas
Yugoslavia sejak 1 Januari 1991. Berbeda dengan Mahkamah
Nuremberg, ICTY tidak dapat memeriksa perkara secara in
absentia. Jika pengadilan tidak dapat menghadirkan terdakwa,
maka penuntut dapat mempresentasikan kasusnya ke majelis
pemeriksa
d) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
Rwanda meupakan negara di Afrika tengah yang
komposisi penduduknya terdiri dari dua (2) kelompok utama,
yaitu suku Hutu (85%) dan suku Tutsi (14%).Pada tahun 1959,
kelompok mayoritas suku Hutu melancarkan pemberontakan
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 24
terhadap pemerintahan Rwanda yang didominasi suku Tutsi.
Pada kurun waktu tahun 1963 hingga 1994, kekerasan etnis
selalu terjadi di negara tersebut, sehingga menimbulkan banyak
korban yang tewas dari penduduk sipil. Melihat kekerasan demi
kekerasan yang terjadi di negara tersebut, akhirnya mendorong
DK PBB membentuk komisi ahli yang bertugas meneliti dan
membuat rekomendasi tentang grave violantions of
international humanitarian law dan evidence of possible act of
genocide di Rwanda. Pada tanggal 29 September 1994, komisi
ahli menyerahkan laporan awalnya kepada DK PBB, serta
merekomendasikan dibentuknya mahkamah kejahatan
internasional. Pada tanggal 8 November 1994, DK PBB
memutuskan membentuk International Criminal Tribunal for
Rwanda (ICTR) dengan yurisdiksi genosida, kejahatan terhadap
kemanusian, dan Pelanggaran berat sebagaimana yang diatur
dalam Konvesi Jenewa 1949 (Arie Siswanto, 2005: 6-8).
3) Melalui International Criminal Court (ICC)
ICC didirikan berdasakan Statuta Roma 1998 tanggal 17
Juni 1998 yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil pemungutan suara
terdiri dari 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21
negara abstain. ICC mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2002.
Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-
kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). ICC
bekerja apabila pengadilan nasional tidak mau (unwilling) atau
tidak mampu (unable). Menurut Pasal 5 sampai dengan 8 Statuta
Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi terhadap empat macam
kejahatan yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
kejahatan perang, dan agresi. Dalam ICC berlaku tanggung jawab
individu, dengan demikian ICC tidak berwenang memeriksa dan
mengadili negara maupun organisasi internasional berdasarkan
pada Pasal 25 Statuta Roma 1998. Jumlah hakim dalam ICC
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 25
berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta Roma 1998 berjumlah 18
orang dengan masa jabatan selama 9 tahun. Secara umum,
pengajuan kasus ICC dapat dilakukan oleh beberapa pihak baik
dalam wilayah negara pihak Statuta Roma 1998 maupun bukan
pihak Statuta Roma 1998, berikut tabel yurisdiksi territorial di
wilayah negara pihak Statuta Roma 1998 maupun bukan pihak
dalam Statuta Roma 1998 (Arie Siswanto, 2005: 41).
Tabel. 1. Yurisdiksi Teritorial ICC
Wilayah Inisiatif
Penuntutan dari
Negara Pihak
Inisiatif
Penuntutan
dari Penuntut
Umum ICC
Inisiatif
Penuntutan
dari Dewan
Keamanan
PBB
Negara
Pihak
Dapat Dapat Dapat
Negara
Bukan
Pihak
Dapat, asal pelaku
pelanggaran adalah
warga negara dari
negara pihak
Dapat, asal
pelaku
pelanggaran
adalah warga
negara dari
negara pihak
Dapat
h. Kriteria Pelanggaran HAM Berat menurut pengadilan Ad hoc dan
International Court of Criminal (ICC)
1) Menurut pengadilan ad hoc:
a) Pengadilan Nuremberg:
(1) Kejahatan terhadap perdamaian
Yaitu, perencanaan, persiapan, inisiasi atau
pelaksanaan perang agresi, atau peperangan yang
melanggar perjanjian internasional, atau ikut serta dalam
suatu konspirasi untuk melakukannya (Pasal 6 huruf a
London Charter 1945).
(2) Kejahatan perang
Yaitu, pelanggaran terhadap hukum-hukum atau
kebiasaan-kebiasaan perang, pembunuhan, perlakuan
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 26
buruk, deportasi, perbudakan, perampasan, dan
penghancuran (Pasal 6 huruf b London Charter 1945).
(3) Kejahatan terhadap kemanusiaan
Yaitu, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
deportasi (pengasingan, pengiriman kembali ketempat
asal) dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak manusiawi
yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebelum atau
selama terjadi peperangan, atau penganiayaan yang
didasarkan pada latar belakang politik, rasial atau agama
dalam pelaksanakan hukuman atau dalam kaitannya
dengan sesuatu kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi
mahkamah yang dilakukan, apakah hal itu melanggar atau
tidak dengan hukum nasional sesuatu Negara (Pasal 6
huruf c London Charter 1945).
b) Pengadilan Tokyo
(1) Kejahatan terhadap perdamaian
Yaitu, persiapan, pencetusan, dan pelaksanaan perang
sebagai tindakan agresi baik yang dideklarasikan maupun
tidak atau perang yang melanggar hukum atau perjanjian
internasional atau yang ikut serta dalam suatu rencana
bersama atau konspirasi demi terlaksananya salah satu
bentuk kejahatan (Pasal 5 huruf a Special Proclamation
Establishment of an International Military Tribunal for
The Far East).
(2) Kejahatan perang
Yaitu, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan
perang (Pasal 5 huruf b Special Proclamation
Establishment of an International Military Tribunal for
The Far East).
(3) Kejahatan terhadap kemanusiaan
Yaitu, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang
dilakukan terhadap populasi sipil manapun, sebelum dan
selama masa perang. Adanya penyiksaan berdasar politik
atau ras, sebagai bagian atau dilakukan sehubungan dengan
bentuk kejahatan lainnya yang masuk dalam yurisdiksi
pengadilan, baik tindakan tersebut dianggap sebagai
kejahatan atau tidak menurut hukum domestik dimana
tindakan tersebut dilakukan (Pasal 5 huruf c Special
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 27
Proclamation Establishment of an International Military
Tribunal for The Far East).
c) International Criminal Trbunal for the Former Yugoslavia
(ICTY)
(1) Pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam Konvesi
Jenewa 1949
Pengadilan Internasional (dalam hal ini ICTY)
dapat memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang
yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan
suatu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12
Agustus 1949, yaitu tindakan berikut terhadap orang atau
harta benda (kekayaan) yang dilindungi berdasarkan
ketentuan Konvensi Jenewa (Pasal 2 Statuta ICTY).
(2) Pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang
Pengadilan Internasional (dalam hal ini ICTY)
dapat memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang
yang melanggar hukum atau kebiasaan perang (Pasal 3
Statuta ICYT).
(3) Genosida
Pengadilan Internasional (dalam hal ini ICTY)
dapat memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang
melakukan genosida sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Pasal ini atau melakukan tindakan-tindakan lain yang
disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini (Pasal 4 ayat (1)
Statuta ICTY).
(4) Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pengadilan Internasional (dalam hal ini ICTY)
dapat memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang
yang bertanggung jawab atas kejahatan berikut ketika
dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang berskala
internasional maupun internal dan ditujukan terhadap
penduduk sipil (Pasal 5 Statuta ICTY).
d) International Criminal Tribunal for the Former Rwanda
(ICTR)
(1) Genosida
The International Tribunal for Rwanda dapat
melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan
genosida yang seperti didefinisikan pada ayat (2) dari Pasal
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 28
ini atau melakukan suatu tindakan yang disebutkan pada
ayat (3) dari Pasal ini (Pasal 2 ayat (1) Statuta ICTR).
(2) Kejahatan terhadap kemanusiaan
The International Tribunal for Rwanda dapat
melakukan penuntutan terhadap orang yang bertanggung
jawab melakukan kejahatan tersebut dan serangan tersebut
meluas dan sistematis dan ditujukan kepada penduduk sipil
pada suatu bangsa, politik, etnis, atau agama tertentu (Pasal
3 Statuta ICTR).
(3) Pelanggaran berat terhadap Pasal 3 ketentuan bersama
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun
1977.
The International Tribunal for Rwanda dapat
melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan
atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran serius
terhadap bagian 3 konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yaitu
tentang perlindungan terhadap korban perang, dan protokol
tambahan II 8 juni 1977. Semua pelanggaran termasuk,
tapi tidak harus terbatas (Pasal 3 Statuta ICTR)
2) Menurut International Court of Criminal (ICC)
a) Genosida
Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap
perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk
menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu
kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan (Pasal 6 Statuta
Roma 1998).
b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap
kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini
apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau
sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk
sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu (Pasal 7 ayat (1)
Statuta Roma 1998).
c) Kejahatan perang
Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan
kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 29
bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian
dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan
tersebut. (Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma 1998)
i. Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh International Court of Criminal
(ICC) menurut Statuta Roma 1998
1) Bersifat komplementer;
Artinya, jika terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi
mahkamah pidana internasional, maka pengadilan terhadap pelaku
kejahatan terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional
negara dimana kejahatan tersebut dilakukan. Apabila negara
tersebut tidak mau atau tidak dapat mengadili pelaku kejahatan
tersebut, maka pengadilan terhadap pelaku dilakukan oleh
mahkamah pidana internasional.
2) Asas legalitas;
Asas ini berlaku secara absolut dan tidak dimungkinkan
penyimpangan terhadapnya selama menyangkut kejahatan-
kejahatan yang menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional.
Tidak hanya larangan hukum berlaku surut (non retroaktif),
larangan terhadap analogi juga termaktub secara eksplisit dalam
Statuta Roma. Bahkan, dalam hal keragu-raguan atau perubahan
peraturan, maka harus diterapkan aturan yang meringankan orang
yang sedang disidik, ditutut, atau diadili berdasarkan Statuta Roma.
3) Asas Ne bis in idem;
Asas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat
dituntut lebih dari satu kali didepan pengadilan dengan perkara
yang sama. Akan tetapi, dalam Statuta Roma, asas ne bis in idem
ini tidak berlaku mutlak. Artinya, asas ini dapat disimpangi jika
pengadilan nasional yang mengadili pelaku kejahatan tidak
berjalan adil (fair) atau bermaksud untuk membebaskan pelaku
dari segala tuntutan.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 30
4) Prinsip pertanggungjawaban pribadi;
5) Percobaan, penyertaan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan
perbuatan yang merupakan yurisdiksi mahkamah;
6) Tidak mengenal relevansi jabatan resmi dan tidak berlaku
tanggung jawab komando dan atasan lainnya;
7) Tidak dimasukannya yurisdiksi anak dibawah 18 tahun (Eddy O.S
Hiariej, 2009: 71-72).
2. Hukum Humaniter Internasional
a. Pengertian hukum humaniter internasional
Menurut Jean Pictet
International humanitarian law in the wide sanse is constitutionall
legal provision, whether written and customary, ensuring respect for
individual and his well being (Haryomataram, 1994: 15).
Terjemahan bebasnya:
Hukum Humaniter dalam arti luas adalah konstitusi ketentuan
hukum, baik tertulis maupun kebiasaan, untuk memastikan
penghargaan dan kesejahteraan terhadap seseorang.
Menurut Geza Herzegh
Part of the rule of public international law which serve as the
protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside
the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly
distinguish from these its purpose and spirit being different (Arlina
Permanasari dkk, 1999: 2).
Terjemahan bebasnya:
Bagian dari peraturan hukum internasional publik yang mengatur
tentang perlindungan seseorang waktu terjadi konflik bersenjata, yang
letaknya terdapat disamping dari norma peperangan dan mereka saling
terkait erat, tapi dapat dibedakan dari tujuan dan semangatnya.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 31
Menurut Mochtar Kusumaatmadja
Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan
pelindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang
mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara
melakukan perang itu sendiri (Mochtar Kusumaatmadja, 1980:5).
Menurut Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan
Perundangan-undangan
Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan
internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum
perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan
terhadap harkat dan martabat seseorang (Arlina Permanasari dkk, 1999:
10).
b. Asas-asas hukum humaniter internasional
1) Asas kepentingan militer (Military Necessity)
Berdasarkan asas ini maka pihak yan bersengketa dibenarkan
menggunakan kekerasan untuk menundukan lawan demi
tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2) Asas perikemanusiaan (Humanity)
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan
memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk
menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3) Asas kesatria (Chivalry)
Asas ini mengadung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus
diutamakan.Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai
macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
Selain ketiga prinsip diatas masih ada prinsip yang dianggap paling
penting dalam hukum humaniter internasional, yaitu Prinsip
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 32
Pembedaan (Distinction principle) berdasarkan prinsip ini pada
waktu terjadinya perang/konflik bersenjata harus dilakukan
pembedaan antara penduduk sipil (civilian) di satu pihak dengan
combatan serta antara obyek sipil di satu pihak dengan obyek
militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan
obyek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan
sasaran (Arlina Permanasari dkk, 1999: 11).
c. Tujuan hukum hummaniter internasional
1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun
penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary
suffering);
2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi
mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke
tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak
diperlukan sebagai tawanan perang;
3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal
batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusian
(Arlina Permanasari dkk, 1999: 12).
d. Sumber-sumber hukum humaniter internasional
1) Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum hukum
humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang
(Arlina Permanasari dkk, 1999: 21-31).
2) Konvensi Jenewa 1949
Hukum jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban
perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian
tersebut adalah keempat (4) konvensi Jenewa 1949, yang
masing-masing adalah:
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 33
a) Konvensi Jenewa pertama (1864) mengenai perbaikan
keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit
di darat;
b) Konvensi Jenewa kedua (1906) mengenai perbaikan
keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit,
dan karam di laut;
c) Konvensi Jenewa ketiga (1929) mengenai perlakuan
tawanan perang;
d) Konvensi Jenewa keempat (1949) mengenai perlindungan
terhadap orang-orang sipil (Arlina Permanasari dkk, 1999:
32).
Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977
ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977 yakni disebut
dengan:
a) Protokol tambahan I tahun 1977 yang mengatur tentang
perlindungan korban pada saat terjadi konflik bersenjata
internasional;
b) Protokol tambahan II tahun 1977 yang mengatur tentang
perlindungan korban pada saat terjadi konflik bersenjata non
intenasional (Arlina Permanasari dkk, 1999: 132-139).
e. Jenis-jenis konflik bersenjata.
Konflik bersenjata menurut Pietro Vierri adalah ungkapan yang
mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu: dua
negara atau lebih, negara dengan suatu entitas bukan negara, negara
dengan kelompok pemberontak, dan dua kelompok etnis dalam satu
negara (Vierri, Pietro, 1992: 34-35). Konflik bersenjata dalam
Konvensi Jenewa dibagi menjadi 2 yaitu :
1) Konflik Bersenjata Non Internasional.
Konflik besenjata non internasional diatur dalam Pasal 3 ketentuan
bersama Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 ketetuan bersama
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 34
Konvensi Jenewa 1949 memberikan pengertian luas terhadap
konflik bersenjata non internasional untuk membedakan konflik
bersenjata non internasional dalam pengertian Pasal 3 ini dengan
situasi ketegangan dan gangguan dalam negeri, kerusuhan atau
tindakan aksi bandit, maka kriteria atau batas tertentu, yaitu:
a) Konflik bersenjata harus mencapai tingkat minimum intensitas,
yaitu ketika pemerintah berkewajiaban untuk menggunakan
kekuatan militer terhadap kelompok pemberontak atau
kelompok non pemerintahan.
b) Kelompok pemberontak atau kelompok non pemerintah
merupakan pihak yang terlibat dalam konflik, adanya
pengorganisasian angkatan bersenjata secara berlanjut, adanya
struktur komando tertentu dan memiliki kapasitas untuk
mempertahankan operasi militer
(www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-
confict.pdf, How is the Term “Armed Conflict” difined in
International Humanitarian Law?, diakses pada tanggal 04
Januari 2017).
2) Konflik Bersenjata Internasional.
Konflik bersenjata internasional diatur pada Pasal 2 ketentuan
bersama Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi:
Pasal 2
“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang
akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini
akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang
diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang
mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta
Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah
satu antara mereka. Konvensi ini juga akan berlaku untuk
semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari
wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan
tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Meskipun
salah satu dari Negara-negara dalam sengketa mungkin
bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang jadi
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 35
peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya
didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya
terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara
bukan peserta, apabila Negara yang tersebut kemudian ini
menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi
ini.”
Pasal 2 ketentuan bersama Konvensi Jenewa 1949 di atas
menunjukan bahwa Konvensi Jenewa berlaku dalam keadaan:
a) Perang atau konflik bersenjata yang melibatkan antara 2 (dua)
atau lebih dari Pihak Peserta Agung.
b) Perang atau konflik bersenjata yang diumumkan.
c) Perang atau konflik bersenjata walaupun keadaan perang atau
konflik bersenjata tersebut tidak diakui.
d) Pendudukan (okupasi) sebagaian atau seluruh dari wilayah
pihak Peserta Agung, meskipun pendudukan tersebut tidak
menemui perlawanan.
Selain memenuhi unsur-unsur yang terdaapat pada Pasal 2
ketentuan bersama Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata
internasional juga dapat terjadi akibat dari pergeseran status hukum
pihak-pihak yang terlibat dari konflik bersenjata non internasional.
Keadaan tersebut dinamakan internationalized internal armed
conflict (internasionalisasi konflik bersenjata non internasional).
Internasionalisasi konflik bersenjata non internasional menurut
Pietro Vierri adalah suatu konflik non internasional dapat dianggap
menjadi konflik bersenjata internasional apabila telah terpenuhi
syarat-syarat berikut:
a) Jika suatu negara yang berperang melawan pihak pemberontak
di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak
tersebut sebagai pihak yang bersengketa (belligerent);
b) Jika terdapat satu atau lebih negara asing memberikan bantuan
kepada salah satu pihak dalam konflik non internasional
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 36
dengan mengirimkan angkatan bersenjata resmi mereka dalam
konflik yang bersangkutan;
c) Jika terdapat 2 negara asing atau lebih dengan angkatan
bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu
negara yang terlibat konflik non internasional, dimana masing-
masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang
saling berlawanan (Vierri, Pietro, 1992: 35).
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 37
B. Kerangka Berpikir
Tertangkapnya Ratko
Mladić di Desa Kravica
pada Tahun 2011
Faktor penyebab konflik
bersenjata antara Bosnia
dengan Serbia
Terjadi Pelanggaran HAM
berat pada saat terjadi
konflik bersenjata di
Bosnia-Herzegovina yang
dilakukan tentara Serbia
(Termasuk Ratko Mladić)
pada tahun 1992-1995
Dibentuknya Mahkamah
Pidana Permanen/
International Court
Criminal (ICC) pada tahun
1 Juli 2002 yang
berdasarkan Statuta Roma
1998 yang bertujuan
mengadili pelaku
kejahatan HAM berat
Pembentukan ICTY(Ad
Hoc) melalui Resolusi DK
PBB Nomor 827 Tahun
1993 yang bertugas
mengadili para pelaku
pelanggaran HAM berat di
wilayah Yugoslavia
DK PBB mengeluarkan
Resolusi No.1966 tahun
2010 tentang pembubaran
ICTY dan ICTR
Mekanisme penegakan
hukum terhadap Ratko
Mladić yang telah
melakukan pelanggaran
HAM melalui MICT
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 38
Keterangan:
Salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu mengenai
penegakan hukum (law enforcement). Suatu perangkat hukum baru dapat
dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat
ditegakan. Maka didalam perangkat hukum itu perlu ada suatu mekanisme yang
mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma itu ditegakan. Mekanisme
penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Yugoslavia
khusunya negara bagian Bosnia-Herzegovina masih menimbulkan permasalahan
karena penjahat yang melakukan pelanggaran HAM tersebut tidak tertangkap dan
diadili pada saat itu juga.
Hal itu dimulai ketika PBB melalui Resolusi DK Nomor 827 tahun 1993
membentuk pengadilan ad hoc International Criminal Tribunal for Former
Yugoslavia (ICTY) sebagai respon terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi
di wilayah Yugoslavia. ICTY dibentuk untuk meginvestigasi, menuntut, dan
mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran
HAM berat selama konflik bersenjata di Yugoslavia sejak tahun 1991.
Permasalahannya adalah tidak semua pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat
yang terjadi di Yugoslavia langsung tertangkap pada waktu itu juga, sebagai
contoh tertangkapnya Jendral Ratko Mladić di Desa Kravica pada tanggal 26 Mei
2011. Disisi lain pada tahun 2010 DK PBB telah mengeluarkan Resolusi No 1966
tahun 2010 tentang pembubaran pengadilan ad hoc ICTY dan ICTR.
Sehingga dalam hal ini menimbukan masalah yurisdiksi mahkamah mana
yang berhak mengadili Ratko Mladić yang melakukan pelanggaran HAM pada
tahun 1992-1995, tetapi tertangkap pada 2011.