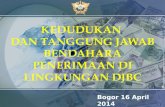TPP
-
Upload
ariska-duti -
Category
Documents
-
view
646 -
download
2
Transcript of TPP

Laporan Praktikum Hari/ Tanggal : Selasa / 20 April 2010
Teknik Penyimpanan dan Golongan :
Penggudangan Dosen : 1. Ir. M. Zein N, M.App.Sc
2. Ir . Sugiarto, M.Si
3. Dr. Ir. Indah Yualisih, Msc
Asisten :1. Hanna Rina K (F34070065)
2. Nova A (F34070011)
PENYAKIT PASCA PANEN KOMODITI PERTANIAN
Disusun oleh
2011
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
Fajar Munichputranto (F34090011)
Yonathan (F34090041)
Ariska Duti Lina (F34090102)
Citra Regina Barus (F34090119)
Imastia (F34090120)
Sulayman (F34090122)

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penanganan Pasca panen merupakan tindakan atau perlakuan yang pada
hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen.
Penanganan pasca panen dibagi menjadi dua bagian, yakni postharvest yang
disebut pengolahan primer dan dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer
(primary processing) merupakan istilah yang digunakan untuk semua
perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi atau untuk
persiapan pengolahan berikutnya, pada perlakuan ini tidak mengubah bentuk
penampilan termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Sedangkan
pengolahan sekunder (secondary processing) merupakan tindakan yang
mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain agar bahan pertanian
dapat tahan lebih lama (pengawetan), selain itu mencegah perubahan yang
tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain juga termasuk pengolahan
pangan dan pengolahan industri.
Dilakukannya penanganan pasca panen untuk mencegah terjadinya loose
pada bahan pertanian, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, seperti
penurunan komoditas sehingga tidak layak pasar ataupun tidak layak. Selain itu
juga dilakukan penanganan penyakiy pada saat penyimpanan berlangsung yang
muncul diakibatkan kerusakan pada bahan komoditi pertanian sehingga terjadi
kerusakan, atau juga disebabkan karena kondisi ruang penyimpanan yang dap
berakibat rusaknya bahan. Oleh sebab itu penanganan penyakit pasca panen
merupakan sesuatu hal yang penting di dalam penanganan komoditi pertanian.
Selain itu penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dalam
kondisi baik dan sesuai/tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan
baku pengolahan.
B. Tujuan
Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa dapat mengidentifikasi tanda-
tanda serangan penyakit pasca panen, kerusakan komoditi pertaniaan akibat
penyakit pasca panen, mengidentifikasi atau menentukan jenis penyakit pasca

panen, menentukan penyebab penyakit pasca panen, serta dapat menentukan
cara pencegahan terjadinya serangan penyakit pasca panen.

II. METODOLOGI
A. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas obyek dan gelas
penutupnya, pipet, dan mikroskop. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan
adalah buah-buahan komoditi pertanian yang sudah rusak atau terkena penyakit,
seperti apel dan pisang rusak.
B. Metode
Jenis penyakit pada bebuahan diidentifikasi dan diamati, seperti warna bagian terserang, perubahan bentuk dan permukaan, ada atau tidaknya luka, memar atau mikroorganisme lain yang tumbuh
Sampel cairan, lendir, atau miselium pada bebuahan yang terserang penyakit diambil sampelnya untuk diamati secara visual ataupun diamati menggunakan mikroskop
Sampel diamati dengan mikroskop lalu digambar penampakannya atau difoto
Penyebab penyakit pasca panen dan penyakit pasca panen yang terajangkit pada bebuahan tersebut diidentifikasi
Bebuahan (Melon, Alpukat, Pisang, Salak, Jeruk, Timun, Cabe Merah) diamati secara visual lalu digambar

III. PEMBAHASAN
A. Hasil Pengamatan
Hasil pengamatan terlampir.
B. Pembahasan
Setelah pemanenan pada produk pertanian metabolisme bahan pada bahan
pertanian sudah dipetik atau sebelum dipetik sudah berbeda. Produk pertanian
yang sudah dipanen akan mengalami loose bobot, hilangnya nutrisi, menurunnya
kualitas bahan ataupun kerusakan yang lain akibat perlakuan saat pemanenan.
Beberapa proses pemanenan yang dapat menimbulkan loose bobot, hilangnya
nutrisi, menurunnya kualitas bahan ataupun kerusakan berarti, yakni pengemasan
dan transportasi dapat menimbulkan kerusakan mekanis lebih lanjut, orientasi
gravitasi dari produk pascapanen umumnya sangat berbeda dengan kondisi
alamiahnya, hambatan ketersediaan CO2 dan O2, hambatan regim suhu dan
sebagainya. Dapat dikatakan secara keseluruhan, bahan hidup hasil pertanian
pascapanen dapat dikatakan mengalami berbagai perlakuan yang menyakitkan
selama hidup pascapanennya (Firdaus,2008).
Jika stress terlalu berlebihan yang melebihi toleransi fisik dan fisiologis
pada bahan pertanian , maka terjadi kematian pada bahan pertanian tersebut
Aktivitas yang menandakan adanya metabolisme pada bahan pertanian pasca
panen adalah respirasi., yang dapat menghasilkan panas sehingga proses seperti
kehilangan air, terjadinya layu pada bahan, dan pertumbuhan mikroorganisme
akan semakin meningkat. Anonim, (2008), menyatakan bahwa deengan kondisi
yang seperti ini (keadaan fisik yang bururk) mikroorganisme dapat tumbuh dan
dapat menginfeksi sayuran atau buah melalui cacat pada buah
Meminimalkan kerusakan pada komoditi pertanian pasca panen harus
mengerti cara penanganan komoditi tersebut saat penyimpanan ataupun saat
distribusi berlangsung sehingga dapat meminimalkan terjadinya kerusakan
tersebut. Menurut Kader, (1992), beberapa contoh penanganan komoditi pasca
paenn seperti pemahaman tentang sifat alami produk dan pengaruh praktek-
praktek penanganannya, hal ini sangat penting untuk agar kualitas bahan dapat

terjaga dengan baik. Faktor lain yang harus diperhatikan seperti, faktor fisiologis,
fisik, patologis dan ekonomis. Apabila komoditi pertanian pasca panen sudah
mengalami kerusakan seperti cacar fisik, diperlukannya pengendalian penyakit
yang dapat dilakukan seperti, indentifikasi terhadap mikroorganisme penyebab
penyakit, pemilihan cara pengendalian yang tepat yang sangat dipengaruhi oleh
apakah penyebab penyakit tersebut melakukan infeksi sebelum atau sesudah
panen, penanganan yang baik untuk meminimumkan pelukaan atau kerusakan
lainnya, menjaga lingkungan untuk tidak memacu perkembangan penyakit
tersebut, memanen produk pada kematangan yang tepat (Pantastico,1991).
Pembusukan atau munculnya mikrooganisme pada buah merupakan akibat
kerusakan fisik pada buah pada saat menyimpanan yang di ditumbuhi
mikroorganisme, selain itu proses metabolisme juga dapat mempengaruhi
terjadinya kebusukan karena respirasi yang berlebihan. Menurut Syarief dan Halid
(1993), pada dasarnya mikroba perusak bahan pangan adalah bakteri, kapang dan
khamir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ketiga jenis mikroba
tersebut berbeda satu sama lain, di antaranya adalah aktivitas air (Aw) bahan
pangan, suhu penyimpanan dan suhu pengolahan, ketersediaan oksigen, pH bahan
pangan dan kandungan zat gizi bahan pangan. Faktor lingkungan fisik tersebut
apabila berada pada kondisi optimal makan pertumbuhan mikroba akan
berlangsung baik. Beberapa golongan buah busuk yakni, buah lunak dan basah
atau busuk bonyok, busuk keras dan kering atau busuk mummi, dan busuk biasa
atau bercak nekrosa. Cendawan, jamur, atau kapang menyerang tanaman
khususnya pohon buah-buahan melalui tiga cara yaitu melalui celah alami yang
terdapat pada tanaman seperti mulut daun (stomata), lentisel dan kelenjar nektar,
melalui luka bekas gigitan serangga atau lainnya, dan melaui kontak langsung
dengan tanaman inangnya (Kalie, 1992).
Beberapa gejala terjadinya pembusukan pada buah adalah tampak bintik
atau bercak kecil pada buah atau sayur atau. Bintik ini kemudian membesar, clan
juga terjadi perubahan warna clan hijau menjadi kuning kehijauan lalu kuning,
cokelat atau hitam. Setelah itu timbul gejala nekrosa, yaitu matinya jaringan
penyusun organ, kemudian buah atau sayur menjadi busuk

Buah dan sayuran yang diamati hampir semuanya mempunyai ciri-ciri
kebusukan yang sama, seperti terdapat bercak pada kulit buah, teksturnya berubah
menjadi lembek dan berlendir, bercak kehitaman dan cekung di beberapa bagian
dan keriput di beberapa bagian lain. Kebusukan juga menyerang daging buah
bagian dalam, beberapa jenis buah di daging buahnya terdapat larva atau ulat.
Semua komoditi pada praktikum ini jika ditinjau dari permukaan luarnya terdapat
banyak memar, baik pada kulit maupun daging buahnya. Memar ini disebabkan
oleh kerusakan fisik dan mekanik yang mengakibatkan kerusakan penampakan
yang tidak bagus dan juga dapat memicu reaksi ezimatis tertentu yang
menimbulkan kerusakan kimiawi. Reaksi ini disebut fenolism dimana enzim
fenoloksidase menyerang jaringan pada buah sehingga menyebabkan warna gelap
dan kerusakan kimiawi lainnya yang diakibatkan tumbuhnya cendawan pada buah
tersebut, pengendalian yanga dapat dilakukan seperti Sanitasi kebun, pemberian
fungisida dan bakterisida yang sesuai, pemusnahan buah atau sayur yang
terserang, clan pemangkasan untuk mengurangi kerimbunan/kelembapan.
Pada praktikum ini bebuahan yang digunakan adalah alpukat, salak, jeruk,
cabe, mentimun, dan melon. Bebuahan tersebut sudah dalam keadaan busuk dan
berlendir juga tumbuh berbagai macam mikrooraginsme lain yang menyebabkan
pembusukan.
Bahan pangan hasil pertanian akan mengalami kerusakan fisik setelah
dipanen. Sebagai akibat dari pengaruh luar dan pengaruh dari sifat bahan itu
sendiri. Yang dimaksud dengan pengaruh luar adalah karena faktor-faktor
mekanis, seperti tekanan fisik (droppingatau jatuhan, shunting atau gesekan) dan
ada juga vibrasi atau getaran, benturan antara bahan dan alat atau wadah selama
perjalanan dan distribusi. Kerusakan fisik yang lain disebabkan oleh serangan
serangga atau hewan lain yang dikategorikan hama dalam penyimpanan (Syarief
dan Halid, 1993). Umur dari alpukat sendiri adalah sekitar 7 hari dari waktu
pemetikan untuk siap makan. Buah ini memiliki kulit lembut tak rata berwarna
hijau tua hingga ungu kecoklatan, tergantung pada varietasnya. Daging buah
alpukat berwarna hijau muda dekat kulit dan kuning muda dekat biji, dengan
tekstur lembut. Hasil pengamatan memperlihatkan warna alpukat yang sudah
tidak lagi berwarna hijau atau kuning namun berwarna coklat kehitaman. Kulit

alpukat terlihat mengeras dan berwarna coklat tua. Biji alpukat mengalami
kerusakan pada bagian luarnya sehingga terlihat seperti mengelupas.
Pittinger, (2002), menyebutkan bahwa hal ini termasuk gejala-gejala dari
penyakit Anthracnose, yaitu timbulnya warna kecoklatan pada buah. Bagian biji
juga terserang penyakit. Hal ini dapat terlihat dari adanya lendir berlebihan pada
bagian dalam buah didekat biji. Selain itu, ketika daging buah dibuka, terdapat
ulat di daging buah. Buah merupakan buah yang telah cacat diserang ulat atau
buah yang telah mengandung ulat. Buah seperti itu tidak dapat dinikmati karena
telah rusak. Ulat, belatung, atau larva itu berasal dari telur sejenis lalat yang
disebut lalat buah. Jenis lalat ini tergolong bangsa Diptera (Kalie, 1992).
Penyakit alpukat yang disebabkan oleh mikroba adalah sebagai berikut,
jamur Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) sacc yang mempunyai miselium
berwarna cokleat hijau sampai hitam kelabu dan sporanya berwarna jingga.
Dengan gejala penyakit yang menyerang semua bagian tanaman kecuali akar.
Bagian yang terinfeksi berwarna cokelat karat, kemudian daun, bunga,
buah/cabang tanaman yang terserang akan gugur. Pengendalian yang dilakukan
adalah pemangkasan ranting dan cabang yang mati dapat juga disemprot
menggunakan fungisida yang berbahan aktif maneb seperti pada Velimex 80 WP.
Fungisida ini diberikan 2 minggu sebelum pemetikan dengan dosis 2-2,5
gram/liter. Sedangkan untuk pembusukan pada buah alpukan itu sendiri
diakibatkan karena jamur Botryodiplodia theobromae pat. Jamur ini menyerang
apabila ada luka pada permukaan buah. Dengan bagian yang pertama kali
diserang adalah ujung tangkai buah dengan tanda adanya bercak cokelat yang
tidak teratur, yang kemudian menjalar ke bagian buah. Pada kulit buah akan
timbul tonjolan-tonjolan kecil. Pengendaliannya dilakukan pengolesan bubur
Bordeaux / semprotkan fungisida Velimex 80 WP yang berbahan aktif Zineb,
dengan dosis 2-2,5 gram/liter.
Menurut Indriani et.al., (1997), alpukat baru dapat dikonsumsi bila sudah
masak. Untuk mencapai tingkat kemasan ini diperlukan waktu sekitar 7 hari
setelah pemetikan (bila buah dipetik pada saat sudah cukup ketuaannya). Bila
tenggang waktu tersebut dipercepat, maka buah harus diperam terlebih dulu. Hal
berbeda jika dilakukan perlakuan ekspor maka, tidak perlu dilakukan pemeraman

karena tenggang waktu ini disesuaikan dengan lamanya perjalanan untuk sampai
di tempat tujuan.
Tanaman salak merupakan salah satu tanaman buah yang disukai dan
mempunyai prospek bisnis yang baik di indonesia. Daerah asal diduga dari
Thailand, Malaysia dan Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa tanaman
salak (Salacca edulis) berasal dari Pulau Jawa. Di dalam budidaya buah salak,
salah satu hal yang menjadi kendalanya adalah terkait hama dan penyakit pada
bagian-bagian pohon salak.
Menurut Agromaret (2009), beberapa jenis penyakit yang sering dijumpai
pada tanaman buah salak:
1. Penyakit yang sering menyerang salak adalah sebangsa cendawan putih.
Gejala: busuknya buah. Buah yang terserang penyakit ini kualitasnya jadi
menurun, karena warna kulit salak jadi tidak menarik.
Pengendaliannya: mengurangi kelembaban tanah, yaitu dengan
mengurangi pohon-pohon pelindung.
2. Noda hitam
Penyebab : cendawan Pestalotia sp.
Gejala: adanya bercak-bercak hitam pada daun salak.
3. Busuk merah (pink)
Penyebab: cendawan Corticium salmonicolor.
Gejala: adanya pembusukan pada buah dan batang.
Pengendalian: tanaman yang sakit dan daun yang terserang harus dipotong
dan dibakar di tempat tertentu.
Dari pengamatan fisiologis salak diperoleh bahwa salak mengalami
pembusukan di bagian ujung yang agak meruncing. Adanya pembusukan ini
diduga akibat perlakuan mekanis seperti penanggulangan pascapanennya yang
tidak mengutamakan keutuhan buah salak. Selain itu, pembusukan ini juga dapat
dipacu oleh adanya mikroorganisme yang menyerang langsung pada buah salak.
Dari pengamatan secara mikroskopis diperoleh bahwa terlihat objek-objek kecil
yang diduga mikroorganisme tertentu yang menyebabkan pembusukan pada buah
salak. Analisa terhadap penyakit menunjukkan memperlihatkan adanya memar
pada bagian atasnya, akan tetapi tidak ditemukan adanya pertumbuhan miselium

kapang. Aroma yang tercium pada pengamatan buah salak menunjukkan bau
khas salak yang tidak terlalu pekat. Selain itu, warna buahnya memperlihatkan
campuran/kombinasi antara coklat kehitam-hitaman
Menurut Widodo (2009), hama pada tanaman salak yang biasa dikenal
yakni sebagai berikut :
a. Kutu wol/putih (Ceratadhis sp) hama ini biasanya bersembunyi di sela-sela
buah
b. Kumbang penggerek tunas (Omotemnus sp) yang diserang adalah pucuk tunas
yang masih muda
c. Kumbang penggerek batang yaitu menyerang ujung daun yang masih muda
(paling muda), kemudian akan masuk ke dalam batang. Hal ini tidak
menyebabkan kematian tanaman, tetapi akan tumbuh anakan yang banyak di
dalam batang tersebut. Untuk mengendalikan penggerek: dimatikan atau
dengan cara meneteskan larutan insektisida (Diazenon) dengan dosis 2 cc per
liter pada ujung daun yang terserang atau dengan cara menyemprot. Dalam hal
ini diusahakan insektisida dapat masuk ke dalam bekas lubang yang digerek.
Cara lainnya dengen memasukkan kawat yang ujungnya lancip ke dalam
lubang yang dibuat kumbang hingga mengenai hama.
Komoditi selanjutnya yang diamati adalah jeruk yang sudah busuk. Jeruk
atau limau adalah semua tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari suku
Rutaceae (suku jeruk-jerukan). Anggotanya berbentuk pohon dengan buah yang
berdaging dengan rasa masam yang segar, meskipun banyak di antara anggotanya
yang memiliki rasa manis. Rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat yang
memang menjadi terkandung pada semua anggotanya (Anonim, 2011).
Setiap jenis buah dan sayur hanya diserang oleh kelompok jamur parasit
dan kemungkinan oleh bakteri, yang unik dan relatif kecil. Kelompok ini
memerlukan persyaratan nutrisi dan kemampuan enzimatis untuk
perkembangannya di dalam jaringan inangnya. Misalnya, jamur Penicillium
digitatum hanya menyebabkan penyakit pascapanen pada jeruk. Selain itu, dalam
atmosfer ruang simpan juga terkadung gas etilen, khususnya yang dihasilkan
secara alami dari produk pasca panen yang disimpan, serta karena adanya
perlakuan dengan etilen buatan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk

penyeragaman tingakat kemasakkan buah dan mengubah warna hijau buah jeruk
(Jufrys, 2010). Pada pengamatan yang dilakukan, jeruk terlihat berjamur, keriput,
dan bonyok. Kulit jeruk berwarna kuning kecoklatan dan mengeluarkan aroma
khas jeruk yang tidak pekat. Menurut literatur, jamur yang teramati kemungkinan
adalah Penicillium digitatum.
Beralih kepada komoditas pertanian yang lainnya yaitu cabai. Bagian yang
sering dimanfaatkan dari sayuran ini adalah buahnya. Biasanya buah cabai diolah
mentah sebagai sambal. Cabai banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin
C, dan pigmen terutama pada bagian kulit dan bijinya.
Cabai yang diamati pada praktikum ini ukurannya besar dan berwarna
merah. Jenis sayuran ini pun rentan terhadap penyakit pasca panen apabila
penyimpanannya kurang benar. Penyakitnya bertahap, diawali dengan terjadinya
kerusakan terlebih dahulu. Dikatakan penyakit karena mampu mengambil
komponen kimia dari bahan komoditi kemudian merombak senyawa kimia secara
enzimatis. Kerusakan yang terjadi antara lain kerusakan mekanis, biologis, dan
mikrobiologis. Kerusakan mekanis yang terjadi dibuktikan adanya goresan akibat
penanganan selama panen dan pasca panen yang salah/kasar seperti penggunaan
alat yang kurang sesuai. Kerusakan biologis dan mikrobiologis terjadi karena
adanya kontaminasi dari kapang. Dengan timbulnya lendir dan serabut putih atau
yang sering disebut miselia yang dihasilkan oleh kapang, maka cabai pun
dikatakan terkena penyakit. Kerusakan biologis dan mikrobiologis itupun dapat
terjadi karena terpacu karena adanya kerusakan mekanis. Adanya goresan pada
cabai, membuat kulitnya menjadi terbuka sehingga melakukan respirasi yang
berlebih.
Menurut (Junaidi, 2009), penyakit yang sering menyerang tanaman cabe
diantaranya adalah rebah semai , layu fusarium, layu bakteri , antraknose / patek ,
busuk Phytophthora, bercak daun Cercospora, penyakit virus. Berdasarkan hasil
pengamatan pada cabai yang kondisinya telah busuk dan cirri-cirinya yang telah
diberikan, dapat dikatakan bahwa cabai ini terserang penyakit antraknose / patek
dan busuk Phytopthora. Penyakit busuk Phytopthora gejalanya adalah bagian
tanaman yang terserang terdapat bercak coklat kehitaman dan lama kelamaan

membusuk. Penyakit ini dapat menyerang tanaman cabe pada bagian daun, batang
maupun buah.
Sedangkan penyakit anthracnose pada cabai memiliki gejala awaln adalah
kulit buah akan tampak mengkilap, selanjutnya akan timbul bercak hitam yang
kemudian meluas dan akhirnya membusuk. Timbulnya bercak hitam yang dilihat
dari hasil pengamatan juga terjadi karena adanya aktifitas dari kapang. Kapang
yang sudah mengontaminasi menghasilkan miselia (ditandai dengan serabut putih)
dan lender. Kapang tumbuh karena dipacu oleh kondisi cabai itu sendiri yang
memiliki Aw yang rendah. Maka kerusakakn atau kerugian yang didaptkan adalah
penampilan yang kurang baik karena warnanya yang coklat kehitaman, berbau
busuk, dan meningkatkan kadar air cabai.
Secara mekanis untuk mencegah penyakit pada cabai ini dapat dilakukan
dengan pengemasan dan penyimpanan yang baik. Bisa dilakukan dengan
pembungkusan cabai engan plastic LDPE kemudian menyimpannya di pendingin
dengan suhu sekitar 3-6o C. bisa juga dengan jalan melapisi sayuran dengan
lapisan lilin/waxing sehingga mampu melindungi permukaan, menutup retak dan
penyok pada kulit, menekan kehilangan air, serta menjaga respirasiny dan secara
kimiawi dapat dilakukan dengan jalan memberikannya pengawet (preservative)
seperti SO2, Na nitrit, dan garam atau gula. Dapat juga dengan penggunaan
iradiasi sinar gamma walupun dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan
mutasi. Pemberian desinfektan diberikan dengan penggunaan chlorine dan SOPP.
Penangan pasca panen pada buah melon dilakukan dengan peyimpanan bebuahan
yang sesuai dengan kondisi fisik buah tersebut, beberapa penyakit yang terdapat
pada melon seperti kapang dan memar yang diakibatkan karena adanya
mikroorganisme dan lukanya buah. Hal tersebut dapat diatasi dengan
pengendalian sebelum pasca panen seperti sanitasi
Mentimun, timun, atau ketimun (Cucumis sativus L; suku labu-labuan atau
Curcubitaceae) merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat

dimakan. Buahnya biasanya dipanen ketika sebelum masak benar untuk dijadikan
sayuran atau penyegar, tergantung jenisnya. Mentimun dapat ditemukan di
berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air yang cukup
banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan. Potongan buah mentimun
juga digunakan untuk membantu melembabkan wajah (Anonim, 2011).
Buah mentimun berwarna hijau ketika muda dengan larik-larik putih
kekuningan. Semakin buah masak, warna luar buah berubah menjadi hijau pucat
sampai putih. Bentuk buah memanjang seperti torpedo. Daging buahnya
perkembangan dari bagian mesokarp, berwarna kuning pucat sampai jingga
terang. Buah dipanen ketika masih setengah masak dan biji belum masak
fisiologi. Buah yang masak biasanya mengering dan biji dipanen, warnanya hitam
(Anonim, 2011).
Penyakit bercak pada timun disebabkan oleh jamur Alternaria
cucumerina. Biasanya penyakit ini hanya menyerang satu jenis tanaman. Tanaman
dapat terserang pada berbagai fase pertumbuhan. Serangan pada bibit tanaman
dapat menyebabkan mati atau kerdil. Sedangkan pada tanaman yang lebih tua
akan layu pada tengah hari pada beberapa waktu, kemudian layu untuk seterusnya
dan akhirnya mati. Jaringan angkut tanaman menjadi kuning atau coklat. Penyakit
ini dapat bertahan di tanah untuk jangka waktu lama. Penyakit ini dapat pindah
dari satu lahan ke lahan lain melalui mesin-mesin pertanian, seresah daun yang
telah terserang, dan air irigasi. Suhu tanah yang tinggi sangat sesuai untuk
perkembangan penyakit ini. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan
menggunakan varietas yang tahan, menghindari penanaman di lahan yang telah
diketahui mengandung penyakit ini, serta mencuci peralatan saat berpindah dari
l;ahan satu ke lahan lainnya. Lahan yang tergenangi untuk padi dapat mengurangi
keberadaan penyakit di tanah (Anonim, 2008).
Layu fusarium merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman
famili timun-timunan. Penyebabnya adalah Fusarium oxysporum f.sp.
cucumerinum pada mentimun. Penyakit ini ditemukan di seluruh dunia, namun
beberapa jenis terdapat hanya pada lokasi tertentu saja. Penyakit ini hanya
menyerang satu jenis tanaman saja (Anonim, 2008).

Downy Mildew termasuk penyakit yang paling merusak pada tanaman
timun-timunan yang disebabkan oleh jamur Pseudoperonospora cubensis.
Penyakit ini banyak terdapat pada mentimun dan melon, tetapi sekali menyerang
dapat merusak seluruh tanaman timun-timunan. Gejala yang timbul biasanya
terjadi pada daun yang berupa bercak kekuningan yang berubah dari kecoklatan
menjadi coklat tua. Saat kelembaban tinggi, timbulnya spora menjadi bukti pada
bagian bawah daun yang luka dimana spora tadi masuk ke dalam daun melalui
stomata dan menghasilkan spora yang berwarna. Penyakit ini merupakan parasit
yang dapat berada pada tanaman yang dibudidayakan, tanaman lokal/induk,
ataupun jenis timun-timunan yang liar di daerah tropis dan subtropis (Anonim,
2008.).
Pada praktikum kali ini, pada timun yang diamati terdapat tanda-tanda
fisiologi penyakit pasca panen pada mentimun, antara lain yaitu busuk, buah
berwarna kuning dan berkerut, bopeng, dan berhifa. Ketika diamati di bawah
mikroskop terdapat warna merah, hijau, dan hitam. Penyakit yang dialami
mentimunyang diamati oleh praktikan antara lain adalah memar, lembek (busuk),
dan berkapang yang ditandai dengan munculnya serabut. Aroma mentimun ketika
telah menderita penyakit pasca panen ini adalah kurang segar.
‘

KESIMPULAN
Produk pertanian yang sudah dipanen akan mengalami loose bobot,
hilangnya nutrisi, menurunnya kualitas bahan ataupun kerusakan yang lain akibat
perlakuan saat pemanenan. Beberapa proses pemanenan yang dapat menimbulkan
loose bobot, hilangnya nutrisi, menurunnya kualitas bahan ataupun kerusakan
berarti, yakni pengemasan dan transportasi dapat menimbulkan kerusakan
mekanis lebih lanjut, orientasi gravitasi dari produk pascapanen umumnya sangat
berbeda dengan kondisi alamiahnya, hambatan ketersediaan CO2 dan O2,
hambatan regim suhu dan sebagainya. Dapat dikatakan secara keseluruhan, bahan
hidup hasil pertanian pascapanen dapat dikatakan mengalami berbagai perlakuan
yang menyakitkan selama hidup pascapanennya
Kerusakan yang terjadi pada bebuahan terasebut diakibatkan karena
tumbuhnya kapang atau memar yang dpat mengakibatkan pembusukan dan
keluarnya lendir, sehingga membuat kerusakan pada bebuahan tersebut
Agar menjaga produk tersebut tidak segera mengalami kerusakan baik dari
segi fisik maka dilakukanlah suatu cara melalui metode-metode penanganan
pascapanen tertentu diwujudkan berupa pengendalian agar buah atau sayur dapat
dipertahankan mutunya seperti dengan cara sanitasi pada kebun dan
penyemprotan fungisida yang sesuai dengan kondisi. Dengan menganalisa
penyakit yang timbul maka dengan mudah dapat menentukan bentuk penanganan
yang terbaik bagi komoditas hasil pertanian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Agromaret. 2009. Penyakit pada Tanaman Buah Salak. www.agromaret.com.
[25 April 2011]
Anonim. 2008. Direktorat Jenderal Hortikultura. Departemen Pertanian. Jakarta.
[9 April 2011]
Anonim. 2008. Budidaya Hortikultura di Musim Hujan Kendala dan Kiat
Mengatasinya. www.bangfad.com [26 April 2011]
Anonim. 2011. Mentimun. www.wikipedia.com [26 April 2011]
Anonim. 2011. Jeruk. http://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk [26 April 2011]
Firdaus, M dan Wagiono, Y.K. 2008. Apakabar Daya Saing Buah Kita?.
firdausipb.files.wordpress.com/2008/04/apa-kabar-dayasaing-buah-
kita.pdf. [19 April 2011]
Indriani, Y. Hetty; Suminarsih, Emi. 1997. Alpukat. Jakarta: Penebar Swadaya.
Jufrys.2010. Faktor Yang Mempengaruhi Penyakit Pascapanen.
http://jufrys.wordpress.com/201 /03 /19/ faktor-yang-mempengaruhi-
penyakit-pascapanen/ [26 April 2011]
Junaidi, Wawan. 2009. Penyakit cabai [terhubung berkala]
Kader, A.A. 1992. Postharvest Technology of Horticultural Crops. The
Regents of the University of California. USA.
Kalie, Moehd. Baga (1997). Alpukat: Budidaya dan Pemanfaatannya.
Yogyakarta: Kanisius.
Pantastico, Er.B. 1991. Postharvest Physiology, Handling and Utilization of
Tropical and Subtropical Fruits and Vegetables. The AVI Publ. Co,Inc.
Westport, Connecticut.
Pittinger, D. 2002. UC Master Gardener’s Handbook. California: University of
California.
Syarief, Rizal dan Hariyadi Halid. 1993. Teknologi Penyimpanan Pangan.
Jakarta: Arcan

Widodo, Slamet. 2009. Pengendalian Hama, Penyakit, Gulma Tanaman Salak.
www.ristek.go.id [25 April 2011]
Bautista, Ofelia K. 1990. Postharvest Technology for Southeast Asian

Perishable Crops. Technology and Livelifood Resource Centre. Los
Banos. The Philippines.
Broto, W., 2003. Apel : Budi Daya, Pascapanen dan Tata Niaganya.
Agromedia Pustaka. Jakarta.
Winarno, F.G. 1981. Fisiology Lepas Panen. Sastra Hudaya Jakarta.