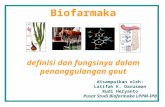Pengertian Kelompok Sosial
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pengertian Kelompok Sosial
A. Pengertian Kelompok Sosial
Kelompok sosial mengandung pengertian suatu kumpulan dari
individu-individu yang saling berinteraksi sehingga
menumbuhkan perasaan bersama. Berikut ini adalah
pengertian kelompok sosial dari beberapa ahli :
a) Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, istilah
kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang
memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling
berinteraksi.
b) Menurut George Homans, kelompok adalah kumpulan
individdu yang melakukan kegiatan, interaksi dan
memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan
yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik.
c) Menurut Soerjono Soekanto, kelompok adalah himpunan
atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama
karena saling berhubungan di antara mereka secara
timbal balik dan saling mempengaruhi. Suatu himpunan
manusia dikatakan kelompok sosial apabila memenuhi
persyaratan berikut ini :
Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa
dia bagian dari kelompok tersebut.
Memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan
hidup kelompok tergantung pada kesungguhan para
anggotanya dalam melaksanakan perannya.
Memiliki norma-norma yang mengatur hubungan
diantara para anggotanya.
Memiliki kepentingan bersama.
Adanya interaksi dan komunikasi diantara
anggotanya.
B. Klasifikasi Kelompok Sosial
1. Klasifikasi Berdasarkan Cara Terbentuknya
a. Kelompok semu , yaitu: kelompok yang terbentuk secara
spontan
Ciri-ciri kelompok semu :
Tidak direncanakan
Tidak terorganisir
Tidak ada interaksi secara terus menerus
Tidak ada kesadaran berkelompok
Kehadiranya tidak konstan
Kelompok semu dibagi menjadi tiga yakni crowd
(kerumunan), publik dan massa.
1) Crowd (kerumunan), dibagi menjadi :
a) Formal audiency / pendengar formal
Contoh: orang-orang mendengarkan khotbah,
Orang-orang nonton di bioskop
b) Inconvenient Causal Crowds adalah: Kerumunan
yang sifatnya terlalu sementara tetapi ingin
menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama,
contoh : orang antri tiket kereta api.
c) Panic Causal Crowds adalah kerumunan yang
terjadi karena suasana panik.
Contoh: Kerumunan orang-orang panic akan
menyelamatkan diri dari bahaya.
d) Spectator Causal Crowds adalah kerumunan orang
yang terbentuk karena ingin menyaksikan
peristiwa tertentu.
Contoh: Kerumunan penonton atau orang-orang
ingin melihat peristiwa tertentu.
e) Lawless Crowds adalah kerumunan yang tidak
tunduk pada pemerintah, contoh : aksi demo.
f) Immoral low less crowds adalah kerumunan orang-
orang tak bermoral, contoh : kerumunan orang
yang minum-minuman keras.
2) Massa
Massa merupakan kelompok semu yang memiliki
ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi
kemungkinan terbentuknya disengaja dan
direncanakan. Contoh : mendatangi gedung DPR
dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan.
3) Publik
Publik adalah sebagai kelompok semu mempunyai
ciri-ciri hampir sama dengan massa, perbedaannya
publik kemungkinan terbentuknya tidak pada suatu
tempat yang sama. Terbentuknya publik karena ada
perhatian yang disatukan oleh alat-alat
komunikasi, seperti : radio, tv, surat kabar,
jejaring sosial dan lain-lain.
b. Kelompok Nyata , mempunyai beberapa ciri khusus
sekalipun mempunyai berbagai macam bentuk, kelompok
nyata mempunyai 1 ciri yang sama, yaitu kehadirannya
selalu konstan.
1) Kelompok Statistical Group
Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan
organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan
kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok
penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan.
2) Societal Group / Kelompok Kemasyarakatan
Kelompok societal memiliki kesadaran akan kesamaan
jenis, seperti jenis kelamin, warna kulit,
kesatuan tempat tinggal, tetapi belum ada kontak
dan komunikasi di antara anggota dan tidak
terlihat dalam organisasi.
3) Kelompok sosial / social groups
Para pengamat sosial sering menyamakan antara
kelompok sosial dengan masyarakat dalam arti
khusus. Kelompok sosial terbentuk karena adanya
unsur-unsur yang sama seperti tempat tinggal,
pekerjaan, kedudukan, atau kegemaran yang sama.
Kelompok sosial memiliki anggota-anggota yang
berinteraksi dan berkomunikasi secara terus
menerus. Contoh : ketetanggaan, teman sepermainan,
teman seperjuangan, kenalan, dan sebagainya.
4) Kelompok asosiasi / associational group
Kelompok asosiasi adalah kelompok yang
terorganisir dan memiliki struktur formal
(kepengurusan).
Ciri-ciri kelompok asosiasi :
Direncanakan
Terorganisir
Ada interaksi terus menerus
Ada kesadaran kelompok
Kehadirannya konstan
2. Klasifikasi Kelompok Berdasarkan Solidaritas Antara
anggota
Istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog yang
bernama Emile Durkheim.
a. Solidaritas Mekanik
Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang muncul
pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh
kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya
pembagian kerja diantara para anggota kelompok.
b. Solidaritas Organik
Solidaritas organik adalah solidaritas yang mengikat
masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal
pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh
saling ketergantungan antar anggota.
3. Klasifikasi Kelompok Berdasarkan Erat Longgarnya Ikatan
dalam Kelompok.
Klasifikasi ini diperkenalkan oleh Ferdinand Tonnies
a. Gemeinschaft / paguyuban
Merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya
memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah
dan kekal.
Ferdinand Thonies membagi menajdi 3 bagian :
1) Gemeinschaff by blood: Paguyuban karena adanya
ikatan darah.
Contoh : kerabat, klien
2) Gemeinschaft of place: Paguyuban karena tempat
tinggal berdekatan.
3) Gemeinschaft of mind: Paguyuban karena jiwa dan
pikiran yang sama.
Contoh : kelompok pengajian, kelompok mahzab
(Sekte)
b. Gesselschaft / patembayan
Merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk
waktu yang pendek, strukturnya bersifat mekanis dan
sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka.
Contoh : ikatan antar pedagang, organisasi dalam
sebuah pabrik.
4. Klasifikasi Kelompok Berdasarkan Indentifikasi Diri
a. In-Group
In group : suatu perasaan perikatan antara satu
orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial
tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga
membentuk suatu perilaku – perilaku sosial tertentu
seperti : Solidaritas, kesediaan berkorban, kerja
sama, konformitas, obediance, dll.
b. Out-Group
Out group : Out-side feeling, seseorang merasa bukan
bagian dari kehidupan kelompok. Out-group feeling
selalu ditandai munculnya perilaku antogonistik dan
antipati. Sehingga muncul gejala prejudiace,
paranoid, etnocentristic, non koperatif, lalai, dan
sebagainya.
5. Klasifikasi Kelompok Berdasarkan Kualitas Hubungan
diantara Para Anggotanya
a. Kelompok Primer
Merupakan suatu kelompok yang hubungan antar
anggotanya saling kenal mengenal dan bersifat
informal. Contoh : keluarga, kelompok sahabat,
teman, teman sepermainan.
b. Kelompok Sekunder
Kelompok Sekunder adalah kelompok sosial yang
terbentuk karena Merupakan hubungan antar anggotanya
bersifat formal, impersonal dan didasarkan pada asas
manfaat. Contoh : sekolah, PGRI
6. Klasifikasi Kelompok Berdasarkan Pencapaian Tujuan
a. Kelompok Formal
Merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan
dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur
hubungan antar anggotanya. Contoh : Parpol, lembaga
pendidikan
b. Kelompok Informal
Merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena
pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki
kepentingan dan pengalaman yang sama.Contoh :
anggota OSIS
Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa
hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk
kerja sama kita dengan orang lain yaitu dengan
membentuk kelompok sosial. Dalam sebuah kelompok
sosial dapat membantu kita untuk mempermudah
menyelesaikan suatu urusan, tugas atau tujuan
dengan cara bekerja sama.
Pekerjaan yang terasa sulit kita kerjakan
sendiri akan menjadi lebih mudah jika dikerjakan
secara berkelompok sebab dalam suatu anggota
kelompok , setiap anggota mempunyai keahlian khusus
di bidangnya masing-masing, sehinga terjadilah
pembagian tugas dan spesifikasi kerja yang membuat
hasil dari pekerjaan tersebut menjadi maksimal.
C. Status Sosial dan Peran Sosial
Dalam sosiologi, terdapat stratifikasi sosial yang dapat
kita jabarkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur stratifikasi
sosial itu sendiri ada dua yakni status sosial dan
peranan sosial. Status sosial dan peranan sosial
merupakan unsur penentu bagi penempatan seseorang dalam
masyarakat. Kedudukan dapat memberikan pengaruh,
kehormatan, kewibawaan pada seseorang, sedangkan peranan
merupakan sikap tindak seseorang yang menyandang status
dalam kehidupan masyarakat.
a. Status Sosial
Menurut Mayor Polak ( 1979 ), status dimaksudkan
sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam masyarakat
maupun kelompok. Status mempunyai dua aspek, yakni
aspeknya agak stabil, dan kedua aspeknya yang lebih
dinamis. Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek
struktural dan fungsional. Pada aspek uang pertama
sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan
tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-
status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan
sebagai peranan sosial ( social role ) yang berkaitan
dengan status tertentu, yang dimiliki seseorang.
Status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut
proses perkembangannya, yaitu sebagai berikut :
1) Status yang diperoleh atas dasar keturunan
(Ascribed-Status). Padaumumnya status ini banyak
dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang menganut
stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal
atau masyarakat yang menganut paham rasialisme.
Contoh lain, seorang suami telah dikodratkan
mempunyai status berbeda dengan istri dan anak-
anaknya dalam keluarga, paling tidak secara fisik
seorang laki-laki apa adanya. Kendatipun
emansipasi telah dapat menyamai kaum laki-laki di
bidang lain, seperti pendidikan, politik,
pekerjaan dan jabatan, akan tetapi tidak
menyamainya dalam hal fisik dan biologis.
2) Status yang diperolea atas dasar usaha yang
disengaja (Achieved-Status), status ini dalam
perolehannya berbeda dengan status atas dasar
kelahiran, kodrat atau keturunan, status ini
bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita
yang direncanakan dan diperhitungkan dengan
matang. Individu dan segenap anggota masyarakat
berhak dan bebas menentukan kehendaknya sendiri
dalam memilih status tertentu sesuai dengan
kemampuannya sendiri. Setiap orang dapat menjadi
hakim, menteri, dokter, guru besar, dan
sebagainya, asal ia dapat memenuhi syarat-syarat
tertentu dalam usaha dan kerja keras dalam proses
pencapaian tujuannya itu. Mayor Polak membedakan
lagi atas satu macam status, yaitu status yang
dberikan (Assigned-Status). Status ini sering
mempunyai hubungan erat dengan achieved status,
dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan
memberikan status yang lebih tinggi kepada
seseorang yang dianggap telah berjasa, telah
memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
b. Peranan Sosial
Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang
dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan
kewajiban sesuai dengan status sosialnya. Seseorang
dapat dikatakan berperanan jika dia sudah menjalankan
hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di
dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status
tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya
ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan
baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan
bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya
dengan dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Dengan
singkat, peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan
tindakan seseorang sesuai dengan statusnya di dalam
masyrakat. Atas dasar definisi tersebut maka peranan
dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai aspek dinamis
dari status.
Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peranan
sosial adalah terletak pada adanya hubungan-hubungan
sosial seseorang dalam masyarakat yang menyangkut
dinamika dari cara-cara bertindak dengan berbagai norma
yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana pengakuan
terhadap status sosialnya. Sedangkan fasilitas utama
seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah
lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.
Biasanya lembaga masyarakat menyediakan peluang untuk
pelaksanaan suatu peranan. Menurut Levinson, bahwa
peranan mencakup tiga hal, pertama, peranan meliputi
norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua,
peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai
organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan
sebagai perikelakuan individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu
proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri
dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang
aneka macam peranan yang melekat pada individu –
individu dalam masyarakat, Soerjono mengutip pendapat
Marion J. Levy, bahwa ada beberapa pertimbangan
sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut :
a) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan
apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan
kelangsungannya.
b) Peranan tersebut seyogianya dilekatkan pada
individu yang oleh masyarakat dianggap mampu
melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih
dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk
melaksanakannya.
c) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-
individu yang tak mampu melaksanakan peranannya
sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh
karena mungkin pelaksanaanya memerlukan
pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-
kepentingan pribadinya.
d) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan
peranannya, belum tentu masyarakat akan mampu
memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahakan
seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa
membatasi peluang-peluang tersebut.\
D. Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial
Setiap individu lahir dan berkembang dalam kondisi yang
berbeda-beda. Keberagaman individu dalam masyarakat ini
disebut dengan perbedaan sosial. Perbedaan sosial secara
umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbedaan
secara horizontal dan perbedaan secara vertikal.
Perbedaan secara horizontal disebut dengan diferensiasi.
Dalam diferensiasi sosial, tidak dikenal adanya tingkatan
atau tinggi rendahnya status sosial seseorang. Sedangkan
pebedaan secara vertikal disebut dengan stratifikasi,
dimana ada masyarakat yang menduduki lapisan atas dan ada
pula yang menduduki lapisan bawah. Stratifikasi sosial
ini terjadi karena adanya sesuatu yang lebih dihargai
dalam masyarakat.
a) Diferensiasi Sosial
Seperti yang telah disebutkan diatas, diferensiasi
sosial adalah pembedaan masyarakat secara horisontal
tanpa mempermasalahkan tinggi rendahnya status sosial
masyarakat tertentu. Diferensiasi sosial muncul karena
adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan-
perbedaan ini menyebabkan adanya pengelompokan
masyarakat ke dalam kategori tertentu berdasarkan ciri
fisik atau ciri sosial budaya. Beberapa contoh bentuk
diferensiasi sosial antara lain diferensiasi sosial
berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan gender.
Ras. Merupakan penggolongan manusia berdasarkan
ciri-ciri fisik yang tampak dari luar (fenotip),
seperti warna kulit, bentuk rambut, ukuran badan,
dan lain-lain. Ras merupakan kodrat setiap
manusia, jadi tidak ada satu ras yang memiliki
kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
ras yang lain. Secara umum, ras-ras manusia di
dunia dapat dibedakan menjadi empat, yaitu ras
Austroloid (orang Aborigin), Mongoloid (Asia dan
penduduk asli Amerika), Kaukasoid (Eropa dan
Arab), dan Negroid (kulit hitam).
Suku Bangsa. Adalah pengelompokan manusia
berdasarkan corak budaya yang dimilikinya. Hildred
Geertz dalam penelitiannya menyatakan bahwa di
Indonesia terdapat 319 suku bangsa, sedangkan
menurut Koentjoroningrat terdapat 200 suku bangsa.
Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa
daerah, adat istiadat, dan kesenian yang khas.
Agama. Merupakan sistem kepercayaan yang telah
dibakukan dan dipandang sebagai sebuah kebenaran.
Agama berisi pedoman-pedoman kepada manusia
tentang hubungan antara sesama manusia dan antara
manusia dengan tuhan.
Gender. Adalah diferensiasi sosial berdasarkan
perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan.
Dalam beberapa kebudayaan, laki-laki dianggap
memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada
perempuan. Akan tetapi, sekarang ini laki-laki dan
perempuan dianggap mempunyai kedudukan dan peran
yang sejajar dalam masyarakat.
b) Stratifikasi Sosial
Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti
lapisan. Jadi stratifikasi sosial bisa disebut dengan
pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara
bertingkat yang biasanya disimbolkan dengan piramida.
Dalam stratifikasi sosial, terdapat kelompok masyarakat
yang menghuni kelas atas dan ada juga yang menghuni
kelas bawah. Stratifikasi sosial muncul karena adanya
sesuatu yang dianggap memiliki kedudukan yang lebih
tinggi dalam masyarakat seperti harta yang dimiliki
seseorang, kekuasaan, keturunan pekerjaan, keahlian,
atau umur.
Sifat-sifat Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial dalam masyarakat pada umumnya
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stratifikasi
tertutup dan stratifikasi terbuka.
Stratifikasi Sosial Tertutup . Mempunyai arti
bahwa seseorang yang berada pada strata
tertentu dalam masyarakat tidak akan mungkin
bisa berpindah ke lapisan yang lainnya baik
yang berada diatas maupun dibawah.
Stratifikasi sosial tipe ini biasanya
didasarkan atas warisan biologis seseorang
yang sudah didapat semenjak ia lahir. Contoh
stratifikasi sosial tertutup adalah sistem
pengkastaan yang terdapat dalam Agama Hindu
dan politik apartheid yang pernah diterapkan
di Afrika Selatan selama masa pendudukan
Inggris.
Stratfikasi Sosial Terbuka . Stratifikasi
sosial tipe ini biasanya terdapat pada
masyarakat modern dimana seorang individu
dapat berpindah dari satu lapisan satu ke
lapisan yang lainnya, baik yang berada di
atasnya maupun yang ada di bawahnya. Contoh
dari sistem stratifikasi sosial terbuka
antara lain jabatan, tingkat pendidikan,
pendapatan, dan gelar.
E. Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Multicultural
Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang pada
prinsipnya hidup berkelompok baik di lingkungan maupun di
masyarakat. Keberadaan ini merupakan proses untuk
berinteraksi atau berhubungan dengan yang lain. Dalam
ilmu sosiologi kelompok sosial sering juga disebut dengan
kerumunan yang dapat diartikan sebagai individu-individu
yang berada pada tempat yang sama. Akan tetapi tetaplah
ada perbedaan antara kerumununan dengan kelompok sosial.
Perbedaan antara kelompok sosial dengan kerumunan
tersebut dibawah ini adalah :
Kelompok sosial Kerumunan :
1. Bersifat tetap 1. Bersifat sementara
2. Memiliki tujuan sama 2. Tujuan berbeda
3. Interaksi jelas dan terfokus 3. Interaksi
tidak terfokus
4. Mengarah pada pembentukan 4. Tidak mengarah
pada pembentukan
Masyarakat
Di dalam kelompok sosial terdapat bermacam macam suku
bangsa, ras, agama dan budaya sehingga terbentuklah
masyarakat multikultural. Kata MASYARAKAT MULTIKULTURAL
dapat kita pilah menjadi tiga kata yaitu :
a) Masyarakat
Artinya adalah sebagai satu kesatuan hidup manusia yang
berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang
bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas
bersama.
b) Multi
Berarti banyak atau beraneka ragam
c) Kultural
Berarti Budaya. Masyarakat Multikultural adalah
kesatuan manusia atau individu yang memiliki beraneka
ragam budaya. Oleh karena itu dalam
masyaarakaatterdapat beranekaragam kelompok sosial
dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda.
Berikut ini pandangan ahli sosiologi tentang masyarakat
multicultural:
J.S FURNIVALL
Masyarakat multikultural terbentuk oleh dua atau
lebih komunitas (kelompok), mereka ini secara budaya
dan ekonomi terpisah satu sama lain. Struktur
kelembagaan yang terdapat di dalam kelompok tersebut
berbeda satu dengan lain.
NASIKUN
Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang
menganut banyak nilai. Hal ini terbentuk karena
kelompok sosial yang ada di dalamnya memiliki sistem
nilai tersendiri.
PIERRE L. VAN DE BERGHE
Masyarakat multikultural memiliki karakteristik
sebagai berikut ini :
a. Memiliki sub kebudayaan
b. Struktur sosial yang terbentuk rawan terjadi
konflik
c. Integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling
ketergantungan di dalam bidang ekonomi
CLIFFORT GEERTZ
Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang
memiliki ikatan-ikatan primordialitas. Ikatan ini
kemudian berkaitan erat dengan label yang diberikan
oleh individu/kelompok lain, dengan demikian setiap
individu/kelompok memiliki karakter yang berbeda
dengan yang lain.
Keaneka ragaman dalam masyarakat memiliki ciri-ciri
sebagai berikut ini :
1) Memiliki lebih dari subkebudayaan.
2) Membentuk sebuah struktur sosial.
3) Membagi masyarakat menjadi dua pihak, yaitu pihak
yang mendominasi dan yang terdominasi.
4) Rentan terhadap konflik sosial.
Dalam Masyarakat multikultural akan dijumpai
perbedaan-perbedaan yang merupakan bentuk
keanegaragaman seperti budaya, ras suku, agama.
Dalam masyarakat multi kultural tidak mengenal
perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok
minoritas dengan mayoritas baik secara hukum
maupun sosial. Kelompok sosial memiliki hubungan
erat dengan masyarakat multikultural yaitu
hubungan :
Kelompok sosial sebagai unsur pembentuk
masyarakat multikultural.
Macam-macam kelompok sosial belum tentu
membentuk sebuah masyarakat multikultural,
namun demikian masyarakat multi kultural
tidak akan terwujud tanpa adanya kelompok
sosial. Kelompok sosial dikatan sebagai salah
satu unsur pembentuk masyarakat
multikultural.
Kelompok sosial sebagai dinamisator
masyarakat multicultural
Urutan terbentuknya masyarakat multikultural
adalah sebagai berikut;
a) Individu
b) Kelompok sosial
c) Masyarakat
d) Masyarakaat multicultural
Dari urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kelompok sosial merupakan unsur pembentuk
masyarakat multikultural. Konflik pada
mayarakat multukultural dapat saja terjadi
karena didalamnya terdiri beranekaragam
perbedaan akan tetapai hal ini dapat dicegah
dengan cara masing-masing saling menjaga diri
maupun menghargai.
Kelompok sosial sebagai pengikat masyarakat
multicultural.
Untuk mempertahankan masyarakat multikultural
yang sudah baik perlu dibuat pengikat
individu maupun kelompok agar tetap tejaga
dengan baik. Pengikat hanya dapat dilakukan
dengan bentuk loyalitas angota kelompok
tersebut.
F. Konflik Sosial
Jumlah suku dan etnis di Indonesia diperkirakan
lebih dari 300, dengan beragam latar belakang dan
karakter. Sehingga persoalan konflik sosial di Indonesia
memang sangat kompleks dan tidak mudah dalam mencari
solusinya. Selain konflik antar-etnis, di Indonesia juga
rawan konflik sosial dengan latar belakang bermacam-
macam.
Kasus Sampit merupakan contoh konflik sosial yang
paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan dewasa
ini. Selain itu, masih ada beberapa konflik, seperti
kasus Ambon tahun 1999-2002, kasus Poso 1998-2001, dan
baru-baru ini ada kasus Sampang, Madura dan Lampung
Selatan tahun 2012. Kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi
oleh SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
Jika kembali ke tahun lebih lampau, juga ada kasus
konflik sosial antar-etnis. Misalnya, kasus konflik etnis
Samawa dengan etnis Bali di Sumbawa pada tahun 1980.
Namun, ketika itu belum banyak media yang memberitakan
kejadian ini. Jika kita runut sejarah ke belakang, Bangsa
Indonesia memang sangat rentan terjadinya konflik sosial.
MODUL IPS
Disusun Oleh :
Nama : Reny Febrianti
No : 12
Kelas : XII . AK 2
SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015
MODUL IPS
Disusun Oleh :
Nama : Syari Falah Azizah
No : 18
Kelas : XII . AK 2
SMK MUHAMMADIYAH 4 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015