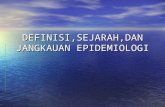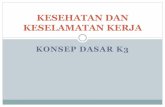Konsep Epidemiologi
-
Upload
diponegoro -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Konsep Epidemiologi
Nama Anggota Kelompok1. Achmad Rizki
Azhari/25010113140258/D20132. Kristian Yudhianto
/25010113140312/D20133. Febri Iswanto /25010113140313/D2013
4. Bhakti Chrisna /25010113130317/D2013
Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas Diponegoro
Semarang2014
Pertanyaan :1. Jelaskan definisi dari penyakit !2. Jelaskan teori terjadinya penyakit :
a) Contagion, b) Hipocratic, c) Miasmatic d) Germe) Segitiga epidemiologif) Web causation g) Wheel causation !
3. Jelaskan definisi riwayat alamiah penyakit !4. Jelaskan definisi stimulus penyakit !5. Jelaskan definisi periode prepatogenesis !6. Jelaskan definisi periode pathogenesis !7. Jelaskan definisi masa inkubasi !8. Jelaskan definisi masa induksi !9. Jelaskan definisi masa menular !10. Jelaskan perbedaan dinamika penularan dan
dinamika penyakit !11. Jelaskan definisi periode jendela !12. Jelaskan definisi periode klinis !13. Jelaskan secara lengkap rantai infeksi !14. Jelaskan pencegahan primordial primer, tersier,
dan sekunder !
Jawaban :1. Pengertian Penyakit
# KATHLEEN MEEHAN ARIAS
Penyakit adalah suatu kesakitan yang biasanya memiliki sedikitnya dua sifat dari kriteria ini: agen atiologik telah diketahui, kelompok tanda serta gejala yang dapat diidentifikasi, atau perubahan anatomi yang konsisten
# DR. BEATE JACOB
Penyakit adalah suatu penyimpangan dari keadaan tubuh yang normal atau ketidakharmonisan jiwa
# WAHYUDIN RAJAB, M. Epid
Penyakit adalah keadaan yang bersifat objektif dan rasa sakit bersifat subjektif
# DR. EKO DUDIARTO
Penyakit adalah jegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsanganatau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh
# THOMAS TIMMRECK
Penyakit adalah suatu keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal.
# ELIZABETH J. CROWN
Penyakit ialah perihal kehadiran seperangkat respons tubuh yang abnormal terhadap agen, dimana manusia mempunyai toleransi sedikit atau tidak samasekali
# GEORGE PICKETT & JOHN J. HANLON
Penyakit adalah fungsi dari kekuatan agens penyebab dan daya tahan tubuh manusia
# AZIZAN HAJI BAHARUDDIN
Penyakit ialah keadaan yang diakibatkan oleh kerusakan keseimbangan fungsi tubuh dan bagian badan
# MUNADJAD ISKANDAR
Penyakit adalah suatu proses alami yang harus kita hadapi, bukan untuk kita musuhi
2. Teori Terjadinya Penyakit
A. Teori ContagionDi Eropa, epidemi sampar, cacar dan demam tifus
merajalela pada abad ke-14 dan 15. Keadaan buruk
yang dialami manusia pada saat itu telah mendorong
lahirnya teori bahwa kontak dengan makhluk hidup
adalah penyebab penyakit menular. Konsep itu
dirumuskan oleh Girolamo Fracastoro (1483-1553).
Teorinya menyatakan bahwa penyakit ditularkan dari
satu orang ke orang lain melalui zat penular
(transference) yang disebut kontagion.
Fracastoro membedakan tiga jenis kontagion, yaitu:
a) Jenis kontagion yang dapat menular melalui
kontak langsung, misalnya bersentuhan,
berciuman, hubungan seksual.
b) Jenis kontagion yang menular melalui benda-
benda perantara (benda tersebut tidak tertular,
namun mempertahankan benih dan kemudian
menularkan pada orang lain) misalnya melalui
pakaian, handuk, sapu tangan.
c) Jenis kontagion yang dapat menularkan pada
jarak jauh
Pada mulanya teori kontagion ini belum
dinyatakan sebagai jasad renik atau mikroorganisme
yang baru karena pada saat itu teori tersebut tidak
dapat diterima dan tidak berkembang. Tapi penemunya,
Fracastoro, tetap dianggap sebagai salah satu
perintis dalam bidang epidemiologi meskipun baru
beberapa abad kemudian mulai terungkap bahwa teori
kontagion sebagai jasad renik. Karantina dan
kegiatan-kegiatan epidemik lainnya merupakan
tindakan yang diperkenalkan pada zaman itu setelah
efektivitasnya dikonfirmasikan melalui pengalaman
praktek.
B. Teori HippocraticMenyusul contagion theory , para pemikir
kesehatan , dipelopori oleh Hipocrates mulai lebihmengarahkan kausa pada suatu factor tertentu.
Hipocrates (460-377 SM), yang dianggap sebagaiBapak Kedokteran Modern, telah berhasil membebaskanhambatan-hambatan filosofis pada zaman itu yangbersifat spekulatif dan superstitif (tahayul) dalammemahami kejadian penyakit. Ia mengemukakan teoritentang sebab musabab penyakit, yaitu bahwa :a) Penyakit terjadi karena adanya kontak dengan
jasad hidup, dan
b) Penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun internal seseorang.
Teori itu dimuat dalam karyanya berjudul “OnAirs, Waters and Places”. Hippocrates mengatakanbahwa kausa penyakit berasal dari alam , cuaca danlingkungan. Perubahan cuaca dan lingkungan yangditunjuk sebagai keladi perkembangan penyakit.Teori ini mampu menjawab masalah penyakit yang adapada waktu itu dan dipakai hingga tahun 1800-an.Kemudian ternyata teori ini tidak mampu menjawabtantangan berbagai penyakit infeksi lainnya yangmempunyai rantai penularan yang berbelit belit.
C. Teori MiasmaticKira-kira pada awal abad ke-18 mulai muncul
konsep miasma sebagai dasar pemikiran untuk
menjelaskan timbulnya wabah penyakit. Kosep ini
dikemukakan oleh Hippocrates. Miasma atau miasmata
berasal dari kata Yunani yang berarti something dirty
(sesuatu yang kotor) atau bad air (udara buruk).
Miasma dipercaya sebagai uap yang dihasilkan dari
sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan,
barang yang membusuk atau dari buangan limbah yang
tergenang, sehingga mengotori udara, yang dipercaya
berperan dalam penyebaran penyakit. Contoh pengaruh
teori miasma adalah timbulnya penyakit malaria.
Malaria berasal dari bahasa Italia mal dan aria yang
artinya udara yang busuk. Pada masa yang lalu
malaria dianggap sebagai akibat sisa-sisa pembusukan
binatang dan tumbuhan yang ada di rawa-rawa.
Penduduk yang bermukim di dekat rawa sangat rentan
untuk terjadinya malaria karena udara yang busuk
tersebut.
Pada waktu itu dipercaya bahwa bila seseorang
menghirup miasma, maka ia akan terjangkit penyakit.
Tindakan pencegahan yang banyak dilakukan adalah
menutup rumah rapat-rapat terutama di malam hari
karena orang percaya udara malam cenderung membawa
miasma. Selain itu orang memandang kebersihan
lingkungan hidup sebagai salah satu upaya untuk
terhindar dari miasma tadi. Walaupun konsep miasma
pada masa kini dianggap tidak masuk akal, namun
dasar-dasar sanitasi yang ada telah menunjukkan
hasil yang cukup efektif dalam menurunkan tingkat
kematian.
Dua puluh tiga abad kemudian, berkat penemuan
mikroskop oleh Anthony van Leuwenhoek, Louis Pasteur
menemukan bahwa materi yang disebut miasma tersebut
sesungguhnya merupakan mikroba, sebuah kata Yunani
yang artinya kehidupan mikro (small living)
D. Teori Germ
Penemuan-penemuan di bidang mikrobiologi dan
parasitologi oleh Louis Pasteur (1822-1895), Robert
Koch (1843-1910), Ilya Mechnikov (1845-1916) dan
para pengikutnya merupakan era keemasan teori kuman.
Para ilmuwan tersebut mengemukakan bahwa mikroba
merupakan etiologi penyakit.
Louis Pasteur pertama kali mengamati proses
fermentasi dalam pembuatan anggur. Jika anggur
terkontaminasi kuman maka jamur mestinya berperan
dalam proses fermentasi akan mati terdesak oleh
kuman, akibatnya proses fermentasi gagal. Proses
pasteurisasi yang ia temukan adalah cara memanasi
cairan anggur sampai temperatur tertentu hingga
kuman yang tidak diinginkan mati tapi cairan anggur
tidak rusak. Temuan yang paling mengesankan adalah
keberhasilannya mendeteksi virus rabies dalam organ
saraf anjing, dan kemudian berhasil membuat vaksin
anti rabies. Atas rintisan temuan-temuannya memasuki
era bakteriologi tersebut, Louis Pasteur dikenal
sebagai Bapak dari Teori Kuman.
Robert Koch juga merupakan tokoh penting dalam
teori kuman. Temuannya yang paling terkenal dibidang
mikrobiologi adalah Postulat Koch yang terdiri
dari:
a) Kuman harus dapat ditemukan pada semua hewan
yang sakit, tidak pada yang sehat,
b) Kuman dapat diisolasi dan dibuat biakannya,
c) Kuman yang dibiakkan dapat ditularkansecara
sengaja pada hewan yang sehat dan menyebabkan
penyakit yang sama
d) Kuman tersebut harus dapat diisolasi ulang dari
hewan yang diinfeksi.
E. Trias Epidemiologi (Segitiga Epidemiologi)
Model tradisional epidemiologi atau segitiga
epidemiologi dikemukakan oleh Gordon dan La Richt (1950),
menyebutkan bahwa timbul atau tidaknya penyakit pada
manusia dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu host,
agent, dan environment. Gordon berpendapat bahwa:
1. Penyakit timbul karena ketidakseimbangan antara agent
(penyebab) dan manusia (host)
2. Keadaan keseimbangan bergantung pada sifat alami dan
karakteristik agent dan host (baik individu/kelompok)
3. Karakteristik agent dan host akan mengadakan
interaksi, dalam interaksi tersebut akan berhubungan
langsung pada keadaan alami dari lingkungan
(lingkungan sosial, fisik, ekonomi, dan biologis).
Agen Penyakit
Agen penyakit dapat berupa benda hidup atau mati dan
faktor mekanis, namun kadang-kadang untuk penyakit
tertentu, penyebabnya tidak diketahui seperti pada
penyakit ulkus peptikum, penyakit jantung koroner dan
lain-lain.
unsur penyebab penyakit dapat dibagi dalam dua bagian
utama, yakni :
1. Penyebab kausal primer
Unsur ini dianggap sebagi faktor kausal terjadinya
penyakit, dengan ketentuan bahwa walaupun unsur ini ada,
belum tentu terjadi penyakit. Sebaliknya pada penyakit
tertentu, unsur ini selalu dijumpai sebagai unsur
penyebab kausal. Unsur penyebab kausal ini dapat dibagi
dalam 5 kelompok utama, yaitu :
1) Unsur penyebab biologis, yakni semua unsur penyebab
yang tergolong makhluk hidup termasuk kelompok
mikroorganisme (Nur Nasry Noor, 2008:30). seperti :
a. Virus,
b. Bakteri,
c. Jamur,
d. Parasit,
e. Protozoa,
f. Metazoa. (Eko Budiarto. 2002: 15).
Unsur penyebab ini pada umumnya dijumpai pada penyakit
infeksi dan penyakit menular. (Nur Nasry Noor, 2008:30).
Sifat-sifat mikroorganisme sebagai agen penyebab penyakit
juga merupakan faktor penting dalam proses timbulnya
penyakit infeksi. Sifat-sifat mikroorganisme tersebut
antara lain:
1. Patogenesis
2. Virulensi
3. Tropisme
4. Serangan terhadap pejamu
5. Kecepatan berkembang biak
6. Kemampuan menembus jaringan
7. Kemampuan memproduksi toksin
8. Kemampuan menimbulkan kekebalan
2) Unsur penyebab nutrisi,
yakni semua unsur penyebab yang termasuk golongan zat
nutrisi dan dapat menimbulkan penyakit tertentu karena
kekuranagn maupun kelebihan zat nutrisi tertentu
seperti protein, lemak, hidrat arang, vitamin, mineral
3) Unsur penyebab kimiawi
yakni semua unsur dalam bentuk senyawaan kimia yang
dapat menimbulkan gangguan kesehatan/penyakit
tertentu. Unsur ini pada umumnya berasal dari luar
tubuh termasuk berbagai jenis zat racun, obat-obat
keras, berbagai senyawaan kimia tertentu dan lain
sebagainya, bentuk senyawaan kimia ini dapat berbentuk
padat, cair, uap, maupun gas. Adapula senyawaan
kimiawi sebagai hasil produk tubuh (dari dalam) yang
dapat menimbulkan penyait tertentu seperti ueum,
kolesterol, dan lain-lain
4) Unsur penyebab fisika
yakni semua unsur yang dapat menimbulkan penyakit
melalui proses fisika, umpamanya panas (luka bakar),
irisan, tikaman, pukulan (rudapaksa) radiasi dan lain-
lain. Proses kejadian penyakit dalam hal ini terutama
melalui proses fisika yang dapat menimbulkan kelainan
dan gangguan kesehatan.
5) Unsur penyebab psikis
yakni semua unsur yang bertalian dengan kejadian
penyakit gangguan jiwa serta gangguan tingkah laku
sosial. Unsur penyebab ini belum jelas proses dan
mekanisme kejadian dalam timbulnya penyakit, bahkan
sekelompok ahli lebih menitikbertkan kejadian penyakit
pada unsur penyebab genetika. Dalam hal ini kita harus
berhati-hati terhadap factor kehidupan sosial yang
bersifat nonkausal serta lebih menampakkan diri dalam
hubungannya dengan proses kejadian penyakit maupun
gangguan kejiwaan.
2. Penyebab non kausal sekunder
Penyebab sekunder merupakan unsur
pembantu/penambah dalam proses kejadian penyakit dan
ikut dalam hubungan sebab akibat terjadinya
penyakit. Dengan demikian, dalam setiap analisis
penyebab penyakit, kita tidak hanya berpusat pada
penyebab kausal primer semata, tetapi harus
memperhatikan semua unsur lain di luar unsur
penyebab kausal primer. Hal ini didasarkan pada
ketentuan bahwa pada umumnya, kejadian setiap
penyakit sangat dipengaruhi oleh berbagai unsur yang
berinteraksi dengan unsur penyebab dan ikut dalam
proses sebab akibat. Faktor yang terinteraksi dalam
proses kejadian penyakit dalam epidemiologi
digolongkan dalam faktor resiko. Sebagai contoh pada
penyakit kardiovaskuler, tuberkulosis, kecelakaan
lalulintas, dan lain sebagainya. Kejadiannya tidak
dibatasi hanya pada penyebab kausal saja, tetapi
harus dianalisis dalam bentuk suatu rantai sebab
akibat yang peranan unsur penyebab sekundernya
sangat kuat dalam mendorong penyebab kausal primer
untuk dapat secara bersama-sam menimbulkan penyakit.
(Nur Nasry Noor, 2008:32).
Host (Penjamu)
Penjamu adalah manusia atau makhluk hidup
lainnya, termasuk burung dam atropoda, yang menjadi
tempat terjadi proses alamiah perkembangan penyakit.
Faktor penjamu yang berkaitan dengan kejadian
penyakit dapat berupa : umur, jenis, kelamin, ras,
etnik, anatomi tubuh, dan status gizi.
Yang termasuk dalam factor penjamu adalah :
a) Genetik; misalnya sickle cell disease
b) Umur; ada kecenderungan penyakit menyerang umur
tertentu
c) Jenis kelamin (gender): ditemukan penyakit yang
terjadi lebih banyak atau hanya mungkin pada
wanita
d) Suku/ras/warna kulit: dapat ditemukan perbedaan
antara ras kulit putih dengan prang kulit hitam
e) Keadaan fisiologi tubuh: kelelahan, kehamilan,
pubertas, stress, atau keadaam gizi
f) Keadaan imunologis: kekebalan yang diperoleh
karena adanya infeksi sebelumnya, memperoleh
antobodi dari ibu, atau pemberian kekebalan
bauatan (vaksinasi)
g) Tingkah laku (behavior): gaya hidup, personal hygiene,
hubungan antarpribadi, dan rekreasi
Lingkungan (Environment)
“Lingkungan” merupakan faktor ketiga sebagai
penunjang terjadinya penyakit. Faktor ini disebut
“faktor ekstrinsik”. (Eko Budiarto. 2002: 16).
Unsur lingkungan memegang peranan yang cukup
penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi
antara pejamu dengan unsure penyebab dalam proses
terjadinya penyakit. Secara garis besarnya, maka
unsure lingkungan dapat dibagi dalam 3 bagian utama.
a. Lingkungan biologis
Segala flora dan fauna yang berada di sekitar manusia
yang antara lain meliputi:
1. Berbagai mikroorganisme pathogen dan yang tidak
pathogen.
2. Berbagai binatang dan tumbuhan yang dapat
mempengaruhi kehidupan manusia, baik sebagai
sumber kehidupan (bahan makanan dan obat-obatan),
maupun sebagai reservoir/ sumber penyakit atau
pejamu antara (host intermedia).
3. Fauna sekitar manusia yang berfungsi sebagai
vector penyakit tertentu
terutama penyakit menular.
Lingkungan biologis tersebut sangat berpengaruh
dan memegang peranan penting dalam interaksi
antara manusia sebagai pejamu dengan unsure
penyebab, baik sebagai unsure lingkungan yang
menguntungkan manusia (sebagai sumber kehidupan)
maupun yang mengancam kehidupan/ kesehatan
manusia.
b. Lingkungan fisik
Keadaan fisik sekitar manusia yang berpengaruh
terhadap manusia baik secara langsung, maupun
terhadap lingkungan biologis dan lingkungan sosial
manusia. Lingkungan fisik (termasuk unsure kimiawi
dan radiasi) meliputi:
1. Udara, keadaan cuaca, geografis, dan geologis.
2. Air, baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai
sumber penyakit serta berbagai unsure kimiawi
serta berbagai bentuk pencemaran pada air.
3. Unsur kimiawi lainnya dalam bentuk pencemaran
udara, tanah dan air, radiasi dan lain
sebagainya.
Lingkungan fisik ini ada yang terbentuk secara
alamiah, tetapi banyak pula yang timbul akibat
kegiatan manusia sendiri.
c. Lingkungan sosial ekonomi
Semua bentuk kehidupan sosial budaya, ekonomi,
politik. System organisasi, serta institusi/
peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang
membentuk masyarakat tersebut. Lingkungan sosial ini
meliputi:
1. Sistem hukum, administrasi dan kehidupan sosial
politik serta system ekomoni yang berlaku.
2. Bentuk organisasi masyarakat yang berlaku
setempat.
3. Sistem pelayanan kesehatan serta kebiasaan
hidup sehat masyarakat setempat.
4. Kepadatan penduduk, kepadatan rumah tangga, dan
berbagai system kehidupan sosial lainnya.
(Nur Nasry Noor, 2008: 33-35)
5. Pekerjaan.
Pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia
seperti pestisida atau zat fisika seperti zat
radioaktif atau zat yang bersifat karsinogen
seperti abses akan memudahkan terkena penyakit
akibat pemaparan terhadap zat-zat tersebut.
6. Perkembangan ekonomi.
Peningkatan ekonomi rakyat akan mengukur pola
konsumsi yang cenderung memakan makanan yang
mengandung banyak kolesterol. Keadaan ini
memudahkan timbulnya penyakit hipertensi dan
penyakit jantung sebagai akibat kadar kolesterol
darah yang meningkat. Sebaliknya bila tingkat
ekonomi rakyat yang rendah akan timbul masalah
perumahan yang tidak sehat, kurang gizi, dan
lain-lain yang memudahkan timbulnya penyakit
infeksi.
7. Bencana alam.
Terjadinya bencana alam akan mengubah sistem
ekologi yang tidak diramalkan sebelumnya.
Misalnya gempa bumi, banjir, meletusnya gunung
berapi, dan perang yang akan menyebabkan
kehidupan penduduk yang terkena bencana menjadi
tidak teratur. Keadaan ini memudahkan timbulnya
berbagai penyakit infeksi.
F. Web Causation
Model ini dicetuskan oleh MacMahon dan
Pugh (1970). Prinsipnya adalah setiap efek atau
penyakit tidak pernah tergantung hanya kepada
sebuah faktor penyebab, melainkan tergantung
kepada sejumlah faktor dalam rangkaian
kausalitas sebelumnya sebagai akibat dari
serangkaian proses sebab akibat. Ada faktor
yang berperan sebagai promotor, ada pula
sebagai inhibitor. Semua faktor tersebut secara
kolektif dapat membentuk “web of causation”
dimana setiap penyebab saling terkait satu sama
lain. Perubahan pada salah satu faktor dapat
berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit.
Kejadian penyakit pada suatu populasi mungkin
disebabkan oleh gejala yang sama (phenotype),
mikroorganisme, abnormalitas genetik, struktur
sosial, perilaku, lingkungan, tempat kerja dan
faktor lainnya yang berhubungan. Dengan
demikian timbulnya penyakit dapat dicegah atau
dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai
titik. Model ini cocok untuk mencari penyakit
yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup
individu.
G. Wheel Causation
Model roda menggambarkan hubungan manusia
dan lingkungannya sebagai roda. Roda tersebut
terdiri atas manusia dengan substansi genetik
pada bagian intinya dan faktor lingkungan
biologi, sosial, fisik yang mengelilingi host
(manusia). Ukuran komponen roda bersifat relatif,
bergantung pada problem spesifik dari
penyakitnya.
Model ini digambarakan dengan lingkaran yang
didalamnya terdapat lingkaran yang lebih kecil.
Lingkaran yang besar sebagai faktor eksternal dan
lingkaran yang kecil sebagai faktor internalnya.
Faktor internalnya (host) menyatakan bahwa suatu
penyakit disebabkan oleh adanya interaksi antara
genetic dengan lingkungannya. Faktor internal ini
juga berkaitan dengan kepribadian individu dimana
kepribadian tertentu akan meningkatkan resiko
penyakit tertentu. Faktor eksternal pada model
ini adalah lingkungan, yang juga dibedakan
menjadi lingkungan biologi (agen, reservoir,
vector, binatang atau tumbuhan), fisik (curah
hujan, kelembaban, atmosfer, bahan kimia, panas,
cahaya, udara, suhu) dan social (politik, budaya,
ekonomi dan psikologi). Model ini biasanya
digunakan untuk menggambarkan enyakit yang
penyebabnya tidak spesifik, seperti penyakit
jantung, stroke, hipertensi, kanker. Dimana
menekankan faktor lingkungan sebagai penyebab
terjadinya penyakit.
3. Riwayat Alamiah Penyakit
Riwayat alamiah penyakit (RAP) merupakan
perjalanan penyakit yang alami dan tanpa
pengobatan apapun, yang terjadi mulai dari
keadaan sehat hingga timbul penyakit.
Pada umumnya secara umum RAP dibagi menjadi 3
tahap, yakni tahap patogenesis, pre-patogenesis
(masa inkubasi, penyakit dini dan penyakit
lanjut), dan tahap pasca patogenesis (penyakit
akhir).
Tahap Pre Patogenesis (Stage of Susceptibility)
Tahap ini telah terjadi interaksi antara
penjamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi
ini terjadi di luar tubuh manusia, dalam arti
bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan
belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini
belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan
daya tahan tubuh penjamu masih kuat dan dapat
menolak penyakit. Keadaan ini disebut sehat.
Tahap inkubasi (Stage Of Presymtomatic Disease)
Pada tahap ini bibit penyakit masuk ke tubuh
penjamu, tetapi gejala-gejala penyakit belum
nampak. Tiap-tiap penyakit mempunyai masa
inkubasi yang berbeda. Masa inkubasi adalah
tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit
ke dalam tubuh yang peka terhadap penyebab
penyakit, sampai timbulnya gejala penyakit.
Tahap penyakit dini (Stage of Clinical Disease)
Tahap ini mulai dihitung dari munculnya gejala-
gejala penyakit, pada tahap ini penjamu sudah
jatuh sakit tetapi masih ringan dan masih bisa
melakukan aktifitas sehari-hari. Bila penyakit
segera diobati, mungkin bisa sembuh, tetapi
jika tidak, bisa bertambah parah. Hal ini
tergantung daya tahan tubuh manusia itu
sendiri, seperti gizi, istirahat dan perawatan
yang baik di rumah (self care).
Tahap penyakit lanjut
Tahap ini penyakit makin bertambah hebat,
penderita tidak dapat beraktivitas sehingga
memerlukan perawatan.
Tahap penyakit akhir
Tahap akhir perjalanan penyakit ini, manusia
berada dalam lima keadaan yaitu sembuh
sempurna, sembuh dengan cacat, karrier, kronis,
atau meninggal dunia.
4. Stimulus Penyakit
Stimulus penyakit adalah interaksi antara inang,
agen penyakit, dan lingkungan yang memicu proses
penyakit
5. Periode Prepatogenesis
Periode saat terjadinya stimulus penyakit sampai
terjadinya respons dari tubuh
6. Periode Pathogenesis
Periode dari mulainya respons sampai proses
berhenti karena sembuh atau mati
7. Periode Inkubasi
Periode waktu dari pemaparan sampai timbulnya
gejala penyakit
8. Periode Induksi
Waktu yang dibutuhkan oleh suatu pemaparan
untuk mencapai dosis yang cukup untuk
menimbulkan reaksi
9. Periode Menular
Periode waktu penderita penyakit dapat
menularkan penyakit
10. Dinamika Penyakit dan Dinamika Penularan
Dinamika penyakit pada umumnya ini berbeda
dengan dinamika penyakit infeksi (penularan).
Dinamika penularan penyakit merupakan suatu proses
transmisi (perpindahan) penyakit dari sumber
(resource) penular atau sering disebut dengan
reservoar ke reservoar lainnya. Dinamika penyakit
pada suatu individu dimulai dari inkubasi,
simptomatis, dan non-diseased (bisa berarti sembuh,
cacat, atau meninggal).
Dinamika penyakit infeksi (penularan) dimulai
dari masa laten, masa infeksi, masa non-infectious.
Masa laten ini berbeda dengan masa laten dalam
dinamika penyakit.
Masa laten pada penularan penyakit infeksi maksudnya
seseorang membutuhkan waktu untuk terinfeksi hingga
menginfeksi orang lain. Jadi, masa laten panjang
maka lebih menguntungkan. Karena jika seseorang
terkena penyakit, maka tidak segera menulari orag
lain.
Contoh: HIV mempunyai masa laten pendek. Jika
terkena HIV, maka dalam satu minggu baru bisa
menginfeksi orang lain.
Masa infeksi yaitu waktu dimana seseorang bisa
menginfeksi orang lain.
Jika masa infeksinya panjang, berarti seseorang
mempunyai waktu panjang juga untuk menginfeksi orang
lain. Artinya, masa infeksi panjang justru tidak
menguntungkan.
Contoh: HIV mempunyai masa infeksi panjang. Jika
seseorang terjangkit HIV sekarang, maka dalam
sepuluh tahun ke depan dia bisa tetap menginfeksi
orang lain.
Masa non-infectious tiap penyakit beda-beda. Masa
ini artinya terdapat gejala klinis tetapi sudah
tidak menginfeksi orang lain.
Contoh: varicella. Ketika gejala klinis varicella
muncul, justru pada saat itu tidak bisa menularkan
ke orang lain.
Terdapat kondisi yang berbeda justru ketika individu
bisa menginfeksi orang lain meskipun dia tidak
menimbulkan gejala klinis (periode jendela).
Contoh varicella justru ketika gejala klinisnya
belum muncul, sudah dapat menularkan virus ke orang
lain.
Masalah masa laten, masa infeksi, dan masa non-
infeksius ini beda-beda untuk setiap penyakit.
Dinamika penyakit bisa disebut sebagai riwayat
penyakit alamiah yang telah dijelaskan pada jawaban
pertanyaan nomor 3.
11. Periode Jendela
Periode subklinis yang tidak terdeteksi namun
mampu menularkan penyakit
12. Periode Klinis
Periode yang ditandai dengan waktu mulai (onset)
timbul gejala penyakit
13. Rantai Infeksi
a) Agen Infeksi
Mikroorganisme yang termasuk dalam agen
infeksi antara lain bakteri,
virus, jamur dan protozoa. Mikroorganisme
dikulit bisa merupakan flora
transient maupun resident. Mikroorganisme
transient normalnya ada dan
jumlahnya stabil, organisme ini bisa hidup
dan berbiak dikulit. Organisme transient
melekat pada kulit saat seseorang kontak dengan
objek atau orang lain dalam aktivitas normal.
Organisme ini siap ditularkan kecuali dengan cuci
tangan. Organisme residen tidak dengan mudah bisa
dihilangkan melalui cuci tangan dengan sabun dan
detergen biasa kecuali bila gosokan dilakukan
dengan seksama. Mikroorganisme dapat
menyebabkan infeksi tergantung pada: jumlah
mikroorganisme, virulensi (kemampuan menyebabkan
penyakit), kemampuan untuk masuk dan bertahan
hidup dalam host serta kerentanan dalam
host/pejamu.
b) Reservoir (sumber mikroorganisme)
Adalah tempat dimana mikroorganisme pathogen
dapat hidup baik
berkembang biak atau tidak. Yang bisa berkembang
sebagai reservoir adalah
manusia, binatang, makanan, air, serangga dan
benda lain. Kebanyakan
reservoir adalah tubuh manusia, terutama
dikulit, mukosa, cairan atau
drainase. Adanya mikroorganisme pathogen dalam
tubuh tidak selalu
menyebabkan penyakit pada hostnya. Sehingga
reservoir yang didalamnya
terdapat mikroorganisme pathogen bisa menyebabkan
orang lain bisa menjadi
sakit (carier). Kuman dapat hidup dan berkembang
biak dalam reservoir jika
karakteristik reservoirnya cocok dengan kuman.
Karakteristik tersebut adalah
air, suhu, ph, udara dan pencahayaan.
c) Portal of exit
Mikroorganisme yang hidup didalam reservoir
harus menemukan jalan
keluar untuk masuk ke dalam host dan
menyebabkan infeksi. Sebelum
menimbulkan infeksi, mikroorganisme harus keluar
terlebih dahulu dari
reservoirnya. Jika reservoirnya manusia, kuman dapat
keluar melalui saluran
pencernaan, pernafasan, perkemihan, genetalia,
kulit, membrane mukosa yang
rusak serta darah.
d) Cara penularan (transmisi)
Kuman dapat berpindah atau menular ke orang
lain dengan berbagai cara seperti kontak
langsung dengan penderita melalui oral, fekal,
kulit atau darahnya. Kontak tidak langsung
melalui jarum atau balutan bekas luka penderita
(Vehicleborne), peralatan yang terkontaminasi
(Vehicleborne), makanan yang diolah tidak tepat
(Vehicleborne), melalui vector nyamuk atau lalat
(vectorborne), dan melalui udara bebas (airbone).
e) Portal masuk
Sebelum seseorang terinfeksi, mikroorganisme
harus masuk dalam tubuh.
Kulit merupakan barier pelindung tubuh terhadap
masuknya kuman infeksius.
Rusaknya kulit atau ketidakutuhan kulit dapat
menjadi portal masuk. Mikroba
dapat masuk kedalam tubuh melalui rute yang
sama dengan portal keluar. Faktor-faktor yang
menurunkan daya tahan tubuh memperbesar
kesempatan pathogen masuk kedalam tubuh.
f) Daya tahan hospes (manusia)
Seseorang terkena infeksi bergantung pada
kerentanan terhadap agen
infeksius. Kerentanan bergantung pada derajat
ketahanan tubuh individu
terhadap pathogen. Meskipun seseorang secara
konstan kontak dengan
mikroorganisme dalam jumlah yang besar, infeksi
tidak akan terjadi sampai
individu rentan terhadap kekuatan dan jumlah
mikroorganisme tersebut.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan tubuh
terhadap kuman yaitu
usia, keturunan, stress (fisik dan emosional),
status nutrisi, terafi medis,
pemberian obat dan penyakit penyerta
14. Pencegahan Primordial ,Primer, Sekunder, dan Tersier
(didasarkan pada fase penyakit dan target)
Pencegahan Primordial
Fase Penyakit :
Misalnya kondisi yang mengarah penyebab
penyakit jantung koroner
Target :
Populasi
Kelompok terseleksi
Pencegahan Primer
Fase Penyakit :
Faktor-faktor penyebab khusus
Target :
Total populasi
Kelompok terseleksi
Individu sehat
Pencegahan Sekunder
Fase Penyakit :
Tahap dini penyakit
Target :
Pasien
Pencegahan Tersier
Fase Penyakit :
Penyakit tahap lanjut (pengibatan dan
rehabilitasi)
Terget :
Pasien
Daftar Pustaka
Budiarto,E & Anggraeni, D. 2001. Pengantar epidemiologiedisi 2.
Jakarta: EGCBudiarto. 1987. Penuntun Epidemiologi. Bandung : Alumni.
Budioro B. 1997. Pengantar Epidemiologi.
Semarang : Universitas Diponegoro.
Budioro B. 2001. Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC
Chandra, Budiman. 2006. Ilmu Kedokteran Pencegahan danKomunitas.
Jakarta: EGC.Heru Subaris K dkk. 2006. Manajemen Epidemiologi.
Yogyakarta: Media PressindoJuwono, Sugeng. Riwayat Alamiah, Spektrum, RantaiInfeksi dan Kejadian
Epidemik Penyakit. 2011M. N. Bustan. 1997. Pengantar epidemiologi. Jakarta :
Rineka Cipta.
Rajab, Wahyudin. 2008. Buku Ajar Epidemologi UntukMahasiswa
Kebidanan. Semarang: Universitas DiponegoroSaraswati, Lintang Dian. 2014. Riwayat AlamiahPenyakit. Bagian
Epidemiologi Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas DiponegoroTimmreck, Thomas c. 2001. Epidemiologi Suatu Pengantar.
Jakarta: EGC
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/3keperawatanpdf/0910712026/bab2.pdf