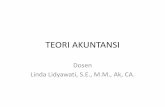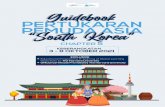Gagasan Inti & Kritik Teori-teori Sosiologi: Fungsionalisme-Struktural, Interaksi-Simbolik dan...
Transcript of Gagasan Inti & Kritik Teori-teori Sosiologi: Fungsionalisme-Struktural, Interaksi-Simbolik dan...
GAGASAN INTI DAN KRITIK DARI TEORI-TEORI: FUNGSIONALISME-
STRUKTURAL, INTERAKSI-SIMBOLIK, DAN PERTUKARAN SOSIAL
Disusun untuk memenuhi tugas Sejarah Pemikiran Sosiologi II
Reyhan Aznar
13/347808/SP/25685
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2
A. TEORI FUNGSIONALISME-STRUKTURAL
A.1. Gagasan Inti
Tokoh sentral teori ini bernama Talcott Parsons. Teori ini dikemukakan pula oleh para
sosiolog lainnya seperti Robert K. Merton (murid Talcott Parsons), Kingsley Davis dan
Moore. Teori yang muncul pada tahun 1940-an ini mempunyai gagasan bahwa masyarakat
dianggap sebagai sebuah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai sub sistem dan mereka
saling berhubungan, ketergantungan, dan kerjasama satu sama lain demi terciptanya suatu
keseimbangan dan kebutuhannya terpenuhi serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang
berlaku yang telah disepakati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan sosial.
Masyarakat cenderung menuju kepada suatu keadaan seimbang atau equilibrium. Bila terjadi
perubahan dalam sistem tersebut, maka akan terjadi keguncangan dan dapat mengganggu
keseimbangan tapi itu berlangsung sementara saja dan selanjutnya akan muncul
keseimbangan baru. Banyak aliran teori struktural fungsional dari para ahli Sosiologi dan
berikut sedikit dipaparkan:
A.1.I. Talcott Parsons dan AGIL
Parsons mengemukakan persyaratan mutlak dalam seluruh sistem, yaitu empat
imperatif fungsional bagi sistem tindakan dengan skema AGIL-nya yang terkenal: Adaptasi
[A (Adaptation)], pencapaian tujuan [G (Goal Attainment)], integrasi [I (Integration)], dan
pemeliharaan pola [L (Latency)]. Agar dapat bertahan hidup, sistem harus menjalankan
keempat fungsi ini:
1. Adaptasi: Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia
harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan kebutuhan-
kebutuhannya jika mereka ingin bertahan hidup.
2. Pencapaian tujuan: Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan
utamanya.
3. Integrasi: Sistem harus mengoordinasi antar bagian yang menjadi komponennya.
Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A, G,
L).
4. Pemeliharaan pola: Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui
motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan
motivasi tersebut. Struktur-struktur menyediakan perawatan dan merevitalisasi
motivasi individu untuk menunjukkan peran mereka berdasarkan harapan sosial.
3
Parsons membuat skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem
teoretisnya. Cara Parsons menggunakan AGIL adalah:
Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi
dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar dan juga merupakan sumber energi bagi
seluruh sistem untuk adaptasi dan transfomasi dari sistem dalam hubungan ke lingkungannya.
Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan
sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Komponen dasar
kepribadian adalah “kebutuhan-disposisi”, merupakan dorongan yang terbentuk dalam setting
sosial. Kebutuhan-disposisi memaksa aktor menerima atau menolak objek yang ada di dalam
lingkungan atau berupaya menemukan objek-objek baru jika objek yang ada tidak cukup
memenuhi kebutuhan-disposisi. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol
bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia menempatkan kompleks status-peran sebagai
suatu unit terdasar dari sistem yang merupakan komponen struktural sistem sosial. Status
merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan
aktor dalam suatu posisi. Akhirnya, sub kebudayaan menjalankan fungsi latensi dengan
membekali norma dan nilai-nilai yang memotivasi kepada aktor untuk bertindak.
Kebudayaan sebagai kekuatan utama mengikat berbagai elemen dunia sosial, dalam hal ini,
sistem tindakan.
L I
A G
Struktur Sistem Tindakan Umum
A.1.II. Robert Merton dan Tiga Postulat Dasar Fungsional
Robert K. Merton terkenal dengan tiga postulat dasar analisis fungsional. Yang
pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini menyatakan bahwa
seluruh kepercayaan dan praktik sosial budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat
secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat.
Sistem Kultural Sistem Sosial
Organisme Behavioral Sistem Kepribadian
4
Postulat kedua adalah postulat fungsionalisme universal. Semua bentuk dan struktur
sosial kultural memiliki fungsi positif. Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan
apa yang kita temukan di dunia nyata. Tidak setiap struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan,
dan lain sebagainya memiliki fungsi positif.
Yang ketiga adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa seluruh
aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif namun juga merepresentasikan
bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada gagasan bahwa
seluruh struktur dan fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat.
Dari sudut pandang tersebut, Merton menjelaskan bahwa analisis struktural-
fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan.
Ia menyatakan bahwa objek apa pun yang dapat dianlisis secara struktural-fungsional harus
“merepresentasikan unsur-unsur standar (yaitu yang terpola dan berulang).” (Merton,
1949/1968: 104).
Untuk memperbaiki kelemahan serius pada fungsionalisme struktural awal ini,
Merton mengembangkan gagasan tentang disfungsi. Ketika struktur atau institusi dapat
memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial, mereka pun dapat
mengandung konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut.
Merton juga mengembangkan gagasan tentang nonfungsi, yang ia definisikan sebagai
konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bentuk-
bentuk sosial yang “masih bertahan” sejak masa awal sejarah. Meskipun bentuk-bentuk
tersebut mungkin mengandung konsekuensi negatif atau positif di masa lalu, tidak ada efek
signifikan yang mereka berikan pada masyarakat sekarang.
A.2. Kritik
Teori fungsionalis-Struktural mempunyai banyak kelemahan. Pertama, penganut teori
ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil
sehingga bisa berjalan dengan baik. Padahal, dalam suatu masyarakat pasti pernah mengalami
kejadian yang berkontradiksi dan akhirnya memicu konflik. Dalam konflik ini, masyarakat
menjadi terpecah dan akan menimbulkan guncangan dalam sistem. Bisa saja sistem yang
dulu terbentuk akhirnya hilang sama sekali. Fungsionalis yang berlebihan pada keharmonisan
mengabaikan peristiwa di mana konflik merupakan keniscayaan dari kebanyakan masyarakat.
Kedua, teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan terutama yang berasal dari luar.
Teori ini hanya berfokus pada segala sesuatu yang bersifat stabil saja. Padahal, kehidupan
5
dan masyarakat itu sendiri berjalan dinamis di mana pasti memerlukan suatu perubahan yang
akan membawa ke arah positif atau negatif.
Ketiga, dengan terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial,
fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif dalam mengkaji kehidupan sosial;
yakni mereka cenderung perlunya mempertahankan segala pengaturan yang ada dalam
sebuah masyarakat. Mereka menerima perubahan sebagai sesuatu yang konstan dan tidak
memerlukan ‘penjelasan’. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat.
Perubahan yang bermanfaat bagi sistem diterima dan perubahan lain yang tidak berguna
ditolak mentah-mentah.
6
B. TEORI INTERAKSI SIMBOLIK
B.1. Gagasan Inti
Interaksi simbolik merupakan salah satu teori yang penting dalam pemahaman
interpretatif. Gagasan perspektif ini adalah kenyataan sosial muncul melalui proses interaksi
dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan dan memanipulasi
simbol-simbol. Interaksi simbolik memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka
mengenai definisi situasi (the definition of situation) bersamaan mengenai arti-arti bersama.
Teori yang sudah masuk ke dalam teori sosiologi modern ini dikemukakan oleh George
Herbert Mead mengenai perbuatan dan diri serta Erving Goffman tentang dramaturginya
yang terkenal.
B.1.I. George H. Mead: Perbuatan dan Diri
Mead memandang perbuatan sebagai “unit paling inti” dalam teorinya (1982:27).
Dalam menganalisis perbuatan, Mead memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons.
Mead mengidentifikai empat tahap dasar yang terkait satu sama lain dalam setiap perbuatan.
Impuls, melibatkan stimulus individu langsung dan reaksi aktor terhadap stimulasi tersebut
untuk berbuat sesuatu serta lingkungan sekitar aktor. Contohnya adalah rasa lapar. Aktor
dapat merespons secara langsung dan tanpa perlu berpikir terhadap impuls namun aktor
cenderung berpikir tentang respons yang sesuai (misal, makan sekarang atau nanti). Dalam
memikirkan respons tersebut, aktor tidak hanya mempertimbangkan situasi sekarang, namun
juga pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap akibat-akibat dari perbuatan tersebut di
masa depan.
Rasa lapar bisa datang dari kondisi batin aktor atau kehadiran makanan di dalam
lingkungan. Orang yang lapar harus menemukan cara untuk memuaskan impuls dalam
lingkungan tempat makanan tidak dapat langsung tersedia ataupun tidak dalam jumlah cukup.
Impuls bisa terkait dengan masalah di dalam lingkungan (yaitu makanan yang tidak langsung
tersedia) yang harus diatasi oleh aktor. Walaupun rasa lapar bisa datang dari individu namun
biasanya terkait dengan keberadaan masalah di dalam lingkungan (misalnya, kurangnya
bahan makanan).
Persepsi. Aktor mencari dan bereaksi terhadap stimulus yang terkait dengan impuls,
dalam hal ini adalah rasa lapar dan berbagai cara yang ada untuk memuaskannya. Orang
memiliki kemampuan mengindra stimulus melalui penciuman, perasa, dan lain sebagainya.
Persepsi melibatkan stimulus yang datang, maupun citra mental yang mereka ciptakan. Orang
7
tidak sekedar merespons secara langsung stimulus eksternal, namun berpikir melalui
bayangan secara mental (mental imagery). Biasanya orang berhadapan dengan beragam
stimulus berbeda, dan mereka memiliki kemampuan untuk memilih mana yang akan diambil
dan mana yang akan diabaikan.
Manipulasi. Begitu impuls mewujudkan dirinya dan objek telah dipersepsi, tahap
selanjutnya adalah manipulasi objek atau mengambil tindakan dalam kaitannya dengan objek
tersebut. Selain keunggulan mentalnya, orang memiliki keunggulan lain di atas binatang yang
lebih rendah. Orang memiliki tangan yang memungkinkan melakukan manipulasi terhadap
objek jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh binatang-binatang yang lebih
rendah. Manusia yang lapar melihat jamur, namun sebelum memakannya, ia cenderung
memetik dulu, mencicipinya, dan mungkin mengeceknya di buku panduan untuk mengetahui
apakah jamur tersebut dapat dimakan atau tidak. Sebaliknya, binatang yang lebih rendah,
cenderung memakan jamur tersebut tanpa menimbang-nimbang dan mencicipinya. Jeda yang
diperoleh dari menimbang-nimbang objek objek tersebut memungkinkan manusia
merenungkan berbagai respons. Ketika berpikir apakah akan memakan jamur tersebut atau
tidak, masa lalu dan masa depan dilibatkan. Orang dapat berpikir tentang pengalaman di
masa lalu, yaitu ketika mereka makan jamur kemudian jatuh sakit, dan mungkin mereka
berpikir tentang sakit yang mungkin muncul di masa-masa yang akan datanf atau bahkan
kematian. Manipulasi jamur menjadi semacam metode eksperimental di mana aktor mencoba
berpikir dengan cara menguji beberapa hipotesis tentang apa yang akan terjadi jika jamur itu
dikonsumsi.
Konsumasi. Merupakan pengambilan tindakan yang akan memuaskan impuls awal.
Berdasarkan pertimbangan sadar ini, aktor dapat memutuskan untuk makan jamur (atau tidak)
Manusia dan binatang cenderung tidak memakan jamur yang buruk karena kemampuannya
memanipulasi jamur dan berpikir (serta membaca) dampak dari makan jamur tersebut.
Binatang pasti melakukan coba-coba, namun ini adalah metode yang tidak efisien
dibandingkan kemampuan manusia berpikir melalui tindakan-tindakan mereka. Dalam situasi
ini, coba-coba adalah cara berbahaya dan binatang lebih rentan terhadap kematian karena
makan jamur beracun ketimbang manusia.
Mead juga mengemukakan konsep diri yang terkenal. Diri adalah kemampuan
seseorang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek. Diri tumbuh melalui perkembangan serta
melalui aktivitas dan relasi sosial. Bagi Mead, mustahil diri bisa lahir di tempat yang tidak
tersedia pengalaman sosial. Namun, bila diri sudah berkembang, dia bisa bertahan tanpa
adanya kontak sosial. Mekanisme perkembangan diri adalah refleksivitas (kemampuan untuk
8
meletakkan diri kita secara bawah sadar di tempat orang lain serta bertindak sebagaimana
mereka bertindak). Akibatnya, orang mampu mengkaji dirinya sendiri sebagaimana orang
lain mengkaji dia. Diri juga membiarkan orang mengambil bagian dalam percakapan mereka
dengan orang lain. Jadi, orang sadar akan apa yang dikatakan orang lain dan mampu
memantau apa yang tengah dikatakan dan menentukan apa yang akan dikatakan selanjutnya.
Agar memiliki diri, individu harus mampu “berada di luar dirinya” sehingga mereka
dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, dan menjadikannya sebagai objek bagi diri mereka
sendiri. Caranya, orang meletakkan dirinya pada arena pengalaman yang sama sebagimana
mereka meletakkan orang lain. Setiap orang adalah bagian dari situasi tersebut dan orang
harus mempertimbangkan apakah mereka mampu bertindak secara rasional pada situasi
tertentu. Setelah dilakukan, mereka berusaha mengkaji dirinya secara objektif, dan tanpa
emosi. Namun, orang tidak dapat mengalami dirinya secara langsung. Mereka hanya dapat
melakukannya secara tidak langsung dengan meletakkan diri mereka pada posisi orang lain
dan melihat diri mereka dari sudut pandang tersebut. Sudut pandang orang dalam melihat
dirinya bisa dari perspektif individu atau kelompok sosial secara keseluruhan.
Mead melacak asal usul diri melalui dua tahap dalam perkembangan masa kanak-
kanak.
1. Tahap Bermain (Play Stage). Pada tahap ini, anak-anak belajar memikirkan sikap
orang lain terhadap dirinya. Hasilnya adalah anak belajar menjadi subjek
sekaligus objek dan mulai mampu membangun diri. Namun, ini adalah diri yang
terbatas karena anak hanya dapat memainkan peran orang lain yang jelas. Ana-
anak bisa saja memainkan peran sebagai “mama” dan “papa” dan dalam proses ini
mereka mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri
sebagaimana orang tua mereka dan orang lain. Namun, mereka tidak memiliki
pemahaman-diri yang lebih umum dan tertata dan tidak memiliki kepribadian
kokoh.
2. Tahap Permainan (Game Stage) diperlukan jika seseorang ingin mengembangkan
diri secara utuh. Dalam tahap permainan, anak harus mengambil peran orang lain
yang terlibat di dalam permainan tersebut. Peran-peran berbeda ini harus memiliki
hubungan pasti satu sama lain. Pada tahap permainan, mulai muncul pemahaman-
diri yang tertata dan kepribadian yang kokoh mulai muncul. Anak-anak mulai
mampu berfungsi dalam kelompok terorganisasi dan mampu menemukan apa
yang akan mereka lakukan dalam kelompok yang spesifik.
9
3. Orang lain pada umumnya (Generalized Others) adalah sikap seluruh komunitas,
Kemampuan untuk memikirkan peran orang lain pada umumnya sangat mendasar
bagi diri: “baru ketika seseorang memasang sikap sebagaimana yang ada dalam
kelompok sosial tempat ia berada guna menyikapi aktivitas sosial yang
terorganisasi secara kooperatif atau serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh
kelompok tersebut, barulah ia berkembang menjadi diri seutuhnya “ (Mead,
1934/1962: 155)
“I” dan “Me” merupakan konsep Mead yang juga mempunyai arti penting dalam
interaksi-simbolik. “I” adalah respons langsung individu terhadap individu yang lain. Dia
tidak dapat dikalkulasi dan merupakan aspek kreatif diri. Orang tidak tahu dengan baik
tindakan yang akan dilakukan “I”: “Baik dirinya maupun orang lain sama-sama tidak
mengetahui apa respons yang akan diberikan. Dia bisa memberikan respons tepat maupun
keliru. Orang-orang tidak pernah sepenuhnya menyadari “I”, dan melaluinya mereka
mengejutkan diri dengan tindakan aktor sendiri. Orang-orang baru mengenal “I” setelah ada
tindakan yang dilakukan. Jadi, orang-orang hanya mengenal “I” di dalam ingatan. Mead lebih
menekankan “I” karena empat alasan. Pertama, “I” adalah sumber utama kebaruan dalam
proses sosial. Kedua, Mead percaya bahwa di dalam “”I”-lah nilai terpenting kita berada.
Ketiga, “I” membentuk hal yang dicari-cari setiap manusia – realisasi diri. “I’”
memungkinkan individu mengembangkan “kepribadian yang ajeg”. Akhirnya Mead melihat
proses evolusi dalam sejarah di mana orang yang berada di dalam masyarakat primitif lebih
didominasi oleh “me” sementara pada masyarakat modern terdapat komponen yang leih
besar.
“Me” adalah pengadopsian orang lain pada umumnya. Berbeda dengan “I”, orang
sadar akan “me”; “me” melibatkan tanggung jawab secara sadar. Mead juga melihat “I” dan
“me” secara pragmatis. Me memungkinkan individu hidup nyaman dengan dunia sosial,
sementara “I” membuka kemungkinan bagi perubahan dalam masyarakat. “I” dan “me”
adalah bagian dari seluruh proses sosial yang memungkinkan individu dan masyarakat
berfungsi lebih efektif.
B.1.II. Teori Interaksi Simbolik Erving Goffman
Karya penting yang membahas diri adalah buku Presentation of Self in Everyday Life
(1959) yang ditulis oleh Erving Goffman. Konsep Goffman tentang diri banyak meminjam
gagasan Mead, khususnya tentang ketegangan antara “I”, diri yang spontan dengan “me”,
10
hambatan sosial di dalam diri. Untuk menjaga citra-diri yang stabil, orang tampil untuk
audien sosial mereka. Akibat dari minatnya pada pertunjukan ini, Goffman memusatkan
perhatiannya pada dramaturgi, atau pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serangkaian
pertunjukan dramatis yang serupa dengan yang ditampilkan di atas panggung.
Goffman memahami diri bukan sebagai milik aktor namun sebagai produk interaksi
dramatis antara aktor dengan audien. Diri “adalah efek dramatis yang muncul . . . dari
skenario yang ditampilkan” (Goffman, 1959: 253). “Karena diri adalah produk interaksi
dramatis, ia rentan mengalami gangguan selama pertunjukan” (Misztal, 2001). Goffman
menunjukkan bahwa kebanyakan pertunjukan sukses dilakukan dan hasilnya adalah bahwa
dalam situasi biasa, diri yang utuh ditentukan oleh pementas, dan diri “terlihat” memancar
dari pementas.
Goffman berpendapat bahwa ketika individu berinteraksi, mereka ingin memberikan
pemahaman tertentu tentang diri yang akan diterima oleh orang lain. Namun, bahkan ketika
menampilkan diri mereka, para aktor sadar bahwa audien dapat mengganggu pertunjukan
mereka. Oleh karena itu aktor menyesuaikan diri dengan kontrol audien dengan harapan agar
pemahaman tentang diri yang mereka sajikan di hadapan audien akan cukup kuat bagi audien
untuk mendefinisikan aktor sesuai yang dikehendaki sang aktor. Aktor pun berharap ini akan
menyebabkan audien bertindak sukarela sebagaimana yang dikehendaki sang aktor. Goffman
menyebut ini sebagai “manajemen kesan”. Manajemen kesan diarahkan untuk melindungi
diri dari tindakan-tindakan yang tidak terduga, seperti gerak yang tidak sengaja dilakukan,
tindakan memalukan, maupun tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan, seperti membuat
skenario.
Mengikuti analogi teatrikal ini, Goffman berbicara tentang panggung depan. Depan
adalah bagian dari pertunjukan yang secara umum berfungsi untuk mendefinisikan situasi
bagi mereka yang memerhatikan pertunjukan tersebut. Di panggung depan, Goffman
membedakan antara setting dengan muka personal. Setting berupa tampilan fisik yang
biasanya harus ada jika aktor tampil. Tanpa itu, aktor biasanya tidak dapat tampil. Sebagai
contoh, ahli bedah biasanya memerlukan ruang operasi. Muka personal terdiri dari berbagai
perlengkapan ekspresi yang diidentikkan audien dengan pementas dan diharapakan agar
dibawa serta dalam setting tersebut. Contohnya ahli bedah akan memakai pakaian dokter.
Goffman membagi lagi muka personal menjadi tampilan dan tingkah laku. Tampilan
berupa pernik-pernik yang mengatakan kepada kita status sosial pementas (misal baju dokter
bedah). Tingkah laku mengatakan kepada audien peran yang diharapkan untuk dimainkan
pementas dalam situasi tersebut (misal penggunaan gerak fisik dan sikap).
11
Pandangan menarik Goffman ada pada ranah interaksinya. Ia berargumen bahwa
karena orang mencoba menyajikan gambaran ideal atas dirinya sendiri dalam panggung
depan, mereka merasa harus menyembunyikan berbagai hal dalam pertunjukan yang mereka
lakukan. Pertama, aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangan rahasia (misal minum
alkohol) yang telah jadi kebiasaan sejak sebelum pertunjukan atau di masa lalu (misal
kecanduan narkoba) yang tidak cocok dengan pertunjukan mereka. Kedua, aktor mungkin
ingin menyembunyikan kekeliruan yang mereka lakukan dalam persiapan pertunjukan
maupun langkah yang telah mereka ambil untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut.
Ketiga, aktor mungkin menganggap hanya perlu menunjukkan produk akhir dan
menyembunyikan proses produksinya. Keempat, pada pertunjukan tertentu, aktor mungkin
harus membiarkan turunnya standar-standar lain. Akhirnya, mungkin aktor menganggap
perlu menyembunyikan cercaan, hinaan, atau perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa agar
pertunjukan terus berlangsung, Pada umumnya, aktor berkepentingan untuk
menyembunyikan fakta-fakta tersebut dari audien mereka.
Unit analisis dasar Goffman bukanlah individu, namun tim. Tim adalah sekumpulan
individu yang bekerja sama dalam mementaskan satu rutinitas yang sama. Setiap anggota
bergantung pada anggota yang lain, karena semuanya dapat mengganggu pertunjukan dan
semua sadar bahwa mereka tengah berakting. Goffman menyimpulkan bahwa tim adalah
semacam “masyarakat rahasia”.
Goffman juga mendiskusikan panggung belakang. Belakang adalah tempat fakta yang
tertekan di panggung depan atau di berbagai tindakan informal dapat terlihat. Pementas
sepenuhnya berharap agar tidak ada anggota audien mereka yang hadir di belakang
panggung. Lebih jauh, mereka terlibat dalam berbagai macam manajemen kesan untuk
memastikannya. Pertunjukan cenderung sulit dilakukan ketika aktor tidak mampu mencegah
audien masuk ke panggung belakang. Juga terdapat wilayah ketiga, wilayah sisa, yaitu sisi
luar, yang bukan depan atau belakang.
Tidak ada wilayah yang selalu berada di salah satu ketiga ranah tersebut. Namun,
wilayah tertentu dapat mencakup ketiga ranah pada waktu yang berlainan. Kantor profesor
adalah panggung depan ketika mahasiswa berkunjung, dan menjadi panggung belakang
ketika mahasiswa pergi, dan sisi luar ketika perofesor tersebut tengah berada pada
pertandingan basket di universitas.
Goffman tertarik pada sejauh mana individu memainkan peran tertentu. Menurut
pandangannya, karena banyaknya peran, tidak banyak orang yang terlibat sepenuhnya dengan
peran tertentu. Jarak peran membicarakan sejauh mana individu memisahkan dirinya dari
12
peran yang mereka mainkan dan juga merupakan fungsi dari status sosial seseorang. Orang-
orang pada status sosial yang tinggi sering kali mewujudkan jarak peran dengan alasan
berbeda dengan orang-orang yang berada pada posisi status rendah. Contoh, tingginya status
ahli bedah dapat mewujudkan jarak peran dalam ruang operasi untuk meredakan ketegangan
antar anggota tim operasi. Orang-orang yang berada pada posisi status rendah biasanya
memasang sikap yang lebih defensif dalam memamerkan jarak peran.
B.2. Kritik
Interaksi-Simbolik mempunyai kelemahan-kelemahan. Pertama, interaksionis terlalu
memperhatikan pada kehidupan sehari-hari dan pembentukan sosial dari diri, namun mereka
hampir (atau bahkan) mengabaikan struktur sosial sama sekali. Padahal, struktur sosial
mempunyai arti penting bagi hadirnya individu yang ada beserta tim. Kedua, interaksi
simbolik mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan, motif, dan niat.
Interaksionis malah hanya memusatkan pada simbol, tindakan, dan interaksi semata sehingga
tidak bisa terlalu mendalam perhatian para penganut ini terhadap segala tindakan yang
dilakukan oleh aktor.
Ketiga, teori ini hanya memfokuskan pada kehidupan manusia sehari-hari tanpa
melihat hal-hal yang membuat atau melatarbelakangi suatu tindakan itu terjadi dan akhirnya
dilakukan.
13
C. TEORI PERTUKARAN SOSIAL
C.1. Gagasan Inti
Teori pertukaran sosial, di mana akarnya berupa behaviorisme yang lebih dikenal
dalam ilmu psikologi, muncul pada tahun 1960-an sebagai teori sosial untuk menantang teori
fungsionalisme. Para ahli yang memfokuskan pada pandangan ini di antaranya George
Homans dan Peter Blau. Mereka mencurahkan perhatian pada hubungan antara efek perilaku
aktor pada lingkungan dan dampaknya pada perilaku aktor selanjutnya. Mereka juga melihat
bahwa individu akan bertindak untuk mendapat imbalan dan menghindari hukuman. Ketika
tindakan mereka dihargai, individu akan mengulanginya dalam situasi yang sama. Namun,
bila tindakan mereka menimbulkan reaksi negatif maka mereka tidak akan mengulanginya.
Ini mendorong kepada pandangan dari tingkah laku manusia dengan istilah biaya dan manfaat
dan indvidu rasional yang dapat menghitung konsekuensi dari aksi mereka sebelum
mengambilnya.
C.1.I Teori Pertukaran George Homans
Menurut Homans, teori ini “memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas,
termilai ataupun tidak, dan kurang lebih menguntungkan atau mahal, bagi sekurang-
kurangnya dua orang” (1961: 13). Homans mencontohkan perkembangan mesin berbahan
bakar dalam industri tekstil, dan selanjutnya Revolusi Industri, melalui prinsip-prinsip
psikologi bahwa orang cenderung bertindak sedemikian rupa untuk meningkatkan imbalan
mereka. Dalam teori ini, ia berusaha menjelaskan perilaku sosial dasar berdasarkan imbalan
dan biaya.
Dalam karya teoretisnya, Homans membatasi dirinya pada interaksi sosial sehari-hari.
Berikut adalah contoh yang digunakan Homans untuk memaparkan jenis hubungan
pertukaran yang menarik perhatiannya:
Bayangkanlah bila ada dua orang melakukan kerja administrasi di suatu
kantor. Menurut aturan kantor, setiap orang harus melakukan kerjanya
sendiri, jika perlu bantuan, ia harus mengonsultasikannya dengan penyelia.
Salah seorang dari mereka, sebut saja si Anu, tidak begitu terampil
mengerjakan tugasnya dan mungkin akan bekerja lebih baik dan lebih cepat
jika ia terus dibantu. Terlepas dari itu semua ia enggan berbicara dengan
penyekia, karena mengakui ketidakmampuannya bisa jadi akan
membahayakan peluangnya untuk promosi. Justru ia menemui orang lain,
14
yang akan kita sebut dengan si Lain, dan meminta bantuan darinya. Si Lain
lebih berpengalaman bekerja daripada si Anu; ia dapat melakukan kerjanya
dengan baik dan cepat dan tidak meluangkan waktu sedikit pun, dan ia
punya alasan untuk berandai-andai bahwa penyelia tidak akan menuju ke
tempatnya untuk mencari-cari pelanggaran aturan. Si Lain membantu si
Anu dan sebagai imbalannya si Anu mengucapkan terima kasih dan memuji
si Lain. Kedua orang tersebut bertukar bantuan dan pujian.
(Homans, 1961: 31-32)
Memusatkan perhatiannya pada situasi semacam ini, Homans mengembangkan
beberapa proposisi.
Proposisi Sukses
Jika makin sering tindakan apa pun yang dilakukan orang memperoleh
imbalan, makin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan
tersebut.
(Homans, 1974: 16)
Menurut contoh si Anu-si Lain dalam situasi kerja di kantor, proposisi ini berarti bahwa
orang lebih cenderung meminta nasihat orang lain jika di masa lalu ia diberi imbalan berupa
nasihat berguna. Selain itu, semakin sering seseorang menerima nasihat berguna di masa lalu,
semakin sering ia akan meminta nasihat. Serupa dengan itu, orang lain akan lebih berniat
memberi nasihat dan memberikannya lebih sering lagi jika di masa sebelumnya ia sering
diberi imbalan pujian.
Homans mencatat beberapa hal terkait dengan proposisi ini. Pertama, meskipun
imbalan yang sering dilakukan akan mendorong peningkatan frekuensi tindakan, situasi
timbal balik ini tidak mungkin berlangsung tanpa batas. Kadang individu sama sekali tidak
dapat berbuat seperti itu. Kedua, semakin pendek interval antara perilaku dan imbalan,
semakin besar kecenderungan seseorang mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, lamanya
interval antara perilaku dan imbalan memperkecil kecenderungan mengulang perilaku
tersebut. Ketiga, imbalan secara tidak teratur cenderung menyebabkan berulangnya perilaku
ketimbang imbalan teratur. Imbalan yang diberikan secara teratur mengakibatkan rasa bosan
dan muak, sementara imbalan pada interval tidak teratur (sebagaimana dalam perjudian)
cenderung menimbulkan berulangnya perilaku.
15
Proposisi Stimulus
Jika di masa lalu terjadinya stimulus tertentu, atau serangkaian stimulus,
adalah situasi di mana tindakan seseorang diberikan imbalan, maka
semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu itu, semakin
besar kecenderungan orang tersebut mengulangi tindakan yang sama, atau
yang serupa.
(Homans, 1974: 23)
Jika di masa lalu, si Anu dan si Lalu menganggap memberi dan menerima nasihat adalah
sesuatu yang menyenangkan, mereka cenderung melakukan tindakan sama dalam situasi
yang sama di masa yang akan datang. Homans tertarik pada proses generalisasi, yaitu
kecenderungan untuk memperbanyak perilaku pada situasi serupa. Jika stimulus krusial
terjadi terlalu lama sebelum perilaku dijalankan, stimulus itu tidak benar-benar merangsang
perilaku tersebut. Bisa jadi seorang aktor menjadi terlalu sensitif terhadap rangsangan,
khususnya jika itu semua sangat bernilai bagi mereka. Sebaliknya, aktor dapat merespons
rangsangan2 yang tidak relevan, paling tidak sampai situasinya dibenahi oleh kegagalan-
kegagalan berulang. Semua itu dipengaruhi oleh kewaspadaan individu atau perhatian mereka
terhadap rangsangan.
Proposisi Nilai
Semakin bernilai hasil tindakan bagi seseorang, semakin cenderung ia
melakukan tindakan serupa.
(Homans, 1974: 25)
Jika imbalan yang ditawarkan satu sama lain dianggap bernilai, aktor lebih cenderung
menjalankan perilaku yang diinginkan daripada perilaku yang imbalannya tidak bernilai. Di
sini, Homans mengenalkan imbalan dan hukuman. Imbalan adalah tindakan yang bernilai
posisif; meningkatnya imbalan lebih cenderung melahirkan perilaku yang diinginkan.
Hukuman adalah tindakan yang bernilai negatif; meningkatnya hukuman berarti aktor
cenderung menampilkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ia menganggap hukuman
sebagai cara yang tidak memadai untuk menggiring orang mengubah perilaku mereka, karena
orang bisa bereaksi terhadap hukuman dengan cara yang tidak diinginkan. Lebih disukai jika
kita tidak memberi imbalan bagi perilaku yang tidak diinginkan; pada akhirnya perilaku
tersebut akan hilang. Imbalan jelas lebih dipilih, namun mungkin saja persediaanya terbatas.
Ia menjelaskan bahwa teorinya bukanlah teori hedonis,; imbalan bisa bersifat materialistis
(misalnya, uang) atau altruistik (membantu orang lain).
16
Proposisi Kelebihan-kekurangan
Jika menjelang saat tertentu, orang makin sering menerima imbalan
tertentu, maka makin kurang bernilai imbalan yang selanjutnya diberikan
kepadanya.
(Homans, 1974: 29)
Di kantor si Anu dan si Lain mungkin saling memberi imbalan begitu seringnya karena telah
memberi dan menerima nasihat, sehingga imbalan mulai tidak bernilai baginya. Dalam hal ini
waktu adalah sesuatu yang krusial; orang cenderung kurang puas jika imbalan-imbalan
tertentu diterima setelah berselang begitu lama.
Dalam hal ini, Homans mendefinisikan 2 konsep lainnya: ongkos dan keuntungan. Ongkos
perilaku didefinisikan sebagai imbalan yang hilang dalam alur tindakan alternatif yang
tengah berlangsung. Keuntungan dalam pertukaran sosial dipandang sebagai jumlah imbalan
yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
Proposisi Agresi-pujian
Proposisi A: Ketika tindakan seseorang tidak mendapatkan imbalan yang
diharapkan, atau menerima hukuman yang tidak ia harapakan, ia akan
marah; ia menjadi cenderung berperilaku agresif ,dan akibat perilaku
tersebut menjadi lebih bernilai untuknya.
(Homans, 1974: 37)
Pada kasus di atas, jika si Anu tidak memperoleh nasihat yang ia harpkan dan si Lain tidak
mendapatkan pujian yang diharapkannya, keduanya cenderung marah. Proposisi A tentang
agresi-pujian hanya merujuk pada emosi negatif, sementara proposisi B lebih banyak
berbicara tentang emosi positif:
Proposisi B: ketika tindakan seseorang menerima imbalan yang
diharapkannya, khususnya imbalan yang lebih besar dari yang
diharapkannyam atau tidak mendapatkan hukuman yang diharapkannya, ia
akan senang; ia lebih cenderung berperilaku menyenangkan, dan hasil dari
tindakan ini lebih bernilai baginya.
(Homans, 1974: 39)
Contoh di kantor, ketika si Anu mendapat nasihat yang diharapkannya dan si Lain
memperoleh pujian yang diharapkannya, keduanya senang dan cenderung memberi dan
menerima. Nasihat dan pujian lebih berharga bagi keduanya.
17
Proporsi Rasionalitas
Ketika memilih tindakan alternatif, seseorang akan memilih tindakan,
sebagaimana dipersepsikannya kala itu, yang jika nilai hasilnya (V)
dikalikan probabilitas keberhasilan (p) adalah lebih besar.
(Homans, 1974: 43)
Proposisi ini menunjukkan pengaruh teori pilihan rasional pendekatan Homans. Dalam
bahasa ekonomi, aktor yang bertindak menurut proposisi rasionalitas tentang memaksimalkan
keuntungannya.
Pada dasarnya, orang mempelajari dan melakukan kalkulasi atas berbagai tindakan
alternatif yang tersedia baginya. Mereka membandingkan jumlah imbalan yang dihubungkan
dengan setiap tindakan. Mereka pun mengalkulasikan kecenderungan bahwa mereka benar-
benar akan menerima imbalan. Imbalan yang bernilai tinggi akan hilang nilainya jika aktor
menganggap bahwa itu semua cenderung tidak akan mereka peroleh. Sebaliknya, imbalan
yang bernilai lebih rendah akan mengalami pertambahan nilai jika semua itu dipandang
sangat mungkin diperoleh. Jadi, timbul interaksi antara nilai imbalan dengan kecenderungan
diperolehnya imbalan. Imbalan yang paling diinginkan adalah imbalan yang sangat bernilai
dan sangat mungkin tercapai. Imbalan yang paling tidak diinginkan adalah imbalan yang
paling tidak bernilai dan cenderung tidak mungkin diperoleh.
C.1.II. Teori Pertukaran Peter Blau
Blau memusatkan perhatiannya pada proses pertukaran yang mengarahkan perilaku
manusia dan mendasari hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau ingin
melampaui pokok bahasan Homans tentang bentuk-bentuk dasar kehidupan sosial dan masuk
ke dalam analisis struktur kompleks. Hasilnya, Blau memaparkan urutan empat tahap mulai
dari pertukaran antar pribadi, struktur sosial sampai dengan perubahan sosial:
Tahap 1: Transaksi pertukaran pribadi antar orang melahirkan..
Tahap 2: Diferensiasi status dan kekuasaan, yang menyebabkan ...
Tahap 3: Legitimasi dan organisasi, yang menumbuhkan benih-benih...
Tahap 4: Oposisi dan perubahan
Menurut Blau, orang tertarik satu sama lain karena berbagai alasan yang mendorong
mereka membangun hubungan. Ketika ikatan terbangun, imbalan yang mereka berikan satu
sama lain, yaitu memelihara dan memperkuat ikatan. Situasi sebaliknya pun mungkin terjadi:
dengan imbalan yang memadai, hubungan akan melemah atau putus. Dua jenis imbalan yang
18
diberikan menurut Blau: imbalan intrinsik berupa hal-hal yang tak berwujud (cinta, kasih
sayang) dan imbalan ekstrinsik berupa hal-hal yang berwujud (uang, kerja fisik).
Blau akhirnya melampaui bentuk perilaku dasar Homans dengan membahas struktur
sosial kompleks, dimulai dengan memperluas teorinya pada level fakta sosial. Ia mencatat
bahwa interaksi sosial mula-mula hadir dalam kelompok sosial. Orang tertarik pada suatu
kelompok ketika mereka mereasa bahwa hubungan tersebut menawarkan lebih banyak
imbalan dibandingkan dengan kelompok lain. Karena mereka tertarik pada kelompok
tersebut, mereka ingin diterima. Agar diterima, mereka harus menawarkan imbalan kepada
anggota kelompok. Hal ini antara lain memberikan kesan pada anggota kelompok dengan
menunjukkan pada mereka bahwa berasosiasi dengan orang-orang baru akan menjadi sesuatu
yang menyenangkan. Hubungan dengan anggota kelompok akan semakin solid ketika
pendatang baru mendapatkan kesan yang baik dari kelompok tersebut-yaitu jika anggotanya
menerima imbalan sebagaimana yang diharapkannya. Upaya para pendatang baru untuk
memberikan kesan pada anggota kelompok umumnya menyebabkan kohesi kelompok,
namun kompetisi dan, akhirnya, diferensiasi sosial dapat terjadi ketika semakin banyak orang
yang secara aktif berusaha memberikan kesan satu sama lain dengan kemampuan mereka
untuk memberikan imbalan.
Bagi Blau, mekanisme yang memerantarai struktur sosial kompleks adalah norma dan
nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Awalnya memandang pada norma sosial, Blau
berargumen bahwa mereka mengganti pertukaran tidak langsung dengan pertukaran
langsung. Satu anggota menerima norma kelompok dan mendapatkan pujian atas sikap
menerima tersebut dan mendapatkan pujian karena fakta bahwa sikap menerima tersebut
memberikan sumbangsih bagi terpeliharanya serta stabilitas kelompok. Dengan kata lain,
kelompok terlibat dalam hubungan pertukaran dengan individu. Ini bertolak belakang dengan
pandangan Homans yang lebih sederhana, yang memusatkan perhatian pada pertukaran antar
pribadi. Blau memberikan contoh pertukaran antara individu dengan kelompok yang
menggantikan pertukaran antar individu:
Staf rendah tidak membantu pegawai yang lebih tinggi dalam kerja mereka
demi imbalan yang akan diterima dari mereka, namun memberikan bantuan
tersebut adalah kewajiban resmi anggota staf, dan atas dijalankannya
kewajiban-kewajiban tersebut mereka mendapatkan imbalan finansial dari
perusahaan.
(Blau, 1964: 260)
19
C.2. Kritik
Teori pertukaran sosial tidak terlepas dari kritik-kritik. Pertama, teori ini hanya
mendasarkan perilaku manusia pada hal-hal ekonomi saja. Teori ini mengabaikan faktor-
faktor dari dalam manusianya, seperti biaya, keinginan, dan minat. Kedua, teori ini hanya
seperti menekankan bahwa tujuan manusia berinteraksi semata-mata hanya untuk
mendapatkan keuntungan satu sama lain.
Ketiga, Blau dalam karyanya walaupun cakupannya mulai meluas kepada masyarakat,
namun ia salah menafsirkannya. Langkah yang salah ketika sebenarnya fokus pada
pertukaran adalah antar individu (bertatap muka), namun diperluas hingga masyarakat.
Keempat, perilaku manusia dalam teori ini hanya ingin memberi dan menerima imbalan
semata (prinsip ekonomi: untung dan rugi). Maka dari itu, perasaan saling mengasihi satu
sama lain hilang seiring dengan pikiran-pikiran rasional sehingga mengabaikan unsur
perasaan.
20
DAFTAR PUSTAKA
Blau, Peter, 1964, Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.
Davis, Kingsley, dan Wilbert Moore, 1945, Some Principles of Stratification, American
Sociological Review 10, pp. 242-249.
Farganis, James, 2000, Readings In Social Theory: The Classic Tradition to Post-
Modernism, Third Edition, The McGraw-Hill Higher Education.
Goffman, Erving, 1959, Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor.
Homans, George C., 1961, Social Behavior: Its Elementary Forms, New York: Harcourt,
Brace and World.
_________________, 1974, Social Behavior: Its Elementary Forms, Edisi Revisi, New
York: Harcourt Brace Jovanovich.
Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, 1992, Sosiologi, edisi 6, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mead, George Herbert, 1934/1962, Mind, Self, and Society: From the Standpoint of A
Social Behaviorist, Chicago: University of Chicago Press.
__________________, 1982, The Individual and the Social Self: Unpublished Work of
George Herbert Mead, Chicago: University of Chicago Press.
Merton, Robert K., 1949/1968, Manifest and Latent Function, New York: Free Press.
Misztal, B., 2001, Normality and Trust in Goffman’s Theory of Interaction Order,
Sociological Theory 19, pp. 312-324.
Poloma, Margaret M, 1979, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
Purwanto, 2007, Sosiologi untuk Pemula, Yogyakarta: Media Wacana.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2013, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi
Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Yogyakarta: Kreasi
Wacana.
Sanderson, Stephen K., 1993, Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas
Sosial, Jakarta: CV. Rajawali Pers.