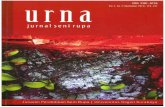BAB IV MAKNA SIMBOLIK SAWER PANGANTEN DALAM ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of BAB IV MAKNA SIMBOLIK SAWER PANGANTEN DALAM ...
47
BAB IV
MAKNA SIMBOLIK SAWER PANGANTEN DALAM PERKAWINAN
ADAT SUNDA
A. Konsep Budaya dan Simbol
Dalam bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta,
buddhayah (bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi), jadi
kebudayaan berarti hal yang berkaitan dengan akal. Wujud kebudayaan yang
berupa ide, norma, dan aturan itu tidak terlepas satu sama lainnya, berkaitan
menjadi satu sistem ialah sistem budaya, atau cultural system, yang biasa
disebut adat istiadat. Adapun wujud kebudayaan yang berupa aktifitas dan
tindakan berpola manusia dalam masyarakat ialah sistem sosial yang terdiri
dari aktifitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan menurut pola
tertentu berdasarkan tata kelakuan.67
Pada tahun tujuh puluhan, muncul James P. spradley (1972) dan Clifford
Geertz (1973) yang mengemukakan dua konsep budaya yang berbeda,
walaupun kedua konsep itu masih terfokus pada inti budaya yang kurang
memperhatikan posisi para pelaku atau pendukung kebudayaan. Menurut
Spradley kebudayaan ialah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia
sebagai makhluk sosial, yang terdiri dari perangkat model-model pengetahuan
yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan melakukan
interpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta tindakan
67
Judistira K. Garna, Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menantang Masa Depan,Bandung:
Lembaga Penelitian Unpad, 2008, hal. 8
48
yang diperlukan. Adapun kebudayaan menurut Geertz ialah pola-pola arti
yang terwujud sebagai simbol-simbol yang diwariskan secara historis, yang
dengan bantuan mana manusia melakukan komunikasi, melestarikan dan
mengembangkan pengetahuan serta sikap terhadap hidup.
konsep kebudayaan berarti suatu pola makna-makna yang diteruskan
secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep-
konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang
dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan
pengetahuan mereka tentang kehidupan serta sikap-sikap terhadap kehidupan.
Simbol secara etimologis berasal dari kata Yunani “sym-ballaein” yang
berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan
suatu ide.68
Adapula yang menyebutkan “symbolos” yang berarti tanda atau
ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang.69
Biasanya simbol
terjadi berdasarkan metonimi, yakni nama untuk benda lain yang berasosiasi
atau yang menjadi atributnya dan metafora, yaitu pemaknaan kata atau
ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan.
Menurut Erwin Goodenough, simbol adalah barang atau pola yang
apapun sebabnya, bekerja pada manusia, dan berpengaruh pada manusia,
melampaui pengakuan semata-mata tentang apa yang disajikan secara harfiah
dalam bentuk yang diberikan itu. Simbol membedakan antara bahasa yang
bersifat denotatif, yaitu tepat, ilmiah, harfiah, dan bahasa yang bersifat
68
B. Rahmanto Dick Hartoko dan, Kamus Istilah Sastra, Yogyakarta, Kanisius, 1998,
hal. 133 69
Budiono Herusatoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa, Yogyakarta, Hanindita Graha
Widya, 2000, hal. 10
49
konotatif, yaitu berasosiasi, tidak persis tepat, memungkinkan beragam
penafsiran. Simbol memiliki makna dan nilainya sendiri. Fungsi simbol ialah
merangsang daya imajinasi, dengan menggunakan sugesti, asosiasi, dan
relasi.70
Titik sentral kebudayaan Geertz terletak pada simbol, bagaimana
manusia berkomunikasi lewat simbol. Di satu sisi, simbol terbentuk melalui
dinamisasi interaksi sosial, merupakan realitas empiris, yang kemudian
diwariskan secara historis, bermuatan nilai-nilai, simbol merupakan acuan
wawasan, memberi petunjuk bagaimana warga budaya tertentu menjalani
hidup, media sekaligus pesan komunikasi, dan representasi realitas sosial.71
Pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan simbol, baik istilah-
istilah rakyat maupun jenis-jenis simbol lain. Semua simbol, baik kata-kata
yang terucapkan, sebuah objek seperti sebuah bendera, suatu gerak tubuh
seperti melambaikan tangan, sebuah tempat seperti masjid atau gereja, atau
suatu peristiwa seperti perkawinan, merupakan bagian-bagian suatu sistem
simbol. Simbol adalah objek atau peristiwa apa pun yang dapat kita
rasakan atau kita alami.
Geertz memfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang
menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai
permasalahan hidupnya. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang
diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol, dan menjadi suatu
konsep yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya
70
Dillistone,FW , The Power of Symbols, Yogyakarta; Kanisius, 2002, hal. 19
71 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal. 49
50
manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan
mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.72
Oleh karena itu, upacara pe rk awinan yang penuh dengan simbol ini
ada aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga masyarakat pendukungnya.
Aturan ini tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan suatu masyarakat
secara turun temurun, dengan perannya yang dapat melestarikan ketertiban
hidup dalam masyarakat. Biasanya kepatuhan setiap anggota masyarakat
terhadap aturan dalam upacara perkawinan disertai dengan keseganan atau
ketakutan mereka terhadap sanksi yang bersifat sakral magis.
B. Upacara Sawer Pengantin
Sawer pengantin merupakan bagian dari urutan adat-istiadat perkawinan
Sunda. Pelaksanaan sawer biasanya dilakukan di halaman rumah, sebab
bagian halaman rumah ini sering disebut dengan istilah “panyaweran”,73
artinya tempat yang biasa terkena air hujan yang terbawa hembusan angin.
Karakter halaman rumah yang semacam inilah yang memunculkan istilah
sawer yang berasal dari kata awer, yang mempunyai arti “air jatuh
menciprat”. maka pelaksanaanya pun yang dilakukan oleh juru sawer seperti
itu misalnya kalau pengertiannya sebagai air jatuh memercik, sesuai dengan
pelaku juru sawer menciprat-cipratkan atau menabur-naburkan perlengkapan
benda-benda sawer ke arah pengantin yang melambangkan bahwa kedua
pengantin tidak boleh segan-segan memberikan bantuan/harta kekayaan
kepada sanak saudara dan orang lain, dan bila di kemudian hari hidup senang,
72
Ibid, hal. 3 73
Yus Rusyana, Bagbagan Puisi Sawer Sunda, Bandung: Projek penelitian pantun dan
Forklore sunda, 1971, hal 1
51
mulia dan berbahagia haruslah senang menolog dan membantu sesama
dengan sedekah.
Dalam sawer, kedua mempelai duduk di kursi yang diletakkan di depan
rumah mempelai perempuan (panyaweran). Didampingi oleh seorang
pemegang payung, sedangkan juru sawer atau panyawer berdiri di depan
pengantin, biasanya perempuan. Sawer merupakan pepatah atau nasihat bagi
pengantin, yang bertujuan agar rumah tangga bahagia, yang dilantunkan
melalui tembang atau pupuh, seperti; asmarandana, Dangdanggula, Kinanti,
dan Sinom dengan menggunakan lagu kidung, yang diakhiri dengan
nyawerkeun beras bercampur irisan kunyit, uang receh, permen, dan daun
sirih yang kesemuanya perlambang/kias yang mengandung makna.74
Dalam tembang sawer, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah
bahasa yang lugas, magis dan simbolis. Tingkat bahasa yang dipakai adalah
bahasa halus dan sedang, serta berbentuk pupuh dan puisi bebas yang banyak
menggunakan kata-kata pilihan. Isi teks tembang sawer umumnya mengenai
nasihat, yang tersusun menjadi tiga bagian, yaitu pembukaan, inti dan
penutup. Pada bagian pembukaan biasanya berisi permohonan maaf kepada
Tuhan, dewa, nabi, wali, leluhur dan hadirin, untuk melaksanakan sawer.
Bagian inti berisi nasihat-nasihat, dan contoh-contoh kehidupan berumah
tangga, dan bagian penutup berupa doa bagi mempelai, keluarga dan hadirin
74
Elis Suryani, Ragam Pesona Budaya Sunda, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 110-111
52
agar mendapat keselamatan dan rahmat Tuhan. Adapun tembang sawer yang
dibawakan pada umumnya tidak diiringi musik.75
Berikut ini potongan dari salah satu syair yang sering disampaikan dalam
pembukaan tembang sawer;
Agung-agung pangapunten
Ka panganten nu saranten
Arimankeun ku maranten
Pitutur munel teu kinten
Maafkan yang sebesar-besarnya
Kepada kedua mempelai yang manis-manis
Yakinilah oleh anda berdua
Nasihat-nasihat yang sangat berguna...76
Satu bait tembang sawer diatas adalah bagian pembukaan yang ditandai
dengan permohonan maaf kepada mempelai dan umumnya kepada semua
orang yang hadir dalam prosesi tersebut. Permohonan maaf adalah salah satu
karakter yang mewakili kerendahan hati dan kehati-hatian sang penutur
tembang sebelum memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Setelah
memohon maaf, sang penutur tembang atau juru sawer mengarahkan objek
nasihat yang akan disampaikannya, yakni kepada kedua mempelai melalui
75
Wawancara dengan Bu Jojoh, Juru Sawer di Desa Cipicung, 20 Mei 2014 pukul. 14.00
WIB, di rumahnya 76
Aep Saepudin, Makna Filosofis Tembang Sawer Dalam Upacara Perkawinan Adat
Sunda; Skripsi; Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 5
53
kalimat “Ka panganten nu saranten”. Kalimat ini merupakan pola bahasa
yang santun dalam bahasa Sunda.
Kemudian pada baris ketiga, juru sawer menyampaikan kepada kedua
mempelai agar memperhatikan nasihat-nasihat yang akan segera
disampaikannya melalui kalimat “arimanken ku maranten”. Yang dimaksud
iman disini adalah yakin dan percaya, agar kedua mempelai yakin dan
percaya, karena ketika yakin dan percaya pasti akan melakukan apapun yang
diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Baris selanjutnya menjelaskan
bahwa nasihat yang akan disampaikan memiliki manfaat yang sangat berguna
bagi kedua mempelai.77
Dengan demikian tembang sawer merupakan salah satu bentuk simbolisasi
dari wujud kebudayaan masyarakat Sunda dengan keseluruhan filosofi
hidupnya yang diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi adat-
istiadat yang dalam beberapa hal, dapat dianggap sakral. Meskipun bahasa
yang digunakan dalam tembang sawer tidak seluruhnya bersifat simbolik.
Namun secara umum bahasa-bahasa ini tetap mengandung makna simbolik
yang menggambarkan pandangan hidup masyarakat Sunda secara umum yang
kemudian disampaikan kepada mempelai.
77
Ibid, hal. 6
54
C. Makna Simbol Sawer Panganten
1. Beras
Kebudayaan digambarkan Geertz, sebagai sebuah pola makna-
makna atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang dengan
simbol tersebut masyarakat menjalani pengetahuan tentang kehidupan
dan mengekspresikan kesadaran masyarakat melalui simbol-simbol.
Karena dalam satu kebudayaan terdapat bermacam-macam sikap dan
kesadaran dan juga bentuk-bentuk pengetahuan yang berbeda-beda.
Simbol-simbol kebudayaan itu mempengaruhi kehidupan sosial sebagai
hubungan satu arah, yang dengan demikian simbol kebudayaan memberi
informasi, pengaruh, dan membentuk kebudayaan.78
Simbol merupakan alat yang kuat untuk memperluas penglihatan,
merangsang daya imajinasi dengan menggunakan sugesti, asosiasi, dan
relasi. Menurut penggunaan Geerts sendiri, “kebudayaan “ berarti suatu
pola makna yang ditularkan secara historis, yang digambarkan oleh
simbol-simbol, suatu sistem konsep yang diwarisi, terungkap dalam
bentuk-bentuk simbolis, yang menjadi sarana manusia untuk
menyampaikan, mengabdikan dan mengembangkan pengetahuan serta
sikap-sikap terhadap kehidupan.79
Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisahkan dari
sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang
ditutupi) dan 'lemma' (bagian yang menutupi). Pada tahap memproses
78
Judistira K. Garna, Op. Cit, hal. 11 79
Dillistone, Op. Cit, hal. 115
55
hasil panen padi, gabah akan ditumbuk di dalam lesung atau digiling
sehingga bagian luarnya (kulit gabah) akan terlepas dari isinya. Bagian
isi inilah yang disebut beras. Dan untuk warna beras itu sendiri biasanya
dibagi ke dalam beberapa farian, beras putih, beras merah, beras ungu,
dan beras hitam. Beras merupakan bahan mentah dari nasi, dan salah satu
dari Sembilan bahan pokok penting di beberapa Negara, terutama Asia.80
Secara makna simbol, beras melambangkan kesejahteraan,
khususnya pada masyarakat Sunda. Hal ini dikarenakan sistem
masyarakat Sunda yang bergantung pada makanan pokok yang berasal
dari beras. Dan kemudian simbol ini biasanya dipakai untuk syarat bagi
pengantin yang hendak menikah, karena simbol ini mewakili kecukupan
bekal pangan bagi kedua mempelai dan harus saling memahami satu
sama lain.81
Hal ini disebutkan dalam potongan syair yang disampaikan
oleh juru sawer;
Bisi tacan pada harti
Anu kurenan teh pasti
Nimuna lulus tarapati
Kudu sili beuli ati..
Jika belum sama mengerti
Suami istri itu pasti
Dapat hidup tenang sesuai
80
Di ambil dari http//www.Indaharitonangfakultaspertanianunpad.blogspot.com
/2013/05/pengertian-beras.html?m=1, Rabu, 26 November 2014 81
Wawancara dengan Bu Jojoh, Juru sawer di Desa Cipicung, 20 Mei 2014, Pukul 14.00
WIB di rumahnya
56
Harus saling mengambil hati..82
Tembang sawer diatas merupakan suatu nasihat, bahwa dalam
rumah tangga bisa baik jika suami dan istri saling memahami. Suami
harus memahami tabiat wanita secara umum, bahwa wanita berbeda
dengan laki-laki. Maka janganlah mengukur wanita seperti laki-laki.
Hendaknya sang suami menjaga apa-apa yang menjadi ketidaksukaan
istrinya, begitupun sebaliknya. Maka harus saling memahami bahwa
masing-masing penuh dengan kekurangan.
2. Kunyit
Dalam paparan Karl Rahner tentang proses simbolisasi ini, kata
kuncinya ialah “ungkapan”, pencurahan diri sendiri ke dalam yang lain”.
Sehingga atas dasar penafsiran simbolisasi ini, selanjutnya
mengembangkan suatu sistem kristologi yang komprehensif. Baginya,
amat penting bahwa simbol tidak pernah boleh dipandang sebagai sesuatu
yang terpisah dari hal yang disimbolkannya, yang berdiri dihadapannya,
menunjuk kepadanya, mengilustrasikannya. Sebaliknya, suatu objek,
suatu diri menjadi terungkap dalam simbol dan dengan demikian menjadi
hadir dalam simbol. Simbol sejati merupakan kehadiran nyata. Simbol
tidak memisahkan ketika mengantarai, tetapi mempersatukan dengan
segera, sebab simbol yang sejati dipersatukan dengan hal yang
82
Thomas wiyasa bratawidjaja, Op. Cit, hal. 69
57
disimbolkan, karena hal yang disimbolkan membentuk simbol sebagai
realisasi dirinya sendiri.83
kunyit adalah salah satu jenis tanaman yang banyak memiliki
manfaat, di antaranya sebagai bumbu masak. Tanaman ini telah dikenal
sejak lama di Indonesia dan penggunaannya cukup banyak dalam
kehidupan sehari-hari, mempunyai rasa yang pahit, agak pedas, baunya
khas aromatik, rimpang berwarna kuning kejingga-jinggaan. Warna
kuning merupakan lambang dari emas, yang mana emas mempunyai nilai
yang sangat berharga. Jadi, Melalui simbolisasi ini, keluarga mempelai
berharap agar rumah tangga calon pengantin saling menghargai satu
sama lainnya.84
Simbol yang terdapat dalam kunyit, mengajarkan bahwa dalam
keluarga, sangat penting menumbuhkan sifat saling menghargai. Seorang
istri harus menghargai suami, suami menghargai istri, anak-anak
menghargai orangtuanya, dan sebaliknya orangtua juga menghargai
pendapat anak-anaknya. Maka faktor utama dalam sebuah keluarga yaitu
dengan adanya komunikasi, karena tanpa komunikasi, kita tidak dapat
mengetahui apa saja yang sudah terjadi. Dengan menjalin komunikasi,
orangtua bisa mengetahui apa yang diinginkan anak untuk masa
depannya. Selain itu, dalam sebuah keluarga harus saling menasehati,
menasehati mempelai wanita untuk mengabdikan diri kepada suami
secara tulus ikhlas sepenuh hati sehingga hidupnya harmonis.
83
Dillistone, Op. Cit, hal. 135 84
Wawancara dengan Bu Tuti, Penata Rias di Desa Cipicung, 22 Mei 2014, pukul 10.00
WIB di kediamannya
58
3. Daun Sirih
Menurut Suzanne K. Langer, simbol adalah ide-ide yang
melambangkan suatu maksud tertentu yang berupa bahasa (pantun, syair,
pribahasa). Hal ini sesuai dengan yang sering digunakan dalam acara
sawer pada upacara perkawinan adat Sunda. Disebutkan pula bahwa
dalam suatu upacara anggota masyarakat menghayati, menegaskan, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu melalui media kata-kata, perbuatan,
dan lambang-lambang benda.85
Sirih adalah jenis tanaman yang banyak digunakan oleh
masyarakat Sunda, baik itu untuk di makan atau pun digunakan sebagai
simbol adat budaya. Misalnya untuk acara perkawinan. Dalam buku
upacara perkawinan adat Sunda, Thomas Wiyasa Bratawidjaja
mendefinisikan sirih kedalam lima macam. Pertama, sirih yang dalam
bahasa Sunda disebut seureuh, yang artinya sindir yang dalam bahasa
Sunda adalah reureuh, maksudnya berhenti nafsunya atau habis
nafsunya, kegunaan sirih ini biasanya tidak terlepas maupun terpisahkan
dalam adat istiadat Sunda. Maka dalam upacara perkawinan, sirih
memiliki makna kerinduan seorang pria maupun wanita yang sedang
dilanda asmara dan kemudian akan berakhir setelah terlaksana
perkawinannya, lebih jauh lagi sirih ini memiliki makna agar kedua
mempelai dapat seia sekata dalam menjalani bahtera rumah tangga.
Kedua, kapur Sirih (berwarna putih) yang mempunyai arti
85
Cepi Irawan, Kontinuitas dan Perubahan Sawer Panganten dalam Upacara
Perkawinan Adat Sunda Kontemporer, Skripsi; Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2012, hal. 94
59
melambangkan sifat dari perempuan, yang artinya suci dan menerima.
Ketiga, gambir (berwarna merah) melambangkan sifat berani seorang
pria terhadap tanggung jawabnya. Keempat, Pinang (jika dimakan akan
menjadi pening), melambangkan peningnya si gadis yang rindu kepada
seorang pria yang dicintainya. Kelima, tembakau (jika dimakan atau
dibuat rokok atau susur akan menimbulkan rasa pusing kepala) hal ini
melambangkan pusingnya seorang pria karena mabuk cinta dengan gadis
yang dicintainya.86
Makna daun sirih dalam kehidupan budaya dan tradisi masyarakat
Sunda pada acara sawer dilambangkan sebagai keterpaduan antara suami
istri, yang mana dalam kehidupan rumah tangga harus seia sekata, jangan
ada yang ego, yang mau menang sendiri, tetapi harus sabeungkeutan
(satu ikatan), satu pendirian, satu kemauan, satu tujuan untuk mencapai
apa yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan tembang sawer yang
dilantunkan oleh juru sawer kepada pengantin;
Tineung ulah pasalia
Sing sapagodos waluya
Lamunna pa-kira-kira
Nya lindeuk pasea tea
Cinta jangan berselisih
Seia-sekata agar selamat
86
Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Op. Cit, hal. 17
60
Jika banyak pertentangan
Mudah datang pertengkaran..87
Sudah menjadi fitrah manusia harus saling mencintai dengan
sesamanya. Baik dengan sesama jenis, maupun dengan lawan jenisnya.
Dengan sesama jenis saling mencintai itu bukan kebutuhan biologis,
melainkan mencintai dalam hubungan hidup. Misalnya tidak bisa
manusia hidup tanpa orang lain. Karena sudah menjadi fitrah manusia
berhubungan atau bersosialisasi dengan manusia lain, Karena manusia
saling membutuhkan satu sama lain. Maka dalam sawer perkawinan,
diajarkan bahwa kita harus saling memberi, saling menasehati, saling
membantu, saling bertukar pikiran, dan sebagainya. Itu pertanda saling
mencintai antar sesama.
Sedangkan cinta-mencintai dengan lawan jenis tidak sama dengan
mencintai sesama jenis. Dalam hal ini mencintai yang berhubungan
dengan kebutuhan nilai biologis (wanita dan laki-laki). Secara naluri
manusia menyadari bahwa tanpa terpenuhi kebutuhan biologis itu,
hidupnya tidak sempurna. Maka dalam membangun suatu rumah tangga
kedua belah pihak harus saling mencintai, saling menyayangi, saling
membela, saling menghargai, bila terjadi percekcokan salah satu harus
mengalah dan bila terjadi kemurungan pihak yang satu, pihak yang
satunya lagi harus dapat menghiburnya.
87
Ibid, hal. 69
61
4. Permen
Bernard Lonergan, mendefinisikan sebuah simbol adalah gambaran
dari suatu objek nyata atau khayal yang menggugah perasaan atau
digugah oleh perasaan. Perasaan-perasaan berhubungan dengan objek,
satu sama lain, dan dengan subjek. Simbol mendahului setiap penafsiran
atau penjelasan. Melalui simbol budi dan tubuh, budi dan hati, hati dan
tubuh berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi seperti itu tidak mudah
ditafsirkan, sebab sebuah simbol yang sejati mempunyai banyak sekali
makna yang mungkin. Simbol dapat mengungkapkan ketegangan,
pertentangan, perjuangan bahkan kontradiksi.88
Dalam acara sawer perkawinan adat Sunda, permen adalah simbol
dari sesuatu yang manis, sebab pada umumnya permen memiliki rasa
manis. Simbol ini melambangkan bahwa sepahit apapun proses
kehidupan yang dijalani dalam hidup berumah tangga harus selalu
diselesaikan dengan cara yang manis, semanis rasa permen. Dan permen
juga merupakan simbol harapan agar rumah tangga harus selalu manis
dan harmonis guna menggapai kebahagiaan.89
Karena kebahagiaan
adalah keinginan yang terpuaskan, dan disadari memiliki sesuatu yang
baik. Jadi, kebahagiaan merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan
yang ditandai dengan kecukupuan hingga kesenangan, cinta, kepuasan,
kenikmatan, atau kegembiraan yang intens.
88
Dillistone, Op. Cit, hal. 137 89
Wawancara dengan Bapak H. Ukari, Tokoh masyarakat Desa Cipicung, 10 agustus
2014 pukul 10.00 WIB di kediamannya.
62
Pada pementasan acara sawer yang disampaikan melalui lagu-lagu
yang bermotif tembang, tampaknya telah terjadi semacam komunikasi
batin antara juru sawer dengan pengantin, yaitu melalui rumpaka-
rumpaka (syair) lagu yang berisi nasihat-nasihat serta petunjuk dalam
berumah tangga. Setiap manusia yang membangun bahtera rumah
tangga, tentunya menginginkan keluarga harmonis yang didalamnya
mengisyaratkan hubungan timbal balik untuk saling mengasihi dan
menyayangi. Keluarga harmonis ialah persekutuan hidup yang dijalin
dengan selaras, damai, saling mencintai dan menyayangi yang ditandai
oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak,
serta ibu dengan anak. Maka dalam rumah tangga, harus mempunyai
perhatian dan menghargai semua keluarga.
5. Uang Logam
Tema sentral Cassirer adalah bentuk-bentuk simbolis. Cassirer
mengatakan; manusia hidup dalam alam semesta simbolis. Bahasa, mite,
kesenian, dan agama adalah bagian-bagian alam semesta itu. Semuanya
itu merupakan pelbagai benang yang membentuk jaring simbolis,
jaringan kusut berliku-liku mengenai pengalaman manusia. Segenap
kemajuan manusia dalam berfikir dan berpengalaman, memperluas serta
memperkuat jaringan ini dari pada berurusan dengan barang-barang itu
sendiri, manusia boleh dikatakan senantiasa berbicara dengan dirinya
sendiri. Ia telah sedemikian melingkupi dirinya sendiri dengan bentuk-
bentuk bahasa, gambar-gambar seni, simbol-simbol mistis, atau
63
upacara-upacara keagamaan sehingga ia tidak dapat melihat atau
mengeahui apa pun kecuali dengan pengantaraan medium buatan ini.“90
Metode Cassirer tentang kehidupan manusia terkenal dengan
metode baru yaitu adaptasi terhadap lingkungan, berdasarkan dengan
sistem simbolik. Hal ini secara langsung sama dengan metode Mead,
yang juga “bahasa, dongeng, seni dan agama” adalah bagian dari respon
manusia terhadap alam.91
Dalam semua pengembangan budaya, manusia
tergantung diatas kepribadian simbolik. Dalam metode ini, Cassirer
membedakan antara tanda dan simbol, bahwasannya simbol tidak dapat
mengurangi signal. Signal dan simbol memiliki dua perbedaan dalam
bahasa. Signal adalah bagian fisik dunia, sedangkan simbol adalah bagian
dari dunia manusia dalam makna. Signal adalah operator, sedangkan
simbol adalah sebagai alat petunjuk.92
Uang merupakan alat tukar yang pada umumnya dipakai oleh
masyarakat untuk lalu lintas perekonomian. Dalam upacara perkawinan,
uang logam justru dapat menjadi syarat dalam upacara sawer. Namun,
tidak hanya uang logam yang digunakan, melainkan uang kertas, karena
keduanya sama-sama mempunyai nilai harga yang berguna bagi manusia.
Dengan adanya uang dalam upacara sawer, jelas hal inilah yang dapat
meramaikan suasana, karena upacara sawer paling dinanti-nantikan dan
sangat disukai anak-anak yang hadir, yang pada umumnya mereka adalah
anak-anak dari pihak sanak saudara sendiri dan dari para tamu undangan.
90
Dillistone, Op. Cit, hal. 122 91
Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik, Bandung : PT Remaja Posdakarya, 2006, hal. 250 92
Ibid, hal. 251,.
64
Mereka semua saling berebut uang, melompat sana-sini dengan perasaan
senang dan gembira. Jadi, uang dalam upacara sawer, melambangkan
simbol dari harta atau kekayaan yang menyiratkan makna bahwa
kekayaan merupakan bekal dalam menjalani kehidupan didunia untuk
menyiapkan bekal di alam akhirat nanti.93
6. Payung
Paul Ricoeur, mendefinisikan simbol sebagai setiap struktur makna
dimana suatu arti yang langsung, primer, harfiah menunjukkan, sebagai
tambahan, arti lain yang tidak langsung, sekunder dan figurative serta
yang dapat dipahami hanya melalui arti yang pertama. Berdasarkan
definisi ini, Ricoeur mendefinisikan penafsiran sebagai pekerjaan pikiran
berupa menyingkapkan makna yang tersembunyi dalam arti yang
tampak, menyibak tingkat-tingkat makna yang terkandung dalam arti
harfiah. Dengan demikian, simbol dan penafsiran menjadi konsep-konsep
yang korelatif.
Menurut pandangan Ricoeur, kewajiban terbesar penafsir adalah
melampaui yang harfiah untuk menerangi makna-makna yang
tersembunyi, makna-makna sekunder, makna-makna yang diperkaya,
makna-makna yang secara tepat disebut simbolis. Dengan menemukan
makna simbolislah diri sendiri terbuka kepada tingkat atau dimensi baru
93
Wawancara dengan Bu Jojoh, Juru sawer di Desa Cipicung, 20 Mei 2014, Pukul 14.00
WIB di rumahnya
65
eksistensi. Menafsirkan simbol-simbol, menelaah makna simbolis berarti
membawa diri ke dalam hidup yang lebih tinggi dan penuh.94
Payung adalah sebuah alat yang melindungi tubuh kita dari
guyuran air hujan. Dari segi rangka, bentuk payung memiliki sebuah
gagang (tiang) ditengah yang ukurannya lebih besar. Kemudian terdapat
beberapa gagang penyangga kecil-kecil yang berada di atasnya serta
terdapat kain yang menyelubungi payung. Payung mempunyai fungsi
penting bagi sebagian aktivitas manusia; melindungi manusia dari terik
matahari, payung juga menjadi pelindung di saat hujan. Selain itu,
payung juga mempunyai makna konotatif yang berarti pelindung atau
penjaga seperti terlihat dalam peribahasa yang menyebutkan „sedia
payung sebelum hujan‟. Dalam peribahasa ini, payung dimaknai
pelindung yang harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal buruk.
Keberadaan payung dalam upacara sawer, mengajarkan untuk
selalu cermat dan bijak dalam memperhitungkan hal-hal terburuk yang
kemungkinan terjadi dan solusi untuk mencegahnya. Payung sebagai
pelindung agar bersikap hati-hati serta waspada terhadap berbagai
godaan. Selain itu, sebagai suami harus dapat menjadi pelindung bagi
istri dan anak-anaknya kelak.95
Petuah yang disampaikan dalam upacara sawer mengandung
makna bagi setiap pengantin yang mau menuju mahligai rumah tangga.
Didalamnya diajarkan bagaimana tugas seorang istri terhadap suami,
94
Dillistone, Op. Cit, hal. 130 95
Wawancara dengan Bu Jojoh, Juru sawer di Desa Cipicung, 20 Mei 2014, Pukul 14.00
WIB di rumahnya
66
tugas suami terhadap istri, bagaimana kewajiban suami dan istri, dan
harus dapat menjalankan roda rumah tangga. Wanita diibaratkan sebagai
kemudinya yang mengemudikan rumah tangga, dan suami berikhtiar
mencari rejeki untuk menafkahi istri. Laki-laki harus menjadi patoknya
dan wanita menjadi talinya. Selain itu dalam penaburan bahan sawer juga
tidak hanya membuang secara percuma, namun seolah-olah
melemparkan harta kekayaan yang harus dipunyai oleh kedua mempelai
pengantin setelah nanti berumah tangga dan sebagai petunjuk agar rumah
tangga setelah mulia dan berbahagia serta berkecukupan bekal, janganlah
sekali-kali menjadi orang yang tamak, melainkan harus suka menolong
dan memberi sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan.
Dalam jurnal yang di tulis oleh Cepi Irawan, Upacara nyawer tidak
terlepas dari kelengkapan yang dulunya hanyalah menggunakan beras,
kunyit, sirih, dan uang logam, yang disimpan dalam satu wadah, namun
pada masa sekarang ada tambahan untuk perlengkapannya yaitu di
tambah dengan permen sebagai pelengkap.96
Dalam hal ini, terdapat
perbedaan dengan bu Jojoh sebagai juru sawer, yang mana beliau
berpendapat bahwa dulu menggunakan gula-gula, namun karena
sekarang sudah modern dan serba instan, gula-gula tersebut digantikan
dengan permen. Tetapi hal ini tergantung dengan juru sawer yang
membawakan, karena tidak wajib dan hanya sebagai siloka.97
96
Cepi Irawan, Op. Cit, hal. 93 97
Wawancara dengan Bu Jojoh, Juru sawer di Desa Cipicung, 20 Mei 2014, Pukul 14.00
WIB di rumahnya
67
Sedangkan menurut Ki Nana, berpendapat bahwa benda yang
pokok dan utama itu hanyalah beras, sedangkan yang lainnya hanyalah
sebagai pelengkap dan hiburan untuk meramaikan suasana. Karena beras
merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia yang berasal
dari padi atau biji-bijian yang kalau di tanam akan menghasilkan uang
sebagai bekal hidup berpisah dengan orang tua. Menurutnya,
Perlengkapan-perlengkapan yang sebagai tambahan selain beras,
tentunya mengandung simbol-simbol yang diciptakan si seniman dengan
bahasanya sendiri yang sangat spesifik. Simbol-simbol seni semata-mata
tidak hanya menyampaikan makna untuk dimengerti saja, tetapi lebih
kepada suatu pesan untuk diresapkan.98
98
Wawancara dengan Ki Nana Kusmayana, Seniman di Ciamis, 15 Februari 2014, Pukul
17.00 WIB.