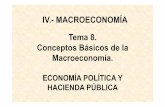s_sej_020036_BAB IV
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of s_sej_020036_BAB IV
47
BAB IV
PERANAN PADEPOKAN MUNGGUL PAWENANG DALAM
MELESTARIKAN KESENIAN TRADISIONAL WAYANG GOLEK
PURWA
Bab ini merupakan interpretasi dari fakta-fakta yang terkumpul tentang
keberadaan kesenian tradisional wayang golek purwa. Fakta-fakta ini diperoleh
melalui sumber lisan (oral history) dengan menggunakan teknik wawancara serta
berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, maupun karya tulis ilmiah.
Pembahasan bab ini dikembangkan menjadi tiga sub pokok bahasan, yaitu
pertama, perkembangan kesenian wayang golek purwa di Kota Bandung pada
tahun 1980-1995. Kedua, memaparkan latar belakang munculnya Padepokan
Munggul Pawenang. Ketiga, sikap dan pemikran Dede Amung Sutarya terhadap
Dunia Padalangan. Keempat, upaya yang dilakukan oleh Padepokan Munggul
Pawenang untuk mempertahankan esensi nilai dari sebuah pertunjukan wayang
golek khususnya wayang golek purwa.
4.1. Perkembangan Kesenian Wayang Golek Purwa di Kota Bandung.
4.1.1. Sejarah Masuknya Wayang Golek ke Priangan.
Asal mula wayang golek tidak diketahui secara jelas karena tidak ada
keterangan lengkap, baik tertulis maupun lisan. Kehadiran wayang golek tidak
dapat dipisahkan dari wayang kulit karena wayang golek merupakan
perkembangan dari wayang kulit. Namun demikian, Salmun (1986) menyebutkan
bahwa pada tahun 1583 Masehi Sunan Kudus membuat wayang dari kayu yang
48
kemudian disebut wayang golek yang dapat dipentaskan pada siang hari. Sejalan
dengan itu Ismunandar (1988) menyebutkan bahwa pada awal abad ke-16 Sunan
Kudus membuat bangun wayang purwo sejumlah 70 buah dengan cerita Menak
yang diiringi gamelan Salendro, pertunjukkannya dilakukan pada siang hari.
Wayang ini tidak memerlukan kelir, bentuknya menyerupai boneka yang terbuat
dari kayu bukan dari kulit sebagaimana halnya wayang kulit. Oleh karena itu,
disebut sebagai wayang golek. Tidak sedikit dari masyarakat kita yang memiliki
anggapan bahwa seni pedalangan atau pewayangan di Pasundan berasal dari Jawa
Tengah. Hal ini didasarkan pada kejadian sejarah bahwa orang Sunda pernah
mendapat pengaruh dari Mataram. Terlebih masih adanya bukti-bukti yang
menguatkan, diantaranya dalam pola raut (keuretan) muka wayang dan mahkota
(hiasan dikepala) yang menyontek dari wayang kulit purwa. Kakawen atau suluk
masih menggunakan bahasa kawi dan Jawa, begitu pula dengan alur ceritera
mengikuti pola ceritera pujangga Jawa (Sutarya, wawancara, 27/12/2007).
Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seni padalangan atau pawayangan
di Priangan datangnya dari Jawa Tengah, yang melewati Tegal dan Cirebon. Akan
tetapi, walaupun seni pedalangan dan pewayangan berasal dari Jawa Tengah tidak
semua pola pagelaran dalam pertunjukan wayang meniru wayang kulit purwa.
Karena, oleh seniman-seniman Sunda pola pagelaran wayang tersebut diolah dan
diserasikan dengan selera masyarakat Sunda, sehingga terjadi perbedaan antara
wayang golek purwa di Jawa Barat dengan wayang kulit di Jawa Tengah. Dengan
kata lain dalam pagelaran wayng golek purwa, kita memiliki sejak atau ciri khas
sendiri (Soepandi, 1988:23).
49
Dari beberapa sumber yang diperoleh penulis mengenai sejarah masuknya
wayang ke Priangan dijelaskan bahwa sekitar tahun 1244 M wayang telah masuk
ke Jawa Barat dibawa oleh Prabu Surya Amiluhur. Bahkan, Brandes berpenapat
sebelum datangnya pengaruh hindu para karuhun kita telah mengenal wayang.
Namun, dari pendapat-pendapat diatas kurang disertai oleh bukti-bukti yang
menguatkan kebenarannya.
Daerah Sunda yang pertama kali tersentuh oleh wayang golek yang
diciptakan Sunan Kudus adalah daerah Cirebon dengan nama Wayang Cepak
yang mulai dikenal di abad ke 16 pada zaman Panembahan Ratu (cicit Sunan
Gunung Jati). Setelah itu kemudian tersebar ke berbagai daerah terutama setelah
adanya jalan Pos yang dibuat antara tahun 1808 sampai 1811 maka
perkembangannya lebih jauh masuk ke daerah priangan. Hal ini, sejalan dengan
penjelasan Salmun, Ismunandar (1988) mengemukakan :
Mulai dari sinilah (Cirebon) wayang tersebar keseluruh penjuru. Pada waktu Priangan berada dalam pengaruh Mataram, wayang golek banyak disenangi oleh masyarakat Priyangan. Setelah terdapat jalan pos, yaitu tahun 1808-1811, maka ikatan keluarga lebih mudah dan wayang golek dari Cirebon makin jauh masuk ke wilayah Priyangan serta dalang-dalang makin bertambah banyak. Mulai saat itulah wayang golek disenangi oleh masyarakat Sunda
Gunardjo (1989), menjelaskan lebih jauh tentang munculnya wayang
golek purwa di Priangan :
Wayang golek purwa sunda baru dikenal di Priyangan pada awal abad ke-19. perkenalan masyarakat Sunda dengan pertunjukan golek dimungkinkan dengan dibukanya jalan raya Daendles yang menembus daerah isolasi darah-daerah Priyangan yang bergunung-gunung dengan daerah pantai
50
Dari keterangan di atas wayang golek purwa mulai dikenal dan
berkembang di Priangan pada abad ke-19 dengan dibukanya jalan raya Daendels
yang menembus daerah pedalaman. Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh
Wiryanapura mengenai asal-usul dalang, didapatkan informasi mengenai sejarah
masuknya wayang ke Jawa Barat. Dijelaskan, pada masa jabatan bupati Bandung
Indradireja atau Adipati Wiranata Koesoemah II tahun 1794-1829 mendatangkan
dalang asal Tegal bernama Ki Dipa Permana yang bertugas menjadi dalang lebet
atau dalang tetap di Kabupaten. Selain mendalang Ki Dipa Permana juga
menurunkan keahliannya pada Ki Gubyar yang menyebarkan wayang di
Purwakarta dan Ki Klungsung yang menjadi guru dalang-dalang di Garut. Jadi,
dapat dikatakan bahwa Ki Dipa Permana merupakan leluhur para dalang
Pasundan atau Jawa Barat (Soepandi, 1988:33).
Setelah Adipati Wiranata Koesoemah II lengser dan digantikan oleh
Dalem Karang Anyar atau Adipati Wiranata Koesoemah III tahun 1829-1846,
beliau memanggil dua dalang asal tegal, yaitu Ki Darman dan Ki Surasungsing.
Kedua dalang tersebut mendapatkan tugas yang berbeda, dimana Ki Darman
ditugaskan untuk mencoba membuat wayang dari bahan kayu atau wayang golek
purwa dan kemudian menetap di Cibiru, sedangkan Ki Surasungsing membuat
gambelan sebagai pengiring jalannya pertunjukan wayang dan kemudian beliau
menetap di Cimahi. Sampai dengan sekarang Cibiru telah menjai sentral atau
kiblat dalam pembuatan wayang golek purwa dan sering disebut gaya Cibiruan,
disamping Jelekong sebagai pelopor pembaharuan bentuk wayang beserta
perubahan bentuk penyajiannya.
51
Pada awalnya bentuk wayang golek purwa yang dibuat oleh Ki Darman
masih berbentuk gepeng dimana pola rautnya masih meniru pada wayang kulit,
hal tersebut dilaterbelakangi oleh pengalaman Ki Darman sebagai juru wayang
kulit (pembuat wayang kulit). Keturunan Ki Darman kemudian melanjutkan
keahliannya sebagai pembuat wayang golek dan dalang, diantaranya Ki Arsip,
dalang Takrim (anak Ki Arsip). Pada awalnya pagelaran wayang golek purwa di
priangan dibawakan dalam bahasa Jawa, baru setelah Adipati Wiranata Kusumah
IV berkuasa, beliau memerintahkan seorang dalang asal Tegal yang bernama
Mama Anting untuk mendalang dengan menggunakan bahasa Sunda, namun
kakawennya tetap menggunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wayang golek purwa di
priangan muncul dan berkembang pertmakalinya di daerah Cibiru. Dari sinilah,
wayang golek mulai menyebar ke berbagai pelosok wilayah Jawa Barat. Sampai
saat ini di Priangan terdapat dua dinasti yang tetap eksis dalam mempertahankan
kesenian tradisonal masyarakat Sunda, yaitu Dinasti Sutarya (sejak kaler) dan
Dinasti Sunarya (sejak kidul). Kedua dinasti ini, hidup dan berkembang
mempengaruhi warna dan bentuk pertunjukan wayang golek daerah-daerah
lainnya di Jawa Barat.
4.1.2. Pasang Surut Pertunjukan Wayang Golek Purwa di Bandung
Pertunjukan Wayang di Jawa Barat pada kenyatannya mengalami pasang
surut dalam dinamika perubahan dan perkembangannya. Adapun kurun waktu
yang akan dipaparkan pada studi ini berkisar tahun 1950-an sampai 1980.
52
Dalam perjalannya seni pertunjukan wayang golek purwa lambat laun
mengalami perubahan dan perkembangan di tengah masyarakat sejalan dengan
kemajuan zaman. Perubahan yang terjadi dalam pertunjukan wayang golek pun
harus diterima oleh pemilik wayang tersebut baik yang bertolak dari tradisi atau
modern sama sekali. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan tersebut, akan
penulis paparkan sebagai berikut.
Sekitar tahun 1950-an ke belakang, pertunjukan wayang masih sangat
subur terbukti dengan seringnya dilaksanakan pertunjukan wayang golek, atau
banyaknya peluang pementasan wayang di tengah masyarakat dalam perhelatan
dan sebagainya. Pertunjukan wayang golek pada tahun 1950-an masih mendapat
tempat dihati masyarakat. Peranan wayang untuk kepentingan kehidupan
dianggap sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat (Sutarya, wawancara,
27/12/2007).
Pada tahun 1960-an peranan pertunjukan wayang golek purwa sedikit
mengalami penurunan dibandingkan tahun 1950-an. Adapun faktor penyebabnya
adalah menurunnya frekwensi pertunjukan wayang golek purwa. Hal ini akibat
dari sikap dalang yang kurang meningkatkan mutu garapan sajian, karena
minimnya pengetahuan dan keteramplilan dalang itu sendiri, serta kurangnya
berlatih. Selain itu, faktor kurangnya ilmu yang diberikan atau diwariskan oleh
generasi sebelumnya baik mengenai kepiawaian olah garapan pewayangannya,
wawasan mengenai kompleksitas seni yang digelutinya, termasuk sempitnya
wawasan terhadap seni yang lain. Oleh sebab itu mereka mulai berani pentas
walaupun mereka belum dikatakan siap karena didorong oleh kebutuhan dirinya
53
maupun masyarakat sebagai penonton. Mereka terpaksa tampil seadanya dengan
pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang sangat kurang. Penenton
disuguhi pertunjukan yang kurang berbobot dan pada akhirnya kebiasaan
menikmati pementasan seperti ini mempengaruji apresiasi penonton.
Kemerosotan wayang golek purwa pada tahun 1960-an disebabkan oleh
faktor lain, yaitu dengan munculnya pesinden-pesinden dari kumpulan kiliningan
Sunda di Jakarta asuhan R. Toteng Johari. Perkumpulan kiliningan yang mengisi
acara rutin stiap minggu di gedung arca Jakarta. Dengan memanfaatkan media
informasi itu pesinden akhirnya banyak dikenal masyarakat, diantaranya: Upit
Sarimanah yang berasal dari Wanayasa Purwakarta dan Titim Patimah dari Jalan
Cagak Subang. Ditengah masyarakat kliningan pesinden Upit Sarimanah dan
Titim Fatimah menjadi pesinden idola dengan penampilannya yang khas dalam
membawakan lagu-lagu dan mengekspresikan lagu lewat alunan suara merdu,
keras dan kadang kala lembut volume suaranya. Disamping itu didukung pula
dengan gerakan-gerakan tangan dan gerakan tubuh diatas panggung (Yoyoh,
wawancara, 08/05/2009).
Dengan munculnya pesinden Upit Sarimanah dan Titim Fatimah, timbul
animo masyarakat didalam wayang golek purwa. Penanggap yang didorong oleh
masyarakat meminta supaya tempat duduk pesinden agak tinggi dari tempat
duduk dalang, dengan memakai level, bangku atau kursi (Madtayuda, wawancara,
27/12/2007).
Pengaruh dari meningkatnya fungsi sinden pada pertunjukan wayang
golek purwa itu, lambat laun peran pertunjukan wayangnya menjadi terlupakan
54
karena perhatian masyarakat atau penonton bukan lagi terhadap sajian pertunjukan
wayang golek melainkan terhadap kecantikan pesinden, kelembutan dan
kelincahan gerakannya. Jadi kenyatannya bukan wayang golek yang diiringi
sinden (disindenan) tetapi sinden yang diwayangi. Dengan kata lain, bukan sinden
sebagai pendukung wayang, tetapi wayang sebagi pendukung sinden (Sutarya,
wawancara, 01/03/2008).
Peranan dalang dalam pertunjukan wayang golek semakin pudar, bahkan
semakin rusak dan semerawut. Disamping penyajian lakon yang tersendat-sendat,
bahkan sering pula terjadi waktu pertunjukan wayang habis tersita oleh lagu-lagu
pesinden atas permintaan para penonton. Struktur lakon atau alur ceritera tidak
utuh lagi, dimana dalam pementasannya tidak lagi mementingkan adanya
pementasan awal, tengah dan akhir ceritera. Pada akhirnya makna, esensi dan
pesan lakon itu terputus tidak sampai ke penonton.
Menginjak tahun 1960-an pertunjukan wayang golek purwa di Jawa Barat
khusunya di kota Bandung semakin merosot dan menurun bahkan kurang diminati
oleh masyarakat karena pengaruh-pengaruh kesenian lain. Kondisi ini ditegasan
oleh Lubis (2003:324), dalam kehidupan sosial budaya tahun 1960-an terjadi
perubahan dikalangan generasi muda pribumi yaitu mulai berpalingnya kepada
jenis-jenis musik pop, seperti pop Barat, Indonesia, Sunda dan juga rock n roll,
akibatnya jenis musik tradisional Sunda, seperti tembang sunda, kecapi suling dan
cianjuran keudukannya semakin tergeser. Pengaruh tersebut dibawa oleh
masuknya kebudayaan asing ke Indonesia tak terkecuali di Jawa Barat. Budaya
55
asing itu masuk melalui mereka yang datang dari luar negeri, siaran RRI, radio
amatir dan siaran radio luar negeri.
Menginjak tahun 1975-an pengaruh dari seni lain, yaitu kiliningan,
ronggeng dan bajidoran dari daerah Subang dan Karawang mulai banyak
mempengaruhi pertunjukan wayang golek. Seni kiliningan yang menampilkan
beberapa sinden berduduk sejejer diatas panggung sudah menjadi kelaziman.
Sekitar awal tahun 1980-an pengaruh kesenian lain yaitu seni baru waktu
itu adalah jaipongan. Kesenian ini sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat
Jawa Barat khususnya Bandung. Munculnya seni jaipongan sangat besar
pengaruhnya terhadap sajian pertunjukan wayang golek purwa. Pribadi dalang itu
sendiri membuka dan menerima kehadiran jaipongan, yang pada akhirnya terjadi
kolaborasi yang harmonis antara seni jaipongan dimana intro-intro gending
jaipongan sering digunakan dalam lagu-lagu tradisi seperti pada tatalu, badaya
dan lagu-lagu lainnya.
Begitulah yang terjadi dalam pasang surut pertunjukan wayang golek
purwa di Jawa Barat pada kurun waktu antara tahun 1950-an sampai pada tahun
1980-an. Secara terbuka dan realistis memang itulah kenyataannya yang
mengakibatkan mundur dan merosotnya nilai-nilai seni pedalangan dan
pewayangan.
Pada tahun 1980-an merupakan titik balik kejayaan wayang golek purwa
di bandung, hal ini dikarenakan adanya pelopor pembaharuan sajian kedua dinasti
dimana dari dinasti sunarya dipelopori oleh dalang Asep Sunandar Sunarya
sedangkan dari dinasti Sutarya dipelopori oleh Dede Amung Sutarya. Keduanya
56
merupakan dalang yang memiliki besik dan motivasi tinggi terhap wayang golek,
terbukti dari hasil kerja kerasnya wayang telah diakui oleh dunia internasional
khusunya oleh UNESCO sebagai salah satu kesenian adiluhung. Pertunjukan
wayang pada tahun 1980 sampai sekarang telah masuk dalam tatanam masyarakat
kelas menengah atas, bukan hanya tontonan masyarakat kelas bawah. Terbukti,
pada tahun 1980-an sampai 1995 wayang golek telah masuk ke Hotel-hotel
berbintang, mengisi acara-acara pemerintahan seperti (milangkala) ulang tahun
kota bandung bahkan pementasan wayang di Universitas-universitas ternama
dikota Bandung (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
4.2. Latar Belakang Munculnya Padepokan Munggul Pawenang
4.2.1. Profil Dede Amung Sutarya
Wayang adalah dunianya sejak kecil, Bukan saja dia dilahirkan dalam
lingkungan budaya yang menjadikan wayang adalah tradisi, tetapi sekaligus juga
dia merasakan kehidupan sebagai seorang dalang wayang golek puwa. Saat ini, di
samping menjadi dalang wayang golek purwa Dede Amung Sutarya juga sebagai
ketua umum Yayasan Padalangan di Jawa Barat.
Beliau merupakan salah seorang Sunda yang akan merasa sangat
kehilangan, jika kesenian wayang golek purwa musnah ditelan kemajuan
peradaban yang percepatannya sangat tinggi. Karena itulah, hingga urusan yang
kecil-kecil tentang wayang golek purwa sangat dia perhatikan. Siapa lagi yang
akan bangga kalau wayang golek akan tetap langgeng. Kemudian siapa pula yang
akan kehilangan apabila wayang golek musnah. Sekarang ini, sudah mulai banyak
57
kesenian tradisi kita yang malah dipelajari oleh orang asing, sementara kita sendiri
tidak pernah ambil peduli (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Dede Amung Sutarya merupakan salah seorang dalang dari dinasti
Sutarya. Beliau dilahirkan dari keluarga seniman, ayahnya I. Biharna merupakan
seniman Sunda yang sangat andal dan ibunya adalah Epon Permasih. Dede
Amung Sutarya dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1954. Belaui adalah anak ke-3
dari tiga bersaudara. Anak pertama, yaitu Amung Sutarya, kedua Ai dan ketiga
Dede Amung Sutarya. Beliau belajar mendalang pada kakanya yang dianggap
sebagai guru sekaligus ayahnya yaitu Amung Sutarya. Sejak kecil beliau tinggal
bersama kakanya dan tertarik dengan kemampuan teknik mendalang disamping
materi yang dimilikinya (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Ketertarikannya terhadap wayang khususnya sebagai seorang dalang telah
mengorbankan pendidikan formalnya. Dalam pandangan Dede Amung Sutarya
pendidikan itu sendiri dapat diperoleh dengan cara mengetahui dan memahami
karakter dari setiap tokoh wayang, jadi tidak semua pendidikan didapat dibangku
sekolah.
Jiwa seni yang mengalir dalam tubuhnya telah mendorongnya untuk maju
nenjadi salah seorang dalang muda yang kreatif dalam mempertahankan
keberadaan kesenian tradisional wayang golek purwa ditengah gempuran budaya
Barat yang mulai masuk dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kota
Bandung pada tahun 1980-an hingga sekarang ini.
58
4.2.2. Latar Belakang dan Tujuan Didirikannya Padepokan Munggul
Pawenang
Padepokan Munggul Pawenang didirikan pada tahun 1966 oleh Dalang
Dede Amung Sutarya di Jl. Padasuka No. 287 Bandung Jawa Barat. Penamaan
padepokan munggul pawenang ini mengambil dari salah satu daerah dalam kisah
pawayangan, yaitu tempat tinggalnya tokoh Bima atau pandawa kedua yakni
Munggul Pawenang.
Dari hasil wawancara dengan dalang Dede Amung Sutarya, penamaan
padepokan tersebut tidak lepas dari pesan atau amanah ibunya. Ibu Epon Permasih
memberikan amanah jika anaknya (Dede Amung Sutarya) mendirikan padepokan
wayang golek ia harus menamakannya padepokan Munggul Pawenang. Hal ini,
dilatar belakangi oleh kesamaan kisah kelahiran Bima dengan Dede Amung
Sutarya. Dede Amung Sutarya dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan masih
terbungsus oleh selaput ketuban sama dengan kisah kelahiran Bima tokoh
Pandawa kedua dalam pawayangan.
Dede Amung Sutarya memulai karirnya sebagai dalang sejak kanak-
kanak. Ketika berusia 9 tahun dan masih duduk dibangku kelas lima SD beliau
sudah mulai aktif membantu pertunjukan kakanya, yaitu dalang Amung Sutarya
dalam setiap pementasan wayang golek purwa. Hal itu menyebabkan pendidikan
formalnya terbengkalai, dan mulai tahun 1966 Dede Amung Sutarya aktif sebagai
dalang wayang golek purwa dengan group Munggul Pawenang.
Pengalaman-pengalaman beliau selama nenjalani profesinya sebagai
dalang wayang golek purwa adalah pentas diseluruh daerah Jawa Barat dab
59
mengadakan pertunjukan diluar negeri seperti di Australia dalam rangka
mengikuti Festival Boneka Sedunia pada tahun 1992. Prestasi yang diraih oleh
beliau adalah juara umum Binojakrama pada tahun 1980, juara I Festival Boneka
Sedunia di Australia bersama Ki Anom Soeroso dari Tegal. Pada saat ini beliau
aktif sebagai ketua Yayasan Padalangan Pusat Jawa Barat, selain itu beliau
merupakan tokoh budayawan Sunda yang mempertahankan eksistensi budaya
Sunda di era globalisasi. Kecintaan terhadap wayang golek bagi beliau sudah
menjadi jalan hidupnya hingga sekarang ini.
4.3. Sikap dan Pemikiran Dede Amung Sutarya Terhadap Dunia
Pedalangan
4.3.1. Panca Bakti dan Tangkal Rahayu Ningrat
Kaluhungan seni padalangan khususna wayang golek anu sumebar hirup
di Tatar Sunda, salilana kudu tetep nanjeur, dijaga tur dimumule, sok sanajan
dina kaayaan kumaha oge, ieu sakabeh mangrupa tanggung jawab dalang anu
migawena. (keadiluhungan seni padalangan khususnya seni wayang golek yag
tumbuh dan berkembang di tatar Pasundan Jawa Barat harus tetap terjaga dan
terpelihara sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun, dan itu semua tergantung
kepada dalang sebagai pelakunya). (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Pernyataan tersebut merupakan wasiat langsung dari Dede Amung Sutarya
yang ditujukan kepada para dalang khususnya pada putra Dede Amung Sutarya
sebagai generasi penerusnya dari dinasti Sutarya. Dede Amung Sutarya dalam
mendidik dan menerapkan ilmu padalangan kepada putra dan para muridnya
60
selalu diingatkan bahwa hakikat tugas seorang dalang bukan hanya semata-mata
menghibur dan menghasilkan uang saja, melainkan dalang harus memberikan
penerangan dan pendidikan moral serta spiritual kepada masyarakat.
Keadiluhungan seni wayang golek, pada hakekatnya harus dapat
memberikan dan menciptakan dimensi memayu hayuning jalma yang artinya
meningkatkan kesadaran tentang makna dan martabat hidup manusia. Memayu
hayuning praja yang artinya meningkatkan arti kehidupan bermasyarakat dan
bernegara dan memayu hayuning bawana artinya menjaga dan meningkatkan
makna kata kehidupan didunia yang lebih baik.
Kunci poko dan esensi tugas dalang adalah harus menegakan panca bakti,
yang artinya lima bakti (pengabdian), yaitu:
1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berbakti kepada orang tua
3. Berbakti kepada guru
4. Berbakti kepada sesama
5. Berbakti kepada pemerintah dan negara.
Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tentunya tidak
hanya cukup dengan hanya tekun beribadah saja, tetapi harus disertai dengan
berbudi kepada kedua orang tua yang telah mendidik, memelihara dan
membesarkan hingga dewasa. Pendidikan pekerti yang tujuannya untuk
menanamkan kepribadian seseorang yang baik, tidak cukup dengan melalui
pendidikan formal dibangku sekolah saja, tetapi dengan pertunjukan wayang pun
bisa berlangsung melalui filterisasi dalang yaitu, Silib, Sindir, Siloka, Simbul dan
61
Sasmita yang menurut paham tradisi padalangan Sunda disebut Panca Curiga
atau Panca S.
Tindak lanjut setelah manusia berbakti terhadap Tuhan, berbakti terhadap
orang tua, dan berbakti kepada guru, maka manusia harus dapat berbakti kepada
sesama sebagai manipestasi kehidupan bermasyarakat melalui pergaulan dengan
sesama anggota masyarakat. Misi tersebut dalam pertunjukan wayang harus
tersajikan melalui lakon yang dibawakan oleh dalang, sehingga penonton merasa
terbekali sebagai suatu ajaran moral dan etika dalam masyarakat.
Untuk lebih menyempurnakan keempat azas kehidupan diatas, maka
manusia dituntut untuk mampu berbakti kepada pemerintah dan negara sebagai
tempat tinggal pada status kewarganegaraan yang sah. Manusia membutuhkan
ketenangan dan kenyamanaan dalam melaksanakan peribadatannya, manusia
membutuhkan perlindungan jaminan keamanan bagi pribadi dan keluarganya,
manusia membutuhkan sarana belajar (sekolah) yang aman dan nyaman, manusia
memerlukan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, bertetangga dan bernegara,
sehingga kesemuanya memerlukan adaya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Apabila mausia sudah berbakti kepada pemerintah dan negara maka
kelima azas (Panca Bakti) dapat berjalan dengan lancar dan sempurna, sehingga
tercapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Kelima azas inilah merupakan roh dari pertunjukan wayang, yang oleh
dalang-dalang keturunan dinasti Sutarya sangat dijungjung tinggi terlebih oleh
Dede Amung Sutarya.
62
Adapun Tangkal Rahayu Ningrat menurut Dede Amung Sutarya adalah
sebagai wujud dari implementasi manusia agar mencintai lingkungan alam sekitar
tempat berlangsungnya kehidupan. Tangkal Rahayu Ningrat berasal dari bahasa
Sunda yang artinya pohon kehidupan yang dapat memberikan air kehidupan bagi
makhluk hidup di jagat raya pramudiata. Apabila manusia telah mengamalkan
panca bakti dengan baik, maka dengan sendirinya akan dapat menjaga dan
melestarikan Tangkal Rahayu Ningrat.
4.3.2. Dalang Harus Jembar Manah (Bersifat Terbuka)
Kekreatoran Dede Amung Sutarya sebagai dalang kondang, secara prinsipil
dalam jiwa kehidupan berkeseniannya, ia menganut konsep “kudu miindung ka
waktu mibapa ka zaman” yang artinya seorang seniman dalang harus mengikuti
perubahan waktu dan perkembangan zaman. Konsep inilah yang mendasari sikap
dan mentalitas Dede Amung Sutarya dalam mensikapi erkembangan zaman
melalui berbagai bentuk kreatipitas didalam lingkup seni wayang golek purwa
sebagai dunianya.
Keberadaan Dede Amung Sutarya yang dibesarkan dilingkungan dunia
tradisi dalam kesenimannya menjadikan lebih respek terhadap berbagai tantangan
yang mengitarinya. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan seni
wayang golek sebagai kesenian tradisional, maka dipandang sebagai suatu seni
yag memiliki nilai tinggi serta potensial untuk dikembangkan, sehingga mampu
sejajar dengan seni-seni modern dalam era persaingan global. Dede Amung
63
Sutarya berprinsif bahwa wayang golek adalah dunia saya, dan saya harus bisa
hidup dengan wayang golek dengan menjadi dalang yang berhasil.
Tradisi bukan harus ditinggalkan bahkan ditakuti, tetapi tradisi harus
disajikan sebagai sumber inspirasi untuk lebih dikembangkan, sehingga seni
tardisi tetap terjaga dan terpelihara, mampu hidup sejajar dengan perkembangan
zaman. Dengan bertolak dari pernyataan tersebut, maka Dede Amung Sutarya
lebih leluasa bersikap dan berkarya melalui bentuk-bentuk kreativitas dengan
tetap menjungjung tinggi etika dan norma padalangan dalam persfektif kreativitas
berkesenian.
Dengan berbekal kejembaran jiwanya yang terbuka, Dede Amung Sutarya
menerima kritik dan tanggapan yang datang dari masyarakat dijadikan sebagai
guru yang akan membawa hikmah terhadap perjalanan karirnya sebagai dalang.
Dede Amung Sutarya menampakan diri sebagai sosok yang harus belajar, tidak
merasa sudah cukup dalam berkarya, selamanya ingin mencari dan menemukan
yang baru sepanjang tidak bertentangan dengan etika dan norma-norma yang
berlaku.
4.4. Upaya Padepokan Munggul Pawenang dalam Mempertahankan Nilai
Pertunjukan Wayang Golek Purwa.
4.4.1. Problema Melestarikan dan Pengembangan Wayang Golek Purwa
Dewasa ini perkembangan dunia pewayangan menimbulkan penilaian
yang beragam. Sebagaian ada yang menilai bahwa pergelaran wayang golek
semakin marak. Banyak perubahan yang dialami selama beberapa puluh tahun
64
terakhir ini. Kreatifitas para seniman pedalangan baik sebagai dalang maupun
sebagai seniman karawitan telah menunjukkan kemampuannya membawa
perkembangan baru dalam garapan seni pedalangan. Sebaliknya ada sebagian
kelompok yang menilai bahwa seni pedalangan sekarang telah mandeg, kreatifitas
para seniman pedalangan tidak berkembang dan bahkan mengalami kemerosotan
mutu seni yang sangat drastis (Sumitra, wawancara, 28/12/2007).
Penilaian yang beragam itu kiranya akan menjadi agak jelas bila kita
mengadakan studi perbandingan antara kondisi dan situasi seni pedalangan
dewasa ini dengan seni pedalangan pada kurun waktu sebelum masa
kemerdekaan. Sebelum merdeka tiap daerah mengembangkan keseniannya sendiri
sesuai dengan sistem nilai budaya etnisnya masing-masing, termasuk wayang dan
semi pedalangannya. Pada masa ini seni pedalangan terutama yang tumbuh dan
berkembang di lingkungan masyarakat penikmatnya sudah mencapai kemapanan
dengan kaidah-kaidah yang ketat dan mantap. Namun seperti halnya setiap unsur
kebudayaan, seni pedalangan selalu mengalami perubahan berkat kreatifitas para
seniman yang dapat timbul setiap saat dan merupakan inovasi dalam penggarapan
wayang golek dan seni pedalangan.
Bagi seniman berkarya dalam seni adalah sebagai pengabdian jiwanya
terhadap seni secara total dan sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan
jiwanya dengan Sang Maha Pencipta. Seni sebagai ungkapan rasa keindahan
dalam pandangan para seniman wayang tiada lain hanya bersumber pada sang
Maha Pencipta. Dengan sikap dan pandangan hidup seperti itu terciptalah karya
seni yang bermutu tinggi dan yang kemudian dikenal sebagai seni klasik atau seni
65
adiluhung. Dalam seni pedalangan pun tercapai suatu kemapanan dengan kaidah-
kaidah yang amat ketat untuk menjamin mutu seninya. Seni pedalangan pada
masa itu dirasakan kuat berakar pada kebudayaan etnisnya sesuai dengan citarasa
pendukungnya. Pengertian citarasa tidak hanya terbatas pada nilai estetis saja,
tetapi meliputi nilai kehidupan tradisi, filsafat dan pandangan hidup serta
ungkapan budaya masyarakatnya.
Penguasaan dalang di bidang seni pedalangan yang meliputi berbagai
unsur seperti apa yang telah ditegaskan dalam tetekon padalangan Jawa Barat,
telah dipolakan sebagai tradisi yang mapan dan diperkokoh oleh tuntunan harapan
estetis masyarakat penontonnya. Jadi baik dalang maupun penonton terikat pada
konvensi-konvensi dan idiom-idiom seni pedalangan yang dianggap sudah mapan
sebagai seni klasik dan adiluhung. Wayang dalam pandangan masyarakat Jawa
Barat menjadi semacam mitos, bukan saja dianggap sebagai karya seni tetapi di
dalamnya terkandung juga daya magis yang perlu disikapi dengan penuh hati-hati.
Merombak pakem pedalangan klasik dianggap dapat membawa akibat buruk yang
bersifat gaib (Soepandi, dkk. 1988:17).
Setelah negara kita merdeka tahun 1945 timbulah pergolakan yang cukup
drastis dalam kehidupan seni budaya, termasuk dunia seni pewayangan dan seni
pedalangan. Perubahan sisitem nilai budaya masyarakat Jawa Barat khususnya
Bandung mengakibatkan perubahan citarasa dalam kehidupan masyarakat
termasuk pertumbuhan dan perkembangan keseniannya. Timbulnya kesadaran
nasional membawa akibat bagi kehidupan seni budaya etnis. Dunia kehidupan
yang semula utuh bulat dengan sistem nilai budaya yang mapan menjadi goyah.
66
Norma-norma kehidupan sosial budaya masyarakat mengalami pergeseran dan
berkembang norma-norma baru sesuai dengan tuntutan zaman.
Sementara itu pengaruh unsur-unsur kebudayaan luar semakin gencar
melanda masyarakat Indonesia yang berakibat berubahnya tata nilai yang semula
telah mencapai kemapanan. Kegelisahan timbul di kalangan para seniman tua
sebagai pendukung seni pedalangan klasik tradisional. Di lain pihak mitos adanya
seni adiluhung yang mengandung unsur kesakralan lambat laun semakin menipis,
terutama di kalangan seniman muda atau dalang-dalang era tahun 80-an. Kaidah-
kaidah dan idiom seni pedalangan klasik adiluhung mengandung unsur feodalisme
dan banyak unsur-unsur kesakralan yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman. Namun di lain pihak diakuinya bahwa dalam seni klasik
adiluhung itu terkandung mutu seni yang sangat tinggi (Sutarya, wawancara,
08/05/2009).
Dengan perubahan sikap itu maka terbukalah hasrat di kalangan seniman
muda untuk mengembangkan kreativitas yang baru dengan memanfaatkan seni
pedalangan klasik sebagai sumber inspirasi dan bahan garapannya yang baru.
Wayang dan seni pedalangan menjadi lahan garapan yang terbuka lebar, tinggal
tergantung pada kepekaan rasa seni dan daya kreativitas para penggarapnya. Seni
pedalangan yang didukung oleh seperangkat unsur teatrikal yang serba artistik
mulai menjadi bahan garapan para seniman angkatan baru yang merasa tidak
harus terikat secara ketat pada kaidah-kaidah seni pedalangan lama. Dalam
kenyataannya di satu pihak kepekaan rasa estetisnya tetap terjaga sehingga unsur
seni pedalangan yang dirasakan cukup tinggi mutunya tetap dijaga kelestariannya,
67
namun dilain pihak terjadi pendangkalan mutu seni karena penggarapnya kurang
mendalami makna estetis-filosofis dari unsur-unsur seni pedalangan yang
digarapnya. Istilah pelestarian mengandung pengertian mempertahankan dan tetap
mentradisikan unsur-unsur seni yang lama.
Sekalipun demikian dalam upaya pelestarian itu disadari pula bahwa bila
tidah melahirkan kreatifitas baru seni pedalangan akan kehilangan daya pesonanya
di kalangan para pendukungnya. Dengan demikian pelestarian setiap seni
menuntut kreativitas para senimannya sehingga terjadi perkembangan yang
hasilnya mengandung unsur tradisi dan sekaligus juga inovasi. Hasil kreativitas
yang berupa garapan seni pedalangan yang bercorak baru dan memukau penonton
itupun pada saatnya juga akan dirasakan membosankan dan menuntut kreativitas
lain yang lebih marak dan segar (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Melestarikan seni pedalangan klasik adiluhung tanpa upaya
pengembangan ternyata tidak dapat menjamin daya pesona penonton, sebab hal
itu berkaitan erat dengan tingkat apresiasi dan citarasa masyarakat penontonnya.
Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelestarian wayang golek purwa
yang semata-mata mempertahankan unsur-unsur klasik tradisional tanpa disertai
pengembangan yang berupa hasil kreatifitas yang memadai justru akan
membekukan seni pedalangan itu sendiri.
Banyak dalang profesional yang tanggap akan situasi demikian itu dan
bagi yang merasa tidak mampu mengembangkan daya kreativatasnya sendiri
maka cara yang ditempuh adalah mencontoh dalang-dalang yang dianggap
berhasil. Hanya saja seringkali yang dicontoh adalah hal-hal yang justru yang
68
bersifat hiburan semata-mata, sedangkan hal-hal yang baik dan bermutu seni tidak
ditekuninya. Akibatnya, seni pedalangan mengalami kemerosotan dan semakin
lama semakin parah. Pertimbangan komersial sering menyeret para dalang untuk
mempergelarkan wayang asal ramai, lucu dan mendapat sambutan meriah dari
penonton, tetapi sayangnya sering mengorbankan nilai-nilai estetis dari seni
pedalangan itu sendiri (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Bila dicermati dengan seksama sebenarnya tiap unsur teatrikal pergelaran
wayang merupakan lahan untuk digarap secara kreatif. Talah banyak eksperimen
yang dilakukan, terutama dikalangan lembaga pendidikan seni dan yang memiliki
jurusan pedalangan. Hasilnya yang nyata antara lain berupa garapan pakeliran
padat. Dalam garapan itu semua unsur pendukung pergelaran mendapat perhatian
secara optimal. Dan penjelajahan di bidang seni pedalangan ini juga memberikan
dampak positif bagi pengembangan seni pedalangan pada umumnya. Namun
karena karya tersebut merupakan hal yang baru dan penggarapannya pun kadang-
kadang terlampau drastis maka masyarakat penonton yang sudah akrap dengan
seni pedalangan gaya lama kurang dapat memberikan apresiasi terhadap garapan
baru itu.
Ratusan bentuk lakon yang menunggu sentuhan kreatif para dalang masa
kini untuk dapat lebih menyentuh rasa etis dan estetis penonton, sehingga fungsi
pergelaran wayang golek purwa sebagai suatu karya seni benar-benar dapat
memenuhi kebutuhan penonton, akan kenikmatan dan kemanfaatan. Kenikmatan
dapat dicapai dengan penyajian garapan seninya, meliputi seni gerak (sabetan),
seni rupa (indahnya wayang golek dan penatahan panggung), seni suara (sulukan,
69
tembang, gending-gending, sindennya dan lainya), seni drama (plot penyajian
lakon), seni sastra (indahnya bahasa pedalangan, meliputi dialog dan narasi), dan
masih banyak lagi unsur-unsur lainnya yang menampilkan garapan estetis.
Kemanfaatan dapat dicapai dengan menerima pesan-pesan yang sarat dengan
nilai-nilai etis dan moral, serta mengundang perenungan dalam upaya
pengembangan kepribadian seseorang.
Dewasa ini banyak keluhan yang terlontar, terutama di kalangan pencinta
wayang golek purwa yang memiliki daya apresiatif dalam seni pedalangan, baik
sebagai warga masyarakat biasa maupun sebagai seniman, pembina, pejabat,
cendikiawan dll. Keluhan itu timbul setelah menyaksikan pergelaran wayang
masa kini yang cenderung mengutamakan segi hiburannya semata-mata atas
pertimbangan komersial. Berbagai cara telah ditempuh agar pergelaran wayang
tidak ditinggalkan oleh penonton (Madtayuda, wawancara, 27/12/2007).
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat menengah dan bawah yang
dirasakan cukup berat menjadi salah satu faktor untuk mencari hiburan santai dan
ringan, padahal kegemaran penonton wayang telah berkembang menjadi tuntutan
untuk dipenuhi. Akibatnya dengan tataran apresiasi yang kurang memadai itu
tuntunan rasa estetis terhadap pergelaran wayang menjadi sangat lemah.
Adegan yang menjadi harapan rekreatif oleh penonton terbatas pada unsur
lawakannya. Untuk melayani selera penonton seperti itu maka adegan-adegan
banyolan atau humor yang dirasakan rekreatif dijadikan sebagai pusat perhatian
para dalang untuk menggarapnya secara optimal. Upaya ini samapi melibatkan
para tokoh-tokoh pelawak dalam adegan-adegan tersebut meskipun harus
70
menyimpang dari bingkai pakelirannya atau dengan kata lain telah keluar dari
tetekon padalangan. Tidak dapat dipungkiri penggunaan bahasa dalam
pertunjukan wayang golek oleh generasi muda sering menyerempet ke hal-hal
pornografi, walaupun hal itu didasari oleh karakteristik orang Sunda yang sering
disebut cawokah. Dengan cara demikian tujuan komersial dari pergelaran wayang
dapat tercapai bahkan sering sangat sukses.
Dalam hal ini dalang sering dihadapkan pada suatu dilema. Sebagai
seniman yang mengutamakan pertimbangan estetis seni pedalangan rasanya
tuntutan selera penonton sedemikian itu menjadi beban mental yang cukup berat.
Tetapi di lain pihak pertimbangan komersial sering menipiskan pertimbangan
yang pertama. Apalagi jika diingat bahwa dalang harus mampu memenuhi
keinginan dan harapan si penanggap, terutama panitia penyelenggaranya (Sutarya,
wawancara, 08/05/2009).
Cara-cara memukau penonton seperti itu kiranya hanya merupakan suatu
mode sesaat. Pada saat tertentu penonton akan merasa jenuh dan mengharapkan
rekreasi baru dalam pergelaran wayang. Sayangnya kreatifitas para dalang itu
mengarah pada selera penonton yang masih kurang memadai tataran apresiasi
seninya. Maka jika hal ini dibiarkan berlarut-larut seni pedalangan semakin lama
akan kehilangan nilai-nilai etis dan estetisnya. Dan hal ini telah menimbulkan
kepribadian yang sangat mendalam di kalangan para pembina seni pedalangan
baik perorangan maupun kelembagaan, Pemerintah atau swasta.
Dukungan media masa dalam pembenahan seni pedalangan yang etis dan
estetis sangat dibutuhkan, mengingat bahwa seni pedalangan merupakan salah
71
satu sarana pendidikan budi pekerti yang cukup ampuh terutama bagi anak-anak
sebelum dewasa. Namun pada umumnya media masa kurang cukup memaparkan
kritik-kritik yang dapat turut mengembangkan seni pedalangan secara sehat.
Kritikus di bidang seni pedalangan masih sangat terbatas, dan bila ada dianggap
kurang cukup berwibawa untuk membawa perubahan-perubahan sikap dikalangan
para dalang masa kini dan kurang mampu mengembangkan dan meningkatkan
apresiasi seni masyarakat (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Penelitian tentang kehidupan seni pedalangan yang penulis dapatkan
masih sangat terbatas. Bukan saja dari segi keseniannya tetapi yang lebih penting
adalah sistem nilai budaya masyarakat pendukungnya, sebab lahirnya unsur
kebudayaan dalam kehidupan masyarakat berpangkal pada sistem budayanya.
Perubahan sistem nilai budaya yang dialami masyarakat pada zaman modern dan
dalam era globalisasi dewasa ini cukup besar. Penelitian di bidang kesenian tidak
dapat dipisahkan dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, meliputi sistem ekonomi,
sistem teknologi, sistem organisasi sosial, sistem religi, sistem pengetahuan dan
bahasa. Telaah wayang dan seni pedalangan secara holistik diharapkan dapat
menjawab problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini.
Setelah membandingkan dua kondisi dan situasi seni pedalangan berikut
sikap dalang dan masyarakat penontonnya dari dua kurun waktu yang berbeda
maka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni pedalangan dewasa ini dan
masa depan perlu dicermati problema-problema apa yang menjadi hambatan bagi
upaya tersebut.
72
Problema yang sangat meresahkan para pecinta wayang golek purwa
adalah penggarapan pakeliran yang menyimpang dari nilai-nilai etik dan moral.
Penyebabnya bersumber dari hasrat para dalang yang merasa kawatir akan
kehilangan penontonnya, dan hal ini akan mematikan sumber mata pencariannya.
Pada awalnya garapan yang mengutamakan segi hiburan itu mendapat sambutan
meriah sehingga dari segi komersial dianggap sukses. Namun kesuksesan itu
mengakibatkan baik dalang maupun penontonnya menjadi kecanduan dan meluas
bagaikan wabah yang menjangkiti para dalang-dalang muda lainnya (Sutarya,
wawancara, 08/05/2009).
Dewasa ini situasi seni pedalangan yang kejangkitan wabah itu tampak
semakin parah. Pergelaran wayang golek purwa yang semula merupakan seni
klasik adiluhung kemudian tak ada bedanya dengan tontonan kemasan seperti
sandiwara, ludruk, lenong, srimulat dan lainnya. Tuntutan dan harapan penonton
sewaktu menonton pertunjukan lambat laun dibebankan pada pergelaran wayang
golek sehingga para dalang dengani pertimbangan komersial berupaya
memenuhinya walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa hal itu menyimpang dan
keluar dari tetekon padalangan.
Kondisi dan situasi pergelaran wayang yang semakin parah itu sangat sulit
untuk ditanggulanginya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh padepokan munggul
pawenang diantaranya melalui seminar, sarasehan, dan forum-forum diskusi,
bahkan sampai pada penyusunan kode etik yang diselenggarakan oleh Yayasan
Padalangan.
73
4.4.2. Struktur Penyajian dalam pertunjukan Wayang Golek Purwa
Wayang golek sebagai bentuk teater tradisional, pada dasarnya memiliki
pola tersendiri kaitannya dengan alur lakon yang dibawakan, dan itu lazim disebut
pola pangadegan. Pola pangadegan dalam model teater tradisional tersebut, tidak
berorientasi kepada tokoh, melainkan kepada tempat. Maka pola pangadegan itu
pun merupakan siklus: keraton - luar keraton - keraton. Pola inilah yang dalam
pertunjukan wayang golek selalu digunakan oleh para dalang, dengan gaya dan
cara pengungkapannya yang berbeda (Saini KM, 2001:16).
Kraton adalah lambang kosmos yang stabil, dimana raja sebagai pusat
kosmos secara mantap berada ditempatnya dan berada dalam hubungan hierarchis
yang harmonis dengan bagian-bagian kosmos lainnya. Kemantapan ini
memancarkan pengaruhnya kesegala arah dan memungkinkan daerah-daerah yang
berada di wilayah kerajaan berbeda didalam kemantapan pula, yaitu keadilan,
kemakmuran, keamanan dan ketertiban.
Kemantapan dan harmoni ini diguncangkan dan terancam ketika datang
berita adanya gerakan pengacau atau agresi penyerangan. Maka mulailah bagian
pola yang kedua (luar keraton) yang penuh dengan ketidak pastian, bahaya,
percobaan, pengorbanan dan sebagainya. Melalui perjuangan, ancaman dan
guncangan tersebut dapat diselesaikan ndan akhirnya kosmos kembali stabil
memasuki adegan keraton sebagai periode terakhir. Dengan demikian, pola
pangadegan dengan menggunakan parameter siklus kosmos dalam lakon
pawayangan adalah merupakan struktur umum dan golbal sebagai alur ceritra
berdasarkan orientasi tempat.
74
Bertolak dari pola global tersebut, Dede Amung Sutarya mencoba
mengembangkan kembali melalui gaya pertunjukannya sendiri, melalui pla-pola
pembabakan yang sudah dibakukan dan berlaku untuk setiap lakon yang
dipertunjukan. Pola yang dimaksudkan adalah berupa pola suatu metode
tersendiri, untuk memenuhi selera penonton dari berbagai tempat yang beragam.
Keadaan ini bagi Dede Amung Sutarya merupakan suatu tantangan sekaligus
sebagi momen yang baik untuk dimanfaatkan. Menurut pemikirannya, selera
penonton dari setiap daerah harus terpenuhi dengan cara mengangkat isu hangat
yang sedang terjadi di tempat bersangkutan, sehingga aspirasinya merasa
tersalurkan melalui dialog suatu tokoh wayang atau pada bedrip (adegan) tertentu.
Metode yang dianggap praktis oleh Dede Amung Sutarya yaitu dengan
cara mencoba memancing emosi penonton melalui materi aspek problematika
yang beragam dan kondusif, seperti membahas tentang ajaran ahlak (tauhid),
politik atau kritik kepada pemerintah dan oknum, guyonan dan isu umum yang
sedang mencuat. Cara seperti ini dilakukan pada adegan pertama, di saat-saat
penonton menikmati kesan pertama dari pertunjukan. Setelah itu, maka selera atau
keinginan emsi penonton dapat terbaca aspek mana yang mendapat perhatian atau
respon, sehingga dalang Dede Amung Sutarya terus mengikuti dan membawanya
ke arah yang lebih larut dan kmunikatif antar dalang dengan penonton. Metode
inilah yang menjadi tolak ukur membawa emosi penontn agar larut dalam esensi
pertunjukan wayang golek (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Menurut pandangan Dede Amung Sutarya sebagai dalang wayang golek
purwa, pada prinsipnya penonton wayang golek terbagi menjadi tiga kelompok,
75
yaitu penonton yang hanya mementingkan unsur hiburan saja, penonton yang
memperhatikan keutuhan pertunjukan termasuk artistik, kekompakan pangrawit,
sabet wayang, kualitas suara sinden dan ketiga adalah kelompok penonton yang
mampu menghayati isi dan makna ceritra yang dibawakan, biasanya kelmpok
penonton ini tidak mementingkan melihat langsung, tetapi memilih tempat yang
aman dan tentram agar bisa konsentrasi dalam menghayati isi lakon. Ketiga
kelompok inilah yang oleh Dede Amung Sutarya dijadikan sebagai suatu bahan
pertimbangan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu pertunjukan
wayang golek purwa yang dibawakan.
Metode lain yang dipergunakan oleh Dede Amung Sutarya dalam hal
mengikat penonton agar tidak cepat meninggalkan tontonannya adalah dengan
teknik penangguhan atau menyisakan permasalahan dari tiap-tiap babak agar
timbul rasa penasaran penonton. Sehingga dengan setia mengikuti babak
selanjutnya meskipun diselingi oleh lagu-lagu dari sinden, hal ini juga
dimanpaatkan oleh dalang untuk beristirahat sejenak. Hal-hal seperti inilah yang
membedakan Dede Amung Sutarya dengan dalang-dalang lainnya dalam suatu
pertunjukan wayang golek purwa, metode-metode semacam ini oleh dalang-
dalang lain tidak diterapkannya sehingga mereka tidak memiliki formulasi
pertunjukan yang baku dan mandiri.
4.4.3. Bentuk-bentuk kereativitas yang diutamakan
Kekeratoran Dede Amung Sutarya dalam menekuni bidangnya sebagai
dalang sangat didasari oleh bakat dan intelegensi yang dimilikinya. Intelegensi
merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam
76
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini
terdapat kemampuan-kemampuan yang spesifik. Kemampuan-kemampuan yang
spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan
tercapainya pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan tertentu setelah melalui
suatu latihan, maka inilah yang disebut bakat (aptitude). Salah satu definisi yang
dikemukakan oleh David Weshler bahwa intelegensi adalah kemempuan uantuk
bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya
secara efektif (Irwanto, 1989:166).
Kretifitas merupakan fenomena sosial budaya disamping sebagai
fenomena psikologi, keduanya memiliki hubungan yang erat. Kreativitas
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui
kreativitas yang dimilikinya, manusia memberikan bobot dan makna terhadap
kehidupannya. S.C.U. Munandar berpendapat bahwa, kretivitas merupakan
kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orsinilitas dalam
berpikir serta kemampuan untuk elaborasi (mengembangkan, memperkaya dan
merinci) suatu gagasan (Soepardi, 1994:22).
Kaitanya dengan pernyataan-pernyataan diatas, maka proses kreatif
seorang dalang dapat berlangsung terkondisikan dengan adanya dorongan dan
pengaruh lingkungan tempat dimana ia tinggal. Pengaruh faktor lingkungan dan
faktor bawaan (garis keturunan), keduanya sangat mentukan seseorang bisa
menjadi kreatif dan berjiwa inovatif. Termasuk sosok Dede Amung Sutarya yang
memiliki bakat seni seperti saudara-saudaranya, namun daya kreatif yang mereka
miliki berbeda dan tingkatannya. Faktor ekternal (personal experience) dan faktor
77
internal (personality characterristic) dapat mempengaruhi daya kreativitas
seseorang. Kreativitas seniman dapat diamati melalui simbol imajinatif yang
dihadirkan lewat karyanya, simbol balam karya seni mereupakan “bahasa” pribadi
yang difungsikan seniman untuk berkomunikasi dengan penikmatnya (Narawati,
1998:80).
Melalui kepekaan daya imajinatif, inovatif, analisis dan interpretasinya
yang kuat, maka Dede Amung Sutarya mencoba mengolah enam aspek atau
elemen dasar teater tradisi (seni padalangan) sebagai wujud kreativitas
kekaryaannya. Ke enam aspek tersebut adalah sebagai berikut:
A. Aspek Sabet (Garapan Wayang)
Salah satu unsur garapan dalang selama pertunjukan berlangsung adalah
sabetan atau lebih dikenal garap wayang, meliputi tarian atau ibingan dan perang
wayang. unsur ini sangat penting untuk menunjukan seseorang dalang sudah
mahir dan layak pentas sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sabetan
dianggap penting, sebab pertunjukan wayang golek adalah pertunjukan yang
memvisualisasikan gerak wayang, artinya wayang golek (boneka kayu) harus
berekting (action) dengan penuh penjiwaan (ekspresif) sesuai tokoh wayang yang
bersangkutan. Apabila dalang tidak mampu menampilkan gerak atau sabetan
wayang dengan penuh keluwesan dan penjiwaan, maka visi pertunjukan melalui
lakon yang dibawakan tidak akan sampai kepada penonton (tidak komiunikatif).
Dengan demikian penonton tidak akan mendapatkan kesan estetis yang
berarti. Sedangkan kesan pertama si penonton terhadap pertunjukan wayang
golek purwa adalah melihat garap wayangnya (sabetan), oleh karena itu dalang
78
harus berusaha menarik rasa simpatis melalui garap atau tarian wayang. Menurut
pengakuan Dede Amung Sutarya prihal penguasaan atau skill dalam memainkan
wayang, bahwa apabila seseorang dalang ingin lebih menjiawi gerakan atau
sabetan wayang yang dimainkannya, maka dalang tersebut akan lebih baik apa
bila mengusai ilmu bela diri tertentu seperti penca silat, karate, gulat dan ilmu-
ilmu bela diri lainnya disamping pengalmannya.
Apabila menengok kebelakang mengenai gaya sabetan wayang golek diera
tahun 1960-an (masa keemasan dalang Amung Sutarya dari dinasti Sutarya),
maka terasa jauh sekali perbedaannya dengan bentuk garap sabet wayang golek
saat ini. Hal ini sangat wajar, sebab saat itu peradaban tuntutan masyarakatnyapun
berbeda dengan zaman teknologi saat ini. Dalang-dalang dahulu kebanyakan agak
mengabaikan sajian sabet wayang, biasanya mereka cenderung lebih
mengutamakan unsur ceritra atau laokon dengan penekanan pada antawacana,
kakawen dan filosofis lakon. Kondisi seperti itu, bagi selera kehidupan
masyarakat modern kiranya sudah sangat tidak sesuai lagi, dalam arti perlu
adanya aspek-aspek penting lainnya yang diharapakan oleh masyarakat, yaitu
wayang sebagai sarana hiburan dengan tanpa mengurangi nilai dan fungsi wayang
yang seutuhnya.
Bagi Dede Amung Sutarya, hal tersebut dipandang sebagai suatu
tantangan yang harus dijawab dengan melalui karya nyata serta didasari niatan
yang baik, agar seni padalangan (wayang golek) dapat tetap sejajar berdampingan
dengan derasnya arus perkembangan dunia iptek. Dalam hal ini Dede Amung
Sutarya selalu berpikir bagai mana nasib wayang golek purwa kedepan, maka
79
salah satunya adalah harus terus meningkatkan kualitas sabetan atau garap
wayang disesuaikan dengan selera yang sedang berlangsung.
Gaya sabetan yang berhasil dikembangkan beliau melalui penampilannya
adalah gerakan wayang dilempar sambil memutar dengan tempo kecepatan yang
tinggi dan sangat cepat, membuat penonton tercengang. Pada adegan tersebut
sangat terlihat ketangkasan dalang dengan teknik keterampilan yang memadai,
disamping itu terlihat pula kekompakan antara gerakan reflek dalang dengan
respon gerakan juru catrik yang berusaha menangkap kembali wayang yang
dilemparkan pada waktu yang tepat pula.
B. Aspek Cerita atau Lakon Wayang
Aspek lain yang harus diperdalam oleh dalang adalah unsur penguasaan
lakon termasuk kekuatan tapsirnya. Seorang dalang dalam membawakan lakon
atau ceritanya, maka secara cermat dan matang dalang harus menyiapkan berbagai
persiapan termasuk kesiapan mental dan kekuatan spiritual yang dimiliki dalang
bersangkutan.
Sumber lakon dalam pewayangan pada prinsipnya sudah tersirat melalui
pakem yang berlaku, seperti Babon Mahabharata, Ramayana dan Babad Lokapala
yang ketiganya merupakan lakon galur. Pakem dalam cerita atau lakon wayang
yang terpenting adalah aspek pancakaki wayang atau silsilah wayang, ini harus
tetap dijungjung tinggi oleh dalang.
Bentuk lakon yang lebih memungkinkan peluang dikembangkan sebagai
sumber kreativitas adalah bentuk lakon sempalan atau carangan. Perlu
80
dikemukakan bahwa bentuk lakon atau cerita dalam pewayangan terbagi tiga,
yaitu lokon galur, sempalan dan carangan. Kelompok bentuk cerita galur adalah
lakon yang bersumber secara utuh kepada babon Ramayana, Mahabharata dan
Babad Lokapala. Sedangkan kelompok bentuk lakon sempalan adalah lakon yang
didalamnya mengambil sebagian dari sumber pokok (galur), artinya lakon
tersebut sudah tidak utuh sepenuhnya bersumber pada cerita pokok, bagian
lainnya merupakan cerita tambahan (pengembangan). Adapun kelompok bentuk
lakon carangan adalah lakon yang sudah lepas sama sekali dari sumber cerita
poko, namun nama-nama tokoh tertentu yang dianggap perlu, tetap mengambil
dari sumber cerita pokok (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Bentuk lakon sempalan dan carangan secara kontekstual bisa dikondisikan
dengan isu-isu hangat yang sedang terjadi, misalnya tentang isu politik, ekonomi
dan sebagainya. Dede Amung Sutarya menanfaatkan peluang tersebut yakni
dengan mengembangkan dan mengemas kembali dengan mencoba menyusun
lakon-lakon baru yang dikondisikan dengan perkembangan zaman terutama selera
atau animo masyarakat sebagai penonton pertunjukan wayang golek.
Salah satu upaya untuk mensiasati penonton agar tidak menimbulkan
kesan monoton dan penuh keingintahuan terhadap jalannya ceritera, maka Dede
Amung Sutarya berupaya menyuguhkan bentuk lakon carangan yang penuh
dengan kandungan nilai yang hakiki, sehingga penonton tercengang dan
penasaran, mau dibagaimanakan arah lakon tersebut. Keadaan seperti itu, terbukti
ketika Dede Amung Sutarya pertama kali menampilkan lakon baru hasil
karangannya, yaitu lakon Cepot Debat. Dimana, inti lakon tersebut menampilkan
81
sosok Astrajingga atau Cepot (Jawa disebut Bagong) yang notabene sebagai tokoh
panakawan atau pengabdi setia terhadap para petinggi negara Amarta (Pandawa),
sehingga keehariannya selalu taat terhadap pemerintah dan atasannya. Namun
pada cerita ini, tokoh Cepot atau Astrajingga tiba-tiba dengan jantannya ia
berterus terang meminta sesuatu terhadap sang raja Darmakusumah, yang
sebenarnya tidak berhak memintanya. Melihat ulah dari Cepot tersebut maka para
petinggi kerajaan terkejut sekali dan sangat marah akan permintaan cepot tersebut,
sehingga dengan cara kasar dan geram Cepot diberi pelajaran untuk
mempertanggung jawabkan kelancangannya itu.
Tetapi sangat tiadak disangka Cepot dengan tenang ia menerima semua
tindakan kasar dari atasannya, hanya tidak seorangpun yang bisa mengalahkan
Cepot yang secara tiba-tiba menjadi sakti mandraguna. Semuanya merasa tidak
mampu, yang pada akhirnya para petinggi negara Amarta meminta pertolongan
kepada Hyang Parmesti Jagatnata (Batara Guru), untuk menaklukan Cepot dari
ulahnya yang spektakuler. Ternyata para Dewa pun tidak berdaya menandingi
keperkasaan Cepot. Klimaks dari cerita Cepot Debat ini, adalah berakhir pada
adegan tumaritis tempat Lurah Semar Badranaya berkumpul sekeluarga.
Inti dari asegan tersebut, Semar bertanya pada kedua putranya, sedang
pergi kemana anak sulungnya Cepot saat ini dimana yang ada pada saat itu yaitu,
Dawala (Petruk) dan Gareng disertai Dewi Setiaragen. Dari semuanya yang ada
tidak mengetahui keberadaan Cepot, namun secara tiba-tiba dikejutkan dengan
sura yang datang dari belakang rumah saat diperiksa ternyata cepot baru saja jatuh
dari bangku setelah tertidur dan bermimpi di siang bolong. Semua merasa kaget,
82
kemudian Cepot menceritakan mimpinya secara spektakuler dengan semua
kesaktiannya menjadikan para juragan-juragannya termasuk dewa sekalipun tidak
bisa berkutik demikian salah satu kecerdikan Dede Amung Sutarya dalam
membuat lakon, untuk menjebak penonton agar penasaran sampai pertunjukan
tuntas.
Diantara banyaknya lakon-lakon yang biasa beliau pentaskan, ada salah
satu lakon yang dianggap terbaik berdasarkan kepuasan Dede Amung Sutarya
yaitu lakon Kumbakarna Gugur. Lakon tersebut serat dengan ajaran moral dan
spiritual yang dalam, sehingga penonton dapat menghayati dan menapsirkannya
dalam realita kehidupan di masyarakat.
Adapun tokoh wayang yang menjadi idolanya adalah Bima dan Gatotkaca
sebagai sosok kesatria yang jujur, tegas dan pemberani. Tokoh Bima menurut
Dede Amung Sutarya adalah tokoh wayang yang bisa lebih dijiwai
(diekspresikan) ketika dimainkan terutama saat adegan perang, untuk
menonjolkan karakter Bima yang perkasa dengan postur tubuh yang memadai.
Sedangkan tokoh wayang yang disukai untuk wayang ibing (wayang menari)
adalah tokoh wayang satria karakter ladak (satria tegak, gagah) seperti Bambang
Arayana. Tokoh lain yang beliau sukai dalam tariannya adalah tokoh wayang
ponggawa lungguh (ponggawa dengan karakter halus) yaitu Gatotkaca (Sutarya,
wawancara, 08/05/2009).
83
C. Aspek bahasa dan sastra pedalangan
Bahasa merupakan sarana yang vital sebagai alat komunikasi seseorang
untuk mengungkapkan maksud tertentu sehingga terjalin komunikasi kedua belah
arah. Begitu pula bahasa dalam pertunjukan wayang golek purwa sangat vital
yang dapat menjadikan pertunjukan komunikatif antara dalang dengan penonton
dan dalang dengan wiyaganya (pengrawit).
Pramasastra, Amardibasa dan Pramakawi adalah tiga aspek garapan
dalang yang termasuk dari 12 Tetekon Padalangan Sunda, dan ketiga aspek
tersebut memiliki hubungan yang erat. Parmasastra dimaksudkan habwa seorang
dalang harus menguasai kaidah-kaidah sastra padalangan yang mencangkup
pembendaharaan bahasa sumber. Amardibasa diartikan bahwa seorang dalang
harus pasih menggunakan bahasa pokok (bahasa Sunda) termasuk penggunaan
undak-usuk basa (tahapan-tahapan penempatan bahasa). Adapun Pramakawi
artinya seorang dalang harus menguasai bahasa Kawi sebagai sumber sastra
padalangan disamping bahasa pokok, yaitu bahasa Sunda (Soepandi, 1988:23).
Ketiga aspek diatas disajikan oleh dalang dalam bentuk antawacana,
nyandra, murwa dan kakawen. Antawacana adalah dialog masing-masing tokoh
wayang, nyandra adalah prolog dalang yang bersifat menerangkan maksud
tertentu dan murwa adalah prolog dalang yang bersifat mempertegas karakter
wayang juga mempertegas suasana pada adegan. Unsur-unaur sastra inilah yang
dianggap esensial dalam pertunjukan wayang golek purwa, sekaligus sebagai
indikator kredibilitas seseorang dalang dalam mengemban tugasnya.
84
Ki dalang Dede Amung Sutarya memiliki gaya tersendiri dalam
menyajikan unsur-unsur terebut, terutama dalam sajian kakwen yang cenderung
memasukan warna suluk pakeliran Jawa. Begitu pula dalam penyajian dialog-
dialog wayang, Dede Amung Sutarya banyak memasukan bahasa-bahasa trend
yang diangkat dari isu-isu hangat serta bahasa-bahasa ilmiah yang dikondisikan.
Kelompok bahasa-bahasa tersebut biasanya diucapkan oleh wayang-wayang
tertentu, agar tidak terlalu bertentangan dengan unsur pakem padalangan.
Salah satu contoh bentuk kakwen yang diambil dari sedon pakeliran Jawa,
kemudian oleh Dede Amung Sutarya diperbaharui dan disesuaikan dengan logat
atau cengkok Sunda, antara lain sebagai berikut;
hanjrah ingkang puspitaning arum kasliring sami ranambrih kasliring sami ranambih sekar gadung kongas gandane, kongas gandane mawe laras rena ing dria Melalui kreativitasnya dalam mengolah sajian kakawen tersebut,
berpengaruh terhadap gaya pertunjukan dalang-dalang lainnya terutama dalang
pemula. Banyak orang berpendapat, bahwa kakawen yang dibawakan oleh dalang
Dede banyak nada sumbangnya, tetapi dari sumbangnya itu banyak pula orang
yang menggandruminya.
Disamping itu Dede memiliki gaya dalam kakawen, juga ia memiliki gaya
murwa (disajikan dalam nyanyian dalang) tersendiri seperti tercantum dibawah
ini:
Dalang : Pundika bubuka panggung rep ngadek purwa sinenggih Wiyaga : Treeeet..... teretet deui hayu batur digawe babarengan Dalang : Purwa mendra-mendra winuwulan Ya sosoroting gantinang pamutus ing cinarita
85
Wiraswara : Sing alakur Wiyaga : Sing jalujur Wiraswara : Sing ariceus Wiyaga : Sing rancingeus Wiraswara : Hirup kumbuh Wiyaga : Sauyunan Wiraswara : Gotong royong Wiyaga : Babarengan Dalang : Tedak saking pundi pundados tandaning cinarita Yakungkung gebang siwa lan tunggal Wiraswara : Ela ela ela ela Wiyaga : Ela ela sama ela Wiraswara : Laksa-laksanakeun Wiyaga : Keluarga Berencana Dalang : Den ayu kaden ayu-ayu Pada tetes tumaretes ingkang tinaretesan Asta, gangga, wira, tanu, kalawan patra Wiraswara : Cimuncang kabanjasari Wiyaga : Kacamatan panumbangan Wiraswara : Ya batur urang ngahiji Wiyaga : Laksanakeun pangwangunan Wiraswara : Pangwangunan Dalang : Asta iku tangan, gangga iku banyu, wira wong lineuwih Tanu mangsi, patra hartosningpun kalam Gung talagung walane aksara jawi sawidak perkawis Binuncang kang tigang dasa Inggih eka kalawan dasa Eka iku sawiji, dasa iku sapuluh, iki jasane para wali Dalang : Salapan ka sapuluh, tunggal wali Kang luhur elmu jembar panalar, sugih pangarti Binekas lan wijaksana weruh sadurung winarah Wiyaga : Masing cararincing, masing-masing cararincing Yu, batur rempung jukung sauyunan Singtaat kana program pamarentah
Dilanjutkan dengan penyajian Nyandra dalam bentuk prolog dalang
sebagai berikut;
Menggah hipun sawiji-wijine aksara kalih dasa, inggih hanacarka datasawala, padajanyanya lan maga batanga. Hananing sikep lanpinterna parapujangga, lajeng aksara kalih dasa iku dipun pecah maring madhapapa. Hanacara tumibaing wetan, datasawala tumubaing kidul, padajayany tumi baling kulon lan magapatanga tumubaing ngalor. Sadina, tutug sadina, sawengi tutug sawengi
86
ngawilang nagri apajang lan apunjung, apajang ikunagara jembar kacapone, apunjung iku nagara dawur wibawane. Lan wonten memada yopasir wukir lohjenawi, pasir iku samudra ukir gunung loh jenawi murwa sarwa ingkang sandang lampangan. Dasar nagara gede ogore padang jagate lan duwur kukuse adoh kakoncarane. Malih kejabi pundika ingkar dadia tuturuning catur bubuka carita, boten wonten kejabi negara... (nama negara dalam lakon). Nagara sampun kaceluk kakandang ewu, kaloka kajanapria, kajamparing angin-angin, kakoncara manca nagara. Demikian penyajian murwa dan nyandra yang dibawakan dalang Dede
sekaligus menjadi ciri khasnya, sebagai dalang dari dinasti Sunarya.
D. Aspek Karawitan atau Musik Pengiring Wayang
Krawitan atau gending iringan wayang merupakan aspek penting untuk
diolah sebagai bagian dari kreativitas. Aspek karawitan merupakan salah satu
sarana untuk menyampaikan rasa estetis kepada penonton, melalui sajian
musikalis dalam mempertegas suasana adegan yang sedang berlangsung.
Dalang harus menyadari sepenuhnya tentang fungsi gamelan terhadap
pertunjukan itu sendiri dan yang terpenting lagi dalang harus memiliki kepekaan
rasa musikalitas terhadap lagu-lagu dan gending-gending yang dibawakan
(amardawalagu). Dengan demikian antara dalang dengan gending atau lagu
pengiring akan komunikatif, teutama peranan dalang akan lebih didukung oleh
kehadiran gending oleh lagu-lagu tersebut. Kebijakan dan ketegasan dalang dalam
mengatur dan membagi jatah waktu, sangatlah penting diterapkan oleh dalang.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar pertunjukan tidak monoton
yang diakibatkan terlalu banyak menyajikan lagu-lagu kepesindenan(Sutarya,
wawancara, 08/05/2009).
87
Menyadari akan pentingnya peranan gamelan atau musik pengiring berupa
gending-gending dan lagu-lagu dalam pertunjukan wayang, maka Dede Amung
Sutarya mensisati dengan cara membuat gamelan selap atau bisa disebut
gamelan multi nada. Dinamakan gamelan multi nada atau masyarakat tradisi
mengistilahkn gamelan selap artinya, dalam satu perangkat gamelan terdapat
beberapa macam laras dan surupan yang seluruhnya berjumlah 7 laras dan
beberapa surupan. Kini rombongan Munggul Pawenang telah memiliki gending
sendiri sebagai ciri khas (trade mark) yang berupa gending-gending intro
(pembuka) dalam lagu-lagu tertentu seperti lagu; Bendrong, Waled dan gending-
gending kemasan dalam sajian Tataluan (Oman, wawancara, 08/05/2008).
Disamping menyajikan lagu-lagu tradisi yang biasa dipergunakan dalam
pertunjukan wayag golek pada umumnya, Munggul Pawenang telah mencoba
memasukan lagu-lagu wanda anyar (kreasi baru) yang sedang trend di
masyarakat. Lagu-lagu tersebut biasanya berasal dari kawih-kaih degung dan
kacapian yang biasa dibawakan oleh penembang-penembang kawakan seperti;
Iyus Wiradirja, Barman Sahyana, Ida Widyawati, Euis Komariah dan lain-
lain(Yoyoh, wawancara, 08/05/2009).
Jenis lagu-lagu yang diangkat diatas, diaransir kembali oleh Padepokan
Munggul Pawenang dengan motif-motif tabuhan yang mengutamakan ritmis-
melodis sehingga lagu tersebut lebih segar dan dinamis, terlebih disajikan dengan
tehnik tabu yang nerjik ekspresif. Biasanya sajian lagu-lagu tersebut ditempatkan
disaat sela-sela antara pergantian babak atau adegan, dimana pada saat itu dalang
beristirahat sejenak untuk mempersiapakan menuju pada adegan berikutnya.
88
Kekompakan atau keterpaduan rombongan seni wayang golek puwa Munggul
Pawenang, sangat didukung oleh persnil-personil pengrawit yang berkualitas
dibidangnya masing-masing. Terutama yang sangat mendukung peranannya
adalah adanya pesinden kawakan Hj. Yoyoh yang memiliki warna suara dan
senggol (cengkok) tersendri, juga didukung oleh wirasuara (pesinden pria) yang
cukup kondang yaitu bapak Eye dan pemain kendang berbakat bapak Oman.
Faktor lainnya yang dianggap mendukung adalah ditunjang oleh sarana peralatan
gamelan yang memadai terutama dengan gamelan selap (gamelan multi nada)
yang terbuat dari jenis logam perunggu kwalitas tinggi buatan Solo Jawa Tengah.
Keadaan hal-hal seperti itulah yang menjadikan rombongan Munggul Pawenang
pimpinan dalang Dede Amung Sutarya lebih menonjol diantara rombongan-
rombongan seni wayang golek lainnya.
E. Aspek Bojegan (banyolan)
Seiring dengan proses percepatan globalisasi yang merambah kepada
berbagai sapek kehidupan, maka sikap dan selera masyarakat pun mengalami
perubahan yang drastis sebagai konsekwensi logis dari evolusi budaya dengan
berbagai dampak problematikanya. Peradaban budaya yang kini sedang memasuki
tatanan masyarakat industri, membawa pengaruh besar terhadap laju
perkembangan seni pertunjukan tradisional yang harus mengimbangi serta
mengkondusifkan dengan selera masyarakat pendukungnya.
Menyadari sepenuhnya terhadap keadaan tatanan masyarakat yang begitu
kompleks, maka Dede Amung Sutarya sebagai seniman praktis seni pedalangan
89
wayang golek purwa berupaya untuk menyesuaikan dengan selera masyarakat
sebagai penonton, agar pertunjukannya dapat diterima dan terjangkau oleh
masyarakat luas. Terlebih dihadapkan dengan budaya masyarakat perkotaan yang
berifat plural, dimana berbagai tata nilai berdampingan, bersaing bahkan
berbenturan satu sama lainnya maka Dede Amung Sutarya sebagai dalang sangat
memperhatikannya, bagaimana cara dan strategi yang harus dijalankan saat
pertunjukan berlangsung. Salah satu kiat dan strateginya adalah dalang Dede
dalam pertunjukannya selalu menghadirkan bojegab (lawakan) yang menarik dan
kontekstual dengan keadaan yang sedang terjadi atau terkait dengan isu hangat.
Dalam pertujukan wayang golek unsur banyolan atau humor adalah
termasuk kepada salah satu dari 12 tetekon padalangan. Lebih jelasnya ke 12
Tetekon padalangan tersebut adalah: Tutug, Enges, Sabet, Banyol, Antawacana,
Renggep, Kawi Raja, Prama Kawi, Prama Sastra, Amardi Basa, Amardawalagu
dan Awi Carita (Soepandi, 1988:17).
Pada penyajiannya banyolan atau humor yan dilakukan oleh dalang terbagi
kedalam dua bentuk, yaitu humor sabet dan humor antawacana (dialog). Humor
sabet adalah bentuk humor yang berupa gerak atau sabet wayang. Sedangkan
humor antawacana adalah bentuk humor yang berupa dialog wayang. Kedua
bentuk humor ini oleh dalang Dede digarap secara matang sehingga menghasilkan
sajian-sajian humor yang menarik. Bentuk-bentuk banyolan yang disjikan oleh
dalang Dede Amung Sutarya, pada prinsipnya merupakan pola ersendiri, sehingga
dari panggung satu ke panggung lainnya selalu ada banyolan yang serupa, tetapi
penonton tidak merasa bosan bahkan banyolan tersebut selalu dinanti. Disamping
90
menyajikan banyolan yang telah terpola, juga selalu menyajikan banyolan yang
spontanitas berlangsung saat itu. Bentuk banyolan seperti ini akan lebih nampak,
sebab yang ikut tertawa tidak hanya penonton tetapi para pengrawitnya ikut
tertawa larut didalamnya, bahan tidak jarang Dede Amung Sutarya sendiri iku
tertawa terbawa emosi yang terjadi (Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Secara khusus dalang Dede Amung Sutarya selalu memunculkan banyolan
yang sifatnya intern, artinya banyolan tersebut hanya dituukan kepada sekitar
pengrawitnya saja, sehingga penonton tidak memahaminya dan yang tertawa
(respon) hanya seputar pengrawit. Banyolan seperti ini sengaja dibuat sebagai
upaya agar para pangrawit tidak mengantuk karena kelelahan terlalu banyak petas.
Topik yang diangkat dalam banyolan khusus tersebut, diambil dari seputar
kejadian-kejadian kecil yang terjadi di kalangan pengrawit, bahkan terkadang
menyudutkan salah seorang pengrawit yang biasana mempunyai sifat yang unik
dari pengrawit lainnya.
Dari keseluruhan bentuk-bentuk banyolan tersebut, secara penyajiannya
tidak ditampikan pada adegan khusus yang terpisah, melainkan selalu muncul
disela-sela tiap bedrip atau adegan. Dengan demikian alur lakon selalu dibumbui
oleh humor-humor segar yang dikondisikan dengan suasana arti adegan tersebut.
Keberhasilan menyajikan humor-humor tersebut pada dasarnya didukung
oleh kelengkapan dan kesempurnaan bentuk-bentuk wayang inovasinya yang
dirancang secara khusus hasil karyanya sendiri degan ragam karakter humoristis.
Bentuk-bentuk wayang kreasi yang dimilikinya sangat lebih memungkinkan untuk
terciptanya bentuk-bentuk humor yang baru dan berpariasi.
91
Bentuk-bentuk gerak humor yang biasa Dede Amung Sutarya tampilkan
memiliki ciri tersendiri, yaitu banyak menampilkan gerakan-gerakan yang cepat
(stakato) tetapi luwes. Gerakan-gerakan tersebut terinsfirasi oleh film-filem
kartun seperti Micky Mouse, Tom & Jerry dan tokoh-tokoh kartun yang lainnya.
Sedangkan untuk bentuk humor dialog, Dede Amung sutarya lebih mengandalkan
kualitas warna suara yang dimilikinya, yang oleh dalang lain susah ditirunya.
Potensi-potensi semacam itulah yang lebih mendukung Dede Amung Sutarya
mahir dalam menyajikan sabetan dan banyolan dengan gaya tersendiri.
F. Aspek Wayang Sebagai Media Pokok
Selain kedua aspek diatas, juga Dede Amung Sutarya melalui daya inovasi
yang kuat, ia berhasil menciptakan bentuk-bentuk wayang baru (bukan wayang
pokok) dengan menggunakan teknik yang praktis seperti wayang yang bisa
menjulurkan lidahnya, wayang bisa bergoyang dan wayang bentuk lainnya
(Sutarya, wawancara, 08/05/2009).
Bentuk karya penciptaan lainnya yang cukup mengundang perhatian
umum, diantaranya jamparing atau perlengkapan memanah, sehingga apabila
salah satu tokoh satria akan memainkan panah senjatanya, maka tokoh tersebut
selalu dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dengan teknik gerak yang
memukau mirip gerakan manusia yang akan memanah.
Menyadari akan pentingnya keutuhan (unity) totalitas pertunjukan
terutama wayang sebagai media pokoknya, maka Dede Amung Sutarya
mengganggap penampilan bentuk tokoh wayang harus dimunculkan terutama
92
busana, asisoris, ketegasan warna cat sesuai dengan karakter tokoh yang
bersangkutan dan bentuk kukirannya.
Dengan demikian apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi maka wayang
ketika masuk pentas akan lebih nampak penampilannya, terlebih dimainkan
dengan menggunakan teknik sabetan yang memukau. Salah satu hasil upaya
pengembangannya dalam memunculkan bentuk pakaian wayang padepokan
munggul pawenang menggunakan kain dodot yang dilengkapi dengan pernak-
pernik warna mas pada setiap wayang tokoh atau wayang pokok. Pada umumnya
dalang-dalang lain apalagi pada generasi sebelum Dede Amung Sutarya tidak
menggunakan kain dodot dalam busana wayang, namun setelah muncul karya
Dede maka dalang-dalang lain berusaha menirunya (Sutarya, wawancara,
08/05/2009).
Melalui bentuk-bentuk kreativitas yang dihasilkan Dede Amung Sutarya
sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada akhirnya masyarakat mengakuinya
bahwa kreativitas dalang Dede Amung Sutarya telah memberikan kontribusi yang
berarti teradap laju perkembangan seni padalangan wayang golek purwa di Tatar
Pasundan (Jawa Barat).