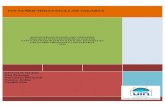Diskusi Kasus Farmasi-Abd.tifoid
-
Upload
zieluphtaz13 -
Category
Documents
-
view
53 -
download
0
description
Transcript of Diskusi Kasus Farmasi-Abd.tifoid

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya
sehingga penyusunan referat ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan
referat ini merupakan salah satu syarat dalam menjalani kepaniteraan klinik di
Laboraturium / UPF Farmasi Fakultas Kedokteran UNISMA / RSUD Dr.
Moewardi Surakarta. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh kepala, dosen pembimbing dan staf Laboratorium / UPF
Farmasi Fakultas Kedokteran UNS / RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
Kami berharap penyusunan referat ini dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya dalam menambah khasanah keilmuan mengenai penyakit typhus
abdominalis. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan
referat ini, untuk itu kami mohon masukan, kritik dan saran yang membangun
demi perbaikan penyusunan referat ini.
Surakarta, Juli 2013

DAFTAR ISI
JUDUL …………………………………………………………………………….i
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………ii
DAFTAR ISI
……………………………………………………………………..iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………………2
BAB III KESIMPULAN ……………………………………………..….…16
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 17
ii

BAB I
PENDAHULUAN
Typhus abdominalis terdapat diseluruh dunia dan penyebarannya tidak
bergantung pada keadaan iklim, tetapi banyak dijumpai di negara-negara sedang
berkembang di daerah tropis. Hal ini disebabkan karena penyediaan air bersih,
sanitasi lingkungan dan kebersihan individu kurang baik. Di Indonesia dapat
ditemukan sepanjang tahun. Insidennya tertinggi didapatkan pada anak-anak
terutama di daerah endemic.
Typhus abdominalis adalah suatu penyakit infeksi akut usus halus oleh
Salmonella typhi. Typhus abdominalis atau demam tifoid merupakan suatu
penyakit endemic di Indonesia. Kelompok penyakit ini mudah menular dan dapat
menyerang banyak orang sehingga menimbulkan wabah. Ada 2 sumber penularan
yaitu pasien dengan tifoid dan carrier. Untuk daerah endemic tranmisi melalui air
yang tercemar. Sedangkan untuk daerah non endemik, penularan paling sering
melalui makanan yang tercemar oleh carrier.
Penatalaksanaan typhus abdominalis meliputi non medikamentosa dan
medikamentosa. Namun alangkah baiknya, jika dilakukan pencegahan dan
pengendalian diantaranya dengan perbaikan sanitasi lingkungan termasuk
pembuangan air limbah dan pemasokan air, sehingga akan menurunkan insiden
dengan tajam.
1

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. DEFINISI
Typhus abdominalis adalah suatu penyakit sistemik akut yang disebabkan
oleh infeksi kuman Salmonella typhi9. Sedangkan menurut Gerald T. Keush
typhus abdominalis adalah suatu infeksi demam sistemik akut yang nyata
pada fagosit mononuclear dan membutuhakan tatanama yang terpisah6.
B. EPIDEMIOLOGI
Typhus abdominalis termasuk penyakit menular yang tercantum dalam
Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Walaupun tercantum
dalam undang-undang wabah dan wajib dilaporkan, namun data yang lengkap
belum ada, sehingga gambaran epidemiologinya belum diketahui secara pasti.
Di Indonesia, jarang dijumpai secara epidemic, tapi lebih sering bersifat
sporadic, terpencar-pencar di suatu daerah dan jarang menimbulkan lebih dari
satu kasus pada orang-orang serumah. Sumber penularan biasanya tidak dapat
ditemukan. Ada 2 sumber penularan Salmonella typhi yaitu pasien dengan
tifoid dan carrier.
Di daerah endemic, tranmisi terjadi melalui air yang tercemar dan
makanan yang tercemar oleh carrier yang merupakan sumber penularn yang
paling sering di daerah non endemik 5.
C. ETIOLOGI
Salmonella adalah basil gram negative, tidak berkapsul, hampir selalu
motil dengan menggunakan flagella peritrikosa, yang menimbulkan dua atau
lebih bentuk antigen H. Kuman ini meragikan glukosa, sehingga terbentuk
dasar asam dan cekungan basa pada agar beri gula tripel ( TSI ). Umumnya
menghasilkan H2S yang dapat terdeteksi sebagai produk reaksi hitam dan
berfungsi awal untuk membedakan isolate dari Shigella, yang juga
2

menimbulkan reaksi TSI basa / asam. Salmonella typhi penyebab utama
demam tifoid atau typhus abdominalis. Beberapa salmonella sangat mudah
beradaptasi pada manusia seperti S.typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B.
sementara sebagian besar spesies beradaptasi pada hewan dan tidak
menyebabkan kesakitan pada manusia. Yang lain menginfeksi baik manusia
dan hewan tingkat rendah, sehingga menyebabkan gastroenteritis atau yang
lebih jarang infeksi terlokalisir, atau septikemik6.
D. PATOFISIOLOGI
Kuman S. typhi masuk tubuh manusia melalui mulut dengan makanan dan
air tercemar. Sebagian kuman dimusnahkan asam lambung. Sebagian lagi
masuk ke usus halus dan mencapai jaringan limfoid plaque Payeri di ileum
terminalis yang hipertropi. Di tempat ini komplikasi perdarahan dan perforasi
intestinal dapat terjadi. Kuman S.typhi kemudian menembus lamina propia
masuk aliran limfe mesenterial, dan mencapai kelenjar limfe mesenterial,
yang juga mengalami hipertropi. Setelah melewati kelenjar-kelenjar limfe ini,
S.typhi masuk aliran darah melalui ductus thoracicus. Kuman-kuman S.typhi
lain mencapai hati melalui sirkulasi portal dari usus. S.typhi bersarang di
plaque Payeri, limpa, hati dan bagian-bagian lain system retikuloendotelial.
Semua disangka demam dan gejala-gejala toksemia pada demam tifoid
disebabkan endotoksemia. Tapi kemudian berdasar penelitian eksperimental
disimpulkan bahwa endotoksemia bukan merupakan penyebab utama demam
dan gejala-gejala toksemia pada typhus abdominalis. Endotoksin S.typhi
berperan pada patogenesis, karena membantu terjadinya proses inflamasi
local pada jaringan tempat S.typhi berkembang biak. Demam pada tifoid
disebabkan karena S.typhi dan endotoksinya merangsang sintesis dan
penglepasan zat pirogen olek leucosis pada jaringan yang meradang5.
3

E. MANIFESTASI KLINIS
Masa tunas berlangsung 10 – 14 hari. Gejala-gejala yang timbul amat
bervariasi. Selain itu, gambaran penyakit bervariasi dari penyakit ringan yang
tidak terdiagnosis sampai gambaran penyakit yang khas dengan komplikasi
dan kematian.
Dalam minggu pertama, keluhan dan gejala serupa dengan penyakit
infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot,
anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut,
batuk, epistaksis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhu badan meningkat.
Dalam minggu kedua, gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam,
bradikardia relative, lidah khas ( kotor di tengah, tepi dan ujung merah serta
tremor ), hepatomegali, splenomegali, meteorismus, gangguan mental berupa
somnolen, stupor, koma, delirium, atau psikosis, roseolae jarang ditemukan
pada orang Indonesia5.
F. DIAGNOSIS
Biakan darah positif memastikan typhus abdominalis, tapi biakan darah
negative tidak menyingkirkan typhus abdominalis. Biakan feces positif
menyokong diagnosis klinis typhus abdominalis5. Biakan feces ini, 75%
positif pada minggu ketiga.
Diagnosis serologis kurang dapat diandalkan dibandingkan biakan.
Sebagian besar pasien dapat mempunyai antibody terhadap antigen O, H, dan
Vi ( tes widal ). Jika tidak mendapatkan imunisasi yang baru, titer antibody
terhadap antigen O ( > 1/ 640 ) adalah sugestif, tapi tidak spesifik selama
salmonella serogrup. Peninggian antibody empat kali lipat pada sediaan
berpasangan adalah criteria yang baik, untuk memastikan diagnosis typhus
abdominalis selama 2 sampai 3 minggu5,6. Jadi pemeriksaan widal dinyatakan
positif apabila :
Titer O widal I 1/ 320 atau
Titer O widal II naik 4 kali atau lebih dibandingkan titer O widal I
atau
4

Titer O widal I ( - ) tapi titer O widal II ( + ) berapapun angkanya
Sedangkan pemeriksaan penunjang lainnya :
Darah perifer lengkap : leucopenia, limfositosis, aneosinofilia
Biakan empedu : tumbuh koloni Salmonella typhi9
G. DIAGNOSIS BANDING
Infeksi virus
Malaria3,9
H. TERAPI
Tujuan pengobatan adalah untuk membasmi infeksi, mengurangi
morbiditas dan mencegah komplikasi 2.
Untuk membasmi infeksi dan mencegah komplikasi, maka pemberian
antibiotika yang tepat adalah hal yang terpenting dan menjadi inti
farmakoterapi terhadap Typhus abdominalis. Antibiotik diberikan secara
empiris bila bukti-bukti klinis menyokong diagnosa typhus abdominalis 2.
Untuk mengurangi morbiditas, pemberian glukokortikoid
(Dexamethasone) dapat diberikan pada pasien yang mengalami demam
toksemik yang berat 1,3. Pemberian harus dengan indikasi dan dosis yang tepat
karena dapat menyebabkan perdarahan dan perforasi usus 3. Pemberian asam
salisilat dan antipiretik lain tidak dianjurkan kaena dapat menyebabkan
perdarahan dan perforasi usus 4 disamping memang tidak banyak berguna 3.
Untuk mengurangi demam dapat dilakukan kompres dengan air hangat3 .
1. Bed rest total, sampai 7 hari bebas panas3.
Maksudnya untuk mencegah terjadinya komplikasi yakni perdarahan
usus atau perforasi usus. Mobilisasi pasien dilakukan secara bertahap,
sesuai dengan kekuatan pasien 5.
2. Diet saring TKTP rendah serat, lunak sampai 7 hari
bebas panas lalu ganti bubur kasar , dan setelah 7 hari ganti dengan nasi3.
Pemberian bubur saring bertujuan untuk menghindari komplikasi
5

perdarahan usus / perforasi usus, karena ada pendapat bahwa usus perlu
diistirahatkan5.
3. Medikamentosa
1.) Antibiotik
Terapi antibiotik merupakan inti dari farmakoterapi dan harus dimulai
jika bukti klinis mendukung gambaran typhus abdominalis 2.
Sejak tahun 1960, telah muncul strain S.typhii yang resisten terhadap
kloramfenicol dan pada tahun 1989, strain S. typhii Multi Drugs
Resistance (MDR) yang kebal terhadap Chloramphenicol, amoxicillin
dan cotrimoxazol muncul dan menyebar di anak benua India dan
beberapa negara di Asia Tenggara. Untuk kasus typhus MDR ini maka
obat pilihan utamanya adalah Flouoroquinolone dan Cepholosporin
generasi ketiga karena kemanjuran serta rendahnya angka kasus relaps
dan carrier 2.
Kloramphenicol terutama digunakan pada daerah-daerah dimana strain
lokal masih sensitif 1,2. Pada kasus Typhus Abdominalis MDR pada
anak, karena penggunaan quinolone tidak dianjurkan, maka
cephalosporine generasi ke tiga menjadi pilihan utama 2.
a. Chloramphenicol
Masih merupakan obat pilihan utama di Indonesia, bekerja
dengan cara berikatan dengan subunit ribosom 50 S bakteri dan
menghambat pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesa protein 2. Efektif untuk bakteri gram positif dan negatif 2,7, namun jika ada
antibiotik lain yang lebih aman, dianjurkan untuk tidak menggunakan
kloramfenikol 7. Saat ini terutama digunakan untuk demam typhoid,
infeksi Salmonella yang lain, serta H. influenzae 7.
Resorpsi dari usus lengkap dan cepat, dengan BA 75-90%.
Distribusi ke jaringan rongga, dan cairan tubuh, kecuali empedu, baik
sekali. Kadar dalam LCS tinggi sekali. PP kurang dari 50%, plasma-t
6

½-nya rata-rata 3 jam. Dalam hati, 90% dirombak menjadi glukoronid
inaktif 8. Ekskresi melalui ginjal dalam bentuk inaktif dan hanya 10%
dalam bentuk utuh 7.
Perbaikan klinis tampak pada hari kedua dan panas mulai turun
pada hari ke 3-5 2,4. Diberikan secara peroral kecuali pasien mengeluh
mual atau diare, dimana dapat diberikan per IV. Pemberian per IM
haruslah dihindari karena menyebabkan penurunan panas yang lambat
serta kadar obat dalam darah kurang memuaskan2.
Efek samping lain yang umum terjadi adalah gangguan lambung
usus, neuropati optis dan perifer, radang lidah dan mulut 8. Efek
samping yang lebih berat yaitu reaksi hematologik berupa depresi
sumsum tulang yang reversibel dan anemia aplastik yang irreversibel 8.
Angka kejadian reaksi hematologik ini adalah 1: 24.000-50.000 7.
Interaksi dengan obat lain :
1. Barbiturat : dapat menyebabkan peningkatan kadar serum barbiturat
sedang kadar serum kloramfenikol menurun sehingga
mengakibatkan toksisitas 2 di samping itu juga memperpendek waktu
paruh kloramfenikol 8.
2. Sulfonil urea : hipoglikemia.
3. Rifampisin : kadar serum kloramfenikol turun.
4. Antikoagulan : peningkatan efek dari antikoagulan.
5. Hydantoin : meningkatkan kadar serum hydantoin.
Penggunaan pada ibu hamil (terutama pada trimester III (aterm atau
dalam persalinan)) dan menyusui tidak dianjurkan karena dapat
menyebabkan sindrom “Grey Baby” 8. Sedang untuk ibu hamil
Trimester I dan II dapat diberikan 3. “Grey Baby Syndrome” juga
dapat terjadi pada pemberian kloramfenikol pada bayi prematur yang
mendapat dosis tinggi. Dosis maksimal untuk bayi kurang dari 1
bulan adalah 25 mg/kgBB/hari 7.
7

b. Tiamfenikol ( Urfamycin )
Dosis dan efektivitas sama dengan chloramphenicol5.
Kelebihan Angka Carrier lebih sedikit pada bakteri yang benar-
benar sensitif
Kekurangan Perbaikan klinis lebih lambat
Kasus relaps lebih banyak.
c. Cotrimoxazol ( Trimetroprim dan Sulfametoksazol )
Dosis untuk orang dewasa adalah 2 x 480 mg sehari, digunakan
sampai 7 hari bebas demam5.
Nama obat Trimethoprim and sulfamethoxazole– Menghambat
pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis
dari asam dihidrofolik. Aktivitas antibakteri dari
TMP –SMZ meliputi bakteri patogen saluran kemih
kecuali Pseudomonas aeruginosa. Sama efektif
seperti chloramphenicol dalam penurunan panas dan
pencegahan relaps. Trimethoprim sendiri juga efektif
pada kelompok kecil pasien.
Dosis Dewasa 6.5-10 mg/kgBB/hari PO bid/tid; dapat diberikan per
IV bila diperlukan; 160 mg TMP/800 mg SMZ PO
setiap 12 jam selama 12-14 hari.
Dosis anak <2 bulan: pemberian tidak dianjurkan
>2 bulan: 15-20 mg/kgBB/hari, berdasarkan pada
TMP, PO tid/qid untuk 14 hari
Kontraindikas
i
Pasien dengan riwayat hipersensitif terhadap obat ini;
anemia megaloblastik pada pasien dengan defisiensi
folat.
Interaksi Obat Dapat meningkatkan Prothrombin Time ada
pemberian bersama dengan heparin (lakukan tes
koagulasi dan penyesuaian dosis bila diberikan
8

bersamaan);pemberian dengan dapsone dapat
meningkatkan kadar serum kedua obat; pemberian
bersama dengan diuretik meningkatkan insiden
trombositopenia purpura pada pasien geriatri; kadar
serum phenytoin dapat meningkat pada pemberian
bersama; dapat mempotensiasi efek dari
methotrexate pada depresi sumsum tulang; respon
hipoglikemik terhadap sulfonylureas dapat meningkat
pada pemberian secara bersamaan; dapat
meningkatkan kadar zidovudine.
Perhatian Hentikan pada timbulnya rash kulit pertama kali atau
tanda reaksi adverse: lakukan kotrol keadaan darah
dengan pemeriksaan Hitung Datrah lengkap secara
rutin, hentikan terapi jika timbul perubahan
hematologis yang signifikan; goiter, diuresis, and
hipoglikemia dapat terjadi pada terapi dengan
sulfonamides; pemberian per IvV yang
berkepanjangan atau dosis yang tinggi dapat
menyebabkan depresi sumsum tulang (jika tanda-
tanda muncul berikan leucovorin 5-15 mg/hari);
perhatian pada defisiensi folat (contoh pada pasien
alkoholisme, geriatri, pasien yang mendapat terapi
antikonvulsan, atau pada pasien dengan sindroma
malabsorbsi); hemoloisis dapat terjadi pada pasien
dengan defisiensi G-6-PD; pasien dengan AIDS dapat
tidak toleran atau merespon pemberian TMP-SMZ;
perhatian pada pasien dengan kerusakan ginjal atau
hepar (lakukan urinanalysis dan tes fungsi renal
selama terapi); pemberian cairan untuk mencegah
terbentuknya kristaluria dan batu saluran kemih.
9

Kelebihan Dapat digunakan pada pasien yang alergi terhadap
Chloraphenicol, Thiamphenicol, dan golongan
Penicillin
Kekurangan Perbaikan klinis lebih lambat
d. Amoxicillin
Dosis yang dianjurkan berkisar 75 – 150 mg / kgBB sehari,
digunakan sampai 7 hari bebas demam5.
Nama obat Amoxicillin– Mempengaruhi sintesis dinding sel
mucopeptides selama multiplikasi aktif,menghasilkan
aktivitas bakterisidal pada bakteri yang sensitif.
Kurang efektif dibandingkan dengan
Chloramphenicoldalam menurunkan panas dan kasus
relaps. Angka Carrier lebih sedikit dibandingkan
antibiotik lain pada bakteri yang benar- benar sensitif.
Biasanya diberikan per oral dengan dosis harian 75-
100 mg/kgBB untuk 14 hari.
Dosis dewasa 1 g PO per 8 jam
Dosis anak 20-50 mg/kg/hari PO dibagi setiap 8 jam selama 14
hari.
Kontra
indikasi
Riwayat hipersensitivitas terhadap golongan
penicillin
Interaksi obat Mengurangi kemanjuran kontrasepsi oral
Perhatian Penyesuaian dosisi pada pasien dengan kerusakan
ginjal; dapat meningkatkan kemungkinan candidiasis
10

Kelebihan Angka Carrier lebih sedikit pada bakteri yang benar-
benar sensitif
Kekurangan Perbaikan klinis lebih lambat
Kasus relaps lebih banyak.
e. Cephalosporin generasi ketiga
Antara lain : cefoperazon, cefriaxon, dan cefotaxim efektif.
11

Nama obat Cefotaxime (Claforan) – menghentikan sintesis
dinding bakteri, yang akan menghambat
pertumbuhan bakteri. Merupakan cephalosporine
dengan spektrum gram negatif. Kemanjuran
terhadap bakteri gram positif kurang. Sangat baik
terhadap S typhi In vitro dan salmonella lain dan
kemanjuran untuk demam typhoid telah diterima.
Hanya tersedia sediaan untuk injeksi per IV. Saat
ini kemunculan infeksi Salmonella domestik yang
resisten terhadap ceftriaxone telah ditemukan.
Dosis
Dewasa
2 g IV setiap 6 jam
Dosis anak 200 mg/kgBB/hari pada dosis terbagi selama 14
hari
bayi dan anak- anak: 50-180 mg/kgBB/hari IV/IM
dosis terbagisetiap 4- 6 jam
>12 tahun: dosis sama dengan dewasa
Kontraindika
si
Pasien dengan riwayat hipersensitivitas
Interaksi
Obat
Probenecid dapat meningkatkan kadar; pemberian
bersama dengan furosemide dan aminoglykoside
dapat meningkatkan toksisitas terhadap ginjal.
Perhatian Sesuaikan dosis pada pasien dengan gagal ginjal;
berhubungan dengan colitis yang parah.
12

Nama obat Ceftriaxone -- Cephalosporin generasi ketiga dengan
aktivitas spektrum luas terhadap gram negatif dan
gram positif; aktivitas invitro sangat baik terhadap S
typhi dan salmonella yang lain.
Dosis Dewasa 1-2 g IV setiap 12 jam
Dosis anak
>7 hari: 25-50 mg/kgBB/hari IV/IM; tidak melebihi
125 mg/hari
Bayi dan anak: 50-75 mg/kgBB/hari IV/IM terbagi
setiap 12 jam; tidak melebihi 2g/ hari
Kontraindikasi Pasien dengan riwayat hipersensitivitas
Interaksi Obat Probenecid dapat meningkatkan kadar; pemberian
bersama dengan ethacrynic acid, furosemide, and
aminoglycoside dapat meningkatkan toksisitas
terhadap ginjal.
Perhatian Sesuaikan dosis pada pasien dengan gagal ginjal;
pseudobiliary lithiasis; diare non–Clostridium
difficile ; ibu menyusui.
13

Nama obat Cefoperazone -- Cephalosporin generasi ketiga
dengan spektrum gram-negatif. Kurang efektif
terhadap organisme gram positif.
Dosis Dewasa 2-4 g/hari dibagi 2 kali sehari; tidak melebihi 12
g/hari
Dosis anak Belum dipastikan, disarankan 100-150 mg/kgBB/hari
dosis terbagi setiap8- 12 jam; tidak melebihi 12 g/hari
Kontraindikas
i
Pasien dengan riwayat hipersensitivitas
Interaksi Obat Probenecid dapat meningkatkan kadar; pemberian
bersama dengan furosemide dan aminoglykoside
dapat meningkatkan toksisitas terhadap ginjal.
Perhatian Sesuaikan dosis pada pasien dengan gagal ginjal;
berhubungan dengan colitis yang parah.
14

f. Quinolon (Flouroquinolone)
Nama obat Ciprofloxacin -- Fluoroquinolone dengan aktivitas
terhadap pseudomonas, streptococci, MRSA,
Staphylococcus epidermidis, dan kebanyakan
organisme gram negatif tapi tidak efektif untuk
kuman anaerobe. Menghambat sintesa DNA bakteri
dan juga pertumbuhannya. Terapi dilanjutkan setelah
tanda dan gejala hilang selama sekurantg- kurangnya
2 hari (biasanya 7-14 hari). Terbukti sangat efektif
untuk demem typhoid dan para typhoid. Panas turun
pada hari ke 3- 5, dan angka kejadian relaps dan
carrier jarang. Quinolone lain (seperti Ofloxacin,
norfloxacin, pefloxacin) biasanya juga efekti. Jika
pasien meneluh mual atau mengalami diare dapat
diberikan per IV. Fluoroquinolone sangat efektif
terhadap strain yang multiresistendan mempunyai
aktivitas antibakteri intraselluler.
Tidak dianjurkan diberikan pada anak dan wanita
hamil karena potensial untuk menyebabkan
kerusakan kartilago pada percobaan terhadap hewan.
Kelebihan Obat pilihan untuk kasus Typus abdominals MDR
Angka carrier dan relaps rendah
Perbaikan klinis lebih cepat
Kekurangan Tidak tersedia dalam sediaan oral
Harga lebih mahal
15

Tetapi arthropati tidak dilaporkan pada penggunaan
asam nalidiksat (quinolon awal yang dikenal
menyebabkan kerusakan sendi yang sama pada
hewan muda) pada anak atau pada anak dengan
fibrosis kistik yang memerlukan pengobatan dosis
tinggi.
Dosis Dewasa 20-30 mg/kgBB/hari bid untuk 14 hari, tapi jangka
pengobatan yang lebih pendek dapat adekuat; 250-
500 mg PO bid untuk 7-14 hari.
Dosis anak <18 tahun: pemberian tidak dianjurkan
>18 tahun: dosis sama dengan dewasa
Kontraindikas
i
Pasien dengan riwayat hipersensitivitas
Interaksi Obat Antasid, garam besi dan seng dapat menurunkan
kadar serum; pemberian antasid 2-4 jam sebelum atau
sesudah meminum flouruquinolone; cimetidine dapat
mempengaruhi metabolisme dari fluoroquinolone;
mengurangi efek terapi dari phenytoin; pemberian
bersama dengan probenesid dapat meningkatkan
konsentrasi serum; dapat mengingkatkan toksisitas
dari theophylline, caffeine, cyclosporine dan digoxine
(monitor kadar digoxine pada pemberian bersama);
dapat meningkatkan efek dari koagulan (monitor PT)
Perhatian Pada terapi yang jangka panjang lakukan evaluasi
periodik terhadam fungsi sistem organ(seperti ginjal,
hepar, dan hematopoetik); sesuaikan dosisi pada
kerusakan fungsi renal; superinfeksi dapat terjadi
pada terapi antibiotik yang berulang atau jangka
panjang.
Kelebihan Angka relaps dan carier lebih sedikit
16

Perbaikan klinis lebih cepat
Obat pilihan untuk kasus Typus abdominalis MDR
Kekurangan Tidak dapat diberikan untuk anak usia dibawah 18
tahun
Harga lebih mahal
2.) Simptomatik
Pemberian obat Parasetamol berguna untuk menurunkan demam
dan mengurangi nyeri. Mekanisme kerjanya dengan hambatan
terhadap enzim siklooksigenase (COX) dan penelitian terbaru
menunjukkan bahwa obat ini lebih selektif menghambat COX-2.
Meskipun mempunyai aktifitas antipiretik, analgesik, tetapi
aktifitas antiinflamasinya sangat lemah karena dibatasi beberapa
faktor,salah satunya adalah tingginya kadar peroksida di lokasi
inflamasi. Hal lain, karena selektifitas hambatannya pada COX-2
sehingga obat ini tidak menghambat aktifitas tromboksan yang
merupakan zat pembekuan darah.
3.) Cairan
Ringer laktat: cairan yang diberikan untuk mengatasi dehidrasi
dengan mengembalikan keseimbangan elektrolit. Kontra indikasi:
hipermatremia, kelainan ginjal, kerusakan sel hati,laktat asidosis.
I. PROGNOSIS
Terapi yang cocok, terutama jika pasien perlu dirawat secara medis pada
stadium dini, sangat berhasil. Angka kematian dibawah 1%, dan hanya
sedikit penyulit yang terjadi6.
17

BAB III
KESIMPULAN
Typhus abdominalis merupakan infeksi akut usus halus oleh Salmonellae
typhii dan mudah menular. Adapun penularannya melalui pasien dengan typhoid
dan carier. Manifestasi klinis bervariasi dari yang ringan sampai dapat
menimbulkan kematian. Diagnosa pasti ditegakkan dengan biakan empedu yang
ditandai dengan tumbuhnya koloni Salmonellae typhii.
Pada kasus diatas diberikan terapi non medikamentosa dan medikamentosa
yang meliputi:
1. Bedrest total untuk mencegah
komplikasi perdarahan usus atau perforasi usus.
2. Diet saring TKTP rendah
serat dan lunak untuk mengistirahatkan usus
3. Pemberian antibiotik untuk
menghilangkan infeksi, mengurangi morbiditas dan mencegah
komplikasi.
4. Pemberian obat simptomatik
untuk mengatasi nyeri dan demam.
5. Pemberian infus RL untuk
mencegah dehidrasi dan nutrisi.
18

Pasien Typhus abdominalis harus segera ditangani karena jika tidak ,
endotoksin kuman akan meluas dan menyebabkan komlikasi bahkan kematian,
sehingga penderita perlu dirawat. Dengan penanganan yang cepat maka reiko
terjadinya komplikasi dan kematian dapat diminimalkan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Butterton, JR., Calderwood, SB., Acute Infectious Diarrheal Disease
and Bacterial Food Poisoning. In Harrison Principles of Internal
Medicine 15-Ed, McGraw- Hill, 2002: 83
2. Corales, R., Typhoid Fever , www.emedicine.com, 2004
3. Hermawan, AG. Bed Side Teaching Ilmu Penyakit Dalam. Edisi
ke-2. Yayasan Kesuma Islam Kedokteran. Surakarta. 1999
4. Hermawan, AG., Sumandjar, T., Penanganan penderita Demam
Tifoid Dewasa Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Dalam: Protap
IPD-FK UNS RSUD Dr. Moewardi, SMF Ilmu Penyakit Dalam FK
UNS- RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 2004 : 115-116
5. Juwono, R. Demam Tifoid. Dalam : Buku Ajar Ilmu Penyakit
Dalam. Jilid I. Edisi ke-3. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. 1999 : 435-
441
6. Keusch, GT. Salmonellosis. Dalam : Harrison Prinsip-prinsip Ilmu
Penyakit Dalam. Jakarta : EGC. 1999 : 755-758
19

7. Setiabudy, I., Kunadi, R., Antimikroba. Dalam Farmakologi dan
Terapi Edisi Ke-4, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, 1995 : 651- 653
8. Tjay, TH., Rahardja, K., Obat- Obat Penting: Khasiat,
Penggunaan , dan Efek- Efek Sampingnya Edisi ke- 5. Jakarta: PT
Elex Media Komputindo. 2001: 64-82
9. Zulkarnain, I., Nelwan, RHH., Pohan, GT., Demam Tifoid.
Dalam : Pedoman Diagnosis dan Terapi di Bidang Ilmu Penyakit
Dalam. Jakarta : Bagian Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 2001 : 256-259
20