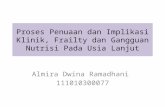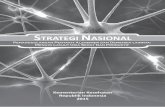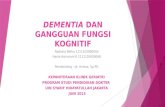Diskusi Kasus Gangguan Kognitif
-
Upload
nurraisya-mutiyani -
Category
Documents
-
view
84 -
download
10
Transcript of Diskusi Kasus Gangguan Kognitif

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
KEPANITRAAN KLINIK SMF GERIATRIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATANUIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2014
DISUSUN OLEH:Eko PrayogaNurraisya MutiyaniNuzma AnbiaTarikh Azis
unu

BAB I
STATUS PASIEN
1.1 Identitas Pasien
- Nama pasien : Ny.YB
- Usia : 60 tahun
- Jenis kelamin : perempuan
- Alamat : Jakarta
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Status perkawinan : Menikah
- Nama Kerabat Terdekat : Tn.A
- Tgl. masuk RS : 2010
- Jumlah anak kandung : 4 orang
- Agama : Kristen protestan
- Suku bangsa : Batak
- Pendidikan Formal : Sarjana
1.2 Anamnesis
Keluhan Utama
pasien mengeluhkan bosan dan ingin keluar dari panti wherda
Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien masuk panti sejak 3 tahun yang lalu. Masuk panti bukan karena keinginan
pribadi, melainkan ketika pukul 4 pagi diatas jembatan penyebrangan di Menteng,
pasien ditangkap petugas lalu dibawa ke panti. Sebelumnya pasien mengaku bekerja
sebagai pegawai BPOM di Medan, Sumatra Utara. Kemudian ke Jakarta setelah
pensiun. Awalnya pasien berada dikamar cempaka selama 2 tahun, lalu dipindahkan ke
kamar tulip. Pasien mengatakan bahwa kamar tersebut merupakan penjara dan merasa
ingin sekali keluar dari panti.
2

Pasien mengaku 1 bulan lagi akan keluar dari penjara/ panti. pasien mengaku
berusia 83 tahun. Anaknya, yaitu Tn.Andri yang diakui sebagai polisi sering
mengunjungi pasien.
Keluhan pusing, muntah, mual, demam tidak ada. nyeri perut ada, disekitar ulu hati.
Biasanya timbul apabila pasien tidak makan. Sudah diberi obat dipanti tapi pasien lupa
nama dan jenis obat tersebut. Pasien mengaku SMA di blok m (SMA 6), selain itu
pasien juga mengaku dari kecil sampai pensiun hanya tinggal di Medan. Pasien juga
tidak dapat menyebutkan secara pasti tempat kuliahnya, dan menyebutkan 3 kampus
berbeda. keluhan cepat lelah ada, dan pasien mengaku berat badannya menurun.
BAB dan BAK lancar, jernih, tidak nyeri. Gangguan pendengaran (-),
pandangan kabur (-), Sesak napas (-), Nyeri dada (-) Nyeri ulu hati (-), kembung (-),
Bengkak di kaki (-). Keluhan disertai dengan mata agak kabur ketika membaca, pasien
telah menggunakan kacamata baca.
Riwayat Penyakit Dahulu
Tidak terdapat riwayat penyakit keras/ penyakit kronis. Tidak pernah dirawat di
RS. Riwayat operasi tidak ada. Riwayat hipertensi dan diabetes tidak ada. Namun
pasien mengaku sering pusing apabila tidak makan.
Riwayat Penyakit Keluarga
Ayah pasien sudah meninggal. Riwayat hipertensi dan kencing manis tidak ada.
Sedangkan ibu pasien juga sudah meninggal dengan Riwayat hipertensi dan kencing
manis tidak diketahui.
Riwayat kebiasaan
Pasien mengaku mengkonsumsi makanan sehari sebanyak 2 kali dari apa yang
disediakan oleh panti. Biasanya pasien konsumsi nasi sebanyak 2 piring, disertai lauk
protein nabati berupa tempe, tahu, terkadang proten hewani seperti daging atau telur.
3

Pasien juga mengaku sering memakan mie yang dibeli dikoperasi dengan frekuensi 1
minggu 3 kali.
Riwayat Penggunaan Obat
Saat ini pasien sedang tidak mengonsumsi obat apapun.
Riwayat sosial
Sering mengikuti aktivitas di panti. Keahliannya menjahit gorden dan
menjualnya dipanti. Pasien mengaku tidak sering ke gereja untuk kegiatan agama,
Pasien mengatakan bahwa natal jatuh tanggal 23 Juni dan bukan 25 desember. Namun
pasien dapat menyebutkan nama bulan dengan benar secara berurutan.
Analisis keuangan
Pasien tidak bekerja hanya menjalankan aktifitasnya dipanti saja. Hanya
mendapatkan penghasilan dari hasil menjahit gorden dipanti. Biasanya penghasilan
yang didapatkan 50-70 ribu perbulan. Namun pasien mengaku anak pertamanya sering
mengunjungi pasien, sekitar 3 bulan sekali dan terkadang memberikan uang saku.
Analisa Lingkungan Rumah
Kamar pasien berukuran kurang lebih 7x4 meter, dihuni oleh 20 lansi dengan
lantai keramik, terdapat penerangan dan jendela yang cukup. Terdapat 1 toilet dalam
kamar tersebut.
Analisis gizi
• Karbohidrat : nasi 1 piring 3 X/ hari, roti dan mie instan minimal 1x/minggu.
• Buah, protein nabati, hewani, dan susu selalu dikonsumsi setiap hari.
4

Kajian MNA
5

Analisis Gizi
Analisis Gizi
• BB ideal = 90% x (153-100)x1 kg = 47,7 kg
• IMT = 43 : 1,532 = 18,36 (BB kurang)
• Kebutuhan kalori basal = 25 kal x 60,3 kg = 1192,5 kal
• Kebutuhan aktivitas (+20%)= 20% x 1192,5= 238,5 kal
• Kebutuhan usia (-10%) = 10% x 1809 = 119,25 kal
Total kebutuhan kalori/hari = 1192,5+ 238,5 – 119,25= 1311, 5 kal
Distribusi makanan
• Karbohidrat 60%=60% x 1131,5 = 678,6 kal= 169,5 ≈ 170 gr (678,6kal :
4gr/kal karbohidrat)
• Protein 20%=20%x 1131,5= 226,2 kal = 56,55 ≈ 57gr (226,2 kal: 4 gr/kal
protein)
• Lemak 20%= 20%x 1131,5= 226,2 kal= 25, 13 gr (226,2 kal: 9gr/kal
lemak)
MMSE
No. Pertanyaan Nilai
Orientasi
1. Sekarang ini (tahun), (musim), (bulan), (tanggal), (hari) 2
2. Kita berada di mana? (negara), (propinsi), (kota), (RS), (lt) 3
Registrasi
6

3. Sebutkan 3 objek: tiap satu detik, pasien disuruh mengulangi nama ketiga
objek tadi. Nilai 1 untuk tiap nama objek yang disebutkan benar. Ulangi
lagi sampai pasien menyebut dengan benar: buku, pensil, kertas
3
Atensi dan Kalkulasi
4. Pengurangan 100 dengan 7. Nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar.
Hentikan setelah 5 jawaban, atau eja secara terbalik kata “B A G U S”
(nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan).
5
Mengenal Kembali
5. Pasien disuruh menyebut kembali 3 nama objek di atas tadi 2
Bahasa
6. Pasien disuruh menyebut: pensil, buku 1
7. Pasien disuruh mengulangi kata: “Jika tidak, dan atau tapi” 1
8. Pasien disuruh melakukan perintah: “Ambil kertas itu dengan tangan anda,
lipatlah menjadi 2, dan letakkan di lantai”
2
Bahasa
9. Pasien disuruh membaca, kemudian melakukan perintah kalimat
“pejamkan mata”
1
10. Pasien disuruh menulis dengan spontan (terlampir) 1
11. Pasien disuruh menggambar bentuk (terlampir) 0
TOTAL 23
7

AMT (Abreviated Mental Test)
• Umur 83 tahun (0)
• Waktu siang (1)
• Alamat tidak bisa menjawab (0)
• Tahun ini 2014 (1)
• Saat ini berada dimana panti werda (1)
• Dokternya (1)
• Tahun kemerdekaan RI 1945 (1)
• Nama presiden RI SBY (1)
• Anak terkahir namanya (0)
• Menghitung terbalik (1)
Berdasarkan hasil MMSE dan AMT pada pasien ini mengalami gangguan demensia
ringan (skor 7)
Penapisan Depresi
Uraian Jawaban
Puas dengan hidup Anda Y T T
Meninggalkan banyak kegiatan Y T T
Merasa kehidupan kosong Y T Y
Sering merasa bosan Y T Y
Mempunyai semangat Y T Y
Takut sesuatu yang buruk terjadi Y T Y
8

pada Anda
Merasa bahagia pada sebagian
besar hidup Anda
Y T Y
Sering merasa tidak berdaya Y T Y
Lebih senang di rumah daripada di
luar
Y T T
Mempunyai masalah daya ingat Y T T
Hidup Anda saat ini menyenangkan Y T T
Merasa tidak berharga Y T T
Merasa penuh semangat Y T Y
Merasa tidak ada ada harapan Y T T
Orang lain lebih baik dari Anda Y T T
SKOR 5
Hasil : Pasien mengalami depresi
Indeks ADL, Barthel
9

Hasil : pasien tergolong Mandiri
Berg Balance Scale: tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia melakukan
1.3 Pemeriksaan Fisik
• Kesadaran : Compos Mentis
• Keadaan Umum : Tampak normal
• Status Gizi : BB 45 TB 151 BMI
• Tanda Vital : TD duduk : 100/70 mmHg
TD berbaring: 100/70 mmHg
TD berdiri : 110/90mmHg
Nadi : 80 kali/menit, reguler, isi cukup
Pernapasan : 14 kali/menit, reguler
Suhu : 37,3o C
Status Generalis :
• Kepala: normocephal, rambut hitam sebagian putih beruban, rambut tidak
mudah dicabut
10

• Mata: sklera ikterik (-/-), konjugtiva anemis (-/-), AVOD 6/60, AVOS 6/60
• Hidung: deviasi septum(-), sekret (-), hipertrofi konka (-), pernafasan cuping
hidung (-)
• Gigi & mulut: higiene baik, gigi tidak komplit , gigi palsu (-), Lendir (-), faring
hiperemi (-) tonsil T1-T1.
• Telinga: normotia, tidak hiperemis, liang telinga lapang, sekret -/-
• Leher: tidak ada pembesaran KGB, JVP 5-2 cmH2O
• Paru :
• I: Pergerakan simetris saat statis dan dinamis, retraksi (-)
• P: Vocal Fremitus simetris, nyeri tekan (-) di kedua lapang paru
• P: Sonor dikedua lapang paru
• A: Vesikuler +/+, Wheezing -/-, Ronkhi -/-
• Jantung:
• I: Iktus kordis terlihat 2 jari medial LMCS ICS 5
• P: Iktus kordis 2 jari medial LMCS ICS 5
• P: Batas jantung kanan relatif ICS 5 parasternal kanan, batas jantung kiri
relatif 2 jari medial LMCS ICS 5
• A: Bunyi Jantung I & II normal, Murmur -, Gallop -
• Abdomen:
• I: Datar, lemas
• P: Supel, nyeri tekan (+), defanse muscular (-), hepatosplenomegali (-)
• P: Shifting Dullness -
• A: Bising Usus + normal
• Kulit: Ikterik (-), kering, dekubitus (-)
• Punggung : deformitas (-), gibus (-)
• KGB : tidak ada pembesaran KGB
• Ekstermitas: perfusi baik, edema (-), akral hangat, sianosis (-) CRT <2 detik
Ekstermitas atas Bahu Siku Wrist (hand) Jari tangan
Deformitas -/- -/- -/- -/-
11

Nyeri -/- -/- -/- -/-
Bejolan -/- -/- -/- -/-
ROM
- - Fleksi
- - Ekstensi
- - Abduksi
- - adduksi
- - Endorotasi
- - Eksorotasi
- - Pronasi
- - Supinasi
Pasif :
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Pasif :
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Pasif :
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Pasif :
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Ekstremitas bawah Paha Lutut Wrist Foot Jari kaki
Deformitas -/- -/- -/- -/-
Nyeri -/- -/- -/- -/-
Bejolan -/- -/- -/- -/-
ROM
- - Fleksi
- - Ekstensi
- - Abduksi
- - adduksi
- - Endorotasi
- - Eksorotasi
- - Pronasi
- - Supinasi
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
Max/Max
1.4 Pemeriksaan Status Neurologis
GCS : E4M5V6
TRM : Kaku kuduk (-), Brudzinski I (- / -), Laseque >70o/>70o, Kernig
>135o/>135o, Brudzinski II (- / - )
12

Nervus kranialis
N.I – Olfaktori : Normosmia +/+
N.II- Optikus
Acies Visus : OD 6/60 OS 6/60
Visus Campus : Sama dengan pemeriksa
Buta warna : Tidak diperiksa
Funduskopi : Tidak diperiksa
N II & III
Pupil Bulat Isokhor Ø 3mm/3mm
OD OS
RCL + +
RCTL + +
N. III (okulomotor), IV (tokhlearis) dan VI (absusen)
1) NIII
Ptosis : (-)
Akomodasi : (+)
2) N.III .IV,VI
Kedudukan bola mata : Normal +/+
Eksoftalmus : (-)/(-)
Pergerakan bola mata :
OD OS
13

3) N. V (Trigeminus)
1. a. Cab. Motorik
Otot pengunyah kuat dan simetris kanan dengan kiri
b. Cab. Sensorik
Opthalmicus : baik/baik
Maksilaris : baik/baik
Mandibularis : baik/baik
2. Refleks Refleks Kornea: +/+
3. Refleks Masetter: +
4) N. VII (Fasialis)
a. Motorik orbitofrontal : Wajah simetris, dapat mengangkat alis dengan
simetris
b. Motorik orbikularis oculi : Dapat menutup mata dengan sempurna pada
kedua kelopak mata
c. Motorik orbikularis oris : Sudut bibir dan plica nasolabial sinistra lebih
datar daripada dekstra saat pasien diminta untuk mneyeringai, ridak ada
kebocoran pipi dekstra et sinistra saat pasien diminta menggembungkan
pipi dan pemeriksa menekan pipi pasien
d. Pengecapan tidak diperiksa
5) N.VIII (Vestibulochoclear)
Pendengaran normal
6) N. IX (glosofaringeus), X (vagus)
a. Arcus faring : simetris
b. Uvula : di tengah
7) N. XI (Aksesorius)
a. M. sternokleidomastoideus : dapat menahan tahanan simetris kanan kiri
b. M. trapezius : dapat menahan tahanan simetris kanan kiri
8) N. XII (Hipoglosus)
Lidah saat statis dan dinamin tidak ada deviasi, tidak ada tremor atau
fasikulasi
14

Kekuatan lidah simetris
Trofi : Eutrofi
Tonus : Normotonus
Sistem Motorik:
Ekstremitas : Atas 5555 | 4444
Bawah 5555 | 4444
Reflek Fisiologis
Biseps : +2 |+ 2
Triseps : +2 |+2
Patella : +2 |+ 2
Achiles: +2 |+ 2
Reflek Patologi
Hoffman tromer : - | -
Babinski : - | -
Chaddok : - | -
Oppenheim : - | -
Schafer : - | -
Gonda : - | -
Rossolimo : - | -
Mendel-Bechterew : - | -
Klonus Patella : - | -
Klonus Achiles : - | -
Gerakan Involunter
Tremor : - | -
Khorea : - | -
Mioklonik : - | -
Fungsi Serebelar
Ataksia : - | -
15

Jari-jari : - | -
Jari-hidung : - | -
Fungsi Bicara:
Disfoni (-)
Disatria (+)
Fungsi Menelan:
Disfagia (-)
16

BAB II
DIAGNOSIS DAN PENGKAJIAN MASALAH
2.1 Diagnosa
Diagnosa Medis
malnutrisi
Diagnoa Psikiatri
1. Gangguan depresi ringan tanpa gejala somatik
2. Gangguan demensia ringan
Diagnosa Fungsional :
Impairment : kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari
Disability : menarik diri dari teman-teman sekamar
Handicap : (-)
17
Penampilan: perempuan, sesuai usia, perawatan diri baikPerilaku dan psikomotorik: normalMood: baikAfek: datar atau tumpulProses pikir: asosiasi longgarIsi pikir: normalGangguan persepsi:(-)

2.2 Sindrom Geriatri
Intelectual impairment
Inanition
Insomnia
Isolation
impecunity
Tatalaksana
antikolinesterase : donepezil 5 mg/ hari. 10 mg/ hari setelah 1 bulan pemakaian
vitamin E : 250 IU/ hari
golongan SSRI: fluoxatine: 20 mg / hari.
2.3 Pengkajian Masalah
1. Gangguan depresi
Gangguan depresi dibawah naungan mood. Sedangkan definisi mood
merupakan subjektivitas peresapan emosi yang dialami, dapat diutarakan oleh
pasien dan terpantau oleh orang lain; termasuk sebagai contoh adalah depresi,
elasi, dan marah. Kepustakaan lain mengemukakan mood adalah perasaan, atau
“perasaan hati” seseorang, khususnya yang dihayati secara bathiniah. Sedangkan
gangguan depresi, tanda dan gejalanya berupa keadaan emosional yang ditandai
kesedihan yang sangat, perasaan bersalah dan tidak berharga, menarik diri dari
orang lain, kehilangan minat untuk tidur, seks, serta hal-hal menyenangkan
18

lainnya.Orang yang depresi mungkin: Sulit konsentrasi, bicaranya pelan, kata-
kata monoton, suara pelan, memilih untuk sendirian dan berdiam diri.
Sedangkan untuk dapat mendiagnosis gangguan depresi dapat digunakan
DSM-IV, yaitu dengan kriteria:
a. Depresi ringan
Sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi; ditambah
sekurang-kurangnya 2 dari gejala lainnya
Tidak boleh ada gejala berat diantaranya
Lama seluruh episode berlangsung sekurang-kurangnya sekitar 2 minggu
Hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa
dilakukannya
b. Depresi sedang
Sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala utama depresi; ditambah
sekurang-kurangnya 3 (dan sebaiknya 4) dari gejala lainnya
Lama seluruh episode berlangsung minimum sekitar 2 minggu
Menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan, dan
urusan rumah tangga
c. Depresi berat tanpa gejala psikotik
Semua 3 gejala utama depresi harus ada
Ditambah sekurang-kurangnya 4 dari gejala lainnya, dan beberapa
diantaranya harus berintensitas berat
Bila ada gejala penting (misalnya agitasi atau retardasi psikomotorik)
yang mencolok, maka pasien mungkin tidak mau atau tidak mampu untuk
melaporkan banyak gejalanya secara rinci. Dalam hal demikian, penilaian secara
menyeluruh terhadap episode depresi berat masih dapat dibenarkan.
Episode depresif biasanya harus berlangsung sekurang-kurangnya 2
minggu, akan tetapi jika gejala amat berat dan beronset sangat cepat, maka
19

masih dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang dari
2 minggu.
Sangat tidak mungkin pasien mampu meneruskan kegiatan social,
pekerjaan, atau urusan rumah tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas.
d. Depresi berat dengan gejala psikotik
Episode depresi berat yang memenuhi kriteria menurut depresi berat tanpa gejala
psikotik
Disertai waham, halusinasi, atau stupor depresif. Waham biasanya melibatkan ide
tentang dosa, kemisikinan, atau malapetaka yang mengancam, dan pasien merasa
bertanggung jawab atas hal itu. Halusinasi auditorik atau olfatorik biasanya berupa
suara yang menghina atau menuduh, atau bau kotoran atau daging busuk. Retardasi
psikomotorik yang berat dapat menuju pada stupor. Jika diperlukan, waham atau
halusinasi dapat ditentukan sebagai serasi atau tidak serasi dengan afek (mood
congruent).
Gejala utama:
Afek depresif
Kehilangan minat dan kegembiraan
Kekurangan energi yang menuju meningkatnya keadaan mudha lelah (rasa lelah
yang nyata sesudah kerja sedikit saja) dan menurunnya aktivitas.
Gejala lainnya:
Konsentrasi dan perhatian berkurang
Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
Gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna
Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis
Gagasan bunuh diri atau membunuh
Tidur tertanggu
Nafsu makan berkurang
20

Pada pasien Ny.Y, 2 dari gejala utama sudah ada gejalanya yaitu merasa
kekurangan energy, mudah lelah, dan menurunnya aktivitas, serta afek depresif.
Sedangkan untuk gejala tambahan terdapat rasa gangguan tidur, dan pandangan
masa depan yang suram. Jadi dari gejala yang dialami pasien, masuk dalam
kategori depresi ringan. Dari hasil pemeriksaan screening depresi dengan
menggunakan Geriatric Depretion Scale (GDS), didapatkan angka 5 yang sudah
menunjukkan kemungkinan pasien mengalami depresi. Dari pemeriksaan
anamnesis, pasien menyatakan tidak ingin tinggal dipanti, karena panti dianggapnya
sebagai penjara. Hal tersebut dirasakan pasien sejak masuk panti, yaitu 3 tahun lalu.
Hal itu menunjukkan bahwa depresi yang dirasakan pasien sudah timbul lebih dari 2
minggu dan masuk dalam kriteria mendiagnosis depresi.
Pada pasien lanjut usia (lansia) dapat terjadi gangguan kognitif yang
mengalami depresi disebut juga sindrom demensia dari depresia (pseudodemensia),
yang mudah rancu dengan demensia sebenarnya. Pada demensia sebenarnya,
gangguan intelektual biasanya bersifat umum dan deficit bersifat menetap. Pada
pseudodemensia, didapatkan deficit pada atensi dan konsentrasi yang bervariasi.
Dibandingkan pasien yang menderita demensia sebenarnya, pasien dengan
pseudodemensia lebih jarang memiliki gangguan bahas san berkonfabulasi. Apabila
mereka tidak yakin, mereka cenderung mengatakan “saya tidak tahu”, kesulitan
daya ingat lebih terbatas pada free-recall. Dibandingkan dengan recall yang
dilakukan pada tes memori. Pseudodemensia terjadi pada kira-kira 15% pasien
lansia yang mengalami depresi, sedang 25-50% pasien dengan demensia mengalami
depresi.
Pada depresi sedang, pasien terganggu saat mengerjakan pekerjaan yang
kompleks. Pasien dengan depresi berat, sering memperlihatkan gejala yang mirip
demensia (pseudodemensia). Hal ini diperkirakan karena pada pasien yang
menderita depresi kronis terjadi juga kerusakan hipokampus karena peningkatan
kadar steroid endogen.
2. Demensia
21

Demensia adalah suatu kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami
kemunduran. Kondisi ini dapat ditandai dengan keadaan seseorang sering lupa akan
sesuatu, keliru, adanya perubahan kepribadian, dan emosi yang naik-turun atau labil.
Banyak penyebab yang membuat seseorang mengalami Demensia, umumnya karena
penyakit-penyakit kronik seperti Stroke dan Parkinson. Namun diketahui bahwa
penyebab utama seseorang mengalami Demensia adalah penyakit Alzheimer.
Penyakit Alzheimer sendiri adalah suatu kondisi sel-sel saraf di otak mati, yang
mengakibatkan sinyal-sinyal otak sulit tersalurkan dengan baik. Hampir sama dengan
Dimensia, Alzheimer juga membuat penderitanya mengalami gangguan pada ingatan,
penilaian, dan sulit berpikir. Hingga saat ini, terdapat 1 juta penderita Demensia di
Indonesia. Menurut penelitian, pada tahun 2009 lalu kasus penderita Demensia
bertambah satu orang setiap 4 detiknya. Menurut perkiraan, pada tahun 2050 akan ada
sekitar 3 juta penderita Demensia di Indonesia atau 3,5 persen dari total penduduk.
Sementara menurut perkiraan, pada tahun 2050 mendatang kasus Demensia di Asia
Pasifik akan mencapai 20 juta insiden pertahun.
Pasien dengan demensia harus mempunyai gangguan memori selain
kemampuan mental lainseperti berpikir abstrak, penilaian, kepribadian, bahasa, praktis,
dan visiospasial. Pada kasus pasien kali ini, dari anamnesis didapatkan bukti terjadinya
penurunan memori, dimana pasien tidak mampu menyebutkan secara jelas jumlah anak
pasien, alamat rumah terdahulunya, tidak dapat menyebutkan dengan benar nama bulan,
dan kehilangan kacamata akibat lupa. Namun pasien masih dapat kembali lagi kekamar
panti dan masih hafal jalan dipanti. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kognitif dan
neuropsikiatrik dengan menggunakan the minimental status examination (MMSE),
didapatkan nilai 23, yang menunjukkan gejala demensia ringan.
Selain itu, terdapat kriteria diagnosis demensia berdasarkan DSM IV:
A. Munculnya deficit kognitif multiple yang bermanifestasi pada kedua keadaan berikut:
22

1. Gangguan memori (ketidakmampuan untuk mempelajari informasi baru atau untuk
mengingat informasi yang baru saja dipelajari)
2. Satu (atau lebih) gangguan berikut:
Afasia (gangguan berbahasa)
Apraksia (ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas motorik walaupun fungsi
motorik masih normal)
Agnosia (kegagalan untuk mengenali atau mengidentifikasi benda walaupun fungsi
sensorik masih normal
Gangguan fungsi eksekutif (seperti merencanakan, mengorganisasi, berpikir runut,
dan berpikir absktrak)
B. Deficit kognitif yang terdapat pada kriteria A1 dan A2 menyebabkan gangguan
bermakna pada fungsi social dan okupasi serta menunjukkan penurunan yang bermakna
dari fungsi sebelumnya. Deficit yang terjadi bukan terjadi khusus saat timbulnya
delirium.
Pada pasien Ny.Y, ditemukan gejala penurunan gangguan memori dan gangguan
fungsi eksekutif, sehingga dapat didiagnosis demensia berdasarkan DSM IV.
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
DEFINISI DEPRESI
Depresi adalah suatu perasaan sedih yang sangat mendalam yang terjadi setelah
mengalami suatu peristiwa dramatis atau menyedihkan, misalnya kehilangan seseorang
yang disayangi. Seseorang bisa jatuh dalam kondisi depresi jika ia terus-menerus
memikirkan kejadian pahit, menyakitkan, keterpurukan dan peristiwa sedih yang
menimpanya dalam waktu lama melebihi waktu normal bagi kebanyakan orang.1
23

Depresi dapat terjadi pada siapa pun, golongan mana pun, keadaan sosial
ekonomi apa pun, serta pada usia berapa pun. Tetapi umumnya depresi mulai timbul
pada usia 20 sampai 40 tahun-an. Depresi biasanya berlangsung selama 6-9 bulan, dan
sekitar 15-20% penderita berlangsung sampai 2 tahun atau lebih. Episode depresi
cenderung berulang sebanyak beberapa kali dalam kehidupan seseorang.
Menurut National Institute of Mental Health (dalam Siswanto, 2002), gangguan
depresi dipahami sebagai suatu penyakit tubuh yang menyeluruh (whole-body), yang
meliputi tubuh, suasana perasaan dan pikiran. Ini berpengaruh terhadap cara makan dan
tidur, cara seseorang merasa mengenai dirinya sendiri dan cara orang berpikir mengenai
sesuatu. Gangguan depresi tidak sama dengan suasana murung (blue mood). Ini juga
tidak sama dengan kelemahan pribadi atau suatu kondisi yang dapat dikehendaki atau
diharapkan berlaku. Orang dengan penyakit depresi tidak dapat begitu saja “memaksa
diri mereka sendiri” dan menjadi lebih baik.
MANIFESTASI KLINIS
Depresi muncul secara bertahap selama beberapa hari atau minggu. Penderita
tampak tenang dan sedih atau mudah tersinggung dan cemas datang silih berganti, lama
– lama gejala tersebut bertambah berat dan menetap. Gejala depresi yang paling serius
adalah pemikiran tentang bunuh diri. Banyak penderita yang ingin mati atau merasa
mereka sangat tidak berguna sehingga mereka sepantasnya mati. Sebanyak 15%
penderita menunjukkan perilaku bunuh diri. Rencana bunuh diri merupakan keadaan
yang sangat berbahaya sehingga penderitanya harus dirawat dan diawasi secara ketat,
sampai keinginan bunuh dirinya hilang.
Banyak penderita yang tidak dapat merasakan emosi sedih, gembira, dan senang
secara normal. Dari perspektifnya dunia tampak semakin suram, tidak ada kehidupan,
dan menjemukan. Berpikir, berbicaram dan kegiatan umum lainnya semakin jarang
dilakukan, dan akhirnya akan menghentikan seluruh aktivitasnya.
Pikirannya dipenuhi oleh perasaan bersalah dan memiliki gagasan untuk
menghancurkan dirinya sendiri, serta tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan daya
24

ingat menurun. Mereka sering bimbang dan menarik diri, merasa tidak berdaya dan
putus asa serta berpikir tentang kematian dan bunuh diri.
Penderita mengalami kesulitan tidur dan seringkali terbangun, terutama pada
dini hari. Gairah dan kenikmatan seksualnya hilang. Nafsu makan yang buruk dan
penurunan berat badan kadang menyebabkan penderita menjadi kurus dan siklus
menstruasinya terganggu atau berhenti. Pada sekitar 20% penderita, gejalanya lebih
ringan tetapi berlangsung selama bertahun – tahun bahkan berpuluh-puluh tahun.
Apabila depresinya ringanm penderita akan makan sangat banyak sehingga terjadi
penambahan berat badan berlebihanm terjadi kegemukan.1,2
MACAM DAN BENTUK DEPRESI
Depresi dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:
1. Depresi Situasional, merupakan depresi yang terjadi setelah mengalami suatu
peristiwa sedih yang berat/traumatik, seperti kematian orang yang dicintai, di-
PHK, kehilangan mata pencaharian mendadak, bangkrut, dan sebagainya.
2. Holiday Blues, merupakan depresi yang terjadi ketika sedang berlibur atau
merayakan suatu momen sedih, mengenang peristiwa masa lalu yang pahit, lalu
timbul depresi. Depresi jenis ini biasanya bersifat sementara, begitu momen
perasaan khususnya selesai, ia akan kembali pulih.
3. Depresi Endogenous, merupakan depresi tanpa penyebab yang pasti, tiba – tiba
saja muncul tanpa diketahui faktor pencetusnya.
4. Depresi Vegetatif, merupakan depresi yang membuat penderita cenderung
menarik diri dari pergaulan, jarang berbicara, tidak mau makan dan tidak mau
tidur. Yang dilakukannya hanya melamun dan bingung.
5. Depresi Agitatif, diketahui dari penderitanya yang tampak sangat gelisah, cemas,
meremas – remas tangannya serta banyak bicara, hiperaktif, tidak bisa diam.
6. Depresi Disrtimik, depresi jenis ini berhubungan dengan perubahan kepribadian
yang nyata. Penderita tampak lusuh, muram, pesimis, tidak suka bercanda atau
tidak mampu menikmati kesenangan. Ia berlaku pasif, menarik diri (introvert),
25

curiga, suka mengkritik, dan sering menyesali dirinya sendiri. Pikiran penderita
dipenuhi dengan kekurangan, kegagalan, dan hal – hal negatif, bahkan
menikmati kegagalannya.
Beberapa penderita mengeluhkan penyakit fisik, berupa sakit dan nyeri,
ketakutan akan musibah, atau takut menjadi gila. Penderita juga merasa bahwa
mereka menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang memalukan
(misalnya kanker atau penyakit menular seksual, AIDS/HIV) dan berpikir telah
menularkannya kepada orang lain sehingga timbul rasa bersalah dan penyelasan
mendalam.
F 34.1 Distimia
Pedoman Diagnostik
• Ciri esensial ialah efek depresif yang berlangsung sangat lama yang tidak
pernah atau jarang sekali cukup parah untuk memenuhi kriteria gangguan
depresif berulang ringan atau sedang (F33.0 atau F33.1)
• Biasanya mulai pada usia dini masa dewasa dab berlangsung sekurang-
kurangnya beberapa tahun, kadang-kadang untuk jangka waktu tidak terbatas.
Jika onsetnya pada usia lanjut, gangguan ini seringkali merupakan kelanjutan
suatu episode depresif tersendiri (F32.) dan berhubungan dengan masa
berkabung atau stress lain yang tampak jelas.
7. Depresi Psikotik. Sekitar 15 % penderita terutama pada depresi berat, akan
mengalami delusi (keyakinan yang salah terhadap sesuatu) atau halusinasi
(melihat atau mendengar sesuatu yang sesungguhnya tidak ada). Mereka yakin
telah berbuat dosa atau kejahatan besar yang tidak dapat diampuni atau
mendengar suara-suara yang menuduh mereka telah melakukan berbagai
perbuatan asusila yang tidak senonoh atau suara-suara yang mengutuk mereka
supaya mati. Kadang penderita membayangkan bahwa mereka melihat peti mati
dan orang-orang yang sudah meninggal. Perasaan tidak aman dan tidak berharga
26

bisa menyebabkan depresi yang sangat berat pada penderita yang yakin bahwa
mereka diawasi dan dihukum.1,2,3
KRITERIA DIAGNOSIS
(Menurut PPDGJ III)
1. Episode Depresif
Pada semua tiga variasi dari episode depresif khas yang tercantum di
bawah ini: ringan, sedang dan berat, individu biasanya menderita suasana
perasaan (mood) yang depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan
berkurangnya energy yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan
berkurangnya aktivitas. Biasanya ada rasa lelah yang nyata sesudah kerja
sedikit saja. Gejala lazim lainnya adalah Konsentrasi dan perhatian
berkurang
a. Harga diri dan kepercayaan diri berkurang
b. Gagasan tentang perasaan bersalah dan tidak berguna (bahkan pada
episode tipe ringan sekalipun)
c. Pandangan masa depan yang suram dan pesimistis
d. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri
e. Tidur terganggu
f. Nafsu makan berkurang
Untuk episode depresif dari ketiga-tiganya tingkat keparahan,
biasanya diperlukan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk penegakkan
diagnosis, akan tetapi periode lebih pendek dapat dibenarkan jika gejala luar
biasa beratnya dan berlangsung cepat
F32.0 Episode depresif ringan
Suasana perasaan mood yang depresif, kehilangan minat dan
kesenangan, dan mudah menjadi lelah biasanya dipandang sebagai gejala
27

depresi yang paling khas; sekurang-kurangnya dua dari ini, ditambah
sekurang-kurangnya dua gejala lazim di atas harus ada untuk menegakkan
diagnosis pasti. Tidak boleh ada gejala yang berat di antaranya. Lamanya
seluruh episode berlansung ialah sekurang-kurangnya sekitar 2 minggu
Individu yang mengalami episode depresif ringan biasanya resah tentang
gejalanya dan agak sukar baginya untuk meneruskan pekerjaan biasa dan
kegiatan social, namun mungkin ia tidak akan berhenti berfungsi sama
sekali
F32.1 Episode depresif sedang
Sekurang-kurangnya harus ada 2 dari 3 gejala yang paling khas
yang ditentukan untuk episode depresif ringan, ditambah sekurang-
kurangnya tiga (dan sebaiknya empat) gejala lainnya. Beberapa gejala
mungkin tampil amat menyolok, namun ini tidak esensial apabila secara
keseluruhan ada cukup banyak variasi gejalanya. Lamanya seluruh episode
berlangsung minimal sekitar 2 minggu Individu dengan episode depresif
taraf; sedang biasanya menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan
kegiatan sosial, pekerjaan dan urusan rumah tangga.
F32.2 Episode depresif berat tanpa gejala psikotik
Pada episode depresif berat, penderita biasanya menunjukkan
ketegangan atau kegelisahan yang amat nyata, kecuali apabila retardasi
merupakan ciri terkemuka. Kehilangan harga diri dan perasaan dirinya tak
berguna mungkin mencolok, dan bunuh diri merupakan bahaya nyata
terutama pada beberapa kasus berat. Anggapan di sini ialah bahwa sindrom
somatik hampir selalu ada pada episode dpresif berat.
Semua tiga gejala khas yang ditentukan untuk episode depresif
ringan dan sedang harus ada, ditambah sekurang-kurangnya empat gejala
28

lainnya, dan beberapa diantaranya harus berintensitas berat. Namun, apabila
gejala penting (misalnya agitasi atau retardasi) menyolok, maka pasien
mungkin tidak mau atau tidak mampu utnuk melaporkan banyak gejalanya
secara terinci. Dalam hal demikian, penentuan menyeluruh dalam
subkategori episode berat masih dapat dibenarkan. Episode depresif
biasanya seharusnya berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu, akan tetapi
jika gejala amat berat dan beronset sangat cepat, maka mungkin dibenarkan
untuk menegakkan diagnosis dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Selama episode depresif berat, sangat tidak mungkin penderita
akan mampu meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah
tangga, kecuali pada taraf yang sangat terbatas.
Kategori ini hendaknya digunakan hanya untuk episode depresif
berat tunggal tanpa gejala psikotik; untuk episode selanjutnya, harus
digunakan subkategori dari gangguan depresif berulang.
F32.3 Episode depresif berat dengan gejala psikotik
Episode depresif berat yang memenuhi kriteria menurut F32.2
terssebut di atas, disertai waham, halusinasi atau stupor depresif. Wahamnya
biasanya melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan atau malapetaka yang
mengancam, dan pasien dapat merasa bertanggung jawab atas hal itu.
Halusinasi auditorik atau olfaktorik biasanya berupa suara yang menghina
atau menuduh atau bau kotoran atau daging membusuk. Retardasi
psikomotor yang berat dapat menuju pada stupor. Jika diperlukan, waham
atau halusinasi dapat ditentukan sebagai serasi atau tidak serasi dengan
suasana perasaan (mood).
Diagnosis banding. Stupor depresif perlu dibedakan dari
skizofrenia katatonik, stupor disosiatif, dan bentuk stupor organik lainnya.
Kategori ini hendaknya hanya digunakan untuk episode depresif berat
tunggal dengan gejala psikotik; untuk episode selanjutnya harus digunakan
subkategori gangguan depresif berulang.
29

TERAPI
Terapi Apabila seorang penderita sudah terdiagnosa menderita
gangguan depresi mayor, maka tindakan terapi bisa dilakukan. Biasanya,
dokter akan bekerjasama dengan penderita untuk menentukan terapi yang
paling sesuai. Diperkirakan hampir 80% dari penderita dengan gangguan
depresi mayor bisa diterapi dengan baik, tetapi keberhasilan terapi
bergantung kepada terapi yang dipilih (Bjornlund, 2010). Penggunaan obat
untuk mengurangi gejala (simptomatis) dan psikoterapi telah terbukti efektif
dalam mengobati gangguan depresi mayor, samada secara sendirian
maupun kombinasi (Halverson, 2011).
Penggunaan obat antidepresan merupakan terapi pertama untuk penderita
gangguan depresi mayor dewasa dengan rekuren dan persisten.
Antidepresan bekerja dengan cara menormalkan kembali neurotransmitter
yang memberi efek pada mood seseorang, biasanya neurotransmitter
serotonin dan norepinefrin. Ada juga obat antidepresan yang bekerja pada
neurotransmitter dopamine (National Institute of Mental Health, 2008).
Obat yang paling sering digunakan adalah selective serotonin reuptake
inhibitors (SSRIs). SSRIs meningkatkan jumlah neurotransmitter serotonin
dengan cara menghambat reuptake kembali serotonin ke sel presinaps.
Hasilnya, jumlah serotonin di synaptic cleft yang akan berikatan dengan
reseptor akan meningkat. Contoh obat yang digunakan adalah fluoxetine
(Prozac), paroxetine (Paxil) dan sertraline (Zoloft). SSRIs paling sering
digunakan
3.2 Demensia
3.2 Demensia
Klasifikasi demensia. Demensia terbagi atas 2 dimensi:
Menurut umur; terbagi atas:
30

Demensia senilis onset > 65 tahun
Demensia presenilis < 65 tahun
Menurut level kortikal:
Demensia kortikal
Demensia subkortikal
Klasifikasi lain yang berdasarkan korelasi gejala klinik dengan patologi-
anatomisnya
1. Anterior : Frontal premotor cortex
Perubahan behavior, kehilangan kontrol, anti sosial, reaksi lambat.
2. Posterior: lobus parietal dan temporal
Gangguan kognitif: memori dan bahasa, akan tetapi behaviour relatif baik.
3. Subkortikal: apatis, forgetful, lamban, adanya gangguan gerak.
4. Kortikal: gangguan fungsi luhur; afasia, agnosia, apraksia.
Pemeriksaan demensia
Diagnosis klinis tetap merupakan pendekatan yang paling baik karena sampai
saat ini belum ada pemeriksaan elektrofisiologis, neuro imaging dan pemeriksaan lain
untuk menegakkan demensia secara pasti. Beberapa langkah praktis yang dapat
dilakukan antara lain :
1. Riwayat medik umum
Perlu ditanyakan apakah penyandang mengalami gangguan medik yang dapat
menyebabkan demensia seperti hipotiroidism, neoplasma, infeksi kronik. Penyakit
jantung koroner, gangguan katup jantung, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes dan
arteriosklerosis perifer mengarah ke demensia vaskular. Pada saat wawancara
biasanya pada penderita demensia sering menoleh yang disebut head turning sign.
2. Riwayat neurologi umum
Tujuan anamnesis riwayat neurologi adalah untuk mengetahui kondisi-kondisi
khusus penyebab demensia seperti riwayat stroke, TIA, trauma kapitis, infeksi
susunan saraf pusat, riwayat epilepsi dan operasi otak karena tumor atau
31

hidrosefalus. Gejala penyerta demensia seperti gangguan motorik, sensorik,
gangguan berjalan, nyeri kepala saat awitan demesia lebih mengindikasikan
kelainan struktural dari pada sebab degeneratif.
3. Riwayat neurobehavioral
Anamnesa kelainan neurobehavioral penting untuk diagnosis demensia atau
tidaknya seseorang. Ini meliputi komponen memori. (memori jangka pendek dan
memori jangka panjang) orientasi ruang dan waktu, kesulitan bahasa, fungsi
eksekutif, kemampuan mengenal wajah orang, bepergian, mengurus uang dan
membuat keputusan.
4. Riwayat psikiatrik
Riwayat psikiatrik berguna untuk menentukan apakah penyandang pernah
mengalami gangguan psikiatrik sebelumnya. Perlu ditekankan ada tidaknya riwayat
depresi, psikosis, perubahan kepribadian, tingkah laku agresif, delusi, halusinasi,
dan pikiran paranoid. Gangguan depresi juga dapat menurunkan fungsi kognitif, hal
ini disebut pseudodemensia.
5. Riwayat keracunan, nutrisi dan obat-obatan
Intoksikasi aluminium telah lama dikaitkan dengan ensefalopati toksik dan
gangguan kognitif walaupun laporan yang ada masih inkonsisten. Defisiensi nutrisi,
alkoholism kronik perlu menjadi pertimbangan walau tidak spesifik untuk demensia
Alzheimer. Perlu diketahui bahwa anti depresan golongan trisiklik dan anti
kolinergik dapat menurunkan fungsi kognitif.
6. Riwayat keluarga
Pemeriksaan harus menggali kemungkinan insiden demensia di keluarga,
terutama hubungan keluarga langsung, atau penyakit neurologik, psikiatrik.
7. Pemeriksaan objektif
Pemeriksaan untuk deteksi demensia harus meliputi pemeriksaan fisik umum,
pemeriksaan neurologis, pemeriksaan neuropsikologis, pemeriksaan status
fungsional dan pemeriksaan psikiatrik.
32

Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan laboratorium rutin
Pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan begitu diagnosis klinis demensia ditegakkan
untuk membantu pencarian etiologi demensia khususnya pada demensia reversible,
walaupun 50% penyandang demensia adalah demensia Alzheimer dengan hasil
laboratorium normal, pemeriksaan laboratorium rutin sebaiknya dilakukan. Pemeriksaan
laboratorium yang rutin dikerjakan antara lain: pemeriksaan darah lengkap, urinalisis,
elektrolit serum, kalsium darah, ureum, fungsi hati, hormone tiroid, kadar asam folat.
Imaging
Computed Tomography (CT) scan dan MRI (Magnetic Resonance Imaging) telah
menjadi pemeriksaan rutin dalam pemeriksaan demensia walaupun hasilnya masih
dipertanyakan.
Pemeriksaan EEG
Electroencephalogram (EEG) tidak memberikan gambaran spesifik dan pada sebagian
besar EEG adalah normal. Pada Alzheimer stadium lanjut dapat memberi gambaran
perlambatan difus dan kompleks periodik.
Pemeriksaan cairan otak
Pungsi lumbal diindikasikan bila klinis dijumpai awitan demensia akut, penyandang
dengan imunosupresan, dijumpai rangsangan meningen dan panas, demensia presentasi
atipikal, hidrosefalus normotensif, tes sifilis (+), penyengatan meningeal pada CT scan.
Pemeriksaan genetika
Apolipoprotein E (APOE) adalah suatu protein pengangkut lipid polimorfik yang
memiliki 3 allel yaitu epsilon 2, epsilon 3, dan epsilon 4. setiap allel mengkode bentuk
APOE yang berbeda. Meningkatnya frekuensi epsilon 4 diantara penyandang demensia
33

Alzheimer tipe awitan lambat atau tipe sporadik menyebabkan pemakaian genotif
APOE epsilon 4 sebagai penanda semakin meningkat.
Diagnosa banding demensia
Delirium
Delirium adalah keadaan akut dan serius, dapat mengancam jiwa. Dapat disebabkan
oleh berbagai penyakit, gangguan metabolik dan reaksi obat.
Delirium
Awitan akut dengan waktu awitan
diketahui dengan tepat
Perjalanan klinis akut, berlangsung
sampai berhari-hari sampai mingguan
Biasanya reversibel
Disorientasi terjadi pada fase awal
penyakit
Fluktuasi dari jam kejam
Perubahan fisiologis yang nyata
Tingkat kesadaran yang berfluktuasi
Gangguan siklus tidur-bangun bervariasi
dari jam ke jam
Gangguan psikomotor jelas terjadi pada
fase awal
Demensia
Awitan tidak jelas dengan waktu awitan
tidak diketahui
Perjalanan klinis perlahan, bertahap dan
progresif memburuk
Biasanya irreversible
Disorientasi terjadi pada fase lanjut
Fluktuasi ringan dari hari ke hari
Perubahan fisiologis tidak begitu nyata
Rentang waktu atensi normal
Gangguan siklus tidur-bangun bervariasi
dari siang ke malam
Gangguan psikomotor terjadi pada fase
lanjut
Pseudodemensia
34

Depresi dapat mempengaruhi status kognisi penyandang, oleh sebab itu sebelum
mencari etiologi demensia perlu dipastikan apakah penyandang mengalami demensia
atau pseudodemensia karena depresi.
Gambaran klinis Pseudodemensia Demensia
Awitan (onset)
Mood /tingkah laku
Pandangan tentang diri sendiri
Keluhan terkait
Durasi
Alasan konsultasi
Riwayat hidup sebelumnya
Akut dengan
perubahaan tingkah
laku
Banyak keluhan;
seperti tidak dapat
melakukan test tetapi
hasil test objektif
baik
Jelek
Ansietas, insomnia,
anoreksia
Bervariasi dapat
berhenti spontan/
setelah terapi
Rujukan sendiri
Riwayat psikiatri
Perlahan, berbulan-
bulan
Test neuropsikologis
jelek tetapi penyandang
berusaha
meminimalkan/merasio
n aliasasi
kekurangannya
Normal
Jarang, kadang-kadang
insomnia
Keluhan progresif
perlahan dalam
berbulan-bulan-
bertahun
Penyandang dibawa
oleh keluarga yang
merasakan perubahan
memori, kepribadian
dan tingkah laku
35

Tidak jarang ditemukan
riwayat keluarga
dengan demensia
Pemeriksaan neuropsikologis
Pemeriksaan neuropsikologis meliputi pemeriksaan status mental, aktivitas
sehari-hari / fungsional dan aspek kognitif lainnya. .(Asosiasi Alzheimer
Indonesia,2003). Pemeriksaan neuropsikologis penting untuk sebagai penambahan
pemeriksaan demensia, terutama pemeriksaan untuk fungsi kognitif, minimal yang
mencakup atensi, memori, bahasa, konstruksi visuospatial, kalkulasi dan problem
solving. Pemeriksaan neuropsikologi sangat berguna terutama pada kasus yang sangat
ringanuntuk membedakan proses ketuaan atau proses depresi. Sebaiknya syarat
pemeriksaan neuropsikologis memenuhi syarat sebagai berikut: mampu menyaring
secara cepat suatu populasi , mampu mengukur progresifitas penyakit yang telah
diindentifikaskan demensia.
Sebagai suatu esesmen awal pemeriksaan Status Mental Mini (MMSE) adalah
test yang paling banyak dipakai. tetapi sensitif untuk mendeteksi gangguan memori
ringan.
Pemeriksaan status mental MMSE Folstein adalah test yang paling sering
dipakai saat ini, penilaian dengan nilai maksimal 30 cukup baik dalam mendeteksi
gangguan kognisi, menetapkan data dasar dan memantau penurunan kognisi dalam
kurun waktu tertentu. Nilai di bawah 27 dianggap abnormal dan mengindikasikan
gangguan kognisi yang signifikan pada penderita berpendidikan tinggi.
36

Penyandang dengan pendidikan yang rendah dengan nilai MMSE paling rendah
24 masih dianggap normal, namun nilai yang rendah ini mengidentifikasikan resiko
untuk demensia. (Asosiasi Alzheimer Indonesia,2003). Pada penelitian Crum R.M 1993
didapatkan median skor MMSE adalah 29 untuk usia 18-24 tahun, median skor 25
untuk yang > 80 tahun, dan median skor 29 untuk yang lama pendidikannya >9 tahun,
26 untuk yang berpendidikan 5-8 tahun dan 22 untuk yang berpendidikan 0-4 tahun.
Clinical Dementia Rating (CDR) merupakan suatu pemeriksaan umum pada demensia
dan sering digunakan dan ini juga merupakan suatu metode yang dapat
Menilai derajat demensia ke dalam beberapa tingkatan. (Burns,2002). Penilaian
fungsi kognitif pada CDR berdasarkan 6 kategori antara lain gangguan memori,
orientasi, pengambilan keputusan, aktivitas sosial/masyarakat, pekerjaan rumah dan
hobi, perawatan diri. Nilai yang dapat pada pemeriksaan ini adalah merupakan suatu
derajat penilaian fungsi kognitif yaitu; Nilai 0, untuk orang normal tanpa gangguan
kognitif. Nilai 0,5, untuk Quenstionable dementia. Nilai 1, menggambarkan derajat
demensia ringan, Nilai 2, menggambarkan suatu derajat demensia sedang dan nilai 3,
menggambarkan suatu derajat demensia yang berat.
PENATALAKSANAAN
Pada prinsipnya penatalaksanaan gangguan prilaku dan demensia dapat dibagi dalam
terapi medikamentosa dan nonmedikamentosa.
Terapi medikamentosa
Terapi obat-obatan diberikan untuk mengatasi faktor penyebab dan mencegah atau
memperlambat perkembangan demensia. Pada kasus demensia lanjut, terapi obat-obatan
tidak untuk mengobati penyebab melainkan ditujukan untuk meminimalkan gejala
psikologis dan gangguan prilaku yang terjadi. Beberapa obat-obatan dapat digolongkan
menjadi:
a. Neurotropika: pyritinol, piracetam, sabeluzole
37

b. Ca-antagonis: nimodipine, citicholine, cinnarizine, pentoxiphiline, pantoyl GABA
c. Acethylcholinesterase inhibitor: tacrine, donopezil, galantamine, rivastigmin,
memantine
Obat-obat lain dapat diberikan sesuai dengan gejala akibat gangguan psikologis dan
perilaku seperti:
a. Antipsikotik tipikal: haloperidol
b. Antipsikotik atipikal: clozapine, risperidone, olanzapine, quetiapine
c. Anxiolitik: clobazam, lorazepam, buspirone, trazodone dan sebagainya.
d. Antidepresan: amitriptilin, tofranil, asendin, SSRI.
e. Mood stabilizer: carbamazepine, divalproex, neurontin dan sebagainya
Terapi nonmedikamentosa
Intervensi nonfarmakologis harus dilakukan secara holistic meliputi lingkungan,
psikologis, kemampuan bahasa dan lain-lain. Intervensi psikologis dapat berupa
psikoterapi untuk mengurangi kecemasan, memberikan rasa aman dan ketenangan baik
dalam bentuk psikoterapi individual, kelompok maupun keluarga. Lingkungan tempat
tinggal juga perlu mendapat perhatian agar memberikan cukup kenyamanan serta
keamanan bagi penderita. Warna, bentuk, bahan, fasilitas seyogyanya disesuaikan untuk
mendukung program yang akan dilaksankan. Pendekatan lain meliputi adat, budaya,
keagamaan, pengembangan kesukaan/ hobi juga biasa dilakukan untuk memaksimalkan
potensi yang ada pada penderita sekaligus memberikan keselarasan dengan sisitem
sosial yang ada. Untuk caregiver diperlukan dukungan mental, pengembangan
kemampuan adaptasi, peningkatan kemandirian dan kemampuan menerima kenyataan.
Meskipun seorang individu dengan demensia harus selalu berada di bawah
perawatan medis, anggota keluarga idealnya menangani sebagian besar perawatan
sehari-hari. Perawatan medis harus fokus pada mengoptimalkan kesehatan individu dan
kualitas hidup sementara anggota keluarga membantu mengatasi dengan banyak
tantangan untuk merawat anggota keluarga dengan demensia. Perawatan medis
tergantung pada kondisi yang mendasari, tapi paling sering terdiri dari obat-obatan dan
perawatan nonmedikamentosa seperti terapi perilaku.Penghilangan stigma dan
diskriminasi secara sosial terutama pada daerah-daerah yang lebih cenderung
38

materialistik menjadi penting untuk memberikan kenyamanan secara psikologis bagi
lansia. International Labour Organization serta WHO menganjurkan pemerintah untuk
memasukkan beberapa prinsip dalam program nasional, diantaranya:
A. Kebebasan
1. Para lansia harus mendapatkan akses yang baik terhadap makanan, air, perlindungan,
pakaian, serta kesehatan melalui ketersediaan pendapatan, dukungan keluarga dan
masyarakat serta kemandirian.
2. Para lansia harus memiliki kesempatan untuk bekerja atau memiliki akses pada
kesempatan yang memungkinkan mereka mendapatkan sumber pendapatan
3. Lansia harus dapat berpartisipasi dalam memutuskan kapan dan bagaimana akan
meninggalkan pekerjaannya
4. Para lansia harus mendapatkan akses untuk pendidikan dan program-program
pelatihan
5. Para lansia harus mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang aman
dan bisa menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya
6. Lansia harus bisa tetap tinggal dirumah selama mungkin
B. Partisipasi
1. Para lansia harus tetap tergabung dalam masyarakat, berpartisipasi secara aktif dalam
formulasi dan implementasi kebijaksanaan yang secara langsung mempengaruhi
kesejahteraannya dan membagikan pengetahuan dan ketrampilan mereka dengan
generasi berikutnya.
2. Lansia harus mampu mencari dan mencari kesempatan untuk melayani masyarakat
sebagai sukarelawan sesuai dengan kemampuannya.
3. Para lansia harus selalu dalam kerjasama dengan lansia lainnya.
C. Perhatian
1. Para lansia harus mendapatlkan keuntungan dari keluarga dan masyarakat serta
pelindungan selaras dengan setiap sistem sosial dari nilai-nilai budaya.
39

2. Para lansia harus memiliki akses pada pelayanan kesehatan untuk membantu mereka
menjaga atau mengembalikan tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan emosional serta
untuk mencegah keterlambatan penyakit.
3. Lansia harus memiliki akses pada pelayanan sosial dan hukum untuk meningkatkan
otonomi, perlindungan dan perhatian.
4. Lansia harus mampu menggunakan ketersediaan institusi perlindungannya dengan
baik untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi, stimulasi sosial dan mental dalam
lingkungan yang aman.
5. Lansia harus mampu menikmati hak asasi manusia dan kebebasan ketika tinggal di
tempat manapun, fasilitas pengobatan, termasuk penghormatan akan martabatnya,
keyakinan, kebutuhan, dan privasi serta hak untuk membuat keputusan untuk kehidupan
dan kualitas hidupnya.
D. Pemenuhan diri
1. Lansia harus mampu mencari kesempatan untuk pembangunan sepenuhnya potensi
diri mereka.
2. Lansia harus memiliki akses akan sumber pendidikan, budaya, spiritual, dan
rekreasional di masyarakat.
E. Martabat
1. Lansia harus mampu hidup dalam lingkungan yang aman dan bermartabat dan bebas
dari eksploitasi fisik maupun mental.
2. Lansia harus diperlakukan dengan baik tanpa melihat umur, jenis kelamin, ras atau
latar belakang etnik, disabilitas atau status yang lain dan di hargai secara bebas akan
kontribusi ekonomis mereka.
Para lansia yang mengalami demensia selayaknya mendapat penghargaan yang baik
tanpa memandang usia serta sejauh mana gangguan yang ada dan bahwasanya setiap
orang adalah unik, memiliki kepribadian tersendiri sehingga pendekatan masing-masing
haruslah disesuaikan. Beberapa kunci pokok dalam penanganan secara holistik yang
dapat dilaksanakan antara lain (NICE, 2004):
40

a. Tanpa diskriminasi
Para penderita demensia tidak boleh dikecualikan dari semua pelayanan semata-mata
karena diagnosis, usia atau gangguan yang ada.
b. Penjelasan yang tepat
Para penyedia layanan kesehatan harus selalu memberikan penjelasan dengn baik
kepada para penderita. Mereka harus mendapatkan informasi dengan baik, dipastikan
bahwa mereka dapat mengerti dan apabila terdapat gangguan dalam pemahaman maka
bias menggunakan alat bantu Mental Capacity Act 2005.
c. Carers/ penjaga yang membantu dalam kegiatan sehari hari
Para penyedia layanan kesehatan harus dipastikan mendapatkan hak untuk mendapatkan
penilaian atas apa yang dibutuhkan dan apabila mengalami stress psikologis, mereka
harus mendapatkan terapi psikologi termasuk cognitive behavioural therapy dari
ahlinya.
d. Koordinasi dan integrasi layanan kesehatan dan sosial
Penyedia layanan keehatan dan sosial harus berkoordinasi dalam bekerja melalui suatu
prosedur tertulis. Rencana dan strategi harus memasukkan sistem lokal serta pendekatan
budaya lokal yang bersifat spesifik mengingat kultur, penilaian, penghargaan serta
peranan setiap lansia dalam masyarakat tidaklah sama dalam setiap system budaya.
e. Penilaian memori
Penilaian memori harus dilakukan dan merupakan titik dimana rujukan dan penanganan
yang komperhensif harus dilakukan pada seseorang yang dicurigai menderita demensia.
f. Alat bantu diagnosis
selain alat bantu terstandar untuk menilai status kognitif, alat bantu untuk menilai
gangguan struktur lain terutama pada otak juga harus ada.
g. Gangguan perilaku
Faktor pencetus terjadinya gangguan prilaku harus diidentifikasi dan penanganan harus
disesuaikan. Terapi kognitif dan perilaku bisa diberikan dengan pendekatan individu
bersamaan dengan terapi medikamentosa.
h. Pelatihan
41

Para penyedia layanan harus dipastikan mendapat pelatihan yang sesuai sesuai dengan
peranan dan tangung jawab masing-masing.
i. Kebutuhan kesehatan mental pada kondisi “acute hospitals”
Dalam keadaan tertentu dimana diperlukan penanganan perawatan rumah sakit, fasilitas
untuk itu harus tersedia sesuai dengan kebutuhan medis, sosial dan mental penderita.
BAB 4
KESIMPULAN
Penatalaksanaan demensia pada usia lanjut harus meliputi beberapa komponen
baik medikamentosa dan nonmedikamentosa dan dilakukan secara holistik, saling
terkait, sistematis dan melibatkan banyak pihak. Pendekatan budaya lokal harus
dilakukan dan penderita harus diperlakukan secara individual sesuai dengan kapasitas,
kondisi, penyakit komorbid, kebiasaan serta gangguan yang ada untuk memaksimalkan
pelayanan yang diberikan. Konsep biopsikososiospiritual harus diterapkan secara
integratif karena keseluruhan aspek merupakan faktor yang sangat terkait dan
mempengaruhi satu sama lain.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sudoyo Aru W, Setiyohadi Bambang, Alwi Idrus, dkk. Buku Ajar Ilmu Penyakit
Dalam. Jilid I dan III. Edisi V. Jakarta : Interna Publishing; 2009
2. Rani A Aziz, dkk. Panduan Pelayanan Medik Perhimpunan Dokter Spesialis
Penyakit Dalam. Jakarta: Interna Publishing; 2009
42

3. Martono H Hadi, Pranaka H Hadi. Buku Ajar Geriatri. Edisi IV. Jakarta: Balai
Penerbit FKUI; 2011
4. Kane Robert L, et al. Essentials of Clinical Geriatrics. 5th edition. New York :
McGraw-Hill; 2004
43