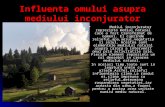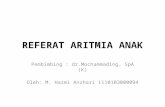Referat radiologi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Referat radiologi
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Leukemia adalah suatu keadaan di mana terjadi
pertumbuhan yang bersifat irreversibel dari sel induk
dari darah. Pertumbuhan dimulai dari mana sel itu
berasal. Sel-sel tesebut, pada berbagai stadium akan
membanjiri aliran darah. Pada kasus leukemia (kanker
darah), sel darah putih tidak merespon kepada
tanda/signal yang diberikan. Akhirnya produksi yang
berlebihan tidak terkontrol (abnormal) akan keluar dari
sumsum tulang dan dapat ditemukan di dalam darah perifer
atau darah tepi. Jumlah sel darah putih yang abnormal ini
bila berlebihan dapat mengganggu fungsi normal sel
lainnya. Seseorang dengan kondisi seperti ini (leukemia)
akan menunjukkan beberapa gejala seperti; mudah terkena
penyakit infeksi, anemia dan perdarahan. (Hematologi Klinik Ed.
2.106).
Acute myeloid leukemia (AML), yaitu leukemia yang terjadi
pada seri myeloid, meliputi (neutrofil, eosinofil,
monosit, basofil, megakariosit dan lain - lain). Di
negara maju seperti Amerika Serikat, LMA merupakan 32%
dari seluruh kasus leukemia. Penyakit ini lebih sering
ditemukan pada dewasa (85%) dari pada anak (15%). (Buku Ajar
Hematologi dan Onkologi Anak).
1.2.Tujuan dan manfaat
1
Tujuan penulisan referat ini adalah agar penulis atau
pembaca dapat mengerti tentang Leukemia Mieloblastik Akut
(LMA) meliputi penyebab, penyebaran, pengertian,
perjalanan penyakit, gejala penyakit, komplikasi dan
penatalaksanaan penyakit ini.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. Definisi
Leukemia mieloblastik akut (LMA) adalah suatu
penyakit yang ditandai dengan transformasi neoplastik dan
gangguan diferensiasi sel-sel progenitor dari seri
mieloid. Bila tidak diobati, penyakit ini akan
mengakibatkan kematian secara cepat dalam waktu beberapa
minggu sampai bulan sesudah diagnosis.
Kemajuan pengobatan LMA dicapai dengan regimen
kemoterapi yang lebih baik, kemoterapi dosis tinggi
dengan dukungan cangkok sumsum tulang dan terapi suportif
2
yang lebih baik seperti antibiotik generasi baru dan
transfusi komponen darah untuk mengatasi efek samping
pengobatan. (Buku Ajar Hematologi dan Onkologi Anak).
2.2. Etiologi
Pada sebagian besar kasus, etiologi dari LMA tidak
diketahui. Meskipun demikian ada beberapa faktor yang
diketahui dapat menyebabkan atau setidaknya menjadi
faktor prediposisi LMA pada populasi tertentu. Benzene,
suatu senyawa kimia yang banyak digunakan pada insidens
penyamakan kulit di negara berkembang, diketahui
merupakan zat leukomogenik untuk LMA. Selain itu radiasi
ionik juga diketahui dapat menyebabkan LMA.
Faktor lain yang diketahui sebagai predisposisi untuk
LMA adalah trisomi kromosom 21 yang dijumpai pada
penyakit herediter sindrom down. Pasien Sindrom Down
dengan trisomi kromosom 21 mempunyai resiko 10 hingga 18
kali lebih tinggi untuk menderita leukemia, khususnya LMA
tipe M7. Selain itu pada beberapa pasien sindrom genetik
seperti Sindrom Bloom dan anemia Fanconi juga diketahui
mempunyai resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan
populasi normal untuk menderita LMA.
Faktor lain yang dapat memicu terjadinya LMA adalah
pengobatan dengan kemoterapi sitotoksik pada pasien tumor
padat. LMA akibat terapi adalah komplikasi jangka panjang
yang serius dari pengobatan limfoma, mieloma multipel,
kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker testis. Jenis
3
terapi yang paling sering memicu timbulnya LMA adalah
golongan alkylating agent dan topoisomerase II inhibitor.
2.3. Patogenesis
Patogenesis utama LMA adalah adanya blokade
maturitas yang menyebabkan proses diferensiasi sel-sel
seri mieloid terhenti pada sel-sel muda (blast) dengan
akibat terjadi akumulasi blast di sumsum tulang.
Akumulasi blast di dalam sumsum tulang akan menyebabkan
gangguan hematopoesis normal dan pada gilirannya akan
mengakibatkan sindrom kegagalan sumsum tulang (bone marrow
failure syndrome) yang ditandai dengan adanya sitopenia
(anemia, leukopeni, trombositopeni). Adanya anemia akan
menyebabkan pasien mudah lelah dan pada kasus yang lebih
berat akan sesak nafas, adanya trombositopenia akan
menyebabkan tanda-tanda perdarahan, sedang adanya
leukopenia akan menyebabkan pasien rentan terhadap
infeksi, termasuk infeksi oportunis dari flora normal
bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Selain itu, sel-
sel blast yang terbentuk juga punya kemampuan untuk
migrasi keluar sumsum tulang dan berinfiltrasi ke organ-
organ lain seperti kulit, tulang, jaringan lunak dan
sistem syaraf pusat dan merusak organ-organ tersebut
dengan segala akibatnya.
2.4. Gejala klinis
Berbeda dengan anggapan umum selama ini, pada
pasien LMA tidak selalu dijumpai leukositosis.
4
Leukositosis terjadi pada sekitar 50% kasus LMA, sedang
15% pasien mempunyai angka leukosit yang normal dan
sekitar 35% mengalami netropenia. Meskipun demikian, sel-
sel blast dalam jumlah yang signifikan di darah tepi akan
ditemukan pada 85% kasus LMA. Oleh karena itu sangat
penting untuk memeriksa rincian jenis sel-sel leukosit di
darah tepi sebagai pemeriksaan awal, untuk menghindari
kesalahan diagnosis pada orang yang diduga menderita LMA.
Tanda dan gejala utama LMA adalah adanya rasa
lelah, perdarahan dan infeksi yang disebabkan oleh
sindrom kegagalan sumsum tulang sebagaimana telah
disebutkan di atas. Perdarahan biasanya terjadi dalam
bentuk purpura atau petekia yang sering dijumpai di
ekstremitas bawah atau berupa epistaksis, perdarahan gusi
dan retina. Perdarahan yang lebih berat jarang terjadi
kecuali pada kasus yang disertai dengan DIC. Kasus DIC
ini pling sering dijumpai pada kasus LMA tipe M3. Infeksi
sering terjadi di tenggorokan, paru-paru, kulit dan
daerah peri rekti, sehingga organ-organ tersebut harus
diperiksa secara teliti pada pasien LMA dengan demam.
Pada pasien dengan angka leukosit yang sangat tinggi
(lebih dari 100 ribu/mm3), sering terjadi leukositosis,
yaitu gumpalan leukosit yang menyumbat aliran pembuluh
darah vena maupun arteri. Gejala leukositosis sangat
bervariasi, tergantung lokasi sumbatannya. Gejala yang
sering dijumpai adalah gangguan kesadaran, sesak nafas,
nyeri dada dan priapismus.
5
Infiltrasi sel-sel blast akan menyebabkan
tanda/gejala yang bervariasi tergantung organ yang di
infiltrasi. Infiltrasi sel-sel blast di kulit akan
menyebabkan leukemia kutis yaitu berupa benjolan yang
tidak berpigmen dan tanpa rasa sakit, sedang infiltrasi
sel-sel blast di jaringan lunak akan menyebabkan nodul di
bawah kulit (kloroma). Infiltrasi sel-sel blast di dalam
tulang akan meninbulkan nyeri tulang yang spontan atau
dengan stimulasi ringan. Pembengkakan gusi sering
dijumpai sebagai manifestasi infiltrasi sel-sel blast ke
dalam gusi. Meskipun jarang, pada LMA juga dapat dijumpai
infiltrasi sel-sel blast ke daerah meningen dan untuk
penegakan diagnosis diperlukan pemeriksaan sitologi dari
cairan serebro spinal yang diambil melalui prosedur
pungsi lumbal.
2.5. Diagnosis
Secara klasik diagnosis LMA ditegakkan berdasarkan
pemeriksaan fisik, morfologi sel dan pengecatan
sitokimia. Sejak sekitar dua dekade tahun yang lalu
berkembang 2 (dua) teknik pemeriksaan terbaru:
immunophenotyping dan analisis sitogenik. Berdasarkan
pemeriksaan morfologi sel dan pengecatan sitokimia,
gabungan ahli hematologi Amerika, Perancis dan Inggris
pada tahun 1976 menetapkan klasifikasi LMA yang terdiri
dari 8 subtipe (M0 sampai dengan M7). Klasifikasi ini
dikenal dengan nama klasifikasi FAB (French American
British). Klasifikasi FAB hingga saat ini masih menjadi
6
diagnosis dasar LMA. Pengecatan sitokimia yang penting
untuk pasien LMA adalah Sudan Black B (SSB) dan
mieloperoksidase (MPO). Kedua pengecatan sitokimia
tersebut akan memberikan hasil positif pada pasien LMA
tipe M1, M2, M3, M4, dan M6.
Kelainan hematologis yang biasa terjadi adalah anemia
dengan jumlah eritrosit yang menurun sekitar 1-3 x
106/mm3; leukositosis dengan jumlah leukosit antara 50-100
x 103 /mm3 (leukosit yang ada dalam darah tepi terbanyak
adalah myeloblas); trombosit jumlah menurun. Mieloblas
yang tampak kadang-kadang mengandung “auer body” suatu
kelainan yang pathogonomis untuk LMA.
Sumsum tulang tampak hiperseluler karena mengandung
mieloblas yang masif, sedang megakariosit dan
pronormoblas dijumpai sangat jarang. Kelainan sumsum
tulang ini sudah akan jelas meskipun mieloblas belum
tampak dalam darah tepi. Jadi kadang-kadang ditemukan
kasus dengan pansitopenia perifer akan tetapi sumsum
tulang sudah jelas hiperseluler karena infiltrasi dengan
mieloblas.
2.6. Dignosis banding
Leukemia mieloblastik akut harus dibuat
diagnosa banding dengan semua leukemia akut dan anemia
aplastik. Apabila ditemukan “auer body” maka diagnosa
banding tidak sulit ditegakkan, oleh karena kelainan ini
patognomis untuk leukemia mieloblastik akut. Apabila
7
tidak ditemukan “auer body” maka harus dikerjakan reaksi
peroksidase dimana pada mieloblas peroksidase akan
positif.
Anemia aplastik dengan mieloblastik akut yang
alekemik dibedakan atas dasar pemeriksaan sumsum tulang.
Secara klinis endokarditis bakterialis mirip leukemia
mieloblastik akut karena adanya demam, anemia,
splenomegali, dan petechiae. Riwayat adanya penyakit
jantung, splenomegali yang lebih besar dan tidak adanya
kelainan pada gusi dapat membedakan kedua keadaan ini.
Anemia pernisiosa yang disertai splenomegali dan ptechiae
dapat menyerupai leukemia mieloblastik akut.
2.7. Komplikasi
Dua macam komplikasi yang sering bersifat fatal
yaitu perdarahan serebelar dan infeksi. Komplikasi yang
jarang terjadi adalah keluhan akibat tekanan oleh suatu
tumor leukemia.
2.8. Penatalaksanaan
Tatalaksana utama adalah dengan memperbaiki
keadaan umum seperti pada kondisi anemia diberikan
tranfusi darah. Trombositopeni berat yang mengancam
perdarahan diatasi dengan transfusi konsentrat trombosit.
Apabila terdapat infeksi diberikan antibiotika yang
adekuat. Terapi spesifik seperti terapi leukemia pada
umumnya dimulai dengan tahap induksi dengan pemberian
8
regimen Doxorubicin 40 mg/mm2 berat badan hari 1-5,
dilanjutkan dengan Ara C 100 mg IV, tiap 12 jam hari 1-7.
Dilakukan evaluasi klinis dan hematologis serta
pemeriksaan sumsum tulang pada akhir minggu ketiga.
Apabila tidak terjadi remisi atau remisi hanya bersifat
parsial maka terapi harus diganti dengan regimen lain.
Apabila terjadi remisi lengkap (klinis dan
hematologis) maka dimulai tahap konsolidasi. Pada tahap
ini diberikan doxorubicin 40 mg/mm2 hari 1-2 dan Ara C 1-
5. Regimen ini diberikan 2 kali dengan interval 4 minggu.
Apabila keadaan memungkinkan maka diberikan cangkok
sumsum tulang pada saat terjadi remisi lengkap.
Terapi standar adalah kemoterapi induksi dengan
regimen sitarabin dan daunorubisin dengan protokol
sitarabin 100 mg/m2 diberikan secara infus kontinyu
selama 7 hari dan daunorubisin 45-60 mg/m2/hari iv selama
3 hari. Sekitar 30-40% pasien mengalami remisi komplit
dengan terapi sitarabin dan dounorubisin yang diberikan
sebagai obat tunggal, sedangkan bila diberikan sebagai
obat kombinasi remisi komplit dicapai oleh lebih dari 60%
pasien. (Buku Ajar Hematologi dan Onkologi Anak).
2.9. Prognosis
Dengan terapi agresif, 40 -50 % penderita yang
mencapai remisi akan hidup lama (30-40 % angka kesembuhan
keseluruhan). Penderita yang mengalami relaps setelah
mendapat kemoterapi atau transplantasi autolog dapat
diterapi dengan CST allogenetik sebagai terapi
9
penyelamatan. Beberapa subtipe morfologi atau genetik LMA
mempunyai prognosis lebih baik.
BAB 3
PENUTUP
Leukemia (kanker darah) adalah jenis penyakit
kanker yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi
oleh sumsum tulang (bone marrow). Sumsum tulang atau bone
marrow ini dalam tubuh manusia memproduksi tiga tipe sel
darah diantaranya sel darah putih (berfungsi sebagai daya
tahan tubuh melawan infeksi), sel darah merah (berfungsi
membawa oksigen kedalam tubuh) dan trombosit (bagian
kecil sel darah yang membantu proses pembekuan darah).
Sampai saat ini penyebab penyakit leukemia belum
diketahui secara pasti, beberapa faktor yang diduga
mempengaruhi frekuensi terjadinya leukemia yaitu :
1. Radiasi.
10
2. Leukemogenik: beberapa zat kimia dilaporkan telah
diidentifikasi dapat mempengaruhi frekuensi terjadinya
leukemia, misalnya racun lingkungan seperti benzena,
bahan kimia industri seperti insektisida, obat-obatan
yang digunakan untuk kemoterapi.
3. Herediter: penderita sindrom Down memiliki insidensi
leukemia akut 20 kali lebih besar dari orang normal.
4. Virus: beberapa jenis virus dapat menyebabkan
leukemia, seperti rotavirus, virus leukemia feline, HTLV-
1 pada dewasa.
Sistem terapi yang sering digunakan dalam
menangani penderita leukemia adalah kombinasi antara
kemoterapi dan pemberian obat-obatan yang berfokus pada
pemberhentian produksi sel darah putih yang abnormal
dalam sumsum tulang. Selanjutnya adalah penanganan
terhadap beberapa gejala dan tanda yang telah ditampakkan
oleh tubuh penderita dengan monitor yang komprehensif.
KASUS
I. IDENTIFIKASI
Seorang anak laki-laki, usia 2 tahun 5 bulan, berat
badan 13 kg, tinggi badan 90 cm, beralamat di Lubuk
11
Linggau. Dirawat di bagian Ilmu Kesehatan Anak RSMH
pada tanggal 4 Maret 2014.
Anamnesis
Keluhan utama: demam.
Keluhan tambahan: kelemahan pada kedua kaki .
Riwayat perjalanan penyakit:
Tiga hari SRMS anak demam yang tidak terlalu
tinggi, demam bersifat naik turun, turun apabila
diberi obat penurun panas, batuk (+), pilek (+),
BAB dan BAK tidak ada keluhan. Anak mulai mengeluh
kaki terasa lemas, saat digunakan berdiri, anak
cenderung terjatuh sehingga anak menolak untuk
berdiri, nyeri (-), bengkak pada kedua kaki (-).
Anak belum dibawa berobat.
Satu hari SMRS anak masih demam, anak mulai
mengeluh susah BAK, saat BAK anak tampak kesakitan
dan menjadi sering BAK tetapi sedikit-sedikit. BAB
dalam batas normal. Anak kemudian dibawa ke Graha
RSMH dan disarankan untuk rawat inap.
Riwayat penyakit dahulu
- Anak telah terdiagnosa AML sejak Januari 2014, sudah
mendapat kemoterapi siklus pertama. Anak kontrol dan
minum obat secara teratur.
- Anak telah terdiagnosa hipotiroid dan sindrom Down,
sedang menjalani terapi dengan tyrax selama 21 hari.
- Riwayat terjatuh disangkal.
- Riwayat sulit BAK sebelumnya disangkal.
Riwayat penyakit keluarga
12
- Riwayat penyakit yang sama dalam
keluarga disangkal.
Riwayat keluarga
Penderita merupakan anak pertama dengan status
sosial dan ekonomi cukup.
Riwayat kehamilan dan kelahiran
Penderita merupakan anak yang diharapkan, ANC
teratur ke SpOG tiap bulan. Ibu hanya mengkonsumsi
vitamin yang diberikan oleh dokter, riwayat minum
obat-obatan lain disangkal. Riwayat memelihara
kucing atau anjing disangkal. Riwayat sering demam
atau menderita ruam saat hamil disangkal. Usia ibu
saat hamil adalah 32 tahun.
Anak lahir ditolong SpOG, spontan, cukup bulan,
lahir langsung menangis, berat badan lahir 2.800
gram, panjang badan tidak diketahui.
Riwayat imunisasi
BCG (+), scar (+), DPT I, II, III (+), Hepatitis I,
II, III (+), Polio I, II, III, IV (+), Campak (+).
Kesan: imunisasi dasar lengkap dan diberikan sesuai
umur.
Riwayat makan
- ASI :dari lahir sampai usia 2 tahun.
- PASI : 3 bulan sampai usia 2 tahun.
- Bubur susu: mulai usia 4 bulan sampai 8 bulan.
13
- Nasi tim :usia 9 bulan sampai 11 bulan.
- Nasi biasa: 1 tahun sampai dengan sekarang
- Kesan: kualitas dan kuantitas cukup
Riwayat pertumbuhan dan perkembangan
- Tengkurap usia 6 bulan.
- Duduk usia 12 bulan.
- Merangkak usia 18 bulan.
- Saat ini anak belum dapat berdiri dengan
sempurna, dapat berdiri apabila dibantu.
- Anak belum dapat berbicara dengan lancar, hanya
dapat mengucapkan beberapa suku kata, misalnya mama,
papa, mamam.
Kesan: riwayat pertumbuhan dan perkembangan
terlambat.
II. PEMERIKSAAN FISIK
Keadaan Umum:
Kesadaran: Kompos Mentis, GCS: E4M6V5=15, Nadi:
110x/menit (isi dan tegangan cukup), pernapasan:
28x/menit, suhu: 38,5 oC.
BB: 13 kg; TB: 90 cm. BB/U: 80% ; TB/U: 88 % ;
BB/TB: 86% LK: 44 cm (normosefali).
Kesan: status gizi baik.
Keadaan spesifik:
Kepala : wajah dismorfik, pupil bulat isokor, 3/3
mm, refleks cahaya +/+, konjungtiva anemis (+),
sklera ikterik (-).
14
Leher : JVP tidak meningkat, kelenjar getah bening
tidak membesar.
Thoraks : bentuk normal, simetris, retraksi (-).
Jantung : bunyi jantung I dan II normal, murmur (-),
gallop (-)
Abdomen : datar, lemas, hepar dan lien tidak teraba,
bising usus (+) normal.
Ekstremitas: akral dingin(-), sianosis(-),
spastis(-), CRT<3”.
Status neurologik:
PemeriksaanMotorik
TungkaiKanan
TungkaiKiri
LenganKanan
LenganKiri
Gerakan Terbatas Terbatas Luas Luas
Kekuatan 3 3 5 5
Tonus Hipotoni Hipotoni Eutoni Eutoni
Klonus Tidakada Tidak ada
Refleksfisiologi Menurun Menurun Normal Normal
Reflekspatologi - - - -
Pemeriksaan sensorik : dalam batas normal.
Pemeriksaan otonom : dalam
batas normal.
Pemeriksaan nervus kranialis : dalam batas
normal.
GRM : tidak ditemukan.
15
RINGKASAN DATA DASAR
Seorang anak laki-laki, usia 2 tahun 5 bulan, berat
badan 13 kg, tinggi badan 90 cm, beralamat di Lubuk
Linggau. Dirawat di bagian Ilmu Kesehatan Anak RSMH pada
tanggal 4 Maret 2014. Anak datang dengan keluhan utama
demam dan keluhan tambahan adanya kelemahan pada kedua
tungkai bawah.
Tiga hari SRMS anak demam yang tidak terlalu tinggi,
demam bersifat naik turun, turun apabila diberi obat
penurun panas, batuk (+), pilek (+), BAB dan BAK tidak
ada keluhan. Anak mulai mengeluh kaki terasa lemas, saat
digunakan berdiri, anak cenderung terjatuh sehingga anak
menolak untuk berdiri, nyeri (-), bengkak pada kedua kaki
(-). Anak belum dibawa berobat.
Satu hari SMRS anak masih demam, anak mulai
mengeluh susah BAK, saat BAK anak tampak kesakitan dan
menjadi sering BAK tetapi sedikit-sedikit. BAB dalam
batas normal. Anak kemudian dibawa ke Graha RSMH dan
disarankan untuk rawat inap.
Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran: kompos
mentis, nadi: 110x/menit (isi dan tegangan cukup),
pernapasan: 28x/menit, suhu: 38,5oC, status gizi baik.
Keadaan spesifik: kepala: wajah dismorfik, pupil bulat
isokor, reflek cahaya normal; thorak: simetris, retraksi
(-); jantung: bunyi jantung I dan II normal, murmur (-),
gallop (-); paru: vesikuler, ronki (-), wheezing (-);
abdomen: datar, lemas, hepar dan lien tidak teraba, BU(+)
normal; ekstremitas: akral dignin (-), sianosis(-).
16
Status neurologis: gerakan tungkai bawah terbatas dengan
kekuatan 3, reflek fisiologis menurun, tidak dijumpai
reflek patologis dan gejala rangsang meningeal.
ANALISIS AWAL
Dilaporkan suatu kasus ependimoma yang dirawat di
divisi neurologi bagian IKA RSMH. Penderita sebelumnya
dirawat di RSUD Lahat kemudian dirujuk ke RSMH. Diagnosa
ditegakkan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan penunjang.
Dari anamnesis diketahui bahwa anak datang dengan
keluhan utama sakit kepala. Secara garis besar, penyebab
sefalgia antara lain vaskuler, musculoskeletal, organik
(tumor, malformasi, infeksi), psikogenik dan lain-lain
(neuralgia). Secara klinis, sefalgia diklasifikasikan
menjadi sefalgia primer dan sekunder. Sefalgia primer
adalah bila tidak ditemukan penyebab organik dari suatu
sakit kepala. Yang termasuk dalam sefalgia primer yaitu
migrain, tension-typed headache, dan cluster headache. Sefalgia
sekunder yaitu bila ditemukan penyebab organik yang
mendasari keluhan sakit kepala pada penderita.
Dari anamnesa didapatkan sakit kepala terutama
dirasakan pada pagi hari, pada bagian belakang kepala,
kadang menjalar ke leher, hilang timbul, intensitas
ringan-sedang, tidak berhubungan dengan aktivitas,
disertai muntah saat serangan dan tanpa perasaan
berputar. Saat serangan tidak diawali dengan adanya
gejala prodromal (fotofobia, aura). Saat tidak dalam
17
serangan sakit kepala, anak dapat melakukan aktivitas
seperti biasa.
Pada sefalgia primer gejalanya adalah nyeri kepala
yang berdenyut, dengan intensitas yang diperberat dengan
aktivitas atau perubahan posisi kepala. Seringkali
sefalgia primer diawali dengan gejala prodromal berupa
mual, fotofobia dan aura yang berlangsung singkat. Pada
pasien tidak ditemukan gejala-gejala tersebut sehingga
sefalgia primer dapat disingkirkan.
Sefalgia yang disebabkan oleh kelainan vaskuler
paling sering disebabkan oleh perdarahan intrakranial dan
seringkali bersifat akut. Tanda akut yang sering dijumpai
adalah adanya gejala peningkatan tekanan intrakranial
berupa penurunan kesadaran, kejang, dan muntah proyektil.
Pada penderita ditemukan riwayat penurunan kesadaran
sesaat, tanpa kejang dan adanya muntah proyektil.
Kemungkinan telah terjadi peningkatan tekanan
intrakranial sehingga diperlukan pemeriksaan lanjut
menggunakan funduskopi. Adanya kemungkinan perdarahan
intrakranial yang berjalan kronis belum dapat
disingkirkan karena anak memiliki riwayat trauma
sebelumnya. Untuk membantu melihat adanya perdarahan
intrakranial, diperlukan pemeriksaan penunjang CT scan
kepala.
Sefalgia yang disebabkan oleh musculoskeletal dan
neuralgia bersifat akut dan terus menerus, dapat berasal
dari infeksi yang terlokalisir misalnya sinusitis, otitis
media, abses gigi ataupun disfungsi sendi
18
temporomandibular. Perlu dilakukan konsultasi ke bagian
THT untuk menilai adanya kemungkinan infeksi yang
terlokalisir.
Gejala sefalgia yang bersifat kronis dan progresif
sesuai dengan kemungkinan sefalgia dengan penyebab
organik (infeksi, tumor, atau malformasi). Dari anamnesa
tidak ditemukan demam atau sumber infeksi lain sehingga
penyebab infeksi dapat disingkirkan. Diperlukan
pemeriksaan penunjang berupa CT scan kepala untuk melihat
adanya tumor atau malformasi.
Adanya penglihatan yang kabur dapat disebabkan oleh
adanya peningkatan TIK, gangguan visus (kelainan
refraksi), kelainan pada bola mata (glaucoma), trauma
nervus optikus, atau karena penekanan nervus optikus oleh
tumor. Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan
funduskopi dan konsultasi ke bagian mata.
Masalah awal
1. Sefalgia ec peningkatan TIK dd/ tumor, sinusitis,
malformasi vaskuler, infeksi SSP
2. Pandangan kabur ec peningkatan TIK dd/ kelainan
refraksi, trauma bola mata, penekanan oleh massa
Rencana diagnostik
1. Pemeriksaan darah rutin, elektrolit, BSS
2. CT-scan kepala
3. Funduskopi
4. Konsul THT
5. Konsul mata
Rencana terapi
19
1. IVFD D5 ½ NS 1580 cc/24 jam gtt 15 makro
2. Parasetamol 3x250 mg (po)
3. Diet 1650 kkal + protein 30 gr dalam bentuk nasi
biasa 3x1 porsi + susu F100 3x150 cc
4. Monitoring : tanda vital (TD, nadi, laju napas),
tanda peningkatan TIK (kejang, penurunan kesadaran)
CATATAN PERAWATAN PENDERITA
Tanggal Follow up18-7-2013
S
O
Masalah: 1. Sefalgia2. Penglihatan kabur
Sakit kepala (+), penglihatan kabur (+),muntah (-), kejang (-)
KU: Sens : compos mentis, N 108 x/m (i/tcukup), T 36,70C, RR 24x/menit, TD 100/60mmHg. KS: Kepala: normosefali, NCH (-),conjungtiva anemis (-), pupil bulatisokor, Ø 3/3 mm, RC +/+ N. Thoraks:simetris, retraksi (-). Jantung: bunyijantung I-II normal, bising (-), Paru:vesikuler +/+, ronkhi -/-, wheezing -/-,Abdomen: datar, lemas, hepar/lien takteraba, bising usus (+) normal.Ekstremitas: pucat (-), akral hangat, CRT< 2”.
Status neurologi: Lengankanan
Lengankiri
Tungkaikanan
Tungkaikiri
Gerakan luas
luas
Kekuatan 4 4 4 4Tonus Eutoni Eutoni Eutoni eutoniKlonus - -
20
A
P
Reflek
fisiologis
N
N
↑
↑
Reflek
patologis
-
- - -
Gejala rangsang meningeal : kaku kuduk(-), brudzinsky I (-), brudzinsky II (-) Laboratorium: Hb 13,1 gr/dl, Ht 36 vol%, leukosit7.200/mm3, LED 12 mm/jam, Trombosit357.000 /mm3, DC : 0/3/0/44/44/9. Natrium 142 mmol/L, Kalium 4,1 mmol/L,GDS 107 mg/dl. Kesan : hasil laboratorium dalam batasnormal.CT scan kepala cito: Kesan: hidrosefalusec suspek tumor kepala
Hasil konsul ke bagian mata: kesan: papiledema bilateral ec peningkatan TIK suspektumor kepala, saran: penurunan TIK sesuaitatalaksana bagian anak.Hasil konsul ke bagian THT: kesan: tidakditemukan kelainan.
Adanya sakit kepala, penglihatan kabur,riwayat muntah proyektil serta adanyapapil edema bilateral melalui funduskopimerupakan tanda adanya peningkatan TIK.Dari hasil CT scan ditemukan hidrosefalusnon komunikans yang disebabkan obstruksialiran LCS karena adanya penekanan olehmassa/tumor. Adanya kecurigaan penyebab hidrosefalusadalah tumor kepala ditunjang dengananamnesa yaitu adanya sakit kepalaterutama pada pagi hari, bersifat kronikdan progresif.
- IVFD D5 1/2NS gtt 15x/mnt (makro)- Asetazolamide 3x250 mg (po) - Parasetamol 3x250 mg (po)- Diit: NB 3x1 porsi + F100 3x150 cc
21
- R/konsul bedah saraf
19-7-2013
S
O
A
P
Masalah:Peningkatan TIK ec tumor kepala +hidrosefalus
Sakit kepala (+), penglihatan kabur (+)
Pemeriksaan fisik : stqaJawaban konsul bedah:Kesan CT scan kepala: hidrosefalus +tumor kepala fossa posteriorSaran: perbaiki KU, rencana pemasangan vpshunt jika KU membaik dan keluargasetuju, MRI.
Tatalaksana peningkatan TIK yangdisebabkan oleh hidrosefalus adalahdengan pemasangan VP-shunt. Denganpemasangan VP-shunt diharapkan obstruksiyang terjadi dapat selesai. Direncanakanpemeriksaan tambahan yaitu MRI kepalauntuk melihat lebih jelas letak dan jenistumor kepala.
- IVFD D5 1/2NS gtt 15x/mnt (makro)- Asetazolamide 3x250 mg (po) - Parasetamol 3x250 mg (po)- Diit: NB 3x1 porsi + F100 3x150 cc- Pro VP-shunt menunggu jadwal 23 Juli2013- R/MRI menunggu jadwal 31 Juli 2013- Observasi tanda-tanda vital- Rawat bersama bedah saraf
23-7-2013
S
O
Masalah:Peningkatan TIK ec tumor kepala +hidrosefalus
Muntah (-), sakit kepala (+), penglihatankabur (-)
Post op pemasangan vp shunt. Keadaan saat tiba dibangsal anak:
22
A
P
KU: Sens: belum dapat dinilai, masihdibawah pengaruh anestesi. N 104 x/m (i/tcukup), T 37,30C, RR 26 x/menit. KS:Kepala: tertutup kasa post op, pupilbulat isokor, Ø 3/3 mm, RC +/+ N. Thoraks: simetris, retraksi (-). Jantung: bunyijantung I-II normal, bising (-), Paru:vesikuler +/+, ronkhi -/-, wheezing -/-,Abdomen: datar, lemas, hepar/lien takteraba, bising usus (+) normal.Ekstremitas: akral hangat, CRT<2’’, SpO296%. Instruksi post operasi:
- Puasa hingga pasien sadar penuh- IVFD RL gtt 15x/mnt (makro)- Ceftriaxon 1x2 gr- Farmadol 3x150mg- Ranitidin 2x25mg
Laboratorium (post op): Hb 11,9 gr/dl, Ht 32 vol%, leukosit14.400/mm3, Trombosit 317.000 /mm3, DC :0/0/0/82/13/5. GDS 98 mg/dl.
Post op pemasangan VP shunt atas indikasihidrosefalus hari 1Hasil laboratorium post op dalam batasnormal. - Puasa hingga pasien sadar penuh- IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro)- Ceftriaxone 1x2 gr (1) R/pemberianselama 7 hari- Farmadol 3x250 mg (iv)- Ranitidin 2x25 mg (iv) - Asetazolamide stop- R/MRI kepala 31 Juli 2013
26-7-2013
S
Masalah:Suspek tumor kepala
Muntah (-), sakit kepala (-), penglihatankabur (-)
23
O
A
P
KU: Sens : compos mentis, N 88 x/m (i/tcukup), T 36,50C, RR 24x/menit, TD :100/70 mmHg. KS: Kepala: normosefali,terlihat luka tertutup perban, perdarahan(-), NCH (-), conjungtiva anemis (-),pupil bulat isokor, Ø 3/3 mm, RC +/+ N.Thoraks: simetris, retraksi (-). Jantung:bunyi jantung I-II normal, bising (-),Paru: vesikuler +/+, ronkhi -/-, wheezing-/-, Abdomen: datar, lemas, hepar/lientak teraba, bising usus (+) normal.Ekstremitas: pucat (-), akral hangat, CRT< 2”.
Status neurologi: Lengankanan
Lengankiri
Tungkaikanan
Tungkaikiri
Gerakan Luas
LuasKekuatan 5 5 5 5Tonus Eutoni Eutoni Eutoni eutoniKlonus - -Reflek
fisiologis
N
N
N
N
Reflek
patologis
-
- - -
Gejala rangsang meningeal : (-)
Setelah pemasangan VP shunt, gejalapeningkatan TIK pada pasien menghilang,terjadi perbaikan klinis, peningkatan TIKteratasi. Diagnosis tumor kepala belumdapat ditegakkan karena pasien masihmenunggu jadwal MRI.
- IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro)- Ceftriaxone 1x2 gr (4)- Farmadol 3x250 mg (iv) gantiParasetamol 3x250 mg (po)- Ranitidin stop- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- R/MRI kepala 31 Juli 2013
24
30-7-2013
S
O
A
P
Masalah:Suspek tumor kepala
Muntah (-), sakit kepala (-), penglihatankabur (-)
Pemeriksaan fisik : stqaLaboratorium : Hb 11,4 gr/dl, Ht 30 vol%, leukosit5.600/mm3, Trombosit 306.000 /mm3, DC :0/4/0/57/30/9.
Hasil pemeriksaan laboratorium dalambatas normal R/MRI kepala 31 Juli 2013
- IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro) R/aff infus setelah MRI selesai- Ceftriaxone 1x2 gr (7) stop- Parasetamol 3x250 mg (po) bila sakitkepala atau T > 38,5°C- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- R/MRI kepala 31 Juli 2013
7-8-2013
S
O
A
Masalah:Suspek tumor kepala
Muntah (-), sakit kepala (-), demam (-)
Pemeriksaan fisik : stqaHasil MRI kepala: Kesan: tumorintraventrikuler IV sugestif ependimomadengan infiltrasi ke aquaductus Silviidan foramen Magendi. Terdapat sinusitismaksilaris kiri dan mastoiditis kanan.
Tumor intraventrikuler IV sugestifependimoma. Tatalaksana pada ependimoma adalah denganpembedahan, radioterapi dan kemoterapi.Pembedahan sulit dilakukan karena letaktumor yang berdekatan dengan organpenting lainnya dan angka keberhasilanlebih kecil dibandingkan resiko yang
25
P
dihadapi. Penggunaan kemoterapi sampaisaat ini belum secara luas digunakan.Pertimbangan menggunakan radioterapikarena tumor bersifat radiosensitifsehingga diharapkan dapat memberikanhasil maksimal.
- Parasetamol 3x250 mg (po) bila sakitkepala atau T > 38,5°C- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- R/ konsul radioterapi
10-8-2013
S
O
A
P
Masalah:Tumor intraventrikuler IV sugestifependimoma
Muntah (-), sakit kepala (-), demam (-)
Pemeriksaan fisik : stqaHasil konsul radioterapi: Setuju dilakukan radioterapi kuratifdefinitif pada pasien. Akan diberikanradioterapi ekstrim 20x1,8 Gy dilanjutkandengan evaluasi MRI kepala (kontras),setelah itu dilakukan booster pada massatumor sampai total dosis 50-54 Gy.Direncanakan simulator pada tanggal15/8/2013 dan mulai radiasi tanggal16/8/2013. Selama pemberian radioterapidiberikan steroid untuk mengurangi edemaotak. Saran: dilakukan lumbal punksiuntuk mengetahui adakah sel-sel tumorpada LCS.
--
- Parasetamol 3x250 mg (po) bila sakitkepala atau T > 38,5°C- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- R/ LP
26
14-8-2013
S
O
A
P
Masalah:Tumor intraventrikuler IV sugestif
ependimoma
Muntah (-), sakit kepala (-), demam (-)
Pemeriksaan fisik : stqaHasil sitologi PA: Kesan: sitologi LCStidak dijumpai sel-sel ganas maupunproses spesifik.Laboratorium : Hb 13,4 gr/dl, Ht 36 vol%, leukosit7.600/mm3, Trombosit 251.000 /mm3, DC :0/3/0/71/15/11.
Tidak dijumpai adanya sel-sel ganas padaLCS menandakan belum terdapat metastaselebih jauh (tumor terlokalisir).Hasil pemeriksaan laboratorium dalambatas normal, sehingga rencanaradioterapi dapat dijalankan.
- Parasetamol 3x250 mg (po) bila sakitkepala atau T > 38,5°C- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- R/ radioterapi
16-8-2013
S
O
Masalah:1. Tumor intraventrikuler IV sugestif
ependimoma2. Post radioterapi hari 1
Muntah (+), nyeri ulu hati (+), sakitkepala (+), nyeri seluruh badan (+)
KU: Sens : compos mentis, N 100 x/m (i/tcukup), T 36,50C, RR 24x/menit, TD :100/60 mmHg. KS: Kepala: normosefali, NCH(-), conjungtiva anemis (-), pupil bulatisokor, Ø 3/3 mm, RC +/+ N. Thoraks:simetris, retraksi (-). Jantung: bunyi
27
A
P
jantung I-II normal, bising (-), Paru:vesikuler +/+, ronkhi -/-, wheezing -/-,Abdomen: datar, lemas, hepar/lien takteraba, bising usus (+) normal.Ekstremitas: pucat (-), akral hangat, CRT< 2”.Status neurologis : DBN
Adanya muntah, nyeri ulu hati, nyeriseluruh badan, dan sakit kepala merupakanreaksi efek samping dari pemberianradioterapi. Efek samping radioterapidapat berupa gangguan gastrointestinal,edema serebri dan defisit neurologis.Pemberian steroid post radioterapidiharapkan dapat mencegah terjadinyaedema serebri.
- IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro) - Dexamethason 3x7,5 mg (iv)- Ranitidin 2x25 mg (iv) - Antasid syr 3xI C - Tramadol 2x50 mg (iv)- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- Radioterapi
20-8-2013
S
O
A
Masalah:1. Tumor intraventrikuler IV sugestif
ependimoma2. Post radioterapi hari 4
Muntah (+), nyeri ulu hati (+)
Pemeriksaan fisik : stqa
Efek samping radioterapi biasanyaberlangsung dalam waktu 7-14 hari.Pemantauan dilakukan terhadap klinispenderita dan keluhan yang dialami.Pemberian terapi disesuaikan dengankeluhan penderita. Pemeriksaan darahrutin berkala seminggu sekali dilakukan
28
Puntuk memantau efek radioterapi padasumsum tulang.Pemberian steroid hanya selama 3 hari,setelah itu pencegahan edema serebridilanjutkan dengan pemberian gliseroloral.- IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro) - Dexamethason 3x7,5 mg stop; gantigliserol 4x60 cc (po)- Ranitidin 2x25 mg ganti OMZ 2x10 mg(iv) - Antasid syr 3xI C - Tramadol 2x50 mg stop; gantiParasetamol 3x250 mg (po)- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- Radioterapi diteruskan
24-8-2013
S
O
A
P
Masalah:1. Tumor intraventrikuler IV sugestif
ependimoma2. Post radioterapi hari 8
Muntah (-), nyeri ulu hati (-), sakitkepala (-)
Pemeriksaan fisik : stqaLaboratorium : Hb 12,2 gr/dl, Ht 33 vol%, leukosit8.500/mm3, Trombosit 330.000 /mm3, DC :0/9/0/61/18/12.
Pemeriksaan laboratorium dalam batasnormal.Meneruskan radioterapi sampai 30x (Senin-Jumat)
← - IVFD D5 ½ NS gtt 15x/mnt (makro) affinfus- Gliserol 4x60 cc (po) stop- OMZ 2x10 mg (iv) ganti OMZ 1x10 mg(po) - Antasid syr 3xI C
29
- Parasetamol 3x250 mg (po) bila nyerikepala- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- Radioterapi diteruskan
20-9-2013
S
O
A
P
Masalah:1. Tumor intraventrikuler IV sugestif
ependimoma2. Post radioterapi hari 25
Keluhan (-)
Pemeriksaan fisik : stqa
Penderita menunjukkan perbaikan klinisdengan pemberian radioterapi. Perludilakukan evaluasi keberhasilan terapidengan MRI.
- OMZ 1x10 mg stop - Antasid syr 3xI C stop- Parasetamol 3x250 mg (po) bila nyerikepala- Diit: NB 3x1 porsi, F100 3x150 cc- Radioterapi diteruskan- R/ MRI kepala (kontras) menunggujadwal
TINJAUAN PUSTAKA
Tumor sistem saraf pusat merupakan tumor padat
terbanyak pada pasien anak. Insiden tumor otak pada anak
usia kurang dari 15 tahun berkisar 28 per satu juta anak,
dimana insiden tertinggi pada kelompok umur 0-4 dan
terendah pada kelompok umur 10-14 tahun.1,2 Tumor otak
merupakan kelompok neoplasma tersering kedua, setelah
leukemia, yang mengenai kelompok umur tersebut.
30
Klasifikasi tumor otak menurut WHO dikelompokkan
berdasarkan pada lokasi, gambaran histologi dan derajat
malignansi.
Tumor pada ventrikel dibagi atas tumor yang berasal
dari dinding ventrikel, dari pleksus koroideus atau tela
khoroidea, dari sisa sel embrionik dan tumor dari
jaringan lain. Ependimoma berasal dari sel ependimal yang
melapisi dinding ventrikel dan kanalis sentralis medulla
spinalis. Ependimoma ini hanya merupakan 5% dari seluruh
glioma intrakranial. Tumor lebih sering terjadi pada pria
dibandingkan wanita dengan perbandingan 3:2. Puncak
tertinggi terjadi pada usia 5 tahun dan 34 tahun.2,3
Sebanyak 30-40% merupakan supratentorial, terutama
terjadi pada masa dewasa. Sebanyak 60-70% merupakan
infratentorial (25% terjadi pada dewasa, 60-70% terjadi
pada anak-anak).4,5
Berdasarkan letaknya, ependimoma dibagi menjadi 2
bagian dengan batas yaitu tentorium. Tentorium adalah
lapisan tipis yang membagi 2/3 bagian atas otak dengan
1/3 bagian bawah otak. Supratentorial ependimoma terjadi
pada bagian atas tentorium dengan area meliputi ventrikel
lateral dan ventrikel III. Infratentorial ependimoma
meliputi ventrikel IV, batang otak dan serebellum.
Ependimoma dibedakan atas 2 tipe yaitu ependimoma
tipikal atau intraspinal (berasal dari sel ependimal yang
melapisi sistem ventrikel atau sisa dari canalis
sentralis dalam medulla spinalis) dan ependimoma
myxopapiler (terdapat pada conus medularis dan filum
31
terminale). Sebanyak 70% ependimoma intrakranial berasal
dari dinding ventrikel IV terutama dari bagian kaudal dan
dari dinding resesus lateralis.6,7
Sebagian besar ependimoma intrakranial terutama
menyerang anak-anak, ependimoma infratentorial tersering
terjadi pada dekade pertama. Tumor ini tumbuh lambat, dan
hanya sedikit menginvasi jaringan sekitar. Ependimoma
pada ventrikel IV akan menyebabkan terjadi penyumbatan
pada ventrikel IV dan aquaductus sehingga bermanifestasi
sebagai hidrosefalus.
Etiologi
Penyebab ependimoma hingga sekarang belum diketahui.
Beberapa pendapat mengatakan terdapat peran serta virus
(SV40) pada perkembangan ependimoma.12,14 Pendapat ini masih
memerlukan penelitian lebih lanjut.
Manifestasi klinis
Gejala klinis ependimoma tergantung dari lokasi dan
ukuran tumor. Pada neonatus dan bayi, pembesaran kepala
mungkin merupakan gejala awal ependimoma. Pada anak dan
dewasa, mual, muntah dan nyeri kepala merupakan gejala
yang paling sering terjadi.9,10
Gejala yang khas yaitu nyeri kepala, muntah dan
vertigo disertai pandangan kabur atau ganda yang akan
bertambah dengan perubahan posisi kepala. Nyeri kepala
merupakan gejala awal, sering dengan eksaserbasi
paroksismal yang memburuk di pagi hari dan nyeri menjalar
32
ke leher, bahkan sampai ke bahu dan lengan. Muntah dan
papil edema merupakan bukti adanya hidrosefalus yang
terjadi dengan cepat. Sering terjadi kaku leher,
terkadang gejala gangguan serebellum pada anggota gerak
dapat ringan atau tidak ada. Gangguan pada saraf kranial
bersifat ringan.10,11 Tumor dapat mengganggu pusat viseral
di medulla, sehingga dapat terjadi serangan takikardi,
dispnoe, pernapasan tidak teratur, cegukan, berkeringat,
dan gangguan vasomotor.
Diagnosis
Diagnosis tumor intrakranial diawali dengan anamnesa
dan pemeriksaan fisik yang baik. Manifestasi klinis yang
timbul dapat memperkirakan struktur mana yang telah
terganggu. Gejala yang paling sering ditemukan pada
ependimoma adalah gejala-gejala peningkatan intrakranial
akibat obstruksi cairan serebrospinal. Pemeriksaan
penunjang diperlukan untuk menentukan lokasi dan
karakteristik tumor intrakranial secara lebih akurat.
Pemeriksaan pencitraan
Pemeriksaan CT scan dilanjutkan dengan MRI kontras
dapat digunakan untuk mengevaluasi massa di ventrikel IV.
Karakteristik tumor seperti ukuran, vaskularisasi dan
homogenisitas dapat dinilai, serta hubungannya dengan
struktur disekitarnya. Batas tumor yang irreguler
memperkirakan suatu jenis tumor yang invasif dan ganas.
PET (Positron Emission Tomography) scan dapat
memberikan gambaran mengenai aktivitas otak. PET dapat
33
digunakan saat hasil CT scan atau MRI memperlihatkan
kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh radiasi. PET
biasanya digunakan sebagai pemeriksaan tambahan setelah
CT scan atau MRI dilakukan. SPECT (Single Photon Emission
Tomography) memberikan informasi yang hampir sama dengan
PET. Saat ini SPECT mulai digunakan secara luas.
Biopsi merupakan suatu prosedur dimana sample tumor
diambil sehingga mempermudah mengetahui karakteristik
jenis tumor. Sample dapat diambil melalui pembedahan atau
dengan jarum biopsi. Meskipun CT scan atau MRI sudah
dapat mengidentifikasi adanya tumor otak, biopsi
merupakan baku emas untuk menegakkan diagnosa tumor otak.
Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan LCS bermanfaat sebelum tindakan operatif,
karena dapat memberikan informasi dalam mempertimbangkan
diagnosis. Selain itu pemeriksaan LCS berguna dalam
mengevaluasi adanya metastase ke tingkat lebih lanjut.
Terapi
Tindakan bedah
Tindakan bedah pada ependimoma di awal diagnosis
diperlukan untuk mengatasi hidrosefalus yang mungkin
timbul. Namun pembedahan untuk reseksi jaringan tumor
pada ependimoma masih bersifat kontroversi. Sebagian
ahli berpendapat bahwa sebagian besar tumor dapat
dilakukan reseksi terbuka. Sebagian ahlinya berpendapat
bahwa hanya 25% tumor yang dapat direseksi, antara
lain:15,16
34
1. Tumor-tumor yang bersifat radioresisten (tumor
nongerminomal)
2. Tumor jinak (meningioma, teratoma)
3. Tumor well capsulated
4. Belum bermetastasis
Tatalaksana pembedahan pada ependimoma memiliki 3
klasifikasi, yaitu
1. Gross total procedure yaitu tidak ada sisa tumor yang
terlihat atau hanya tumor mikroskopik yang terlihat
dengan mikroskop dan post pembedahan tidak ditemukan
lagi gejala tumor.
2. Near total procedure yaitu terdapat minimal residual
tumor (<10% ukuran tumor) yang dengan pembedahan
kedua tidak akan memberikan keuntungan. Residual
tumor dapat berupa area berukuran <1.5 cm2 atau tumor
ukuran <5 mm.
3. Subtotal / incomplete procedure yaitu masih terlihat
residual tumor paska pembedahan >50% ukuran tumor.
Radioterapi
Terapi radiasi biasa juga disebut radioterapi,
menggunakan X-ray sebagai alat untuk menghancurkan sel
tumor. Radioterapi pada tumor otak meliputi dua bagian,
yaitu kraniospinal dan otak. Pada kasus dimana tidak
dapat dilakukan tindakan pembedahan, pemberian
radioterapi dapat meningkatkan angka ketahanan hidup.
35
Ependimoma bersifat radiosensitif. Jika pada
pemeriksaan MRI tumor mempunyai gambaran uniform dan
mendukung suatu ependimoma, maka beberapa ahli
menyarankan pemberian radioterapi. Bila ada pengecilan
ukuran tumor maka radioterapi dilanjutkan tanpa
tindakan pembedahan.18
Peranan radioterapi terhadap masih terus dievaluasi
terutama efek samping dan angka keberhasilan terapi
pada anak. Kovnar dkk meneliti pasien dengan reseksi
total ependimoma yang diikuti dengan pemberian
radioterapi memberikan angka ketahanan hidup yang lebih
tinggi yaitu 88% dibandingkan dengan hanya reseksi
total yaitu 38%.19
Dosis optimal untuk radiasi yaitu 45-50 Gy digunakan
untuk meningkatkan kontrol lokal terhadap
ependimoma.20,21 Penelitian terbaru menggunakan
hyperfractionated radiation dengan total dosis 69.6 Gy sebagai
terapi ependimoma pada fossa posterior. Radioterapi
membatasi dosis tinggi hanya pada tumor primer dan
dosis minimal pada jaringan normal. Pembatasan dosis
minimal memberikan keuntungan pada anak, akan tetapi
perlu dipertimbangkan juga dengan pemberian dosis
minimal akan meningkatkan kegagalan terapi. Suatu
penelitian awal menggunakan St.Jude protokol (RT-1)
pada 64 anak dengan ependimoma, memberikan hasil dosis
optimal untuk terapi adalah 59.4 Gy.21,22
Pemberian radioterapi berdasarkan umur pasien,
lokasi tumor serta ada tidaknya metastase. Radioterapi
36
tidak diberikan pada pasien berumur < 3 tahun karena
akan memberikan efek keberhasilan yang lebih kecil
dibandingkan efek samping yang ditimbulkan. Apabila
letak tumor terlokalisir, radioterapi diberikan hanya
pada otak. Akan tetapi apabila sudah terdapat
metastase, radioterapi akan diberikan pada kraniospinal
dan otak dengan dosis ekstra (booster) pada lokasi awal
tumor berada. Efek optimal dapat dicapai pada pemberian
radioterapi 5 hari dalam seminggu selama 6 minggu.22,23
Penelitian yang dilakukan oleh Chiu dkk menunjukkan
bahwa pengurangan ukuran tumor dengan pemberian
hyperfractionated radiation selama 6 minggu mencapai 25-30%
ukuran tumor.25
Pada pasien anak perlu dipantau adanya efek samping.
Efek samping dapat berupa masalah yang timbul saat
pemberian radioterapi dan efek jangka panjang pemberian
radioterapi. Masalah yang timbul saat pemberian
radioterapi meliputi mual, muntah, rasa terbakar pada
kulit, rambut rontok, kesulitan menelan, serta efek
pada sumsum tulang berupa penurunan jumlah leukosit dan
trombosit.
Pemberian radioterapi dapat menimbulkan efek samping
jangka panjang berupa gangguan belajar dan gangguan
pertumbuhan. Penelitian oleh Ris dkk menunjukkan adanya
penurunan IQ pada anak usia > 6 tahun dengan tumor
infratentorial yang timbul pada 30 bulan awal pemberian
radioterapi high dose 59.4 Gy. Gangguan pertumbuhan dapat
disebabkan oleh efek langsung radioterapi pada sumsum
37
tulang atau karena gangguan sintesis hormon
pertumbuhan. Gangguan pada sintesis hormon pertumbuhan
biasanya timbul pada tahun pertama setelah pemberian
radioterapi. Pemantauan terhadap efek samping sangat
penting, sehingga efek samping yang bersifat permanen
dapat dicegah dari awal. Pemantauan terhadap hormon
tiroid dan hormon pertumbuhan sebaiknya dilakukan 6
bulan-1 tahun post terapi.26
Kemoterapi
Kemoterapi menggunakan obat-obatan tertentu untuk
membunuh sel tumor. Pemberian kemoterapi biasanya
diberikan setelah tindakan reseksi pembedahan.
Kemoterapi juga diberikan pada anak usia < 3 tahun atau
pada kondisi tidak memungkinkan dilakukan tindakan
radioterapi.
Kemoterapi diberikan untuk meminimalisir jumlah
radiasi efektif yang dibutuhkan untuk seorang anak
dengan ependimoma. Seperti halnya dengan radioterapi,
respon pasien ependimoma terhadap kemoterapi tergantung
histologi tumor.
Prognosis
38
Prognosis pasien anak dengan tumor otak tergantung
dari beberapa faktor, yaitu usia anak, keadaan umum anak,
lokasi tumor, kerusakan struktur sekitar tumor, derajat
metastasis, serta jenis terapi yang didapatkan. Prognosis
pasien dengan ependimoma secara khusus tergantung pada
gambaran histologi tumor dan struktur sekitar yang
terganggu. Tipe tumor akan menentukan jenis terapi yang
dapat digunakan. Pasien dengan ependimoma, prognosisnya
lebih baik karena tumor bersifat radiosensitif.
Modalitas kemoterapi, radioterapi atau pembedahan
digunakan tergantung jenis tumor. Tidak ada
penatalaksanaan khusus untuk mencegah rekurensi
ependimoma. Tindakan pembedahan ulang dapat dilakukan
pada ependimoma yang mengalami rekurensi setelah beberapa
tahun kemudian. Radiosurgeri juga dapat dipertimbangkan
pada tumor-tumor rekuren dengan ukuran diameter kurang
dari 3 cm.
Keberhasilan terapi dapat dipantau melalui MRI yang
dilakukan setiap 3-4 bulan pada 2 tahun pertama diagnosis
ditegakkan. Pemantauan melalui scan untuk menilai
keberhasilan terapi dan kemungkinan rekurensi, disamping
pemantauan dengan menilai gejala klinis penderita.
39
ANALISIS KASUS
Penderita masuk rumah sakit dengan keluhan sakit
kepala. Secara garis besar, penyebab sefalgia dapat
dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu nyeri kepala
vaskuler, muskuloskeletal (nyeri tegang otot), organik
(tumor, malformasi, ensefalopati), psikogenik, dan lain-
lain (peradangan, arthritis, neuralgia).1,2 Berdasarkan
pola sakit kepala, kemungkinan penyebab dapat dibagi
menjadi akut terlokalisir (ISPA misalnya sinusitis,
otitis media, kerusakan pada gigi, disfungsi
temporomandibular; infeksi sistemik misalnya meningitis;
dan perdarahan intrakranial), akut rekuren (migrain),
kronis non progresif (psikis), dan kronis progresif
(tumor, adanya peningkatan TIK).
Dari anamnesa didapatkan sakit kepala yang hilang
timbul, terutama pada pagi hari, saat serangan disertai
muntah dan adanya pandangan kabur. Sakit kepala dirasakan
40
sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit dan terus
memburuk sampai 3 hari sebelum perawatan. Berdasarkan
pola sakit kepala, penderita mengalami sakit kepala yang
bersifat kronis dan progresif, dengan lokasi di belakang
kepala dan menjalar ke leher, kemungkinan penyebabnya
adalah adanya tumor otak atau adanya peningkatan TIK.
Adanya riwayat trauma kepala memungkinkan terjadinya
perdarahan yang bersifat kronik dan memberi gejala klinis
yang sama. Pada pasien tidak ditemukan adanya riwayat
demam, kejang serta penurunan kesadaran, tidak ditemukan
gejala rangsang meningeal, sehingga penyebab sistemik
yaitu meningitis dapat disingkirkan. Etiologi lain
ditelusuri dengan melakukan konsultasi ke bagian mata dan
THT. Hasil konsul ke bagian THT memberi kesan tidak ada
kelainan, sehingga penyebab sefalgia terlokalisir dapat
disingkirkan. Hasil konsul ke bagian mata memberi kesan
adanya papil edema bilateral yang disebabkan oleh
peningkatan TIK, kemungkinan penekanan oleh tumor otak.
Direncanakan pemeriksaan penunjang CT-scan kepala cito
untuk melihat kemungkinan tumor otak atau perdarahan
intrakranial.
Adanya sakit kepala, muntah proyektil, gejala okular
(edema papil, diplopia, pandangan kabur) merupakan gejala
peningkatan TIK. Sakit kepala merupakan keluhan sebagian
besar anak dengan gejala TIK yang meninggi (level of
evidence III). Sakit kepala sering bertambah pada waktu
bangun pagi, dan menjadi makin hebat bila penderita
melakukan kegiatan yang menyebabkan peninggian TIK
41
misalnya batuk, bersin, mengedan atau perubahan posisi
kepala yang tiba-tiba. Sakit kepala cenderung berulang
dan makin menetap sesuai dengan peninggian TIK
selanjutnya. Tumor pada fosa posterior menyebabkan
iritasi serabut posterior medulla spinalis bagian
servikal atas, sehingga menyebabkan rasa sakit di bagian
belakang kepala dan leher.3,4
Muntah merupakan gejala sekunder peningkatan TIK
atau akibat iritasi langsung terhadap inti nervus X atau
pusat muntah di dasar ventrikel IV. Gejala muntah pada
tumor infratentorial sering tidak disertai dengan rasa
mual. Gejala ini mungkin disebabkan oleh distorsi
pembuluh darah dan batang otak. Pada awalnya muntah
timbul waktu bangun pagi, kemudian dapat terjadi pada
setiap waktu.7,8 Pollack dkk menemukan 84% kasus muntah
pada tumor infratentorial dan 35% pada tumor
supratentorial, pada kelompok usia kurang dari 12 tahun.
Berbagai kelainan fungsi okular yang berhubungan
dengan peninggian TIK termasuk edema papil, atrofi optik
sekunder (sering ditafsirkan sebagai penglihatan kabur),
atrofi optik primer, gangguan lapangan penglihatan,
diplopia atau strabismus dan eksoftalmus. Edema papil
merupakan gejala peninggian TIK yang penting, terutama
pada anak dengan ubun-ubun besar yang telah menutup
(level of evidence III). Duffner dkk menemukan sebanyak
88% tumor infratentorial terlihat edema papil.
Diagnosa tumor otak ditegakkan atas dasar gejala
klinis, gejala peninggian TIK, dan gejala neurologik
42
fokal serta dibantu oleh pemeriksaan penunjang.
Pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan adalah foto
rontgen kepala, EEG, pemeriksaan LCS, USG kepala, CT-scan
kepala, MRI dan pemeriksaan patologi anatomi.
CT-scan merupakan pilihan utama untuk menegakkan
diagnosis pada kasus yang dicurigai terdapatnya massa
dalam otak. Prosedur ini memberikan informasi yang lebih
tepat dibandingkan pemeriksaan radiologis lain. CT-scan
dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tumor, menentukan
lokasi dan besar tumor, serta memberi gambaran mengenai
kelainan patologis yang menyertai adanya tumor misalnya
hidrosefalus, edema otak, perdarahan, efek massa,
pembentukan kista dan nekrosis paska radiasi (level of
evidence I).
Hasil CT-scan menunjukkan adanya hidrosefalus yang
kemungkinan disebabkan oleh SOL. Dilakukan konsul ke
bagian bedah saraf dan direncanakan pemasangan VP-shunt
serta penjadwalan MRI untuk melihat letak dan jenis tumor
lebih rinci.
Hasil MRI kepala memberi kesan suatu tumor ventrikel
IV sugestif ependimoma dengan penjalaran ke aquaductus
Silvii dan foramen Magendi. MRI sangat baik dan esensial
untuk mendiagnosa glioma derajat rendah, tetapi untuk
glioma derajat tinggi tidak lebih baik dibandingkan CT-
scan. Pada ependimoma fosa posterior, MRI lebih akurat
dalam menggambarkan lokasi tumor di dalam ventrikel IV
dan yang berekstensi ke luar.
43
Tatalaksana tumor ventrikel adalah dengan tindakan
operatif, radioterapi dan kemoterapi. Tujuan operatif
pada tumor otak adalah bila mungkin mengangkat tumor
secara total. Indikasi reseksi tumor adalah bila tumor
terdapat pada daerah serebellum, lobus frontal dan
temporal yang tidak dominan, dan korteks pre-frontal atau
temporal anterior. Sedangkan kontraindikasi adalah bila
tumor terdapat pada daerah korteks motoris, korteks
sensoris, pusat penglihatan, pusat bicara, hhipotalamus
dan batang otak.
Pada tumor fosa posterior sering terjadi
hidrosefalus obstruktif. Keadaan ini dapat menyebabkan
perembesan cairan serebrospinal melalui dinding ventrikel
ke hemisfer yang berbatasan sehingga menyebabkan edema
interstitial. Selain itu terjadi pula edema peritumor
yang merupakan edema vasogenik. Kedua keadaan tersebut
dapat menyebabkan peninggian TIK.
Pembedahan mempertimbangkan lokasi, ukuran dan jenis
tumor. Pada tumor ventrikel yang lokasinya berdekatan
dengan organ penting otak, sulit dilakukan tindakan
operatif. Ukuran tumor yang terlalu besar juga beresiko
terjadinya komplikasi pada tindakan operatif. Jenis tumor
sangat menentukan apakah tumor bersifat operable atau non
operable. Seringkali tindakan operatif yang dilakukan
adalah memasang shunt untuk menurunkan tekanan intrakranial
yang disebabkan oleh hidrosefalus.
Tatalaksana awal adalah dengan menurunkan
peningkatan TIK. Gejala peningkatan TIK berupa muntah
44
proyektil, sakit kepala dan pandangan kabur pada pasien
ini disebabkan oleh hidrosefalus yang terjadi akibat
adanya obstruksi aliran LCS karena adanya SOL. Terapi
pilihan adalah pemasangan VP-shunt untuk membebaskan
obstruksi aliran LCS. Sebelum pembedahan dilakukan,
pasien diberikan asetazolamide, suatu diuretik yang
bersifat menghambat carbonic anhidrase, sehingga produksi
LCS dapat dihambat.
Kemoterapi menggunakan obat-obatan tertentu untuk
menghancurkan sel tumor. Penggunaan kemoterapi pada tumor
otak masih terbatas, karena susunan saraf pusat relatif
sukar dicapai oleh obat yang diberikan secara sistemik.
Jumlah penderita yang mendapat kemoterapi belum banyak
sehingga sukar untuk menilai hasil pengobatan, toksisitas
obat dan keadaan yang tidak menguntungkan bagi penderita
(level of evidence III).
Kemoterapi biasanya digunakan pada anak dibawah 3
tahun dan pertimbangan dokter untuk tidak melakukan
radioterapi. Penggunaan kemoterapi pada ependimoma masih
bersifat kontroversi. Disamping hasilnya yang kurang
memuaskan, efek samping kemoterapi juga dianggap
memperberat kondisi umum pasien.
Tujuan radioterapi adalah untuk mematikan sel secara
selektif. Radioterapi dapat merupakan pengobatan tambahan
45
dari reseksi subtotal atau sebagai pengobatan definitif
sesudah biopsi, atau bila diagnosis ditegakkan hanya atas
dasar gejala klinis (level of evidence III).
Jumlah radiasi yang diberikan tergantung dari
kecenderungan tumor bermetastasis ke ruang subarachnoid.
Terhadap tumor yang mempunyai risiko tinggi untuk
menyebar ke ruang subarachnoid misalnya medulloblastoma
dan ependimoma ventrikel IV yang sangat ganas, dilakukan
radiasi kraniospinal. Terhadap tumor yang terbatas
metastasenya seperti glioma dan astrositoma
supratentorial derajat rendah, diberikan radiasi lokal
saja.24,25
Pada pinealoma, glioma batang otak, dan tumor
ventrikel IV, radioterapi dapat langsung diberikan
setelah diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis.
Hal ini dilakukan karena ekstirpasi tumor dapat
membahayakan kehidupan penderita.14,15
Pada pasien ini sulit dilakukan tindakan pembedahan
karena letaknya pada ventrikel IV yang berdekatan dengan
vermis serebelum dan pons, sehingga dipertimbangkan untuk
dilakukan radioterapi. Pertimbangan radioterapi juga
berdasarkan jenis tumor yang kemungkinan adalah
ependimoma yang berasal dari ependimal, yang bersifat
radiosensitif.
Optimalisasi radioterapi tergantung pada volume,
dosis dan teknik yang digunakan. Pada pasien yang sudah
menjalani reseksi tumor, seringkali diberikan dosis
konvensional (54-56 Gy) dibandingkan dengan yang belum
46
menjalani reseksi tumor, akan diberikan dosis tinggi
(70,4 Gy). Pemberian dosis juga mempertimbangkan efek
samping yang mungkin timbul. Efek samping yang mungkin
timbul yaitu mual-muntah, sakit kepala, rasa nyeri di
seluruh tubuh, penurunan jumlah leukosit dan trombosit,
dan gangguan gastrointestinal.25,26
Prognosis pada pasien ependimoma bergantung pada
beberapa faktor, yaitu umur anak, kondisi kesehatan anak
secara keseluruhan, lokasi tumor, metastase tumor, jenis
tumor, dan waktu terapi diberikan. Pada pasien yang
menjalani reseksi tumor komplit, angka kelanjutan hidup
adalah 4-5 tahun.21,22 Meskipun demikian, kemungkinan
rekurensi adalah 20-30%. Prognosis terburuk adalah pada
pasien dengan tingkat metastase yang tinggi dan bersifat
non operable. Pada penderita dengan kondisi seperti ini
angka kelanjutan hidup adalah 1-2 tahun, angka ini akan
lebih rendah pada pasien usia kurang dari 5 tahun.25,26
Tujuan pengobatan operasi pada pasien ini adalah
menghilangkan gejala hidrosefalus. Reseksi tumor yaitu
mengangkat jaringan tumor sebanyak mungkin sulit
dilakukan tanpa merusak ventrikel IV. Mortalitas paska
operasi diperkirakan 50% dan kemungkinan hidup 5 tahun
berkisar 33-70%.
Prognosis ependimoma yang terletak supratentorial
dengan ependimoma yang terletak infratentorial lebih
baik. Pada pasien ini, letak tumor adalah infratentorial,
pada dasar ventrikel IV, sehingga sulit dilakukan
pembedahan. Atas dasar pertimbangan inilah dilakukan
47
radioterapi kuratif definitif dengan radiasi ekstrem
diberikan 20x1,8 Gy. Setelah itu dilakukan evaluasi
dengan MRI kepala, dan dilanjutkan booster pada massa
tumor sampai total dosis 50-54 Gy.
PENUTUP
Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Bagian
IKA, Ketua Program Studi IKA dan khususnya supervisor sub
bagian Neurologi Anak, dr. Msy. Rita Dewi, SpA(K); dr.
Syarif Darwin, SpA(K); dr. RM. Indra, SpA, sub bagian
Radiologi dr. SNA Ratnasari Devi ES, SpRad, dan sub
bagian Onkologi-Radioterapi dr. Dini Andriani P,
Sp.Onk.Rad yang telah membimbing saya sehingga laporan
kasus ini dapat diajukan.
48
1. Ries LAG et al: Cancer Statistics Review, 1973-1997.
National Cancer Institute, Bethesda, Md, 2005.
2. Foreman NK, Love S, Thorne R: Intracranial
ependimomas: Analysis of prognostic factors in a
population-based series. Pediatr Neurosurg 24:119-
125, 2001.
3. Perilongo G, Massimino M, Sotti G, et al: Analyses
of prognostic factors in a retrospective review of
92 children with ependimoma: Italian Pediatric
Neuro-oncology Group. Med Pediatr Oncol 29:79-85,
2002.
4. Horn B, Heideman R, Geyer R, et al: A multi-
institutional retrospective study of intracranial
ependimoma in children: Identification of risk
factors. J Pediatr Hematol Oncol 21:203-211, 1999.
5. Sutton LN, Goldwein J, Perilongo G, et al:
Prognostic factors in childhood ependimomas. Pediatr
Neurosurg 16:57-65, 1999-2004.
6. Pollack IF, Gerszten PC, Martinez AJ, et al:
Intracranial ependimomas of childhood: Long-term
outcome and prognostic factors. Neurosurg 37:655-
666, 1995.
7. Rousseau P, Habrand J, Sarrazin D, et al: Treatment
of intracranial ependimomas of children: Review of a
15-year experience. Int J Radiat Biol Phys 28:381-
386, 2003.
8. Robertson PL, Zeltzer PM, Boyett JM, et al: Survival
and prognostic factors following radiation therapy
50
and chemotherapy for ependimomas in children: A
report of the Children’s Cancer Group. J Neurosurg
88:695-703, 2005.
9. Needle MN, Goldwein JW, Grass J, et al: Adjuvant
chemotherapy for the treatment of intracranial
ependimoma of childhood. Cancer 80:341-347, 2005.
10. Nazar GB, Hoffman HJ, Becker LE, et al:
Infratentorial ependimomas in childhood: Prognostic
factors and treatment. J Neurosurg 72:408-417, 2006.
11. Sanford RA, Gajjar A: Ependimomas. Clin
Neurosurg 44:559-570, 1999.
12. Sala F, Talacchi A, Mazza C, et al: Prognostic
factors in childhood intracranial ependimomas.
Pediatr Neurosurg 28:135-142, 2008.
13. Duffner PK, Krischer JP, Sanford RA, et al:
Prognostic factors in infants and very young
children with intracranial ependimomas. Pediatr
Neurosurg 28:215-222, 2006.
14. Merchant TE, Haida T, Wang MH, et al:
Anaplastic ependimoma: Treatment of pediatric
patients with or without craniospinal radiation
therapy. J Neurosurg 86:943-949, 2008.
15. Merchant TE, Jenkins JJ, Burger PC, et al: The
influence of histology on the time to progression
after irradiation for localized ependimoma in
children. Int J Radiat Oncol Biol Phys. In press.
2003.
51
16. Hukin J, Epstein F, Lefton D, et al: Treatment
of intracranial ependimoma by surgery alone. Pediatr
Neurosurg 29:40-45, 2007.
17. Palma L, Celli P, Mariottini A, et al: The
importance of surgery in supratentorial ependimomas.
Long-term survival in a series of 23 cases. Childs
Nerv Syst 16:170-175, 2000.
18. Foreman NK, Love S, Gill SS, et al: Second-look
surgery for incompletely resected fourth ventricle
ependimomas: Technical case report. Neurosurgery
40:856-860, 2005.
19. Kovnar E, Curran W, Tomita, et al:
Hyperfractionated irradiation for childhood
ependimoma: Improved local control in subtotally
resected tumors (abstract). Childs Nerv Syst 14:489,
2007.
20. Vanuytsel LJ, Bessell EM, Ashley SE, et al:
Intracranial ependimoma: Long-term results of a
policy of surgery and radiotherapy. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 23:313-319, 2002.
21. Merchant TE, Zhu Y, Thompson SJ, et al:
Preliminary results from a phase II trial of
conformal radiation therapy for localized pediatric
brain tumors. Int J Radiol Oncol Biol Phys 52:325-
332, 2006.
22. Merchant TE, Goloubeva O, Kiehna EN, et al:
Neurocognitive effects of radiation therapy. 43rd
Annual Meeting of the American Society of
52
Therapeutic Radiology and Oncology. San Francisco,
Nov 4-8, 2008.
23. Merchant TE, Goloubeva O, Pritchard DL, et al:
Radiation dose-volume effects on growthy hormone
secretion. Int J Radiat Oncol Biol Phys 52:1264-
1270, 2002.
24. Ris MD, Packer R, Goldwein J, et al:
Intellectual outcome after reduced-dose radiation
therapy plus adjuvant chemotherapy for
medulloblastoma: A Children’s Cancer Group study. J
Clin Oncol 19(15):3470-3476, 2001.
25. Chiu JK, Woo SY, Ater J, et al: Intracranial
ependimoma in children: Analysis of prognostic
factors. J Neurooncol 13:283-290, 2002.
26. Bouffet E, Perilongo G, Canete A, et al:
Intracranial ependimomas in children: A critical
review of prognostic factors and a plea for
cooperation. Med Pediatr Oncol 30:319-331, 2008.
53
54
DIAGRAM TUMBUH KEMBANG ANAK DENGAN EPENDIMOMA
LINGKUNGAN
Meso:= Bidan 1 km
= Puskesmas 2 km= RSUD 1 jam
= RSMH 6 jam
Makro:Jamsoskes
(+)
Mikro:= Ibu : SMP= ASI 0-2 tahun= Imunisasi dasar lengkap
Mini:= Ayah : SMP= Kerja : Supir ojek= Anak ke 1 dari 3 bersaudara= Sosial ekonomi kurang
ASUH Cukup
ASIH Cukup
ASAH Cukup
KEBUTUHAN DASAR
Neonatus cukup bulan
-
TUMBUH KEMBANG
Bayi sehat
Anak dengan ependimoma
Tatalaksana adekuat:- Pembedahan dan radioterapi - Pencegahan komplikasi-Follow up berkala melalui poli neurologi
Tumbuh Kembang Optimal (?)
Genetik - Heredokonstitusional Baik
-genetik (?)-kurangnya informasi-sosek kurang