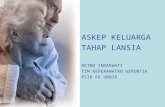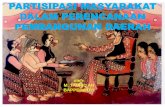Pembangunan dan Keterbelakangan_Kritik 5 Tahap Pembangunan Rostow
Transcript of Pembangunan dan Keterbelakangan_Kritik 5 Tahap Pembangunan Rostow
Kritik Teori 5 Tahap Pembangunan W.W Rostow
I. Sekapur Sirih Tahap Linear Pembangunan Ekonomi Rostow
Berbicara tentang pembangunan, tidak akan lepas korelasinya dengan apa yang dewasa ini
disebut modernisasi. Terlebih lagi di dunia ketiga, dimana indikator pembangunan diukur
berdasarkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan kemajuan teknologi.
Beragam teori barat berusaha diaplikasikan oleh pemerintah. Salah satunya yang terkenal adalah
Lima Tahap Pembangunan milik Rostow. Walt Whitman Rostow merupakan seorang ahli
ekonomi yang teorinya begitu populer dan diadaptasi oleh hampir seluruh negara dunia ketiga
dalam dua dekade terakhir. Berbeda dengan tokoh lainnya yang lebih menekankan pada
pembangunan ekonomi, perhatiannya meluas sampai pada masalah sosiologis dalam proses
pembangunan, meskipun titik berat analisisnya masih tetap pada masalah ekonomi1.
Teori ini berawal dari artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal pada Maret
1956 berjudul The Take-Off Into Self-Sustained Growth pada awalnya memuat ide sederhana
bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek historis kesejarahannya.
Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif identifikasi dimensi
ekonomi tersebut menjadi lima tahap kategori dalam bukunya The Stages of Economic Growth:
A Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960. Sehingga teori milik Rostow
dapat dikelompokkan kedalam linier stages model. Rostow berusaha membendung spirit
sosialisme dengan penciptaan teorinya ini pasca perang dingin yang terjadi di daratan Eropa.
Rostow membuat klasifikasi serta membuat jarak antara sektor tradisional dan sektor
kapitalis modern. Terminologi ‘less developed’ ia gunakan untuk menyebut kondisi suatu negara
yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi ’more developed’ untuk menyebut
kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor
kapitalis modern2.
1 Budiman, Arif, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
2 http://protuslanx.wordpress.com/2010/10/23/teori-tahap-tahap-pertumbuhan-walt-whitman-rostow/
Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi suatu Negara bisa dibedakan kedalam lima
tahap :
a. Masyarakat tradisional (the traditional society)
Pada masyarakat tradisional, sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional
adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih
rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh
struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Menurut Budiman (1995) dalam
masyarakat tradisional ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai , karena masyarakat pada
saat itu, masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan
menusia atau hal gaib. Manusia yang percaya akan hal demikian, tunduk kepada alam dan belum
bias menguasai alam akibatnya produksi sangat terbatas masyarakat tradisional itu cenderung
bersifat statis (kemajuan berjalan sangat lamban) produksi dipakai untuk konsumsi sendiri, tidak
ada di investasi. Sementara dalam perspektif Rostow, pembangunan akan dicapai apabila
terdapat tabungan dan investasi.
b. Tahap Pra-kondisi tinggal landas (the preconditions for takeoff)
Dalam tahapan ini, terjadi perubahan dalam masyarakat yang dapat dikatakan dinamis.
Tingkat investasi menjadi lebih tinggi karena campur tangan pihak luar atau ‘eksternal’.
Masyarakat dalam kategori ini belum memiliki kesadaran kolektif dan terjerat dalam belenggu
konservatisme. Perubahan yang dinamis ini ditandai dengan masuknya teknologi dalam sebuah
negara yang merupakan produk dari lahirnya revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang
mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer
berlebihan. Masyarakat juga mulai memikirkan investasi jangka panjang berupa pendidikan
karena hal ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang disarankan oleh pihak ‘eksternal’
tersebut.
Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi
dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri
(self-sustainable growth). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan
ekonomi akan terjadi secara otomatis3.
Fokus pertumbuhan ekonomi Rostow tidak hanya pada peningkatan tabungan dan
investasi. Lebih dari itu, iklim sosial, ekonomi dan politik merupakan elemen yang mendukung
pembangunan seutuhnya. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang tinggi akan
mengakibatkan tingkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang
dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun menurut Rostow pertumbuhan ekonomi
hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat.
Perubahan yang dimaksud Rostow misalnya kemampuan masyarakat untuk
menggunakan ilmu pengetahuan modern dan inovasi baru yang bisa menekan biaya produksi.
Disamping itu harus ada pula orang-orang yang secara kreatif menjadi wiraswasta untuk
menunjang perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, singkatnya kenaikan
investasi akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan
semata-mata tergantung pada kenaikkan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal
dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik produksi, pengambilan
resiko dan sebagainya. Disinilah perubahan multidimensional diperlukan. Manusia-manusia
kontemporer dengan pemikiran yang open minded dibutuhkan. Maka pada tahap inilah, menurut
Rostow aspek sosiologis dalam pembangunan memiliki peranannya yang signifikan.
Dengan intensifikasi terhadap sektor perekonomian tradisonal (agrarian), diskursus
pembangunan ekonomi mulai ditindaklanjuti. Pertanian sebagai sektor potensial mengingat
sumberdaya alam yang ada dipergunakan secara optimal. Kemajuan di sektor pertanian,
pertambangan dan prasarana harus terjadi semata-mata dengan proses peningkatan investasi.
Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan
sebelum mencapai tahap tinggal landas.
Peranan sektor pertanian tersebut diantaranya, kemajuan pertanian menyediakan bahan
makanan bagi penduduk di pedesaan maupun diperkotaan. Hal ini menjamin penduduk agar
3 Fakih, Mansour, 2009, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta : Insist Press & Pustaka
Pelajar.
tidak kelaparan dan menghemat devisa kerena impor bahan makanan dapat dihindari. Kedua,
kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai kegiatan
industri. Kenaikan pendapatan petani akan memperluas pasar industri barang-barang konsumsi,
kenaikan produktivitas pertanian akan memperluas pasar industri-industri penghasil input
pertanian modern seperti mesin-mesin pertanian dan pupuk kimia, kenaikan pendapatan disektor
pertanian akan menciptakan tabungan yang bias digunakan sektor lain (terutama industri)
sehingga bias meningkatkan investasi di sektor-sektor lain tersebut.
c. Lepas Landas atau Tinggal Landas (take off)
Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakteristik utama
dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak
membutuhkan dorongan dari luar. Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan
yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan
wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode pra kondisi untuk lepas
landas4.
Pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini
terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti seperti revolusi politik, terciptanya
kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. Sebagai akibat dari
perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan
investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan
nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan
perkapita semakin besar.
Untuk mengetahui apakah sesuatu negara sudah mencapai tahap tinggal landas atau
belum, Rostow mengemukakan tiga ciri dari masa tinggal landas yaitu:
1. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5 persen atau kurang
menjadi 10 persen dari Produk Nasional Netto atau NNP.
4 Prayitno, Hadi, 1986, Pengantar Ekonomika Pembangunan Edisi I, Yogyakarta : BPFE.
2. Berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju
perkembangan yang tinggi.
3. Adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa
menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan
pertumbuhan ekonomi terus terjadi.
d. Menuju Kedewasaan (the drive to maturity)
Menurut Budiman (Teori Pembangunan Dunia Ketiga, 1995 : 28) setelah lepas landas
akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi
pasang surut. Pendapatan asional selalu di investasikan kembali sebesar 10% sampai 20%, untuk
mengatasi persoalan pertambahan penduduk.
Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga
60 persen. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri
kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran ekonomi dan sosial.
Pada umumnya, tahapan ini dimulai sekitar 60 tahun setelah tinggal landas. Di Eropa, tahapan ini
berlangsung sejak tahun 1900. Kedewasaan dimulai ketika perkembangan industri terjadi tidak
saja meliputi teknik-tiknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang
diproduksikan bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.
e. Era Konsumsi Tingkat Tinggi (high mass consumption)
Ini merupakan tahapan terakhir dari lima tahap model pembangunan Rostow. Pada tahap
ini, sebagian besar masyarakat hidup makmur. Orang-orang yang hidup di masyarakat itu
mendapat kemakmuran dan keberagaman sekaligus. Masyarakat dalam tahapan ini dikatakan
sebagai masyarakat multikultur yang tidak lagi mempermasalahkan soal produksi, investasi,
melainkan berfokus pada persoalan social welfare.
Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang
paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang
terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pada titik ini,
pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang
kemajuan secara terus menerus5.
Sehingga berdasarkan data deskriptif diatas dapat disimpulkan bahwa :
Karakteristik Masyarakat Berdasarkan 5 Tahap Pembangunan Rostow
No. Tahap Indikator
1. Tahap masyarakat tradisional (the
traditional society)
Pertanian padat tenaga kerja;
Belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi (era Newton)
Ekonomi mata pencaharian;
Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan; dan
Adanya sistem barter.
2. Tahap pembentukan prasyarat
tinggal landas (the preconditions
for takeoff)
Pendirian industri-industri pertambangan;
Peningkatan penggunaan modal dalam pertanian;
Perlunya pendanaan asing;
Tabungan dan investasi meningkat;
Terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional;
Adanya elit-elit baru
Perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar.
3. Tahap tinggal landas (the take-off) Industrialisasi meningkat;
Tabungan dan investasi semakin meningkat;
Peningkatan pertumbuhan regional;
Tenaga kerja di sektor pertanian menurun;
Stimulus ekonomi berupa revolusi politik,
Inovasi teknologi,
Perubahan ekonomi internasional,
Laju investasi dan tabungan meningkat 5 – 10 persen dari
Pendapatan nasional,
Sektor usaha pengolahan (manufaktur)
Pengaturan kelembagaan (misalnya sistem perbankan).
4. Tahap pergerakan menuju
kematangan ekonomi (the drive to
maturity)
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
Diversifikasi industri;
Penggunaan teknologi secara meluas;
5 Abraham, M. Francis, 1991, Modernisasi Di Dunia Ketiga Yogyakarta : Tiara Wacana.
Pembangunan di sektor-sektor baru
Investasi dan tabungan meningkat 10 – 20 persen dari
pendapatan nasional.
5. Tahap era konsumsi-massal
tingkat tinggi (the age of high
mass-consumption)
Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa;
Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan
jasa
Peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran
Karakteristik masyarakat berdasarkan adaptasi dari
http://teacherweb.ftl.pinecrest.edu
II. Mengkritisi Teori Rostow
a. Dualisme Masyarakat Dunia Ketiga
Berbicara seputar pembangunan, tidak lepas kaitannya dengan dualisme yang selama ini
masih dialami oleh Indonesia. Indonesia belum dapat sepenuhnya terlepas dari sistem
masyarakat tradisional yang mengandalkan sektor agraris sementara di lain pihak, tidak
dipungkiri persaingan global memaksa Indonesia untuk melakukan modernisasi di berbagai lini.
Produksi pertanian tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan
pertumbuhan penduduk yang bertambah secara signifikan. Sejalan dengan teori Malthus bahwa
produksi pertanian cenderung mengikuti deret hitung sementara populasi penduduk mengikuti
deret ukur6. Sehingga semakin banyaknya junmlah penduduk berbanding terbalik dengan
ketersediaan pangan yang dimiliki.
Di satu sisi, Indonesia merupakan late comers dalam pembangunan7. Indonesia memang
secara mantap mencanangkan pembangunan dalam kurun waktu 3 dekade terakhir. Namun
seharusnya hal ini (pembangunan-pen) dimulai saat Indonesia masih berada dalam posisi awal
pasca kemerdekaan. Terlepas dari persepsi diatas, pandangan modernisasi beranggapan bahwa
sektor pertanian tidak dapat menaikkan pendapatan, sebagaimana yang dicita citakan oleh
pembangunan. Pembangunan ekonomi hanya akan tercapai apabila terdapat surplus pendapatan
dan tabungan. Sebaliknya, sektor pertanian tidak dapat menghasilkan profit secara produktif.
Diperlukan suatu inovasi baru. Industrialisasi dan perdagangan global digadang-gadang sebagai
cara yang patut diupayakan. There is no other way, except capitalism. Demikian yang
diungkapkan oleh Margareth Teacher, Perdana Menteri Inggris yang sangat mendukung
kontestasi perdagangan era global.
Kembali pada upaya intensifikasi pertanian, nyatanya tidak dapat terealisasikan dengan baik.
Pada awalnya, petani di Indonesia terbiasa menanam padi gogo. Petani di Indonesia, sejalan
dengan pemikiran James Scott masih menganut paham safety first. Tidak masalah jika tidak
mendapat untung, asalkan cukup untuk balik modal dan proses tanam berikutnya. Namun dalam
6 http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Malthus.htm
7 Sukirno, Sadono, 1981, Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Medan : Borta Gorat, hal
16
rangka intensifikasi pertanian, pemerintah memberikan bibit padi IR, pupuk berbahan dasar
kimia, kemudian traktor. Mekanisasi tradisional masyarakat diubah secara revolusioner. Panen
tahap awal berhasil, namun lama kelamaan padi IR susah untuk dipelihara. Dibutuhkan air yang
mengalir serta perawatan yang intensif, baik itu pestisida dan pupuk kimia. Petani tidak bisa
menggunakan pupuk organic seperti yang biasa dilakukan dan pada akhirnya petani tidak
mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan proses penanamannya. Ditambah dengan SDM yang
belum sepenuhnya memahami teknologi. Disinilah letak involusi pertanian terjadi, pemerintah
akhirnya mengimpor kebutuhan beras. Petani lokal seperti dianak tirikan.
Hal ini tertuang dalam tahap tinggal landas Rostow yang secara tersirat mengagungkan
Industrialisasi dan menurunkan peran sektor pertanian. Pada awalnya, Rostow mengatakan
bahwa intensifikasi di bidang pertanian dapat mensejahterakan dan menstabilkan kondisi internal
(pra kondisi lepas landas—pen). Lalu kemudian pada tahap berikutnya, Ia justru
mengesampingkan peran pertanian dan memuja Industrialisasi (kondisi lepas landas hingga masa
konsumsi tingkat tinggi—pen). Argumentasi Rostow tentang pertanian sebagai ciri
keterbelakangan tidak beralasan. Disinilah titik mula ketidakcocokan antara teori Rostow dengan
kondisi masyarakat Indonesia. Di satu pihak, Indonesia digadang-gadangkan sebagai negara
lumbung padi Asia serta wacana swasembada beras pada kala itu. Namun disisi lain Indonesia
juga mengupayakan modernisasi yang tidak seimbang dengan kompetensi sumber daya
manusianya. Dapat dikatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini masih kebingungan
dalam merencanakan plan map bagi Indonesia. Bodohnya lagi, Negara dengan secara terang-
terangan mengadopsi teori ini dan menganggap Teori Rostow sebagai sesuatu yang mutakhir.
Contoh Riil : Intensifikasi Pertanian Gagal
Kembali pada upaya intensifikasi pertanian, nyatanya tidak dapat terealisasikan dengan baik.
Pada awalnya, petani di Indonesia terbiasa menanam padi gogo. Petani di Indonesia, sejalan
dengan pemikiran James Scott masih menganut paham safety first. Tidak masalah jika tidak
mendapat untung, asalkan cukup untuk balik modal dan proses tanam berikutnya. Namun dalam
rangka intensifikasi pertanian, pemerintah memberikan bibit padi IR, pupuk berbahan dasar
kimia, kemudian traktor. Mekanisasi tradisional masyarakat diubah secara revolusioner. Panen
tahap awal berhasil, namun lama kelamaan padi IR susah untuk dipelihara. Dibutuhkan air yang
mengalir serta perawatan yang intensif, baik itu pestisida dan pupuk kimia. Petani tidak bisa
menggunakan pupuk organic seperti yang biasa dilakukan dan pada akhirnya petani tidak
mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan proses penanamannya. Ditambah dengan SDM yang
belum sepenuhnya memahami teknologi. Disinilah letak involusi pertanian terjadi, pemerintah
akhirnya mengimpor kebutuhan beras. Petani lokal seperti dianak tirikan.
b. Teori Rostow Tidak Dapat Digeneralisir dan Berlaku Secara Universal
Berkaca terhadap teori yang dikembangkan Rostow, menurut analisis saya hal tersebut hanya
merupakan kajian referensi teori yang dapat melengkapi indikator saja dalam pembangunan.
Teori Rostow terlalu sederhana untuk diaplikasikan dalam struktur masyarakat Indonesia yang
kompleks. Mansour Fakih dalam bukunya Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi
(2002) menjelaskan prasyarat modernisasi di beberapa negara. Pertama adalah tahap prasyarat
lepas landas yang dialami oleh Negara Eropa, Asia, Timur tengah, dan Afrika, dimana tahap ini
dicapai dengan perombakann masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua
adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh Negara-negara Born free (menurut
Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dimana Negara-negara tersebut mencapai
tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini
disebabkan oleh sifat dari masyarakat Negara-negara tersebut terdiri dari imigran yang telah
mempunyai sifit-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal
landas.
Berdasarkan kutipan pernyataan diatas, secara tersirat Rostow mengungkapkan prasayarat
menuju modernisasi adalah perombakan sistem masyarakat. Masyarakat yang tradisional niscaya
harus mengalami sebuah tahap evolusioner guna melanggengkan proses industrialisasi dengan
melakukan homogenisasi di semua lini. Baik itu di Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika. Pada
kenyataannya sejarah tidak akan berulang dengan cara yang sama. Dengan kata lain, bahwa
setiap pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia tidak selalu sama, tetapi justru punya
karakteristik masing-masing. Lima tahap yang dikemukakan Rostow menganggap bahwa setiap
negara akan mengalami fase serupa. Rostow sendiri mengesampingkan potensi kearifan lokal
dan karakteristik masyarakat yang tidak bisa secara serempak menerima pembaharuan.
Modernisasi memang berhasil di negara Eropa, namun nampaknya menjadi proses yang
terseok-seok dengan kultur masyarakat Asia khususnya Indonesia. Dalam pandangan saya,
Indonesia secara keseluruhan belum mampu memantapkan jati dirinya. Indonesia belum menjadi
negara yang madani sebagaimana yang dicita citakan oleh pendahulu bangsa. sementara
mengapa kenerhasilan modernisasi dapat berhasil di Eropa? Hal ini karena basis struktur civil
societies begitu kuat. Perubahan multidimensional yang diceritakan Rostow pada awalnya
merujuk pada demokrasi yang berjalan dengan lancar disana. Human rights bukan lagi menjadi
persoalan yang diperdebatkan, sistem sosial masyarakat telah berjalan dengan stabil. Cairncross
menjelaskan bahwa masyarakat Eropa memiliki tabungan yang memadai untuk dilaksanakannya
pembaharuan.. Sehingga apabila terjadi chaos dalam pemerintahan, mereka telah memiliki
cadangan riil.
Salah satu indikator sebuah negara telah mengalami pembangunan ekonomi menurut Rostow
adalah Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat
dari ditentukan oleh kedudukan keluarga atau suku bangsanya menjadi ditentukan oleh
kesanggupan dalam melakukan pekerjannya (Prayitno, 1986). Sementara Indonesia berada dalam
sistem otriterian yang melanggengkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini (rezim
otoriterian—pen) menumpulkan ke-kritisan masyarakat. Demokrasi yang dibangun juga
merupakan buatan para elite. Masyarakat kala itu belum memahami apa, mengapa dan seberapa
pentingnya modernisasi. Masyarakat dan Pemerintah tidak mempunyai cukup bekal untuk
melanggengkan modernisasi. Namun disisi lainnya, Indonesia dipaksa untuk bersaing ke ranah
global. Alhasil Indonesia hanyalah negara prematur yang terombang-ambing dalam sistem
global.
c. Kaki tangan kapitalis
Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan sosial yang semula mengarah kedalam
suatu daerah menjadi berorientasi keluar merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi
suatu negara8. Berdasarkan analisis Rostow, ia mengemukakan bahwa dibutuhkan kontak dengan
negara-negara lain untuk meningkatkan iklim investasi yang baik. Negara dapat dikatakan maju
apabila jumlah dana investasi asing yang besar di sektor pertambangan, perbankan dan lain
sebagainya. Negara yang menerapkan teori ini seringkali memperoleh sumberdaya modal dari
8 Abraham, M. Francis, 1991, Modernisasi Di Dunia Ketiga Yogyakarta : Tiara Wacana.
investasi langsung modal asing yang ditanamkan pada bidang pembangunan prasarana,
pembukaan tambang, dan struktur produktif yang lain. Investasi ini biasanya dalam bentuk
pinjaman, baik dari Negara, kreditor, maupun dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank
Dunia, IMF atau dari MNC (Multi Natioanl Corporation). Pinjaman juga sering diberikan pada
pemerintah Negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Dari pola itu
terlihat terdapat ketidakseimbangan posisi karena Negara berkembang tersebut berposisi sebagai
debitor, sedangkan negara asing atau lembaga asing adalah kreditor. Negara berkembang
selanjutnya sering ditekan sehingga yang tampak, pemerintah Negara berkembang tersebut tidak
lebih hanyalah tangan kanan dari Negara asing atau lembaga asing yang ingin mensukseskan
agenda-agenda politik maupun ekonominya di Negara yang sedang berkembang. Negara
berkembang juga seringkali terjerat utang dan sulit untuk menyelesaikan persoalan utang
sehingga menjadikan mereka sulit menuju kemajuan yang diharapkan.
d. Rusaknya lingkungan
Kenaikan pendapatan nasional sejumlah 10% menjadi indikator utamanya berdasarkan teori
ini. Akhirnya negara harus melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya
alamnya sehingga mencapai tingkat investasi produktif di semua sektor. Efek dari teori itu adalah
terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam dan bahan-bahan mentah, tanpa
mempertimbangkan kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.
Kerusakan alam justru berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat tradisional, penurunan
kesehatan, merebaknya penyakit, kerawanan sosial, dsb.
Selain itu, tahap tinggal landas merupakan tahap yang sangat kritis. Dalam teori yang
disampaikan oleh Rostow, ia tidak meberikan gambaran seputar efek samping yang terjadi.
Rostow tidak secara gamblang memberikan gambaran problematika yang kritis dalam tahap
tinggal landas. Rostow tidak memberikan pembahasan yang mendalam bagaimana cara
mengatasi efek negatif dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seperti misalnya efek
kesenjangan sosial, distabilitas sosial dan distabilitas politik yang seringkali justru berakibat pada
kehancuran yang mendalam seperti yang misalnya terjadi di Indonesia.
Pembukaan sektor pertambangan memang membawa keuntungan terhadap Indonesia.
Disamping menjadi kaki tangan kapitalistik karena Indonesia tidak memiliki cukup investasi
untuk mengolahnya. Pertambangan juga membawa resiko bagi kehidupan masyarakat
kedepannya. Kekayaan alam yang terus menerus dikeruk lama kelamaan akan habis.
Pembangunan menghasilkan produktivitas yang tinggi, namun dibarengi dengan dampak
terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak, sementara keepatan bagi alam untuk
melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kerusakan sumber alam tersebut.
Industrialisasi juga menghasilkan limbah yang mengganggu ekosistem lingkungan.
Akibatnya ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada di sekitar. Pembangunan
yang yang berhasil seharusnya memiliki daya pelestarian yang memadai, sehingga akhirnya
pembangunan tidak berkelanjutan (sustainable). SDM yang unggul juga merupakan modal
pembangunan sebuah negara. Namun apabila SDM nya sendiri terkena polutan limbah
berbahaya dan menurunkan kadar kesehatan, lantas bagaimana pembangunan dapat berlanjut?
e. Bukan Hanya Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai indikator pembangunan, seharusnya Rostow juga mengikutsertakan aspek lainnya
selain pertumbuhan ekonomi. Perlunya infrastruktur lainnya seperti sumber daya manusia yang
unggul (pendidikan), jalan-jalan, jalur kereta api, jaringan-jaringan komunikasi serta iklim yang
sehat guna kelancaran pembangunan. Baik itu iklim sosial, iklim berpolitik dan stabilitas
keamanan masyarakat. Aspek humanistis juga harus diperhatikan disini supaya masyarakat tidak
hanya digunakan sebagai alat penyokong pembangunan. Karena SDM yang unggul berpengaruh
besar terhadap pembangunan, disinilah peran institusi-institusi sosial akan sangat signifikan
peranannya.
ANALISA DAN KRITIK TEORI MODERNISASI
“Kritik Terhadap 5 Tahap Pembangunan W.W Rostow”
Mata Kuliah : Pembangunan dan Keterbelakangan
Dosen Pengampu : Suharman M.Si, Fina Itriyati, MA
Dibuat Oleh : Hamada Adzani
NIM : 11/318160/SP/24904
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arif, 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Fakih, Mansour, 2009, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta : Insist Press & Pustaka
Pelajar.
Prayitno, Hadi, 1986, Pengantar Ekonomika Pembangunan Edisi I, Yogyakarta : BPFE.
Abraham, M. Francis, 1991, Modernisasi Di Dunia Ketiga Yogyakarta : Tiara Wacana.
http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Malthus.htm diakses tanggal 20 Oktober 2012 Pukul
17.50
Sukirno, Sadono, 1981, Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Medan : Borta Gorat, hal
16
http://protuslanx.wordpress.com/2010/10/23/teori-tahap-tahap-pertumbuhan-walt-whitman-rostow/ diakses tanggal
20 Oktober 2012 Pukul 19.34
http://teacherweb.ftl.pinecrest.edu diakses tanggal 20 Oktober 2012 Pukul 22.00