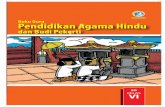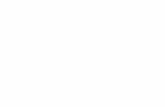makalah moral hindu
-
Upload
ubrawijaya -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of makalah moral hindu
MAKALAH
AJARAN MORAL DARI SISI AGAMA HINDU
“Disusun Sebagai Tugas Mata Kuliah Etika Profesi”
Oleh Kelas M
Anggota Kelompok:
1. Yusuf Ilham A.H 115100900111003
2. Tia Dwi Irawandani 115100913111005
3. Siti Muamanah 115100913111003
4. Rifny Ardianita 115100901111009
5. Mardiyanti Adnan Aksa 115100901111011
6. Ario Wicaksana 115100900111035
7. Patricia
PROGRAM STUDI TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014
BAB I
PENDAHULUAN
I.1Latar Belakang
Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa
Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau
adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), moral
diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara
terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari
segi substantif materiilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya
berbeda. Widjaja (1985) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik
dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Sementara itu
Wila Huky, sebagaimana dikutip oleh Bambang Daroeso (1986)
merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensip rumusan
formalnya yang pertama sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah
laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh
sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Kedua moral adalah
ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau
agama tertentu.
Indonesia merupakan Negara independen dengan enam Negara yang
diakui di wilayahnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29
bahwa setiap warga Negara berhak memilih dan beragama sesuai dengan
keyakinan masing-masing. Dari setiap agama (Islam, Hindu, Budha,
Konghuchu, Kristen Protestan, dan Kristen katolik) tentu mengandung
tujuan baik dengan ajaran moral yang baik pula. Hanya mungkin cara
penyampaian dan cara pengaplikasiannya yang berbeda. Terlepas dari
perbedaan tersebut, moral yang diajarkan tiap agama selalu
menganjurkan ajaran moral tersebut diterapkan kedalam kehidupan
sehari-hari. Tetapi pada era ini adalah masa dimana moral baik sudah
tidak diindahkan pada kehidupan social masyarakat, banyak
kriminalitas dan perilaku negative menyimpang yang dilakukan manusia
tanpa mengingat dasar ajaran moral yang dianut dalam agamanya. Hal
ini menunjukkan kehancuran moral yang menandakan kehancuran bangsa
Indonesia juga. Berangkat dari hal tersebut, makalah kali ini
membahasan ajaran moral kemanusiaan dengan salah satu agama yaitu
agama Hindu.
I.2Tujuan
Pembahasan dari makalah ini bertujuan untuk mengetahui ajaran
moral secara spesifik dari Agama Hindu.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Moralitas
Berbicara moral ternyata yang dimaksudkan adalah sesuatu yang
penting karena moral dimengerti sebagai filsafat, yaitu filsafat
moral. Untuk menunjuk istilah “filsafat moral” dalam kajian teoretis
digunakan “etika”, tetapi dalam pengalaman hidup sehari-hari
penggunaannya sering tidak jelas. Kadang-kadang kata “moral” dan
“etika” digunakan secara bergantian untuk menunjuk suatu fenomena
dari gejala yang sama. Bertens (2002) mengatakan bahwa etika
merupakan filsafat moral atau filsafat yang mempelajari moralitas.
Etika menyelidiki apa itu moralitas, sama seperti filsafat kesenian
menyelidiki apa itu kesenian. Tentang pertanyaan terakhir ini perlu
dikatakan: etika tidak sama dengan cabang-cabang filsafat yang lain
dalam arti bahwa ia membatasi diri pada pertanyaan “apa itu moral?”.
Oleh karena itu, ada baiknya dengan mempelajari terlebih dahulu
cara-cara kata itu dipakai bersama dengan beberapa istilah yang
dekat dengannya.
Bertens (2002) menjelaskan bahwa kata “moral” berasal dari bahasa
Latin mos (jamak: mores) yang berarti juga kebiasaan, adat. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), kata mores masih dipakai dalam
arti yang sama. Jadi, etimologi kata “etika” sama dengan etimologi
kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat
kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda, yaitu yang pertama berasal
dari bahasa Yunani, sedangkan yang kedua berasal dari bahasa Latin.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 1988), “etika” dijelaskan dengan membedakan tiga
arti, yaitu “(1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk,
tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau
nilai yang berkenan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.
Tentang kata moral yang etimologinya sama dengan etika, walaupun
bahasa asalnya berbeda, tetapi memiliki arti yang sama, yaitu adat,
kebiasaan. Akan tetapi, kata moral yang artinya sama dengan etika
menurut arti pertama tadi, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur
tingkah lakunya. Sebaliknya, “moralitas” (dari kata sifat Latin
moralis) mempunyai arti yang pada dasarnnya sama dengan “moral”
hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang “moralitas suatu
perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya.
Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang
berkenan dengan baik dan buruk.
Sampai di sini telah diperoleh pengertian moralitas, tetapi ada
baiknya mengetahui bagaimana istilah “moralitas” digunakan bersama
istilah-istilah lain yang dekat dengannya. Seperti dijelaskan oleh
Bertens (2002) bahwa kata Inggris amoral berarti “tidak berhubungan
dengan konteks moral”, “di luar suasana etis”, “non-moral”.
Sebaliknya, immoral berarti “bertentangan dengan moralitas yang
baik”, “secara moral buruk”, “tidak etis”. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia yang baru tidak dimuat kata “immoral”, sedangkan terdapat
kata “amoral” yang dijelaskan sebagai “tidak bermoral, tidak
berakhlak”. Pengertian ini mengacaukan arti amoral dan immoral. Oleh
karena itu, dikatakan sebaiknya kata “amoral” diartikan sebagai
“netral dari sudut moral” atau “tidak mempunyai relevansi etis”.
Seperti telah diuraikan di atas bahwa moralitas hanya terdapat
pada manusia dan tidak terdapat pada makhluk lain. Oleh karena itu
banyak filsuf berpendapat bahwa manusia adalah binatang-plus, yaitu
binatang dengan ditambah suatu perbedaan khas. Perbedaan khas itu
adalah rasio, bakat untuk menggunakan bahasa (symbol), kesanggupan
untuk tertawa, untuk membikin alat-alat, dan seterusnya. Mungkin
semua ciri ini dapat diterima sebagai sifat khas manusiawi, tetapi
sekurang-kurang harus ditambah satu lagi, yaitu manusia adalah
binatang-plus karena mempunyai moral. Moralitas merupakan suatu ciri
khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain di bawah
tingkat manusiawi. Pada binatang tidak ada kesadaran tentang baik
dan buruk, tentang yang boleh dan dilarang, tentang yang harus
dilakukan dan tidak pantas dilakukan.
Mengenai kata “harus” merupakan keharusan moral. Kaharusan ini
didasarkan atas suatu hukum moral. Hukum moral tidak dijalankan
dengan sendirinya, karena merupakan semacam imbauan kepada kemauan
manusia. Hukum moral mengarahkan diri kepada kemauan manusia dengan
menyuruhnya dia untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan juga bahwa
hukum moral mewajibkan manusia, maka keharusan moral adalah
kewajiban. Keharusan moral didasarkan pada kenyataan bahwa manusia
mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma. Norma adalah
hukum, tetapi manusia sendiri harus menaklukkan diri pada norma-
norma itu. Manusia harus menerima dan menjalankannya.
2.2Moralitas dalam Ajaran “KARMAPHALA”
Agama Hindu mengenal lima ajaran Sradha (keyakinan) yang kita
kenal dengan Panca Sradha yang terdiri dari Brahman, Atman,
Karmaphala, Punarbhawa, dan Moksa.
a. Brahman yaitu percaya dan yakin tentang adanya Sang Hyang
Widhi (Tuhan) sebagai sumber dan kembalinya yang ada.
b. Atman artinya yakin dan percaya adanya percikan terkecil dari
Tuhan yang menghidupi semua makhluk hidup dan juga bisa
disebut dengan leluhur yang telah melahirkan, memelihara, dan
mendidik kita.
c. Karmaphala yaitu percaya dan yakin tentang adanya buah
perbuatan. Segala yang kita lakukan pasti akan mendatangkan
hasil (pahala) entah itu perbuatan baik maupun buruk.
d. Punarbhawa yaitu yakin dan percaya tentang adanya kelahiran
berulang-ulang sebagai akibat dari pada pahala yang belum
habis kita nikmati pada kehidupan yang sebelumnya.
e. Moksa yaitu yakin dan percaya tentang adanya kelepasan atau
kebebasan sang atman dari belenggu punarbhawa dan mampu
menyatu (Manunggaling kawulo lawan Gusti).
Manusia berasal dari Brahman dan nantinya akan kembali ke Brahman
yang kita sebut dengan Moksa yang merupakan tujuan tertinggi dalam
Hindu. Untuk dapat mencapai Moksa, sang Atma yang menghidupi makluk
hidup yang disebut dengan jiwatman harus menanamkan karma yang baik
sehingga mampu memetik pahala yang sempurna sehingga mampu lepas
dari belenggu Punarbhawa. Ajaran Karmaphala merupakan kontrol dari
manusia untuk selalu melakukan dan menanamkan perbuatan-perbuatan
baik yang berguna untuk memperbaiki kehidupan sebagai hakekat dari
Tujuan Utama Manusia dilahirkan. Seperti tersirat di dalam
Sarasamuccaya Sloka 2 dan 3 berikut:
"Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wenang gumawayaken ikang subha
asubhakarma, kuneng panentasakena ring subhakarma juga ikang asubhakarma
phalaning dadi wwang" Artinya : “diantara semua makhluk hidup, hanya
yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melaksanakan
perbuatan baik ataupun buruk, leburlah ke dalam perbuatan baik,
segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya menjadi
manusia”
"apan iking dadi wwang, uttama juga ya, nimittaning mangkana, wenang ya tumulung
awaknya sangkeng sengsara, makasadhanang subhakarma, hinganing kottamaning dadi
wwang ika" Artinya : “ menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-
sungguh utama, sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya
dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan
berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi
manusia.”
Kelahiran itu adalah suatu anugrah dan juga suatu musibah bagi
mereka yang mengerti arti dari kelahiran itu sendiri. Anugrah jika
kita mampu memahami kelahiran kembali ini merupakan alat untuk
mencapai kesempurnaan (moksa), dan musibah karena kelahiran kita
merupakan alat untuk menerima pahala-pahala kita yang belum sempat
kita nikmati pada masa kehidupan sebelumnya, dan akan lebih parah
lagi jika dalam kehidupan ini kita tidak mampu berbuat baik.
Karmaphala sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan
ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami hakekat tentang karmaphala,
maka manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan
tercela yang jelas-jelas keluar dari ajaran agama dan menyebabkan
kerugian, kehancuran bagi orang lain. Semua karma (perbuatan) yang
kita lakukan tidak bisa telepas dari pahala yang akan kita dapatkan.
Pahala yang nantinya akan kita dapatkan tidak dapat ditebus oleh
apapun. Hal inilah yang menyebabkan umat Hindu yang memahami ajaran
karmaphala akan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.
Berpikir akan dampak yang akan didapatkan dan mengerti kalau dampak
atau akibat dari perbuatan kita tidak bisa kita hindari. Karmaphala
adalah ajaran keadilan tertinggi bagi manusia, dimana karma kita
yang merupakan jaminan dalam persidangan tertinggi (Karmaphala).
Karmaphala tidak dapat dihindari, karena ajaran karmaphala
sendiripun dibagi menjadi tiga yang diantaranya yaitu :
1. Sancita karmaphala yang berarti bahwa hasil perbuatan pada
masa lalu akan kita nikmati pada kehidupan sekarang.
2. Prarabda karmaphala yang artinya hasil perbuatan masa sekarang
dinikmati juga pada kehidupan yang sekarang.
3. Kriyamana Karmaphala yang artinya hasil perbuatan kita
sekarang akan kita terima pada kehidupan yang akan datang.
Berdasarkan atas ketiga hal itulah, maka manusia Hindu hendaknya
mampu mengendalikan dirinya dalam segala hal, terutama di dalam
mengejar arta, kama dalam kehidupan ini harus berlandaskan atas
dharma (kebenaran). Karena jika kita mengejar arta dan kama tanpa
dasar daripada dharma maka pastilah pahala dari karma yang akan kita
peroleh akan lebih buruk dan menyesatkan sang Atman untuk mencapai
Sang Brahman, dan selamanya kita akan tidak bisa telepas dari
belenggu Punarbhawa, dan akibat terburuk dari pada pahala yang akan
kita terima yaitu kita dilahirkan menjadi binatang berbisa.
Ajaran Karmaphala akan selalu mengingatkan kita akan semua
perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan selalu berdasarkan atas
dharma dan pahala, maka yakinlah kehidupan moral manusia akan
semakin meningkat, tidak akan ada kekerasan, kerakusan, dan
keegoisan sehingga kehidupan manusia akan menjadi hamonis, penuh
dengan kedamaian, dan penuh dengan bhakti yang tulus kehadapan
Tuhan, saling menghargai sesama manusia, dan saling merasakan apa
yang orang lain rasakan.
2.3Moralitas dalam Ajaran “BHAGAVADGITA”
Bhagavadgita merupakan Upanisad yang terdiri atas Brahmavidya dan
Yogasastra, seperti dijelaskan pada setiap akhir bab yang membahas
suatu topik secara khusus. Walaupun kitab ini terdiri atas 18 bab
dan 700 seloka, tetapi pada intinya mengandung lima tema ajaran,
yaitu tentang
(1) Brahman (Tuhan),
(2) Atman (hidup),
(3) Prakrti (material),
(4) Kala (waktu), dan
(5) Karma (perbuatan).
Brahman dijelaskan sebagai kenyataan utama, satu tiada duanya, di
luar batas nama dan rupa, tanpa sifat, tanpa permulaan, pertengahan,
dan akhir. Brahman, juga dikatakan sebagai kebenaran yang tak
berubah, di luar batas ruang, waktu, dan sebab-akibat. Agar dapat
dipercaya maka Brahman tak terbatas mewujudkan dirinya sebagai alam
semesta dan makhluk hidup melalui maya-Nya. Ini dikatakan sebagai
Isvara. Brahman, Tuhan Yang Maha Esa juga dijelaskan sebagai
pengendali. Artinya, segala sesuatu bekerja dibawah kehendak dan
perintah-Nya. Ketika menjadi hidup dari hidupnya segala makhluk ,
Brahman disebut Atman.
Atman, para jiwa atau makhluk hidup diakui oleh Tuhan sebagai
bagian dari diri-Nya yang mempunyai sifat sama seperti-Nya. Makhluk
hidup adalah isvara-isvara kecil yang takluk. Artinya, makhluk hidup
adalah prakrti yang utama. Alam material atau alam semesta merupakan
prakrti yang lebih rendah atau alam rendah. Kedua prakrti ini, baik
alam semesta maupun makhluk hidup semuanya tunduk, dikuasai, dan
dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan dalam
Gita.VII.5 bahwa inilah prakrti-Ku yang lebih rendah, tetapi berbeda
dengannya, ketahuilah prakrti-Ku yang lebih tinggi, unsur hidup,
yaitu jiwa yang mendukung alam semesta ini. Dalam seloka ini Tuhan
hendak menyatakan unsur-unsur kandungan-Nya yang terdiri atas
prakerti atau material dan jiwa-hidup sebagai esensi dari realitas
yang dinyatakan pula sebagai unsur pendukung yang lebih tinggi.
Prakrti atau alam semesta dimanifestasikan melalui ruang, waktu,
dan penyebab (desa-kala-nimitta). Ruang tercipta ketika manusia dan
makhluk hidup lainnya mendapatkan badan. Waktu tercipta ketika
manusia mulai berpikir. Penyebab, yaitu karma atau perbuatan
tercipta ketika manusia dibatasi. Artinya, Gita memberikan pelajaran
tentang apa itu Tuhan, apa itu makhluk hidup atau jiwa, apa itu
manifestasi alam semesta, dan bagaimana alam semesta dikendalikan
oleh waktu, serta bagaimana kegiatan (karma) para makhluk hidup.
Oleh karena itu, manusia adalah ilahi. Sifat sejatinya adalah atman
tak terbatas, abadi, suci identik dengan brahman. Tujuan kehidupan
manusia adalah untuk menyadari keilahiannya dan tujuan agama adalah
untuk mengajar manusia bagaimana memanifestasikan keilahian dalam
dirinya. Jadi, ajaran ini hanya dapat dipahami berdasarkan panca
sradha, yaitu keimanan Hindu.
Alam material memiliki tiga sifat yang disebut triguna, yaitu
sattva, rajah, dan tamah. Satva sebagai sifat kebaikan, rajah
sebagai sifat nafsu, dan tamah sebagai sifat kebodohan. Dalam
Gita.XIV.5 dijelaskan bahwa sattva – rajah – tamah, ini adalah guna
(sifat hakikat) yang lahir dari prakrti, yang mengikat penghuni
badan yang kekal dengan eratnya. Dari seloka ini dapat diketahui
bahwa yang mengikat Sang Jiwa di dalam raga adalah sifat-sifat dari
prakrti, yaitu triguna. Sifat sattva memancar karena kesuciannya,
rajah bersumber pada nafsu yang lahir dari keterikatan pada
keinginan, dan sifat tamah lahir dari kebodohan. Hal ini diuraikan
dalam Gita.XIV.16 bahwa dinyatakan hasil perbuatan orang yang
sattvika memperoleh kesucian, pahala sifat rajah adalah penderitaan,
sedangkan kebodohan adalah pahala sifat tamah.
Dalam Gita.XIV.17 dinyatakan bahwa dari sifat sattva muncul
kebijaksanaan dan dari sifat rajah (timbul) loba, serta dari tamah
timbul ketidakpedulian dan kesalahan, demikian juga kebodohan. Dalam
Gita.XIV.18 ditegaskan pula bahwa ke atas perginya yang sattvika, di
tengah-tengah bersemayamnya yang rajahika, sedangkan yang tamahika
ke bawah perginya diantar sifat keadaan yang paling rendah. Jadi,
apabila rajah memberi dorongan kepada sattvam maka timbul
kebijaksanaan dan apabila rajah memberi dorongan pada tamah akan
muncul sifat-sifat kebodohan yang terbingungkan. Apabila rajah hanya
menggunakan kekuatan bagi dirinya sendiri maka lahir kegiatan-
kegiatan secara terus-menerus, yaitu kelobaan. Artinya, rajah adalah
inti sebagai asas kekuatan dari gerak yang dinamis, sedangkan
sattvam dan tamah keduanya sama-sama hanya memiliki sifat statis
yang apatis. Di atas ketiga sifat tersebut ada waktu yang kekal dan
kegiatan yang disebut karma terjadi karena gabungan dari sifat-sifat
alam tersebut di bawah pengendalian dan pengawasan waktu. Kegiatan
tersebut dilakukan sejak masa lampau, dari waktu ke waktu, dan
manusia menikmati hasilnya sebagai penderitaan. Inilah yang disebut
karma.
Gita memandang bahwa manifestasi alam semesta ini terjadi dalam
jangka waktu tertentu, bertahan selama beberapa waktu, dan kemudian
lenyap. Akan tetapi, peredaran ini berjalan terus-menerus dan
selamanya. Oleh karena itu, prakrti adalah kekal walaupun
keberadaannya hanya sementara. Manifestasi dunia tidak dianggap
palsu, tetapi sebagai sesuatu yang nyata yang benar-benar ada, dalam
Gita.VII.5 dikatakan bahwa prakrti ini sebagai prakrti-Ku. Alam
semesta adalah tenaga yang terpisah dengan Yang Maha Esa, sedangkan
makhluk hidup adalah tenaga dari Yang Maha Esa. Makhluk hidup
mempunyai hubungan yang kekal dengan Tuhan. Jadi, Tuhan, makhluk
hidup, alam semesta, dan waktu semua mempunyai hubungan antara yang
satu dengan yang lain dan semuanya adalah kekal. Akan tetapi karma,
yaitu perbuatan tidaklah kekal, dan karenanya boleh jadi karma
merupakan tema sentral dalam Gita.
Setiap kelahiran disebabkan oleh benih karma masa lampau dan
setiap kelahiran adalah untuk menikmati hasil karma masa lampau.
Oleh karena itu, setiap kelahiran sudah pasti diikuti oleh kematian,
seperti dijelaskan dalam Gita.II.27 bahwa sesungguhnya setiap yang
lahir, kematian adalah pasti, demikian pula setiap yang mati
kelahiran adalah pasti, dan ini tak terelakkan. Artinya, manusia
meninggalkan bekas perbuatannya pada masa kini, dan ini yang
menyebabkan kelahiran berulang-ulang. Oleh karena itu, setiap
kelahiran merupakan masa untuk meningkatkan kualitas karma atau
perbuatan. Sebelum karma itu mencapai kesempurnaan dan kebebasan
selama itu pula kelahiran dan kematian akan dialami secara terus
menerus. Jadi, di samping untuk menikmati karma masa lalu,
terpenting dari kelahiran adalah untuk menyempurnakan karma atau
perbuatan masa kini agar mencapai pembebasan. Dalam hal ini, dasar-
dasar moralitas sebagai panduan perbuatan sesuai dengan kitab suci
mutlak diperlukan.
Kedudukan Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai kesadaran yang
tertinggi. Makhluk hidup sebagai prakrti merupakan bagian dari Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan, yaitu
sadar. Akan tetapi, prakrti yang lain karena terpisah dari Tuhan
maka ia tidak memiliki kesadaran. Artinya, manusia sadar hanya pada
(badan) dirinya sendiri, sedangkan Tuhan sadar secara sempurna
sehingga sadar akan segala badan. Hal ini disebabkan kerena Tuhan
bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup, Beliau sadar akan
gerak-gerik batin para jiwa masing-masing. Paramatma, Kepribadian
Yang Maha Esa bersemayam di dalam hati setiap manusia sebagai
isvara, yaitu kepribadian yang mengendalikan segala tindakan dan
kehendak makhluk hidup. Artinya, baik kesadaran Tuhan maupun
kesadaran manusia merupakan kesadaran yang bersifat rohani.
Kesadaran ini disebut kesadaran lain karena berada di luar
pengetahuan konvensional, di luar kesempurnaan alat candra dan
empiri manusia.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Gita memandang manusia
dari dua dimensi tubuh, yaitu yubuh jasmani dan tubuh rohani.
Realitas dalam segala manifestasinya merupakan kesatuan dari yang
Satu ketika menjadi dua, yaitu jiwa dan raga. Seperti dijelaskan
dalam Gita II.13 bahwa sebagaimana halnya sang roh itu ada pada masa
kecil, masa muda dan masa tua demikian juga dengan diperolehnya
badan baru, orang bijaksana tak akan tergoyahkan. Demikian sang roh
itu ada dalam badan yang terus menerus mengalami perubahan dari masa
kanak-kanak sampai usia tua dan sampai sang roh masuk ke badan lain
pada waktu meninggal. Manusia menjadi lupa akan esensinya sebagai
roh individu karena dipengaruhi oleh maya atau kekuatan alam
material, yaitu sattva, rajah, dan tamah.
Oleh karena itu, Gita mengajarkan empat cara atau jalan (yoga)
agar manusia memperoleh kembali kesadarannya sebagai sang diri dan
bukan badan jasmani.
Karmayoga merupakan perbuatan tanpa pamrih.
Jnanayoga merupakan jalan kebijaksanaan.
Bhakti dengan jalan pengabdian.
Rajayoga dengan jalan meditasi.
Jalan ini sebagai sarana yang bisa mengantarkan manusia sampai pada
kesadaran murni, yaitu sang diri sadar akan Jati Dirinya. Dikatakan
demikian karena tat tvam asi mengajarkan bahwa engkau adalah itu.
Jadi, engkau bukan badan ini, badan ini bukanlah engkau. Dalam Weda
dikatakan dengan “Brahman Atman Aikyam”, dan atau “Aham Brahman
Asmi”.
Walaupun untuk menyempurnakan karma Gita telah memberikan empat
jalan utama, tetapi Gita juga memberikan dasar-dasar moralitas
sebagai penuntun bagi pikiran, ucapan, dan tindakan agar senantiasa
berada dalam kerangka dharma. Perbuatan yang diperintahkan dan harus
dilaksanakan Gita mengidentifikasikannya melalui sifat-sifat manusia
yang mulia, yaitu sifat-sifat devata. Akan tetapi, perbuatan yang
dilarang dan tidak boleh dilaksanakan Gita mengidentifikasikannya
melalui sifat-sifat manusia yang jahat, yaitu sifat-sifat raksasa.
Hal ini diuraikan sebagai berikut.
Gita menjelaskan bahwa ada dua jenis makhluk ciptaan, yaitu yang
mulia dan yang jahat, seperti uraikan dalam XVI.6 bahwa ada dua
jenis makhluk ciptaan di dunia ini, yaitu yang mulia dan yang jahat.
Artinya, sebagai makhluk hidup manusia juga ada dua jenis, yaitu
yang mulia dan yang jahat. Ciri-ciri manusia yang mulia itu dirinci
pada Gita.XVI.1—3 sebagai sifat-sifat devata, yaitu dalam
a. Gita.XVI.1 dijelaskan bahwa tak gentar, kemurnian hati,
bijaksana, mantap dalam mencari pengetahuan dan melakukan
Yoga, dermawan, menguasai indera, berkurban, dan mempelajari
kitab suci, melakukan tapa, dan kejujuran. Dalam
b. Gita.XVI.2 dijelaskan bahwa tidak menyakiti, benar, bebas dari
nafsu amarah, tanpa keterikatan, tenang, tidak memfitnah,
kasih sayang terhadap sesama makhluk, tidak dibingungkan oleh
keinginan, lemah lembut, sopan, dan berketetapan hati.
Selanjutnya dalam
c. Gita.XVI.3 dijelaskan bahwa cekatan, suka memaafkan, teguh
iman, budi luhur, tidak iri hati, tanpa keangkuhan, semuanya
ini adalah harta dari dia yang dilahirkan dengan sifat-sifat
devata. Ini merupakan dasar-dasar moralitas yang dinyatakan
dengan pernyataan positif sehingga yang harus dilaksanakan.
d. Sebaliknya, manusia yang jahat dilahirkan dengan memiliki
sifat-sifat raksasa diuraikan dalam Gita.XVI.4 – 20 sebagai
berikut:
Dalam seloka 4 disebutkan bahwa berpura-pura, angkuh,
membanggakan diri, marah, kasar, bodoh.
Dalam seloka 5 disebutkan bahwa sifat-sifat ilahi
dipandang sebagai jalan yang menyesatkan atau jalan menuju
keterikatan.
Dalam seloka 6 dipertegas lagi mengenai keberadaan dua
jenis manusia, yaitu yang suci atau mulia (bersifat
devata) dan yang jahat (bersifat raksasa).
Dalam seloka 7 dijelaskan bahwa yang jahat tidak
mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak
memiliki kemurnian kelakukan baik dan benar.
Dalam seloka 8 dijelaskan bahwa mereka mengatakan “dunia
ini tidak nyata, tanpa dasar moral, tanpa Tuhan, yang
timbulnya hanya karena hubungan yang disebabkan oleh hawa
nafsu birahi, lain tidak”.
Dalam seloka 9 dikatakan bahwa jiwa yang rusak dengan
pengertian picik timbul karena pandangan yang teguh ini
menimbulkan perbuatan keji yang menonjol untuk memusnahkan
dunia sebagai musuhnya.
Dalam seloka 10 disebutkan bahwa mereka yang memiliki
sifat berpura-pura, kebanggaan, dan kesombongan.
Dalam seloka 11 dijelaskan bahwa mereka yang memiliki
keinginan yang tak habis-habisnya dengan menganggap
pemuasan nafsu keinginan sebagai tujuan utama.
Dalam seloka 12 dijelaskan bahwa mereka yang dibelenggu
oleh ratusan ikatan harapan, menyerahkan diri kepada nafsu
dan kemarahan serta berusaha mengumpulkan kekayaan demi
kepuasan nafsu dengan jalan yang tidak halal.
Dalam seloka 13 disebutkan bahwa mereka berpikir hari ini
telah kudapatkan, keinginan ini harus kupenuhi, ini
kekepunyaaku dan kekeyaan itu juga akan menjadi milikiku
nanti.
Dalam seloka 14 disebutkan bahwa mereka yang berpikir
musuh ini telah kubunuh dan yang lain akan kubunuh pula,
aku adalah penguasa, aku adalah penikmat, aku berhasil,
berkuasa, dan bahagia.
Dalam seloka 15 disebutkan bahwa mereka yang berpikir aku
kaya raya dan kelahiran bangsawan dan mengkhayal dalam
ketololan.
Dalam sloka 16 bahwa mereka yang terperangkap dalam
berbagai macam pikiran yang membingungkan, terseret ke
dalam pemuasan nafsu yang menjijikkan.
Dalam seloka 17 disebutkan bahwa mereka yang senang memuji
diri sendiri, benar sendiri, bangga dan mabuk akan harta
dan tidak mengindahkan peraturan.
Dalam seloka 18 disebutkan bahwa mereka yang memiliki
kebiasaan buruk, membohongi diri sendiri dengan keakuan,
kekuatan, kesombongan, nafsu dan kemarahan serta membenci
Tuhan yang ada di dalam dirinya.
Dalam seloka 19 disebutkan bahwa mereka yang membensi dan
mencampakkan diri sendiri.
Dalam seloka 20 disebutklan bahwa mereka yang
terbingungkan terjerumus dalam kandungan raksasa sehingga
jatuh ke jalan yang paling rendah.
Semua sifat raksasa ini dipertentangkan dengan sifat-sifat devata
yang telah teridentifikasi melalui sat, cit, dan ananda seperti
telah dijelaskan di atas. Sesungguhnya sifat-sifat raksasa itu
bersumber dari nafsu dalam bentuknya berupa keinginan-keinginan,
kemarahan, keserakahan, keangkuhan, kebodohan, dan kebingungan.
Sifat-sifat ini dikatakan sebagai jalan menuju ke neraka, yaitu
jurang kehancuran diri. Oleh karena itu, ini merupakan larangan dan
sama sekali tidak boleh dilaksanakan. Seperti dijelaskan dalam
Gita.XVI.21 dikatakan bahwa tiga pintu menuju ke neraka, jurang
kehancuran diri, yaitu kama, kroda, dan loba. Jadi, ada tiga gerbang
menuju ke gelapan atau kehancuran, yaitu nafsu dalam wujudnya
berbagai keinginan, rasa marah, dan keserakahan. Pemenuhan terhadap
nafsu merupakan pemuasan yang membabi buta, sedangkan rasa marah
timbul kalau jalan ke arah pemuasan nafsu ini terhalang. Keserakahan
adalah salah satu nafsu untuk memperkaya diri sendiri dengan objek-
objek duniawi, baik secara material maupun psikologis yang
sebenarnya demi memenuhi nafsu indera-indera pribadi. Hal ini
bertentangan dengan realitas raga manusia yang dikatakan hanya
sebagai instrumen atau alat untuk memenuhi kebutuhan spiritual.
Potensi spiritual yang ada di dalam diri setiap manusia
sebenarnya merupakan kekuatan luar biasa yang sekiranya dapat
digunakan secara baik dan benar akan memungkinkan mencapai Yang Maha
Esa dengan lebih sempurna. Akan tetapi bila manusia berjalan di atas
jalan nafsu dan keserakahan maka ia akan menghadapi oposisi dari
pihak lain karena ia berjalan di jalan yang salah. Jalan yang salah
ini berarti bertentangan dan berlawanan dengan dharma sebagai hukum
kebenaran abadi. Vivekananda (1991) mengatakan bahwa dharma sebagai
hukum ini tidak tampak, tetapi senantiasa hadir dan berkuasa di alam
semesta ini. Hukum ini yang akan membuat manusia meledak dalam
kemarahan yang dasyat, membenci, dan menyerang secara brutal
terhadap mereka yang berada dalam oposisi. Selama dikuasai oleh
kemarahan, yakinlah bahwa manusia sedang dalam keadaan diikat erat-
erat oleh nafsu inderawi dan objek-objek duniawi dan ini berarti
perjalanan sedang melaju dengan cepat ke neraka yang dalam dan
gelap. Jadi, selama manusia mengeksploitasi nafsu-nafsu dan dirinya
sendiri, merusak alam, dan makhluk lainnya maka selama itu pula ia
akan hanyut dalam perputaran lingkaran lahir-mati.
Akan tetapi bila mampu melepaskan diri dari ketiga pintu tersebut
maka manusia akan dapat mencapai tujuan tertinggi. Hal ini
dijelaskan dalam Gita.XVI.22 dikatakan bahwa orang yang terbebas
dari ketiga pintu kegelapan mencapai tempat teritinggi. Manakala
manusia tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan lagi maka ia bebas dari
kegelapan yang berarti kesadarannya telah tercerahkan maka ia
mencapai tempat tertinggi, Yang Maha Esa. Untuk itu, kitab suci
hendaknya dijadikan pedoman dalam berpikir, berujar, dan berperilku.
Seperti dijelaskan dalam Gita.XVI.23 dikatakan bahwa ia yang
meninggalkan ajaran kitab suci dan berada dalam pengaruh nafsu
keinginan tidak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuan
tertinggi. Seloka ini menegaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan,
kebahagiaan, dan tujuan tertinggi hendaknya manusia berpegang teguh
pada kitab suci. Dengan tuntunan kitab suci manusia dapat
membebaskan diri dari cengkraman nafsu keinginan yang oleh banyak
ahli psikologi dikatakan sebagai dasar perilaku. Hanya saja nafsu
keinginan ini ditransformasikan ke dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan
sebagai akibat dari norma dan aturan manusia, yaitu etika-moralitas.
Oleh karena itu, dalam Gita.XVI.24 disebutkan bahwa biarkanlah
kitab-kitab suci menjadi petunjukmu untuk menentukan apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh. Setelah mengetahui apa yang
dikatakan dalam ajaran kitab suci engkau hendaknya mengerjakannya.
Seloka ini menganjurkan agar manusia menggunakan kitab suci sebagai
satu-satunya tuntunan dalam hidupnya untuk menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan.
Ditegaskan pula, bila sudah mengetahuinya jangan dibiarkan
berhenti hanya sebagai pengetahuan saja dalam wujud konsep-konsep
atau teori-teori belaka. Pengetahuan kebenaran hendaknya
dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata untuk mendapatkan makna dan
artinya yang luas dan sedalam-dalamnya. Swami Rama (2002) juga
menyatakan bahwa hanya dalam pengalaman langsung teori dan konsep
memperoleh makna yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Di luar itu
pengetahuan tidak berarti apa-apa bagi manusia. Artinya, hanya dalam
prakteknya sebuah konsep atau teori akan mendapatkan nilai tertinggi
dari kebenarannya yang sebenar-benarnya dalam konteks kemanfaatan
dan kegunaannya.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa seseorang dikatakan baik tentulah
ia telah secara nyata berbuat baik dan bukan hanya dalam kata-kata
dan pikirannya. Pikiran hanyalah bahasa hati yang sangat rahasia dan
kata-kata hanyalah bahasa yang penuh misteri, tetapi dalam tindakan
semuanya memiliki nilai dan mendapatkan arti yang sebenarnya. Oleh
karena itu, Gita menyarankan agar manusia selalu bekerja dan secara
terus-menerus berada dalam kerja yang didasari oleh pikiran dalam
pengetahuan yang benar. Dengan demikian seluruh perbuatan telah
berubah menjadi pengabdian yang tinggi dalam batasan bhakti yang
tulus dan sungguh-sungguh, yaitu yadnya. Ini yang dikatakan sebagai
tindakan atau perbuatan yang berdasarkan tuntunan kitab suci dan
perbuatan seperti ini juga dikatakan akan mengantarkan manusia
sampai pada tujuan tertinggi, yaitu realisasi diri.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Gita ditemukan
dasar-dasar moralitas yang dalam bentuk pernyataan positif
teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia. Akan tetapi,
dalam bentuk pernyataan negatif terindentifikasi melalui manusia
yang jahat.
2.4Moralitas dalam Ajaran “YAMA-NIYAMA”
Yama dan Niyama, dasar etika dan moralitas dalam Hindu, selain
dirinci sebagai Panca Yama dan Panca Niyama dalam Yoga Sutra
Patanjali, juga dirinci sebagai Dasa Yama dan Dasa Niyama dalam
kitab Sarasamuccaya oleh Bhagavan Vararusi. Rinciannya adalah
sebagai berikut:
a. Dasa Yama :
1. Anrshangsya – Tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri
2. Kshama – Sabar. Suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan.
3. Satya – Kebenaran. Tidak berniat untuk menipu orang lain dalam
pikiran, serta kata-kata dan tindakan.
4. Ahimsa – Tanpa kekerasan.Tidak merugikan orang lain atau
makhluk hidup lainnya. Tidak merugikan diri sendiri. Tidak
merusak lingkungan. Toleransi bahkan untuk yang kita tidak
sukai. Tidak berbicara yang, meskipun jujur, akan melukai
orang lain.
5. Dama – Dapat menasehati diri sendiri.
6. Arjava – Jujur dan mempertahankan kebenaran.
7. Priti – Cinta kasih terhadap sesama makhluk.
8. Prasada – Berpikir dan berhati suci dan tanpa pamrih.
9. Madhurya – Ramah tamah, lemah lembut dan sopan santun.
10. Mardava – Rendah hati, tidak sombong dan berpikir halus.
b. Dasa Niyama :
1. Dana – Dermawan. Suka memberikan layanan atau bantuan tanpa
pamrih.
2. Ijya – Sembahyang. Pemujaan terhadap Brahman, para Dewa dan
leluhur.
3. Tapa – Kesederhanaan. Komitmen yang mendalam untuk sadhana
kita.
4. Dhyana – Memusatkan pikiran kepada Brahman.
5. Upasthanigraha – Mengendalikan hawa nafsu seksual.
6. Svadhyaya – Mengenal diri sendiri. Edukasi diri spiritual.
Kontemplasi dan penerapan kitab suci atau teks-teks suci dari
jalan yang kita pilih.
7. Vrata – Tidak mengkhianati sumpah dan janji.
8. Upavasa – Berpuasa; berpantang makan dan minum.
9. Mauna – Membatasi perkataan. konservasi energi untuk tujuan
latihan spiritual, termasuk melindungi energi dengan
menghindari berceloteh tak berujung tanpa tujuan yang jelas.
10. Snana – Kebersihan. Tidak hanya kebersihan tubuh eksternal,
tetapi memperhatikan kebersihan internal seperti menghindari
kotoran berupa kemarahan dan egoisme. Sikap sederhana, tidak
berlebih-lebihan.
“yamaan seveta satatam na tiyam niyamaan budhah, yamaan patatyasevan hi niyamaan
kevalaan bhayan.” –Sarasamuccaya 258.
Maksudnya: Yama harus diusahakan pelaksanaannya setiap saat;
sedangkan Niyama tidak dilaksanakan sepanjang waktu. Orang yang
melaksanakan Niyama tetapi mengabaikan Yama, orang yang demikian
akan masuk ke dalam bahaya (tidak menemukan ketenangan dan
kemuliaannya).
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Moralitas (dari kata sifat Latin moralis) mempunyai arti sama
dengan “moral” yang artinya keseluruhan asas dan nilai yang
berkenan dengan baik dan buruk. Ini merupakan ukuran
kemanusiaan. Oleh karena itu hanya berkenaan dengan manusia,
dan karenanya menjadi ciri khas manusia dari makhluk lainnya.
2. Dasar moralitas karmaphala dalam mengenal lima ajaran Sradha
(keyakinan) dikenal dengan Panca Sradha yang terdiri dari
Brahman, Atman, Karmaphala, Punarbhawa, dan Moksa. Karmaphala
sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan ajaran pokok
untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Dengan memahami hakekat tentang karmaphala
yaitu Sancita karmaphala yang berarti bahwa hasil perbuatan
pada masa lalu akan kita nikmati pada kehidupan sekarang.
Prarabda karmaphala yang artinya hasil perbuatan masa sekarang
dinikmati juga pada kehidupan yang sekarang. Kriyamana
Karmaphala yang artinya hasil perbuatan kita sekarang akan
kita terima pada kehidupan yang akan datang.
3. Moralitas dalam Bhagavadgita dirumuskan dengan dua jenis
pernyataan, yaitu positif dan negatif. Pernyataan positif
merupakan perintah yang harus dilaksanakan yang
teridentifikasi melalui sifat-sifat devata, yaitu sat
(kebenaran), cit (kesadaran), dan ananda (kebahagiaan).
Sebaliknya, pernyataan negatif merupakan larangan sehingga
tidak boleh dilaksanakan yang terindentifikasi melalui sifat-
sifat raksasa, yaitu kama (keinginan), kroda (kemarahan), dan
loba (keserakahan). Bagian esensial dari ajaran Gita adalah
Karmayoga merupakan perbuatan tanpa pamrih, Jnanayoga
merupakan jalan kebijaksanaan dan Bhakti dengan jalan
pengabdian serta Rajayoga dengan jalan meditasi
4. Moralitas dalam Yama-Niyama harus dilakukan dengan seimbang
dan sejalan. Yama harus diusahakan pelaksanaannya setiap saat;
sedangkan Niyama tidak dilaksanakan sepanjang waktu. Orang
yang melaksanakan Niyama tetapi mengabaikan Yama, orang yang
demikian akan masuk ke dalam bahaya (tidak menemukan
ketenangan dan kemuliaannya).