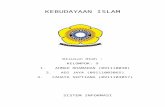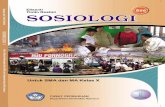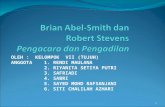Kebudayaan dalam Kajian Sosiologi
-
Upload
ubrawijaya -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Kebudayaan dalam Kajian Sosiologi
KEBUDAYAAN
SKRIPSI
Ditulis untuk Memenuhi Tugas Terstruktur
Matakuliah Sosiologi
Oleh:
Pamela Sakina 135120201111096
Tiara Amelia 135120201111102
Adryan Dwi K. 135120207111004
Devina Maharani 135120207111046
Galuh Pandu L. 135120207111052
Astika Nurmadioni 135120207111058
Jurusan IlmuKomunikasi
Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik
Universitas BrawijayaMalang
2013KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
selalu memberikan limpahan rahmat kesehatan, kekuatan dan
kesabaran, serta petunjuk dan bimbingan-Nya kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
“KEBUDAYAAN”.
Dalam upaya penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari
bahwa kelancaran penyusunan karya tulis ini adalah berkat
bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu
penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak pihak yang
telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah berusaha
menyajikan yang terbaik. Penulis berharap semoga tugas akhir
ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.
Malang, 17 Desember 2013
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………….i
Daftar Isi ………………………………………………………………………………..ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………..……………………………………………………..…..1
1.2 Rumusan Masalah …..……………………………………………………….......2
1.3 Tujuan Penelitian …...…………………………………………………………....2
1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………………………….....2
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Kebudayaan .................................................
.........................................................4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7 ..................................................
..........................5
2.2
Globalisasi ................................................
............................................................
BAB III PEMBAHASAN
3.1 .......................................................
................................
3.2 .......................................................
................................
3.3 .......................................................
................................
3.4 .......................................................
................................
3.5 .......................................................
................................
BAB IV
5.1 Kesimpulan ………………………………………………..……………….
5.2 Saran .……………………………………………..………………………..
Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Masyarakat tidak mungkin tidak berhubungan dengan hasil-
hasil kebudayaan. Setiap hari masyarakat melihat,
mempergunakan, dan bahkan kadamg-kadang masyarakat merusak
kebudayaan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang
menghasilkan kebudayaan, dengan demikian tak ada masyarakat
yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tak ada
kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.
Rasa saling menghormati dan menghargai akan tumbuh apabila
antar sesama manusia menjujung tinggi kebudayaan sebagai
alat pemersatu kehidupan, alat komunikasi antar sesama dan
sebagai ciri khas suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan
berperan penting bagi kehidupan manusia dan menjadi alat
untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain dan pada
akhirnya menjadi ciri khas suatu kelompok manusia. Manusia
sebagai mahluk sosial membutuhkan alat sebagai jembatan
yang menghubungkan dengan manusia yang lain yaitu
kebudayaan. Bagi bangsa Indonesia kebudayaan adalah salah
satu kekuatan bangsa yang memilki kekayaan nilai beragam
termasuk keseniannya. Kesenian rakyat adalah salah satu
dari kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak luput dari
pengaruh globalisasi.
Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan
cepat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan
dan kemudahan dalam memeroleh akses komunikasi dan berita
namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan
menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting
dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu
pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya negara
tersebut selalu khawatir akan tergerus arus globalisasi
dalam berbagai bidang khususnya kebudayaan. Globalisasi
secara bertahap menghilangkan budaya asli suatu negara,
terjadi erosi nilai-nilai suatu budaya, menurunkan rasa
nasionalisme, dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan
dan gotong-royong, kepercayaan diri hilang, gaya hidup
kebarat-baratan serta masalah dalam eksistensi kebudayaan
daerah yang dapat kita lihat dari menurunnya rasa cinta
terhadap kebudayaan yang menjadi jati diri bangsa. Sebagai
generasi muda, kita seharusnya bisa menyeleksi mana yang
baik dan bermanfaat untuk masa depan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi dan kebudayaan?
2. Apa pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan bangsa
Indonesia?
3. Siapa yang bertanggung jawab terhadap erosi nilai-nilai
kebudayaan bangsa akibat globalisasi?
4. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi nilai-nilai budaya
bangsa?
5. Dimana budaya bangsa dapat ditanamkan sehingga tidak
terkikis oleh pengaruh globalisasi?
6. Bagaimana globalisasi memengaruhi kebudayaan asli bangsa
Indonesia?
7. Bagaimana sikap generasi muda dalam menghadapi arus
globalisasi?
1.3 Tujuan Penulisan
Ada beberapa tujuan dari penulisan makalah ini, diantaranya
adalah:
1. Menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa
Indonesia.
2. Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam
penyebarluasan arus globalisasi.
3. Menjelaskan sebab-sebab masuknya arus globalisasi
4. Memaparkan cara-cara masuknya globalisasi kedalam
kebudayaan asli bangsa Indonesia serta bagaimana
menyikapinya.
5. Memberikan penjelasan kepada para generasi muda mengenai
pentingnya kebudayaan termasuk bagaimana mereka harus
bersikap dalam menghadapi arus globalisasi yang menggerus
nilai-nilai budaya bangsa.
1.4 Manfaat Penulisan
Penulisan makalah ini diharap dapat memberikan manfaat
untuk masyarakat terutama generasi muda. Generasi muda
diharapkan memahami secara mendasar mengenai makna
kebudayaan yang merupakan warisan luhur nenek moyang bangsa
Indonesia sehingga perlu dijiwai dan dilestarikan
keberadaannya. Perlunya sikap selektif terhadap berbagai
kebudayaan yang datang dari luar akibat globalisasi sehingga
dapat menghasilkan sikap positif untuk lebih menghargai
khasanah budaya bangsa dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa
masa depan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebudayaan
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan
dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan
dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak
unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat
istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan
karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan
bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak
orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.
Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang
yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-
perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.
Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya
bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya
turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-
budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial
manusia..
Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan
ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat
dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai
yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas
keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk
berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika,
"keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.
Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali
anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang
layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat
dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk
memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup
mereka.
Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu
kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas
seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang
lain.
Beberapa pengertian budaya menurut para ahli:
1. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski
mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam
masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu
adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan
sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke
generasi yang lain, yang kemudian disebut
sebagaisuperorganic.
2. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan
pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan
serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan
lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan
artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
3. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan
keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat
istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat
seseorang sebagai anggota masyarakat.
4. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan
adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh
pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan
memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide
atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat
abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda
yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang
berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat
nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan
hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang
kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam
melangsungkan kehidupan bermasyarakat.1
2.1.1 Fungsi Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi
manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus
dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya. Manusia dan
masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang
spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan
masyarakat tersebut di atas, sebagian besar dipenuhi
oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu
sendiri.
Masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan
kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. Teknologi pada hakikatnya
meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu:
1. Alat-alat produktif,
2. Senjata,
3. Wadah,
4. Makanan dan minuman,
5. Pakaian dan perhiasan,
6. Tempat berlindung dan perumahan,
7. Alat-alat transportasi.
Dalam tindakan-tindakannya untuk melindungi diri
terhadap lingkungan alam, pada taraf permulaan
manusia bersikap menyerah dan semata-mata bertindak
di dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Taraf
tersebut masih banyak dijumpai pada masyarakat-
masyarakat yang hingga kini masih rendah taraf
kebudayaannya. Misalnya suku bangsa Kubu yang
tinggal di pedalaman daerah Jambi, masih bersikap
menyerah terhadap lingkungan alamnya. Rata-rata
mereka itu masih merupakan masyarakat yang belum
mempunyai tempat tinggal tetap, hal mana disebabkan
karena persediaan bahan pangan semata-mata
tergantung dari lingkungan alam. Taraf teknologi
mereka belum mencapai tingkatan dimana manusia
diberikan kemungkinan-kemungkinan untuk memanfaatkan
dan menguasai lingkungan alamnya.
Keadaannya berlainan dengan masyarakat yang sudah
kompleks, di mana taraf kebudayaannya lebih tinggi.
Hasil karya manusia tersebut, yaitu teknologi,
memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas
untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan apabila
mungkin menguasai alam. Perkembangan teknologi di
negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Soviet
Rusia, Perancis, Jerman dan sebagainya, merupakan
beberapa contoh dimana masyarakatnya tidak lagi
pasif menghadapi tantangan alam sekitar.
2.1.2 Unsur Kebudayaan Universal
Istilah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur
kebudayaan bersifat universal, yaitu dapat dijumpai
pada setiap kebudayaan di manapun di dunia ini.
Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural
universals, yaitu:
1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
(pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga,
senjata, alat-alat produksi transpor dan
sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi
(pertanian peternakan, sistem produksi, sistem
distribusi dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistern kekerabatan,
organisasi politik, sistem hukum, sistem
perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan
sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).
2.1.3 Kebudayaan sebagai Sistem Norma
Kebudayaan berarti menyangkut aturan yang harus
diikuti, maka kebudayaan menentukan standar
perilaku. Sebagai contoh untuk bersalaman kita
mengulurkan tangan kanan; untuk menggaruk kepala
boleh menggunakan tangan kiri atau kanan. Istilah
norma memiliki dua kemungkinan arti. Suatu norma
budaya adalah suatu konsep yang diharapkan ada.
Kadang norma statis dianggap sebagai kebudayaan yang
nyata. Norma statis sering disebut sebagai suatu
ukuran dari perilaku yang sebenarnya, disetujui atau
tidak. Norma kebudayaan adalah seperangkat perilaku
yang diharapkan suatu citra kebuadayaan tentang
bagaimana seharusnya seseorang bersikap. Kejadian
itu diteruskan kepada generasi penerus sebagai salah
satu kebiasaan.
2.1.4 Etnosentrisme
Etnosentrisme bisa diartikan sebagai pandangan
bahwa kelompoknya sendiri adalah pusat dari
segalanya dan semua kelompok lain dibandingkan dan
dinilai sesuai dengan standar kelompok sendiri.
Secara bebas bisa dikatakan etnosentrisme adalah
kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap
kebudayaan kelompoknya sebagai kebuadayaan yang
paling baik. Kita mengasumsikan tanpa pikir atau
argumen bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat
“progresif” sedangkan masyarakat di luar dunia
“terbelakang”, kesenian kita indah, sedangkan
kesenian lain aneh.
Etnosentrisme membuat kebuadayaan kita sebagai
patokan untuk mengukur baik buruknya, tinggi
rendahnya dan benar atau ganjilnya kebudayaan lain.
Hal ini sering dinyatakan dalam ungkapkan orang-
orang terpilih, ras unguul, penganut sejati, dsb.
2.1.5 Xenosentrisme
Istilah ini berarti suatu pandangan yang lebih
menyukai hal-hal yang berbau asing. Xenosentrisme
adalah kebailkan yang tepat dari etnosentrisme. Ada
banyak kebanggaan bagi orang-orang tertentu ketika
mereka membayar lebih mahal untuk barang-barang
impor dengan asumsi bahwa segala yang datang dari
luar negeri lebih baik.
2.1.6 Relativisme Kebudayaan
Kita tidak mungkin memahami perilaku kelompok
lain dengan sudut pandang motif, kebiasaan dan nilai
yang kita anut. Relativisme kebudayaan fungsi dan
arti dari suatu unsur adalah berhubungan dengan
lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Motif,
kebiasaan, nilai suatu kebudayaan harus dinilai atau
dipahami dari sudut pandang mereka. Relativisme
kebuadayaan juga bisa diartikan “segala sesuatu
benar pada suatu tempat-tetapi tidak benar pada
semau tempat”.2
2.2 Globalisasi
Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan
dunia tunggal (Robertson, 1992K 396). Masyarakat di seluruh
dunia menjadi saling tergantung di semua aspek kehidupan:
politik, ekonomi, dan kultural. Cakupan saling-tergantungan
ini benar-benar mengglobal. Kini orang dapat berbicara
mengenai strukutur global hubungan politik, ekonomi, dan
kultural yang berkembang melampau batas tradisional dan
mngikat satuan masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam
satu sistem: sistem global.
Di bidang kultur terlihat kemajuan menuju keseragaman.
Media massa, terutama TV, mengubah dunia menjadi sebuah
“dusun global” (McLuhan, 1964). Informasi dan gambar
peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat
ditonton jutaan orang pada waktu bersamaan. Suguhan
pengalaman kultural yang sama itu (Olimpiade, konser rock
sepak bola, dan sebagainya) menyatukan selera, presepsi dan
pilihan mereka. Contoh kecenderungan globalisasi ini adalah
jaringan TV (CNN) dan kotran (Herald Tribune). Aliran
barang konsumsi serupa yang menjangkau seluruh penduduk
dunia adalah Coca-Cola. Pergerakan penduduk – migrasi,
pengiriman tenaga kerja keluar negeri dan pariwisata –
memberikan peluang untuk mengenali pola kehidupan asing
secara langsung. Muncul bahasa global. Bahasa inggris
berperan sebagai alat komunikasi profesional di bidang
iptek, bisnis, komputer, dan untuk komunikasi pribadi dalam
bepergian. Tradisi kulutural pribumi atau lokal semakin
terkikis dan terdesak sehingga menyebabkan kultus konsumen
atau budaya massa model Barat menjadi kultur universal yang
menjalar ke seluruh dunia.
Hannerz melukiskan empat kemungkinan yang akan terjadi
dari penyatuan kultur di masa mendatang. Pertama,
homogenisasi global. Kultur Barat akan mendominasi seluruh
dunia. Seluruh dunia akan menjadi jiplakan gaya hidup, pola
konsumsi, nilai, dan norma, serta gagasan dan keyakinan
masyarakat Barat.
Kedua, versi khusus dari proses homogenisasi global
yang disebut kejenuhan. Tekanannya pada dimensi waktu. Makin
pelan-pelan makin bertahap masyarakat pinggiran menyerap
pola kultur barat, makin menjenuhkan mereka. Dalam jangka
panjang, setelah melewati beberapa generasi maka bentuk,
makna dan penghayatan kultur lokal akan lenyap di kalangan
masyarakat pinggiran
Ketiga, kerusakan kultur pribumi dan krusakan kultur
barat yang diterima. Bentrokan dengan nilai kultur pribumi
makin merusak nilai kultur barat yang diterima.
Keempat, kedewasaan. Berarti penerimaan kultur barat
melalui dialog dan pertukaran yang lebih seimbang ketimbang
penerimaan sepihak. Masyarakat pribumi menerima unsur
kultur Barat secara selektif; memperkayanya dengan nilai
lokal tertentu; dalam menerima gagasan Barat, masyarakat
pinggiran memberikan interpretasi lokal. Rakyat biasa pun
penting perannya. Mereka memberi makna tersendiri dan
mungkin mengubah unsur kultur impor itu serta memasukannya
menjadi unsur kultur mereka sendiri. Hasil akhirnya adalah
pencampuran kultur. 3
Maraknya media-media massa asing yang melanda ke
berbagai kawasan dunia menunjukan betapa tingginya volume
penyebaran budaya antarbangsa. Falsafah orang Jawa pada
zaman dahulu adalah; “Wong Jawa kari separo, Wong Cina kari Sejodho,
Wong Landa gela-gelo”, artinya: orang Jawa tinggal separo,
orang Cina tinggal sejodoh, orang barat geleng-gelen
kepala. Falsafah ini menunjukan betapa lemah sistem nilai
kultural suatu bangsa, sehingga bangsa ini dengan mudah
kehilangan jari diri atau kepribadiannya.
Globalisasi dalam aspek budaya tidak lebih dari ajang
propaganda kultural yang menggunakan berbadai media sebagai
alat untuk “membaratkan dunia”. Dengan demikian juga
menjadi alat untuk menempatkan kultur Barat sebagai
imeprium kultur dunia yang menjadikaan homogenitas kultural
ini sebagai indikator kemenangan kultur Barat atas dunia.4
1http://kistiaulia18.blogspot.com/2013/03/kebudayaan-
sosiologi.html
2 http://pengantar-sosiologi.blogspot.com/2009/04/bab-7-
kebudayaan-dan-masyarakat.html
3Judul buku: Sosiologi Perubahan Sosial
Halaman: 101
Penulis: Piotr Sztompka
Tahun: 2008
Penerbit: Prenada, jakarta
4Judul buku: Pengantar Sosiologi
Halaman: 696
Penulis: Elly M. Setiadi & Usman Kolip
Tahun: 2011
Penerbit: Kencana, Jakarta
BAB III
PEMBAHASAN
Berbicara tentang kebudayaan Indonesia yang ada
dibayangan kita adalah sebuah budaya yang sangat beraneka
ragam. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia, hal inilah yang menyebabkan Indonesia
memiliki kebudayaan yang beraneka ragam.
Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan
keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Indonesia
sendiri sebagai Negara kepulauan dikenal dengan keberagaman
budayanya, yang mana keanekaragaman itulah menunjukkan betapa
pentingnya aspek kebudayaan bagi suatu Negara. Karena jelas
bahwa kebudayaan adalah suatu identitas dan jati diri bagi
suatu bangsa dan Negara.
3.1 Proses Perkembangan Budaya
Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui
penetrasi. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh
suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi
kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara:
3.1.2 Penetrasi damai (penetration pasifique)
Penetrasi damai merupakan proses masuknya sebuah
kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya
pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.
Contoh lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan
India dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk
melalui proses yang damai yaitu melalui penyebaran
agama Hindu dan Buddha di Nusantara yang jauh sebelum
Indonesia terbentuk. Kerajaan-kerajaan yang bernafaskan
agama Hindu dan Budha sempat mendominasi Nusantara pada
abad ke-5 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan
tertua di Nusantara, Kutai, sampai pada penghujung abad
ke-15 Masehi.
Kebudayaan Tionghoa masuk dan mempengaruhi
kebudayaan Indonesia karena interaksi perdagangan yang
intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dan
Nusantara (Sriwijaya). Selain itu, banyak pula yang
masuk bersama perantau-perantau Tionghoa yang datang
dari daerah selatan Tiongkok dan menetap di Nusantara.
Mereka menetap dan menikahi penduduk lokal menghasilkan
perpaduan kebudayaan Tionghoa dan lokal yang unik.
Kebudayaan seperti inilah yang kemudian menjadi salah
satu akar daripada kebudayaan lokal modern di Indonesia
semisal kebudayaan Jawa dan Betawi.
Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak
mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah
budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan
ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli
budaya masyarakat.
Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan
Akulturasi, Asimilasi, atau Sintesis. Akulturasi adalah
bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan
baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli.
Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang
merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia
dan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua
kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru.
Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan
yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru
yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.
3.1.2 Penetrasi kekerasan (penetration violante)
Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan
merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke
Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan
kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang
merusak keseimbangan dalam masyarakat. Wujud budaya
dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang
menjajah selama 350 tahun lamanya. Budaya warisan
Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada
sistem pemerintahan Indonesia.
Secara garis besar kebudayaan Indonesia dapat kita
klasifikasikan dalam dua kelompok besar. Yaitu
Kebudayaan Indonesia Klasik dan Kebudayaan Indonesia
Modern. Para ahli kebudayaan telah mengkaji dengan
sangat cermat akan kebudayaan klasik ini. Mereka
memulai dengan pengkajian kebudayaan yang telah
ditelurkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sebagai
layaknya seorang pengkaji yang obyektif, mereka
mengkaji dengan tanpa melihat dimensi-dimensi yang ada
dalam kerajaan tersebut. Mereka mempelajari semua
dimensi tanpa ada yang dikesampingkan. Adapun dimensi
yang sering ada adalah seperti agama, tarian, nyanyian,
wayang kulit, lukisan, patung, seni ukir, dan hasil
cipta lainnya.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa perkembangan
kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan modern dimulai sejak
bangsa Indonesia merdeka. Bentuk dari deklarasi ini menjadikan
bangsa Indonesia tidak dalam pengaruh dan tekanan bangsa lain
dengan budayanya. Dari sini bangsa Indonesia mampu menciptakan
rasa dan karsa yang lebih sempurna sehingga mulailah
berkembang kebudayaan modern bangsa Indonesia.
Dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia ini ada
beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya sebuah
kebudayaan diantaranya adalah faktor pengaruh budaya dari
luar, apabila budaya asli ini tidak dapat mempertahankan
eksistensinya maka budaya asli yang ada akan tergusur dan
tergantikan dengan budaya asing yang baru tersebut. Pada saat
ini kita semua dapat melihat bahwa bangsa Indonesia dalam
situasi yang mengkhawatirkan, karena banyak sekali budaya
asing yang masuk dan tidak tersaring sehingga mempengaruhi
kebudayaan asli bangsa Indonesia.
3.2 Kondisi Sosial Budaya Indonesia
Kondisi sosial budaya Indonesia saat ini adalah sebagai
berikut :
1. Bahasa
Dapat kita ketahui bahwa sampai saat Indonesia masih
konsisten dan tetap berpegang teguh dalam satu bahasa yaitu
bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan
kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman
nenek moyang kita. Bahasa merupakan salah satu unsur budaya
yang terbentuk karena adanya komunikasi antara manusia
Indonesia. Bahasa asing (Inggris, mandarin, dan lan
sebagainya) belum terlihat begitu diminati dalam penggunaan
sehari-hari, hanya mungkin pada acara saat seminar, atau
kegiatan ceramah formal diselingi dengan bahasa Inggris
sekedar untuk menyampaikan kepada penonton kalau penceramah
mengerti akan bahasa Inggris.
2. Sistem teknologi
Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan
kebudayaan Indonesia. Perkembangan yang sangat terlihat
adalah teknologi informatika. Dengan perkembangan teknologi
ini tidak ada lagi batas waktu dan negara pada saat ini,
apapun kejadiannya di satu negara dapat langsung dilihat di
negara lain melalui televisi, internet atau sarana lain
dalam bidang informatika. Sehingga, budaya-budaya luar
mampu menyusup kedalam budaya asli Indonesia itu sendiri.
3. Sistem mata pencarian hidup masyarakat atau ekonomi
masyarakat
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih dalam
situasi krisis, yang diakibatkan oleh tidak kuatnya
fundamental ekonomi pada era orde baru. Kemajuan
perekonomian pada waktu itu hanya merupakan fatamorgana,
karena adanya utang jangka pendek dari investor asing yang
menopang perekonomian Indonesia.
4. Organisasi Sosial
Bermunculannya organisasi sosial yang berkedok pada agama
(FPI, JI, MMI, Organisasi Aliran Islam/Mahdi), Etnis (FBR,
Laskar Melayu) dan Ras.
5. Sistem Pengetahuan
Dengan adanya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
diharapkan perkembangan pengetahuan Indonesia akan terus
berkembang sejalan dengan era globalisasi.
6. Kesenian
Dominasi kesenian saat ini adalah seni suara dan seni
akting (film, sinetron). Seni tari yang dulu hampir setiap
hari dapat kita saksikan sekarang sudah mulai pudar,
apalagi seni yang berbau kedaerahan. Kejayaan kembali
wayang kulit pada tahun 1995 – 1996 yang dapat kita nikmati
setiap malam minggu, sekarang sudah tidak ada lagi. Seni
lawak model Srimulat sudah tergeser dengan model Overa Van
Java, Pesbuker, dan lain-lain. Untuk kesenian nampaknya
paling dinamis perkembangannya. Namun akibat perkembangan
budaya yang sangat pesat menyebabkan banyak masyarakat
Indonesia yang mulai melupakan kesenian asli bangsa
Indonesia dan akhirnya banyak kesenian Indonesia yang
diakui oleh pihak lain.
7. Sedang menghadapi suatu pergeseran-pergeseran budaya.
Hal ini mungkin dapat dipahami mengingat derasnya arus
globalisasi yang membawa berbagai budaya baru serta
ketidakmampuan kita dalam membendung serangan itu dan
mempertahankan budaya dasar kita.
Kebudayaan bukan hanya sesuatu yang indah, artistik, atau
agung tetapi juga berarti sesuatu yang sederhana saja. Segala
hal yang berbau tradisional pun seperti nyanyian pantun-pantun
di kampung juga termasuk budaya. Kebudayaan merupakan
keseluruhan dari pernyataan pikiran dan perasaan manusia,
material, dan immaterial untuk menyesuaikan dirinya kepada
lingkungannya dan meningkatkan taraf hidupnya.
Kebudayaan terus tumbuh dari generasi ke generasi dengan
kuantitas dan kualitas yang semakin baik sehingga manusia
sekarang hidup lebih maju dibandingkan nenek moyang karena
kita tidak perlu memelajari terjadinya budaya tetapi secara
langsung mengikuti taraf kebudayaan yang ada. Masyarakat dan
kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam
interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai
masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok
masyarakat yang mendiami nusantara telah mengalami proses
dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah merupakan
sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu
kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang
senantiasa berubah. Perubahan yang terjadi saat ini
berlangsung begitu cepat. Hanya dalam jangka waktu satu
generasi banyak negara-negara berkembang telah berusaha
melaksanakan perubahan kebudayaan, padahal di negara-negara
maju perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi.
Pada hakekatnya bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain,
berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar.
Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak
luar, hal inilah yang terjadi dalam proses globalisasi. Oleh
karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi namun juga
terkait dengan masalah atau isu makna budaya dimana nilai dan
makna yang terlekat di dalamnya masih tetap berarti. Terkait
dengan kebudayaan, kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-
nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang
dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau
kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang
mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan
(Koentjaraningrat), dimana hal-hal tersebut terwujud dalam
kesenian tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai maupun
persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau
psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-
aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari,
bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang
ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah
satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian,
yang merupakan subsistem dari kebudayaan.
3.3 Kondisi Kebudayaan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi
Perkembangan keubudayaan Indonesia yang dari masa
kerajaan sampai era globalisasi ini memberikan beberapa
dampak bagi masyarakat. Kebudayaan Indonesia adalah
serangkaian gagasan dan pengetahuan yang telah diterima
oleh masyarakat-masyarakat Indonesia (yang multietnis) itu
sebagai pedoman bertingkah laku dan menghasilkan produk-
produk kebudayaan itu sendiri. Hanya persoalannya, ide-ide
dan pengetahuan masyarakat-masyarakat Indonesia juga
mengalami perubahan-perubahan, baik karena faktor internal
maupun eksternal.
Berikut dampak globbalisasi bagi masyarakat, antara lain:
a) Pengaruh Positif dapat berupa :
1. Peningkatan dalam bidang sistem teknologi, Ilmu
Pengetahuan, dan ekonomi.
2. Terjadinya pergeseran struktur kekuasaan dari otokrasi
menjadi oligarki.
3. Mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis
dan masyarakat madani dalam skala global.
4. Tidak mengurangi ruang gerak pemerintah dalam kebijakan
ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
5. Tidak berseberangan dengan desentralisasi.
6. Bukan penyebab krisis ekonomi.
b) Pengaruh Negatif
1. Menimbulkan perubahan dalam gaya hidup, yang mengarah
kepada masyarakat yang konsumtif komersial. Masyarakat akan
minder apabila tidak menggunakan pakaian yang bermerk (merk
terkenal).
2. Terjadinya kesenjangan budaya. Dengan munculnya dua
kecenderungan yang kontradiktif. Kelompok yang
mempertahankan tradisi dan sejarah sebagai sesuatu yang
sakral dan penting (romantisme tradisi). Dan kelompok ke
dua, yang melihat tradisi sebagai produk masa lalu yang
hanya layak disimpan dalam etalase sejarah untuk dikenang
(dekonstruksi tradisi/disconecting of culture).
3. Sebagai sarana kompetisi yang menghancurkan. Proses
globalisasi tidak hanya memperlemah posisi negara melainka
juga akan mengakibatkan kompetisi yang saling
menghancurkan.
4. Sebagai pembunuh pekerjaan. Sebagai akibat kemajuan
teknologi dan pengurangan biaya per unit produksi, maka
output mengalami peningkatan drastis sedangkan jumlah
pekerjaan berkurang secara tajam.
5. Sebagai imperialisme budaya. Proses globalisasi membawa
serta budaya barat, serta kecenderungan melecehkan nilai-
nilai budaya tradisional.
6. Globalisasi merupakan kompor bagi munculnya gerakan-
gerakan neo-nasionalis dan fundamentalis.. Proses
globalisasi yang ganas telah melahirkan sedikit pemenang
dan banyak pecundang, baik pada level individu, perusahaan
maupun negara. Negara-negara yang harga dirinya diinjak-
injak oleh negara-negara adi kuasa maka proses globalisasi
yang merugikan ini merupakan atmosfer yang subur bagi
tumbuhnya gerakan-gerakan populisme, nasionalisme dan
fundamentalisme.
7. Malu menggunakan budaya asli Indonesia karena telah
maraknya budaya asing yang berada di wilayah Indonesia.
Berbicara globalisasi dalam kebudayaan, yang terlintas
adalah seberapa cepat globalisasi itu dapat berkembang
dimana hal ini yang tentunya dipengaruhi oleh adanya
kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi
dan informasi dalam segala aspek kehidupan. Namun, hal ini
justru malah akan menjadi bumerang tersendiri dan menjadi
suatu masalah yang paling membahayakan atau penting dalam
globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu
pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki
dan mampu menggerakkan komunikasi internasional justru
negara-negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang
seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam
arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik,
ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian kita. Wacana
globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia
mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan
transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas
budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung
mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia
sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Simon
Kimoni, sosiolog asal Kenya mengatakan bahwa globalisasi
dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya
dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini,setiap
bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan
perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan
kehidupan dan menghindari kehancuran.
Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai
negara yang kaya akan budayanya, dengan memiliki keragaman
yang cukup bervariasi, dapat digunakan sebagai penambah
indahnya khasanah sebuah negara. Namun, Indonesia harus
tetap mampu mempertahankan eksistensi kebudayaannya.
Apabila diulang kembali berbagai peristiwa yang terjadi,
banyak kebudayaan Indonesia yang telah dirampas oleh
negara-negara lain. Hal ini dapat membuktikan dengan jelas
bahwa belum adanya kekuatan hukum yang kuat yang dimiliki
oleh bangsa Indonesia tentang kebudayaannya. Sehingga akan
menyebabkan kemudahan bagi bangsa lain untuk mengambil dan
mengakuinya.
Bukan hanya itu saja, kemajuan teknologi informasi pada
masa sekarang ini telah cepatnya merubah kebudayaan
Indonesia menjadi kian merosot. Sehingga menimbulkan
berbagai opini yang tidak jelas, yang nantinya akan
melahirkan sebuah kebingungan di tengah-tengah berbagai
perubahan yang berlangsung begitu rumitnya dan membuat
pusing bagi masyarakatnya sendiri dan yang lebih
memprihatinkan lagi, banyak kesenian dan bahasa Nusantara
yang dianggap sebagai ekspresi dari bangsa Indonesia akan
terancam mati. Sejumlah warisan budaya yang ditinggalkan
oleh nenek moyang sendiri telah hilang entah kemana.
Padahal warisan budaya tersebut memiliki nilai tinggi dalam
membantu keterpurukan bangsa Indonesia pada jaman sekarang.
Sungguh ironis memang apabila ditelaah lebih jauh lagi.
Akan tetapi, kita tidak hanya mengeluh dan menonton saja.
Sebagai warga negara yang baik, mesti mampu menerapkan dan
memberikan contoh kepada anak cucu nantinya, agar
kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun akan
tetap ada dan senantiasa menjadi salah satu harta berharga
milik bangsa Indonesia yang tidak akan pernah punah.
Globalisasi juga memberikan dampak bagi kebudayaan
Indonesia, Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan
pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia.
Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata
menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap
memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T
(Transportasi, Telekomunikasi,dan Teknologi) mengakibatkan
berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri
sendiri.
Budaya Indonesia yang dulunya ramah-tamah, gotong royong
dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan
bebas. Bahkan bila kita tinjau Tapanuli (Sumatera Utara)
misalnya, dua puluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya
masih banyak yang berminat untuk belajar tari tor-tor dan
tagading (alat musik batak). Hampir setiap minggu dan dalam
acara ritual kehidupan, remaja di sana selalu diundang
pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Namun saat ini,
ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan-
kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat,
bahkan hanya dapat disaksikan di televisi dan Taman Mini
Indonesi Indah (TMII). Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah
tersebut,bila dikelola dengan baik selain dapat menjadi
pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk
pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi
lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat
sekitarnya.
Hal lain yang merupakan pengaruh globalisasi adalah dalam
pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa juga
salah satu budaya bangsa). Sudah lazim di Indonesia untuk
menyebut orang kedua tunggal dengan Bapak, Ibu, Pak, Bu,
Saudara, Anda dibandingkan dengan kau atau kamu sebagai
pertimbangan nilai rasa. Sekarang ada kecenderungan di
kalangan anak muda yang lebih suka menggunakan bahasa
Indonesia dialek Jakarta seperti penyebutan kata gue (saya)
dan lu (kamu). Selain itu kita sering dengar anak muda
menggunakan bahasa Indonesia dengan dicampur-campur bahasa
inggris seperti OK, No problem dan Yes’, bahkan kata-kata
makian (umpatan) sekalipun yang sering kita dengar di film-
film barat, sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kata-kata ini disebarkan melalui media TV dalam film-film,
iklan dan sinetron bersamaan dengan disebarkannya gaya
hidup dan fashion. Gaya berpakaian remaja Indonesia yang
dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan telah berubah
mengikuti perkembangan jaman. Ada kecenderungan bagi remaja
putri di kota-kota besar memakai pakaian minim dan ketat
yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya perpakaian
minim ini dianut dari film-film dan majalah-majalah luar
negeri yang ditransformasikan ke dalam sinetron-sinetron
Indonesia.
Derasnya arus informasi yang juga ditandai dengan
hadirnya internet turut serta menyumbang bagi perubahan
cara berpakaian. Pakaian mini dan ketat telah menjadi trend
di lingkungan anak muda. Salah satu keberhasilan penyebaran
kebudayaan Barat ialah meluasnya anggapan bahwa ilmu dan
teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu yang
universal. Masuknya budaya barat (dalam kemasan ilmu dan
teknologi) diterima dengan baik. Pada sisi inilah
globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan
budaya Timur (termasuk Indonesia) sehingga terbuka pula
konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai ketimuran.
Kebudayaan dari barat saat ini sudah mendominasi segala
aspek kehidupan pada masyarakat Indonesia. Peradaban yang
disebarkan oleh barat telah mengacu terhadap segala hal dan
hal itu telah menguasai dunia tak terkecuali bangsa
Indonesia, peradaban bangsa kita saat ini secara perlahan
mulai mengikuti kebudayaan bangsa barat.
Kebudayaan barat masuk ke Indonesia disebabkan oleh
beberapa hal, salah satunya adalah kerana adanya krisis
globalisasi yang telah meracuni sebagian besar masyarakat
Indonesia. Siapa yang bisa menolak segala kemajuan yang
ditawarkan oleh peradaban barat. Pengaruh kebudayaan barat
berjalan sangat cepat dan menyeluruh. Tentunya hal itu akan
menimbulkan pengaruh yang sangat luas pada sistem sosial
dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh yang berjalan
begitu cepat tersebut menimbulkan terjadinya goncangan
sosial atau culture shock yaitu suatu keadaan dimana
masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan
yang dating dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan di
dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adanya
penyerapan unsure budaya dari luar yang dilakukan secara
cepat dan tidak melalui suatu proses internalisasi yang
mendalam dapat menimbulkan ketimpangan antara wujud yang
ditampilkan dan nilai-nilai yang menjadi landasannya atau
yang biasa disebut sebagai ketimpangan budaya. Setiap
peradaban akan saling mempengaruhi. Peradaban yang dianggap
lebih maju cenderung memiliki pengaruh yang lebih luas bagi
peradaban-peradaban yang lain.
Budaya barat yang masuk ke Indonesia menimbulkan multi
efek. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya barat ke
Indonesia, tanpa disadari secara perlahan telah
menghancurkan kebudayaan bangsa Indonesia. Rendahnya
pengetahuan menyebabkan akulturasi kebudayaan yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam
kebudayaan bangsa Indonesia. Masuknya kebudayaan barat
tanpa disaring oleh masyarakat dan diterima secara
mentah/apa adanya, mengakibatkan terjadinya degredasi yang
sangat luar biasa terhadap kebudayaan asli.
Budaya asli Indonesia secara perlahan mulai punah,
berbagai budaya barat yang menghantarkan kita untuk hidup
modern yang meninggalkan segala hal yang tradisional, hal
ini memicu orang bersifat antara lain sebagai sikap
individualis, matrealistis dan hedonisme.
1. Individualis: Masyarakat merasa dimudahkan dengan
teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan
orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa
mereka adalah makhluk social. Individualisme adalah paham
yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu
kepercayaan bagi setiap orang, paham yang mementingkan hak
perseorangan di samping kepentingan masyarakat.
Dengan adanya sikap individualisme, orang tidak akan peduli
terhadap kehidupan bangsa. Banyak orang yang tidak peduli
terhadap sesama. Prinsip gotong royong di negara kita lama-
kelamaan akan hilang. Dilihat dari sikap, banyak orang yang
kini tidak memiliki sopan santun dan cenderung tidak peduli
terhadap lingkungan. Sebab mereka menganggap bahwa
globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga
mereka bertindak sesuka hati mereka. Jika pengaruh tersebut
dibiarkan maka, moral bangsa menjadi rusak.
2. Matrialistis: Adalah sebuah faham dimana masyarakat
memandang segalanya dari segi materi. Orang yang memiliki
jabatan dan harta yang melimpah pasti akan lebih dihargai
oeleh masyarakat sekitarnya, walaupun orang tersebut tidak
memiliki intelektual yang bagus. Sebaliknya, orang yang
memiliki intelektual tinggi tetapi tidak memiliki harta dan
jabatan maka orang tersebut akan selalu direndahkan. Orang
yang merasa dirinya kaya maka berhak merendahkan dan
meremehkan orang yang miskin. Itulah yang sekarang terjadi
dimasyarakat kita.
3. Konsumerisme: adalah paham atau ideologi yang menjadikan
seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses
konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara
berlebihan atau tidak sepantasnya secara berkelanjutan. Hal
tersebut menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu
produk, sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau
susah untuk dihilangkan. Sifat konsumtif yang ditimbulkan
akan menjadikan penyakit jiwa yang tanpa sadar menjangkit
manusia dalam kehidupannya. Di Indonesia hamper semua orang
mempunyai kendaraan bermotor, televisi, computer dan
sebagainya. Indonesia merupakan Negara pembeli motor Honda
yang nomer satu didunia. Mulai dari pejabat hingga
masyarakat kalangan menengah pun berbondong-bondong membeli
dan menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang
aktifitasnya. Misalnya saja yang terlihat dikampus kita,
mahasiswa ,pegawai , dosen sebagian besar menggunakan
kendaraan bermotor untuk ke kampus. Bandingkan saja dengan
Negara yang lebih maju dari pada Indonesia, misalnya yang
terjadi dinegara jepang. Semua kampus di Jepang penuh
dengan sepeda, tak terkecuali dekan atau bahkan Rektorpun
ada yang naik sepeda datang ke kampus. Bagaimana yang
terjadi di kampus kita sungguh berbanding terbalik dengan
hal itu, Rektor selalu menggunakan mobil mewah begitu juga
dengan sebagian pegawai dan mahasisiwa. Ketika beberapa
pengusaha ingin memberi pinjaman kepada pemerintah
Indonesia mereka menjemput pejabat Indonesia di Narita.
Dari Tokyo naik kendaraan umum, sementara yang akan
dijemput, pejabat Indonesia naik mobil dinas kedutaan yaitu
mercy. Sungguh ironis, tapi itulah yang terjadi di
masyarakat kita.
4. Hedonisme: Hedonisme menurut Pospoprodijo (1999:60)
adalah kesenangan atau (kenikmatan) adalah tujuan akhir
hidup dan yang baik yang tertinggi. Namun, kaum hedonis
memiliki kata kesenangan menjadi kebahagiaan. Kemudian
Jeremy Bentham dalam Pospoprodijo (1999:61) mengatakan
bahwasanya kesenangan dan kesedihan itu adalah satu-satunya
motif yang memerintah manusia, dan beliau mengatakan juga
bahwa kesenangan dan kesedihan seseorang adalah tergantung
kepada kebahagiaan dan kemakmuran pada umumnya dari seluruh
masyarakat. Adapun hedonisme menurut Burhanuddin (1997:81)
adalah sesuatu itu dianggap baik, sesuai dengan kesenangan
yang didatangkannya. Disini jelas bahwa sesuatu yang hanya
mendatangkan kesusahan, penderitaan dan tidak menyenangkan,
dengan sendirinya dinilai tidak baik. Orang-orang yang
mengatakan ini, dengan sendirinya, menganggap atau
menjadikan kesenangan itu sebagai tujuan hidupnya. Orang-
orang lebih senang menghabiskan waktu di tempat-tempat
perbelanjaan dan tempat hiburan malam dari pada melakukan
hal-hal yang lebih bermanfaat. Pergaulan bebas, narkotika
dan miras semakin digemari oleh generasi muda saat ini.
3.4 Solusi Mengadapi Pengaruh Negatif Peradaban Global
Globalisasi merupakan sebuah realita yang harus dihadapi
oleh bangsa Indonesia. Globalisasi berpengaruh terhadap
kemajuan bangsa. Persiapkan diri kita untuk menghadapi
adanya globalisasi tanpa menghilangkan jati diri bangsa.
Gunakan globalisasi melalui hal-hal positif. Gunakan
teknologi sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat,
menerima adanya budaya luar yang masuk ke negara kita tanpa
melupakan budaya kita sendiri. Jadikan budaya luar sebagai
motivasi untuk memajukan budaya Indonesia.
Untuk mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang
ditimbulkan karena adanya peradaban global dapat kita
lakukan hal-hal seperti berikut:
1) Memperkuat jati diri bangsa (identitas nasional) dan
memantapkan budaya nasional. Memperkokoh ketahanan nasional
sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang
bernilai negatif dan memfasilitasi adopsi budaya asing yang
produktif dan bernilai positif.
2) Pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai
yang positif seperti kemandirian, amanah, kedisiplinan,
kejujuran, etos kerja, gotong royong, toleransi, tanggung
jawab dan rasa malu. Dengan aktualisasi nilai moral dan
agama ,transformasi budaya melalui adaptasi dan adopsi
nilai-nilai budaya asing yang positif guna memperkaya
budaya bangsa, revitalisai dan reaktualisasi budaya-budaya
local yang bernilai luhur.
3) Meningkatkan keimanan dan moralitas bangsa karena dengan
adanya keimanan dan moralitas, maka pengaruh negatif dari
globalisasi dapat diatasi. Kita dapat menjaring hal-hal
yang baik dan buruk dari budaya luar yang masuk ke negara
kita.
Dinamika sosial dan kebudayaan selalu melanda semua
bangsa dan negara di dunia demikian pula tidak terkecuali
melanda masyarakat Indonesia, walaupun luas permasalahan
dan tingkat permasalahan itu berbeda-beda. Demikian pula
masyarakat dan kebudayaan Indonesia pernah berkembang
dengan pesatnya di masa lampau, walaupun perkembangannya
dewasa ini bisa dikatakan lebih tertinggal apabila
dibandingkan dengan perkembangan di negera maju lainnya.
Bagaimanapun masalah yang dihadapi, masyarakat dan
kebudayaan Indonesia yang beranekaragam itu tidak pernah
mengalami kondisi kehilangan kebudayaan sebagai perwujudan
tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul
akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun
pergantian generasi.
Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya
perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara
umum ada dua kekuatan yang menyebabkan timbulnya perubahan
sosial, hal yang pertama adalah kekuatan dari dalam
masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian
generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Hal
kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor),
seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact)
secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta
perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat
memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang
harus menata kembali kehidupan mereka .
Seberapa cepat atau lambatnya perkembangan sosial budaya
yang melanda, dan faktor apapun penyebabnya, setiap
perubahan yang terjadi akan menimbulkan reaksi pro dan
kontra terhadap masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.
Besar kecilnya reaksi pro dan kontra itu dapat mengancam
kemapanan dan bahkan dapat pula menimbulkan disintegrasi
sosial terutama dalam masyarakat majemuk dengan multi
kultur seperti Indonesia.
Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas maka
kesimpulan yang dapat dipaparkan pada makalah ini adalah
sebagai berikut :
Pertama, rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan
kenyataan, yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan
resiko atau beban. Rakyat adalah potensi nasional harus
diberdayakan, ditingkatkan potensi dan produktivitas fisikal,
mental dan kulturalnya.
Kedua, tanah air Indonesia sebagai aset nasional yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai
Rote, merupakan tempat bersemayamnya semangat kebhinekaan.
Adalah kewajiban politik dan intelektual kita untuk
mentransformasikan “kebhinekaan” menjadi “ketunggalikaan”
dalam identitas dan kesadaran nasional.
Ketiga, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh
prinsip mutualisme, kerjasama sinergis saling menghargai dan
memiliki (shared interest) dan menghindarkan pola pikir persaingan
tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme, namun sebaliknya,
perlu secara bersama-sama berlomba meningkatkan daya saing
dalam tujuan peningkatan kualitas sosial-kultural sebagai
bangsa.
Keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah
kepada suatu strategi kebudayaan untuk dapat menjawab
pertanyaan, “Akan kita jadikan seperti apa bangsa kita?” yang
tentu jawabannya adalah “menjadi bangsa yang tangguh dan
entrepreneurial, menjadi bangsa Indonesia dengan ciri-ciri
nasional Indonesia, berfalsafah dasar Pancasila, bersemangat
bebas-aktif mampu menjadi tuan di negeri sendiri, dan mampu
berperanan penting dalam percaturan global dan dalam
kesetaraan juga mampu menjaga perdamaian dunia”.
Kelima, yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Tanpa
segera ditegakkannya upaya “membentuk” secara tegas identitas
nasional dan kesadaran nasional, maka bangsa ini akan
menghadapi kehancuran.
Saran
Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang
terbentuk dari berbagai macam kebudayaan suku dan agama
sehingga banyak tantangan yang selalu merongrong keutuhan
budaya itu tapi dengan semangat kebhinekaan sampai sekarang
masih eksis dalam terpaan zaman. Kewajiban kita sebagai anak
bangsa untuk tetap mempertahankannya budaya itu menuju bangsa
yang abadi, luhur, makmur dan bermartabat.
DAFTAR PUSTAKA
Budiono Kusumohamodjojo. 2000. Kebhinekaan Masyarakat Indonesia.
Jakarta: Grasindo.
Burhanudin Salam. 1997. Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan
Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Harimanto, Winarno.2009. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta : Bumi
Aksara.
Syukur, Abdul et al. 2005. Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar.
Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve.
Staf Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1989. Ensiklopedia
Nasional Indonesia. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
Tim Dosen ISBD. 2012. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta :
Universitas Negeri Jakarta
Herimanto dan Winarno. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi
Aksara, 2010.
Iljas, Mohamad. Pengantar Sosiologi. UNBRA-MALANG: Biro Penerbitan
Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali
Pers, 2012.
http://kistiaulia18.blogspot.com/2013/03/kebudayaan-
sosiologi.html
http://pengantar-sosiologi.blogspot.com/2009/04/bab-7-
kebudayaan-dan-masyarakat.html
Judul buku: Sosiologi Perubahan Sosial
Halaman: 101
Penulis: Piotr Sztompka
Tahun: 2008
Penerbit: Prenada, jakarta
Judul buku: Pengantar Sosiologi