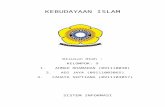MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Transcript of MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
MAKALAH SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
Oleh:
Kelompok 6
Nama Anggota: *Aditya Adidaya
*Muliana
*Sri Hardiyanti
*Yandi Firdaus
*Yaumil Oktarina
KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI MODEL PALANGKA RAYA 2014-2015
ISLAM DI INDONESIA Proses Masukya Agama Islam ke IndonesiaA. Teori-teori Masukya Agama Islam ke Indonesia.
Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut
Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori
yaitu:
1) Teori Gujarat
Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan
pembawanya berasal dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini
adalah:
a. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab
dalam penyebaran Islam di Indonesia.
b. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui
jalur Indonesia – Cambay – Timur Tengah – Eropa.
c. Adanya Batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan
Malik Al-Shaleh pada tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat
Pendukung teori Gujarat adalah Snouck Hurgronye,W.F. Stutterheim dan
Bernard H. M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan
perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu adanya
kerajaan Samudra Pasai.
Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari Venesia. (Italia)
yang pernah singgah di Perlak ( Perureula) tahun 1292. Ia menceritakan
bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak
pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam
2) Teori Mekkah
Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap
teori lama yaitu teori Gujarat.Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk
ke Indonesia pada abad ke 7 dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir).
Dasar teori ini adalah:
a. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera
sudah terdapat perkampungan Islam, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab
sudah mendirikan perkampungan sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan
berita dari Cina.
b. Kerjaan Samudera Pasai penganut aliran mahzab Syafi’i, dimana
pengaruh mahzab Syafi’i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah.
Sedangkan Gujarat/India adalah penganut mahzab Hanafi.
c. Raja-raja Samudera Pasai menggunakan gelar Al-Malik yaitu
gelar tersebut berasal dari Mesir.
Pendukung Teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan T.W. Arnold. Para
ahli yang mendukung teori menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan
polotik Islam, jadi masuknya ke Inonesia terjadi jauh sebelumnya abad ke-7
dan berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab
sendiri.
3) Teori Persia
Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan
pembawanya berasal dari Persia (Iran). Dari teori ini adalah kesamaan
budaya Persia dengan budaya masyarakat IslamIndonesia seperti:
1) Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan
Husein, cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh orang Syiah/Islam
Iran. DiSumatra Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara
Tabuik/Tabut.Sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur
Syuro.
2) Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jennar
dengan sufi dari Iran yaituAl – Hallaj.Penggunaan istilah bahasa
Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi Harakat.
3) Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.
4) Adanya perkampungan Leren/Leran di Giri daerah Gresik.
Leren adalah namasalah satu Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husen
dan P.A. Hussein Jayadiningrat.
Ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran
dankelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan
bahwaIslam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke – 7 dan
mengalami perkembangannya pada abad 13. Sebagai pemegang peranan dalam
penyebaranIslam adalah bangsa Arab, bangsa Persia dan Gujarat (India).
Sumber-sumber yang menerangkan masuk dan berkembangnya agama Islam ke
nusantara.
a. Sumber dari luar negeri.
1. Berita dari bangsa Arab yang melakukan perdagangan dengan
Indonesia sekitar abad ke-7 pada masa kerajaan Sriwijaya.
2. Berita dari Marco Polo tentang adanya kerajaan Islam yang
pertama di Nusantara yaitu Samudera Pasai.
3. Berita dari India bahwa para pedagang India dari Gujarat
telah melakukan penyebaran Islam di Nusantara.
4. Catatan Ma-Huan dari Cina, yang menceritakan bahwa kira-kira
sekitar tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang tinggal di
pesisir pantai utara Pulau Jawa.
b. Sumber dari dalam negeri.
1. Penemuan batu di Lenan Gresik yang telah menggunakan bahsa
Arab dan diduga telah adalah makam dari Fatimah Binti Maimun (1028).
2. Makam Sultan Malik As-Shaleh di Sumatera Utara yang meninggal
pada bulan Ramadhan 676 H atau1297 M.
3. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang Wafat tahun
1419 M.
Ditengah perbedaan penafsiran proses masuk dan berkembangannya agama
Islam di Nusantara tersebut, para ahli sepakat bahwa golongan pembawa
agama Islam di Nusantara adalah kaum pedagang, selain sebagai kewajiban
seorang Muslim, penyebaran agama melalui perdgangan ketika itu merupakam
jalan yang paling efisien. Pada saat itu pelayaran dan perdgangan
internasional sangant berkembang. Tidak heran jika daerah pesisir pantai
terlebih dahulu memeluk agama Islam adalah daerah Pesisir. Selain itu,
kaum mubaligh atau guru agama juga datang untuk mengajarkan dan
menyebarkan agama Islam. Kedatangan para mubaligh ini mempercepat
islamisasi daerah-daerah di Nusantara. Mereka mendirikan banyak pesantren
yang mencetak kader-kader ulama atau guru agama lokal. Golongan lain yang
juga disebut sebagai pembawa agama Islam adalah penganut Tasawuf (kaum
sufi). Mereka diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13.
Selain golongan pembawa tentu terdapat pula golongan penerima agama
Islam. Diantaranya adalah
1. Para adipati pesisir yang langsung berhubungan denagn
pedagang muslim,
2. Raja dan bangsawan yang ikut mempercepat perkembangan
Islam,
3. Para pedagang muslim yang terlibat langsung dengan
pedagang Islam dari luar,
4. Para wali songo,
5. Rakyat yang di Islamkan Wali songo.
Saluran dan Proses Islamisasi di Nusantara
Islamisasi di nusantara pada umumnya berjalan damai, melalui
perdagangan dan dakwah oleh para mubaligh dan sufi. Namun, ada kalanya
penyebaran diwarnai dengan penaklukan, misalnya jika situasi politik
dikerajaan-kerajaan itu mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan.
Disamping itu, islam juga berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan
kekuasaan dalam menghadapi lawan.
a. Perdagangan
Islamisai melaluai jalur perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu
sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga
abad ke-16. Pada saat iti, pedagang muslim yang berdagang ke nusantara
semakin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan.
Dari tempat ini, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat
asli sambil menyebarkan agama Islam.
b. Perkawinan
Para pedagang yang datang ke nusantara danyak yang menikah dengan
wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang
belum beragama Islam diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima
Islam sebagai agamanya. Dengan proses seperti ini, kelompok mereka semakin
besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-
kerajaan Islam.
c. Tasawuf
Saluran penyebaran Islam yang tidak kalah pentingnya adalah melalui
tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada
Tuhan. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babad dan hikayat
masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah
Hamzah Fansuri, Syamsudin, Syekh Abdul Shamad dan Nuruddin Ar-Ranirry.
d. Kesenian
Saluran penyebaran agama Islam di Nusantara terlihat pula dalam
kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seno pahat, seni musik,
dan seni sastra. Hasil-hasil tersebut dapat pula dilihat pada masjid-
masjid kuno di Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh.
e. Dakwah Wali Songo
Proses penyebaran Islam di Nusantara khususnya di pulau Jawa tidak
lepas dari peranan para wali. Para wali bertindak sebagai juru dakwah,
penyebar dan perintis agama Islam. Dengan bekalpengetahuan agama dan
keahlian tersebut,para wali mendapat banyak pengikut dan sangat dihormati.
Di Jawa, terdapat sembilan wali yang sangat terkenal. Para wali ini
kemudian dikemal dengan sebutan Wali Songo ( wali sembilan, karena jumlah
wali ada sembilan orang). Mereka adalah sebagai berikut.
1. Sunan Ampel (Raden Rahmat), di Ampel, Surabaya.
2. Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik.
3. Sunan Giri (Raden Paku), di Bukit Giri, Surabaya.
4. Sunan Drajat, di Drajat, Surabaya.
5. Sunan Bonan (Makdum Ibrahim), di Bonang, Tuban
6. Sunan Muria, yang tinggal di lereng gunung Muria, Kudus.
7. Sunan Kalijaga (Joko Said), di Kalidangu, Demak.
8. Sunan Kudus, yang bertempat tinggal di Kudus.
9. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), di Gunung Jati,
Cirebon
Perkembangan Islam di Nusantara
Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang
dengan cepat di Indonesia. Diantaranya sebagai berikut.
1. Syarat masuk agama Islam sangatlah mudah. Seseorang hanya
butuh mengucapkan kalimat syahadat untuk bisa secara resmi masuk Islam.
2. Agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat
berdasarkan perbedaan kasta. Setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan
yang sama sebagai hamba Allah SWT. Kenyataan ini berbeda dengan kondisi
sebelumnya dimana masyarakat terbagi dalam kasta-kasta.
3. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif
damai (tanpa melalui kekerasan)
4. Sifat masyarakat Nusantara yang ramah tamah memberi peluang
untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan itu,
terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian.
5. Upacara-upacara ke agamaan dalam Islam lebih sederhana, dan
di padankan dengan upacara-upacara yang telah ada sebelumnya.
Faktor-faktor diatas, didikung pula dengan semangat para penganut Islam
untuk terus menyebarkan agama yang telah dianutnya. Bagi penganut agama
Islam, menyebarkan agama Islam adalah sebuah kewajiban.
Kerajaan-kerajaan islam di
indonesia (SEJARAH)
KERAJAAN SAMUDERA PASAI
1. Awal Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai
Kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai utara Aceh, pada muara
Sungai Pasangan (Pasai). Pada muara sungai itu terletak dua kota, yaitu
samudera (agak jauh dari laut) dan Pasai (kota pesisir). Kedua kota yang
masyarakatnya sudah masuk Islam tersebut disatukan oleh Marah Sile yang
masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif
Mekah. Merah Selu kemudian dinobatkan menjadi sultan (raja) dengan
gelar Sultan Malik al Saleh.
Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Samudera Pasai berkembang pesat
menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang
dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina serta daerah di sekitarnya
banyak berdatangan di Samudera Pasai.
Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaan ke
daerah pedalaman meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Beruana,
Simpag, Buloh Telang, Benua, Samudera, Perlak, Hambu Aer, Rama Candhi,
Tukas, Pekan, dan Pasai.
2. Aspek Kehidupan Politik
Ada beberapa raja yang pernah memerintah Samudera Pasai, antara lain:
1) Sultan Malik al Saleh ( 1290 – 1297)
2) Muhammad Malik az Zahir ( 1297 – 1326 )
3) Mahmud Malik az Zahir ( 1326 – 1345)
4) Mansur Malik az Zahir ( …. – 1346 )
5) Ahmad Malik az Zahir ( 1346 – 1383 )
6) Zain al Abidin Malik az Zahir ( 1383 – 1405 )
7) Nahrasiyah ( 1405 – 1412 )
8) Sallah ad Din ( 1412 – … )
9) Abu Zaid Malik az Zahir ( … – 1455 )
10) Mahmud Malik az Zahir ( 1455 – 1477 )
11) Zain al Abidin ( 1477 – 1500 )
12) Abdullah Malik az Zahir ( 1501 – 1513 )
13) Zain al Abidin ( 1513 – 1524 )
Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat
pada masa pemerintahan raja-raja berikut ini:
1. Sultan Malik al Saleh
Sultan Malik al Saleh merupakan raja pertama di Kerajaan Samudera
Pasai. Dalam menjalankan pemerintahannya, Beliau berhasil menyatukan
dua kota besar di Kerajaan Samudera Pasai, yakni kota Samudera dan kota
Pasai
dan menjadikan masyarakatnya sebagai umat Islam. Setelah beliau mangkat
pada tahun 1297, jabatan beliau diteruskan oleh putranya, Sultan Malik
al Thahir. Lalu takhta kerajaan dilanjutkan lagi oleh kedua cucunya
yang bernama Malik al Mahmud dan Malik al Mansur.
2. Malik al Mahmud dan Malik al Mansur.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Malik al Mahmud dan Malik al Mansur
pernah memindahkan ibu kota kerajaan ke Lhok Seumawe dengan dibantu
oleh kedua perdana menterinya.
3. Sultan Ahmad Perumadal Perumal
Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Perumadal Perumal inilah, Kerajaan
Samudera Pasai pertama kalinya menjalin hubungan dengan Kerajaan /
Kesultanan lain, yakni Kesultanan Delhi (India).
3. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial
Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Samudera Pasai dititikberatkan
pada kegiatan perdagangan, pelayaran dan penyebaran agama. Hal ini
dikarenakan, banyaknya pedagang asing yang sering singgah bahkan
menetap di daerah Samudera Pasai, yakni Pelabuhan Malaka. Mereka yang
datang dari berbagai negara seperti Persia, Arab, dan Gujarat kemudian
bergaul dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama serta
kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat Samudera Pasai bertambah maju, begitupun di bidang
perdagangan, pelayaran dan keagamannya.
Keberadaan agama Islam di Samdera Pasai sangat dipengaruhi oleh
perkembangan di Timur Tengah. Hal itu terbukti pada saat perubahan
aliran Syi’ah menjadi Syafi’i di Samudera Pasai. Perubahan aliran tersebut
ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang
terjadi pergantian kekuasaan dari Dinasti Fatimah yang beraliran Syi’ah
kepada Dinasti Mameluk yang beraliran Syafi’i.
Aliran Syafi’i dalam perkembangannya di samudera Pasai menyesuaikan dengan
adat istiadat setempat. Oleh karena itu kehidupan sosial masyarakatnya
merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat.
4. Kemunduran Kerajaan Samudera Pasai
Pada waktu Samudera Pasai berkembang, Majapahit juga sedang
mengembangkan politik ekspansi. Majapahit setelah meyakini adanya
hubungan antara Samudera Pasai dan Delhi yang membahayakan
kedudukannya, maka
pada tahun 1350 M segera menyerang Samudera Pasai. Akibatnya, Samudera
Pasai mengalami kemunduran. Pusat perdagangan Samudera Pasai pindah ke
pulau Bintan dan Aceh Utara (Banda Aceh). Samudera Pasai runtuh
ditaklukkan Aceh
KERAJAAN ACEH
1. Awal Perkembangan Kerajaan Aceh
Aceh semula menjadi daerah taklukkan Kerajaan Pedir. Akibat Malaka jatuh
ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh di pelabuhan Malaka
beralih ke pelabuhan milik Aceh. Dengan demikian, Aceh segera
berkembang dengan cepat dan akhirnya lepas dari kekuasaan Pedir. Aceh
berdiri sebagai kerajaan merdeka. Sultan pertama yang memerintah dan
sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah (1514-
1528 M).
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar karena didukung oleh faktor
sebagai berikut:
1) Letak Ibu kota Aceh yang sangat strategis.
2) Pelabuhan Aceh ( Olele ) memiliki persyaratan yang baik sebagai
pelabuhan dagang.
3) Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada sebagai mata dagangan
ekspor yang penting.
4) Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam
banyak yang singgah ke Aceh.
Sultan Ali Mughayat Syah merupakan Raja pertama di Aceh sekaligus
beliau merupakan pendiri Kerajaan Aceh. Setelah beliau mangkat, raja
selanjutnya adalah Sultan Ibrahim. Dalam pemerintahannya beliau
berhasil menaklukkan Pedir. Raja berikutnya adalah Iskandar Muda. Pada
masa pemerintahan beliau, Aceh mencapai puncak kejayaan dan menjadi
sumber komoditas lada dan emas. Beliau mangkat pada tahun 1636 M dan
digantikan oleh menantunya Iskandar Thani yang tidak memiliki
kecakapan. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Aceh terus-menerus mengalami
kemunduran.
3. Aspek Kehidupan Kebudayaan
Letak Aceh yang strategis menyebabkan perdagangannya maju pesat. Dengan
demikian, kebudayaan masyarakatnya juga makin bertambah maju karena
sering berhubungan dengan bangsa lain. Contohnya, yaitu tersusunnya
hukum adat yang dilandasi ajaran Islam yang disebut Hukum Adat Makuta
Alam. Dengan hukum adat Makuta Alam itulah, sehingga tata kehidupan dan
segala aktivitas masyarakat Aceh didasarkan pada aturan Islam. Dengan
demikian, keadaan Aceh seolah-olah identik dengan Mekah, Arab Saudi.
Atas dasar itulah, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah.
4. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial
Bidang perdagangan yang maju menjadikan Aceh makin makmur. Setelah
Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh
makin bertambah makmur dan menjadi sumber komoditas lada dan emas.
Dengan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang
kuat.
5. Kemunduran Kerajaan Aceh
Kemunduran Kerajaan Aceh ketika itu disebabkan oleh hal-hal sebagai-
berikut:
1. Kekalahan perang antara Aceh melawan Portugis di Malaka pada
tahun 1629 M.
2. Tokoh pengganti Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya.
3. Permusuhan yang hebat di antara kaum ulama yang menganut ajaran
berbeda.
4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat melepaskan diri
dengan Aceh.
5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa lainnya
berhasil mendesak dan menggeser daerah-daerah perdagangan Aceh.
Akibatnya perekonomian semakin melemah.
KERAJAAN DEMAK
1. Awal Perkembangan Kerajaan Demak
Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak
sebelumnya merupakan daerah vasal atau bawahan dari Majapahit. Daerah
ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir.
Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan
diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478 M. Dengan dukungan dari
para bupati, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak dengan gelar
Senopati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. Sejak
saat itu, kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat.
Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau
Jawa. Sementara itu, daerah pengaruhnya sampai ke luar Jawa, seperti ke
Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Pada tahun 1507 M, Raja Demak pertama, Raden Patah mangkat dan
digantikan oleh putranya Pati Unus. Pada masa pemerintahan Pati Unus,
Demak dan Portugis bermusuhan, sehingga sepanjang pemerintahannya, Pati
Unus hanya memperkuat pertahanan lautnya, dengan maksud agar Portugis
tidak masuk ke Jawa. Setelah mangkat pada tahun 1521, Pati unus
digantikan oleh adiknya Trenggana. Setelah naik takhta, Sultan Trenggana
melakukan usaha besar membendung masuknya portugis ke Jawa Barat dan
memperluas kekuasaan Kerajaan Demak. Beliau mengutus Faletehan beserta
pasukannya untuk menduduki Jawa Barat. Dengan semangat juang yang
tinggi, Faletehan berhasil menguasai Banten dan Sunda Kelapa lalu
menyusul Cirebon. Dengan demikian, seluruh pantai utara Jawa akhirnya
tunduk kepada pemerintahan Demak. Faletehan kemudian diangkat menjadi
raja di Cirebon. Pasukan demak terus bergerak ke daerah pedalaman dan
berhasil menundukkan Pajang dan Mataram, serta Madura. Untuk memperkuat
kedudukannya, Sultan Trenggana melakukan perkawinan politik dengan Bupati
Madura, yakni mengawinkan Putri Sultan Trenggana dengan Putra Bupati
Madura, Jaka Tingkir. Sultan Trenggana mangkat pada tahun 1546 M.
Mangkatnya Beliau menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Demak.
Negara bagian banyak yang melepaskan diri, dan para ahli waris Demak
juga saling berebut tahta sehingga timbul perang saudara dan muncullah
kekuasaan baru, yakni Kerajaan Pajang.
3. Aspek Kehidupan Sosial dan Budaya
Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur.
Pemerintahan diatur dengan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma
lama begitu saja. Hasil kebudayaan Demak merupakan kebudayaan yang
berkaitan dengan Islam. Seperti ukir-ukiran Islam dan berdirinya Masjid
Agung Demak yang masih berdiri sampai sekarang. Masjid Agung tersebut
merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam.
4. Aspek Kehidupan Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Demak berperan penting karena mempunyai daerah
pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan, terutama
beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor,
antara lain beras, madu, dan lilin.
5. Keruntuhan Kerajaan Demak
Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan karena pembalasan dendam yang
dilakukan oleh Ratu Kalinyamat yang bekerja sama dengan Bupati Pajang
Hadiwijaya (Jaka Tingkir). Mereka berdua ingin menyingkirkan Aria
Penansang sebagai pemimpin Kerajaan Demak karena Aria Penansang telah
membunuh suami dan adik suami dari Ratu Kalinyamat. Dengan tipu daya
yang tepat mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan dari Bupati Jipang
yang tidak lain adalah Aria Penansang. Aria Penansang sendiri berhasil
dibunuh Sutawijaya. Sejak saat itu pemerintahan Demak pindah ke Pajang
dan tamatlah riwayat Kerajaan Demak.
KERAJAAN BANTEN
1. Awal Perkembangan Kerajaan Banten
Semula Banten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Rajanya (Samiam)
mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung
meluasnya kekuasaan Demak. Namun melalui, Faletehan, Demak berhasil
menduduki Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sejak saat itu, Banten
segera tumbuh menjadi pelabuhan penting menyusul kurangnya pedagang
yang berlabuh di Pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis.
Pada tahun 1552 M, Faletehan menyerahkan pemerintahan Banten kepada
putranya, Hasanuddin. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin (1552-1570
M), Banten cepat berkembang menjadi besar. Wilayahnya meluas sampai ke
Lampung, Bengkulu, dan Palembang.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Raja Banten pertama, Sultan Hasanuddin mangkat pada tahun 1570 M dan
digantikan oleh putranya, Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf memperluas
daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun 1579 M kekuasaan Kerajaan
Pajajaran dapat ditaklukkan, ibu kotanya direbut, dan rajanya tewas
dalam pertempuran. Sejak saat itu, tamatlah kerajaan Hindu di Jawa
Barat.
Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten mengalami puncak kejayaan.
Keadaan Banten aman dan tenteram karena kehidupan masyarakatnya
diperhatikan, seperti dengan dilaksanakannya pembangunan kota. Bidang
pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi.
Sultan Maulana Yusuf mangkat pada tahun 1580 M. Setelah mangkat,
terjadilah perang saudara untuk memperebutkan tahta di Banten. Setelah
peristiwa itu, putra Sultan Maulana Yusuf, Maulana Muhammad yang baru
berusia sembilan tahun diangkat menjadi Raja dengan perwalian
Mangkubumi.
Masa pemerintahan Maulana Muhammad berlangsung tahun 1508-1605 M.
Kemudian digantikan oleh Abdulmufakir yang masih kanak-kanak didampingi
oleh Pangeran Ranamenggala. Setelah pangeran Rana Menggala wafat,
Banten mengalami kemunduran.
3. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial
Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena
menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedangang Cina, India, gujarat,
Persia, dan Arab banyak yang datang berlabuh di Banten. Kehidupan
sosial masyarakat Banten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam.
Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan,
tetapi meluas hingga ke pedalaman.
4. Kemunduran Kerajaan Banten
Penyebab kemunduran Kerajaan Banten berawal saat mangkatnya Raja Besar
Banten Maulana Yusuf. Setelah mangkatnya Raja Besar terjadilah perang
saudara di Banten antara saudara Maulana Yusuf dengan pembesar Kerajaan
Banten. Sejak saat itu Banten mulai hancur karena terjadi peang
saudara, apalagi sudah tidak ada lagi raja yang cakap seperti Maulana
Yusuf.
KERAJAAN MATARAM ISLAM
1. Awal Perkembangan Kerajaan Mataram Islam
Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan
dilantik menjadi Bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya
membantu menumpas Aria Penangsang. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan
diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan
wafat pada tahun 1575 M, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram.
Setelah menjadi bupati, Sutawijaya ternyata tidak puas dan ingin
menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa, sehingga terjadilah
peperangan sengit pada tahun 1528 M yang menyebabkan Sultan Hadiwijaya
mangkat. Setelah itu terjadi perebutan kekuasaan di antara para
Bangsawan Pajang dengan pasukan Pangeran Pangiri yang membuat Pangeran
Pangiri beserta pengikutnya diusir dari Pajang, Mataram. Setelah
suasana aman, Pangeran Benawa (putra Hadiwijaya) menyerahkan takhtanya
kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke
kotagede pada tahun 1568 M. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Mataram.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Dalam menjalankan pemerintahannya, Sutawijaya, Raja Mataram banyak
menghadapi rintangan. Para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak,
Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk pada Pajang memberontak ingin
lepas dan menjadi kerajaan merdeka. Akan tetapi, Sutawijaya berusaha
menundukkan bupati-bupati yang menentangnya dan Kerajaan Mataram
berhasil meletakkan landasan kekuasaannya mulai dari Galuh (Jabar)
sampai pasuruan (Jatim).
Setelah Sutawijaya mangkat, tahta kerajaan diserahkan oleh putranya,
Mas Jolang, lalu cucunya Mas Rangsang atau Sultan Agung. Pada masa
pemerintahan Sultan Agung, muncul kembali para bupati yang memberontak,
seperti Bupati Pati, Lasem, Tuban, Surabaya, Madura, Blora, Madiun, dan
Bojonegoro.
Untuk menundukkan pemberontak itu, Sultan Agung mempersiapkan sejumlah
besar pasukan, persenjataan, dan armada laut serta penggemblengan fisik
dan mental. Usaha Sultan Agung akhirnya berhasil pada tahun 1625 M.
Kerajaan Mataram berhasil menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten,
Batavia, Cirebon, dan Blambangan. Untuk menguasai seluruh Jawa, Sultan
Agung mencoba merebut Batavia dari tangan Belanda. Namun usaha Sultan
mengalami kegagalan.
3. Aspek Kehidupan Sosial
Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram, tertata dengan baik
berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu
saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat
kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naid, dan
surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang
pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas
menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh
kerajaan, diciptakan peraturan yang dinamakan anger-anger yang harus
dipatuhi oleh seluruh penduduk.
4. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Kebudayaan
Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak dan Pajang.
Kerajaan ini menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris.
Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram
juga memiliki daerah kekuasan di daerah pesisir utara Jawa yang
mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting
bagi arus perdagangan Kerajaan Mataram. Kebudayaan yang berkembang
pesat pada masa Kerajaan Mataram berupa seni tari, pahat, suara, dan
sastra. Bentuk kebudayaan yang berkembang adalah Upacara Kejawen yang
merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Budha dengan Islam. Di
samping itu, perkembangan di bidang kesusastraan memunculkan karya
sastra yang cukup terkenal, yaitu Kitab Sastra Gending yang merupakan
perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Hukum
Surya Alam.
5. Kemunduran Mataram Islam
Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut
Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu,
kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat
dikerahkan untuk berperang.
KERAJAAN MAKASSAR
1. Awal Perkembangan Kerajaan Makassar
Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan,
tetapi yang terkenal adalah Gowa, Tallo, bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Berkat
dakwah dari Datuk ri Bandang dan Sulaeman dari Minangkabau, akhirnya Raja
Gowa dan Tallo masuk Islam (1605) dan rakyat pun segera mengikutinya.
Kerajaan Gowa dan Tallo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya. Dua
kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Dari Makasar, agama Islam
menyebar ke berbagai daerah sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Makassar merupakan salah satu kerajaan
Islam yang ramai akan pelabuhannya. Hal ini, karena letaknya di tengah-
tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Kerajaan Makassar mula-mula diperintah oleh Sultan Alauddin (1591-1639 M).
Raja berikutnya adalah Muhammad Said (1639-1653 M) dan dilanjutan oleh
putranya, Hasanuddin (1654-1660 M). Sultan Hasanuddin berhasil
memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan
kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. VOC setelah
mengetahui Pelabuhan Makassar, yaitu Sombaopu cukup ramai dan banyak
menghasilkan beras, mulai mengirimkan utusan untuk membuka hubungan
dagang. Setelah sering datang ke Makassar, VOC mulai membujuk Sultan
Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Banda (pusat rempah-rempah).
Namun, bujukan VOC itu ditolak. Setelah peristiwa itu, antara Makassar
dan VOC mulai terjadi konflik. Terlebih lagi setelah insiden penipuan
tahun 1616. Pada saat itu para pembesar Makassar diundang untuk suatu
perjamuan di atas kapal VOC, tetapi nyatanya malahan dilucuti dan
terjadilah perkelahian yang menimbulkan banyak korban di pihak
Makassar. Keadaan meruncing sehingga pecah perang terbuka. Dalam
peperangan tersebut, VOC sering mengalami kesulitan dalam menundukkan
Makassar. Oleh karena itu, VOC memperalat Aru Palakka (Raja Bone) yang
ingin lepas dari kerajaan Makassar dan menjadi kerajaan merdeka.
3. Aspek Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan
Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Hasil perekonomian
terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan
Sombaupu ( Makassar ) banyak didatangi kapal-kapal dagang sehingga
menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Dengan demikian,
masyarakatnya hidup aman dan makmur. Dalam menjalankan pemerintahannya,
Raja dibantu oleh Bate Salapanga (Majelis Sembilan) yang diawasi oleh
seorang paccalaya (hakim). Sesudah sultan, jabatan tertinggi dibawahnya
adalah pabbicarabutta (mangkubumi) yang dibantu oleh tumailang matoa dan
malolo. Panglima tertinggi disebut anrong guru lompona tumakjannangan.
Bendahara kerajaan disebut opu bali raten yang juga bertugas mengurus
perdagangan dan hubungan luar negeri. Pejabat bidang keagamaan dijabat
oleh kadhi yang dibantu imam, khatib, dan bilal. Hasil kebudayaan yang
cukup menonjol dari Kerajaan Makassar adalah keahlian masyarakatnya
membuat perahu layar yang disebut pinisi dan lambo.
4. Kemunduran Kerajaan Makassar
Kemunduran Kerajaan Makassar disebabkan karena permusuhannya dengan VOC
yang berlangsung sangat lama. Ditambah dengan taktik VOC yang
memperalat Aru Palakka ( Raja Bone) untuk mengalahkan Makassar.
Kebetulan saat itu Kerajaan Makassar sedang bermusuhan dengan Kerajaan
Bone sehingga Raja Bone setuju bekerja sama dengan VOC.
KERAJAAN TERNATE
1. Awal Perkembangan Kerajaan Ternate
Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota
Kerajaan Ternate terletak di Sampalu (Pulau Ternate). Selain Kerajaan
Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain, seperti Jaelolo,
Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate
yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang,
baik dari Nusantara maupun pedagang asing.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Pemerintahan
Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Marhum (1465-1495 M). Raja
berikutnya adalah putranya, Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya,
Zainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di
sekitarnya, bahkan sampai ke Filiphina Selatan. Zainal Abidin
memerintah hingga tahun 1500 M. Setelah mangkat, pemerintahan di
Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan
Baabullah. Pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, Kerajaan Ternate
mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan Ternate meliputi
Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Bersamaan
dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas.
3. Aspek Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan
Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga
pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang
asing datang ke Ternate menjual barang perhiasan, pakaian, dan beras
untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Ramainya perdagangan memberikan
keuntungan besar bagi perkembangan Kerajaan Ternate sehingga dapat
membangun laut yang cukup kuat. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam,
masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan
hukum Islam . Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Hairun dari
Ternate dengan De Mesquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan
mengangkat sumpah dibawah kitab suci Al-Qur’an. Hasil kebudayaan yang
cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakatnya
membuat kapal, seperti kapal kora-kora.
4. Kemunduran Kerajaan Ternate
Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan
Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing ( Portugis dan Spanyol
) yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah
tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka
telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu
dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku.
Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk
Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil
menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi
dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.
KERAJAAN TIDORE
1. Awal Perkembangan Kerajaan Tidore
Kerajaan tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah
raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad
Naqal yang naik tahta pada tahun 1081 M. Baru pada tahun 1471 M, agama
Islam masuk di kerajaan Tidore yang dibawa oleh Ciriliyah, Raja Tidore
yang kesembilan. Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam
berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab.
2. Aspek Kehidupan Politik dan Kebudayaan
Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku
(1780-1805 M). Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk
bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta
terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat
apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik,
berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak
diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris sehingga
kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup
luas, meliputi Pulau Seram, Makean Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai,
dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Zainal Abidin. Ia juga
giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali.
3. Aspek Kehidupan Ekonomi dan Sosial
Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan
sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam . Hal itu dapat dilihat
pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugis
melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah dibawah kitab suci Al-
Qur’an.
Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah
Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, kerajaan Tidore banyak
didatangi oleh Bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku,
antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda.
4. Kemunduran Kerajaan Tidore
Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan
Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing ( Spanyol dan
Portugis ) yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-
rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa
mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian
bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan
Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang
dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku
berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang
teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.
NAMA-NAMA ULAMA AWAL DI INDONESIA
Ulama adalah sebutan bagi para mubaligh yang pekerjaannya lebih khususu
mengajarkan agama Islam dan benar-benar menguasai dan memahami mengenai
seluk beluk agam dan ajaran Islam. Dengan adanya para ulama ini tentu
akan lebih mudah dalam proses Islamisasi dan memperdalam tentang agama
Islam. Ada dua cara yang dilskuksn oleh para ulama untuk menyebarkan
agama dan ajaran Islam, yakni
Membentuk kader-kader ulama, yaitu dengan menyelenggarakan pengajaran
dan pendidikan Islam melalui Pendidikan pesantren-pesantren di Jawa,
dayah di Aceh, dan surau Minangkabau yang akan bertugas sebagai
mubaligh ke daerah-daerah.
Melalui karya-karya yang tersebar dan dibasa di berbagai tempat yang
jauh. Karya-karya tersebut menggambarkan perkembangan pemikiran dan
ilmu-illmu keagamaan di Indonesia pada masa itu. Para ulama di
Indonesia banyak bermunculan sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi.
Berikut adalah nama-nama ulama awal di Indonesia serta beberapa
penjelasannya.
1). Hamzah Fansuri
Hamzah Fansuri dilahirkan pada akhir abad ke-16 di Barus, Sumatra
Utara. Pada tahun 1726, Francois Valentijn dalam bukunya Oud en Nieuw
Oost-Indie pada bab mengenai Sumatra menyebutkan banwa Hamzah Fansuri
adalah sebagai penyair yang dilahirkan di Fansur. Hamzah Fansuri telah
mengembara ke berbagai tempat untuk menambah pengeteahuannya seperti
Mekah, Madinah, Baghdad, Kudus, dan tempat-tempat jawa lainnya. Ia
menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang
menjadi bahasa ibunya. Hamzah Fansuri adalah mengembang tarekat
wujudiyah atau Martabat Tujuh. Menurutnya yang disebut wujud iru hanya
satu, walaupun kelihatannya banyak. Wujud yang satu itu mempunyai dua
dimensi, yang meliputi dimensi batin (isi) dan dimensi lahir (kulit).
Semua benda yang tampak itu merupakan perwujudan dari dimensi batin,
yaitu waujud yang hakiki, yang tiada lain adalah Allah. Wujud yang
hakiki tersebut mempunyai tujuh martabat, yakni
1. Ahadiyah, hakikat sejati Allah.
2. Wahdah, hakikat Muhammad.
3. Wahidiyah, hakikat Nabi Adam.
4. Alam Arwah, hakikat nyawa.
5. Alam Mistad, hakikat segala bentuk.
6. Alam Ajsam, hakikat tubuh.
7. Alam Ihsan, hakikat manusia.
Semua martabat tersebut bermuara pada yang satu, yaitu ahadiyah, itulah
Allah. Pemikiran tasawufnya ini dipengaruhi oleh paham wahdat al wujud
dari Ibnu Arabi dan al Hallaj, ahli tasawuf yang masyhur pada akhir
abad ke-12 dan awal abad ke-13. Dibawah ini adalah karya-karya Hamzah
Fansuri;
1. Asrar all-Arifin (Rahasia Orang yang bijaksana)
2. Syarab al-Asyikin (Minuman Segala Orang yang Berani)
3. Zinat al-Muwahidin (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesakan)
4. Syair si Burung Pingai
5. Syair si Burung Pinggak
6. Syair Sidang Fakir
7. Syair Dagang
8. Syair Perahu
Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu ketika masa Sultan Iskandar
Muda,
1606-1636 M (abad ke-17, meghasilkan beberapa buah syair dan prosa).
Berikut ini merupakan syair karyanya;
Syair Perahu
Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Disanalah i’tikad diperbetuli sudah
Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil tubuhmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal diammu
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjaka
Itulah jalan membetuli insane
2). Syeikh Abdul Qadir Al Fathani
Kedudukan Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani dari sudut
ilmu pengetahuan adalah setaraf dengan ulama-ulama besar yang berada di
Mekah dan Madinah pada zaman itu. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman
al-Fathani menjalankan tugas ulama dengan aktivitis pengajarannya di
Masjidil Haram, Mekah dan di rumahnya sendiri.
Syeikh al-Fathani menyebut bahwa ayahnya, Syeikh Wan Muhammad Zain al-
Fathani lahir dalam tahun 1233 H/1817 M. Diriwayatkan bahawa Syeikh
Abdul Qadir al-Fathani itu lebih tua daripada Syeikh Muhammad Zain al-
Fathani. Riwayat lain menyebut bahwa usia Syeikh Abdul Qadir al-Fathani
lebih tua sekitar lima tahun daripada Syeikh Wan Muhammad Zain al-
Fathani. Jadi bererti Syeikh Abdul Qadir al-Fathani lahir dalam tahun
1228 H/1813 M. Diriwayatkan pula bahawa Syeikh Abdul Qadir al-Fathani
lebih tua daripada Syeikh Nawawi al-Bantani (Imam Nawawi Tsani).
Syeikh Nawawi al-Bantani lahir dalam tahun 1230 H/1814 M. Kedua-dua
ulama yang berasal dari Patani dan Banten itu bersahabat ketika kedua-
duanya belajar di Mekah. Kedua-duanya menerima bai`ah Thariqat
Qadiriyah-Naqsyabandiyah daripada Syeikh Ahmad Khatib Sambas (1217
H/1802 M-1289 H/1872 M). Dalam beberapa hal Syeikh Nawawi Banten
belajar kepada Syeikh Abdul Qadir al-Fathani, di antaranya ilmu qiraah.
Dan demikian sebaliknya dalam beberapa hal Syeikh Abdul Qadir al-
Fathani belajar pula kepada Syeikh Nawawi al-Bantani. Syeikh Abdul
Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani telah menyelamatkan cukup banyak
karya yang masih dalam bentuk tulisan tangan (manuskrip) yang dikarang
oleh ulama dunia Melayu, terutama sekali karya-karya Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fathani. Selain memelihara manuskrip dengan rapi, Syeikh
Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani pula telah melakukan
pentahqiqan dan pentashhihan beberapa buah kitab yang dianggap penting,
yang secara tradisinya banyak diajarkan dari sebelum hingga zaman
beliau. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani ini sangat
penting bagi orang-orang Melayu yang berada di Mekah pada zamannya.
Beliau adalah guru bagi seluruh ulama Asia Tenggara, pakar tempat
rujukan dalam semua bidang keilmuan keislaman. Telah disebutkan bahawa
Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani adalah keluarga dekat
kepada Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, maka Syeikh Abdul Qadir bin
Abdur Rahman al-Fathani inilah yang pertama mengambil tempat
kemasyhuran Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani setelah beliau
meninggal dunia. Pengetahuan Islam dan predikat ulama pada peribadi
Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani tidak pernah diragukan
oleh para ulama yang sezaman dengan beliau. Kedudukan Syeikh Abdul
Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani dari sudut ilmu pengetahuan adalah
setaraf dengan ulama-ulama besar yang berada di Mekah dan Madinah pada
zaman itu. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani menjalankan
tugas ulama dengan aktiviti pe-
ngajarannya di Masjidil Haram, Mekah dan di rumahnya sendiri. Suatu hal
yang menarik disebut di sini bahawa Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman
al-Fathani adalah seorang ulama yang besar pengaruhnya di kalangan
Thariqat Syathariyah. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani
adalah seorang Mursyid dalam Thariqat Syathariyah tersebut. Syeikh
Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani menerima Thariqat Syathariyah
adalah secara langsung kepada Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Oleh sebab Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani telah
diperbolehkan mentawajjuh, membai'ah, dan mengijazahkan Thariqat
Syathariyah tersebut, maka pengaruh beliau lebih besar di kalangan
masyarakat pengamal sufi Islami. Syeikh Wan Ali Kutan al-Kalantani
dipercayai telah menerima Thariqat Syathariyah daripada Syeikh Abdul
Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani kerana ulama yang berasal dari
Kelantan itu tidak bertemu ketika dewasa dengan Syeikh Daud bin
Abdullah al-Fathani.
Syeikh Abdul Qadir al-Fathani bin Abdur Rahman al-Fathani sekurang-
kurangnya telah menghasilkan 14 buah karangan, namun kerana kekurangan
ruangan perbicaraan tentangnya terpaksa ditangguhkan.
3). Syeikh Muhammad Mukhtar (Tuan Mukhtar Bogor)
Nama lengkap beliau ialah Syeikh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughri
al-Batawi al-Jawi. Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada hari Khamis, 14
Sya’ban 1278 H/14 Februari 1862 M, wafat di Mekah, 17 Shafar 1349 H/13
Juli 1930 M. Tuan Mukhtar Bogor menguasai banyak bidang disiplin ilmu
termasuk ilmu-ilmu hadis, beliau berpegang dengan Mazhab Syafi’ie,
pengikut setia Mazhab Ahlis Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abu Hasan al-
Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Beliau memperoleh pendidikan
dari orang tuanya sendiri. Dalam tahun 1299 H/1881 M melanjutkan
pelajarannya di Betawi/Jakarta, belajar kepada al-Allamah al-Habib
Utsman bin Aqil bin Yahya, Mufti Betawi. Melalui ulama Arab keturunan
Rasulallah s.a.w tersebut Tuan Mukhtar Bogor hafal matan-matan ilmu.
Syeikh Muhammad Mukhtar Bogor menghasilkan karya yang tersebar berupa
cetakan ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang
telah diketahui dan dijumpai adalah sebagai yang tersebut di bawah ini:
1. Taqribul Maqshad fil Amali bir Rub'il Mujaiyab ( ilmu falakiyah)
2. Ushulud Din I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah ( akidah, sifat dua
puluh)
3. Ar-Risalatul Wahbatil Ilahiyah fi Bayani Itsqati ma'alal Maiyiti
minal Huquqi was Shiyam was Shalati ( membicarakan fidiyah sembahyang,
puasa dan lain-lain)
4. As-Shawa'iqul Muhriqah lil Auhamil Kazibah fi Bayani Hillil Baluti
war Raddu `ala man Harramahu (membicarakan hukum boleh makan belut )
Dan sebagainya.
4). Syeikh Abdul Hamid
Nama lengkapnya ialah Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud. Ayah dan datuk
neneknya berasal dari Talu, Minangkabau. Abdul Hamid dilahirkan di
Tanjung Balai Asahan tahun 1298 H/1880 M. Wafat pada hari Khamis,
petang Jumaat pada 10 Rabiulakhir 1370 H/18 Februari 1951 M. Menjelang
perang dunia kedua, sekitar tahun 1930an, Abdul Hamid menyelesaikan
beberapa buah karangan, yang dapat diketahui ialah:
1. Ad-Durusul Khulasiyah, pernah dicetak di Mekah.
2. Al-Mathalibul Jamaliyah, pernah dicetak di Mekah.
3. Al-Mamlakul `Arabiyah.
4. Nujumul Ihtiba.
5. Tamyizut Taqlidi minal Ittiba.
6. Al-Ittiba.
7. Al-Mufradat.
8. Mi'rajun Nabi.
Selain mengarang kitab, Abdul Hamid juga pernah menerbitkan majalah
bahasa Arab dan Melayu yang diberi judul Majallah `Ulumil Islamiyah.
5) Syamsudin al Sumatrani
Ilmuwan muslim yang merupakan murid Hamzah Fansuri. Syamsudin menulis
buku yang berjudul Mir’atul Mu’minin (Cermin Orang beriman), 1601 M.
6) Nuruddin al Raniri
Ulama yang berasal dari aceh yang banyak menuangkan hasi pemikirannya
tentang ajaran Islam dalam berbagai buku. Ia berasal dari Ranir,
Gujarat (India) dan keturunan bangsa quraisy Hadramaut. Raniri dikenal
sebagai orang yang giat membela ajaran Ahlussunah Waljamaah. Menurut
catatan Ahmad Daudi, karyanya yang sudah diketahui yaitu 29 buah.
Diantara karya-karyanya adalah:
1. Al Shirat dan Al Mustaqim berisi uraian tentang hokum.
2. Bustan Al Salathin, berisi sejarah dan tuntunan bagi para raja.
3. Asrar Al Insani fi Ma’rifati al Ruh wa al Rahman, karyanya dalam
ilmu kalam.
4. Tibyan fi Ma’rifat al Adyan, yang berisikan perdebatan dengan kaum
wujudiyah.
5. Al lama’ah fi Takfir an qala bi Khalq al qur’an, yang juga merupakan
bantahan terhadap pendapat Hamzah Fansuri bahwa al Qur’an itu makhluk.
Raniri berusaha melenyapkan pemikiran Hamzah Fansuri. Dalam dunia
tasawuf, paham Raniri dalam banyak hal lebih cocok dengan ilmu kalam.
7) Syeikh Kuala (Abdurauf)
Berasal dari kerajaan Aceh dari Singkel. Dilahirkan kira-kira tahun
1620. Abdurauf mendalami ilmu pengetahuan di Mekkah dan Madinah. Dia
menghidupakan kembali ajaran tasawuf yang sebelumnya dikembangkan oleh
Hamzah Fansuri. Abduraug juga membuat tafsir AlQur’an dalam bahasa
Melayu dan Jawa.
8) Syeikh Yusuf Makasar
Di Sulawesi, pemikiran tasawuf juga berkembang melalui Syeikh Yusuf
Makasar (1626-1699) yang lama belajar di Timur Tengah. Karya-karyanya
diperkirakan berjumlah 20 buah dan masih dalam bentuk naskah yang belum
diterbitkan.
9) Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari (1710-1812 M)
Ulama yang muncul sekitar abad ke-19 M, pemikirannya tidak mengenai
tasawuf, tetapi pemikiran fiqih. Ia menulis kitab Sabilul Muhtadin,
sebuah kitab fiqih dan kitab Perukunan Melayu.
10) Haji Ahmad Rifangi (1786-1875 M)
Berasal dari kalisasak yang menuis banyak buku, diantaranya Husnul
Mathalib, asnal Maqashid, Jam’u l Masa’ilAbyanul Hawa’ij, dan Ri’ayatul
Himmah, yang umumnya membahas ushuluddin, fiqih, dan tasawuf.
11) Syeikh Nawawi
Syeikh Nawawi berasal dari Banten menulis tidak kurang dari 26 buah
kitab, yang terkenal diantaranya adalah al Tafsir al Munir.
WALI SONGO DALAM ISLAMISASI DI INDONESIAA. Wali Songo dalam Islamisasi di indonesia.
Ada 9 ulama yang sangat berjasa dalam penyabaran islam di jawa. Wali
Songo mengembangkan agama islam antara abad ke 14 sampai 16, menjelang
dan setelah runtuhnya kerajaan majapahit. Dalam babad tanah jawi dalam
berdakwah para wali dianggap sebagai kepala sekelompok mubalig untuk
daerah penyiaran tertentu. Selain dikenal sebagai ulama, mereka juga
berpengaruh besar dalam kehidupan politik pemerintahan. Karena itu,
mereka diberi gelar “Sunan” (Susuruhan, junjungan).
a. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik.
Dikenal juga dengan nama Maulana Magribi (syekh magribi). Ia juga
berasal dari magribi (afrika utara). Ia berasal dari keluarga muslim
yang taat, dan belajar agama islam sejak kecil. Ia berdakwah secara
intensif dan bijaksana. Upaya menghilangkan sistem kasta dalam
masyarakat pada masa itu menjadi objek berdakwah. Cita – cita dan
perjuangannya dilanjutkan oleh anaknya, Sunan Ampel.
b. Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta (
dekat surabaya ) Jawa Timur. Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang dan
Sunan Drajat adalah murid – muridnya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali
yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat jawa misalnya,
kebiasaan mengadakan sesaji dan selamatan. Namun para wali lain
berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera. Mereka
mengusulkan agar adat istiadat itu diberi warna islam. Akhirnya Sunan
Ampel menyetujui bahwa hal itu akan berkembang menjadi bid’ah.
c. Raden Paku ( Raden Ainul Yaqin ) atau Sunan Giri.
Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Ia di tugaskan Sunan Ampel untuk
menyiarkan agama islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di
pesantren ampel denta. Setelah dewasa, pada suatu perjalanan haji
bersama Sunan Bonang, ia singgah di pasai untuk memperdalam ilmu agama.
Sekembalinya ke jawa, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah giri.
Ia juga banyak mengirim juru dakwah ke Bawean.
d. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang.
Menyebarkan agama islam dengan cara menyesuaikan diri dengan corak
kebudayaan masyarakat jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan.
Untuk itu, ia menciptakan gending – gending yang memiliki nilai
keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan dua kalimah
syahadat sehingga musik gamelan yang mengiringinya kian dikenal dengan
istilah sekaten. Sunan Bonang pernah belajar islam di Pasai, Aceh.
Sekembalinya dari pasai, ia memusatkan kegiatan dakwahnya di Tuban yang
mendirikan pondok pesantren.
e. Sunan Drajat (Raden Qosim Syarifudin )
Dikenal sebagai seorang wali yang dermawan. Ia banyak memberikan
pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, orang sakit dan orang
sengsara. Perhatiannya yang besar terhadap masalah sosial sangat tepat
pada masa itu. Ia hidup pada saat kerajaan majapahit runtuh ( 1428 M )
dan rakyat mengalami suasana kritis serta prihatin.
f. Syarif hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.
Adalah wali yang sangat berperan dalam penyebaran islam di jawa barat,
khususnya Cirebon. Ia pendiri dinasti kesultanan Banten. Kesultanan
Banten dimulai dari putranya, Sultan Maulana Hasanudin. Sunan Gunung
Jati memprakarsai penyerangan ke sunda kelapa pada tahun 1527 m dibawah
pimpinan fatahillah, panglima perang Kesultanan Demak yang juga menantu
Sunan Gunung Jati.
g. Raden Jafar Sadiq atau Sunan Qudus.
Sunan Qudus membangun masjid di daerah loran pada tahun 1549 m namanya
masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, wilayah sekitarnya disebut qudus. Sunan
Qudus digelari wali Al-Ilmi ( orang berilmu luas ) oleh para wali songo
karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama.
h. Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga
Dikenal sebagai budayawan dan seniman ( seni suara, ukir dan busana ).
Ia menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan islam yang dibuat
dari kulit kambing ( wayang kulit ). Pada masa itu wayang populer
dilukis pada semacam kertas lebar ( wayang beber ). Dalam seni suara,
ia adalah pencipta lagu dandang gula. Sunan kalijaga berasal dari suku
jawa asli. Ia melakukan dakwahnya dengan cara berkelana. Karena
wawasannya luas dan pemikirannya tajam, Sunan Kalijaga tidak hanya
disukai rakyat, tetapi juga oleh para cendikiawan dan penguasa.
i. Raden Said ( Raden Prawoto ) atau Sunan Muria.
Adalah salah seorang wali yang sangat berjasa bagi penyebaran islam di
daerah pedesaan. Sunan Muria pun menggunakan kesenian sebagai sarana
berdakwah. Dua tembang yang diciptakannya dan sangat terkenal adalah
sinom dan kinanti. Tembang sinom umumnya melukiskan suasana ramah tamah
dan berisi nasihat. Adapun tembang kinanti yang bernada gembira
digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat dan filsafat