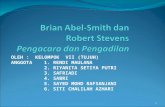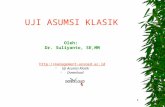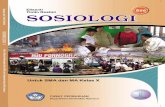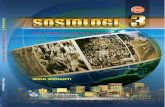TEORI SOSIOLOGI KLASIK
Transcript of TEORI SOSIOLOGI KLASIK
TEORI SOSIOLOGI KLASIK
KATA PENGANTAR
Buku ajar Teori Sosiologi Klasik adalah sebagai bahan bacaanatau literatur mata kuliah Teori Sosiologi Klasik di JurusanSosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasLampung. Dengan adanya buku ini merupakan salah satu jalan dalammempermudah mahasiswa untuk mendapatkan literatur Teori SosiologiKlasik.
Sebagai sebuah mata kuliah wajib jurusan, maka telaah dalambuku ini dibuat secara simpel dan universal agar mahasiswa mampumenyerap secara baik semua tema yang dipaparkan dalam buku ajarini. Dan materi yang menjadi kajian dalam buku ajar ini dibagidalam delapan bab pokok bahasan
Bab pertama membahas tentang Teori Sosiologi. Salah satukesulitan yang mungkin timbul bagi para peminat di bidang ilmusosiologi adalah kurangnya pemahaman tentang pengertian apa yangdisebut dengan teori. Bagaimana kedudukan teori sosiologi didalam usahanya untuk memahami kenyataan-kenyataan sosial. Olehkarena itu pada bab pertama ini akan dijelaskan tentang teori danteori sosiologi.
Bab kedua membahas tentang Filsafat Sosial sebagai DasarTeori Sosial. Pokok bahasan yang akan diuraikan pada bab keduaini adalah lahirnya filsuf-filsuf yang terkenal di era Yunaniyaitu Socrates, Plato dan Aristoteles. Ke tiga tokoh yangmenjadi ‘sufi’ di zamannya ini, akan dibahas secara rinci mulaidari riwayat hidupnya, metode berfikirnya hingga filsafat sosialyang dilahirkannya yang akan menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori sosial selanjutnya khususnya teori-teori sosiologi.
Bab ketiga membahas tentang Periode Transisi dan PemikiranFilsafat Ke Pemikiran Ilmu Pengetahuan. Pokok bahasan pada babini menguraikan pemikiran sosial para tokoh masa transisi dariperiode filsafat ke ilmu pengetahuan yang ditandai besarnyakekuasaan gereja dalam kehidupan kemasyarakatan dengan salah satupelopornya adalah Thomas van Aquinas. Bab ini juga menguraikan
pemikiran para tokoh sosial masa revolusi industri danRenaissance dengan tokohnya F. Bacon, N. Machiavelli, ThomasHobbes, John Lock dan Vico.
Bab keempat membahas Lahirnya Sosiologi Sebagai IlmuPengetahuan. Uraian utama pada bab keempat ini adalah menjelaskansumbangan pemikiran sosial yang berguna bagi lahirnya sosiologisebagai ilmu pengetahuan. Sumbangan pemikiran itu khususnya daritokoh Saint Simon, Auguste Compte dan Herbert Spencer. Ke tigatokoh ini akan diuraikan secara jelas mulai dari riwayat hiduphingga sumbangan pemikiran mereka yang begitu berarti danberperan dalam melahirkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.
Pokok pembahasan yang akan diuraikan pada bab kelima ini adalahsumbangan pemikiran dari Karl Marx terhadap Ilmu Sosiologi.Adapun materi-materi yang akan dibahas adalah sejarah singkatriwayat hidup Karl Marx serta menjelaskan pemikiran Karl Marxtentang materialisme historis, model-model masyarakat,alinasi,kesadaran kelas dan perubahan sosial.
Bab keenam membahas tentang sumbangan pemikiran dari EmileDurkheim terhadap Ilmu Sosiologi. Durkheim dapat dipandangsebagai salah seorang yang meletakkan dasar-dasar sosiologimodern. Pada bab enam ini akan dijelaskan tentang fakta sosial,karakteristik dan metode pengamatan fakta sosial Durkheim.Menjelaskan juga tentang pengertian solidaritas sosial danmembedakan jenis-jenis solidaritas social. Menjelaskanpengertian kesadaran kolektif Durkheim, teori bunuh diri danjenis-jenis bunuh diri, pengertian anomi, serta pengertianintegrasi masyarakat menurut Durkheim.
Bab ketujuh pokok bahasannya adalah menguraikan sumbanganpemikiran Max Weber yang berguna bagi pemikiran dan perkembanganilmu sosiologi. Materi yang akan dijelaskan diantaranya sejarahsingkat riwayat hidup Max Weber, konsepsi tindakan sosial dantipe-tipe tindakan sosial menurutWeber, pengertian verstehende, serta penjelasan Etika Protestandan Spirit Kapitalisme Weber yang cukup menggemparkan dan menjadibahan pergunjingan yang kontroversial bagi kehidupan ilmiah.
Di penutup bab ini (bab kedelapan) akan dibahas tentangParadigma Sosiologi. Dalam perkambangan selanjutnya setelahterlepas dari pengaruh filsafat dan psikologi, sosiologi mulaimemasuki arena pergulatan pemikiran yang bersifat interen dikalangan teoritisnya sendiri. Pergulatan yang bersifat interenini hingga sekarang masih saja berlangsung. Perkembangansosiologi ditandai dan tercermin dari adanya berbagai paradigmadi dalamnya. Pada bab kedelapan ini akan dijabarkan tentangpengertian paradigma sosiologi, sebab timbulnya berbagaiparadigma sosiologi. menjelaskan 3 paradigma sosiologi yaituparadigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigmaperilaku sosial serta menjelaskan hubungan antara paradigma yangsatu dengan yang lainnya.
Akhirnya penulis berharap agar apa yang telah dipaparkandalam buku ini dapat dipahami oleh semua pembaca. Untuk itukritik dan saran dari mana dan dari siapapun jua datangnya dalamusaha penyempurnaan buku ini, penulis sambut dengan senang hatidan ucapan terima kasih.
Bandar Lampung, Juni 2011
Tim Penyusun
SANWACANA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karenaatas Taufik dan Hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan bukuini., yang mana hasilnya masih jauh dari sempurna. Buku yangberada di hadapan para pembaca ini adalah sebagai pelengkap dansekaligus memperkaya bahan bacaan atau literatur dalam matakuliah Teori Sosiologi Klasik bagi mahasiswa di JurusanSosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitaslampung khususnya dan di perguruan Tinggi lainnya baik di negerimaupun swasta di Propinsi Lampung ini.
Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa buku ini tidakakan selesai andaikata tidak ada bantuan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannyakepada penulis khususnya kepada Hibah Peningkatan Mutu BukuAjar Universitas Lampung, yang telah memberi bantuan dana untukproses pembuatan buku ajar ini.
BAB I
TEORI SOSIOLOGI
A. PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Salah satu kesulitan yang mungkin timbul bagi parapeminat di bidang ilmu sosiologi adalah kurangnya pemahamantentang pengertian apa yang disebut dengan teori. Bagaimanakedudukan teori sosiologi di dalam usahanya untuk memahamikenyataan-kemyataan sosial. Kesulitan ini akan lebih mudahteratasi apabila sebelum orang membicarakan teori-teorisosiologi, sudah terlebih dahulu memahami bagaimanapengertian teori dan kedudukannya di dalam usaha untukmemahami kenyataan sosial.
Tujuan khusus mempelajari teori sosiologi adalahmenjelaskan batasan yang disebut teori dan teori sosiologi,serta bagaimana mempergunakan teori sosiologi tersebut didalam usaha memahami atau menganalisa kenyataan sosial.
Untuk itu setelah mengikuti perkuliahan ataumempelajari teori sosiologi, mahasiswa diharapkan dapat :
1. menjelaskan manfaat teori dalam kehidupan sehari-hari.
2. menjelaskan peran teori dalam memecahkan problemateoritis.
3. menggunakan teori sosiologi dalam usaha memahami danmenganalisa kenyataan
sosial.
A. TEORI
Sadar atau tidak, semua orang sebetulnya berteori. Orangyang paling erat hubungannya dengan kegiatan praktek
sekalipun, seperti seorang pengacara yang membela perkara danmemperingati hakim supaya tetap berpegang pada fakta, harusmenginterpretasikan fakta sehingga relevan baginya. Ininamanya proses berteori.
Berteori dengan jalan memberikan interpretasi itu sangatlahpenting, karena perlu untuk menjelaskan peristiwa. Betapapunlingkungan suasana yang kita hadapi itu baik atau buruk, kitaharus jelaskan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain,mengapa demikian. Caranya adalah dengan jalan menghubungkansituasi sekarang dengan pengalaman atau keputusan keputusanyang sudah kita berikan dimasa lampau, pengaruh-pengaruhsosial atau tekanan-tekanan dari orang lain, krisis-krisisyang umumnya dihadapi pada waktu itu, atau hambatan-hambatanserta kesempatan-kesempatan yang tersedia dalam lingkunganitu.
Orang tua berusaha menjelaskan mengapa anak-anaknyamenanggung suatu akibat tertentu, mahasiswa berusahamenjelaskan kepada dirinya sendiri mengapa mereka tidak luluswalaupun mereka merasa bahwa tidak harus terjadi demikian,guru, polisi, para pemimpin politik menjelaskan kepada dirinyasendiri dan kepada orang lain, mengapa dan apa yang merekabuat.
Merencanakan atau meramalkan masa depan menuntut kita untukmelihat apa yang ada dibelakang fakta, dan berarti itu kitaberteori. Tak seorangpun dapat meramalkan masa depan denganmutlak. Apa yang kita buat adalah membuat dugaan-dugaan danmenyesuaikan perilaku kita sekarang ini dalam hubungannyadengan harapan-harapan. Orang muda yang memilih karir, orangtua yang menyesuaikan diri dengan perilaku anak-anaknya, paralangganan yang merencanakan pembelanjaannya yang penting,penjual yang mengembangkan taktik-taktik penjualan, pemimpinpolitik yang yang berdebat mengenai dilema kebijaksanaan luarnegeri, dan mahasiswa yang berspekulasi mengenai kira-kira apayang diberikan oleh profesor dalam ujian yang akan datang,semua ini menunjukkan kepada kita akan adanya kebutuhan untukbisa melihat apa yang ada dibalik fakta yang ada sekarang, dankita berteori.
Ada sikap yang umumnya dikemukakan orang dalam bentukpertanyaan “apa guna teori” dan mana faktanya. Kalau tidak adafakta yang kuat, ide seringkali menjadi tidak karuan karenaapa artinya teori tanpa fakta. Mahasiswa yang mempelajarisosiologi juga mempersoalkan perlunya mempelajari ide-ideabstrak yang kelihatannya mempunyai hubungan erat dengan dunianyata. Asumsi bahwa kalau semua fakta diketahui maka orangakan berbicara tentang fakta saja dan teori tidak diperlukanlagi.
Tetapi tidak semua fakta yang kita butuhkan tersedia.Kalaupun faktanya sudah ada, masih harus diinterpretasikansupaya fakta itu mempunyai arti yang sesuai dengan kebutuhandan rencana kita. Karena arti fakta itu tidak selalu jelasdengan sendirinya, maka teorilah yang dapat membantu kitauntuk menginterpretasikan dan menilainya.
Suatu teori yang baik dapat membantu kita untuk memahamifakta, menjelaskan, dan memberikan ramalan yang valid, hal inisangat perlu dalam suatu perencanaan untuk masa yang akandatang, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kitasendiri maupun yang berhubungan dengan perencanaankebijaksanaan umum.
Para ahli ilmu sosial dan akademisi lainnya kadang-kadangdituduh terlalu menjauhkan diri dari dunia nyata dan hidupdalam menara gading. Teori-teori yang mereka berikan seringtidak praktis dan relevan. Kenyataan kehidupan sehari-harinampaknya menjadi kabur karena mereka menjelaskannya denganistilah-istilah tertentu yang hanya dimengerti oleh kelompok-kelompok tertentu saja (jargon).
Meskipun penggunaan istilah khusus yang sangat abstrak itudapat merugikan, namun para spesialis dalam semua bidang ilmupengetahuan, mulai dari ahli fisika dan hakim sampai denganpekerja-pekerja dibengkel mobil dan konstruksi, memilikiperbendaharaan istilah sendiri. Hal ini sangat membantu merekauntuk dapat berkomunikasi secara tepat, memungkinkan merekauntuk dapat mengambil bagian dan mempertegas ide-ide yangbersifat teknis, serta memungkinkan mereka untuk dapat bekerja
sama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lebih bergunalagi kiranya, bahwa dengan istilah-istilah itu, batas-batassuatu profesi dapat ditarik, dan meningkatkan status paraanggota profesi, serta membedakannya dari mereka yang tidaktermasuk dalam profesi itu.
Teori yang dipergunakan orang dalam kehidupan sehari-haribiasanya bersifat implisit, tidak eksplisit. Sering teori-teori dapat kita lihat dalam tradisi dan dalam kebijaksanaanrakyat yang dapat diterima dengan akal sehat. Asumsi-asumsiteoritis yang mendasar itu dapat kita lihat dalam simbol-simbol kepercayaan yang sudah sangat berkambang mengenaikodrat manusia atau masyarakat, seperti misalnya kepercayaanagama yang mengatakan bahwa manusia memiliki satu keistimewaantertentu yang diperolehnya dari Allah, dan yang membedakanmanusia dari binatang-binatang lainnya, atau adannyakepercayaan bahwa dalam jangka waktu yang panjang, orang yangberperilaku baik akan dihargai dan yang berperilaku jahat atauburuk akan disiksa.
Teori-teori implisit itu mewarnai sikap kita pada umumnyaterhadap orang lain dan terhadap masyarakat. Kita semua tahubahwa ada orang yang sinis yang percaya bahwa manusia ituhanya tertarik pada kesejahteraannya sendiri saja, dan adamanusia yang optimis yang terus menerus menerus mencari sifat-sifat yang baik atau yang positif pada orang lain dan seringmelihatnya demikian, sedangkan orang lain tidak. Karena banyakdari asumsi-asumsi ini bersifat implisit, maka orang lalutidak menjadi sadar kalau mereka tidak konsisten.
Bagi kebanyakan orang, teori-teorinya itu mungkin tetapbersifat implisit, tetapi karena pelbagai alasan, orang lainmenjadi lebih sadar dimana segi-segi tertentu dari teori-teorimereka yang implisit itu menjadi eksplisit dan tunduk padaanalisa objektif atau analisa kritis. Proses ini tidak harusberarti bahwa teori-teori implisit itu akan ditolak,sebaliknya teori-teori itu mungkin mendapat dukungan.Bagaimanapun individu menjadi sadar akan beberapaa dariasumsi-asumsi teoritis yang mendasar dan rela mengujinyasecara objektif, paling kurang dalam tingkatan tertentu.
Umumnya kekuatan sesuatu teori terletak pada kemampuannyauntuk membawa banyak pemikiran dan informasi mengenai suatuproblem khusus. Teori demikian bisa menghasilkan danmengandung ide-ide yang siap dipakai pada suatu ketika. Sebuahteori mencoba memecahkan sebuah problem teoritis ke dalamempat kategori yaitu .
1. Teori memungkinkan adanya ide-ide tambahan untukpemecahan beberapa problem teoritis yang ada.
2. Teori memungkinkan adanya model-model dari buah pikirandan dengan demikian menghasilkan suatu deskripsi skematis.Deskripsi itu dapat dibayangkan sebagai suatu pola dan didalam pola itu ide-ide tersebut tersusun rapi dan serasi.
3. Model-model memungkinkan adanya teori-teori.
4. Teori memungkinkan adanya hipotesa-hipotesa.
1. Teori Memungkinkan adanya Ide-Ide
Sebuah pendekatan teoritis terhadap suatu ide secaraalamiah menyebabkan penciptaan ide-ide lain yang membantuuntuk menjelaskan yang satu dan mendefinisikan hubungannyadengan yang lain.Contohnya: kelas sosial bisa dirasakan ataudialami tapi tidak ada arti teoritis dalam batasan itusendiri. Teori itu baru muncul kalau ide kelas sosial tersebutdiletakkan bersama-sama dengan ide-ide tambahan yang ikutmenerangkan hal-hal lainnya. Misalnya memahami kelas sosialharus juga memahami arti struktur sosial, hak-hak istimewa,hubungan sosial, kewajiban, otoritas, dan ide-ide lainnya.Jadi, pada prinsipnya sebuah ide bisa dihasilkan denganmenguji sesuatu secara empiris, dan menjabarkan ide ini kedalam peta ide-ide yang disebut dengan teori.
2. Teori Memungkinkan adanya Model-Model
Teori dan model berbeda, kalau teori menerangkan sesuatusecara langsung, sedangkan model menerangkan sesuatu dengan
analogi. Suatu model dari sesuatu hal bukanlah hal itu sendiritapi suatu yang punya sebuah persamaan dengan hal tersebut.Contohnya pesawat model dan Boeing 747 tidaklah sama, tapikeduanya memiliki kesamaan yaitu terbangnya pesawat modelkarena dilemparkan, namun bergeraknya sayap-sayapnya diudara, bentuk dan struktur sayap-sayap dan hubungan denganstruktur lainnya adalah analog dengan terbangnya Boeing 747.
3. Model-Model Memungkinkan adanya Teori-teori
Sebuah teori bisa memprediksikan bahwa ada suatu hubungantertentu antara dua ide tetapi kurang membicarakan hubunganantara ide-ide ini dengan ide-ide lainnya. Dengan menemukansuatu model yang nampaknya mendekati hubungan antara ide-ideyang pertama, bisa dengan analogi bahwa ada ide-ide lain yangmemungkinkan terjadinya hubungan itu oleh karena model itumemungkinkan tambahan-tambahan untuk teori tersebut.
4. Teori-Teori Memungkinkan adanya Hipotesa-Hipotesa
Sebuah hipotesa adalah suatu pernyataan mengenai hubunganantara dua atau lebih ide-ide atau kelas-kelas dari suatu hal.Dalam hubungan yang paling kuat antar teori dan hipotesaadalah terjadi secara deduktif, yaitu hipotesa-hipotesa itumengikuti secara langsung dari generalisasi dan konsep-konsepyang telah ditetapkan dalam sebuah teori. Sebuah teori dapatmenghasilkan hipotesa-hipotesa bila teori itu ditetapkan dalamproblem teoritis atau empiris tertentu. Contohnya teorisolidaritas sosial dan praktek-praktek keagamaan seperti yangdilakukan Emile Durkheim dalam bukunya Suicide, kita bisamembuat hipotesa-hipotesa atau pernyataan-pernyataan mengenaihubungan yang mungkin terjadi antara praktek-praktek agama dansosial tertentu seperti bunuh diri misalnya
Salah satu cara untuk mengklasifikasikan teori adalahmengikat diri dengan teori-teori itu menurut wilayah-wilayahdi mana teori-teori itu mula-mula diajukan atau digunakanuntuk berbagai macam keperluan. Cara lain ialah mengelompokkanteori-teori menurut wilayah di mana teori-teori itu dilahirkandan digunakan secara paling luas.
Ada satu lagi cara untuk mengklasifikasikan teori yangbanyak dianjurkan orang akhir-akhir ini, yaitu yang menekankanbahwa untuk mendapatkan teori mengenai sesuatu , sesuatu ituharus pertama-tama didefinisikan secara tepat dan kemudiansesuatu hal itu dapat diperhitungkan.
B. TEORI SOSIOLOGI
Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mencoba menjelaskanaspek-aspek kehidupan manusia, maka sosiologi juga peka untukmelakukan pembahasan tentang nilai dan moral yang terlibatdalam berteori. Pada umumnya argumentasi kebebasan nilaidalam teori sosiologi telah berjalan, yang mana agar dapatditemukan sesuatu dan mengkonsepsikan sesuatu itu, parasosiolog perlu menghilangkan prasangka pribadi mengenaihubungan sosial dalam studinya. Pernyataan ini tidak berartibahwa dia harus tidak menjadi seorang yang bermoral. Tetapiuntuk tujuan deskripsi dan teori ini bila seseorang inginmengetahui yang sebenarnya maka dia harus mengobservasikan,menguraikan, dan menggunakan teori dengan tidak berat sebelah.Bila kejujuran tidak dipakai sepenuhnya, apa yang dianggapseharusnya terjadi dapat ia nyatakan sebagai sesuatu yangsesungguhnya, dogma akan turut lebur dalam pemikirannya.
Sosiologi sejak awal perkembangannya dipermulaan abad 19hingga dewasa ini, telah mengalami perubahan yang terusmenerus. Ilmu yang oleh Auguste Compte disebut dengan “SosialPhysics” , dikenal dengan nama sosiologi, berkembang terusseiring perubahan yang timbul dalam masyarakat. Adalah Compte,bapak pendiri sosiologi yang mengatakan ada 2 cara untukmempelajari suatu ilmu pengetahuan yaitu secara dogmatis dansecara historis.
Mempelajari ilmu pengetahuan secara dogmatis akan membawakita pada pemahaman teori-teori ilmu yang bersangkutan,sedangkan mempelajarinya secara historis memaksa kitamenelusuri awal mula, konteks situasi di mana teori itu lahir.
Pernyataan di atas ini sesungguhnya juga berawal dari banyakpendapat para sarjana di lapangan ilmu pengetahuan sosialbahwa tujuan yang fundamental dari ilmu-ilmu sosial termasuksosiologi adalah menerangkan tentang kenyataan-kenyataanperubahan sosial. Bahkan khusus untuk sosiologi itu sendiriada yang menyatakan ilmu ini adalah ilmu tentang krisissosial. Dinyatakan demikian karena pada kenyataannya, sejakawal pertumbuhannya hingga perkembangannya dewasa inisosiologi cenderung memperoleh bentuk-bentuk baru selarasdengan krisis sosial.
Charles A Ellwood, di dalam bukunya yang terkenal A History ofSosial Philosophy menyebut adanya sebuah teori yang dikenal dengan“ the crisis of thought” atau Teori Krisis Pemikiran. Menurut teoriini, orang hanya akan berfikir bila mana timbul persoalan-persoalan, bila mana kebiasaan-kebiasaan lama kita tidak lagiberfungsi dan kita membutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru.Sebagaimana akan diterangkan kemudian di dalam buku ini,Charles Ellwood mengambil contoh krisis yang menimbulkanlahirnya pemikiran-pemikiran di lapangan ilmu kemasyarakatanketika Athena, negara kota di abad Hellenic yang angkuh ituberantakan ketika dikalahkan oleh Sparta, suatu bangsa yangoleh orang Athena dianggap bangsa yang terbelakang.
Jadi jelaslah bahwa sosiologi adalah merupakan refleksi darikeadaan masyarakat yang sedang berubah dan teori-teori yangdihasilkannya merupakan hasil dari keadaan masyarakat itusendiri. Dan karena pada kenyataannya tiada satupunmasyarakat yang tidak mengalami perubahan, maka sosiologiakan terus berkembang di dalam masyarakat. Teori-teorinya akanterus berkembang dengan segala konsekuensinya, yang mungkinakan terlempar dari peredaran atau mungkin juga akan bertahan.Sementara itu pula akan muncul teori-teori baru yangdihasilkan seiring dengan perubahan kemasyarakatan yangterjadi.
Untuk membuktikan hal itu mungkin kita bisa melacaknya jauhke belakang pada permulaan abad ke 19 dimana terjadi perubahanyang sangat cepat dan hebat di dalam masyarakat akibatterjadinya revolusi industri dan juga terjadinya revolusi
sosial di Eropa. Sebuah perubahan yang memperkenalkankekuasaan masyarakat dan kekuasaan massa. Penemuan-penemuanbaru di bidang teknologi pada masa itu telah menghasilkanpolarisasi yang sangat hebat antara kaum pemilik modal denganmereka yang tidak memiliki.
Berkembangnya industri-industri di daerah perkotaan telahmengakibatkan mengalirnya urbanisasi dari daerah pedesaanuntuk mencari kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Tetapikemudian kenyataannya menunjukkan telah terjadi semacampenghisapan oleh kaum majikan yakni para pemilik modal yangmenguasai indusri-industri tersebut terhadap para buruh yangbekerja di pabrik-pabrik. Perubahan ini kemudian menghasilkanberbagai krisis sosial dengan meningkatnya kriminalitas dankemiskinan rakyat jelata yang tidak punya modal. Di dalamsituasi sedemikian inilah sosiologi mencatat tampilnya teori-teori yang membela kaum buruh yang tertindas yang dipeloporioleh Karl Marx dan kawan-kawannya.
Demikian juga kalau kita ingin mencari bukti-bukti lain,misalnya pada abad pertengahan. Di abad ini tidak terjadiperubahan yang berarti di lapangan kemasyarakatan. Pada abadini gereja merupakan pendukung kebudayaan, merupakan tenagayang menyatukan dan menguasai masyarakat. Prinsip-prinsipkemasyarakatan dirumuskan oleh bapa-bapa gereja seperti SantoAgustinus dan dan Thomas van Aquinas sebagai pemuka-pemukanya.Dan sejarah mencatat dalam abad ini praktis tidak adaperhatian tentang masalah-masalah sosial atau dengan kata laindalam periode ini terjadi perubahan-perubahan yang sangatlambat di lapangan ilmu pengetahuan sosial.
Sebaliknya pada akhir abad pertengahan, terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam masyarakat. Tumbuhnyanasionalisme yang mendesak feodalisme, berkembangnyaperdagangan dan tumbuhnya borjuis yang kemudian menjadisemakin berpengaruh. Di dalam perode ini terjadi pertentanganyang memenuhi dunia dan pertengahan yakni pertentangan antararaja dan paus untuk saling berebut kekuasaan. Juga periode iniditandai tumbuh dan berkembangnya kota-kota dan mengalirnyapenduduk desa ke kota yang kemudian menghasilkan perubahan-
perubahan terhadap tradisi adat kebiasaan dan moral yangkemudian mulai menghilangnya yang mengikat masyarakat.Timbullah dari keadaan ini pemikiran-pemikiran yang reflektifdan diskusi-diskusi tentang apa yang disebut dengan problem-problem sosial. Abad inilah yang mungkin dikenal denganperiode Renaissance, dimana muncul kembali pemikiran-pemikiranYunani dan Romawi abad ke 4 sebelum masehi, yaitu periodePlato dan Aristoteles, ahli-ahli sejarah seperti Herodotus,Tucydides, Polybos, dan juga Cicero yang dalam ilmupengetahuan diklasifikasikan sebagai ahli teori kemasyarakatandari abad Hellenic.
Abad Hellenic ini, seperti halnya abad modern sekarang iniadalah suatu masa transisi yang mana terjadi disorganisasisosial yaitu ketika rejim Negara kota membuka jalan bagitumbuhnya suatu negara kekaisaran sesudah penaklukan Alexanderatas negara-negara Yunani.
Dari uraian terdahulu, kembali kita melihat hubungan antarakrisis dengan munculnya teori-teori sosial sebagaimanadinyatakan oleh Teori Krisis Pemikiran. Sehingga dapatlahdinyatakan pula bahwa suatu ilmu sosial sesungguhnya padasuatu waktu dan tempat tertentu, menggambarkan usaha parapemikir untuk dapat memahami keadaan masyarakat di mana merekahidup, terutama keadaan yang timbul dari keadaan yang berubahbaik untuk kepentingan para pemikir itu sendiri maupun untukkepentingan masyarakat.
RINGKASAN
Suatu teori yang baik dapat membantu kita untuk memahamifakta, menjelaskan, dan memberikan ramalan yang valid, hal inisangat perlu dalam suatu perencanaan untuk masa yang akandatang, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kitasendiri maupun yang berhubungan dengan perencanaankebujaksanaan umum.
Umumnya kekuatan suatu teori terletak pada kemampuannyauntuk membawa banyak pemikiran dan informasi mengenai satu
problem khusus atau seperangkat problem dan dengan demikianmelampaui pemikiran yang tidak sistematis dalam detail danketepatan untuk pembentukan kosep yang berikutnya. Teori yangdemikian itu bisa menghasilkan dan mengandung ide-ide yangsiap pakai pada suatu ketika.
Sebuah teori mencoba memecahkan sebuah problem teoritis kedalam empat kategori yaitu
1. Teori memungkinkan adanya ide-ide tambahan untuk pemecahanbeberapa problem teoritis yang ada.2. Teori memungkinkan adanya model-model dari buah pikiran dandengan demikian menghasilkan suatu deskripsi skematis. Deskripsiitu dapat dibayangkan sebagai suatu pola dan di dalam pola ituide-ide tersebut tersusun rapi dan serasi.3. Model-model memungkinkan adanya teori-teori.4. Teori memungkinkan adanya hipotesa-hipotesa.
Sosiologi adalah merupakan refleksi dari keadaan masyarakatyang sedang berubah dan teori-teori yang dihasilkannyamerupakan hasil dari keadaan masyarakat itu sendiri. Dankarena pada kenyataannya tiada satupun masyarakat yang tidakmengalami perubahan , maka sosiologi akan terus berkembang didalam masyarakat. Teori-teorinya akan terus berkembang dengansegala konsekuensinya, yang mungkin akan terlempar dariperedaran atau mungkin juga akan bertahan. Sementara itu pulaakan muncul teori-teori baru yang dihasilkan seiring denganperubahan kemasyarakatan yang terjadi.
LATIHAN
1. Jelaskan manfaat teori!2. Sebuah teori memecahkan problem toritis ke dalam 4 kategori,sebutkan dan jelaskan!
3. Para ahli ilmu sosial dan akademisi lainya kadang-kadangdituduh terlalu menjauhkan diri dari dunia nyata dan hidup dalammenara gading, apa maksudnya?4. Jelaskan latar belakang munculnya teori sosiologi dalammasyarakat!
TUGAS
Buatlah makalah sebagai tugas kelompok denganmengkaji secara sosiologis sebuah fenomena sosial yang ada dimasyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Johnson, D.P., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman. 1986.Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosilogi. Erlangga. Jakarta.
BAB II
FILSAFAT SOSIAL SEBAGAI DASAR TEORI SOSIAL
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Alam pikiran mengenai masyarakat sesungguhnya sama tuanyadengan alam pikiran ilmiah itu sendiri. Masyarakat selaludikenal dalam pengalaman dan masyarakat selalu menghadapkanmanusia pada persoalan-persoalan yang diikhtiarkan olehmanusia itu untuk menjawabnya. Karena dia selalu menghadapkanmanusia pada persoalan-persoalan dan masalah-masalah praktisinilah sebabnya masyarakat menjadi buah pikiran.
Dalam alam pemikiran mengenai masyarakat tercerminlahmasyarakat itu sendiri sebagai yang dialami, yang dalamperkembangannya melahirkan dua hal yaitu perkembangan darikenyataan sosial yaitu masyarakat itu sendiri dan perkembanganpemikiran ilmiah. Dan karena pengetahuan yang paling tuaadalah filsafat, maka di dalam filsafat itu pastilahdibicarakan tentang masyarakat. Dan karena filsafat lahir dialam pikiran Yunani maka yang pertama-tama perlu dibicarakanadalah alam pikiran Yunani.
Pokok bahasan yang akan diuraikan pada bab dua ini adalahlahirnya filsuf-filsuf yang terkenal di era Yunani yaituSocrates, Plato dan Aristoteles. Ke tiga tokoh yang menjadi‘sufi’ di zamannya ini, akan dibahas secara rinci mulai daririwayat hidupnya, metode berfikirnya hingga filsafat sosialyang dilahirkannya yang akan menjadi dasar bagi lahirnyateori-teori sosial selanjutnya khususnya teori-teorisosiologi.
Setelah mempelajari uraian pokok bahasan ini mahasiswadiharapkan mampu
1. Menjelaskan tentang riwayat hidup, metode berfikirdan filsafat sosial Socrates.
2. Menjelaskan tentang riwayat hidup, metode berfikirdan filsafat sosial Plato.
3. Menjelaskan tentang riwayat hidup, metode berfikirdan filsafat sosial Aristoteles.
4. Membandingkan metode berfikir dan filsafat sosialSocrates dengan Plato.
5. Membandingkan metode berfikir dan filsafat sosialAristoteles dengan Plato/Socrates.
A. SOCRATES
1. Riwayat Hidup
Sufi terbesar ini lahir kira-kira 470 SM, dan meninggal padatahun 399 SM. Dia berasal dari keluarga terpandang. Ayahnyaseorang seniman patung, dan banyak memberikan inspirasi padacara berpikir Socrates. Dia juga merupakan seorang prajuritpada angkatan perang Athena.
Pada suatu ketika, ia mendapat panggilan suci (devinecommision) untuk menunjukkan kearah mana kebenaran harusdikembangkan dan bagaimana menghilangkan kebodohan sesamawarga Negara Athena. Sebagai prajurit dalam perang Peloponesusdia pergi dari satu barak ke barak yang lain, dan kepadasetiap orang yang dijumpainya dia selalu menanyakan pendapanyamengenai masalah-masalah sosial dan politik. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya ia mengetahui bahwa iasesungguhnya tidak mengetahui apa-apa, seperti orang lainpuntadak mengetahui apa-apa pula. Oleh karena itu dia berpendapatbahwa yang diperlukan adalah sesuatu penyelidikan yang dapatdipercaya. Dengan penyelidikan itu dicarilah hakekat kehidupansosial politik yang kemudian melahirkan pemikiran filsafatnya.
Ketika pada suatu hari Oracle Delphy menyatakan bahwaSocrates adalah seorang yang paling bijaksana di Athena, makadia menjawab: “Hanya satu hal saja yang saya ketahui, ialahbahwa saya tidak tahu apa-apa”. Dari pernyataan inilahSocrates memberi dasar metode berpikir filsafatnya.
2. Metode Berfikir
Socrates adalah orang pertama yang menggunakan cara berpikiruntuk meragukan sesuatu dan mengutamakan pentingnya definisimengenai sesuatu. Ia berpendapat bahwa langkah pertama untukmendapatkan pengetahuan adalah dengan lebih dahulu menjelaskanidea-idea dan konsepsi-konsepsi. Definisi yang tepat mengenaiistilah-istilah dan konsepsi-konsepsi adalah paling sulit didalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Akan tetapi definisi inijustru harus difahami lebih dahulu untuk dapat menemukan
kebenaran. Secara singkat Socrates berpendapat bahwa definisiadalah merupakan langkah pertama di dalam ilmu pengetahuan.Dari sudut ini Socrates dapat disebut sebagai orang yangpertama menunjukkan perlunya logika sebagai dasar bagi ilmupengetahuan dan filsafat.
3. Filsafat Sosial
Kita mengenal pemikiran Socrates hanya melalui tulisan-tulisan Plato muridnya, dalam bentuk drama timbal cakap.Akan tetapi sesuatu yang tidak perlu diragukan sebagai ajaranSocrates adalah pernyataan bahwa ‘kecerdasan adalah merupakandasar dari semua keutamaan’, di dalam adat kebiasaan, di dalamlembaga-lembaga sosial dan di dalam hubungan sosial manusiamaupun di dalam kehidupan pribadi. Menurut Socrates tabiatyang baik adalah sinonim dari kecerdasan, pengetahuanmenjadikan seseorang bijaksana.
Seseorang yang adil misalnya, harus mengetahui hukum dengansebaik-baiknya. Akan tetapi, Socrates menyatakan bahwadisamping hukum-hukum manusia terdapat juga hukum Tuhan; dankeadaan adalah kebijakan yang mengalir dari pengetahuantentang hukum Tuhan. Socrates mengajarkan bahwa kebajikandalah sesuatu yang dapat dicapai dengan kecerdasan manusia.Apabila kita hendak membangun masyarakat dengan berhasil, makakita harus membangun dengan landasan ilmu pengetahuan.
Kritik yang pertama terhadap pemikiran Socrates adalah bahwaia terlalu intelektualistik. Kenyataannya, orang-orang cerdikpandai, sekalipun mereka banyak mengetahui kebenaran akantetapi mereka banyak pula melakukan kesalahan. Tentang hal iniSocrates menjawab, bahwa mereka memang tidak akan dapatmengetahui benar bagimana mereka dapat mencapainya. Akantetapi bilamana suatu pengetahuan dilaksanakan, orang tidakakan melakukan kesalahan yang lebih jauh.
B. PLATO
1. Riwayat Hidup
Plato dilahirkan kira-kira 427 SM. Dan meninggal pada tahun347 SM. Ia berasal dari keluarga bangsawan Athena yang sangatmemuliakan kaumnya.
Sesudah Socrates meninggal, Plato merantau ke berbagainegeri seperti Mesir, Asia, Sisilia dan Italia bagian selatan,dimana dia kemudian berkenalan dengan pemikiran Phythagoras.Pada tahun 387 SM, ia kembali ke Athena dan mendirikan suatusekolah yang terkenal dengan nama ‘Academia’ yang karena banyakmenarik pemuda-pemuda terpelajar Yunani, dapat disebut sebagaiUniversitas pertama di Eropa
Terdapat tiga buah bukunya yang paling terkenal yaitu :
1. The Republic.
The Republic merupakan usaha pertamanya yang besar untukmenggambarkan suatu masyarakat ideal di mana keadilan dapatdiwujudkan.
2. The Laws yang merupakan buku yang membuat garis besarkonstitusi sosial politik.
3. The Statesman (Negarawan) yang membuat suatu diskusitentang konstitusi politik.
2. Metode Berfikir
Dia mengembangkan metoda dialektika Socrates, denganmemulainya dan menguji konsep-konsep pikiran. Kita dapatmengenal ‘manusia’ misalnya, melalui cara mengenal pengertianumum tentang manusia, inilah yang disebut dengan ‘Platonicidealism’, yang sebagai suatu metoda berpikir biasa disebut‘Conseptualism’, suatu doktrin yang mengajarkan bahwa kebenaran
harus diperoleh dengan menguji atau membuktikan konsep-konsep.Metoda berpikir Plato ini (dan juga Socrates), bertolakbelakang dengan metoda yang dipergunakan oleh ilmu-ilmupengetahuan modern. Plato berpendapat bahwa kebenaranuniversal tidak dapat dicapai melalui pengertian-pengertiantentang gejala-gejala yang nampak.
Plato adalah pencipta ajaran ‘serbacita’ (ideenleer), karenaitu filsafatnya disebut ‘idealisme’. Diapun beranggapan bahwapengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan atas gejala-gejala yang nampak, adalah bersifat relatif. Kebajikan tidakmungkin ada tanpa memiliki pengetahuan dan pengetahuan tidakdapat hanya terbatas pada pengamatan saja. Sebab pengetahuanitu dilahirkan oleh ‘alam bukan benda’, melainkan alamsebacita. Contohnya cita atau konsep tentang kuda yangmemiliki semua sifat kuda dalam bentuk yang murni, tidak dapatdiamati di dunia ini. Kuda kita lihat berbeda satu sama laindalam bentuk, warna, dan sifatnya. Kuda dalam bentuk yangmurni dan sempurna ada di idealisme pikiran manusia, sedangkandalam kenyataannya kuda dikenali dalam keadaan yang kurangsempurna di dunia ini.
Jadi serbacita itu adalah pengertian-pengertian yang sudahada pada saat manusia lahir. Mencari pengetahuan berartimenimbulkan kembali ingatan-ingatan dan tata tertib darikerinduan jiwa kita akan dunia sebacita, dimana jiwa kitadahulu berada.
3. Filsafat Sosial
The Republic sebenarnya bernilai sebagai tulisan tentang etikasosial, mengenai masyarakat ideal, The Republic itu sebagaitulisan pertama dan terbesar yang bersifat sosiologis. Platomenganggap bahwa masyarakat ideal adalah merupakan perluasandari konsep tentang individu manusia.
Menurut Plato manusia pada dasarnya memiliki tiga sifattingkatan kegiatan yaitu
a. The Appetites or the senses (nafsu atau perasaan-perasaan)b. The Spirit or the will (semangat atau kehendak-kehendak)c. Inteligence, reason, and judgment (kecedasan atau akal)
Berdasarkan tiga elemen aktivita individu tresebut platokemudian menyusun suatu masyarakat ideal di dalam tiga lapisanatau kelas yaitu :
a. Mereka yang mengabdikan hidupnya untuk memperolehpemuasan nafsu dan perasaannya.
b. Mereka yang mengabdikan hidupnya untuk memperolehpenghormatan dan perbedaan sebagai manifestasidari pada spirit or will
c. Mereka yang mempersembahkan hidupnya untukpemeliharaan akal atau kecerdasan untuk mengajarkebenaran.
Berdasarkan tiga lapisan sosial Plato kemudian merumuskantiga kegiatan lapisan sosial. Ketiga aktivita lapisan sosialitu adalah :
1. Mereka yang mengabdikan hidupnya bagi pemenuhannafsu dan perasaan, bertugas untuk menghidupi ataumemelihara masyarakat. Mereka ini adalah kelaspekerja (manual work), yang meliputi pekerja-pekerja di sektor pertanian dan industri yangharus mendukung dan menghidupi dua kelas yanglain. Kepada kelas inilah didalam masyarakat idealPlato, diberi hak-hak yang penuh dan istimewasebagai seorang warga negara yang diperolehkanmemiliki kekayaan pribadi, oleh karena berfungsimenyediakan atau memprodusir barang-barangkebutuhan hidup seluruh anggota masyarakat.
2. Mereka yang hidupnya diabdikan untuk memperolehpenghormatan dan perbedaan sebagai manifestasidari spirit or the will bertugas untuk melindungimasyarakat dari serangan yang datang dari luarmaupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Merekaini adalah kelas militer (a citizen soldier class).
Mereka inilah warga negara dalam pengertian yangsesungguhnya. Mereka adalah gambaran darimasyarakat komunis yang sempurna dan tidakmemiliki kehidupan yang bebas dan ganjaran merekasatu-satunya adalah penghormatan yang diberikanmasyarakat dan kemenangan-kemenangan perang.
3. Mereka yang mempersembahkan hidupnya untukmemelihara akal atau kecerdasan bertugas untukmemerintah dan memimpin masyarakat disebut sebagaikelas penguasa (magistrates or guardian class). Kelasini terutama diangkat dari kelas militer melaluiseleksi dalam kemampuan dan kecerdasan otaknya.Mereka tidak hanya menjadi filosof dan negarawan,tetapi lebih dari itu juga seorang guru.
Meskipun Plato membagi masyarakat ke dalam 3 kelas sosial,tetapi tidak berarti bahwa pembagian tersebut merupakanlapisan yang tertutup setiap orang mempunyai kesempatan yangsama di dalam masyarakat.Plato menghendaki masyarakat yangideal itu yakni aristokratis di bawah kaum intelek di manakekuasaan dan pengawasan akan dipegang oleh kelas yangberpendidikan dan berkecerdasan tinggi.
Yang terpenting bagi studi sosiologi dalam buku Plato TheRepublic adalah konsepsinya tentang keadilan (justice). Hanya didalam masyarakat tertentu, Kata Plato, keadilan dapatdirealisir. Orang yang adil hanya dapat ada di dalammasyarakat adil. Dengan demikian konsepsi Plato tentangkeadilan adalah merupakan konsepsi sosial.
Dalam bukunya ’The Laws’ Plato hanya memuat garis besarkonstitusi politik. Di dalam buku ini tahap perkembangansosial. Plato mengemukakan perkembangan masyarakat melaluilima tahap yaitu :
a. Tahap kehidupan masyarakat yang terisolir di dalammasyarakat pemburu dan yang hidup di padang-padangrumput.
b. Masyarakat yang Patriarchal di mana keluarga-keluarga tersusun ke dalam ikatan-ikatan klan dan
suku-suku, tetapi masyarakat ini masih hidup dipadang-padang sebagai masyarakat pemburu danpenggembala.
c. Masyarakat petani yang sudah mulai mendiami desa-desa pertanian
d. Masyarakat yang hidup di kota-kota perdagangane. Masyarakat yang hidup di kota yang mapan seperti
Sparta atau Athena
Plato adalah pencipta pertama dari pada ide tentangkomunisme, dia hanya membatasi komunismenya pada dua lapisanatas dalam masyarakat. Menurut pendapatnya terdapat banyakpersamaan antara ide komunisme Plato dengan komunisme Rusia,yaitu :
a. Keduanya membenci perdagangan dan ekonomi uangb. Keduanya menaruh perhatian pada persoalan hak
milik sebagai satu-satunya sumber semua kejahatandan kebusukan
c. Keduanya menghendaki hapusnya kemakmuran dan hakmilik perseorangan
d. Keduanya menghendaki pengawasan kolektif bagianak-anak
e. Keduanya menghendaki pengawasan semua ilmupengetahuan dan ideologi bagi kepentingan negara
f. Keduanya memiliki ajaran dogmatis yang menghendakiagama negara terhadap mana semua aktivitas harusdi-subordinasikan kepadanya.
Plato adalah pencipta pertama tentang kesamaan sosial yangmutlak antara wanita dan laki-laki, dan perlunya pengawasanterhadap perkawinan. Disamping itu Plato adalah orang pertamayang menghargai ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Iamenunjukkan bahwa tidak saja perlu adanya leadership yang cakaptetapi ia menunjukkan pula keuntungan sosial dari padapemerintah oleh orang-orang bijaksana (para cendekiawan).Fasisme modern barang kali merupakan suatu bentuk modernberdasarkan konsep plato. Hanya saja berbeda dari komunismeRusia Plato sebaliknya mengatakan bahwa setiap masyarakat
harus selalu terdapat susunan-susunan kelas yang bersifatnatural.
Plato menekankan adanya perbedaan-perbedaan antara individu-individu dan kelas-kelas sosial ciptaannya terlampau kaku.Perbedaan antara kelas-kelas tersebut lebih bersifat gradualdari pada bersifat kualitatif.
C. ARISTOTELES
1. Riwayat Hidup
Filsuf ini dilahirkan pada tahun 384 SM, di Stagira, danmeninggal pada tahun 332 SM, pada usia 62 tahun. Ibu Aristotelesadalah seorang ahli kesehatan dari Raja Amyntas II, dan ayahnyajuga seorang ahli kesehatan, penjinak binatang, dan pecinta alamyang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran Aristoteles yangbersifat naturalistik.
Setelah kematian ayahnya, Aristoteles pergi ke Athena pada usia18 tahun untuk belajar di academy dibawah asuhan Plato. Platomengakui bahwa Aristoteles adalah muridnya yang paling brilliant,karena ia mampu mengembangkan pikirannya sendiri. Pada kematianPlato, Aristoteles memiliki hak terbesar untuk memimpin Academia,sekalipun demikian pimpinan jatuh ketangan kemenakanPlato. Aristoteles merasa perlu untuk meninggalkan Athena, iaakhirnya mengungsi ke istana Hermias. Di sini ia berdiam selamatiga tahun, kemudian ia menikahi anak angkat Hermias yang cantik,bernama Pythias.
Tahun 342 SM Aristoteles dipanggil ke istana raja Philip II dariMecodonia untuk menjadi guru dari puteranya Alexander yang masihberusia 13 tahun. Sesuia dengan ide-ide pendidikannya sendiri,
Aristoteles tidak mendidik Alexander sebagai murid privat,melainkan mendidiknya dalam satu sekolah bagi anak bangsawanMecedonia. Setelah Alexander diangkat menjadi raja, Alexandermemberikan bantuan kepada Aristoteles untuk membeli buku-bukuguna mendirikan suatu perpustakaan dan sebuah museum sertamengumpulkan informasi-informasi ilmiah. Itulah sebabnyaAristoteles dapat mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagainegara kota di jamannya. Hal itu pula yang menyebabkan dia mampumelakukan studi induktif yang luas berbagai masyarakat Yunani dannon Yunani.
Pada usianya yang ke 50 tahun Aristoteles kembali lagi ke Athenadengan membawa serta perpustakaan dan museumnya. Kemudiandipanggil ke istana raja Philip II dari Mecodonia untuk menjadiguru dari puteranya Alexander Banyak diantara tulisan aristotelesmerupakan catatan muridnya, cara yang demikian merupakan dasaryang baik bagi pembentukan pemikiran, karena muridnya merupakankumpulan ingatan yang hidup. Kemudian Aristoteles menyingkir keCalcis sampai ia meninggal. Pikiran Aristoteles bersifatensiklopedis, adalah merupakan pembangunan banyak ilmupengetahuan dan disiplin filsafat.
2. Metode Berfikir
Aristoteles berbicara tentang filsafat dan dunia realita.Pemikiran Aristoteles adalah objektif dan dan realitas, teorinyadibangun berlandaskan fakta-fakta, ia menemukan sember kebenaranpada pengalaman. Aristoteles merupakan orang pertama yangmenggunakan metoda historis dalam mempelajari kenyataan sosial.Dia adalah pembangun logika, yaitu suatu ilmu tentang caraberpikir yang benar, ilmu pengetahuan menurutnya adalah bangunanpengetahuan yang masuk akal. Jelaslah bahwa Aristoteles tidakpernah memimpikan untuk memisahkan penyelidikannya tentang ‘apayang ada’ dan ‘apa yang seharusnya ada’.
3. Filsafat Sosial
a. Ajaran Tentang Asal mula Masyarakat
Ada dua bentuk asosiasi manusia yang bersifat dasar danessensial, yaitu asosiasi antara laki-laki dan wanita untukmendapatkan keturunan, dan asosiasi antara penguasa dan yangdikuasai. Kedua asosiasi ini bersifat naturalistic (tidakdisengaja). Negara berasal dari perkumpulan kampung/dusun,sedangkan dusun berasal dari kumpulan keluarga yang terbentuksecara alamiah. Ciri-ciri negara : merdeka penuh (full independent),memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficiency) dan memilikipemerintahan sendiri (self government). Negara adalah suatu ‘naturalgroup’, dan manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon).Masyarakat manusia memiliki dasar kultur dan dasarnya yangalamiah.
b. Ajaran Tentang Organisasi Sosial
Aristoteles membagi ilmu tentang keluarga kedalam empat bagian :
1. Tentang hubungan antara tuan dengan budaknya.
2. Tentang hubungan antara suami dengan istri.
3. Tentang hubungan antara orangtua dengan anaknya.
4. Tentang ilmu atau seni keuangan.
c. Ajaran Tentang Organisasi Politik
Aristoteles mengemukakan pembagian fungsi pemerintahan kedalamfungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif, dengan maksud agarterdapat pengawasan satu sama lain. Ada enam bentuk fundamentaldaripada negara, yaitu : pemerintahan oleh seseorang disebut‘Monarki’ apabila baik dan ‘Tyrani’ apabila buruk. Pemerintahanoleh sejumlah orang disebut ‘Aristokrasi’ apabila baik dan
‘Oligarkhi’ apabila buruk, pemerintahan oleh banyak orang disebut‘Demokrasi’ dalam bentuk baik maupun korup.
d. Ajaran Tentang Sosial Development
Aristoteles mengemukakan bahwa monarki adalah merupakan bentukpemerintahan yang paling tua dan primitif, yang bersumberlangsung dari kekuasaan laki-laki dalam keluarga patriarchal.Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh kaumbangsawan yang memerintah untuk orang banyak. Dalam pikiranAristoteles sebab-sebab daripada revolusi adalah bersifatpsikologis dan karenanya dapat dicegah.
e. Ajaran Tentang Etika Sosial
Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah suatu asosiasi yangtidak semata-mata bertujuan untuk menyelenggarakan perlindunganbersama atau mengusahakan kemakmuran komersial. Ada tigakesejahteraan atau kehidupan individu yang bahagia menurutAristoteles, yaitu :
5. External goods, or wealth (kekayaan).
6. Good of the body, or health (kesejahteraan).
7. Goods of the soul, or intelligence and character (kecerdasan ataukarakter).
Sistem sosial yang baik menurut Aristoteles adalah suatu sistemdimana setiap orang dapat berbuat sebaik-baiknya dan hidupbahagia. Dengan demikian idealisme Aristoteles tentang masyarakatadalah merupakan idealisme seimbang antara kemakmuran material,kesehatan fisik, kecerdasan yang tersebar, dan karakter yangmerata.
f. Ajaran Tentang Social Progress
Aristoteles memiliki pengajaran tentang perbaikan sosial, yaituajaran tentang bagaimana membangun atau memelihara suatumasyarakat yang ideal yaitu melalui pendidikan.Ada tiga jalanyang dapat membuat manusia menjadi baik dan bijaksana, yaitu :Alam, habit dan akal atau pikiran.
Pendidikan mengandung dua hal, yaitu : ‘habituasi’ atau apa yangdisebut dengan latihan membiasakan diri, dan pendidikan kekuatan-kekuatan rasional, yakni akal atau pikiran. Yang harusdiperhatikan di dalam setiap pendidikan adalah meningkatkankarakter atau moral warga negara, karena karakter yang lebihtinggi akan menghasilkan tertib sosial yang tinggi pula.
RINGKASAN
Socrates, Plato dan Aristoteles adalah pemikir-pemikir sosialyang muncul di zamannya yaitu di abad Yunani. Sebagai ‘sufi’bagi masyarakat Yunani ketika terjadi krisis besardimasyarakatnya itu, dimana kebenaran dan keadilan sulitdidapat, yang ada hanya ketidakpastian. Khususnya krisis terbesarketika negara kecil Sparta mengalahkan Athena yang begitu kuatsehingga membuat shock masyarakatnya. Persoalan yang dialamimasyarakat Yunani yang serba dalam ketidakjelasan danketidakpastian akhirnya melahirkan filsafat sosial dari Socratesbahwa’ kecerdasan sumber keutamaan’. Dengan kecerdasan atau ilmupengetahuan maka kebajikan akan tercapai sehingga membangunmasyarakat pun akan berhasil baik. Metode berfikir dan filsafatsosial Socrates selanjutnya dikembangkan oleh muridnya yaituPlato yang terkenal dengan ajaran ‘idealismenya’. Denganmenguraikan sketsa masyarakat idealnya yang merupakanpengembangan sifat-sifat manusia dalam buku ‘The Republic’nya.Plato adalah pencipta pertama ide tentang komunisme. Aristotelessebagai murid Plato ternyata mampu mengembangkan arah pikirannyasendiri berbeda dengan gurunya. Dengan membangun teori di atas
landasan fakta-fakta meskipun masih spekulatif, serta metodeberfikir induktif berbeda dengan teori Plato/Socrates yangdibangun berdasarkan dunia idea saja serta bersifat deduktif.Filsafat sosial Aristoteles yang terkenal adalah bahwa manusiamenurut kodratnya adalah mahluk sosial (man is naturally a politicalanimal) atau “Zoon politicon”. Oleh karena itu, Aristoteles dipandang sebagai pelopor dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial.Meskipun demikian, baik Aristoteles maupun Plato dan Socratessebagai filsuf besar yang namanya menembus zaman sekalipun, tetapjuga tidak luput dari berbagai kesalahan sebagaimana lazimnyakehidupan dunia ilmu pengetahuan.
LATIHAN
1. Jelaskan kritik sosial yang diberikan pada filsafat sosialSocrates!
2. Jelaskan perbedaan metode berfikir antara Plato denganAristoteles !
3. Coba jelaskan kembali menurut anda tentang “zoon politicon“yang dikemukakan oleh Aristoteles !
4. Jelaskan 6 persamaan antara ide komunisme Plato dengankomunisme Rusia!
5. Mengapa sekolah yang didirikan oleh Aristoteles lebihdikenal dengan nama Parepatetic school !
TUGAS
Buatlah makalah yang berisikan rangkuman kritik-kritik yangdiberikan oleh para ahli terhadap metode berfikir maupun filsafat
sosial dari Socrates, Plato dan Aristoteles, berdasarkan sumberrujukan yang diberikan dan yang anda ketahui. Selanjutnya akandidiskusikan di kelas!
DAFTAR PUSTAKA
Bouman, P.J., 1956. Ilmu Masyarakat Umum. Terjemahan Sujono. Cetakanke delapan. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan danMetode. Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakrta.
Johnson, D.P., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman. 1986.Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosilogi. Erlangga. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Radjawali.Jakarta
.-----------------------, 1985. Pengantar Konsep dan TeoriSosiologis. Unila Press. Lampung
BAB III
PERIODE TRANSISI DARI PEMIKIRAN FILSAFAT KE PEMIKIRAN ILMUPENGETAHUAN
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Pokok bahasan pada bab ini menguraikan pemikiran sosial paratokoh masa transisi dari periode filsafat ke ilmu pengetahuanyang ditandai besarnya kekuasaan gereja dalam kehidupankemasyarakatan dengan salah satu pelopornya adalah Thomas vanAquinas. Bab ini juga menguraikan pemikiran para tokoh sosialmasa revolusi industri dan Renaissance dengan tokohnya F. Bacon,Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Lock dan Vico.
Setelah mempelajari uraian pokok bahasan tadi, mahasiswadiharapkan mampu :
1. menjelaskan pemikiran sosial tokoh masa transisi abadpertengahan yang dikenal dengan sebutan abad Scholastik yang salahsatu tokohnya yaitu Thomas Van Aquinas.2. menjelaskan pemikiran sosial tokoh-tokoh masa revolusiindustri dan Renaissance yaitu F. Bacon, N. Machiavelli, ThomasHobbes, J.Locke dan Vico.
A. Campur Tangan Lembaga Agama dalam Urusan Pemerintahan
Dalam perkembangan teori-teori selanjutnya periode akhir Yunanitidak begitu besar peranannya dalam pemikiran teori sosial,dibandingkan dengan periode abad pertengahan atau apa yangdikenal dengan abad Scholastik.
Pada abad Scholastik pertumbuhan sosial terasa tersendat-sendatkarena besarnya kekuasaan gereja dalam kehidupan kemasyarakatan.Abad ini adalah suatu abad di mana agama kristen berkembangpesat, di mana bapak-bapak gereja tidak saja di lapangankebudayaan, melainkan juga di lapangan politik. Bahkan di sebutabad Scholastik adalah karena pemikiran filsafat pada masa itumenyusun ajaran gereja dalam suatu sistem ilmiah. PengaruhAristoteles sangat besar dalam periode ini, terutama padapemikiran tokoh Sholastik, Thomas Van Aquinas.
Thomas Van Aquinas
a. Riwayat Hidup
Thomas Van Aquinas dilahirkan di daerah Napoli pada tahun 1225.Dia berasal dari keturunan bangsawan dan mengenyam pendidikan diuniversitas Napoli. Aquinas belajar filsafat di University of Cologne,kemudian pada tahun 1245 Ia melanjutkan pendidikannya di Universityof Paris. Seusai studi, Aquinas kemudian menjadi maha guru diuniversitas tersebut. Aquinas memperoleh gelar kehormatan dengansebutan ‘Doctor Angelicus’ oleh mahasiswanya. Di antara tulisan-tulisannya yang paling terkenal yaitu ‘a Commentary on Aristotle’ danjuga ‘Summa Theologica’. Aquinas meninggal pada tahun 1247.
b. Metode Berpikir
Aquinas membedakan dua sumber kebenaran yaitu “Wahyu” dan “Akal”.Dengan wahyu dimaksudkan adalah yang bersumber dari Al-Kitab dantradisis-tradisi Gereja. Metode berpikirnya menunjukkan bagaimanadia berusaha untuk menyelaraskan kedua sumber pengetahuantersebut, sekalipun dia lebih menitik beratkan kepada sumberwahyu. Menggunakan akal pikiran secara benar danmenginterpretasikan ajaran Aristoteles secara benar, akan membawakepada kesimpulan yang sama sebagai mana diberikan oleh wahyusebagai sumber pengetahuan, kata Aquinas.
c. Filsafat Sosial Aquinas
Asal mula negara karena adanya kebutuhan sosial. Aquinasmenambahkan bahwa wewenang (authority) negara, tidak hanyabersifat natural, tetapi juga bersumber dari Tuhan.
Hukum menurut Aquinas dibagi dalam 4 bagian, yakni:
1. Eternal Law (hukum abadi)
adalah hukum yang keseluruhannya berakar dalam jiwaTuhan.
2. Natural Law (hukum alam)
sekedar manusia sebagai makhluk yang berpikir yangmenjadi bagian daripadanya.
3. Human Law (hukum manusia atau hukum positif)
merupakan pelaksanaan dari hukum alam berhubung dengansyarat-syarat khusus
yang diperlukan oleh keadaan di dunia.
4. Divine Law (hukum Tuhan)
mengisi kekurangan-kekurangan dari pikiran manusia danmembimbing dengan
wahyu-wahyu Nya kearah alam baka, dengan cara yang takmungkin salah.
Wahyu merupakan sumber utama dari hukum ini dan tugasgereja untuk
menginterprestasikan wahyu ini. Keadilan merupakanpenerapan teologi.
B. Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Perkembangan PemikiranSosial
Abad pertengahan sekalipun mendapat perhatian besar secarahistoris dan sosiologis, tetapi tidak memiliki hasil pikiran yangorisinil. Abad yang kemudian menjelang sesudah abad pertengahanini adalah abad rasional serta empiris yang percaya pada kemajuandan kekuasaan akal. Yang kemudian menjadi abad yang meletakkandasar ke arah nasib ilmu pengetahuan selanjutnya Abad ini adalahabad Aufklarungyang berkembang di Ingris dan Perancis akhir abadke 18 dengan tokoh-tokoh diantaranya F. Bacon, N.Machiavelli,Thomas Hobbes, John Locke dan Giambattista Vico.
1. Francis Bacon
Empirisme yang menjadi metode berfikir utama di dalam awalpertumbuhan modern di abad Renaissance sebenarnya bermula ditanah Inggris. Negara ini terkenal sebagai pemula pemikiran baruitu melalui tokoh yang bernama Francis Bacon (1561-1628), seorangpemikir yang gelisah. Tokoh ini berasal dari Verulam. Ungkapanyang sangat terkenal dari orang ini adalah bahwa bagi dia, tujuanilmu pengetahuan adalah untuk menguasai alam, pengetahuan adalahkekuasaan, katanya kita dapat menguasai alam jika kita mengetahuiundang-undang yang mengatur perkembangan alam. Dan usaha inihanya bisa berhasil melalui pengamatan-pengamatan yangsistematis. Metode berfikir yamg paling tepat untuk pengamatanini adalah melalui metode berfikir induktif.
2. Niccolo Machiavelli
Machiavelli dilahirkan di Florence pada tahun 1469 dan wafattahun 1527. Machiavelli adalah seorang realis yang menganjurkanpolitik kekuasaan praktis dengan tidak memakai dasar-dasarkesusilaaan atau alam metafisika. Machiavelli dapat disebutsebagai wakil dari paham baru yaitu paham Negara kebangsaan, danpemahaman pemisahan gereja dengan Negara, di mana di dalam pahamini terjelma suatu kecondongan alam pikiran yang hendakmemisahkan antara alam rohaniah dengan alam pikiran duniawi.Dalam tulisan yang terkenal “The Prince” Machiavelli mengatakanbahwa negara, setelah bebas dari kekuasaan gereja, hendaklahberakar pada rakyat bangsa, pada kesadaran kebangsaan.
Menurut Machiavelli tujuan dari Negara adalah untuk memperolehkekuasaan, tidak perduli bagaimana caranya dapat memperolehkekuasaan tersebur, apakah akan melanggar moral atau tidak.Politik tidak perlu dihubungkan dengan moral.
Machiavelli mengemukakan 5 cara bagi negara untuk memperbesarkekuasaan :
1. Meningkatkan jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk adalahmerupakan
sumber kekuasaan. Untuk meningkatkan jumlah penduduk dapatdilakukan melalui
peningkatan kelahiran.
2. Memperluas perdagangan dan komersialisasi.
3. Mengadakan perjanjian atau persekuutuan yang menguntungkandengan negara lain.
4. Membangun tentara yang kuat (termasuk tentara sewaaan)
5. Diplomasi. Menurut Machiavelli Negara harus pandai melalukandiplomasi. Sebab
suatu diplomasi apabila dilakukan secara berhasil, akanmerupakan kekuatan yang
lebih besar dari kekuatuan tentara.
Dengan metode yang diajarkan oleh Machiavelli ini, maka dia dapatdisebut sebagai bapak dari militerisme modern, dan merupakanorang yang pertama kali sekali mengajarkan pentingnya suatuekspansi politik perdagangan dan politik imperialismeperdagangan. Dan lebih dari semua itu, Machiavellli adalahperumus dari politik amoral, terutama dalam usaha memperolehkekuasaan. Sebab menurutnya, barang siapa mempunyai kekuasaanakan mempunyai hukum dan barang siapa yang tidak mempunyaikekuasaan dia tidak akan pernah mempunyai hukum.
3. Thomas Hobbes
a. Riwayat Hidup
Lahir pada tahun 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Ia merupakananak seorang pendeta gereja Inggris yang mendapat pendidikan dariperguruan Magdalena dan kemudian di Oxford, kemudian menjadiseorang Kepala Sekolah Gereja.
b. Metode Berpikir
Metode berpikir yang dikembangkan oleh Hobbes sebenarnya terbataspada prinsip-prinsip hukum alam dan matematika. Cara berpikirsarjana ini adalah bersifat materialistic dan mekanistik.Teorinya yang bersifat egoistic itu terkenal denganungkapan “Belium Omnium Comtra Omnes” artinya ; perang antara semuamelawan semua. Manusia menurut Hobbes pada dasarnya hidup dalamkeadaan soliter, miskin, jahat brutal dan keji.
Tiga faktor yang mengakibatkan terjadinya pergulatan yang terus-menerus antara manusia, yaitu:
1. Persaingan diantara manusia untuk memuaskan nafsu-nafsunya.2. Ketakutan dari tiap orang terhadap orang lain3. Kerinduan manusia yang bersifat alamiah untuk memperolehpujian serta rasa kekaguman sebagai makhluk yang lebih superiordibandingkan dengan makhluk yang lain, atau kecintaan manusiauntuk memperoleh keagungan.
Demikianlah, Hobbes menganggap egoisme manusialah yang mendorongmanusia untuk mempertahankan serta memperbaiki hidupnya.
c. Filsafat Sosial Hobbes
Masyarakat menurut Hobbes terbentuk dari adanya perjanjiandiantara menusia, sedangkan negara terbentuk diatas perjanjiandiantara kekuasaan dan ketaatan. Manusia menyerahkan segenapkekuasaan dan hak nya kepada negara dan negara kemudianmenjadi Leviathan yang berkuasa mutlak, dan tidak dapat di bagi-bagi kepada seseorang atau kepada suatu perwakilan. Kekuasaanharuslah ditangan satu orang, dan kekuasaannya meliputi seluruhlapangan hidup.
Hobbes adalah orang pertama yang menganjurkan sesuatu sistempemerintahan negara yang totaliter. Apabila negara bersifatmonarki, maka kekuasaan raja adalah bersifat suci, sedangkan bilakedaulatan negara tersebut bersifat demokrasi, maka suara rakyatadalah suara Tuhan.
Hobbes memandang bahwa kehidupan sosial dan kehidupan politikbersifat statis dan tidak memperhitungkan faktor histories, sertatidak memiliki ajaran tentang perkembangan dan kemajuan sosial.Di atas semua itu, Hobbes tidak memberi tempat mengenaipentingnya etika dalam pemikirannya tentang kehidupan politik dankehidupan masyarakat, padahal ajaran tentang etika merupakan idedasar dari ilmu pengetahuan sosial.
4. Giambattista Vico
a. Riwayat Hidup
Dilahirkan tahun 1668 dan meninggal tahun 1744. Ia berasal darikeluarga sangat miskin di Napoli. Teorinya yang sangat terkenalyakni mengenai perkembangan masyarakat. Vico menulis bukuberjudul “The Principle of A New Science” pada tahun 1725, sebuah buku
tentang filsafat sejarah dan memuat teori tentang perkembangansosial.
b. Filsafat Sosial
Vico memandang manusia sebagai makhluk sosial. Ia jugamenyetujui pendapat bahwa rasa takut yang melingkupi dirimanusialah yang kemudian melahirkan agama, kemudian agamamelahirkan kebajikan serta ajaran-ajaran moral.
Teorinya mengatakan bahwa sejarah perkembangan umat manusia padadasarnya adalah sama, dari masa lalu maupun masa yang kemudian.Perkembangan sosial itu dimulai dari keadaan manusia yangbersifat biadab menuju kepada keadaan manusia yang menganut agamakemudian perkembangan manusia yang menganut ajaran-ajaran moral,lalu masyarakat yang memiliki hukum, masyarakat bernegara, lalumasyarakat menjadi terorganisir
c. Ajaran Perkembangan Sosial
Ada tiga tahap perkembangan sosial/kemasyarakatan, yaitu :
1. The age of gods
Masa ini adalah suatu masa didalam kehidupan sosial yang mulaimengenal tentang Tuhan atau berbagai Tuhan. Rasa takutmenciptakan suatu dunia mengenai adanya Tuhan. Masa ini disebutsebagai masa mitologis. Bentuk pemerintahan didalam masa iniadalah Theokratis. Vico berusaha untuk menunjukkan bahwa bentukpemerintahan yang mula-mula sekali adalah pemerintahan yangdidominasi oleh kelas rohaniawan, karena itu bersifat theokratis.
2. The age of heros, or of demigods, or of great men apotheosized
Masa ini ditandai oleh berkembangnya kepala-kepala keluarga yangbersifat patrialchal menjadi pemimpin atau penguasa masyarakat.Abad kepahlawanan ini adalah abad dimana sisa-sisa kebiadabanmanusia masih terasa. Kepala keluarga tersebut kemudian bersama-sama membentuk pemerintahan di dalam masyarakat yang lebih luas.Bentuk pemerintahan ini bersifat aristokratis.
Tahap kedua ini juga ditandai oleh perkembangan perbudakan ,sekalipun didalam masa ini ada juga budak yang mampu membebaskandiri dan mempertahankan hak-hak mereka didalam pertarungan antarakaum bangsawan dan rakyat jelata.
3. the age of men
Masa ini adalah masa dimana manusia sudah mulai menemukandirinya. Bahasa juga sudah mulai berkembang ke dalam wujudtulisan. Hak-hak sipil dan politik mulai diperluas, bentukpemerintahannya demokrasi dan monarki. Agama juga mulaimemanusiawi dan tujuannya diarahkan kepada pengembangan moral.Vico menyebut masa ini sebagai masa pemerintahan bebas ataupemerintahan Republik. Selanjutnya Vico menambahkan bahwa masaini mengandung pula benih-benih keruntuhan. Agama telahdipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat skeptis. Masyarakattelah dikorupsi oleh kemewahan sehingga muncul pertentanganantara golongan kaya dan golongan miskin. Sementara itupemerintahan telah menjurus menjadi korup. Keadaan yang demikianini akan ditaklukkan oleh dua kekuatan, yaitu musuh yang datangdari luar atau tenggelam kedalam bentuknya yang barbar.
5. John Locke
a. Riwayat Hidup
Dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal tahun 1704. Iamemperoleh pendidikan di Gereja Kristen, Oxford, dan pernahmenjadi anggota Gereja Inggris pada masa restorasi. Locke seorangpenganut aliran Liberal di dalam bidang politik dan agama.Seorang yang sangat mempertahankan kebebasan individual. Padadasarnya ia adalah seorang pemikir metafisis. Dia sangat menaruhperhatian yang sangat besar terhadap masalah-masalah filsafatyang meliputi teori-teori ilmu pengetahuan, sebagai mana terbuktidari tulisannya yang terkenal “Essay Concerning Human Understanding”.
b. Filsafat Sosial Locke
Locke dapat dipandang sebagai salah satu pemuka di dalammenggunakan metode psikologi didalam ilmu sosial. Dasar ajaranfilsafat sosial mengemukakan bahwa semua pengetahuan manusiadiperoleh melalui pengamatan serta pemahaman terhadap kenyataan-kenyataan. Secara umum Locke menganut metode berfikir induktif,sekalipun ia juga menganut metode deduktif.
Manusia menurut Locke adalah makhluk sosial yang mendambakanperdamaian, kemauan baik dan tolong-menolong. Locke mengemukakanadanya hak-hak alamiah yang dimiliki manusia, yaitu hak untukhidup, kemerdekaan, dan hak milik pribadi.
Pemerintah dibentuk adalah untuk melindungi hak-hak yang bersifatalamiah ini. Negara diperlukan karena kelemahan dan kejahatankebanyakan orang. “Negara diciptakan karena adanya perjanjiansosial diantara rakyat.” Tujuan dari negara adalah melindungi hakmilik, hak hidup, serta kebebasan yang merupakan hak azasimanusia.
Locke adalah ahli pikir yang terkenal dengan kekuasaan membuatundang-undang dengan yang menjalankan undang-undang. Apabilaundang-undang dipegang oleh masyarakat seluruhnya sedangkanpemerintah menjalankannya, maka negara itu dalah negara yangbersifat demokrasi. Apabila kekuasaan perundang-undangandiserahkan kepada satu orang atau beberapa orang, maka ia disebutdengan monarki atau aristokrasi. Demikianlah uraian tentang J.Locke yang buah pikirannya menandai abadAufklarung, terutamatentang pentingnya ‘kesatuan’ di dalam membentuk negara dan‘pembatasan kekuasaan pemerintahan’. Ajaran Locke ini sangatberakar di Amerika.
RINGKASAN
Abad pertengahan adalah abad di mana kekuasan gereja di bawahPaus mempunyai wewenang besar terhadap kebudayaan dan politikTumbuhnya kekuasaan gereja itu ditopang oleh ahli-ahli pikir yangberlatar belakang gereja dengan pemikiran yang tidak orisinil.Thomas Aquinas misalnya, hanya berusaha untuk memadukan filsafatsosial Aristoteles dengan filsafat Kristen. Abad yang kemudianmenjelang sesudah abad pertengahan adalah abad Aufklarung yangberkembang di akhir abad ke 18 yang muncul pada masa revolusi diInggris dan Perancis. Abad Aufklarung adalah abad permulaan daripikiran yang bersifat positivistis, yang percaya pada kemajuandan kekuasan akal. Dan pemikiran-pemikiran mereka mempunyaikaitan langsung terhadap sosiologi dalam pertumbuhannya sebagaiilmu yang langsung bertumpu pada persoalan-persoalankemasyarakatan. F. Bacon, Machiavelli, Thomas Hobbes, J. Lockeserta G. Vico adalah tokoh-tokoh yang lahir pada abad itu.
LATIHAN
1. Bagaimakah Francis Bacon memandang pengetahuan dan metodeapa yang digunakannya ?
2. Bagaimanakah pendapat Hobbes mengenai terbentuknya suatumasyarakat dan negara ?
3. Jelaskan kaitan antara wewenang (authority) negara denganagama menurut Aquinas ?
4. Jelaskan teori tentang perkembangan sosial yangdikemukakan oleh Vico ?
5. Jelaskan teori tentang asal mula masyarakat dan negarayang dikemukakan oleh John Locke ?
6. Sebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinyapergulatan di antara manusia menurut Hobbes ?
TUGAS
Buatlah makalah tentang berbagai persoalan ekonomi, sosial,maupun politik yang terjadi di masyarakat kita denganmenggunakan konsep pemikiran dari Nicccolo Machiavelli!
DAFTAR PUSTAKA
De Haan, J. Bierens. 1953. Sosiologi Perkembangan danMetode. Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan.Jakarta.
Laeyendecker,L., 1994. Tata, Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman, 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi.Erlangga. Jakarta.
BAB IV
LAHIRNYA SOSIOLOGI SEBAGAI SUATU ILMU PENGETAHUAN
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Uraian utama pada bab empat ini adalah menjelaskan sumbanganpemikiran sosial yang berguna bagi lahirnya sosiologi sebagaiilmu pengetahuan. Sumbangan pemikiran itu khususnya dari tokohSaint Simon, Auguste Compte dan Herbert Spencer. Ke tiga tokohini akan diuraikan secara jelas mulai dari riwayat hidup hinggasumbangan pemikiran mereka yang begitu berarti dan berperan dalammelahirkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu :
1. menjelaskan riwayat hidup dan sumbangan pemikiran Saint Simonterhadap
sosiologi.
2. menjelaskan riwayat hidup dan sumbangan pemikiran A. Compteterhadap sosiologi.
3. menjelaskan riwayat hidup dan sumbangan pemikiran H. Spencerterhadap sosiologi.
A. Saint Simon
1. Riwayat Hidup
Saint Simon dilahirkan dari keluarga bangsawan pada tahun 1760.Simon adalah seorang amatir dan avontunis di bidang ilmupengetahuan. Selain itu, beliau juga seorang ahli tehnikmatematik sekaligus seorang pemikir agama.
Buku-buku karyanya antara lain:
a. An Introductie on to the Scientific Work of the Nineteenth Century (1808)b. Memoir upon the Science of Man (1813)c. Treatise on Universal Gravitation (1814)d. Monograph yang berjudul The Reconstruction of European Society (1816)e. Industry (1817)f. New Cristiany (1825)
2. Sumbangan Pemikiran Terhadap Sosiologi
Saint Simon berusaha untuk menggunakan metoda ilmu alam di dalammempelajari masyarakat. Simon juga menyatakan bahwa dalam
mempelajari masyarakat harus secara menyeluruh, sebab semuagejala sosial adalah saling berhubungan satu sama lain, dan olehsebab itu pula sejarah perkembangan masyarakat sebenarnyamenunjukan suatu kesamaan.
Menurut Simon, semua ilmu pengetahuan haruslah bersifat positifyang dicapai melalui metoda-metoda pengamatan, eksperimentasi dangeneralisasi sebagaimana yang digunakan dalam ilmu alam.
a. Ajaran tentang Perkembangan Sosial
Saint Simon menggunakan 2 prinsip untuk menerangkan perkembangansosial :
1. Adanya perkembangan yang terus menerus dan meluas darimasyarakat
2. Hukum tentang kemajuan pengetahuan manusia
Menurut Simon, dua prinsip tersebut yang mampu merubahmasyarakat. Simon mengatakan bahwa adanya kesejajaran (paralelisme)antara perkembangan individu dengan masyarakat yang kemudianditerangkannya dalam dua cara berfikir manusia, yaitu:
1. Cara berfikir Sintesis2. Cara berfikir Analisis
Masyarakat yang berpola pikir sintesis akan bersifat konstruktifatau organis, dan pada masyarakat yang berfikir analisis akanmembawa pemikiran yang kritis. Simon mengambil contoh masyarakatperiode kritis adalah pada masa Yunani sampai kelahiran Socrates,kemudian masa reformasi Eropa pada abad pertengahan sampaiterjadinya Revolusi Perancis yang merupakan awal dari periodekonstruktif atau organis.
Saint Simon mengatakan bahwa bentuk pengetahuan manusiaberkembang mulai dari tingkatannya yang spekulatif atau
theologies menuju tingkatannya yang semakin konkrit, ataubersifat positif atau ilmiah. Ini berarti bahwa kita harusmemandang masyarakat secara keseluruhan yang berkembang daritingkatannya yang berdasarkan pemikiran yang spekulatif atautheologies, menuju masyarakat yang diorganisir berdasarkanpemikiran yang bersifat positif atau ilmiah.
b. Ajaran tentang Organisasi Politik
Simon mengemukakan tiga bentuk lembaga perundang-undangan yaitu:
1. Invitation, yang bertugas untuk merumuskan hukum-hukum2. Examination, yang bertugas menyusun kebijaksanaan3. Execution, yang bertugas untuk menetapkan hukum-hukum sertakebijaksanaan tersebut dalam kenyataan sehari-hari
B. Auguste Comte
1. Riwayat Hidup
Auguste Comte lahir di Perancis pada tahun 1798. Comte adalahanak keluarga monarki Katolik yang terdidik dalam lingkunganpsikologi dan kedokteran pada Polytechnique. Kemudian, Comtemengajar filsafat positivistic dan mendirikan masyarakatpositivis. Dalam tradisi filsafat pencerahan, beliauberpengalaman pada katalis politik Perancis sebagaimana pascapenolakan revolusi, permulaan revolusi industri, dan konflik yangmeningkat antara ilmu dan agama.
Buku-buku karyanya antara lain:
1. A Course of Positive Philosophy (1830-1862)2. A General view of Positivism (1848)
3. Subjective Synthetis (1856)
Comte sangat dikenal sebagai seorang yang telah memberikannama Sosiologi. Sosiologi baru disebut sebagai ilmu pada abad 19.Dan usaha untuk membangunnya sebagai suatu ilmu yang berdirisendiri barulah pada jaman Auguste Compte. Dalam kontekskemasyarakatan Comte, dapat dipahami bahwa tujuan utama sosiologinya adalah mengeliminasi konstruksi masyarakat modern secararevolusioner (seperti menghentikan disorganisasi moral). Comtetertarik dengan organisasi masyarakat dalam konteks humanismepositivistik filsafatnya.
2. Sumbangan Pemikiran Terhadap Sosiologi
Sejak melakukan fondasi terhadap masyarakat, gagasan sosiologinyamenekan pada tuntunan moral. Comte berupaya mengembangkan “fisikasosial” yang akan melahirkan hukum-hukum sosial dan reorganisasisosial, sesuai dengan sistem nilai yang dikemukakan oleh Comteyang banyak bernilai dan sebagai hal yang sangat natural.
Dalam hal ini, dikatakan Comte bahwa tugas sosiologi sebagaisuatu ilmu pengetahuan positif adalah mengkaji dan memahami sistemini secara menyeluruh untuk memberikan sumbangan bagi pemecahanilmiah terhadap masalah-masalah sosial.
3. Metodologi Auguste Comte
Menurut Comte, alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang takterlihat (invisible natural) sejalan dengan evolusi dan perkembanganalam pikiran atau nilai-nilai sosial yang dominan. Comtemenyatakan bahwa proses evolusi ini terjadi melalui tiga tahapanutama yang disebut dengan hukum tentang perkembangan intelegensimanusia (the law of the three stages), yaitu: tahapan theologies ataufiktif, tahapan metafisis atau abstrak, dan tahapan scientifik
atau positivistik sebagai proses peradaban dan pengaruh faktor-faktor tertentu, seperti kebosanan, harapan hidup, sifat-sifatpopulasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya ketiga tahapantersebut, dapat mengubah tatanan naluri yang rendah menujutatanan yang lebih tinggi yang mengarah pada penekanan yangbersifat intelektual menuju tahapanpositif, yaitu tahapan yang palingilmiah dan keutuhan moralitas. Dalam setiap tahap perkembanganintelegensi manusia terdapat pula bagian-bagian yang merupakansub-ordinat.
Tahap tingkatan pemikiran yangbersifat theological atau fictitious dapat dibagi dalam tiga subordinat yaitu: fetishism, polytheism, dan monotheism. Fetishism adalahtingkatan pemikiran yang menganggap bahwa semua gejala yangterjadi dan bergerak dibawah pengaruh kekuatan supernatural ataukekuatan gaib. Oleh para ahli agama sebagai perkembangan agamapada tingkat animisme. Proses evolusi manusia berkembang ketahap Polytheism yaitu tingkatan pemikiran bahwa segala sesuatuyang ada di alam dikendalikan oleh dewa-dewa. Perkembanganselanjutnya ke tingkat pemikiran yang Monotheism yang menganggaphanya ada satu Tuhan yang mengendalikan alam ini.
Tingkat pemikiran manusia kedua adalah the methaphysical or abstractstage yaitu tingkat pemikiran yang menganggap bahwa alam semestaini segala sesuatunya diatur oleh hukum-hukum alam. Tahap iniadalah tahap transisi manusia untuk sampai ke tahap ketiga daritingkatan pemikiran manusia yaitu the positive or scientific stage, yaitusuatu tingkatan pemikiran yang menganggap semua gejala alamdengan segala isinya hanya dapat diterangkan serta dipahamimelalui kenyataan-kenyataan obyektif/positif. Arti cara berfikirpositif adalah suatu cara berfikir bahwa untuk memahami semuagejala alam haruslah melalui pengamatan/observasi terhadap gejalaitu sendiri tanpa melihat kekuatan-kekuatan yang abstrak di luarkenyataan itu.
Metode positif ini, mengembangkan penggunaan observasi (penelitian),percobaan (eksperiment), serta perbandingan untuk memahamikeseluruhan statistika dan dinamika sosial. Metode-metodetersebut memberikan gambaran terhadap hukum-hukum sosial melaluieksperimentasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,sebagaimana halnya evolusi masyarakat secara umum. Dengan ini,Comte menyebutkan sebagai metodologi yang mengarah padapengembangan yang lebih luas terhadap model teorinya yangdidasarkan organik dan natural, yaitu pada asumsi-asumsi organikdan natural.
4. Tipologi Masyarakat Compte
Auguste Comte membagi masyarakat atas dua bagian utamayaitu model masyarakat statis (sosial statics)yang menggambarkan struktursosial kelembagaan masyarakat dan prinsip perubahan sosial yangmeliputi sifat-sifat sosial (agama seni, keluarga, kekayaan, danorganisasi sosial), dan sifat kemanusian (naluri emosi, perilaku,dan inteligensi). Dan model masyarakat dinamis (sosial dynamics) yangmenggambarkan struktur sosial kelembagaan masyarakat dan prinsipperubahan sosial yang terdiri atas hukum-hukum perubahan sosial,dan faktor yang berhubungan dengan tingkat kebosanan masyarakat,usia harapan hidup, perkembangan penduduk, dan tingkatperkembangan intelektual. Comte memandang bagian-bagian inisebagai suatu kesatuan yang berkembang melalui tiga macam tahapanperkembangan intelektual menuju positivisme. Tipologi Comte inilebih menggambarkan unsur-unsur pokok dan beberapa proses dalamsistem sosial sehingga dapat mengantisipasi pekerjaan selanjutnyaoleh golongan struktur fungsional, bahkan konflik para ahli teorisosiologi.
Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa pandangan-pandanganComte itu tidak sederhana dan karya-karyanya yang menggambarkandasar-dasar, baik bagi sosiologi maupun teori sosiologi, danmengandung unsur-unsur yang signifikan yang masih relevan dengan
masalah-masalah sosiologi yang ada dalam masyarakat modern saatini. Dengan mengonseptualisasikan masyarakat seperti yangdilakukan Comte, dimana Comte telah meletakan dasar pengembangansebuah ilmu tentang kemayarakatan. Meskipun sebenarnya Comptetidak pernah menyebut nama sosiologi, sebab semua ajaran sosialtentang apa yang kita sebut dengan sosiologi pada dewasa ini,oleh Compte disebut dengan ‘sosial physics’. Namun, sejarah telahmenyebut bahwa Auguste Compte adalah pendiri sosiologi.
C. Herbert Spencer
1. Riwayat Hidup
Herbert Spencer adalah seorang bangsawan Inggris yang dilahirkandari keluarga pembangkang(nonconformist dissenter). Spencer menerimapendidikan klasik dirumahnya dan bekerja sebagai seorang jurugambar, kemudian menjadi editor pada majalah “TheEconomist”. Pandangan Spencer tentang masyarakat tampaknyadipengaruhi oleh Revolusi Industri dan ekspansi ekonomi, dariperspektif teori evolusi Darwin. Teorinya sangat banyakberhubungan dengan tipe evolusi organik, seperti halnya teoriComte tentang pembagian masyarakat menjadi masyarakat statis dandinamis. Karya-karya utama Spencer antaranya:
1. Sosial Statics (1850)
2. First Principle (1862)
3. The Study of Sociology (1873)
Perhatian utama Spencer adalah melacak atau menemukan prosesevolusi sosial melalui masyarakat secara historis dansosiologis. Dalam penerapan prinsip-prinsip evolusi biologisterhadap masyarakat merupakan sesuatu yang tidak begitu
mengejutkan. Dengan demikian, analogi organik yang diterapkanpada masyarakat secara langsung dalam kerangka evolusi. Memahamievolusi organik seperti ini menjadi penting untuk kontrol yanglebih besar terhadap masyarakat yang mengakibatkan korelasi yanglebih dekat antara kebutuhan-kebutuhan individual dan masyarakat.Seperti juga Comte, Spencer juga menjelaskan tentang teoriorganik, evolusi, dan dasar-dasar teori praktis kemasyarakatanyang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yangtertinggi.
Dalam hal sosiologi, Spencer memandang masyarakat sebagai suatukesatuan dan perkembangan yang utuh, menggambarkan lebih darisejumlah bagiannya dan bukunya subjek yang menghilangkan bagian-bagian itu. Hubungan-hubungannya sama dengan hubungan-hubunganfungsional dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini,Spencer merupakan seorang pelopor dari paham fungsionalisstrukturalis kontemporer.
2. Sumbangan Pemikiran Terhadap Sosiologi
Dalam tradisi Victorian, Spencer memandang bahwa alam semestaberada dalam keadaan yang terus-menerus mengalami evolusi danperubahan (dissolusion). Spencer menganggap bahwa inilah tugassosiologi untuk melacak proses-proses ini seperti yang merekaterapkan dalam masyarakat.
Spencer memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh danberkembang sesuai dengan hokum-hukum evolusi alam. Sistem organikini terdiri atas subsistem inner dan outer dan secara terus-menerusberkembang jauh dari tingkat-tingkat baru sebagaimana iaberkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat yang moderndan industri. Tugas utama sosiologi adalah memahami proses-proses
ini secara lebih mendalam supaya tercipta sebuah masyarakat yangharmonis.
3. Metodologi Herbert Spencer
Metodologi yang digunakan Spencer hampir sama dengan metodologiComte, yaitu observasi empirik, metode perbandingan, sertasejarah deduktif dan induktif. Metode-metode ini digunakan untukmenjelaskan atau melacak proses evolusi sosial.
4. Tipologi Masyarakat Spencer
Tipologi utama Spencer adalah pembagian masyarakat menjadimasyarakat statis dan masyarakat dinamis. Spencer menguraikansecara rinci sifat-sifat ideal dua tipe masyarakat tersebut.Spencer menggambarkan masyarakat berdasarkan kepatuhan individu,kekakuan yang tinggi, cara hidup yang teratur, dan ketentuandistribusi penghargaan serta bentuk sentralisasi yang tinggi daripemerintah. Masyarakat industri dipandang sebagai kondisi yangmemungkinkan individu memperoleh status yang lebih tinggi karenalebih sedikitnya peraturan, adanya disentralisasi, danpenghargaan yang menyebar dalam kontrak sosial. Tipe-tipe sosialini pada dasarnya menggambarkan tingkatan-tingkatan evolusi dariprimitif sampai modern.
RINGKASAN
Dari bahasan-bahasan diatas, setelah dikaji kembali ada sejumlahpersamaan mendasar antara pemikiran Saint Simon, A. Compte dan H.Spencer yaitu :
1. Memberikan reaksi terhadap masalah-masalah politik danekonomi pada masanya di dalam tradisi pencerahan. Fokus kajianmereka adalah memahami bagaimana hukum-hukum alam berlaku dalammasyarakat sebagaimana yang telah berkembang dalam memberikandasar-dasar ilmiah bagi kontrol sosial, dan kebahagiaanmasyarakat.2. Memandang bahwa masyarakat diatur oleh hukum-hukum alam.3. Memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh danberkembang terus melalui serangkaian tahapan-tahapan menujumasyarakat yang lebih positif dan industri.4. Menjelaskan susunan masyarakat yang terdiri dari masyarakatstatis dan dinamis serta masyarakat yang sintesis dan analitis.5. Menekankan pada observasi empiris dan metode komperatifsebagai metode-metode yang sesuai.6. Menggaris bawahi tipe-tipe masyarakat pada tahapan tertentudari evolusi sebagai tipologi-tipologi dasar mereka.
LATIHAN
1. Menurut Saint Simon, terdapat adanya kesejajaran antaraperkembangan individu dengan masyarakat. Dari pernyataantersebut, hal apakah yang dapat menjadi penyebab kesejajarantersebut, serta adakah pengaruh terhadap perkembangan masyarakatdi dalamnya?
2. Menurut Auguste Comte, tipologi yang Comte kemukakanmenggambarkan masyarakat yang bagaimana dan jelaskan apa yangdimaksud dengan masyarakat statis dan masyarakat dinamis?3. Dalam teori yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, apa yangmenjadi bahasan utama dalam sosiologi?4. Apa yang membedakan teori yang dikemukakan oleh Saint Simon,Auguste Comte, dan Herbert Spencer dalam perspektif sosialmasyarakat?
TUGAS
Buatlah rangkuman pemikiran sosiologi dari Saint Simon, A.Comptedan Herbert Spencer, berdasarkan literatur rujukan yangdiberikan. Kemudian jelaskan persamaan dan perbedaan daripemikiran sosiologis ke tiga tokoh tersebut. Selanjutnya akandidiskusikan di kelas!
DAFTAR PUSTAKA
De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan dan Metode.Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
Johnson, Paul D, 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I.Gramedia. Jakarta
Kinloch, Graham. 2005. Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi.Pustaka Setia. Bandung
Laeyendecker, L., 1994. Tata Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah Dan TeoriSosiologi. Erlangga. Jakarta
Soekanto, Soerjono, 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali. Jakarta.
Veeger, K.J., 1986. Realitas Sosial. Refleksi Filsafat Sosial atas HubunganIndividu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
Pokok bahasan yang akan diuraikan pada bab lima ini adalahsumbangan pemikiran dari Karl Marx terhadap ilmu sosiologi.Adapun materi-materi yang akan dibahas adalah sejarah singkatriwayat hidup Karl Marx serta menjelaskan pemikiran Karl Marxtentang materialisme historis, model-model masyarakat,alinasi,kesadaran kelas dan perubahan sosial.
Setelah mengetahui materi pokok bahasan pada bab lima, mahasiswadiharapkan mampu :
1. menjelaskan konsep materialisme historisnya Karl Marx.2. menjelaskan model-model masyarakat Karl Marx.3. menjelaskan konsep alienasi dan membedakan macam-macamalienasi Karl Marx.4. menjelaskan perjuangan kelas dan analisa dialektikaperubahan sosial Karl Marx.5. mengkaji fenomena masyarakat saat ini dengan menggunakanteori Karl Marx
A. Riwayat Hidup Marx
Jika secara spontan orang ditanya tentang Karl Marx, biasanyajawaban yang muncul akan berkisar pada Marx sebagai seorang kakektua berjenggot dengan wajah angker yang ide-idenya perludicurigai dan dihindari. Ia akan dipahami sebagai seorang lelakidari Jerman yang adalah filsuf, ahli ekonomi, dan teoritikussosial yang mempelopori gagasan mengenai materialisme dialektisdan materialisme historis. Selanjutnya ia akan dipandang sebagaiseorang penganjur perjuangan kelas dan revolusi komunis; seorangatheis pejuang gagasan “diktator proletariat” dan “masyarakattanpa kelas”; atau seorang anti-kapitalis yang membenci kaumborjuis sambil menunjukkan ketakterpisahan antara politik danekonomi.
Mengingat adanya kesulitan teknis menemukan sumber-sumberbiografis Marx pada masa awal hidupnya, di sini catatan mengenaihal itu akan disampaikan secara sekilas saja. Marx lahirdi Trier (kini di Jerman), pada tanggal 5 Mei 1818. AyahnyaHenrich Marx dan ibunya Henrietta berasal dari keluarga rabbiYahudi. Ayahnya Henrich Marx, adalah seorang pengacara di negaraPrusia, ssebelum negara itu pada tahun 1867 menjadi bagian darikonfederasi Jerman.
Usia delapan belas tahun, sesudah memperlajari hukum selamsetahun di Universitas Bonn, Marx pindah ke Universitas Berlin.Selama masa studinya di Berlin, Marx amat dipengaruhi olehfilsafat idealisme George Hegel (1770-1831). Di sini ia jugabehubungan dan amat dipengaruhi dengan kaum “HegelianMuda”. Mereka ini bermaksud.menerapkan gagasan Hegel gunamelawan agama sebagai lembaga yang tak ramah(organized religion) danpemerintah Prusia yang dirasakan sebagai otoritarian. Pada tahun1841, di usianya yang ke-23, Marx meriah gelar doktor dalambidang filsafat. Perjalanan hidupnya setelah itu adalahperjalanan yang penuh kesulitan dan tantangan.
Setelah menyelesaikan disertasi doktornya di Universitas Berlin,Marx menerima tawaran untuk menulis dalam surat kabar borjuisliberal, bernama Rheinishe Zeitung di Cologne. Kemudian ia menjadipimpinan surat kabar ini walaupun pada akhirnya harus ditutupoleh pemerintah karena dianggap terlalu kritis.
Setelah itu ia pun pindah ke Paris. Di Paris inilah Marx menikahdengan Jenny pada tanggal 19 Juni 1843. Di sini pula ia bertemudengan Friedrich Engels. Pada tahun 1845 ia dan keluarganyaberpindah ke Brussels. Kemudian tahun 1846 Marx bersama temankerjanya Friedrich Engels (sekaligus teman dekat sampai Marxmeninggal) mengikuti Communist League suatu organisasirevolusioner yang bermarkas di London.
Dua tahun kemudian (1848) dia diusir karena pemerintah Belgiatakut bahwa Marx akan mendorong revolusi di situ. Marx punkembali ke Paris, lalu ke Rhineland, namun di sana ia jugaberbenturan dengan penguasa setempat. Akhirnya pada tahun 1849Marx pindah ke London. Ia tinggal dan berkarya di kota itu sampaimeninggalnya, pada tanggal 14 Maret 1883.
B. Alam Berpikir Marx
Sebagai seorang ahli sosial sekaligus filosof yang juga menguasaiilmu ekonomi, Marx dalam melihat masalah kemasyarakatan memilikipusat perhatian pada tingkat struktur sosial dan bukan padatingkat kenyataan sosial budaya. Marx dalam hal ini lebihmemusatkan perhatiannya pada cara orang menyesuaikan diri denganlingkungan fisiknya. Dia juga melihat hubungan-hubungan sosialyang muncul dari penyesuaian ini dan tunduknya aspek-aspekkenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi.
Bagi Marx, kunci untuk memahami kenyataan sosial tidak ditemukandalam ide-ide abstrak, tetapi dalam pabrik-pabrik atau dalamtambang batu bara. Di mana para pekerja menjalankan tugas yang diluar batas kemanusiaan dan berbahaya, untuk menghindarkan diridari mati kelaparan dan berbagai penderitaan kaum buruh, inilahkenyataan sosial. Kenyataan sosial bukan impian naif danidealistik yang dibuat oleh ilmu pengetahuan, teknologi danpertumbuhan industri untuk meningkatkan kerjasama danmeningkatkan kesejahteraan dalam bidang materil semua orang.
Karl Marx dalam pemikiran filosofisnya banyak dipengaruhi olehGeorge Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dan Ludwig Feurbach(1804-1872), keduanya filsuf Jerman. Kalau Hegel dalampemikirannya lebih bersifat idealistik, Feurbach lebih bersifat
materialistik, humanistik dan inderawi. Namun, pada akhirnyapengaruh kedua tokoh ini hanya akan menjadi titik tolak bagi Marxuntuk sampai ke pemikiran-pemikirannya sendiri.
Sedikit banyak dalam ingatan orang Marx lebih dikenal sebagaipengikut Hegelian. Marx sendiri menggunakan inti model analisadialektik Hegel. (lihat gambar).
1.
3. 2.
Penjelasan pengertian dasarnya dalam analisa dialektika berintikan :
Pandangan mengenai pertentangan antara tesis dan antitesis sertatitik temu keduanya yang akhirnya akan membentuk sintesa baru;kemudian ini menjadi tesis baru, dan dalam pertentangan dengan
tesis baru itu, muncul suatu antitesis baru, dan akhirnya keduatesis yang saling bertentangan ini tergabung dalam satu sintesabaru yang lebih tinggi tingkatannya.
Meskipun model ini agak abstrak, mungkin dapat digambarkan dalamsatu hal yang terdapat dalam tradisi masyarakat kita sendiridengan adanya pertentangan antara ide-ide yang digunakan untukmembenarkan pelbagai bentuk pelapisan sosial dan ide-ide mengenaipersamaan. Namun, sulit untuk membayangkan suatu dilema dasarseperti itu yang dapat dipertemukan sepenuhnya.
Menurut kebanyakan ahli selain alam pikirnya, Marx dalam berkaryadan menelurkan karya-karyanya berpijak pada tiga “sila dasar”:
1. Teori Materialisme Historis
Materialisme Historis Marx menjelaskan sejarah denganmemposisikan material manusia sebagai dasar sejarah dan memandangproduksi mental, intelektual seseorang dan kehidupan budayasebagai efeknya.
2. Teori Perjuangan Kelas
Menurut hasil analisa dan pengamatan Antoni Gidden terhadap teoriPerjuangan Kelas Marx bahwa di dunia ini di belahan manapunmasyarakat terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu GolonganBorjuis (pemilik modal) dan Golongan Proletar (kaum buruh, tani).
3. Teori Nilai Lebih
Konsep ini menjelaskan keuntungan kaum kapitalis dan eksloitasiburuh. Marx mendefinisikan nilai lebih sebagai perbedaan antaranilai upah yang diterima buruh dan nilai dari apa yang merekahasilkan. Artinya, perbedaan antara upah yang harus dibayar kaumkapitalis kepada buruh dan produk hasil kerja kaum buruh yangbisa dijual kaum kapitalis untuk kepentingan kaum kapitalis.
C. Karya-Karya Karl Marx
Berikut adalah beberapa karya Marx semasa hidupnya:
1. Economic and Philosophical Manusript.
Tulisan ini terinspisrasi karena Marx banyak mengenal tulisan-tulisan ahli ekonomi politik seperti Adam Smith dan DavidRicardo. Marx dalam hal ini mengambil isu individualismependekatan ini dengan mengatakan bahwa deengan individualismemanusia dikesampingkan.
2. The German Ideology
Karya ini merupakan hasil pemikirannya dengan Engles. Karya inimengenai suatu interpretasi komprehensif tentang perubahan danperkembangan sejarah sebagai alternatif terhadap interpretasiHegel mengenai sejarah.
3. The Class Strruggles in France dan The Eighteenth Brumaire of LouisBonaparte.
Kedua esai ini menerapkan metode materialis historisnya Marxdengan berusaha untuk mengungkapkan kondisi-kondisi sosial danmaterial yang mendasar yang terdapat di bawah permukaanperjuangan-perjuangan ideologis yang dinyatakan hanya dengankondisi-kondisi sosial dan materil.
4. The Communist Manifesto
Sebuah tulisan yang ditugaskan kepada Marx olehorganisasi Communist League setelah perdebatan antara Marx danWeikting dalam organisasi itu mengenai waktu yang tepat untukrevolusi proletariat. Dan ini merupakan pernyataan yang akanmenjadi program teoretis untuk organisasi itu.
5. Das Kapital
Dalam Das Kapital Marx mengembangkan dan mensistematisasisebagian besar ide-ide yang sudah diuraikan sebelumnya secaarasingkat dari karya-karya sebelumnya
D. Materialisme Historis Marx
Dari karya ‘The Comunist Manifesto’, dan ‘Das Kapital’, Marx sangatterkenal dengan dialektika materialis dan dialektika historisnya.Baginya, kekuatan yang mendorong manusia dalam sejarah adalahcara manusia berhubungan antara manusia yang satu dengan manusiayang lain, yang dalam perjuangannya yang abadi untuk merengutkehidupan dari alam. Tindakan historis yang pertama adalahmembina kehidupan material itu sendiri. Keinginan untuk memenuhikebutuhan makan dan minum, tempat tinggal serta sandang adalahtujuan manusia yang utama pada awalnya. Namun demikian,perjuangan manusia tidaklah terhenti pada saat kebutuhannya yangpaling utama terpenuhi atau tercapai, manusia memang sesungguhnyabinatang yang tetap tidak akan terpuaskan. Ketika kebutuhan-kebutuhan pokok telah terpenuhi, pemenuhan kebutuhan itu justrumenyebabkan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru, yang mengawaliterbentuknya kelas-kelas yang saling bertentangan. Menurut Marx,semua periode sejarah ditandai oleh perjuangan kelas yang berbedasatu sama lain sesuai dengan periode sejarahnya. Meskipun gejalahistoris merupakan hasil dari saling mempengaruhi antar berbagaikomponen, sesungguhnya hanya faktor ‘ekonomi’ yang merupakanindependent variabelnya. Perkembangan politik ,hukum, filsafat,kesusasteraan dan kesenian semuanya bertopang pada faktorekonomi.
E. Teori Alienasi
Selain teori Perjuangan Kelas dan beberapa hal di atas ada sebuahteori Marx yang menjelaskan dampak dari produktifitas manusiaterhadap keterasingan manusia itu sendiri. Teori ini lebihdikenal dengan Teori Alienasi.
Alienasi atau keterasingan merupakan masalah yang menjadi menarikuntuk dikaji ketika orang mulai sadar bahwa lama kelamaan barang-barang yang diproduksi manusia makin menjadi otonom, bahkanseakan-akan menguasai manusia. Menurut Marx alienasi ada dandijumpai orang di mana-mana dalam segala bidang dan dalam semualembaga di mana manusia memasukinya. Tetapi alienasi yang palingpenting adalah alienasi yang dijumpai di tempat orang bekerja,karena manusia menurut Marx adalah‘homo faber’ artinya manusiasebagai pekerja/pencipta. Alienasi dalam bidang kerja ada empataspek yaitu :
a. Manusia diasingkan dari produk hasil pekerjaannya.
b. Terasing dari kegiatan produksi.
c. Terasing dari sifat sosialnya sendiri.
d. Terasing dari rekan-rekannya atau masyarakatnya.
Demikianlah, sesungguhnya Marx telah mengemukakan bagaimanamanusia teralienasi adalah merupakan manusia yang sebenarnya hidupdi dalam dunianya yang tidak terhayati oleh dirinya sendiri.
F. Kesadaran Kelas dan Perjuangan Kelas
Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa “sejarah darisegala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalahsejarah pertikaian antara golongan’. Menurut pandangannya, sejakmasyarakat manusia mulai dari bentuknya yang primitif secararelatif tidak berbeda satu sama lain, namun tetap mempunyaiperbedaan-perbedaan fundamental antara golongan yang bertikai didalam mengejar kepentingannya masing-masing. Bagi Marx, dasardari sistem stratifikasi adalah tergantung dari hubungankelompok-kelompok manusia terhadap sarana produksi. Yang disebut
kelas dalam hal ini adalah suatu kelompok orang-orang yangmempunyai fungsi dan tujuan yang sama dalam organisasi produksi.
Kelas-kelas yang memiliki kesadaran diri, memerlukan sejumlahkondisi tertentu untuk menjamin kelangsungannya, yaitu merekamemerlukan adanya suatu jaringan komukasi ddi antara mereka,pemusatan massa rakyat serta kesadaran akan adanya musuh bersamadan adanya bentuk organsisasi yang rapi. Organisasi ini dapatberupa serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnyauntuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kodisi kerja,dan sebagainya. Akhirnya organisasi kelas buruh ini akan menjadicukup kuat bagi mereka untuk menghancurkan seluruh struktursosial kapitalis dan menggantikan dengan struktur sosial yangmenghargai kebutuhan dan kepentingan umat manusia seluruhnya yangdiwakili oleh kelas proletar.
G. Analisa Dialektika Perubahan Sosial
Cara analisa dialektik merupakan inti model bagaimana konflikkelas mengakibatkan perubahan sosial. Umumnya analisa dialektikmeliputi suatu pandangan tentang mansyarakat yang terdiri darikekuatan-kekuatan yang berlawanan yang sewaktu-sewaktu menjadiseimbang. Dalam pandangan Marx, kontradiksi yang paling pentingadalah antara kekuatan-kekuatan produksi materil dan hubungan-hubungan produksi, dan antara kepntingan-kepentingan kelas yangberbeda. Karena kontradiksi inilah, setiap tahap sejarah dalamperkembangan masyarakat dapat dilihat sebagai tahap yangmempersiapkan jalan untuk kehancuran akhirnya sendiri, denganmasing-masing tahap baru yang menolak tahap sebelumnya di manasecara paradoks memasuki awalnya. Namun gerak sejarah yangbersifat dialektik itu tidak terlepas dari kemauan atau usahamanusia. Manusialah yang menciptakan sejarahnya sendiri, meskipunkegiatan kreatifnya ditentukan dan terikat oleh lingkunganmateril dan sosial yang ada. Khusus dalam ‘The Communist Manifesto’,Marx mendesak kaum buruh untuk mempergunakan moment yang tepat
dalam sejarah yang ditimbulkan oleh munculnya krisis ekonomi,untuk mengubah masyarakat melalui kegiatan revolusioner merekasendiri.
RINGKASAN
Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran KarlMarx dalam perkembangan sosiologi telah memberikan warna baru.Bahkan dalam perkembangannya kelak, sosiologi modern telahmenampilkan lagi ajaran-ajarannya yang dikenal dengan NeoMarxian yang mewarnai suatu aliran dalam sosiologi yaitupendekatan konflik. Juga dapat dicatat secara sosiologis adalahjasa Marx untuk menampilkan pendapatnya bahwa kesadaran manusiadan kesadaran golongan (kelas menurut Marx) senatiasa ditentukanpula oleh keadaan masyarakat di mana kesadaran itu hidup danberkembang.
Kebesaran Marx tidak terlepas pula dari kesilapan. Dia terlampaumenekankan faktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang palingpenting menggerakkan sejarah. Dalam kenyataannya, berbagai faktorlain seperti faktor geografis dan dorongan-dorongan biologis yanginherent dalam diri manusia, lebih dahulu mengemuka dan bekerjadibandingkan dengan faktor ekonomis. Demikian juga faktor-faktorintelegensi, pengalaman, ide-ide religi, tata hukum bahkan senimemberikan aktifitas yang ditujukan kepada apa yang disebutdengan tujuan-tujuan ideal. Sebagaimana banyak kita temukan didalam kehidupan masyarakat primitif, di mana seluruh aktifitas dilapangan sedemikian itu, merupakan faktor yang lebih dahulu dijalankan sebelum melaksanakan aktifitas ekonomi.
LATIHAN
1. Jelaskan maksud dari teori perjuangan kelas Karl Marx!2. Apa yang dimaksud dengan alienasi, serta sebutkan 4 aspekmanusia sebagai homo faberteralinasi dalam pekerjaannya!3. Jelaskan maksud konsep pemikiran Marx tentang materialismehistoris!
4 Sebutkan dan jelaskan 3 sila dasar menurut para ahlisebagai pijakan Marx dalam
Berkarya!
5. Jelaskan kritik utama yang diberikan terhadap teori KarlMarx!
TUGAS
1. Carilah serta kumpulkan dari surat-surat kabar atau mediamassa lainnya, 2 artikel yang menyangkut persoalan-persoalan yangberkaitan dengan dunia kerja, khususnya dalam dunia industri diIndonesia.2. Analisakan persoalan-persoalan itu dengan menggunakan teoriKarl Marx yang telah kamu pelajari!
DAFTAR PUSTAKA
De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan dan Metode.Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
Giddens, Anthony, 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu AnalisisKarya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. UI Press. Jakarta.
Laeyendecker, L., 1994. Tata, Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
Lavine, T.Z., 2002.Dari Socrates Ke Sartre: Petualangan Filsafat, Jendela.Yogyakarta
M. Siahaan, Hotman, 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosiologi. Erlangga. Jakarta.
P. Johnson, Doyle, 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Dindonesiakan: Robert M.Z. Lawang. Gramedia. Jakarta
Wardaya, Baskara T., 2003. Marx Muda: Marx Muda Berwajah Manusiawi. BukuBaik.Yogyakarta.
Ramli, Andi Muawiyah. 2000. Peta Pemikiran Karl Marx. LKLS. Yogyakarta.
Suseno, Frans Magnis. 2000. Pemikiran Karl Marx. Gramedia. Jakarta.
SUMBANGAN PEMIKIRAN SOSIOLOGI DARI EMILE DURKHEIM
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Pokok bahasan yang akan diuraikan pada bab keenam ini adalahsumbangan pemikiran dari Emile Durkheim. Durkheim dapat dipandangsebagai salah seorang yang meletakkan dasar-dasar sosiologimodern. Durkheim adalah seorang ahli sosiologi yang sangat luasbidang perhatiannya. Ia menulis tentang metode-metode sosiologi,tentang pengetahuan dan sosiologi agama, tentang pembagian kerjadan bunuh diri, tentang pendidikan dan moral, dan tentangsosialisme. Hubungan dengan masalah-masalah sosial selau tampakdalam karyanya.
Durkheim sebagi tokoh klasik utama yang pendekatan teoritisnyamenekankan tingkat analisa struktur sosial serta memperhatikanproses sosial yang meningkatkan integrasi dan solidaritas dalammasyarakat. Sosidaritas sosial dan integrasi mungkin dilihatsebagai suatu contoh dari fakta sosial yang berada diluarindividu dan tidak dapat dijelaskan menurut karakteristikindividu. Untuk memahami tingkat dan tipe solidaritas sosial yangterdapat dalam masyarakat, perlu menganalisa stuktur sosialnya.
Tekanan Durkheim pada tingkat analisa struktur sosial adalah padaanalisa mengenai
hasil-hasil tindakan sosial yang obyektif terlepas dari motif-motif subyektif, serta minatnya pada penelitian mengenai dasar-
dasar keteraturan sosial, merupakan elemen-elemen utama dalamteori fungsional masa kini.
Setelah mempelajari pokok bahasan di bab enam ini, mahasiswadiharapkan mampu :
1. menjelaskan fakta sosial, karakteristik dan metodepengamatan fakta sosial Durkheim.2. menjelaskan pengertian solidaritas sosial dan membedakanjenis-jenis solidaritas sosial menurut Durkheim.3. menjelaskan pengertian kesadaran kolektif Durkheim4. menjelaskan teori bunuh diri dan jenis-jenis bunuh dirimenurut Durkheim.5. menjelaskan pengertian anomi Durkheim6. menjelaskan pengertian integrasi masyarakat menurut Durkheim7. mengkaji fenomena masyarakat saat ini dengan menggunakanteori Durkheim
A. Riwayat Hidup
Sosiolog besar ini dilahirkan di Epinal di propinsi Lorraine diPerancis Timur pada 15 April 1858 dan meninggal tahun 1917.Durkheim bolehlah disebut sebagai sosiolog Perancis pertama yangsepanjang hidupnya menempuh jenjang ilmu sosiologi yang palingakademis. Dialah yang memperbaiki metode berfikir sosiologi yangtidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofistetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang yangbenar katanya apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi.Tonggak sejarah yang pentng dicapaiketika Durkheim mendirikan L’Anee Sociologique, jurnal ilmiah pertamauntuk sosiologi. Jurnal itu meningkatkan pengertian sertapenghargaan terhadap disiplin sosiologi yang mengalamiperkembangan pesat.
B. Fakta Sosial Durkheim
1. Pengertian Fakta Sosial
Fakta sosial didefinisikan oleh Durkheim sebagai cara-carabertindak, berfikir, dan merasa yang ada diluar individu dan yangmemiliki daya paksa atas dirinya. Dalam arti lain, yangdimaksudkan adalah pengalaman umum manusia. Pengertian faktasosial meliputi suatu spectrum gejala-gejala sosial. Yangterdapat bukan saja cara-cara bertindak dan berfikir melainkanjuga cara-cara berada, yaitu fakta-fakta sosial morfologis,seperti bentuk permukiman, pola jalan-jalan, pembagian tanah, dansebagainya.
Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam :
1. Dalam bentuk material. Yaitu barang sesuatu yang dapatdisimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentukmaterial ini adalah bagian dari dunia nyata. Contohnya arsitekturdan norma hukum.
2. Dalam bentuk non material. Yaitu sesuatu yang dianggapnyata. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifatinter subjective yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaranmanusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme, dan opini.
2. Karakteristik Fakta Sosial
Bagaimana gejala sosial itu benar-benar dapat dibedakan darigejala yang benar-benar individual (psikologis) Durkheim
mengemukakan dengan tegas tiga karakteristik fakta sosial,yaitu :
1. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Individusejak awalnya mengkonfrontasikan fakta sosial itu sebagai suatukenyataan eksternal. Hampir setiap orang sudah mengalami hidupdalam satu situasi sosial yang baru, mungkin sebagai anggota barudari suatu organisasi, dan pernah merasakan adanya norma sertakebiasaan yang sedang diamati yang tidak ditangkap/ dimengertinyasecara penuh. Dalam situasi serupa itu, kebiasaan dan norma inijelas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal.
2. Fakta itu memaksa individu. Individu dipaksa, dibimbing,diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi olehpelbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. SepertiDurkheim katakan : Tipe perilaku atau berfikir ini mempunyaikekuatan memaksa yang karenanya kereka memaksa individu terlepasdari kemauan individu itu sendiri. Ini tidak berarti bahwaindividu itu harus mengalami paksaan fakta sosial dengan carayang negatif atau membatasi atau memaksa seseorang untukberprilaku yang bertentangan dengan kemauannya kalau sosialisasiitu berhasil, sehingga perintahnya akan kelihatan sebagai halyang biasa, sama sekali tidak bertentangan dengan kemauanindividu.
3. Fakta itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalamsuatu masyarakat.
Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersamabukan sifat individu perorangan. Sifat umumnya ini bukan sekedarhasil dari penjumlahan beberapa fakta individu. Fakta sosialbenar-benar bersifat kolektif, dan pengaruhnya terhadap individumerupakan hasil dari sifat kolektifnya ini.
3. Metode Pengamatan Fakta Sosial
Durkheim dalam bukunya yang berjudul “The Rules Of Sosiological Method”memberikan dasar-dasar metodologi dalam sosiologi. Salah satuprinsip dasar yang ditekankan Durkheim adalah bahwa fakta sosialharus dijelaskan dalam hubungannya dengan fakta sosial lainnya.Ini adalah asas pokok yang mutlak. Kemungkinan lain yang besaruntuk menjelaskan fakta sosial adalah menghubungkannya dengangejala individu (seperti kemauan, kesadaran, kepentingan pribadiindividu, dan seterusnya) seperti yang dikemukakan oleh ahliekonomi klasik dan oleh Spencer.
Prinsip dasar yang kedua (dan salah satu yang fundamental dalamfungsionalisme modern) adalah bahwa asal-usul suatu gejala sosialdan fungsi-fungsinya merupakan dua masalah yang terpisah. Sepertiditulis Durkheim “Lalu apabila penjelasan mengenai suatu gejalasosial diberikan kita harus memisahkan sebab yangmengakibatkannya (efficient cause) yang menghasilkan gejala itu, danfungsi yang dijalankannya. Sesudah menentukan bahwa penjelasantentang fakta sosial harus dicari di dalam fakta sosial lainnya,Durkheim memberikan strategi tentang perbandingan terkendalisebagai metoda yang paling cocok untuk mengembangkan penjelasankausal dalam sosiologi.
Metoda perbandingan Durkheim lebih ketat dan terbatas. Padaintinya, metoda perbandingan terkendali itu meliputi klasifikasisilang dari fakta sosial tertentu untuk menentukan sejauh manamereka berhubungan. Kalau korelasi antara dua himpunan faktasosial dapat ditunjukkan sebagai valid dalam pelbagai macamkeadaan, hal ini memberi satu petunjuk penting bahwa tipe faktaitu mungkin berhubungan secara kausal. Artinya, variasi dalamnilai dari satu tipe variable mungkin merupakan sebab darivariasi dalam nilai variable yang kedua.
C. Solidaritas Sosial Durkheim
Solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individudan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dankepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalamanemosional bersama.
Sumber utama bagi analisa Durkheim mengenai tipe-tipe yangberbeda dalam solidaritas dan sumber struktur sosialnya diperolehdari bukunya “The Devision Of Labour In Society”. Tipe/jenis solidaritasyang dijelaskan Durkheim tersebut yaitu:
a. Solidaritas mekanik.
Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadarankolektif bersama, yang
menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersamayang rata-rata ada
pada warga masyarakat yang sama itu. Indikator yangpaling jelas untuk
solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnyahukum-hukum yang
bersifat menekan itu (repressive). Ciri khas yang pentingdari solidaritas mekanik
adalah bahwa silidaritas itu didasarkan pada suatutingkat homogenitas yang
tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya.Homogenitas serupa itu
hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangatminim.
b. Solidaritas organik.
Solidaritas organik didasarkan pada tingkat salingketergantungan yang tinggi.
Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil daribertambahnya spesialisasi
dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan jugamenggairahkan
bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Durkheimmempertahankan bahwa
kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnyahukum yang bersifat
memulihkan dari pada yang bersifat represif. Dalam sistemorganik, kemarahan
kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadikecil kemungkinannya,
karena kesadaran koleftif itu tidak begitu kuat.
Selain itu, Durkheim juga membandingkan sifat pokok darimasyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanik dengan sifatmasyarakat yang didasarkan pada solidaritas organik.
Perbandingan tersebut yaitu :
Solidaritas Mekanik Solidaritas Organik
- Pembagian kerjarendah
- Kesadarankolektif rendah
- Hukum represifdominan
- Individualitasrendah
- Pembagian kerjatinggi
- Kesadarankolektif lemah
- Hukum restitutifdominan
- Individualitas
- Konsensusterhadap pola-polanormatif itu penting
- Peranan komunitasdalam menghukum orangyang menyimpang
- Salingketergantungan itu rendah
- Bersifat primitifatau pedesaan
tinggi
- Konsensusterhadap nilai abstrak danumum itu penting
- Badan kontrolsosial yang menghukumorang yang menyimpang
- Salingketergantungan yang tinggi
- Bersifatindustrial-perkotaan
D. Kesadaran Kolektif
Kesadaran kolektif dapat memberikan dasar moral yang tidakbersifat kontraktual yang mendasari hubungan kontraktual. Dalambenak Durkheim, kesadaran kolektif yang mendasar ini diabaikanoleh ahli teori seperti Spencer, yang melihat dasar fundamentaldari keteraturan sosial ini dalam hubungan-hubungan yang bersifatkontraktual. Kesadaran kolektif juga ada dalam bentuk yang lebihterbatas dalam pelbagai kelompok khusus dalam masyarakat.
Durkheim juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif bersamayang mungkin ada dalam pelbagai kelompok pekerjaan dan profesi.Keserupaan dalam kegiatan dan kepentingan pekerjaanmemperlihatkan suatu homogenitas internal yang memungkinkanberkembangnya kebiasaan, kepercayaan, perasaan, dan prinsip moraldan kode etik bersama. Akibatnya, anggota kelompok ini dibimbingdan dipaksa untuk berprilaku sama seperti anggota satu sukubangsa primitif dengan pembagian kerja yang rendah yang dibimbingdan dipaksa oleh kesadaran kolektif yang kuat. Durkheim merasa
bahwa solidaritas mekanik dalam pelbagai kelompok pekerjaan danprofesi harus menjadi semakin penting begitu pembagian pekerjaanmeluas, sebagi satu alat perantara yang penting antara individudan masyarakat secara keseluruhannya.
E. Teori Bunuh Diri (Suicide)
Selain konsepsinya tentang solidaritas mekanis organis, Durkheimsangat terkenal dengan studinya tentang kecenderungan orang untukmelakukan bunuh diri. Dalam bukunya yang kedua, Suicidedikemukakandengan jelas hubungan antara pengaruh integrasi social terhadapkecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Durkheim dengan tegasmenolak anggapan lama bahwa penyebab bunuh diri yang disebabkanoleh penyakit kejiwaan sebagaimana teori-teori psikologimengatakannya. Dia juga menolak anggapan Gabriel Tarde bahwabunuh diri akibat imitasi. Durkheim juga menolak teori yangmenghubungkan bunuh diri dengan alkoholisme. Durkheimmenolak teori bunuh diri karena kemiskinan, kenyataan orang-orang lapisan atas tingkat bunuh dirinya lebih tinggidibandingkan orang-orang dari lapisan atas. Dari hasilpenelitiannya Negara-negara miskin seperti Italia dan Spanyoljustru memiliki angka bunuh diri yang lebih rendah dibandingkandengan Negara-negara Eropa yang lebih makmur seperti Perancis danJerman.
Menurut Durkheim peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnyakenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapatdijadikan sara penelitian dengan menghubungkannya dengan derajatintegrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Untukmembuktikan teorinya, Durkheim memusatkan perhatiannya pada 3macam kesatuan sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kesatuanagama, keluarga dan kesatuan politik.
Dalam kesatuan agama, Durkheim membuat kesimpulan bahwa penganut-penganut agama Protestan mempunyai kecenderungan lebih besaruntuk melakukan bunuh diri dibandingkan dengan penganut agamaKatholik.Hal ini dikarenakan perbedaan derajat integrasi sosialdi antara penganut agama Katolik dengan Protestan. Penganut agamaProtestan memperoleh kebebasan yang jauh lebih besar untukmencari sendiri hakekat ajaran-ajaran kitab suci. Pada agamaKatolik tafsir agama lebih ditentukan oleh para pater. Olehkarena itu kepercayaan bersama dari penganut Protestan menjadiberkurang, hingga sekarang ini terdapat banyak gereja (sekte-sekte). Integrasi yang rendah dari penganut agama protestanitulah yang menyebabkan angka laju bunuh diri dari penganutajaran ini lebih besar dibandingkan dengan penganut ajaranKatolik.
Dalam kesatuan keluarga, Durkheim menunjukkan bahwa angka lajubunuh diri lebih banyak terdapat pada orang-orang yang tidakkawin daripada mereka yang sudah kawin. Kesatuan keluarga yanglebih besar umumnya terintegrasi mengikat anggota-anggotanyauntuk saling membantu.
Dalam kesatuan politik, Durkeim menyebutkan bahwa dalam keadaandamai, golongan militer ummunya lebih besar kecenderungan bunuhdirinya dibandingkan golongan masyarakat sipil. Sedangkan dalamsuasana perang, golongan militer justru lebih sedikit melakukanbunuh diri bila dibandingkan golongan sipil karena mereka lebihterintegrasi dengan baik (disiplin keras). Dalam situasi perangjustru kecenderungan bunuh diri lebih rendah dibandingkan situasidamai. Dalam masa revolusi/pergolakan politik, anggota-anggotamasyarakat justru lebih terintgrasi dalam menghadapi musuh-musuhnya.
Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai setiap kematian yangmerupakan akibat langsung atau tidak langsung dari suatu
perbuatan positif atau negatif oleh korban itu sendiri, yangmengetahui bahwa perbuatan itu akan berakibat seperti itu.Definisi itu terlampau luas, sebab didalamnya juga termasukkematian para prajurit yang mengajukan dirinya untuk melaksanakantugas yang sukar, ataupun kematian seorang ayah yang inginmenyelamatkan anaknya dari arus kencang yang bergolak. Hal iniakan berakibat negatif dalam penalaran seperti yang akan ternyatakemudian.
Durkheim membagi bunuh diri dalam beberapa jenis yaitu :
- Bunuh diri egoistis (egoistic suicide) Yaitu yang merupakanakibat dari kurangnya integrasi dalam kelompok. Misalnya, lebihbanyak orang Protestan yang bunuh diri dari pada orang Katolik.Sebab orang Katolik lebih terikat pada komunitas keagamaansedangkan dalam Protestan terdapat anjuran yang kuat untukbertanggung jawab secara individual. Kenyataan ini dinyatakansecara tepat sekali di dalam rumusan bahwa seorang Protestandipaksa untuk bebas.
- Bunuh diri anomi (anomie suicide). Anomi adalah suatusituasi dimana terjadi suatu keadaan tanpa aturan, dimanakesadaran kolektif tidak berfungsi. Jenis bunuh diri ini terjadidalam waktu krisis dan bukannya krisis ekonomi saja. Bunuh diriini juga terjadi bilamana sekonyong-konyong terjadi kemajuan yangtidak terduga.
- Altruistic Suicide, adalah bunuh diri karena merasa dirinyamenjadi beban masyarakat. Bunuh diri ini sifatnya tidak menuntuthak, sebaliknya memandang bunuh diri itu sebagai suatu kewajibanyang dibebankan oleh masyarakat. Contoh : Harakiri orang jepang.
- Bunuh diri Fatalistik. Merupakan lawan dari bunuh dirianomi, dan yang timbul dari pengaturan kelakuan secara berlebih-lebihan, misalnya dalam rezim yang sangat keras dan otoriter.
]
F. Anomi Durkheim
Anomi adalah suatu situasi di mana terjadi suatu keadaan tanpaaturan, di mana ‘colective conciousness(kesadaran kelompok)’ tidakberfungsi. Suatu situasi di mana aturan-aturan dalam masyarakattidak berlaku/berfungsi lagi sehingga orang merasa kehilanganarah dalam kehidupan sosialnya. Contohnya krisis yang seringterjadi di dalam perdagangan dan industri, terhadap spesialisasiyang jauh di dalam ilmu pengetahuan yang merugikan kesatuan dalamilmu pengetahuan sendiri, terhadap sengketa antara modal dankerja. Durkheim menamakan situasi ini situasi pembagian kerjaanomis.
Sebaliknya, menurut pendapat Comte bahwa disintegrasi itu timbulpada saat pembagian kerja melewati suatu batas kritis.Disintegrasi ini hanya dapat dibendung oleh negara yang harusmengadakan tindakan yang mengatur. Durkheim berpendapat bahwapandangan ini tidak benar. Aturan-aturan hanya timbul apabilaterdapat interaksi yang cukup banyak dan cukup lama, kalauinteraksi seperti itu tidak ada, maka terjadi anomi, yaitu samasekali tidak ada aturan, atau aturan-aturan yang ada tidak sesuaidengan taraf perkembangan pembagian kerja. Karena itu, anomitidak boleh diberantas dengan mengurangi pembagian kerja, tetapidengan menghilangkan sebab-sebab anomi itu.
G. Integrasi Masyarakat menurut Durkheim
Didalam karya besarnya yang pertama Durkheim membahas masalahpembagian kerja. Durkheim merumuskan masalahnya : Apakahpeningkatan pembagian kerja harus dipandang sebagai kewajibanmoral yang tidak boleh dihindari oleh manusia? Ia mencobamerumuskan jawabannya atas dasar suatu analisa obyektif terhadap
fakta-fakta. Menurut penglihatannya, fungsi pembagian kerja ituialah peningkatan solidaritas. Antara kawan-kawan dan didalamkeluarga ketidaksamaan menciptakan suatu ikatan : justru karenaindividu mempunyai kualitas yang berbeda maka terdapatlahketertiban, keselarasan, dan solidaritas. Karena individumelakukan berbagai kegiatan, maka mereka menjadi tergantung satusama lain dan karenanya terikat satu sama lain. Karenaketertiban, keselarasan, dan solidaritas merupakan keperluan umumatau syarat-syarat hidup yang merupakan keharusan bagi organismesosial, maka hipotesa bahwa pembagian kerja adalah syarat hidupbagi masyarakat modern dapat dibenarkan.
RINGKASAN
Durkheim adalah akademisi yang sangat mapan dan berpengaruh. Diaberhasil dalam melembagakan sosiologi sebagai satu disiplinakademi yang sah. Sebelum Durkheim, sosiologi merupakan bidangyang belum jelas perbedaannya dengan filsafat menurut ide-ideteoritisnya, juga tidak jelas perbedaannya dengan sejarah ataupsikologi menurut isi dan metoda-metodanya. Pendiriannya mengenaikenyataan gejala sosial yang berbeda dengan gejala individu,analisanya mengenai tipe struktur sosial yang berbeda danmengenai dasar soilidaritas sosial serta integrasinya yangberbeda-beda. Perhatiannya untuk menelusuri fungsi sosial darigejala sosial yang terlepas dari maksud dan motivasi yang sadardari individu, pemecahan sosilogisnya mengenai gejalapenyimpangan, bunuh diri dan individualisme, serta studistatistiknya yang cermat mengenai angka bunuh diri sebagai contohbagaimana menganalisa gejala sosial secara empiris, dalam semuabidang ini Durkeim memberikan sumbangan penting terhadapperkembangan perspektif sosilogi modern. Pengaruhnya mungkinsangat menyolok dalam aliran fungsionalisme sosiologi modern.
LATIHAN
1. Menurut Durkheim fakta sosial terbagi menjadi dua macam.sebutkan dan jelaskan!
2. Durkheim mengemukankan dengan tegas tiga karakteristikfakta sosial. Sebutkan dan jelaskan tiga karakteristik faktasosial tersebut !
3. Dalam bukunya yang berjudul “The Rules of Sosiological Method”,Dukheim menjelaskan metode pengamatan fakta sosial. Dengan caraapa fakta sosial tersebut dijelaskan ?
4. Jelaskan perbedaan antara solidaritas mekanik dengansolidaritas organik !
5. Apa yang dimaksud dengan bunuh diri, dan sebutkan jenis-jenis bunuh diri menurut Durkheim !
TUGAS
1. Saat ini cukup banyak peristiwa-peristiwa bunuh diri yangterjadi di masyarakat. Cari dan kumpulkan 3 berita tentang bunuhdiri yang terdapat di surat kabar atau media massa lainnya!2. Berikan analisa anda terhadap persoalan-persoalan bunuh diritersebut dengan menggunakan teori “Suicidenya” E. Durkheim!
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik dan A.C. Van Der Leeden (Penyunting).1986. Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta.
De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan dan Metode.Terjemahan Adnan
Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
Gidden, Anthony, 1985. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, UI Press.Jakarta.
Johnson, D.P., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I. Gramedia.Jakarta.
Laeyendecker, 1994. Tata Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosiologi. Erlangga. Jakarta.
Ritzer, George. 1991. Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda, Rajawali.Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1985. Emile Durkheim. Aturan-Aturan Metode Sosiologis.Seri Pengenalan Sosiologi 2. Rajawali. Jakarta.
Veeger, K.J., 1986. Realitas Sosial. Gramedia. Jakarta.
BAB VII
SUMBANGAN PEMIKIRAN SOSIOLOGI DARI MAX WEBER
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Pokok bahasan pada bab ketujuh ini adalah menguraikan sumbanganpemikiran Max Weber yang berguna bagi pemikiran dan perkembanganilmu sosiologi. Materi yang akan dijelaskan diantaranya sejarahsingkat riwayat hidup Max Weber, konsepsi tindakan sosial dantipe-tipe tindakan sosial menurutWeber, pengertian verstehende, serta penjelasan etika protestandan spirit kapitalisme Weber yang cukup menggemparkan dan menjadibahan pergunjingan yang kontroversial bagi kehidupan ilmiah.
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pemikiran Max Weber tentang tindakan sosial dantipe-tipe tindakan
sosial.
2. Menjelaskan pemikiran Max Weber tentang verstehen.
3. Menjelaskan pemikiran Max Weber tentang etika protestandan spirit kapitalisme.
A.` Riwayat Hidup
Max Weber dilahirkan sebagai anak tertua dari tujuh bersaudarapada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia wilayah Jerman Timur.Weber meninggal pada 14 Juni 1920. Sosiologi lahir dalam kontekslatar belakang sosial masyarakat Jerman di mana dia berada, suatumasyarakat yang berada dalam masa transisi yang pesat dan penuhdengan kontradiksi internal. Selagi Weber hidup, Jerman mengalamitransisi dari suatu masyarakat yang sangat bersifat agraris kemasyarakat yang sangat bersifat industri dan perkotaan. Transisiini disertai oleh rasionalisasi yang semakin bertambah dalamsemua bidang kehidupan politik dan ekonomi. Seperti Durkheim,Weber juga aktif menerbitkan jurnal ilmu sosial di Jermanyaitu Archiv fur Sozialwissenschaften dan menjadi editornya. Jurnal inimenjadi jurnal sosial yang terkemuka di Jerman. Diantara sekianbanyak karyanya yang ditulis, adalah antara lain :
1. Wirtschaft und Gessellschaft (Economy and Society) 1920
2. Gessamelter Aufsatze zur Religionssoziologie (diterjemahkan Ephraim Fischoffdengan judul Sociology of Religion) 1921
3. The Protestan Ethic and The Spiritof Capitalism 1904
4. The Theory of Sosial and Economic Organization (terjemahan Talcott Parsons,1947)
5. From Max Weber; Essay in Sociology (terjemahan dan diedit H.H. Gerth and c.Wright Mills, 1946)
B. Tindakan Sosial Weber
Max Weber sangat tertarik pada maslah-masalah sosiologis yangluas mengenai struktur sosial dan masyarakat. Oleh karena itu iamendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yangberusaha memperoleh pemahaman interpretative mengenai tindakansosial agar dengan demikian bisa sampai ke suatu penjelasankausal mengenai arah dan akibat-akibatnya.
Atau bisa diartikan sosiologi sebagi ilmu tentang perilakusosial. Kata “ keprilakuan “ yang dipakai oleh Weber untukperbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif.Dimana si pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau didorongmotivasi. Artinya, yang menjadi inti dari sosilogi Weber bukanlahbentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilaiobyektif dari tindakan, melainkan semata-mata arti yang nyatadari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan-alasansubyektif. Adanya kemungkinan untuk memahami tindakan seseoranginilah yang membedakan sosiologi dari ilmu pengetahuan alam, yangmenerangkan peristiwa-peristiwa tetapi tidak memahami perbuatanobyek-obyek.
Kegagalan teoritisasi sosial memperhitungkan arti-arti subyektifindividu serta orientasinya, dapat membuatnya memasukkanperspektif dan nilainya sendiri dalam memahami perilaku oranglain. Pelaku individual mengarahkan kelakuannya pada penetapan-penetapan atau harapan-harapan tertentu yang berupa kebiasaanumum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan olehUndang-Undang.
Adapun beberapa klasifikasi perilaku sosial yang dibedakanmenjadi 4 tipe, yakni :
1. .Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainyasuatu tujuan.
2. Kelakuan yang berorientasi kepada suatu nilai, suatukeindahan (nilai estetis),
kemerdekaan(nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan)dan lain-lain.
3. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosiseseorang atau
disebut kelakuan afektif atau emosional.
4. Kelakuan yang menerima arahnya dari tradisi atautradisional.
Keempat tipe kelakuan tersebut sebagai tipe-tipe murni yangberarti bahwa konstruksi-konstruksi konseptual dari Weber untukmemahami dan menafsirkan realitas empiris yang beraneka ragam.
Tekanan yang diberikan Weber bersama dengan kaum historis Jermanberlawanan dengan strategi idealistik yang hanya menginterpretasiperilaku individu atu perkembangan sejarah suatu masyarakatmenurut asumsi-asumsi apriori yang luas. Tekanan yang bersifatempirik ini juga sejalan dengan positifisme, tetapi itu tidakberarti menghilangkan aspek-aspek subyektif dan hanyamemperhatikan aspek-aspek obyektif yang nyata.
Tindakan sosial itu harus dimengerti dalam hubungannya denganarti subyektif yang terkandung di dalamnya, orang perlumengembangkan suatu metode untuk mengetahui arti subyektif inisecara obyektif dan analistis. Namun bagi Weber, konseprasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenaiarti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandinganmengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.
Asumsi yang mendasari adalah pendekatan “obyektif” hanyaberhubungan dengan gejala yang dapat diamati (benda fisik/
perilaku nyata), sedangkan pendekatan “subyektif” berusaha untukmemperhatikan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidakdapat diamati seperti , perasaan individu, pikirannya dan motif-motifnya. Cara lain untuk melihat perbedaan antara obyektif dansubyektif dalam hubungannya dengan hal di mana pengalamansubyektif pribadi seseorang dimiliki bersama oleh suatu kelompoksosial.
Weber juga memberikan 4 tipe ideal dari tindakan sosial dalmsosiologinya, yaitu:
a. Rasionalitas instrumental (zweck rationalitat)
Merupakan tindakan sosial yang melandaskan diri kepadapertimbangan-
pertimbangan manusia yang rasional ketika menghadapilingkungan
eksternalnya.
b. Rasionalitas yang berorientasi nilai (Wert rationalitat)
Merupakan tindakan sosial yang rasional, namun yangmenyandarkan diri
kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu.
c. Tindakan tradisional
Merupakan tindakan sosial yang didorong dan berorientasikepada teradisi masa
lampau.
d. Tindakan afektif
Merupakan suatu tindakan sosial yang timbul karena doronganatau motivasi
yang sifatnya emosional.
Pola perilaku khusus yang sama sesuai dengan kategori-kategoritindakan sosial yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda,tergantung pada orientasi subyektif dari indifidu yang terlibat.Tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subyektif danpola-pola motifasional yang berkaitan. Untuk tindakan rasionalarti subyektif dapat ditangkap dengan skema alat tujuan (means-ends schema).
C. Verstehende Weber
Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal adalah yangmencerminkan tradisi idealis yaitu tekanannyapada verstehen (pemahaman subyektif) sebagai metode untukmemperoleh pemahaman yang paling valid mengenai arti-artisubyektif tindakan sosial atau disebut dengan introspeksi, yaitumemberikan seseorang pemahaman akan motifnya sendiri atau arti-arti subyektif dalam tindakan-tindakan orang lain.
Dengan kata lain verstehende adalah suatu metode pendekatan yangberusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitariperistiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak darigagasan bahwa setiap situasi sosial didukung oleh jaringan maknayang dibuat oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.
D. Tindakan Sosial dan Struktur Sosial
Tulisan-tulisan Weber secara metodologis menekankan pentingnyaarti-arti subyektif dan pola-pola motivasional, karyasubstansifnya meliputi suatu analisa struktural dan fungsional.Hal ini dapat dilihat tentang stratifikasi yang memiliki 3dimensi, studinya mengenai dominasi birokratik dan pengaruhnyadalam masyarakat modern. Serta ramalannya yang berhubungan dengankonsekuensi-konsekuensi jangka panjang dari pengaruh etikaProtestan.
Struktur sosial dalam perspektif Weber sebagai suatu istilah yangbersifat probabilistic dan bukan sebagai kenyataan empirik yangterlepas dari individu-individu. Suatu keteraturan sosial akandiarahkan ke suatu kepercayaan akan validitas keteraturan itu.Realitas akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebihbesar adalah tindakan sosial individu dengan arti-artisubyektifnya.
Karena orientasi subyektif individu mencakup kesadaran (tepatatau tidak) akan tindakan yang mungkin dan reaksi yang mungkindari orang lain, maka probabilitas-probabilitas ini mempunyaipengaruh yang benar-benar terhadap tindakan sosial, baik sebagaisesuatu yang bersifat memaksa maupun sebagai alat untukmempermudah satu jenis tindakan daripada lainnya.
E. Stratifikasi: Ekonomi, Budaya, dan Politik
Weber mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yangfundamental untuk kelas. Bagi Weber, kelas sosial terdiri darisemua mereka yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalambidang ekonomi, yaitu:
Sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yangmerupkan sumber dalam kesempatan hidup mereka.
Komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomiberupa kepemilikan benda-benda dan kesempata-kesempatan untukmemperolh pendapatan.
Kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja.
Bahwa kelas sosial berlandaskan pada dasar stratifikasi yangbersifat impersonal dan obyektif. Bagi Weber, kekuasaan adalahkemampuan untuk melaksanakan kehendak seseorang meskipun mendapattantangan dari orang lain. Partai politik merupakan organisasidimana perjuangan untuk memperoleh atau menggunakan kekuasaandinyatakan paling jelas ditingkat organisasi rasional. Strukturkekuasaan tidak harus setara dengan struktur otoritas.
F. Tipe Otoritas dan Bentuk Organisasi Sosial
Hubungan sosial dalam tipe keteraturan menujukkan keanekaragamanyang berbeda-beda. Weber mengidentifikasikan beberapa tipe yangberbeda, sehingga muncul organisasi dalam suatu struktur otoritasyang mapan, artinya suatu struktur dimana individu-individudiangkat, bertanggung jawab untuk mendukung keteraturan sosial.Kalau hubungan itu bersifat asosiatif (rasional) dan bukankomunal (emosional), meliputi sifat administratif, maka hubunganitu menunjukkan pada “Organisasi yang Berbadan Hukum”.
Namun bagi Weber yang utama adalah pada landasan keteraturansosial yang absah. Artinya bahwa keteraturan sosial dan pola-poladominasi yang berhubungan dengan itu diterima sebagai yang benar,baik oleh mereka yang tunduk pada suatu dominasi maupun merekayang dominan. Weber mengidentifikasikan 3 dasar legitimasi yangutama dalam hubungan otoritas, ketiganya dibuat berdasarkantipologi tindakan sosial. Masing-masing tipe berhubungan dengan
tipe struktur adminstratifnya sendiri dan dinamika sosialnyasendiri yang khusus. Tipe-tipe itu adalah :
1. Otoritas Tradisional
Tipe ini berlandaskan pada kepercayaan yang mapan pada tradisiyang sudah ada. Hubungan antar tokoh pemilik otoritas denganbawahannya adalah pribadi. Weber membedakan 3 otoritastradisional yaitu ; gerontokrasi, patriakalisme, danpatrimodialisme. Pengawasan dalam gerontokrasi berada pada tanganorang-orang tua dalam suatu kelompok, dalam patriarkalisme adapada satuan kekerabatan individu tertentu pewaris, dan dalamsistem otoritas patrimodial pengawasan oleh staf administrasiyang ada hubungan pribadi dengan pemimipinnya.
2. Otoritas Karismatik
Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimilikipemimpin sebagai pribadi. Menurut Weber, istilah ‘kharisma’ akanditerapkan pada mutu tertentu yang terdapat pada kepribadianseorang, yang berbeda dengan orang biasa yang dianugerahikelebihan. Kepatuhan para pengikut tergantung pada identifikasiemosional pemimpin itu sebagai pribadi. Orientasi kepemimpinankharismatik biasanya menantang status-quo kebalikan darikepemimpinan tradisional.
3. Otoritas Legal-Rasional
Otoritas yag didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat aturanyang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipeini erat kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Jiadi,
peraturan berhubungan dengan posisi baik sebagai atasan ataubawahan.
Otoritas legal-rasional diwujudkan dalam organisasi birokratis.Analisa Weber yang sangat terkenal mengenai birokratis adalahmembandingkan birokrasi dalam bentuk-bentuk administrasitradisional kuno yang didasarkan pada keluarga dan hubunganpribadi. Weber melihat birokrasi sebagai suatu bentuk organisasiyang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Dalammasyarakatnya sendiri, yang dikuasai ketika sedang berada dibawahbirokrasi militer dan birokrasi politik Prusia, ketika melihatperkembangan administrasi industri dan administrasi politiknasional di negara-negara Barat lainnya, ia mendapat kesan bahwaperkembangan dunia modern ditandai oleh semakin besarnya pengaruhbirokrasi.
Salah satu alasan pokok mengapa bentuk organisasi birokratis itumemiliki efisiensi adalah karena organisasi itu memiliki carayang secara sistematis menghubungkan kepentingan individu dengantenaga pendorong dengan pelaksana fungsi-fungsi organisasi. Inidilihat dari dari pelaksanaan fungsi organisasi yang secarakhusus menjadi kegiatan yang utama bagi pekerjaan pegawaibirokrasi.
Dalam mengembangkan dan meningkatkan bentuk organisasibirokratis, orang orang membangun bagi dirinya suatu “KandangBesi” dimana pada suatu saat mereka sadar bahwa mereka tidak bisakeluar lagi dari situ. Proses ini tidak hanya ada pada masyarakatkapitalis tetapi juga masyarakat sosialis. Menurut Weber bahwakelak akan muncul seorang pemimpin karismatik yang akan membuatdobrakan dari cengkraman mesin birokratis yang tanpa jiwa itu dantidak memberi tempat kepada perasaan dan cita-cita manusia.
G. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme
Analisa Weber dalam bukunya ‘The Protestant Ethic and The Spirit ofCapitalism” memiliki pengaruh ide-ide yang bersifat independendalam perubahan sejarah. Weber hidup di Eropa Barat yang sedangmenjurus ke arah pertumbuhan kapitalisme modern. Hal ini yangmendorongnya untuk mencari sebab hubungan antara tingkah lakuagama dan ekonomi, terutama di masyarakat Eropa Barat yangmayoritas beragama Protestan.
Adapun karakteristik dari sifat Spirit Kapitalisme Modern menurutWeber, yaitu:
1. Adanya usaha-usaha ekonomi yang diorganisir dan dikelolasecara rasional diatas landasan-landasan dan prinsip-prinsip ilmupengetahuan dan berkembangnya pemilikan atau kekayaan pribadi.
2. Berkembangnya produksi untuk pasar.
3. Produksi untuk massa dan melalui massa.
4. Produksi untuk uang.
5. Adanya Anthusiasme, etos dan efisiensi yang maksimal uangmenuntut.
Bahwa kapitalisme modern merupakan bersumber didalam agamaProtestan, yang hal ini merupakanWirischaflsethik. Spirit kapitalismemodern adalah Protestanisme yaitu merupakan aturan-aturan agamaprotestan tentang watak dan perilaku penganut-penganutnya didalamkehidupan sehari-hari.
Weber menunjukkan bahwa spirit protestan didalam etika praktissehari-hari. Menurut Weber etika protestan mewujudkan dirisebagai suatu pengertian tertentu tentang Tuhan, dimana Tuhandianggap sebagai Yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Penguasa
Dunia. Akibat konsepsi mengenai Tuhan tersebut, maka penganutagama protestan menganggap kesenangan adalah merupakan sesuatuyang tidak baik, sebaliknya untuk mengagungkan Tuhan orang harusberhemat.
Inti dari spirit kapitalisme modern adalah menganggap bahwabekerja keras adalah merupakan callingatau suatu panggilan sucibagi kehidupan manusia. Spirit protestan juga menganut pahambahwa membuat atau mencari uang dengan jujur merupakan aktivitasyang tidak berdosa. Itulah pembuktianpertama secara analitis dariWeber tentang hubungan antara spirit kapitalisme modern identikdengan spirit protestan, bahwa agama berpengaruh pada faktorekonomi.
Pembuktian kedua ditunjukkan Weber bahwa sejak zaman reformasi,negara-negara yang menganut agama protestan sebagai mayoritasadalah negara-negara yang lebih maju ekonominya.
Pembuktian ketiga Weber ditunjukkan bahwa di Jerman, penduduknyayang menganut agama protestan secara ekonomi lebih kaya dibandingdengan penganut agama non protestan.
Demikian Weber secara bertahap menunjukkan bahwa setiap sektedalam protestan itu nyatanya memiliki kecenderungan yang samadalam menunjang kehadiran Kapitalisme Modern, sehingga dengandemikian ia memperkuat pendapatnya dengan menstudi semua penganutProtestan di negara-negara Jerman, Inggris, Belanda, Amerika, danlain-lain sebagaimana ajaran agama itu mendorong kehadirankapitalisme.
RINGKASAN
Weber menaruh perhatian yang besar pada struktur sosial yangbesar dan perubahan sejarah. Gambaran dasarnya mengenai kenyataansosial yang dpusatkan pada tindakan individu yang dapatdimengerti hanya dalam arti-arti subyrktif yang dicerminkannya.Hal ini berbeda dengan pusat perhatian Durkheim pada fakta sosialyang mengatasi individu. Dalam perspektif Weber, pelbagaikategori struktur sosial didefinisikan dengan istilah-istilahyang bersifat probabilistik, tidak sebagai fakta obyektif, danstrategi analisa tipe ideal diberikan untuk memungkinkan suatuanalisa perbandingan mengenai tipe-tipe struktur sosial yangberbeda atau tipe orientasi budaya yang berbeda. Analisa Webermengenai etika protestan serta pengaruhnya dalam meningkatkanpertumbuhan kapitalisme menunjukkan pengertiannya mengenaipentingnya kepercayaan agama serta nilai dalam membentukmotivasional individu serta tindakan ekonominya. Selain itu juga,Weber telah memberikan corak tersendiri dengan verstehendesoziologienya, yang dalam perkembangan selanjutnya banyak dijadikanmodel dalam analisa-analisa sosiologi oleh sosiolog-sosiologmodern masa kini.
LATIHAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan verstehende sociologie Weber!
2. Inti dari sosiologi Weber adalah tindakan sosial, jelaskanmaksudnya serta sebutkan
tipe-tipe tindakan sosial Weber!
3. Sebutkan dan jelaskan 3 tipe otoritas yang dibuat berdaarkantipologi tindakan sosial
Weber!
4. Jelaskan 3 pembuktian analitis yang dilakukan Weber yangmenjelaskan hubungan
antara spirit kapitalisme modern dengan spirit protestan!
6. Sebutkan 5 karakteristik dari spirit kapitalisme modernmenurut Weber!
TUGAS
1. Buatlah makalah tentang rangkuman kritik-kritik yangdiberikan oleh para ahli
sosiologi terhadap karya-karya Weber, khususnya padakaryanya yang paling
kontroversial yang berjudul “The Protestant Ethic andThe Spiritof Capitalism”.
2. Carilah rujukannya sesuai dengan rujukan pustaka yang telahdiberikan.
3. Diskusikan di kelas !
DAFTAR PUSTAKA
De Haan, J.Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan dan Metode.Terjemahan Adnan Sjamni. Yayasan Pembangunan Jakarta.
Johnson, D.P., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I. Gramedia.Jakarta
Giddens, Anthony. 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. UI Press.Jakarta
Laeyendecker, L., 1994. Tata, Perubahan, dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman, 1986. Pengantar ke arah Sejarah dan TeoriSosiologi. Erlangga.
Jakarta.
Soekanto,Soerjono, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
----------------------, 1985. Max Weber. Konsep-Konsep Dasar DalamSosiologi. Seri Pengenalan Sosiologi I. Rajawali. Jakarta.
Veeger, K.J., 1986. Realitas Sosial. Gramedia. Jakarta.
BAB VIII
PARADIGMA SOSIOLOGI
PENDAHULUAN
Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Sosiologi lahir di tengah-tengah persaingan pengaruh antarafilsafat dan psikologi, oleh karena itu tak mengherankan kalaupengaruh kedua cabang ilmu ini masih saja terasa sampai saat ini.Emile Durkheim adalah orang pertama yang mencoba melepaskansosiologi dari dominasi kedua kekuatan yang mempengaruhinya itu.
Durkheim terutama berusaha melepaskan sosiologi dari alamfilsafat positif Auguste Comte untuk kemudian meletakkansosiologi ke atas dunia empiris. Dua karyanya yang besar danberpengaruh itu semula disusunnya dalam rangka usaha untukmelepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat filsafat Comte danHerbert Spencer. Masing-masing adalah Suicide (1951) dan The Rule ofSociological Method (1964).
Suicide adalah hasil karya Durkheim yang didasarkan atas hasilpenelitian empiris terhadap gejala bunuh diri sebagai suatufenomena sosial. Sedangkan The Rule Of Sosiological Method berintikankonsep-konsep dasar tentang metode yang dapat dipakai untukmelakukan penelitian empiris dalam lapangan sosiologi,
Auguste Comte mendapat kehormatan sebagai bapak sosiologi melaluikarya filsafat positifnya. Ia merupakan orang pertama yangmengusulkan pemberian nama sosiologi terhadap keseluruhanpengetahuan manusia tentang kehidupan bermasyarakat. Namundemikian, Durkheim menempati posisi yang sangat penting puladalam mengembangkan sosiologi modern sebagai disiplin yangberdiri sendiri. Peranan Durkheim yang terpenting terletak padausahanya dalam merumuskan objek studi sosiologi.
Durkheim adalah orang pertama yang menunjukkan fakta sosial(social fact) sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari olehdisiplin sosiologi. Fakta sosial dinyatakannya sebagai barangsesuatu yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaranpenyelidikan dari filsafat. Menurut Durkheim, fakta sosial takdapat dipelajari dan difahami hanya dengan melalui kegiatanmental murni atau melalui proses mental yang disebut pemikiranspekulatif.
Untuk memahaminya diperlukan suatu kegiatan penelitian empiris,sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari objek
studinya. Dengan menerangkan tentang obyek penyelidikan sosiologiinilah Durkheim berusaha untuk melepaskan sosiologi daripengaruh filsafat positif Comte dan Spencer yang mengarahkansosiologi kepada dunia ide, yang hanya dapat dipahami melaluipemikiran spekulatif. Dengan meletakkan fakta sosial sebagaisasaran yang harus dipelajari oleh sosiologi, berarti menempatkansosiologi sebagai suatu disiplin yang bersifat empiris danberdiri sendiri terlepas dari pengaruh filsafat.
Dalam perkambangan selanjutnya setelah terlepas dari pengaruhfilsafat dan psikologi, sosiologi mulai memasuki arena pergulatanpemikiran yang bersifat interen di kalangan teoritisnya sendiri.Pergulatan yang bersifat interen ini hingga sekarang masih sajaberlangsung. Perkembangan sosiologi ditandai dan tercermin dariadanya berbagai paradigma di dalamnya.
Setelah mengikuti perkuliahan dan mempelajari tentang paradigmasosiologi, mahasiswa diharapkan dapat :
1. menjelaskan pengertian paradigma sosiologi
2. menjelaskan sebab timbulnya berbagai paradigma sosiologi
3. menjelaskan 3 paradigma sosiologi yaitu paradigma faktasosial, paradigma definisi
sosial, paradigma perilaku sosial.
4. menjelaskan hubungan antara paradigma yang satu dengan yanglainnya.
A. Latar Belakang Munculnya Paradigma Sosiologi
Istilah paradigma ini pertama kali diperkenal oleh Thomas Kuhndalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (1962), intinyamenyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlahterjadi secara kumulatif tetapi secara revolusi. Ia berpendapatbahwa sementara kumulatif memainkan peranan dalam perkembanganilmu pengetahuan, maka sebenarnya perubahan utama dan pentingdalam ilmu pengetahuan itu terjadi sebagai akibat dari revolusi.
Model perkembangan ilmu pengetahuan menurut Kuhn adalah sebagaiberikut :
Parad I – Normal Science – Anomalies – Crisis – Revolusi – ParadII
Kuhn melihat bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentudidominasi oleh satu paradigma tertentu, yakni suatu pandanganyang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (Subjectmatter) dari suatu cabang ilmu.
Normal Science adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan, dimana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedangberpengaruh. Namun para ilmuwan tidak dapat mengelakkanpertentangan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi(anomalies) karena tidak mampunya paradigma I memberikanpenjelasan secara memadai terhadap persoalan yang timbul. Selamapenyimpangan memuncak, suatu krisis akan timbul dan paradigma itusendiri mulai disangsikan validitasnya. Bila krisis sudahsedemikian seriusnya maka suatu revolusi terjadi dan paradigmayang baru akan muncul sebagai yang mampu menyelesaikan persoalanyang dihadapi oleh paradigma sebelumnya. Jadi dalam peroderevolusi telah terjadi suatu perubahan yang besar dalam ilmupengetahuan. Paradigma yang lama telah mulai menurun pengaruhnya,digantikan oleh paradigma baru yang lebih dominan.
Dalam perkembangan selanjutnya Masterman mencoba mereduksi konsepparadigma Kuhn menjadi tiga tipe, yakni ; Paradigma metafisik(metaphisical paradigm), paradigma sosiologis (Sosiological paradigm) danparadigma konstrak (costruct paradigm). Robert Friedrichs adalahorang pertama yang mencoba merumuskan pengertian Paradigma inisebagai upaya menganalisa perkembangan sosiologi, ia merumumuskanparadigma “ sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplinilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yangsemestinya dipelajarinya. (a fundamental image a discipline has of its subjectmatter).
Lebih jauh George Ritzer, dengan mensintesakan pengertianparadigma yang dikemukakan oleh Kuhn, Masterman dan Friedrichs,secara lebih jelas bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasardari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yangsemestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan(discipline).
Persoalannya sekarang adalah mengapa terjadi perbedaan antarkomunitas atau sub-komunitas dalam suatu cabang ilmu, khususnyadalam Sosiologi, George Ritzer mengungkapkan tiga faktor, yakni :
1. Karena dari semula pandangan filsafat yang mendasari pemikiranilmuwan tentang
apa yang semestinya menjadi subtansi itu berbeda, dengankata lain diantara
komunitas-komunitas ilmuwan itu terdapat perbedaan pandanganyang mendasar
tentang pokok persoalan apa yang semestinya dipelajari.
2. Sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbedaitu maka teori-teori
yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing komunitasitu berbeda, pada
masing-masing komunitas ilmuwan berusaha bukan sajamempertahankan kebenaran
teorinya tetapi juga berusaha melancarkan kecaman terhadapkelemahan teori dari
komunitas ilmuwan lain.
3. Metode yang dipergunakan untuk memahami substansi ilmu itujuga berbeda.
Ritzer menilai bahwa sosiologi itu terdiri atas kelipatanbeberapa paradigma (multiple paradigm), pergulatan pemikiransedemikian itu dijelaskan dalam uraian tentang masing masingparadigma dibawah ini.
B. Paradigma Fakta Sosial
Exemplar paradigma fakta sosial ini diambil dari kedua karyaDurkheim. Durkheim meletakkan landasan paradigma fakta socialmelalui karyanya The Rules of Sociological Method (1895) dan Sucide (1897).Durkheim melihat sosiologi yang baru lahir itu dalam upaya untukmemperoleh kedudukan sebagai cabang ilmu social yang berdirisendiri, tengah berada dalam ancaman bahaya kekuatan pengaruh duacabang ilmu yang telah berdiri kokoh yakni filsafat danpsikologi. Menurut Durkheim, riset empiris adalah yang membedakanantara sosiologi dengan filsafat. Kenyataan tentang hidupbermasyarakat nyata adalah sebagai obyek studi sosiologi menurutDurkheim, bukan ide keteraturan masyarakat (social order) yang lebihbernilai filosofis.
Fakta sosial menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi,fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu (thing) yang
berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikandari seluruh ilmu pengetahuan. Menurut Durkheim fakta sosialtidak dapat dipelajari melalui introspeksi, fakta sosial harusditeliti dalam dunia nyata. Lebih jauh Durkheim menyebutkan faktasosial terdiri atas dua macam :
1. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapatdisimak, ditangkap dan
diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalahbagian dari dunia nyata
(external world) contohnya arsitektur dan norma hukum.
2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata(external), fakta sosial
jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjectiveyang hanya dapat muncul
dari dalam kesadaran manusia, contohnya egoisme, altrusismedan opini.
Fakta Sosial yang berbentuk material lebih mudah difahami,misalnya norma hukum jelas merupakan barang sesuatu yang nyataada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu, begitu pulaarsitektur.
Dalam paradigma ini pokok persoalan yang menjadi pusat perhatianadalah fakta-fakta sosial yang pada garis besarnya terdiri atasdua tipe, masing-masing struktur sosial (social structure) danpranata sosial (social institution). Norma-norma dan pola nilai inibiasa disebut dengan pranata, sedangkan jaringan hubungan sosialdimana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir sertamelalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompokdapat dibedakan, sering diartikan sebagai struktur sosial. Dengan
demikian struktur sosial dan pranata sosial inilah yang menjadipokok persoalan persoalan penyelidikan sosiologi menurutparadigma fakta sosial.
Ada empat teori yang tergabung dalam paradigma fakta sosial iniseperti teori fungsionalisme structural, teori konflik, teorisystem dan teori sosiologi makro, dimana dua teori yang palingdominan didalamnya yakni (1) Teori Fungsionalisme Struktural dan(2) Teori Konflik.
Metode observasi tidak cocok untuk studi fakta social. Faktasocial tidak dapat diamati secara langsung, hanya dapatdipelajari melalui pemahaman (interpretative understanding). Penganutparadigma fakta sosial cenderung mempergunakan metode kuesionerdan interview dalam penelitian empiris mereka. Namun, penggunaanmetode kuesioner dan interview oleh para penganut paradigma faktasocial ini mengandung ironi karena kedua metode ini tidak mampumenyajikan secara sungguh-sungguh bersifat fakta social.Informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner dan interview banyakmengandung unsure subyektifitas dari si informan.
1. Teori Fungsionalisme Struktural
Teori Fungsionalisme Struktural menekankan kepada keteraturan danmengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsimanifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakansuatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen
yang saling berkitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahanpula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwasetiap struktur dalam sistem sosial, adalah fungsional terhadapyang lain. Sebaliknya kalu tidak fungsional maka struktur itutidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.
Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semuaperistiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi sutumasyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalammasyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori FungsionalismeStruktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana caramenyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbanganRobert K. Merton sebagai penganut teori ini berpendapat bahwaobjek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti; peranansosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasikelompok, pengendalian sosial.
Penganut teori fungsional menganggap segala pranata sosial yangada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artianpositif dan negative. Merton mengistilahkan ‘fungsional dandisfungsional’. Contohnya; perbudakan dalam sistem sosial AmerikaSerikat lama khususnya bagian selatan. Perbudakan jelasfungsional bagi masyarakat Amerika Serikat kulit putih. Karenasistem tersebut dapat menyediakan tenaga buruh yang murah,memajukan ekonomi pertanian kapas serta menjadi sumber statussosial terhadap kulit putih. Tetapi sebaliknya, perbudakanbersifat disfungsi. Sistem perbudakan membuat orang sangattergantung kepada sistem ekonomi agraris sehingga tidak siapuntuk memasuli industrialisasi.
Dari pendapat Merton tentang fungsi, maka ada konsep barunyayaitu mengenai sifat dari fungsi. Merton membedakan atasfungsi manifest dan fungsi latent. Fungsi manifest adalah fingsi yangdiharapkan(intended) atau fungsional. Fungsi manifest dari institusi
perbudakan di atas adalah untuk meningkatkan produktifitas diAmerika Selatan. Sedangkan fungsi latent adalah sebaliknya yaitufungsi yang tidak diharapkan, sepanjang menyangkut contoh diatas fungsai latentnya adalah menyediakan kelas rendah yangluas.
Penganut Teori Fungsionalisme Struktural sering dituduhmengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam teori-teori mereka. Karena terlalu memberikan tekanan pada keteraturan(order) dalam masyarakat dan mengabaikan konflik dan perubahansosial, mengakibatkan golongan fungsional ini dinilai sebagaisecara ideologis sebagai konservatif. Bahkan ada yang menilaigolongan fungsional ini sebagai agen teoritis dari status quo.
Hal penting yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat menurutkacamata teori fungsional senantiasa berada dalam keadaaanberubah secara berangsur-angsur dengan tetap memeliharakeseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada,fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula dengan institusiyang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinanserta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalamkondisi dinamika dalam keseimbangan.
2. Teori Konflik
Teori Konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secaralangsung terhadap teori fungsionalisme structural. Tokoh utamateori ini adalah Ralp Dahrendorf. Proposisi yang dikemukakan olehpenganut Teori Konfik bertentangan dengan proposisi yangdikemukakan oleh penganut Teori Fungsionalisme Struktural.Perbedaan proposisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :
Menurut teori Fungsionalisme Struktural :
1. Masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerakdalam kondisi
keseimbangan
2. Setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukunganterhadap stabilitas.
3. Anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma,nilai-nilai dan
moralitas umum.
4. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi latent,fungsi manifest, dan
keseimbangan (equilibrium)
Menurut Teori Konflik :
1. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yangditandai oleh
pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya.
2. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap desintegrasisocial.
3. Keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanyatekanan atau
pemaksaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.
4. Konsep-konsep sentral Teori Konflik adalah wewenang danposisi, keduanya
merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan danwewenang secara tidak merata
tanpa terkecuali menjadi faktor yang menentukan konfliksosial secara sistematis.
Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagaiposisi dalam
masyarakat.
Menurut Dahrendorf kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkanindividu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karenawewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tundukterhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikianmasyarakat disebut sebagai Dahrendorf sebagai persekutuan yangterkoordinasi secara paksa (imferatively coordinated associations).
Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antarapenguasa dengan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selaluterdapat dua golongan yang saling bertentangan. Pertentangan ituterjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusahamempertahankan status quo sedangkan golonganyang dikuasaiberusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangankepentingan ini selalu ada di setiap waktu dan dalam setiapstruktur.
Menurut Dahrendorf terdapat mata rantai antara konflik danperubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin ke arah perubahandan pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibatmelakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalamstruktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat makaperubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalaukonflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahanstruktural akan efektif.
Pierre van Berghe (1963) mengemukakan empat fungsi konflik;
1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi.
4. Fungsi komunikasi.Sebelum konflik, kelompok tertentu mungkintidak mengetahuai
posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batasantara kelompok menjadi
lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di manamereka berada dan
karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untukbertindak dengan lebih
tepat.
Kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa teori konflikini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yangmemang ada dalam masyarakat disamping konflik itu sendiri.Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikannorma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjaminterciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat sepertitidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Sepertimembenarkan Hobbes yang mengatakan : bellum omnium contraomnes (perang antara semua melawan semua).
C. Paradigma Definisi Sosial
Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologisebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungansosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan
individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau artisubyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda matiatau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakanorang lain bukan merupakan tindakan sosial. Tindakan seseorangmelempar batu ke sungai bukan tindakan social. Tapi tindakantersebut dapat berubah menjadi tindakan social kalau denganmelemparkan batu tersebut menimbulkan reaksi dari orang lainseperti mengganggu seseorang yang sedang memancing.
Secara definitif Weber merumuskan Sosiologi sebagai ilmu yangberusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretativeunderstanding) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuksampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandungdua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial, kedua konseptentang penafsiran dan pemahaman.Konsep terakhir ini inimenyangkut metode untuk menerangkan yang pertama.
Konsep pertama tentang tindakan sosial yang dimaksud Weber dapatberupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain.Juga dapat berupa tidakan yang bersifat ‘membatin’ atau bersifatsubyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif darisituasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengansengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atauberupa persetujuan pasif dalam situasi tertentu.
Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antarhubungan sosial sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokokyang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu :
1. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yangsubyektif. Ini
meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata dan yang bersifat, membatin sepenuhnya danbersifat subyektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi,tindakan yang sengaja
diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapaindividu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarahkepada orang lain itu.
Untuk mempelajari tindakan sosial itu Weber menganjurkan melaluipenafsiran dan pemahaman (interpretative understanding), atau menurutterminology Weber disebut dengan verstehen. Bila seseorang hanyaberusaha meneliti perilaku (behavior) saja, dia tidak akanmeyakini bahwa perbuatan itu mempunyai arti subyektif dandiarakan kepada orang lain. Maka yang perlu dipahami adalah motifdari tindakan tersebut. Menurut Weber ada 2 cara memahami motiftindakan yaitu : 1) kesungguhan, 2) mengenangkan dan menyelamipengalaman si actor. Peneliti menempatkan dirinya dalam posisi siactor serta mencoba memahami sesuatu yang dipahami si actor.
Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannyadalam empat tipe, dimana semakin rasional tindakan sosial itusemakin mudah dipahami, empat tipe itu adalah :
a. Zwerk rational, yakni tindakan sosial murni,. Dalam tindakan iniaktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untukmencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itusendiri.
b. Werktrational action, dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapatmenilai apakah cara-cara yang dipilinya itu merupakan yang palingtepat untuk mencapai tujuan yang lain. Dalam tindakan ini memangantara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukaruntuk dibedakan, namun tindakan ini rasional karena pilihanterhadap cara-cara sudah menentukan tujuan yang diinginkan.
c. Affectual action, adalah tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhioleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan inisukar dipahami kurang atau tidak rasional.
d.Traditional action, tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja.
Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya merupakantanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karenaitu tidak termasuk dalam jenis tindakan yang penuh arti yangmenjadi sasaran penelitian sosiologi.
Konsep kedua dari Weber adalah konsep tentang antar hubungansocial (social relationship). Hubungan sosial didefinsikan sebagaitindakan yang beberapa orang aktor yang berbeda-beda, sejauhtindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkankepada tindakan orang lain. Tidak semua kehidupan kolektifmemnuhi syarat sebagai antar hubungan sosial, dimana tidak adasaling penyesuaian (mutual orientation) antara orang yang satu denganyang lain meskipun ada sekumpulan orang yang diketemukanbersamaan.
Ada tiga teori yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosialini, yakni : Teori aksi (action theory), teori interaksionismesimbolik (symbolic interactionism) dan teori fhenomenologi(fhenomenology). Ketiga teori ini mempunyai kesamaan ide dasarnyayang berpandangan bahwa manusia adalah aktor yang aktif
dan kreatif dari realitas sosialnya. Artinya tindakan manusiatidak sepenuhnya ditentukan norma-norma, kebiasaan-kebiasaan,nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya itu tercakup dalamfakta sosial. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untukbertindak di luar batas kontrol dari fakta sosial.
Di sini pula terletak perbedaan yang sebenarnya antara paradigmadefinisi sosial dengan paradigma fakta sosial. Paradigma faktasosial menganggap bahwa perilaku manusia dikontrol oleh berbagainorma, nilai-nilai serta sekian alat pengendalian sosial lainnya.Sedangkan paradigma perilaku sosial (social behavior) adalah bahwayang terakhir ini melihat tingkahlaku manusia senantiasadikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuasaan ataukemungkinan penggunaaan kekuatan (re-enforcement).
Penganut paradigma Definisi Sosial cenderung menggunakan metodeobservasi dalam penelitian mereka. Alasannya adalah untuk dapatmemahami realitas intrasubjective dan intersubjective dari tindakan sosialdan interaksi sosial. Namun kelemahan teknik observasi adalahketika kehadiran peneliti di tengah-tengah kelompok yangdiselidiki akan mempengaruhi tingkah laku subyek yang diselidikiitu. Lagipula tidak semua tingkah laku dapat diamati, sepertitingkah laku seksual misalnya.
1. Teori Aksi (Action Theory)
Tokoh-tokoh Teori Aksi di antaranya Florian Znaniecki, The Methodof Sociology (1934) dan Social Actions(1936), Robert Mac Iver,
Sociology: Its Structure and Changes (1931), Talcot Parsons; The Structureof Social Action (1937).
Beberapa asumsi dasar fundamental dari Teori Aksi dikemukakanHinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsonsebagai berikut ;
a. Tidakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagaisubyek dan dari situasi
ekternal dalam posisinya sebagai obyek.
b. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untukmencapai tujuan–tujuan
tertentu, jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur,metode serta
perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuantersebut.
d. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisiyang tak dapat diubah
dengan sendirinya.
e. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakanyang akan, sedang
dan yang telah dilakukannya.
f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moraldiharapkan timbul pada saat
pengambilan keputusan.
g. Studi mengenai antar hubungan social memerlukan pemakaianteknik penemuan
yang bersifat subjektif seperti metode verstehen,imajinasi, sympathetic
reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri (vicariousexperience).
Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa tindakan sosialmerupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilankeputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untukmencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, yang kesemua itudibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalambentuk norma-norma, ide-de dan nilai-nilai sosial. Di dalammenghadapi yang yang bersifat kendala baginya itu, aktormempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemauan bebas.
2. Teori Interaksionisme Simbolik
Tokoh-tokoh teori Interaksionisme Simbolik adalah John Dewey,Charles Horton Cooley, G.H. Mead. Ide dasar teori ini bersifatmenentang behaviorisme radikal yang dipelopori oelh JB Watson.Hal ini tercermin dari gagasan tokoh sentral teori ini yakni G.H.Mead yang bermaksud untuk membedakan teori interaksionismesimbolik dengan teori behavioralisme radikal.
Behaviorisme Radikal berpendirian bahwa perilaku individu adalahsesuatu yang dapat diamati. Mempelajari tinglahlaku (behavior)manusia secara obyektif dari luar. Penganut behaviorismecenderung melihat perilaku manusia itu seperti perilaku binatangdalam arti hanya semata-mata merupakan hasil rangsangan dariluar.
Mead dari Interaksionisme Simbolik, mempelajari tindakan sosialdengan mempergunakan teknik intropeksi untuk dapat mengetahuisesuatu yang melatarbrlakangi tindakan sosial tu dari sudut aktordengan pengggunaan bahasa serta kemampuan belajar yang tidakdimiliki oleh binatang.
Menurut teori Interaksionisme Simbolik , fakta sosial bukanlahsesuatu yang mengendalikan dan memaksa tindakan manusia. Faktasosial ditempatkan dalam kerangka simbol-simbol interaksimanusia. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial danparadigma perilaku sosial ( social behavior) yang tidak mengakuiarti penting kedudukan individu. Padahal kenyataannya manusiamampu menciptakan dunianya sendiri.
Bagi paradigma fakta sosial, individu dipandangnya sebagai orangyang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dariluar dirinya sendiri seperti kultur, norma, dan peranan-peranansosial. Sehingga pandangan ini cenderung mengingkari kenyataanbahwa manusia mempunyai kepribadian sendiri. Sedangkan paradigmaperilaku sosial melihat tingkah laku.
Beberapa asumsi tori Interaksionisme Simbolik menurut ArnoldRose :
1. Manusia hidup dalam suatu lingkungan simbol-simbol. Manusiamemberikan
tanggapan terhadap simbol-simbol melalui proses belajar danbergaul dalam
masyarakat. Kemampuan manusia berkomunikasi, belajar, sertamemahami simbol-
simbol itu merupakan kemampuan yang membedakan manusia denganbinatang.
2. Melalui simbol-simbol manusia berkemampaun menstimulir oranglain dengan cara
yang mungkin berbeda dari stimuli yang diterimanya dari oranglain.
3. Melalui komunikasi simbol-simbol dapat dipelajari sejumlahbesar arti dan nilai-nilai,
dan karena itu dapat dipelajari cara-cara tindakan oranglain.
4. Terdapat satuan-satuan kelompok yang mempunyai simbol-smbolyang sama., atau
akan ada simbol kelompok.
5. Berfikir merupakan proses pencarian kemungkinan yang bersifatsimbolis dan untuk
mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menaksirkeuntungan dan kerugian
relative menurut individual, di mana satu diantaranya dipilihuntuk dilakukan.
Kesimpulan utama dari teori Interksionisme Simbolik bahwakehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dankomunikasi antara individu dan antar kelompok dengan menggunakansimbol-simbol yang dipahaminya melalui proses belajar. Tindakanseseorang dalam proses interkasi bukan semata-mata tanggapan yangbersifat langsung terhadap stimulus yang datang darilingkungannya, tetapi melalui proses belajar.
3. Teori Fenomenologi (Phenomenological Sociology)
Ada empat unsur pokok dari teori Fenomenologi Yaitu :
1. Perhatian terhadap aktor dengan memahami makna tindakan aktoryang ditujukan
kepada dirinya sendiri.
2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau pokokdan kepada sikap
yang wajar atau alamiah (natural attitude). Teori ini jelas bukanbermaksud fakta
sosial secara langsung. Tetapi proses terbentuknya faktasosial itulah yang menjadi
pusat perhatiannya. Artinya bagaimana individu ikut sertadalam proses
pembentukan dan pemeliharaan fakta-fakta sosial yang memaksamereka itu.
3. Memusatkan perhatian kepada masalah makro. Maksudnyamempelajari proses
pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkatinteraksi tatap muka
untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi tertentu.
4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan.Berusaha memahami
bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dandipelihara dalam pergaulan
sehari-hari. Norma-norma dan aturan-aturan yang mengendalikantindakan manusia
dan yang memantapkan struktur sosial dinilai sebagai hasilinterpretasi si aktor
terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya.
D. Paradigma Perilaku Sosial
Tokoh pendekatan behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yangmemegang peranan penting dalam pengembangan sosiologi behavior.Skinner mengkritik obyek studi paradigma fakta sosial dan
definisi sosial bersifat mistis tidak konkrit relistis. Obyekstudi sosiologi yang konkrit realistis adalah perilaku manusiayang nampak serta kemungkinan perulangannya (behavior of man andcontingencies of reinforcement).
Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiaannya kepadahubungan antara individu dengan lingkungannya, dimana lingkunganitu terdiri atas : a) bermacam-macam obyek social dan b)bermacam-macam obyek non sosial. Prinsip yang menguasai antarhubungan individu dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsipyang menguasai hubungan antara individu dengan obyek nonsosial. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalahtingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya denganfaktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atauperubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadaptingkahlaku.
Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memilikikebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat dasarstimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi tingkah laku manusialebih bersifat mekanik. Beda dengan paradigma definisi sosialyang menganggap aktor adalah dinamis dan mempunyai kekuatankreatif di dalam proses interaksinya. Ada dua teori yang termasukke dalam paradigma Perilaku Sosial, yakni Teori BehavioralSociology dan Teori Exchange.
Paradigma ini lebih banyak menggunakan metode eksprimen dalampenelitiannya. Keutamaan metode eksprimen ini adalah memberikankemungkinan terhadap penelitian untuk mengontrol dengan ketatobyek dan kondisi di sekitarnya. Metode ini memungkinkan pulauntuk membuat penilaian dan pengukuran dengan tingkat ketepatanyang tinggi terhadap efek dari perubahan-perubahan tingkahlakuaktor yang ditimbulkan dengan sengaja di dalam eksprimen.Walaupun eksprimen merupakan suatu metode penelitian langsungyang agak baik terhadap tingkahlaku aktor, namun peneliti masih
dituntut untuk mengamati perilaku lanjut aktor yang sedangditeliti.
1. Teori Behavioral Sociology
Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibatdari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengantingkah laku aktor. Akibat tingkah laku diperlakukan sebagaivariabel independen. Ini berarti teori ini berusaha menerangkantingkah laku yang terjadi melalui akibat-akibat yangmeengikutinya. Konsep dasar teori ini yang menjadi pemahamannyaadalah “reinforcement” yang dapat diartikan sebagai ganjaran(reward). Tak ada sesuatu yang melekat dalam objek yang dapatmenimbulkan ganjaran. Sesuatu ganjaran yang tak membawa pengaruhterhadap aktor tidak akan diulang. Contohnya tentang makanansebagai ganjaran yang umum dalam masyarakat. Tetapi bila sedangtidak lapar maka makan tidak akan diulang. Bila si aktor telahkehabisan makanan, maka ia akan lapar dan makanan akan berfungsisebagai pemaksa.
2. Teori Exchange
Tokoh utama teori ini adalah George Homan, teori ini dibangundengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial,yang menyerang ide Durkheim secara langsung dari tiga jurusan,yakni :
a) pandangan tentang emergence. Selama berlangsung interaksitimbul fenomena baru
yang tidak perlu proposisi baru pula untuk menerangkan sifatfenomena baru yang
timbul tersebut.
b) pandangan tentang psikologi. Sosiologi dewasa ini sudahberdiri sendiri lepas dari
pengaruh psikologi.
c. Metode penjelasan Durkheim. Fakta sosial tertentu selalumenjadi penyebab
fakta sosial yang lain yang perlu dijelaskan melaluipendekatan perilaku
(behavioral), yang bersifat psikologi.
Keseluruhan materi Teori Exchange secara garis besarnya dapatdikembalikan pada 5 proposisi George Homan yaitu :
1. Jika tingkahlaku tingkahlaku atau kejadian yang sudah lewatdalam konteks stimulus
dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besarkemungkinan tingkahlaku atau
kejadian yang mempunyai hubungan dan stimulus dan situasiyang sama akan terjadi
atau dilakukan.
2. Menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima. Makin seringdalam peristiwa tertentu
tingkahlaku seseorang memberikan ganjaran terhadaptingkahlaku orang lain, makin
sering pula orang lain itu mengulang tingkahlakunya itu.
3. Memberikan arti atau nilai pada tingkahlaku yang di arahkanoleh orang lain terhadap
aktor. Makin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkahlakuorang lain yang ditujukan
kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering ia akanmengulangi
tingkahlakunya itu.
4. Makin sering orang menerima ganjaran atas tindakannya dariorang lain, makin
berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukanberikutnya.
5. Makin dirugikan seseorang dalam dalam hubungannya denganorang lain, makin
besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi.
RINGKASAN
Paradigma adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadipokok persoalan (subject matter)disiplin tertentu. Paradigma adalahkesatuan konsensus yang terluas dalam satu disiplin yangmembedakan antara komunitas ilmuwan (sub komunitas) yang satudengan yang lain. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinyaperbedaan paradigmatik dalam sosiologi ; 1) perbedaan pandanganpandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masingsosiolog tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajarisosilogi. 2) Akibat logis yang pertama, maka teori-teori yangdibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwanberbeda. 3) Metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkansubstansi disiplin inipun berbeda. Atas dasar perbedaan pandanganmengenai apa yang semestinya dipelajari dalam sosiologi itulahterdapat tiga paradigma sosiologi dewasa ini yaitu, paradigmafakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilakusosial.
Paradigma Fakta Sosial menempatkan fakta sosial menjadi pokokpersoalan penyelidikan sosiologi. Bahwa fakta sosial tidak dapatdipelajari dengan introspeksi melainkan harus diteliti secaraempiris. Dalam penelitiannya penganut paradigma ini cenderungmenggunakan metode interview dan kuesioner. Exemplar paradigmafakta social adalah karya Durkheim Suicide dan The Rule of SociologicalMethod.Dalam paradigma ini pokok persoalan yang menjadi pusatperhatian adalah fakta-fakta sosial yang pada garis besarnyaterdiri atas dua tipe, masing-masing struktur sosial (socialstructure) dan pranata sosial (social institution). Teori yang tergabungdalam paradigma ini adalah teori fungsionalisme structural, teorikonflik, teori system, dan sosiologi makro.
Paradigma Definisi Sosial menempatkan pokok persoalan sosiologiadalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatuaksi serta interaksi sosial. Exemplar paradigma ini adalah karyaMax Weber tentang tindakan sosial (social action) Paradigma DefinisiSosial secara pasti memandang manusia sebagai orang yang aktifmenciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Ada tiga teori yangtermasuk dalam paradigma ini yaitu : teori aksi sosial, teoriinteraksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Metode yangumum digunakan penganut paradigma definisi sosial ialahobservasi.
Paradigma Perilaku Sosial menempatkan pokok persoalan sosiologiialah perilaku dan perulangannya. Bagi paradigma ini perilakusosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. Ada dua toeriyang termasuk dalam paradigma ini yaitu teori sosiologibehavioral dan teori pertukaran (exchange theory). ParadigmaPerilaku Sosial lebih banyak menggunakan metode eksprimen dalampenelitiannya.
LATIHAN
1. Jelaskan model perkembangan ilmu pengetahuan menurut ThomasKuhn!
2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaanparadigmatik dalam
sosiologi!
3. Jelaskan Paradigma Fakta Sosial melalui eksemplar, teori-teori serta metode yang
dipergunakan.
4. Jelaskan perbedaan proposisi yang dikemukakan penganut teoristruktural fungsional
dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori konfliksehingga
menimbulkan pertentangan!
5. Sebutkan dan jelaskan 4 tipe tindakan sosial menurut Weber!
6. Tokoh pendekatan behaviorisme B.F. Skinner mengkritik obyekstudi paradigma
fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis tidakkonkrit relistis, Jelaskan
maksudnya!
TUGAS
Buatlah makalah individu yang isinya mengkaji sebuah fenomenasocial yang adaa dalam masyarakat dengan menggunakan pisauanalisa teori sosiologi yang kamu pahami!
DAFTAR PUSTAKA
Johnson, D.P., 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern I. Gramedia.Jakarta.
Laeyendecker, 1994. Tata Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
M. Siahaan, Hotman. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosiologi. Erlangga. Jakarta.
Ritzer, George. 1991. Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda, Rajawali.Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1985. Emile Durkheim. Aturan-Aturan Metode Sosiologis.Seri Pengenalan Sosiologi 2. Rajawali. Jakarta.
----------------------, 1985. Max Weber. Konsep-Konsep Dasar DalamSosiologi. Seri Pengenalan Sosiologi I. Rajawali. Jakarta.
Veeger, K.J., 1986. Realitas Sosial. Gramedia. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufik dan A.C. Van Der Leeden (Penyunting).1986. Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta.
Bouman, P.J., 1956. Ilmu Masyarakat Umum. Terjemahan Sujono. Cetakanke delapan. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
De Haan, J. Bierens, 1953. Sosiologi Perkembangan danMetode. Terjemahan Adnan Syamni. Yayasan Pembangunan. Jakarta.
Giddens, Anthony, 1986. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu AnalisisKarya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber. UI Press. Jakarta.
Kinloch, Graham. 2005. Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi.Pustaka Setia. Bandung
Laeyendecker, 1994. Tata Perubahan dan Ketimpangan. Suatu PengantarSejarah Sosiologi. Gramedia. Jakarta.
Lavine, T.Z., 2002.Dari Socrates Ke Sartre: Petualangan Filsafat, Jendela.Yogyakarta
M. Siahaan, Hotman. 1986. Pengantar Ke Arah Sejarah dan TeoriSosiologi. Erlangga. Jakarta.
P. Johnson, Doyle, 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Dindonesiakan: Robert M.Z. Lawang. Gramedia. Jakarta
Ramli, Andi Muawiyah. 2000. Peta Pemikiran Karl Marx. LKLS. Yogyakarta.
Ritzer, George. 1991. Sosiologi Ilmu Paradigma Ganda, Rajawali.Jakarta.
Soekanto,Soerjono, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1985. Emile Durkheim. Aturan-Aturan Metode Sosiologis.Seri Pengenalan Sosiologi 2. Rajawali. Jakarta.
.-----------------------, 1985. Pengantar Konsep dan TeoriSosiologis. Unila Press. Lampung
----------------------, 1985. Max Weber. Konsep-Konsep Dasar DalamSosiologi. Seri Pengenalan Sosiologi I. Rajawali. Jakarta.
Suseno, Frans Magnis. 2000. Pemikiran Karl Marx. Gramedia. Jakarta.