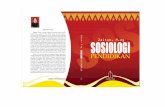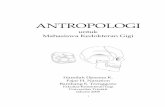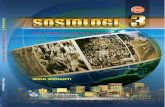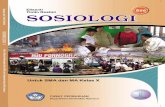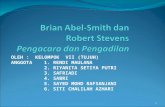antropologi sosiologi kesehatan - UMI Repository
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of antropologi sosiologi kesehatan - UMI Repository
i
ANTROPOLOGI SOSIOLOGI KESEHATAN
Penulis
Dra. Nurbaeti, M.Kes
Dr. Sundari, S.ST.,M.PH
Nurlina, S.ST.,M.Kes
Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang
ii
ANTROPOLOGI SOSIOLOGI KESEHATAN
Penulis:
Dra. Nurbaeti, M.Kes
Dr. Sundari, S.ST.,M.PH
Nurlina, S.ST.,M.Kes
ISBN 978-623-6032-21-3
Editor :
Prof. Dr. Hj. Kembong Daeng, M.Hum
Penyunting:
Harmawati, S.Sos
Desain Sampul dan Tata Letak
Muh. Yunus Nabbi
Penerbit:
Percetakan CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG
Redaksi :
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo BTN Indira Residence Blok E No. 10
Sungguminasa Kab. Gowa
No. HP: 085290480054
Email : [email protected]
Distributor Tunggal
Percetakan CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo BTN Indira Residence Blok E No. 10
Sungguminasa Kab. Gowa
No. HP: 085256649684/ WA: 085290480054
http//cv-cahayabintangcemerlang.co.id
Anggota UMKM Nomor : 04933-0615-20
Anggota IKAPI Nomor : 027/SSL/2020
Cetakan Pertama, Januari 2022
Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.
iii
KATA PENGANTAR
Rasa Syukur yang sedalam-dalamnya kami sampaikan
kehadirat Allah Subhanahu Wa ta’ala yang maha pengasih dan
penyayang karena berkat kemudahannya maka buku “Antropologi
Sosiologi Kesehatan” ii dapat terselesaikan. Buku Antropologi
Sosiologi Kesehatan disusun sebagai mata kuliah wajib setiap
mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Program Studi
Kebidanan. Buku ini ditujukan agar dapat memberikan arahan bagi
mahasiswa menambah pengetahuan tentang pentingnya memahami
kebudayaan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat.
Buku Antropologi Sosiologi Kesehatan merupakan alat bantu
dalam menerapkan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kebidanan.
Dengan demikian buku ini secara berkala akan direvisi berdasarkan
kurikulum yang berlaku dan kondisi perkembangan masyarakat.
Penyusunan buku ini memerlukan waktu dan pemikiran mendalam.
Oleh karena itu kritik membangun dan saran dari berbagai pihak akan
bermanfaat guna penyempurnaan buku ini dimasa mendatang.
Akhirnya penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada
semua pihak, terutama kepada suami dan anak-anak kami yang
memberikan dukungan dari penyusunan hingga terbitnya buku ini.
Semoga buku ini meberi manfaat dan informasi bagi para pembaca
dan penulis khususnya.
Makassar, Januari 2022
Penyusun
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .................................................................... i
HALAMAN REDAKSI PENERBIT ............................................... ii
KATA PENGANTAR ..................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................... iv
BAB I ANTROPOLOGI SOSIOLOGI ...................................... 1
A. Pengertian Antropologi ................................................... 1
B. Pengertian Sosiologi ..................................................... 4
C. Ruang Lingkup Kajian Antrosos ................................... 5
D. Hubungan Sosiologi & Antropologi .............................. 6
E. Masyarakat Terasing Di Indonesia ................................. 8
BABII KEBUDAYAAN ............................................................... 19
A Konsep Kebudayaan ....................................................... 19
B. Wujud Kebudayaan ........................................................ 21
C. Unsur Kebudayaan ......................................................... 22
D. Kepribadian ................................................................... 23
E. Susunan Kepribadian ..................................................... 23
F. Pembentukan Kepribadian ............................................. 25
G. Kebudayaan dan Pengaruhnya Terhadap
Kepribadian .................................................................... 26
BAB III STRUKTUR SOSIAL, INDIVIDU, KELUARGA
MASYARAKAT ............................................................. 31
A. Struktur Sosial ................................................................ 31
B. Pengertian Individu ......................................................... 35
C. Pengertian Masyarakat ................................................... 36
D. Hubungan Individu dan Masyarakat .............................. 38
E. Keuarga .......................................................................... 40
F. Struktur dan Prnata Sosial .............................................. 42
BAB IV TEORI PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA .................... 46
A. Teori Tehnologi dan Ketertinggalan oleh W.F.Ogbun .. 46
B. Teori Perubahan Budaya oleh Bronislaw Malinowski .. 47
C. Teori Perubahan Sosial Budaya ..................................... 47
D. Faktor-faktor Menyebabkan Perubahan-Perubahan
Sosial dan Kebudayaan .................................................. 48
E. Dampak Perubahan Sosbud Terhadap
Kehidupan Masyarakat ................................................. 51
v
F. Dampak Perubahan Budaya Terhadap
Kehidupan Masyarakat .................................................... 52
BAB V LEMBAGA/PRANATA SOSIAL ................................... 56
A. Institusi Sosial ................................................................ 58
B. Baasan Pengertian .......................................................... 59
C. Proses Pertumbuhan Lembaga Sosial ............................ 60
D. Fungsi Lembaga Sosial .................................................. 65
E. Ciri-Ciri Dan Tipe Lembaga Kemasyarakatan ............... 66
BAB VI PROSES-PROSES SOSIAL ........................................... 69
A. Pembatasan Pengertian .................................................. 69
B. Interaksi Sosial ............................................................... 70
C. Syarat-Syarat Interaksi Sosial ........................................ 71
D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial ..................................... 72
BAB VII SOSIOLOGI KESEHATAN ........................................... 75
BAB VIII KONSEP DASAR SOSIOLOGIS, NILAI/NORMA
KESEHATAN ............................................................... 80
BAB IX MODEL-MODEL PERUBAHAN PERILAKU .......... 86
BAB X LAYANAN KESEHATAN DAN TANTANGAN
PERUBAHAN SOSIAL .................................................. 92
BAB XI MAKANAN: MAKNA BUDAYA DAN KESEHATAN
.......................................................................................................... 100
BAB XII SIKLUS HIDUP, KESEHATAN, DAN PERAN SOSIAL
.......................................................................................................... 107
BAB XIII BUDAYA DALAM PERSALINAN ........................... 114
BAB XIV BUDAYA PERSALINAN DI LUAR NEGERI ........... 139
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 148
SOAL LATIHAN ............................................................................ 155
BIODATA PENULIS ...................................................................... 168
1
BAB I
ANTROPOLOGI SOSIOLOGI
A. Pengertian Antropologi
Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani asal kata
antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian
secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para ahli
antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi
merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun
generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan
untuk memperoleh pengertian ataupun
Jadi antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai
pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari
aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaannya.
Beberapa defenisi antropologi dari para ahli:
1. William A, Haviland; antropologi adalah studi tentang umat
manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian
yang lengkap tentang beraneka ragam manusia.
2. David Hunter; antropologi adalah ilmu yang lahir dari
keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
3. Koentjaraningrat; antropologi adalah ilmu yang mempelajari
umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka
warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang
dihasilkan.
4. Coral Ender dan Malvin ember; menyatakan bahwa antropologi
adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman manusia di
dunia, hal yang dipelajari tidak hanya manusia yang hidup
sekarang, tetapi juga manusia yang sudah pernah dan hidup
jutaan tahun yang lalu
Dari beberapa defenisi di atas dapat disusun pengertian
sederhana, antropologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari
manusia dari segi keanekaragaman, ciri fisik serta kebudayaan
(cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan
sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-
beda.
Menurut Koentjaranigrat, pada dasarnya konsep dasar dari
antropologi mencakup lima pokok permasalahan kajian mengenai
2
manusia.
Kajian permasalahan tersebut yakni:
1. Masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia
mislanya mahluk biologis.
2. Masalah sejarah terjadinya aneka warna manusia berdasarkan
ciri-ciri tubuhnya.
3. Masalah persebaran dan terjadinya keragaman bahasa
yang diucapkan manusia.
4. Masalah perkembangan, persebaran dan terjadinya aneka
warna Kebudayaan manusia dan
5. Masalah dasar-dasar dan keragaman kebudayaan dalam
kehidupan masyarakat dan suku-suku bangsa di seluruh dunia
dewasa ini.
Untuk memecahkan kelima masalah tersebut, maka
antropologi secara umum dapat digabungkan dalam dua bagian
yaitu :
1. Antropologi fisik
2. Antropologi budaya
Ad. 1. Antropologi Fisik
Antroplogi fisik adalah mencacat, menelaah manusia
sebagai mahluk fisik yang tumbuh dan berkembang sehingga
terjadinya keanekaragaman mahluk manusia, ciri-ciri tubuh
seperti kulit, warna dan bentuk rambut, indeks tengkorak,
bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi dan bentuk
serta ciri-ciri genotype seperti golongan darah.
Antropologi fisik terbagi ke dalam 2 bagian yaitu :
a. Paleo antropologi adalah merupakan ilmu bagian dari
antropologi fisik yang mencoba menelaah tentang asal usul
atau terjadinya perkembangan mahluk manusia seperti sisa
tubuh dan fosil manusia.
b. Samatologi adalah menelaah tentang variasi alam
keanekaragaman ras manusia melalui ciri-ciri tubuh
manusia secara keseluruhan. Seperti ciri-ciri fenotive dan
ciri-ciri genotife:
- Ciri-ciri fenotifa merupakan ciri lahiriah dari diri yang
dihasilkan karena interaksi antara ciri-ciri keturunan dan
3
lingkungannya seperti warna kulit, rambut, bentuk mata,
hidung, bibir, mute dsb.
- Ciri-ciri genotife didasarkan pada analisa kimiawi
terhadap gen ras (keturunan).
Ad. 2. Antropologi budaya
Antropologi budaya ialah bagian dari antropologi yang
mengkaji aneka kebudayaan manusia di muka bumi ini. Salah
satu pendekatannya adalah dengan membandingkan
kebudayaan berbagai bangsa, pendekatan ini disebut dengan
lintas budaya.
Antropologi budaya mempelajari kebudayaan berbagai
bangsa di dunia serta perubahannya. Kebudayaan yang
dipelajari serta perubahannya. Kebudayaan yang dipelajari
tidak hanya kebudayaan manusia yang masih hidup tetapi juga
kebudayaan dari manusia yang sudah lama berlalu.
Oleh karena itu antropologi budaya sangat berkaitan
dengan penelaahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
kebudayaan seperti ilmu pengetahuan, bahasa, kepercayaan
hukum, agama, keberadaan dan larangan-larangannya.
Berdasarkan bidang kajiannya antropologi budaya di
bag! berdasarkan kajian khusus, yaitu :
a. Arkeologi ialah ilmu yang mempelajari kebudayaan
sebelum manusia mengenal tulisan termasuk di dalamnya
perkembangan dan penyebaran kebudayaan.
b. Etnologi adalah merupakan ilmu bagian dari antropologi
budaya yang mencoba menelusuri asas-asas manusia
seperti;
- Mempelajari pola-pola kelakuan masyarakat, seperti
adat istiadat, perkawinan
- Mempelajari dinamika kebudayaan seperti perubahan
dan perkembangan kebudayaan serta bagaimana dapat
mempengaruhi kebudayaan lain.
c. Antropologi linguistik, mempelajari bahasa-bahasa
berbagai suku bangsa di dunia. Bahasa memegang peranan
penting dalam mempelajari kebudayaan suatu masyarakat,
karena melalui bahasa kebudayaan dapat diturunkan dari
generasi ke generasi berikutnya.
4
d. Antropologi sosial budaya, adalah mengkaji tentang
masyarakat, dalam perkembangan antropologi social
budaya dan bergerak di bidang kependudukan, pendidikan,
kelihatan, hukum, politik, psikologi, dll.
B. Pengertian Sosiologi
Sosiologi termasuk kelompok ilmu-ilmu sosial (social
science), sosiologi juga disebut ilmu kemasyarakatan, sosiologi
sebagai ilmu muncul pada abad ke-19, dipopulerkan oleh seorang
filosof prancis yang bernama Augustecomte (1798-1853). Menurut
A.comte, sosiologi berasal dari kata latin, sociens artinya teman
atau sesame dan logos dari kata Yunani artinya cerita jadi berarti
bercerita tentang teman atau kawan (masyarakat).
Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang
tersusun dari hasil-hasil penelitian ilmiah dan dapat dikontrol
secara kritis oleh orang lain atau manusia. Beberapa senyawa
memberikan defenisi tentang sosiologi sebagai berikut.
1. Pltirim A. Sorokin, sosiologi adalah suatu ilmu yang
mempelajari:
a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam
gejala social (misalnya, gejala ekonomi, agama, keluarga dan
moral, dsb)
b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social
dengan gejala social (misalnya gejala geografis, biologis dan
sebagainya)
c. Cirri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial
2. Roucek dan Warren; sosiologi adalah ilmu yang mempelajari
hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.
3. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkof; sosiologi adalah
penelitian secara ilmiah terhadap interaksi social dan hasilnya
yaitu organisasi social.
4. Alex Weber; sosioiogi adalah ilmu yang berupaya memahami
tindakan social.
5. Seto Soemardjan dan Soelaiman Soemardi ; sosiologi adalah
ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur social dan
proses-proses social termasuk perubahan social.
6. Soerjono Soekamto; (sosiologi suatu pengantar), sosiologi
5
adalah ilmu social yang murni, abstrak, rasional dan empiris,
bersifat umum, menurut pengertiannya, hakekat sosiologi adalah
sebagai berikut:
1) Sosiologi adalah ilmu social
2) Sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu normative,
melainkan disiplin ilmu kategori yang membatasi dirt pada
kejadian dewasa ini, bukan apa yang terjadi atau seharusnya
terjadi.
3) Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni bukan ilmu
pengetahuan terapan. Misalnya, para sosiologi pendapat yang
berguna untuk petugas administrasi, pembentuk undang-
undang diplomat, guru-guru dan sebagainya.
4) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak, bukan ilmu
pengetahuan konkret dalam sosiologi yang diperhatikan
adalah bentuk dan pola peristiwa-peristiwa masyarakat.
5) Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola
umum, serta mencari prinsip-prinsip dan hukum-hukum
umum dari interaksi manusia, sifat, hakekat, bentuk, is! dan
struktur masyarakat manusia.
6) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan
rasional. Hal ini menyangkut metode yang digunakan.
7) Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan
pengetahuan khusus.
Dengan melihat uraian dari para ahli, dapat disimpulkan
bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri
sendiri dan mempunyai objek studi tersendiri. Sosiologi termasuk
ilmu pengetahuan karena di dalamnya mengandung pengetahuan
yang tersusun secara sistematis, yang dapat dipahami akal
pikiran, dapat ditelaah, serta dapat dikontrol secara kritis (dapat
dilihat kesalahan dan kekeliruannya) oleh orang lain yang ingin
mengetahuinya.
C. Ruang Lingkup Kajian Antropologi Sosiologi
Objek kajian antropologi sosiologi sangat dekat, terutama
antropologi budaya, jika sosiologi membahas tentang hubungan
social antar warga masyarakat, hasil hubungan sosial itu adalah
budaya oleh karena itu para ahli mengatakan bahwa hubungan
6
antara masyarakat dan budaya adalah hubungan system.
Secara garis besar kajian antropologi adalah :
1. Asal usul manusia
2. Evolusi fisik manusia
3. Keanekaragaman bentuk fisik manusia atau ras
4. Kebudayaan
5. Berbagai kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Ruang lingkup sosiologi mencakup semua
interaksi yang berlangsung antar individu dengan individu,
individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok
dan lingkungan masyarakat sosiologi mengkaji beberapa ha)
antara lain:
1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya
2. Masalah kewenangan yang berkaitan yang dialami warganya
3. Persoalan sejarah.
D. Hubungan Sosiologi dengan Antropologi
Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, dan masyarakat
selalu berkebudayaan, masyarakat dan kebudayaan tidak sama,
tetapi berhubungan erat, masyarakat menjadi kajian pokok
sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi.
Menurut Ralphlinton masyarakat menunjuk pada
segolongan manusia yang pandai dan bekerjasama, sedangkan kata
kebudayaan menunjuk pada cara hidup yang khas dari golongan
manusia tersebut. Dengan kata lain, masyarakat merupakan fungsi-
fungsi yang asasi dalam hubungan manusia, sedangkan kebudayaan
adalah cara fungsi itu dilaksanakan.
Masyarakat berhubungan dengan susunan dan proses
hubungan antar manusia dan golongan; kebudayaan berhubungan
dengan isi/corak dengan hubungan yang ada, karena itu keduanya
baik masyarakat dan kebudayaan penting bagi sosiologi dan
antropologi.
Oleh karena dua disiplin ilmu yang terkait sangat erat
sosiologi memusatkan perhatiannya kepada interaksi sosial dalam
masyarakat, sedangkan antropologi mengkaji nilai-nilai budaya
yang menjadi latar belakang atau acuan bagi manusia dalam
melakukan interaksi. Ringkasnya, sosiologi mempelajari
7
masyarakat, sedangkan antropologi mempelajari budaya, kita
mengetahui bahwa antara masyarakat dan kebudayaan adalah dua
unsur yang tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat menjadi wadah bagi perkembangannya
kebudayaan dan kebudayaan menjadi isi atau jiwa yang
mengakibatkan masyarakat menjadi hidup dan berkembang.
Berdasarkan sejarah dan pokok kajian antropologi dan di
sosiologi dibedakan sebagai berikut:
- Antropologi lahir dari lingkungan masyarakat bersahaya
(masyarakat sederhana) yaitu untuk kepentingan kolonialisme
bagi bangsa-bangsa Eropa. Pada waktu itu antropologi lebih
dikenal sebagai etnologi yang menggambarkan dengan lengkap
tentang suku-suku bangsa yang masih sederhana dan
terbelakang. Gambaran menyeluruh tersebut sangat membantu
para colonial yang umumnya bangsa Eropa untuk memasuki dan
menaklukkan daerah-daerah baru tetapi kaya dengan sumber
daya alamnya.
- Sosiologi lahir dari kalangan masyarakat industri yang relatif
lebih maju seperti Amerika, Inggris dan Prancis
Lahirnya sosiologi pada awalnya adalah untuk memahami
hubungan manusia dalam masyarakat yang terkotak-kotak
seperti kaum Borjuis dan Proletar.
Kaum borjuis adalah kelompok pemilik modal yang
menguasai perekonomian Kaum proletar adalah orang-orang yang
dikuasai dan menjadi “hamba” kaum borjuis. Akibatnya timbul
berbagai gejolak dalam masyarakat yang intinya perjuangan hak-
hak kaum proletar yang umumnya terdiri dari para buruh.
Masa sekarang atau transisi sosiologi bersama antropologi
mengkaji masyarakat transisi atau peralihan proses saling
mempengaruhi antara unsur-unsur tradisional dan unsur-unsur non
tradisional. Sedangkan sosiologi memperhatikan unsur-unsur non
tradisional /baru. Hal ini disebabkan adanya pertemuan antara
masyarakat dan kebudayaan lain serta suasana kata modern yang
dipengaruhi desa, makin berkurangnya masyarakat primitive di
dunia, mengakibatkan makin mendekatnya kedua item tersebut
meskipun masih ada perbedaannya.
8
E Masyarakat Terasing Di Indonesia
Masyarakat terasing merupakan kelompok masyarakat
yang karena loyalitasnya terpencil dan terisolir mengalami
keterbatasan komunikasi denganmasyarakat lain serta pelayanan
pemerintah sehingga mengakibatkan keterbelakangan dalam
penghidupan dan tertinggal dalam proses perkembangan
kehidupan dibidang agama, politik, ideologi, ekonomi, sosial dan
budaya (Suparlan, 1995:512). Menurut Departemen sosial
masyarakat terasing sebagai bagian dari masyarakat Indonesia,
masih mengalami berbagai permasalahan sosial meliputi berbagai
segi kehidupan dan penghidupan yang perlu memperoleh
pembinaan secara sistematik untuk meningkatkan taraf
kehidupannya. Masyarakat terasing adalah sekelompok
masyarakat yang memiliki kesamaan ciri fisik, budaya dan
mendalami wilayah tertentu yang terpencil sulit dijangkau dan
secara geografis terisolasi, sehingga mengalami kesulitan dalam
berinteraksi sosial (budaya) dengan masyarakat diluar mereka.
Dilihat dari keberadaan lokasi masyarakat terasing dapat
dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu:
1) Mereka yang hidup di dataran tinggi seperti suku Dani, Ngalum,
Ekari di Irian Jaya.
2) Mereka yang hidup di pedalaman (dataran rendah, hutan atau
sekitar hutan misalnya suku Dayak Kenyah, Punan, Iban, Wana,
Anak Dalam dan sebagainya).
3) Mereka yang hidup di pantai atau di rawa-rawa seperti suku
Asmat, Askit, Bonai, Marin, dan lain-lain.
4) Mereka yang mengembara di laut seperti orang Bajo dan suku
lau
10
Gambar Suku Bajoe
Selain dari keberadaaan masyarakat terasing juga
dikelompokkan dalam
Tingkat kondisi kehidupan dan penghidupannya, yakni:
1) Masyarakat berkelana.
2) Masyarakat menetap sementara.
3) Masyarakat menetap.
Kehidupan mereka ini harus menghadapi dan menyesuaikan
diri dengan lingkungan di sekelilingnya agar dapat menganbil bahan
makanan. Apabila dilaut dan dirawa mereka menjadi nelayan untuk
menangkap ikan, bila dilingkungan berupa hutan mereka akan
berburu dan mencari makanannya (Soekanto,1990).
Keadaan masyarakat terasing pada umumnya dapat
digambarkan sebagai berikut:
1) Hidup dalam kelompok kecil, berpencar dan sulit dijangkau.
2) Kehidupannya tergantung dengan alam sekitar.
3) Tata cara kehidupan sesuai dengan adat istiadat dan sulit
menerima perubahan.
4) Kepercayaan mereka masih dipengaruhi oleh tabu atau larangan
yang membatasiruang gerak mereka.
5) Penggunaan alatnya masih sangat sederhana.
6) Cara berproduksi mereka masih sangat substansi.
11
7) Mereka tertutup dangan pendatang baru, hal ini yang membuat
mereka sulitberadaptasi dengan budaya luar.
8) Sangat sedikit menerima pelayanan pembangunan dari
pemerintah, sehinggatingkat hidup mereka masih rendah. Pada
sisi lain permasalahan yang disandang oleh masyarakat terasing
dapatdisebutkan antara lain:
1) Pemenuhan sumber kehidupan yang sangat rendah.
2) Rasa aman terusik dengan pendatang baru.
3) Masih sulit beradaptasi dengan lingkungan social.
4) Terjadinya perubahan yang cepat akibat dari adanya
pembangunan.
5) Ruang hidup mereka semakin sempit dan terdesak.
6) Kehidupan masyarakat terasing yang sempurna ditandai
dengan ketidakmampuannya berinteraksi sosial dengan pihak
lain. Permasalahan masyarakat terasing yang komplek yang
akan menimbulkan dampak sebagai berikut:
1) Terjadi desparitas yang jauh dalam tingkat kesejahteraan
antar masyarakat terasing dengan masyarakat Indonesia
lainnya.
2) Dapat menimbulkan pandangan bahwa pembangunan
pemerintah belumberkembang secara merata.
3) Dapat mengurangi citra pembangunan Indonesia.
4) Belum sepenuhnya diwujudkan integrasi masyarakat
secara nasional dalam budaya bahasa Indonesia
Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok
minoritas yang ada dipulau sumatera tepatnya di daerah pedalaman
yang ada di Provinsi Jambi dengan jumlah populasi seluruhnya 2.951
kepala keluarga yang tersebar di berbagaikabupaten yaitu Kabupaten
Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten
Merangin. Suku Anak Dalam hidup secara berkelompok dan tidak
dibatasi oleh wilayah tempat tinggal tertentu. Mereka bebas hidup
dengan kelompok lain namun tidak mudah untuk pindah dari
kelompoknya. Suku Anak Dalam atau yang biasa dikenal dengan
orang kubu biasa hidup dengan berpindah- pindah dari hutan satu ke
hutan yang lain dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Suku
anak dalam memiliki adat_istiadat seperti orang melayu lainnya dan
menjadi pegangan mereka dalam ikatan sosial. Suku Anak Dalam
12
atau yang biasa dikenal dengan orang rimba merupakan suku yang
menggantungkan kehidupanya terhadap hutan, baik itu dari berburu
maupun buah-buahan yang ada didalam hutan.
Kehidupan Suku Kubu
1) Pola Pemukiman
Kelompok suku Kubu di Bukit Duabelas, merupakan
salah satu kelompok yang bertekad untuk mengikuti gaya
kehidupan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka sebaik
mungkin. Tempat pemukiman terdiri dari beberapa kediaman
yang terletak beberapa ratus meter dari rumah (Bubungan)
Temenggung Tarib. Bubungan bertiang yang didiami oleh
Temenggung Tarib terdiri dari dinding kayu, atap dari daun, yang
tinggin lantainya sekitar 2 meter dari tanah.kediaman ini lebih
sederhana, dengan tinggi lantainy sekitar setengah meter dari
tanah dan Lantainya dibuat dari batang kecil kayu bulat. Untuk
rumah sementara, misalnya waktu mereka memburu binatang
atau sedang pindah ke tempat lain saat istirahat, mereka membuat
pondok bernama sudung yang bentuknya lebih sederhana tanpa
lantai tetapi dengan atap dari daun kayu. Sudung itu cepat
dibangun untuk pelindungan di waktu malam. Semua keluarga
dalam satu kelompok Kubu punya tempat tinggal sendiri-sendiri
yang berjarak satu sama lain sekitar 5m sampai 10m. Dalam satu
kelompok terdiri dari 3 sampai 5 Bubungan (Rumah), dalam satu
Bubungan dihuni oleh satu keluarga yang beranggotakan rata-rata
4 orang sampai 7 orang suku kubu.
2) MataPencarian
a. Makanan dan Hasil Hutan
Secara tradisional pada dasarnya kebutuhan
makanan pokok dan kebutuhan lain dipenuhi oleh hutan.
Gaya hidup tradisional terdiri dari berburu dan meramu
(hunting and gathering). Makanan pokok mereka biasanya
terdiri atas ubi dan daging, terutama daging babi. Di hutan
mereka meramu buah-buahan, Umbi- umbian, dan damar
yang pada umumnya, tidakselalu, dilakukan oleh kaum
perempuan. Memburu binatang besar dilakukan oleh kaum
13
laki-laki dan pola berburu bergantung pada musim. Ada
beberapa jenis binatang yang ditangkap dengan cara dipanah
antara lain: babi hutan (Sus vitatur), babi jengkot (sus
barbatus) babi biasa (sus scrofa). Temasuk Rusa (Cervus
equimus) dan kijang (Cervulusmuntjac) Ketika Suku Kubu
menemukan pohon di hutan yang menjadi bagian tanah
tradisional mereka, dan pohon tersebut bernilai guna tinggi,
seperti pohon 7 kedondong dengan sarang lebah, atau durian
yang belum dimiliki orang maka orang Kubu bisa memberi
tanda kepemilikannya di batang atau sekitarnya supaya Suku
Kubu lain tahu pohon itu tidak harto samo (milik bersama),
tetapi milik pribadi. Radcliff-Brown menulis mengenai
penduduk pulauAndaman.
b. Peralatan
Suku Terasing didefinisikan sebagai orang yang
memiliki harta benda minimal, termasuk barang seni dan alat
teknologi yang minimal pula. Sebetulnya, gaya hidup Suku
Kubu hampir tabu untuk memiliki atau menambah harta
benda yang tidak termasuk kebutuhan primer atau memiliki
barang-barang yang menyulitkan untuk berpindah-pindah.
Kelihatannya menurut kosmologi Suku Kubu, mereka tidak
terdorong atau tergoda mempunyai harta benda. Mereka
mengutamakan alat-alat kehidupannya seperti alat pemanah
untuk berburu, Parang untuk pemotong dan kampak untuk
menebang pohonman,
3) Sistem Kekerabatan
Sistem kekerabatan Suku Kubu adalahmatrilineal yang
sama dengan sistem kekerabatan budaya Minangkabau. Tempat
hidup pasca pernikahan adalah uxorilokal, artinya saudara
perempuan tetap tinggal didalam satu pekarangan sebagai sebuah
keluarga luas uxorilokal. Sedangkan saudara laki-laki dari
keluarga luas tersebut harus mencari istri diluar pekarangan
tempat tinggal. Dalam arti lain masyarakat Kubu menganut
sistem kekerabatan matrilineal dan poligami. Matrilineal, artinya
saudara perempuan tinggal bersama di kelompok orang tua dan
saudara laki-laki harus ikut kelompok isterinya. Poligami artinya
14
suaminya boleh mempunyai hubungan dengan beberapa istri.
Alasannya perempuan subur, mandul, dan janda harus dilindungi
sebagai sumber hidup.
Dalam hal perkawinan ada tiga jenis perkawinan, yaitu;
pertama dengan mas kawin. Kedua, dengan prinsip pencurahan,
yang artinya laki-laki sebelum menikah harus ikut mertua dan
bekerja di ladang dan berburu untuk dia membuktikan dirinya.
Ketiga, dengan pertukaran gadis, artinya gadis dari kelompok lain
bisa ditukar dengan gadis dari kelompok tertentu sesuai dengan
keinginan laki- laki dan gadis-gadis tersebut
4) Kepercayaan dan Kosmos Suku Kubu
Menurut salah satu mitos yang di ceritakan Suku Kubu,
mereka berasal dari Pagaruyung (Minangkabau) dan bersumpah
bahwa mereka tidak berkampung, dan tidak makan makanan
binatang yang dipelihara termasuk ayam, bebek, kambing dan
sapi. Makanan lain yang haram atautabu termasuk telur dan susu.
Dengan pengalaman hidup di hutan danpengalaman
interaksi terbatas dengan dunia luar, kepercayaan dan kosmologi
yang muncul dan unik serta 9 berbeda dari pola pikir masyarakat
umum. Kepercayaan suku Kubu masih bersifat animisme, mereka
mempunyai dewa kebaikan dan dewa keburukan.
Tujuan pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing
adalah terwujudnyakondisi kehidupan dan penghidupan
masyarakat terasing, baik fisik, sosial budaya, dan sosial ekonomi
yang semakin membaik, serta terbebasnya dengan keterasingan
dan keterbelakangan, sehingga setra dengan integrasi dengan
masyarakat Indonesiapada umumnya. Sesuai dengan tujuan
tersebut, maka indikator keberhasilan pembinaan masyarakat
terasing adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kebutuhan dasar hidup seperti makanan,
kesehatan, rumah danpendidikan.
2) Terbentuknya satuan-satuan permukiman masyarakat
terasing dan merka telahbertempat tinggal menetap dengan
senang dan tenang.
3) Meningkatkan taraf hidup peradaban ditandai dengan
kesediaan untuk menyekolahkan anak-anaknya.
4) Dapat berintegrasi dalam system kemasyarakatan bangsa
15
Indonesia
Program Pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing
(PKSMT) merupakan suatu bentuk program yang dikeluarkan
oleh pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial
RI Nomor 5/HUK/1994, sebagai bentuk program yang memiliki
tujuan untuk terentasnya masyarakat terasing dari ketertinggalan
dan terbelakangan di berbagai bidang dan dapat beradaptasi
dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan masyarakat
lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi masyarakat
mandiri. PKSMT merupakan suatu upaya pembinaan yang
diberikan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena
keterbelakangan dan keterangsingan, dengan tujuan untuk
menciptakan kondisi sosial yang sesuai dengan kehidupan
masyarakat modern dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Kegiatan PKSMT ini selalu berorientasi pada masyarakat yang
terisolasi dan berada di pedalaman pedesaan yang mengalami
keterbelakangan komunikasi dengan masyarakat yang lain.
PKSMT adalah program yang diperuntukkan untuk masyarakat
suku anak dalam, karena 10 pemerintah melihat bahwa suku anak
dalam sudah kehilangan kontak dengan perubahan umum dari
segi agama, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pemerintah
dalam hal ini selalu melakukan pembinaan bagi masyarakat Suku
Anak Dalam. Adapun bentuk PKSMT ini adalah bantuan rumah
atau pemukiman, mengenalkan cara-cara berproduksi,
mengenalkan budaya baru, pendidikan formal, dan mengajarkan
untuk berinteraksi dengan masyarakat lain (Yanto, 2016).
Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
5/HUK/1994 tentang Program PKSMT memiliki proses untuk
melaksanakan program yaitu:
Tahapan Pelaksanaan
Program PKSMT dilaksanakan melalui sistem pembangunan
pemukiman sosial dengan cara:
1) mendayagunakan berbagai potensi serta sumber daya manusia,
sumber daya alam dan teknologi melalui pendekatan sosial
budaya.
16
2) mewujudkan tipe pemukiman ditempat asal, tipe pemukiman
ditempat baru, tipe stimulus pembinaan masyarakat serta tipe
kesepakatan dan rujukan
Tahap Pembinaan
Proses pembinaan merupakan rangakaian kegiatan
Pembinaan masyarakat secara komprehensif, terpadu dan
berkelanjutan selama kurun waktu tertentu. Proses pembinaan
masyarakat terasing sebagaimana terdiri dari tahap
a) persiapan
b) bimbingan
c) Pembinaan dan
d) pengalihan
Tahap persiapan
Tahap persiapan merupakan kegiatan untuk memperoleh
data dan informasi tentang keberadaan masyarakat terasing,
mengetahui tentang kondisi habitat dan penghidupan mereka,
memahami nilai sosial budaya dan aspirasi mereka serta
mengkondisikan masyarakat terasing agar siap menerima proses
perubahan kearah kemajuan. Tahap persiapan dilaksanakan melalui
kegiatan seperti orientasi masyarakat terasing, pendekatan social
budaya, motivasi sosial budaya, pemantapan persiapan pemukiman
sosial, dan penyiapan kondisi sosial masyarakat.
Tahap bimbingan
Tahap bimbingan merupakan kegiatan pengenalan dan
pemahaman tentang nilai_nilai sosial budaya baru dan pemberian
keterampilan yang lebih baik untuk dapat didayagunakan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tahap bimbingan
dilaksanakan seperti kegiatan bimbingan beradaptasi lingkungan,
bimbingan pemanfaatan bantuan, dan bimbingan pendayagunaan
sarana.
Tahap Pembinaan
Tahap Pembinaan merupakan kegiatan meningkatkan
kesadaran warga binaan untuk menumbuhkan sikap dan tekad
17
kemandiriannya dengan mendayagunakan sumber manusia, sumber
daya alam, dan teknologi melalui peningkatan berbagai bidang
keterampilan dan stimulasi agar terwujud kondisi kehidupan dan
penghidupan yang lebih baik. Tahap Pembinaan dilaksanakan melalui
kegiatan Pembinaan pemenuhan kebutuhan hidup, Pembinaan nilai
sosial budaya, Pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial
Tahap pengalihan
Tahap pengalihan merupakan rangkaian kegiatan akhir
dalam proses pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing. Tahap
pengalihan dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi akhir,pemantapan
pengertian dan peran serta dibidang ipteksosbud, dan pengalihan
status pembinaan.
Organisasi pengelola program PKSMT yang diberikan
untuk SAD adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT). KAT meupakan
organisasi yang berada dibawah kewenangan Dinas Sosial dibawah
Kabid Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang mulai dibentuk pada
tahun 2014 dengan jumlah anggota 3 orang, yang pada mulanya
disebut dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Suku Anak
Dalam. UPTD terbentuk karena ada suku yang berasal dari Provinsi
Jambi yang masih mengalami keterasingan dan keterbelakangan yaitu
Suku Anak Dalam (SAD), namun perkembangan UPTD Suku Anak
Dalam tidak berlangsung lama. Kemudian pada tahun 2016
diperbaharui menjadi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang
terbentuk karena adanya inisiatif dan kesepakatan bersama dari Dinas
Sosial. Pada pelaksanaan program PKSMT KAT bermitra dengan
LSM Pundi Sumatera dan juga perkumpulan Gereja GKSBS. LSM
Pundi Sumatera memiliki 12 anggota 2 orang, dipilih untuk ikut
membantu dalam program PKSMT. LSM Pundi Sumatera merupakan
fasilitator dalam pelaksanaan program PKSMT, sedangkan Gereja
GKSBS sebagai fasilitator dalam pemberian ilmu rohani atau agama.
Program yang dilaksanakan pemerintah untuk Suku Anak Dalam
adalah untuk membantu mengentaskan masyarakat terasing dari
ketertinggalan danterbelakang diberbagai bidang dan dapat
beradaptasi dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan
masyarakat lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi
masyarakat mandiri. Teori struktur fungsional ini terdapat empat
18
fungsi yang diperlukan dalam sistem yang biasa disebut dengan
skema AGIL yaitu:
1) Adaption, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial
untuk menghadapi lingkungannya. Pelaksanaan program
PKSMT yang dilaksanakan oleh Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dibawah kewenangan Dinas Sosial untuk sekelompok
Suku Anak Dalam sesuai dengan kehidupan mereka yang
nomaden (berpindah-pindah).
2) Goal Attainment, merupakan persyaratan yang tindakan
sekelompok masyarakat diarahkan pada tujuan-tujuannya, dan
untuk mencapai tujuan dari program PKSMT KAT menjalankan
program PKSMT ini dibantu oleh LSM Pundi Sumatera dan
Perkumpulan Gereja GKSBS.
3) Integration, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan
internalisasi antara para anggota dalam sistem sosial itu, dengan
melaksanakan program PKSMT kepada SAD telah
memunculkan ikatan integrasi yang mulai baik antara SAD
sendiri dengan masyarakat lokal dimana terlihat saat mereka
bermukim satu kawasan yang sama, menjadikan mereka untuk
berbaur dan saling membantu ketika membutuhkan bantuan hal
tersebut tercermin saat SAD sedang melangsungkan pernikahan
salah satu keluarganya, masyarakat lokal ikut bergotong royong
untuk membantu proses pernikahan tersebut. Dan sebaliknya
SAD yang sudah terbuka dengan masyarakat luar hal tersebut
tercermin pada saat pelaksanaan gotong royong untuk
membangun prasarana olahraga, SAD ikut aktif didalamnya
untuk membantu
4) Latency, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan
memperbaiki baik motivasi individual atau kultural yang
menciptakan dan menopang motivasi. Pemeliharaan nilai dan
norma memiliki perenan penting dalam kehidupan masyarakat,
dimana pendamping SAD membantu dalam pemeliharaan nilai
dan norma yang ada pada masyarakat SAD.
19
BAB II
KEBUDAYAAN
A. Pengertian Kebudayaan
Dalam ilmu Antropologi yang menjadikan berbagai cara
hidup manusia dengan berbagai macam sistem tindakan sebagai
obyek penelitian dan analisanya, aspek belajar itu merupakan
aspek yang sangat periling.
Dalam hal memberi pembatasan tentang konsep-konsep
"kebudayaan" Antropologi sering kali sangat berbeda dengan
ilmu yang lain. Menurut ilmu Antropolgi "kebudayaan" adalah
keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri
manusia dengan belajar (Koentjaraningraf).
Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan
manusia adalah “kebudayaan” karena amat sedikit tindakan
manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu
dibiasakannya dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan
naluri beberapa refleks. Beberapa tindakan akibat proses fisiologi
bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan
naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam gennya
bersama kelahirannya juga dirombak olehnya menjadi tindakan
berkebudayaan.
Kata “kebudayaan” dan “Culture”. Kata “kebudayaan
berasal dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan
demikian ke – budaya – an dapat diartikan : “Hal-hal yang
bersangkutan dengan Akal”
Adapun kata culture, yang merupakan kata asing yang
sama artinya dengan “kebudayaan” berasal dari kata latin Colere
yang berarti “mengolah, mengerjakan” terutama mengolah tanah
atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture sebagai “segala
daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan
berubah alam”.
Ada beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli:
1. E.B. Tylor.
Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang
meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat
20
istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari
oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. Linton
Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan, sikap dan
prilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan
oleh anggota. suatu masyarakat tertentu.
3. A.L Kroeber.
Kebudayaan adalah keseluruhan realita gerak, kebiasaan,
tata cara gagasan dan nilai yang dipelajari dan diwariskan, dan
prilaku yang ditimbulkannya.
4. Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi.
Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta
masyarakat
5. Herskovits.
Kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang
diciptakan oleh manusia.
6. Kluckhohn dan Kelly.
Kebudayaan adalah semua rancangan hidup yang
tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit
ataukah rasional maupun irasional yang ada pada suatu waktu
sebagai pedoman yang potensial untuk prilaku manusia.
Berdasarkan defenisi para ahli tersebut dapat dinyatakan
bahwa unsur belajar merupakan hal penting dalam tindakan
manusia yang berkebudayaan.
Dari konsep dan pengertian kebudayaan yang demikian
luas dapat ditunjukkan sekurang-kurangnya 5 sifat kebudayaan
masyarakat manusia sebagai berikut.
1. Kebudayaan dipahami dan dibagi bersama anggota
masyarakat.
Suatu aspek kebudayaan apakah itu berwujud mental kognitif
seperti religi atau berwujud material berupa candi, mesjid,
dan lain-lain merupakan miliki yang dapat dipahami oleh
semua masyarakat pendukung kebudayaan.
2. Kebudayaan diperoleh dan diteruskan secara sosial dan
21
belajar
Pewarisan budaya merupakan suatu proses peralihan nilai-
nilai budaya melalui proses belajar didalamnya terkandung
adanya interaksi antara generasi terdahulu, sekarang dan
yang akan datang. Oleh karena itu suatu generasi harus
mampu menciptakan untuk memberi kehidupan dan nuansa
baru kepada kebudayaan yang diterimanya. Hal ini penting
karena masyarakat selalu berubah dan berkembang
membawa nilai-nilai dan ukuran-ukuran baru yang
disesuaikan dengan perkembangan zaman.
3. Kebudayaan itu sangat bervariasi
Latar – belakang tumbuhnya antropologi suatu bidang ilmu
sosial ditandai dengan adanya kenyataan bahwa sebenarnya
kebudayaan umat manusia yang hidup dimuka bumi ini
berlain-lainan. Jadi justru kebudayaan yang berfariasi itu
menyebabkan suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain
meskipun bangsa-bangsa termasuk dalam klasifikasi ras yang
sama. Misalnya : kebudayaan Jawa, Sunda, Padang, Bugis,
dll.
4. Nilai dalam kebudayaan itu relatif
Nilai-nilai yang terkandung didalam kebudayaan itu bersifat
relatif, misalnya suatu gagasan, prilaku yang dianggap baik
dalam satu kebudayaan belum tentu dianggap baik pada
kebudayaan lain.
5. Kebudayaan berubah
Cepat atau lambat kebudayaan itu pasti berubah itu
tergantung pada faktor-faktor atau kondisi yang menghambat
atau mendukung baik dari dalam maupun dari luar, baik yang
terencana maupun tanpa terencana.
B. Wujud Kebudayaan
Bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu :
1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide,
gagasan, nilai-nilai, unsur-unsur, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta
tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
22
- Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan, sifatnya
abstrak, tak dapat diraba atau di baca. Lokasinya ada
dikepala-kepala atau pikiran warga masyarakat dimana
kebudayaan bersangkutan itu hidup.
Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama
dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat
itu. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas satu dari yang
lain, melainkan selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Para
Ahli Antropologi dan Sosiologi menyebut sistem ini budaya
adalah Cultural system.
- Wujud kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial atau
social system mengenai tindakan berpola bagi manusia itu
sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang
berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang
lain. Menurut pola tertentu yang berdasarkan adat tata
kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia
dalam suatu masyarakat. Sistem sosial itu bersifat kongkrit
terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa di observasi, difoto
dan di dokumentasi.
- Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan
tidak memerlukan banyak penjelasan karena berupa seluruh
total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya semua
manusia dalam masyarakat. Maka sifatnya paling konkrit dan
berupa benda-benda yang sangat besar seperti pabrik.
Ketiga wujud dari kebudayaan diatas, dalam kenyataan
kehidupan masyarakat tentu tak terpisah satu dengan lain.
Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi
arah kepada tindakan dan karya manusia, baik pikiran-
pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia,
menghasilkan benda, kebudayaan fisiknya. Sebaliknya
kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup
tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari
lingkungan alam lainnya sehingga mempengaruhi pola-pola
perbuatannya. Bahkan juga cara berfikirnya.
C. Unsur Kebudayaan
Koentjaraningrat mengacu pada pendapat Kluckhohn
23
menggolongkan unsur pokok yang ada pada tiap kebudayaan
dunia antara lain sebagai berikut:
1. Bahasa.
2. Sistem pengetahuan.
3. Organisasi sosial.
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
5. Sistem mata pencaharian hidup.
6. Sistem religi.
7. Kesenian.
D. Kepribadian
Konsep kepribadian adalah konsep yang luas sehingga
tidak mungkin dapat merumuskan satu defenisi yang tajam tapi
dapat mencakup keseluruhannya oleh karena itu, pengertian dari
satu ahli dengan yang lainnya berbeda, namun demikian defenisi
yang berbeda tersebut saling melengkapi dan memperbanyak
pemahaman tentang konsep kepribadian.
Beberapa defenisi kepribadian menurut para ahli antara lain :
1. M.A.W. Brower.
Kepribadian corak tingkah laku sosial yang meliputi corak
kekuatan, dorongan, keinginan opini dan sikap seseorang.
2. Theodgre .R. Newcombe.
Kepribadian adalah organisasi sikap yang dimiliki seseorang
sebagai latar belakang terhadap perilaku.
3. Yinger.
Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang
individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang
berinteraksi dengan serangkaian situasi.
4. Euber.
Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat yang
tampak dan dapat dilihat oleh seseorang.
E. Susunan Kepribadian
Pada perilaku setiap manusia secara individual sebenarnya
unik dan berbeda satu sama lainnya perilaku ditentukan atas
naluri, dorongan, atau kelakuan manusia yang tidak lagi
dipengaruhi dan ditentukan oleh akal dan jiwanya. Unsur akal
24
dan jiwa yang menentukan perbedaan prilaku tiap-tiap individu
dan disebut juga susunan kepribadian yang meliputi:
1. Pengetahuan.
Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman
dan konsep yang lahir dari pengamatan dan penyaluran
mengenai bermacam-macam hal yang berbeda-beda dalam
lingkungan individu tersebut.
2. Perasaan.
Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia
yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap
sesuatu, bentuk penilaian itu dipengaruhi oleh
pengetahuannya.
3. Dorongan Naluri.
Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah merupakan
naluri pada setiap manusia. Ada tujuh dorongan naluri yaitu :
a. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini
memang merupakan suatu kekuatan biologi yang juga
ada pada semua mahluk di dunia ini dan yang
menyebabkan bahwa semua jenis mahluk mampu
mempertahankan hidupnya di muka bumi ini.
b. Dorongan sex. Dorongan ini malahan telah menarik
perhatian banyak ahli psikologi dan berbagai teori telah
dikembangkan sekitar soal ini. Suatu hal yang jelas
adalah bahwa dorongan ini timbul pada tiap individu
yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan, dan
memang dorongan ini mempunyai landasan biologi yang
mendorong mahluk manusia untuk membentuk
keturunan yang melanjutkan jenisnya.
c. Dorongan untuk usaha mencari makan. Dorongan ini
tidak perlu dipelajari, dan sejak bayipun manusia sudah
menunjukkan dorongan untuk mencari makan yaitu
dengan mencari susu ibunya atau botol susunya tanpa
dipengaruhi oleh pengetahuan tentang adanya hal-hal itu
tadi
d. Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama
manusia. Dorongan ini memang merupakan landasan
biologi dari kehidupan masyarakat manusia sebagai
25
mahluk kolektif.
e. Dorongan untuk memicu tingkah laku sesamanya.
Dorongan ini merupakan sumber dari adanya beraneka
warna kebudayaan diantara mahluk manusia karena
adanya dorongan ini manusia mengembangkan adat
yang memaksanya berbuat konforn dengan manusia
disekitarnya
f. Dorongan untuk berbakti. Dorongan ini mungkin ada
dalam naluri manusia, karena merupakan mahluk yang
hidup kolektif, sehingga untuk dapat hidup bersama
dengan manusia lain secara serasi. Ia mempunyai suatu
landasan biologi untuk mengembangkan rasa simpati,
cerita dan sebagainya.
g. Dorongan untuk keindahan bentuk warna, sarana, gerak
pada seorang bayi. Dorongan ini sudah sering tampak
pada gejala tertariknya seorang bayi pada bentuk-bentuk
tertentu dari benda-benda disekitarnya, kepada warna –
warna cerah. Kepada suara nyaring dan berirama, dan
kepada gerak-gerak yang selaras. Beberapa ahli berkata
bahwa dorongan naluri ini merupakan landasan dari
suatu unsur penting dalam kebudayaan manusia yaitu
kesenian.
F. Pembentukan kepribadian
Pembentukan kepribadian di pengaruhi adanya empat
unsur penting yaitu:
1. Warisan Biologis (Heridity).
Warisan biologis merupakan faktor keturunan yang
berpengaruh terhadap perilaku konpulsif (terpaksa dilakukan)
dan kemudahan dalam pergaulan sosial serta keramah tamahan.
Faktor keturunan dalam warisan biologis mempunyai pengaruh
dalam membentuk jiwa kepemimpinan, pengendalian diri,
dorongan hati, sikap, dan minat pada din seseorang.
2. Warisan Lingkungan Alam.
Adanya perbedaan iklim dan sumber daya alam
menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri terhadap
lingkungan alam, kebudayaan akan dipengaruhi juga oleh
26
lingkungan alam.
3. Warisan Sosial.
Kebudayaan yang merupakan warisan sosial sangat
berpengaruh pada proses sosialisasi manusia.
4. Kelompok Manusia.
Kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh
kelompoknya, setiap anggota kelompok memiliki peranan-
peranan yang di wariskan kepada anggota kelompoknya.
seperti keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah,
lingkungan kerja dan media massa.
G. Kebudayaan dan Pengaruhnya Terhadap Kepribadian
Kebudayaan dan Kepribadian
Kebudayaan merupakan karakter suatu masyarakat bukan
karakter individual. Semua yang dipelajari dalam kehidupan
sosial dan diwariskan dan suatu generasi ke generasi berikutnya
merupakan kebudayaan. Menurut Ralph Union, kebudayaan
adalah warisan sosial dari anggota-anggota suatu masyarakat .
M.J. Herskovits.
Memandang budaya sebagai sesuatu yang super organik
karena budaya bersifat turun temurun meskipun masyarakat
senantiasa selisih berganti disebabkan oleh kematian dan
kelahiran. Kemudian budaya langsung mempengaruhi perilaku
dan kepribadian individu, karena individu tinggal dalam
lingkungan masyarakat yang memiliki budaya.
Theodore M. Nencomb.
Mengatakan kepribadian menunjuk pada organisasi sikap-
sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berfikir dan
merasakan secara khusus apabila dia berhubungan dengan orang
lain atau menanggapi sesuatu keadaan.
Goodman dan Marx
melihat kebudayaan sebagai warisan yang dipelajari dan
ditransmisikan secara sosial, yang terdiri dari artefak,
pengetahuan, kepercayaan, nilai dan harapan-harapan normatif
yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi
masalah – masalahnya. Kebudayaan menerangkan dan menjamin
27
ketersediaan makanan, pakaian, bahasa, nilai-nilai kepercayaan
dan praktek-praktek untuk masyarakatnya. Secara sederhana,
kebudayaan memberi bentuk dan struktur pada kehidupan sosial.
Kebudayaan tidak bisa lepas dan kepribadian individu
melalui suatu proses belajar yang panjang, dalam proses belajar
disebut sosialisasi. Kepribadian atau watak tiap-tiap individu
mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan secara
keseluruhan.
Sebaliknya, kebudayaan suatu masyarakat turut
memberikan sumbangan pada pembentukan kepribadian
seseorang. Kepribadian suatu individu dalam suatu masyarakat,
walaupun berbeda-beda satu sama lainnya dipengaruhi oleh nilai-
nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan juga oleh sistem
sosial yang telah diserap ke dalam dirinya melalui proses
sosialisasi dan proses pembudayaan selam hidup sejak masa
kecilnya.
Perkembangan Watak/Kepribadian
Ciri-ciri dan unsur kepribadian seorang individu dewasa
sebenarnya sudah tertanam ke dalam jiwa seseorang sejak awal yaitu
pada masa kanak-kanak melalui proses sosialisasi, Koentjoroningrat
menyatakan bahwa kepribadian adalah watak khas seseorang yang
tampak dari luar sehingga orang luar memberikan kepadanya suatu
identitas khusus. Identitas khusus tersebut diterima dari warga
masyarakatnya. Jadi terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh faktor
lain.
b. Kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan
c. Cara hidup di kota dan di desa
d. Agama
e. Profesi
f. Kelas sosial
Kepribadian ada yang selaras dan ada yang tidak selaras
dengan lingkungan alam serta sosial. Pembentukan watak banyak
dipengaruhi oleh pengalamannya ketika sebagai anak-anak yang
berbeda dalam asuhan orang-orang terdekat dilingkungannya, yaitu
bapaknya, ibunya, kakaknya juga individu – individu lainnya yang
berada disekelilingnya.
Watak juga sangat ditentukan oleh cara-cara bagaimana ia
28
diajari makan, bermain, disiplin, dan bergaul dengan anak-anak
lainnya pada waktu kecil, tiap-tiap kebudayaan mempunyai cara
pengasuhan anak yang berbeda-beda-beda menunjukkan adanya
kesamaan pola-pola adat dan norma-norma tertentu. Setelah anak-
anak itu menjadi dewasa, beberapa unsur watak yang sama akan
tampak menonjol pada banyak individu yang telah menjadi dewasa.
Dalam era globalisasi, sesuai dengan kemajuan dan
perkembangan yang demikianpesat dalam semua bidang.. ilmudan
teknologi, maka hal yang sangat pentingdan mendasar. terulang pada
manusia sendiri. Yang di_maksud dengan kata mendasar di sini ialah
kepribadian. Beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan sekeliling
kita menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Setiap hari media
cetak maupun media audio memuat berita-berita tentang penggunaan
wewenang seeara salah, korupsi, pencurian, perampokan dan
sebagainya. Gejala-gejala di atas, secara filosofis mencuatkan
pertanyaan-pertanyaan: Siapakah manusia itu? Apakah kepribadian?
Bagaimanakah pembentukan kepribadian manusia? Dan, bagaimana
implementasinya dalam pembentukan kepribadian manusia
Indonesia·?
Tinjauan filsafati· terhadap sosok tubuh manusia dengan
kepribadiannya, akan menghasilkan pengetahuan tentang manusia
pada umumnya, dan tentang manusia Indonesia pada khususnya yang
telah menentukan filsafat hidupnya yaitu Pancasila.
Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu keadaannya
seimbang. Benda-bends yang berada di sekeliling kita itu tidak pemah
tanpa bentuk, tidak pemah melulu materi. Benda_benda itu selalu
berada dalam satu kerangka yang dapat dikenali dan dapat tergapai
oleh pikiran manusia.. Semua kejadian yang berada di dunia ini
mempunyai satu sifat tertentu, yaitu ada bentuk-bentuknya menonjal
kedepan dan merealisasikan diri. Tanaman_tanaman di dalam proses
pertumbuhannya selalu menuju ke kesempurnaan sampai pada bentuk
yang paling bagus.
Filsuf Perancis, Bergson (1859- 1941), melihat manusia
sebagai satu_satunya makhluk hidup yang memiliki kesadaran bahwa
dalam dirinya ada yang disebutnya gairah hidup atau 'elan vital'.
Manusia tidak hidup dalam satu kotak meminjam istilah van Uexkuhl
'Umwelt'. la mengenal kemungkinan akan berhasil atau gagal, ia
29
mempunyai pengertian akan kata 'mati'. la dikaruniai insting dan
inteligensi. Inteligensi ini menduduki tempat yang amat penting
dalam hidup manusia.
Van Peursen melihat manusia dalam kerangka budaya.
Berdasarkan kemampuannya itu manusia meru_pakan makhluk
pembentuk budaya. Kebudayaan di sini adalah alam, dilihat dari sudut
pandang kemungkinan-kemungkinan manusiawi Manusia itu
memproyeksikan jalan hidupnya yang terbuka bagi dunia yang
mengelilinginya. Petani sejak jaman purba telah mengusahakan
tanahnya untuk pada suatu waktu menuai hasilnya. Sungai dibuat
menjadi waduk-waduk tempat air. Hasil-hasil pekerjaan tanah liat,
jembangan misalnya dihias dengan tanda-tanda yang berisi magi.
Matahari dipuja sebagai dewa.
Kepribadian
Membahas suatu kepribadian bukan sesuatu yang mudah,
terutama karena konsep kepribadian telah diberi arti yang bermacam-
macam sangat hervariasi dan tergantung dari aliran yang dianut oleh
si penulis. Juga dari gambaran yang telah disusun oleh penulis yang
bersangkutan mengenai manusia. Satu hal yang jelas disini adalah
kenyataan bahwa manusia merupakan sesuatu yang sentral. Manusia
hidup dalam masyarakat bersama manusia lain dan dalam kehidupan
bersama ini dituntut suatu sikap dari masing-masing individu. Di atas
telah disebutkan nama Bergson yang menyatakan, bahwa sebagai
makhluk hidup, manusia adalah satu-satunya yang memiliki
inteligensi, dan dengan inteligensinya ia menghadapi hidup.
Kecerdasannya, masyarakat dan bahasanya, menyatakan dengan tegas
perbedaannya dari makhluk hewan. Tetapi, gambaran tentang dunia
yang diterima oleh manusia lewat inteligensinya, belumlah lengkap,
karena mereka hanya menun_juUan lapisan luamya saja. Menerobos
lapisan luar, maraih inti kedalaman untuk menuju ke perkembangan
lebih lanjut, itulah kemampuan intuisi. Bagi Bergson, intuisi
merupakan kemam_puan manusia untuk meraih kenyataan yang tidak
tergantung pada posisi seseorang, dengan lain perkataan kenyataan
mutlak. Hal ini sangat penting artinya, dalam seorang manusia
mengambil satu keputusan (Bergson, 1932, hal. 199-201).
Suatu yang harus dicatat ialah konsep tentang tata tertib, struktur
30
dan sistem merupakan hal yang pokok untuk mengerti tentang
personalitas: mereka sama pentingnya bagi manusia untuk mengerti
tentang masyarakat dan kebudayaan. Harus diakui bahwa kepribadian
pada satu taraf mengandung artian organisasi, dan karenanya dia
merupakan struktur dan sistem dalam berbagai manifestasi mental
seorang individu. Namun demikian ini dapat diartikan dalam dua cara.
Pertama, istilah-istilah organisasi, struktur dan sistem menunjuk ke
sum_ber-sumber d.alam yaitu, impuls, dorongan dan perasaan dari
kehidupan mental seorang individu. Pendekatan yang kedua bertujuan
mempelajari tingkah laku organisme, baik hewani ataupun manusiawi
untuk menyusun hubungan-hubungan dan keajegan, dan berdasarkan
itu sampai pada suatu model teoritik mengenai organisme khusus.
Ada lagi suatu teori yang mengandalkan saat beroperasi, yaitu saat ini,
situasi ini dan di sini. Jadi menurut teori ini kepribadian adalah suatu
faktor yang bersifat situasional (Barbu, 1971, hal 125- 126).
31
BAB III
STRUKTUR SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA,
MASYARAKAT
A. Struktur Sosial
Struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang
lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi
sosial hierarkis dan pembagian kerja, serta dilandasi oleh
kaidahkaidah, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai sosial budaya.
Setiap manusia terkait dengan struktur masyarakat di mana ia
menjadi anggotanya. Artinya, setiap orang termasuk ke dalam
satu atau lebih kelompok, kebudayaan, lembaga sosial,
pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang yang terdapat di
dalam masyarakat.
Hal ini terjadi karena manusia mempunyai beragam
kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan ekonomi, politik, hukum,
sosial, dan lain-lain, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu
pun juga beragam. Untuk memenuhinya, manusia memerlukan
interaksi sosial dengan pihak lain atau lembaga yang
menyediakannya. Interaksi sosial merupakan salah satu wujud
dari sifat manusia yang hidup bermasyarakat. Sebagai anggota
masyarakat, manusia tertata dalam struktur sosial atau jaringan
unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur itu
mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial,
pelapisan sosial, kekuasaan, dan wewenang. Kemudian,
unsurunsur tadi berhubungan dengan berbagai segi kehidupan,
seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan lain-lain, serta saling
memengaruhi. Misalnya, segi ekonomi selalu berhubungan
dengan politik, segi politik selalu berhubungan dengan hukum,
dan seterusnya. Untuk memahami lebih jauh mengenai apa itu
struktur sosial, mari kita pelajari bersama pengertian struktur
sosial menurut pendapat para ahli sosiologi berikut ini.
a. George C. Homan, Mengaitkan struktur sosial dengan perilaku
elementer (mendasar) dalam kehidupan sehari-hari.
b. Talcott Parsons, Berpendapat bahwa struktur sosial adalah
keterkaitan antarmanusia.
32
c. Coleman, Melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan
antarmanusia dan antarkelompok manusia.
d. Kornblum, Menekankan konsep struktur sosial pada pola
perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-
ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan
antarkelompok dalam masyarakat.
e. Soerdjono Soekanto, Melihat struktur sosial sebagai sebuah
hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara
peranan-peranan.
. Unsur-Unsur Struktur Sosial
Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu
masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung
bersifat tetap. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu
diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta
suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup
bermasyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya unsur-
unsur tertentu.
Apa saja unsur yang terdapat dalam suatu struktur sosial
dalam masyarakat? Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial
tersusun atas sepuluh unsur penting berikut ini.
a. Adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para
anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari
anggota masyarakat.
b. Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat
c. Adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga
masyarakat.
d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan
sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam
bertingkah laku.
e. Adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan
pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat.
f. Adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari
anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga
sistem sosial dapat berlanjut.
g. Adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh
status dan peranan anggota masyarakat.
33
h. Adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman
dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara.
i. Adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial,
seperti pranata sosial dan lembaga.
j. Adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang
menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga
masyarakat.
Fungsi Struktur Sosial
Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku
perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, sehingga dapat
dilihat sebagai pembatas terhadap perilaku-perilaku individu atau
kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan
perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakatnya.
Seperti dikatakan di atas, bahwa struktur sosial merujuk pada
suatu pola yang teratur dalam interaksi sosial, maka fungsi pokok
dari struktur sosial adalah menciptakan sebuah keteraturan sosial
yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. Sementara
itu, Mayor Polak menyatakan bahwa struktur sosial dapat
berfungsi sebagai berikut.
1. Pengawas sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan-
kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan
kelompok atau masyarakat. Misalnya pembentukan lembaga
pengadilan, kepolisian, lembaga adat, lembaga pendidikan,
lembaga agama, dan lain-lain
2. Dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau
masyarakat karena struktur sosial berasal dari kelompok atau
masyarakat itu sendiri.
Dalam proses tersebut, individu atau kelompok akan
mendapat pengetahuan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan,
dan kepercayaan kelompok ataumasyarakatnya. Individu
mengetahui dan memahami perbuatan apa yang dianjurkan oleh
kelompoknya dan perbuatan apa yang dilarang oleh
kelompoknya.
Ciri-Ciri Struktur Sosial
Segala sesuatu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang
membedakan dengan sesuatu yang lain. Misalnya masyarakat desa
mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti bersifat gotong royong,
34
mengutamakan kebersamaan, tidak ada spesialisasi dalam pembagian
kerja, dan lain-lain yang membedakan dengan masyarakat perkotaan
yang cenderung individualistis dan adanya pembagian pekerjaan
sesuai dengan keahlian. Begitupun juga dalam struktur sosial. Abdul
Syani menyebutkan bahwa ada beberapa cirri struktur sosial, di
antaranya adalah sebagai berikut:
a. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan social yang
dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan
memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar
dilakukan secara organisatoris.
b. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial di antara
individu-individu pada saat tertentu. Artinya segala Bentuk pola
interaksi sosial dalam masyarakat telah tercakup dalam suatu
struktur sosial.
c. Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat.
Artinya semua karya, cipta, dan rasa manusia sebagai anggota
masyarakat merupakan aspek dari struktur sosial. Misalnya
komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, kesenian,
ilmu pengetahuan, dan lain-lain.
d. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis,
sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai
bagian tubuh yang membentuk struktur. Misalnya dalam sebuah
organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara,
dan seksi-seksi yang kesemuanya membentuk suatu struktur.
e. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan
perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian,
yaitu sebagai berikut.
1) Pertama, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang
bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan
2) Kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut
terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas,
keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan
sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan
dalam tubuh masyarakat.
35
B. Pengertian Individu
Individu berasal dari kata individum (latin) yaitu satuan kecil
yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis
artinya individu yang hidup berdiri sendiri tidak mempunyai kawan
atau sesuatu yang tidak dapat dibagi lag i yaitu suatu kesatuan
yang terkecil dan terbatas.
Menurut Soediman Kartohadi Prodjo menanamkan individu
sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras,
rasio dan rukun.
Raga atau jasmani merupakan bentuk jasad manusia yang
khas yang dapat membedakan antara individu satu dengan individu
yang lain sekalipun dengan ciri hakekat yang sama sebagai
manusia.
- Raga ini dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan
- Rasa atau perasaan individu dapat menangkap obyek gerakan
dari benda-benda, isi alam semesta seperti kerusakan, panas,
dingin, dan lain sebagainya.
- Rasio atau akal pikiran, merupakan kelengkapan manusia untuk
dapat mengembangkan diri mengatasi segala sesuatu yang
diperlukan dalam diri tiap individu.
- Rukun atau hidup bergaul dengan sesama individu secara
harmonis, damai dan saling melengkapi. Rukun ini merupakan
perangkat yang dapat mempengaruhi individu untuk dapat
membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut
masyarakat.
Individu yang memiliki empat syarat di atas hidup bersama
dalam masyarakat. Masyarakat terjalin dan terikat dalam hubungan
interaksi serta interaksi sosial dalam hidup manusia yang
bermasyarakat senantiasa terjadi penyesuaian antar individu
melalui proses sosialisasi ke arah hubungan yang saling
mempengaruhi.
Menurut George H. Mead (Soerjono Soekanto, 1983)
menyatakan bahwa hakekat pribadi (individu) terbentuk dari
tanggapan yang berasal dari pihak-pihak lain, oleh karena itu, maka
identitas merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai ciri-ciri
yang tetap maupun situasional, ciri-ciri tetap yang bersifat stabil
36
diperoleh dari tanggapan-tanggapan pihak-pihak lain yang bersifat
sinambung, sedangkan variasi situasional mungkin ada karena
peranan yang berbeda-beda dari pihak-pihak lainnya yang tidak
mustahil mengalami perubahan pada kedudukan maupun peranan.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa adanya perubahan-
perubahan lain di dalam proses interaksi sosial, merupakan hal
yang sangat penting di dalam pembentukan identitas pribadi
maupun perkembangannya kemudian.
Perhatian sosiologi terhadap perilaku manusia sebagai
individu timbul dan berkembang atas dasar ciri-ciri sosial dan
hubungan-hubungan yang kemudian memberikan identitas pada
individu. Identitas individu itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan
siapa individu tersebut mengadakan hubungan.
Dalam buku Pengantar Sosiologi karangan Haky (1982)
Coolye mengemukakan tiga fase dalam memunculkan konsep
tentang diri sendiri yaitu :
1. Fase persepsi yaitu apa yang dilihat orang lain dalam
kepribadian dan tingkah laku
2. Fase penafsiran yaitu bagaimana orang-orang lain menilai
apa yang mereka lihat di dalam diriku.
3. Dalam fase ketiga, individu dengan dasar jawabannya
sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan
sejumlah perasaan hidup diri sendiri dan mengembangkan
sejumlah sikap tentang dirinya, seperti sikap bangga,
sombong, rendah hati dan sebagainya.
C. Pengertian Masyarakat
Masyarakat berasal dari kata Musyarah (Arab) yang artinya
bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang
artinya berkumpul dan bersama, hidup bersama dengan saling
berhubungan dan saling mempengaruhi.
Dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi
dua pengertian yaitu :Society dan Community
Perkataan masyarakat sebagai community cukup
memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan
kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. Jadi ciri
dari community ditekankan pada kehidupan bersama dengan
37
berdasarkan pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau
sentimen.
Menurut Abdul Syani (1987) bahwa masyarakat sebagai
community dapat dilihat dari dua sudut pandang :
- Memandang community sebagai unsur statis, artinya community
terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas
tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan
masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat
setempat.
Misalnya : kampung, dusun dan kota-kota kecil
Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari
kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya
hubungan sosial, disamping itu dilengkapi pula oleh adanya
perasaan sosial. Nilai-nilai dan norma yang timbul atas akibat
dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.
- Community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya
menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor
psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya
terkandung unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan
yang sifatnya fungsional, contoh masyarakat pegawai negeri,
masyarakat mahasiswa dan sebagainya.
Dari kedua ciri-ciri khusus yang dikemukakan di atas, berarti
dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi
syarat tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti
society. Masyarakat dalam pengertian society terdapat interaksi
sosial, perubahan-perubahan sosial, perlindungan-perlindungan
nasional dan like interest hubungan-hubungan menjadi bersifat
pamrih dan ekonomis.
- Aguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan
kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas
baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan
berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri,
masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi
manusia. Sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan
mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.
- Hasan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat
didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa
38
manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan
dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.
- Ralph Linton bahwa masyarakat adalah setiap kelompok
manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama,
sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan
berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan
batas-batas tertentu.
Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa masyarakat
sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan
bersama manusia maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok,
yaitu :
a. Manusia yang hidup bersama
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
d. Merupakan suatu sistem hidup bersama, sehingga
menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota
kelompok merasa dirinya terlibat satu dengan yang lainnya.
D. Hubungan Antara Individu dan Masyarakat
Hubungan individu dan masyarakat pada hakekatnya
merupakan hubungan fungsional artinya hubungan antar individu
dalam suatu karakteristik merupakan kesatuan yang terbuka dan
ketergantungan antara satu sama lainnya. Alasan pokok terjadinya
kondisi ini adalah bahwa individu lain hidupnya senantiasa
menghubungkan kepentingan dan kepuasannya pada orang lain.
Hubungan individu dengan masyarakat bermula timbul dari
pengaruh keluarga dan dari kondisi sosial keluarga kemudian
membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan
sosialnya.
Dengan perbedaan-perbedaan ini berarti individu semakin
menyadari akan kekurangan masing-masing, yang apabila tidak
dipertukarkan, maka individu-individu itu tidak akan dapat
mencapai harapan hidup yang sempurna.
Beberapa pendapat para ahli memberi kesimpulan bahwa
manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa berhubungan dan
bekerjasama dengan orang lain menurut Hassan Shadily dalam
bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia mengatakan bahwa
39
manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat
karena didorong oleh beberapa faktor yaitu :
1. Hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang diluar
penguasaan akal) untuk mencari teman hidup, pertama
untuk memenuhi kebutuhan seksual makhluk hidup dari
sifat manusia yang biologis itu kemudian mendorongnya
untuk memenuhi kebutuhan seksnya, kebutuhan ini sebagai
manusia yang beradat dan beragama biasanya dipenuhi
dengan syarat-syarat perkawinan secara sah.
2. Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari
kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat dengan
orang lain, sehingga dapat berlindung bersama-sama dan
dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan
usaha bersama, akhirnya mendorong setiap individu
(manusia) untuk tidak terlepas hidup bermasyarakat.
3. Aristoteles berpendapat bahwa manusia ini adalah zoon
politicon, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup
bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup
bersama lebih suka daripada hidup sendiri.
4. Menurut Bergson, bahwa manusia ini hidup bersama bukan
atas karena persamaan, melainkan oleh karena perbedaan
yang terdapat dalam sifat, kedudukan dan sebagainya. Ia
mengatakan bahwa kenyataan hidup baru terasa dengan
perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam
kehidupan bergolongan.
Bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat, ada
tiga alternatif jawaban yaitu :
1. Individu memiliki status yang relatif dominan terhadap
masyarakat
2. Masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap
individu
3. Individu dan masyarakat saling bergantung
Hubungan antara individu dengan masyarakat seperti
dimaksud di atas menunjukkan bahwa individu memiliki status
yang relatif dominan terhadap masyarakat, sedangkan lainnya
menganggap bahwa individu itu tunduk pada masyarakat.
Sementara itu masih terdapat suatu hubungan lagi yaitu adanya
40
hubungan inter dependen (saling ketergantungan) antara individu
dengan masyarakat. Namun demikian masalah status individu di
dalam masyarakat biasanya merupakan satuan-satuan dari bentuk
masyarakat yang tidak terbatas kuantitasnya, setiap satuan individu
itu masing-masing mempunyai kekhususan yang berpengaruh
terhadap dinamika kehidupan masyarakat.
E. Keluarga
Keluarga adalah ikatan suatu kelompok manusia yang
berdasarkan tali perkawinan, membentuk sebuah rumah tangga,
secara bersama-sama/ kelompok tersebut menyatu antara hubungan
satu dengan yang lain, dan bekerjasama guna pemenuhan
kebutuhan hidup.
Kedudukan keluarga dalam masyarakat merupakan lembaga
sosial terkecil, yang berperang serta dalam kehidupan sosial,
bersama-sama keluarga lain mewujudkan masyarakat
berkebudayaan, peranan keluarga dalam masyarakat adalah
melaksanakan proses sosialisasi dan kontrol sosial.
- Fungsi Pokok Keluarga.
1. Keluarga memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan
biologis.
2. Keluarga berfungsi sebagai wadah emosional atau perasaan.
3. Keluarga berfungsi sebagai pendidikan sosialisasi.
4. Keluarga berfungsi sebagai ekonomi.
5. keluarga berfungsi sebagai pengawasan sosial.
- Susunan keluarga yang memberlaku.
1. Unilateral adalah susunan keluarga yang mengikuti satu garis
keturunan.
a. Patrilineal yaitu susunan keluarga yang mengikuti garis
keturunan ayah (laki-laki).
b. Matrilineal yaitu susunan keluarga yang mengikuti garis
keturunan ibu.
2. Bilateral (parental). Susunan keluarga yang mengikuti garis
ayah maupun ibu, kedua garis ini derajatnya sama.
3. Dauble Unilateral.
41
Susunan keluarga yang mengikuti garis ayah dan ibu secara
jalin-menjalin, ayah berkuasa dalam hal tertentu dan ibu
berkuasa dalam hal tertentu pula.
- Proses Pembentukan Keluarga. Proses perkawinan pada
umumnya melalui dua cara:
1. Cara mengikuti adat.
2. Cara yang bertentangan dengan adat.
1. Cara mengikuti adat melalui empat fase.
a) Penjajakan.
b) Mengirim utusan resmi.
c) Sebelum hari pemikahan mengirim utusan untuk
menyerahkan benda-benda tertentu.
d) Pelaksanaan perkawinan.
2. Cara yang bertentangan dengan adat.
a) Perkawinan lari: calon pengantin tidak disetujui oleh
orang tua.
b) Perkawinan levirat dan sororat.
Levirat : perkawinan seorang janda dengan saudara
sekandung bekas mendiang suaminya.
Sororat : perkawinan seorang duda dengan saudara
sekandung bekas mendiang istrinya.
c) Perkawinan meminjam jago.
Biasanya pada masyarakat patrilineal data rumah tangga
yang tidak mempunyai anak laki-laki (orang tua
wanita). Tujuan untuk meningkatkan upacara
keagamaan atau urusan lain-Jain.
d) Perkawinan jasa
Suatu perkawinan yang ditentukan karena jasa.
e) Perkawinan darurat
Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin
masyarakat dengan tujuan untuk menghilangkan rasa
malu terhadap orang lain.
- Beberapa bentuk perkawinan yang terjadi di beberapa daerah,
baik di Indonesia maupun negara-negara lain.
1. Monogami.
2. 2. Polygami.
- Polygamy.
42
- Polyandri.
3. Endogami.
4. Eksogami.
5. Eteutherogami.
6. Perkawinan cross causin.
F. Struktur dan Pranata Sosial
Dalam antropologi sosial, konsep struktur sosial sering
dianggap sama dengan organisasi sosial terutama apabila
dihubungkan dengan masalah kekerabatan dan kelembagaan atau
hukum pada masyarakat yang tergolong bersahaja.
Menurut Firth (Soejono Soekanto, 1983) bahwa organisasi
sosial berkaitan dengan pilihan dan keputusan dalam hubungan-
hubungan sosial yang lebih fundamental yang memberikan bentuk
dasar pada masyarakat yang memberikan batas-batas pada aksi
yang mungkin dilakukan secara organisatoril, sedangkan E.R.
Leach menetapkan konsep tersebut pada cita-cita tentang distribusi
kekuasaan diantara orang-orang dan kelompok-kelompok.
Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa struktur sosial
mencakup berbagai hubungan sosial antara individu-individu
secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis
dari suatu sistem sosial. Jadi struktur sosial tidak hanya
mengandung unsur kebudayaan belaka, melainkan sekaligus
mencakup seluruh prinsip-prinsip hubungan sosial yang bersifat
tetap dan stabil.
Dalam sosiologi, struktur sosial sering digunakan untuk
menjelaskan tentang keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada
prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang
sama. Menurut Soejono Soekanto (1983) bahwa struktur sosial
diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial
dan antara peranan-peranan. Secara singkat struktur sosial dapat
didefinisikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat
yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status
dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang
menumpuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat
memberikan bentuk sebagian suatu masyarakat.
Ciri-ciri struktur sosial :
43
1. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial
yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada
masyarakat.
2. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara
individu-individu pada saat tertentu.
3. Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat
yang dapat dilihat dari sudut pandang teoritis artinya dalam
setiap meneliti tentang kebudayaan selayaknya diarahkan
pada pemikiran terhadap pelbagai derajat dari susunan
sosialnya.
4. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis
atau yang membeku, sehingga dapat dilihat kerangka
tatanan dari berbagai bagian tubuhnya yang berbentuk
struktur.
5. Struktur merupakan tahapan perubahan dan perkembangan
masyarakat yang mengandung dua pengertian yaitu
pertama di dalam struktur sosial terdapat peranan yang
bersifat empiris dalam proses perubahan dan
perkembangan. Kedua, dalam setiap perubahan dan
perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian stabilitas
keteraturan dan integrasi sosial yang berkesinambungan
sebelum kemudian terancam proses ketidakpuasan dalam
tubuh masyarakat.
Pranata sosial adalah suatu sistem norma yang mengatur
segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya
dalam hidup bermasyarakat. Pranata sosial disebut juga dengan
institusi.
Wujud konkrit dari pranata sosial adalah tembaga atau institut,
suatu kebiasaan atau norma bisa menjadi pranata sosial apabila
telah melalui instrtusionalisasi, dan memenuhi tiga syarat, diterima
oleh masyarakat, menjiwai seluruh rakyat, dan harus mempunyai
sanksi.
Fungsi pokok suatu pranata sosial adalah sebagai berikut.
1. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
2. Memberikan pedoman bag! anggota dalam hkJup
bermasyarakat.
44
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat dalam menandakan
sistem pengendalian atau pengawasan sosial.
Fungsi-fungsi tersebut dapat diperjelas dalam tiap jenis
pranata sosial yang ada lima jenis pranata sosial yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat yaitu:
1. Pranata keluarga.
a. Fungsi pengaturan hubungan biologis.
b. Fungsi reproduksi.
c. Fungsi sosialisasi.
d. Fungsi afeksi.
e. Fungsi penentu kedudukan atau status.
f. Fungsi perlindungan dan
g. Fungsi ekonomi
2. Pranata pendidikan
a. Pranata pemindahan warisan kebudayaan.
b. Memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerjaan.
c. Mempersiapkan peranan sosial yang di kehendaki oleh
individu.
d. Memberikan landasan penilaian dan pemahaman status
relatif.
e. Memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan
hubungan sosial.
3. Pranata agama.
a. Bantuan terhadap pencarian identitas moral.
b. Memberikan penapsiran untuk menjelaskan keberadaan
manusia.
c. Peningkatan kehidupan sosial dan mempererat kohesi sosial
(hubungan sosial).
4. Pranata ekonomi.
a. Pengaturan produksi barang dan jasa.
b. Fungsi distribusi barang dan jasa.
c. Fungsi konsumsi barang dan jasa.
5. Pranata politik.
a. Melembagakan norma melalui undang-undang.
b. Melaksanakan undang-undang yang telah disetujui.
c. Menyesuaikan konflik yang terjadi.
d. Menyelenggarakan pelayanan umum.
46
BAB IV
TEORI PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
A. Teori Tehnologi dan Ketertinggalan oleh W.F. Ogburn.
William .F. Ogburn yang mendapat pendidikan di Universitas
Columbia dan menghabiskan sebagian besar hidup akademisnya di
Universitas Chigago. Sumbangannya yang paling terkenal terhadap
bidang sosiologi adalah konsepnya tentang ketertinggalan budaya
(cultural log). Konsep itu mengacu kepada kecendrungan dan
kebiasaan-kebiasaan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang
tertinggal di belakang perubahan kebudayaan material. Akibatnya
perubahan sosial selalu ditandai oleh ketegangan antara kebudayaan
materiil dan non materiil (Ogbum, "social change"). Pemikiran
Ogbum dapat di golongkan dalam pendekatan perilaku
(behaviorisme). Oleh karena Ogburn dalam karyanya
mengemukakan sebagai berikut:
a) Perilaku manusia merupakan produk warisan sosial atau budaya
bukan produk faktor- faktor biologis yang diturunkan lewat
keturunan.
b) Kenyataan sosial dasarnya terdiri atas pola-pola perilaku nyata
memperlihatkan suatu tingkat keteraturan tinggi yang
menemukan penemuan-penemuan baru yang inovatif, sedangkan
konsekuensinya adalah ketimpangan integrasi atau ketegangan
antara kebudayaan, materi yang lebih maju dengan kebudayaan
non materi yang tertinggal.
c) Perubahan-perubahan kebudayaan materiil terbentuk mulai dan
penemuan awal seperti perkakas tangan, komputer, satelit-satelit
komunikasi, sedangkan kebudayaan non materiil seperti
kebiasaan dan tata cara organisasi sosial yang akhirnya
berkonsekuensi harus menyesuaikan din dengan kebudayaan-
kebudayaan materiil. Namun karena adanya berbagai sumber
yang menolak perubahan proses penyesuaian itu selalu
ketertinggalan di belakang perubahan-perubahan budaya materiil,
akibatnya terjadi ketimpangan integrasi atau ketegangan budaya
antara budaya materiil dan non materiil.
d) Kebudayaan non materiil yang tidak mampu mengejar karena
kecepatan perubahan dalam kebudayaan materiil terus melaju.
47
Hasilnya adalah suatu ketegangan yang terus meningkat antara
budaya materiil dengan non materiil, akhirnya selalu
menimbulkan ketertinggalan budaya khususnya budaya non
materiil.
B. Teori Perubahan Budaya oleh Bronislaw Malinowski.
Dalam karyanya tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat
penduduk kehidupan Trobriand terbit, salah satu reaksi dan
kalangan antropologi adalah bahwa Malinowski tidak
memperhatikan proses perkembangan kebudayaan dalam
pemikirannya. Dengan melukiskan suatu masyarakat dengan
mengintegrasikan seluruh aspeknya menjadi satu, ia seolah-olah
mengambil gambaran dan masyarakat itu pada satu saat saja,
sehingga gambaran tadi merupakan suatu pembekuan dari
kehidupan masyarakat pada satu detik dalam ruang waktu
kekacauan itu rupanya diperhatikannya dan pada akhir
kehidupannya ia berhasil menulis sebuah buku. Dengan mengambil
bahan dan contoh-contoh dari Afrika, dalam buku itu ia
mengajukan suatu metode untuk mencatat dan menganalisa sejarah
dan proses-proses perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat
yang hidup.
C. Teori Perubahan Sosial Budaya
Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, ada yang
cepat, ada yang lambat. Pengaruh perubahan tersebut bisa terbatas
dari ruang lingkup yang kecil, tetapi bisa juga tidak terbatas dalam
ruang lingkup yang luas.
Perubahan-perubahan dalam masyarakat mengenai norma-
norma sosial, nilai-nilai sosial interaksi sosial, pada perikelakuan,
organisasi sosial, lapisan masyarakat dan lain-lain.
- Menurut pendapat W.F. Ogbum dalam bukunya "social change"
ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-
unsur kebudayaan material maupun isi material namun yang
terbesar adalah unsur-unsur kebudayaan material.
- Menurut John Levis Gillian & John Philips Gillian, perubahan
sosial adalah suatu variasi cara hidup yang telah diterima yang
disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi, geografis,
48
kebudayaan material ideology susunan masyarakat, penentuan,
baru dan adanya difusi dalam masyarakat.
- Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial ialah gejala
perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di
dalam nilai-nilai sikap, pola-pola perilaku diantara kelompok
dalam masyarakat
- Pendapat Mac Iver dalam bukungabn "A Textbook of Sociology*
membedakan antara kebudayaan (culture) dan peradaban
(civilization) ia meyakinkan bahwa perubahan-perubahan sosial
lahir perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai
perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut.
D. Faktor-faktor Menyebabkan Perubahan-perubahan Sosial
dan Kebudayaan
Untuk mempelajari suatu perubahan yang terjadi dalam
masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang
mengakibatkan terjadinya perubahan itu apabila diteliti lebih
mendalam apa sebabnya dapat terjadi suatu perubahan dalam
masyarakat maka pada umumnya dapat dikatakan bahwa yang
diubah mungkin dengan sadar, mungkin juga tidak dengan sadar
oleh masyarakat suatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi
adanya, adapun penyebab masyarakat tidak puas lagi pada suatu
faktor, mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan
masyarakat sebagai pengganti dan faktor lama. Pada umumnya
sebab tersebut bersumber pada 2 faktor
- Faktor dalam masyarakat
- Faktor diluar masyarakat (pengaruh dan masyarakat dan dari
alam sekitarnya)
Adapun sebab yang bersumber dalam masyarakat antara lain
adalah:
1. Bertambah dan berkurangnya penduduk
Bertambahnya penduduk menyebabkan terjadinya perubahan
dalam struktur masyarakat dan yang menyangkut lembaga
kemasyarakatan misalnya sewa tanah, gadai, bagi hasil.
Berkurangnya penduduk akibat perpindahan dari desa ke kola.
2. Ada penemuan-penemuan bam
49
Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-
perubahan dapat dibedakan dalam pengertian:
- Discovery, penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru
balk berupa alat maupun ide-ide yang diciptakan untuk
seseorang maupun gabungan dari beberapa individu.
- Invention: masyarakat sudah mengakui menerima serta
menerapkan penemuan-penemuan baru itu.
Apabila ditelaah lebih Ianjut perihal penemuan-penemuan
baru, ada beberapa pendorong bagi penemuan-penemuan baru
tersebut dalam masyarakat.
Adapun yang mendorong individu untuk mencari
penemuan-penemuan baru tersebut adalah:
a. Kesadaran dari seseorang akan kekurangan dalam
kebudayaannya
b. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
c. Perangsang bagi aktivitas penciptaan dalam masyarakat.
Suatu penemuan baru tidak hanya mempunyai suatu
akibat yang terbatas tetapi akibatnya dapat memancar ke bidang
lain lainnya penemuan radio dapat menyebabkan perubahan
dalam hai pendidikan, agama, kesenian, pemerintahan dan lain-
lain.
3. Pertentangan (Conflict) dalam masyarakat
Pertentangan tersebut mungkin terjadi orang perorangan
dengan antar kelompok.
Misalnya orang tidak menerima adat apakah meninggal waktu
anak-, jatuh di rawat oleh keluarga dari pihak bapak, dalam hal
ini tidak barlaku lagi.
4. Terjadinya perberontakan atau revolusi di dalam tubuh
masyarakat itu sendiri.
Sebab yang bersumber dari luar masyarakat:
1. Lingkungan alam/phisik yang ada di sekitar manusia.
Terjadinya bencana alam menyebabkan masyarakat (orang)
berpindah dan mendiami tempat baai yang mengakibatkan
terjadinya perubahan pada lembaga masyarakat.
2. Adanya peperangan
Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan
terjadinya perubahan, karena biasanya negara yang memang
50
akan memaksakan negara yang takluk untuk menerima
kebudayaannya menganggap lebih tinggi tarafnya.
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain:
Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat
mencukupi kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh
tambah baik secara langsung maupun melalui media massa.
Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan:
1. Kontak dengan kebudayaan lain, salah satu proses yang
menyangkut hal ini difusi.
Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari
orang perorangan atau dari masyarakat yang lain. Dengan
terjadinya difusi perubahan baru yang telah ditemui oleh
masyarakat, dapat diteruskan dan disebabkan pada masyarakat
luas sehingga dapat menikmati kegunaan bagi kemajuan
peradaban.
2. Sistem pendidikan formal yang maju
Pendidikan memberikan nilai lebih nilai terutama dalam
membuka fikirannya serta menerima hal-hal yang baru dan
bagaimana berfikir dinamis dan obyektif.
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan kemungkinan
untuk maju Apabila sikap tersebut melembaga dalam
masyarakat maka masyarakat akan memberikan pendorong
bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru
misalnya pemberian kalpataru.
Faktor-faktor yang menghambat proses perubahan
1. Kurangnya hubungan terhadap masyarakat lain,
Apabila suatu masyarakat tidak mau mengadakan hubungan
dengan masyarakat lain, maka warga masyarakat itu akan
terkungkung contohnya suku terasing.
2. Pendidikan yang masih terbelakang
Kehidupan masyarakat terasing (yang hanya dijajah) biasanya
kurang mengenal pendidikan, sehingga kurang memungkinkan
lahirnya unsur-unsur budaya baru.
3. Masyarakat yang bersikap tradisional
Masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lalu menganggap
bahwa tradisinya tidak perlu diubah, lebih-lebih jika para
pengusaha bersifat konservatif, sehingga perubahan akan
51
tertutup olehnya.
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertatam dengan
kuat atau disebut Vested Interests.
Golongan ini biasanya menjadi pelopor dalam masa-masa
transisi maka selalu mereka mengidentifikasikan diri dengan
usaha-usaha jasanya. Golongan tersebut sekali melepaskan
kedudukannya di dalam proses perubahan.
5. Rasa takut integrasi kebudayaan tergoyahkan
Masyarakat merasa takut Integrasi kebudayaannya goyah
karena sudah merasa mapan, sehingga takut terjadi bahaya
besar hal ini akan menghambat terjadinya perubahan.
6. Prasangka buruk terhadap unsur-unsur budaya asing yang
masuk Sikap ini biasanya terdapat pada masyarakat yang
pemah dijajah dan mereka mempunyai perasaan trauma
terhadap penderitaan akibat penjajah bangsa asing.
7. Hambatan yang bersifat ideologis
Usaha-usaha pemantapan budaya rohaniah tertentu, kadang-
kadang diartikan berlawanan dengan prinsip ideologis yang
berlaku, bahkan sering ada tuduhan yang meresahkan
kehidupan masyarakat.
8. Adat atau kebiasaan, setiap masyarakat adapt atau kebiasaan
yang merupakan pola-pola prilaku bagi anggota masyarakat
dalam mamenuhi kebutuhan pokoknya, suatu krisis akan timbul
apabila kemudian ternyata bahwa pola-pola perlakuan tersebut
tidak efektif lagi dalam memenuhi kebutuhan pokok.
9. Nilai bahwa hidup ini pada hakekatnya buruk tidak mungkin
diperbaiki prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau
sikap yang tertutup.
E. Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Kehidupan
Masyarakat
Perubahan Sosial budaya, perubahan yang terjadi dalam salah satu
unsur yang lain, sifat perubahan sosial ialah berantai
Jadi perubahan sosial ialah perubahan struktur dan hubungan
sosial.
- Menurut Parsudi Suparlan bahwa perubahan kebudayaan adalah
perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama
52
oleh para warga masyarakat, selera, rasa, keindahan dan
kesenian serta bahasa,
- Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua segi dari satu
kenyataan kehidupan sosial manusia telah ada masyarakat yang
tidak berbudaya, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa
masyarakat
- Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian
perubahan kebudayaan, perubahan kebudayaan lebih luas
cakupannya, dibandingkan perubahan sosial. Perubahan
kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, termasuk di
dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat,
bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.
F. Dampak Perubahan Budaya Terhadap Kehidupan Masyarakat
1. Perubahan Bahasa
Perubahan yang terjadi pada bahasa misalnya kata-kata yang
telah usang tidak dipakai lagi, perbendaharaan kata baru masuk
berdasarkan bahasa asing maupun bahasa daerah. Contoh: kata
bekas = mantan, bekas sekarang hanya diperuntukkan sesuatu
yang tidak berfungsi lagi. Kata bekas dewasa ini hanya
dipergunakan untuk menyebut benda-benda yang sudah tidak
dipakai.
2. Sistem Pengetahuan
Pada zaman dahulu, dalam kegiatan menghitung, biasanya
cukup dengan menggunakan jari, dalam perkembangan
selanjutnya, setelah tumbuhnya ilmu pengetahuan, lebih-lebih
masuknya pengaruh Cina di Indonesia, maka digunakan alat
hitung dari kayu yang dibuat bulat-bulat kecil yang berfungsi
sebagai angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan sebagainya.
Alat tersebut diberi nama Cempoa. Setelah ilmu pengetahuan
berkembang, maka ditemukan alat hitung yang disebut mesin
hitung, kalkulator dan computer. Hal ini membawa dampak
bahwa pekerjaan menghitung dan lain-lainnya akan cepat
selesai, yang berarti hemat waktu, tenaga, pikiran dan biaya,
maka akhirnya kesejahteraan menjadi lebih meningkat.
3. Sistem Organisasi Sosial
Pada zaman feudal Indonesia mengalami pemerintahan yang
53
berbentuk kerajaan yang bersifat absolut, kekuasaan di Indonesia
didominasi oleh para bangsawan yang dianggapnya sebagai
titisan atau penjelmaan dewa. Karena dewalah yang memiliki
dunia seisinya, maka raja yang dianggap titisan dewa tersebut
harus dihormati lebih dari manusia biasa, bahkan harus
mendapat perlakuan khusus, setelah proklamasi dari bentuk
kerajaan yang absolut, berubah menjadi negara yang berbentuk
republik yang didasarkan demokrasi. Dalam negara demokrasi,
maka para penguasa negara dipilih oleh rakyat berdasarkan
prestasi kerjanya. Dampak dari adanya perubahan budaya
semacam itu, mengakibatkan seseorang rakyat biasa bukan
keturunan bangsawan dapat memegang jabatan negara.
4. Sistem Teknologi
Sebelum terjadinya revolusi industri (abad 18) untuk
transportasi darat baru dapat membuat gerobag delman, yang
ditarik mula-mula dengan tenaga manusia, kemudian diganti
dengan tenaga hewan. Dalam transportasi laut dikenal perahu
dayung, kapal layar, kapal dayung menggunakan tenaga
manusia, sedang kapal layar menggunakan tenaga angin.
Setelah terjadinya revolusi industri, maka transportasi darat yang
semula digerakkan oleh tenaga hewan maupun manusia diganti
dengan tenaga uap, oleh karena itu lahirlah alat angkut darat
yang disebut kereta api. Dalam perkembangan selanjutnya
tenaga uap yang berasal dari air yang dipanaskan diganti dengan
minyak sebagai ganti air. Akhirnya lahirlah angkutan darat yang
disebut mobil, truk dan lain sebagainya.
Untuk angkutan Iaut, tenaga manusia dan angin digantikan oleh
tenaga uap, dengan demikian maka ditemukan alat angkutan
Iaut yang disebut kapal bermesin, akhirnya setelah ditemukan
bahan bakar minyak, maka berkembang alat angkutan laut yang
disebut kapal bermotor.
Dengan teknologi mutakhir, untuk alat angkutan udara,
ditemukan pesawat terbang yang telah mengalami berkali-kali
regenerasi yaitu dan pesawat terbang dengan menggunakan
baling-baling berkembang dengan pesawat yang menggunakan
tenaga jet.
Demham keterangan di atas, maka berkomunikasi antar
54
daerah, antar bangsa dan negara menjadi lebih cepat. Hal ini
membawa dampak bahwa pengiriman hasil-hasil produksi dapat
menjadi habis awal sampai pada konsumer? dan untuk barang
dapat habis terjamln. Hal ini mengakibatkan baik konsumen
maupun produsen menjadi lebih sejak area.
5. Sistem Mata Pencaharian
Pada waktu Indonesia masih dalam prasejarah, mula-mula
nenek moyang kita masih hidup dalam masa berburu dan
mengumpulkan makanan. Mereka telah mengenal bercocok
tanam, lambat laun nenek moyang mereka dapat mengenal
bercocok tanam, dalam hal ini mereka harus memperhatikan
tanaman-tanamannya, agar tanaman-tanaman tersebut dapat
menghasilkan diharuskan dapat dipelihara tanaman dengan baik.
Dalam perkembangan selanjutnya mereka lebih mengenal
sifat-sifat tanaman, ada tanaman yang memerlukan air dan ada
tidak, maka dalam hal ini dikenal sistem irigasi.
Dalam abad ke-20 sistem irigasi pertanian lebih
ditingkatkan pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda
melaksanakan trilogy Van De Venter yaitu dalam bidang transisi
dorsi, irigasi dan edukasi, trilogy tersebut untuk meningkatkan
hasil produksi bumi. Hal ini tidak mengalami perubahan nasib.
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia selalu
berusaha untuk meningkatkan hasil-hasil pertaniannya. Berbagai
upaya telah dilakukan, dengan menciptakan alat-alat pertanian
baru, mengembangkan bibit unggul, alat-alat, juga mengenalkan
pertanian dengan sistem supra unsur, dengan menggunakan
pupuk berimbang yang terakhir ditemukan pupuk urea dan
dalam bentuk tablet yang ternyata lebih efisien.
Bangsa Indonesia yang semula mata pencahariannya
mengandalkan pertanian akhirnya oleh pemerintah dianjurkan
untuk mengembangkan kerajinan rumah (home widotory)
industri berat, dan home industri dan industri pariwisata
6. Sistem Religi
Pada jaman pra sejarah ketika hidup Homo Wajakensis, orang
telah mengenal penguburan mayat, soal mati adalah salah satu
hal yang sangat merisaukan hati manusia. Dalam hal kematian
orang-orang pada waktu itu percaya adanya kekuatan gaib di
55
luar dirinya yang menguasai hidup manusia.
Pada waktu bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan
bangsa India, maka kepercayaan Indonesia asli itu diwarnai oleh
budaya India akhirnya berkembang ajaran Hindu, Buddha yang
diselaraskan dengan kepercayaan yang telah ada. Karena itulah
kehidupan beragama di Indonesia sejak zaman dahulu sudah
saling mengadakan semangat toleransi. Tidak diherankan bahwa
sejak Indonesia merdeka diakui adanya lima agama yang sah
yang berkembang di Indonesia yang dikelola oleh departemen
agama.
7. Sistem Kesenian
a. Pada zaman pra sejarah, kegiatan seni sudah ada, berbagai
barang dapur di kemukakan misalnya benang, perhiasan,
manik-manik, lukisan berwarna di dinding goa Sulsel, kebun
batu di Sumatera Selatan, sudah menemukan adanya
kesenian yang cukup tinggi.
b. Pada zaman sejarah
Kesenian yang sudah berkembang pada zaman pra sejarah
berkembang terus, meskipun sudah masuk dalam zaman
sejarah, bahkan kesenian diperkaya dengan bertambahnya
kesenian antara lain;
a. Sastra
b. Teater
56
BAB V
LEMBAGA/PRANATA SOSIAL
Kerangkan sosial masyarakat tidak muda diidentifikasikan
atau diobservasi seperti struktur pisiknya. Di dalam inter-relasi dan
interaksi manusia menciptakan bentuk-bentuk asosiasi yang
merupakan unit-unit aktifitas di kalangan mereka sendiri,
disamping menyusun mekanisme-mekanisme utama bagi
kegiatannya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan
adanya lembaga sosial, di mana interaksi sosial dapat terjadi di
dalamnya. Dengan adanya lembaga sosial akan tercipta keteraturan
sosial dalam hidup bermasyarakat. Tak hanya itu, lembaga
sosial juga menjadi pedoman individu dalam bersikap serta
memberikan batas-batas dalam bertingkah laku agar individu tidak
menyimpang. Masing-masing lembaga sosial dibentuk atas dasar
fungsi dan tujuan yang berbeda antara satu lembaga dengan
lembaga lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai lembaga sosial,
bisa memahami pengertian dari para ahli, beserta jenis-jenisnya.
• Koentjaraningrat
Lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan
yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-
kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
• Leopold Von Weise dan Becker
Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antarmanusia dan
antarkelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta
pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan
kelompoknya.
• Robert Mac Iver dan C.H. Page
Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah
diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung
dalam suatu kelompok masyarakat.
• Soerjono Soekanto
57
Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala
tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam
kehidupan masyarakat.
Jenis-Jenis Lembaga Sosial
• Lembaga Keluarga
Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil, yang
terbentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Meski
lembaga keluarga merupakan yang paling kecil, memiliki peran
yang sangat besar dalam kehidupan manusia.
• Lembaga Pendidikan
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya
proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu
ke arah yang lebih baik.
Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai lembaga sosial
lanjutan setelah keluarga. Penyelenggaraan pendidikan sekolah
dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan luar
sekolah.
Lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan
informal.
• Lembaga Ekonomi
Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di
bidang ekonomi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lembaga
ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan
antarmanusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi
dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya
kebutuhan masyarakat.
• Lembaga Agama
58
Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai
kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama merupakan
sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat.
Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia,
yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan agama
menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama
manusia, mahkluk hidup lain, dan alam sekitar.
• Lembaga Politik
Lembaga politik adalah suatu bentuk kegiatan dalam suatu
kelompok masyarakat yang proses pembentukan dan pembagian
kekuasaannya ditentukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri.
Lembaga politik dapat berbentuk pemerintahan yang berperan
sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, serta melayani dan
melindungi masyarakat.
• Lembaga Budaya
Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang
berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni,
lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu
daerah atau negara. Lembaga-lembaga kebudayaan, baik yang
berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), sanggar, atau
paguyuban merupakan elemen lain yang dapat berperan serta
dalam pelestarian seni dan budaya.
Bentuk-bentuk lembaga ini mempunyai fungsi khusus
yang telah diklasifikasikan sebagai unsur-unsur dari struktur sosial
yang mengikat mereka menjadi suatu struktur secara menyeluruh.
Berikut ini akan dikemukakan beberapa bentuk utama struktur
persekutuan hidup manusia yang menyusun masyarakat serta
menentukan hubungan-hubungannya.
A. Institusi Sosial
Institusi sosial yang dalam bahasa Asing dikenal
dengan istilah social institution, para ahli dan sarjana sosiologi
menterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bermacam-
macam istilah, karena belum terdapatnya kesepakatan tentang
penggunaan istilah dalam Bahasa Indonesia. Hingga pada saat
59
sekarang ini para ilmuwan belum memiliki suatu istilah yang
dirasakan secara tepat dapat menggambarkan secara keseluruhan
isi yang terkandung dalam institusi sosial.
Prof.Dr.Koentjaraningrat, misalnya memakai istilah
pranata sosial, oleh karena beliau beranggapan bahwa social
institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur
peri kelakuan para anggota masyarakat. Lalu beliau
mengemukakan bahwa pranata sosial adalah “suatu sistem tata
kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas
untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam
kehidupan masyarakat”.
Istilah lain dalam bahasa Indonesia, diusulkan
bangunan sosial, mungkin terjemahan dari Soziale Gebilde,
istilah mana lebih mendekat gambaran bentuk dan susunan sosial
institution. Tepat tidaknya istilah tersbut, tentunya tergantung
pada para pemakainya. Khusus dalam diktat ini akan dipinjam
dan digunakan istilah dai Prof.Dr.Soejono Soekanto, SH.,MA;
istilah Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Sosial.
Mac Iver dan Charles H.Page, mengartikan Lembaga
Sosial sebagai:
Tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur
hubungan antar manusia yang berkelompok dalam satu
kelompok kemasyarakatan yang dinamakan “asosiasi”.
William Graham Summer, melihat dari sudut kebudayaan dan
mengemukakan Lembaga Sosial, ialah:
Perpolaan fungsional dari pola-pola kebudayaan yang juga
meliputi perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan
kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
B. Batasan Pengertian
Sosial intitution atau Lembaga Sosial menunjuk pada
adanya unsur-unsur yang mengatur peri-kelakuan para anggota-
anggota masyarakat. Dari segi bahasa dan percakapan sehari-hari
yang dimaksudkan dengan “lembaga”ialah biasanya suatu badan,
misalnya lembaga pemeliharaan anak yatim, lembaga pendidikan
atau secara umum berbagai bentuk organisasi yang mempunyai
60
tujuan amal atau memelihara dan memperluas pengetahuan dan
sebagainya.
Dalam ilmu sosiologi, yang dimaksudkan dengan
lembaga sosial ialah suatu kompleks atau sistem peraturan-
peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang
penting.
Lembaga tersebut mempunyai tujuan untuk mengatur
antar hubungan yang diadakan dalam memenuhi kebutuhan
manusia yang penting. Lembaga sosial memberikan pengertian
kata lembaga, yang lebih banyak menunjuk pada sesuatu bentuk
dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang
abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan
tertentu yang menjadi ciri dari lembaga tersebut. Dapat pula
dikatakan bahwa lembaga sosial ialah himpunan dari pada norma-
norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan
pokok didalam kehidupan masyarakat.
C. Proses Pertumbuhan Lembaga Sosial (Lembaga
Kemasyarakatan).
1. Norma-norma Masyarakat
Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu
masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka
dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma
tersebut berbentuk secara tidak sengaja. Namun lama
kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar.
Misalnya, dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak
harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi lama
kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat
bagiannya. Contoh lain perihal perjanjian tertulis yang
menyangkut pinjam meminjam uang yang dahulu tidak
pernah dilakukan. Norma-norma yang ada di dalam
masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-
beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang
terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir, umumnya anggota-
anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya. Untuk
dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma
tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian
61
yaitu :
a. Cara (usage)
b. Kebiasaan (folkways)
c. Tata kelakuan (mores)
d. Adat-istiadat (custom)
Masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar
yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma
kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku
seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap pengertian di
atas mempunyai kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan
menunjuk pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya
mentaati norma. Cara (ussage) menunjuk pada suatu bentuk
perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan sangat lemah bila
dibandingkan dengan kebiasaan (folkways). Kebiasaan menunjuk
pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
Cara (usage) lebih menonjol di dalam hubungan antar
individu di dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya
tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya
sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. Misalnya orang
mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu
bertamu. Ada yang minum tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula
yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda rasa kepuasannya
menghilangkan kehausan. Dalam cara yang terakhir biasanya
dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan. Apabila cara
tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak orang yang
diajak minum bersama akan merasa tersinggung dan mencela
cara minum yang demikian.
Kebiasaan (folways) mempunyai kekuatan mengikat
yang lebih besar dari pada car. Kebiasaan diartikan sebagai
perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama,
merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan
tersebut. Sebagai contoh kebiasaan memberi hormat kepada
orang lain yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan,
maka akan dianggap suatu penyimpangan terhadap kebiasaan
umum dalam masyarakat. Kebiasaan menghormati orang-orang
yang lebih tua, merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan
setiap orang akan menyalahkan penyimpangan terhadap
62
kebiasaan tersebut.
Menurut Mac Iver Page kebiasaan merupakan perilaku
yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya dikatakan
bahwa apabila hal tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai
cara perilaku saja. Akan tetapi bahkan diterima sebagai norma-
norma pengatur, maka disebutkan kebiasaan tadi sebagai mores
atau tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang
hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat
pengawas, secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat
terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan disatu pihak
memaksakan dan di lain pihak melarangnya, sehingga secara
langsung merupakan alat, agar anggota masyarakat menyesuaikan
perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut.
Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang
sungguh-sungguh berlaku, apabila norma-norma sepenuhnya
membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku
perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal
sekunder bagi lembaga kemasyarakatan.
Paksaan hukum di dalam pelaksanaan lembaga
kemasyarakatan yang berlaku sebagai peraturan tidak selalu
digunakan. Sebaliknya tekanan diutamakan pada paksaan
masyarakat. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
berlaku sungguh-sungguh faktor paksaan tergantung dari
pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong royong, kerja
sama dan sebagainya.
Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga
(instituonalized), apabila norma tersebut :
I. Diketahui
II. Difahami atau dimengerti
III. Ditaati dan
IV. Dihargai.
2. Sistem Pengendalian Sosial (Social Control)
Sebagaimana diketahui bahwa nilai dan norma tercipta
oleh anggota-anggota masyarakat, tetapi mereka sekaligus
menjadi alat pengontrol tingkah laku anggota-anggota
masyarakat. Melalui sosial control ini, nilai dan norma
digunakan un tuk mendidik, mengamengajak atau bahkan
63
memaksa warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah
dan nilai-nilai sosial yang berlaku yang mengatur hubungan
individu, kelompok dan antar keduanya (individu dalam
kelompoknya).
Dalam bukunya Prof Dr. Soejono Soekanto, SH, MA.,
dikatakan bahwa Pengendalian sosial (social control)
bertujuan untuk secara mencapai keserasian antara stabilitas
dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu
sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai
keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan
keadilan/kesebandingan.
Kehidupan bersama dalam masyarakat tidak akan
mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya usaha agar
anggota-anggota masyarakat menyesuaikan tindakan-
tindakannya dengan nilai-nilai serta norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat tersebut. Namun hal tersebut
tidaklah berarti bahwa sosial control bertujuan untuk secara
mutlak memaksakan nilai-nilai dan norma-norma yang
berlaku terhadap kelakuan para anggota masyarakat.
Dari sudut sifatnya pengendalian sosial dibagi dua
macam. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa social control
dapat bersifat preventif dan represif atau bahkan keduanya.
Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap
terjadinya gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran
kaidah/nilai pada keserasian norma-norma yang seharusnya
berlaku dan dipatuhi sebagai contoh pendidikan formal dan
informal (pendidikan anak dalam keluarga, sekolah, lembaga
keagamaan dan sebagainya).
Social control repressif berwujud penjatuhan sanksi
terhadap warga masyarakat yang melanggar kaidah/norma
yang berlaku serta mempunyai sifat untuk
mengembalikan/memulihkan pada keadaan yang dianggap
baik (benar) oleh masyarakat.
Suatu contoh social control, baik yang preventif
maupun repressif dapat diambil dari salah satu pasal dari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya pasal 362
KUHP tentang pencurian. Para ahli hukum bermaksud
64
pertama-tama agar tidak terjadi pencurian, karena merugikan
masyarakat, jadi sifatnya preventif. Selanjutnya bila terjadi
juga pencurian tersebut, msks pelakunya akan mendapat
ganjaran berupa hukuman yang mengakibatkan penderitaan
baginya. Hal tersebut dimaksudkan agar dimasa akan datang
perbuatan tersebut tak akan diulanginya lagi.
Social control yang preventif, kadang-kadang
merupakan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat
yang dapat dijadikan teladan bagi warga masyarakat lainnya.
Contohnya pemberian tanda jasa atau penghargaan kepada
orang-orang yang berjasa kepada bangsa/negara atau
membawa harum nama baik bangsa/negara.
Menurut Prof.Dr.Koentjaraningrat, ada lima tujuan dan cara
social control sebagai berikut :
1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat, akan
kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Dalam hal ini
dilakukan melalui pendidikan atau dengan menciptakan
social suggestion, yaitu yang antara lain berwujud cerita-
cerita tentang orang besar, pahlawan-pahlawan dan lain-lain
yang tealah berhasil menjaga keutuhan norma-norma dalam
masyarakat
2. Memberikan penghargaan anggota masyarakat yang taat
pada norma-norma kemasyarakatan. Selain dengan cara
pemberian penghargaan sebagaimana yang tersebut, maka
dalam ajaran-ajaran agama banyak dijumpai ajaran yang
menganjurkan berkelakuan baik agar kelak mendapat pahala.
3. Menimbulkan rasa takut. Dalam hal ini rasa takut akan
sangsi-sangsi anggota-anggota masyarakat terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya. Disamping itu
adanya pula ketakutan atau pelanggaran terhadap magie.
4. Mengembangkan rasa malu dalam diri perasaan anggota-
anggota masyarakat, bila merasa menyimpang atau
menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-
nilai yamg berlaku.
5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan
sangsi-sangsi yang tegas bagi para pelanggarnya.
Dalam sistem hukum tersebut dikenal formal social control,
65
sebagai lawan dan informal social control, oleh karena
sistem hukum pada umumnya terwujud dalam tata cara yang
dibentuk oleh badan-badan tertentu (misalnya DPR) tatacara
mana dapat dipaksakan berlakunya. Sebaliknya informal
social control daya berlakunya banyak tergantung pada
kenyataan-kenyataan apakah masyarakat menyukai atau
tidak.
D. Fungsi Lembaga Sosial
Fungsi lembaga sosial adalah sebagai pedoman
masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di
kehidupan sehari-harinya. Tak hanya itu, lembaga sosial juga
berfungsi sebagai penyatu individu-individu yang ada di
lingkungan kehidupan masyarakat. Lembaga sosial biasanya
dijadikan sebagai tempat belajar sekaligus sebagai penegak
berbagai macam tindakan yang dilakukan masyarakat. Selain itu,
lembaga sosial merupakan wadah tempat bersatunya masyarakat
yang ada di sekitar lembaga sosial tersebut.
Dengan memperhatikan segala batasan pengertian dan
defenisi-defenisi tersebut, maka dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa; suatu lembaga social adalah merupakan suatu
kompleks peraturan-peraturan dan peranan-peranan social. Jadi
lembaga tersebut lebih bersifat suatu konsepsi dan bukan sesuatu
yang konkrit. Atau dengan kata lain, lembaga sosial tersebut ada
seginya yang kulturil, berupa norma-norma dan nilai-nilai, tetapi
ada pula seginya yang strukturil, berupa berbagai peranan sosial.
Norma-norma dalam masyarakat mengatur pergaulan
hidup dengan bertujuan untuk mencapai suatu tata-tertib. Norma-
norma tersebut apabila diwujudkan dalam hubungan antar
manusia dinamakan organisasi sosial (social organization).
Dalam perkembangan norma-norma tersebut
berkelompok-kelompok pada berbagai keperluan pokok daripada
kehidupan manusia seperti; kebutuhan hidup, kebutuhan
pencaharian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk
rasa keindahan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya
kebutuhan hidup kekerabatan (pembentukan keluarga), setelah
dua orang muda-mudi saling berkenalan lalu saling tertarik
66
(saling jatuh cinta), lalu terjadilah
- Proses terjadinya lembaga sosial
- Saling bercintaan – pacaran
- Peminangan – sirih pinang
- Tukar cincin – pesta pernikahan
- Perkawinan – terbentuklah rumah tangga dan seterusnya.
Dari contoh tersebut diatas kiranya dapatlah diambil
suatu kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan
terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah
masyarakat tersebut telah mempunyai taraf kebudayaan yang
tinggi perkembangannya ataupun masih sederhana. Hal tersebut
disebabkan oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai
kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-
kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga sosial.
Untuk memberikan suatu btasan umum, dapatlah
dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan dar pada
norma-norma dan segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
Asosiasi (asosiation) adalah wujud yang konkrit
daripada lembaga sosial. Lembaga sosial , yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia pada
dasarnya mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Menetapkan pedoman pada anggota-anggota masyarakat,
bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam menghadapi
masalah-masalah dalam masyarakat.
2. Menjaga keutuhan dan kelestarian dari masyarakat.
3. Memberikan petunjuk kepada anggota-anggota masyarakat
dalam sistem social-control.
E. Ciri-ciri Dan Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan
Menurut Gillian dan Gilan dalam karyanya yang
berjudul General Features of Social Institution menguraikan ciri
dan tipe lembaga kemasyarakatan.Ciri-ciri Lembaga
Kemasyarakatan sebagai berikut :
1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola
pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui
aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Seperti:
67
adat istiadat, tata kelakuan kebiasaan serta unsur-unsur
kebudayaan lainnya baik secara langsung maupun secara
tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu, sistem kepercayaan dan
aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga
setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Mempunyai suatu tujuan tertentu
4. Mempunyai alat perlengkapan yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan lembaga bersangkutan seperti bangunan,
peralatan, mesin dan lain sebagainya.
5. Memiliki lambang-lambang yang secara simbolis
menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang
bersangkutan.
6. Mempunyai tradisi tertulis maupun yang tak tertulis, yang
merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.
Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan.
Menurut Gillian dan Gillian lembaga kemasyarakatan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Crescive institution dan enacted institution yang merupakan
klasifikasi dari sudut perkembangannya. Crescive institution
disebut lembaga-lembaga paling primer yang secara tak
disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, contohnya hak
milik, perkawinan, agama dan seterusnya.
2. Dari sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, timbul
klasifikasi atas Basic institutions dan subsidiary institution
dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting
untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam
masyarakat. Misalnya sekolah-sekolah, keluarga, negara dan
lain-lain dianggap sebagai basic institution yang pokok.
Sebaliknya subsidiary insttitution yang dinggap kurang penting
seperti, kegiatan rekreasi.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat, dapat dibedakan approved
atau social sanctioned institutions dengan unsanctioned
institutions. Approved atau social santioned institutions, adalah
lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah,
perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah
68
unsantioned institutions yang ditolak yang ditolak oleh
masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil
memberantasnya, misalnya kelompok penjahat, pemeras,
pencoleng dan sebagainya.
4. Pembedaan antara general institutions dengan restricted
institutions, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada
faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu
general institution, karena dikenal hampir seluruh masyarakat
dunia. Sedangkan agama-agama Islam, protestan, katolik,
Budha dan lain-lainnya merupakan restricted institution, karena
dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia lain.
5. Sudut fungsinya terdapat pembedaan operative institutions,
berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau
tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga.
Yang kedua bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata-
kelakuan yang tidak menjadi bagian untuk lembaga itu sendiri.
69
BAB VI
PROSES-PROSES SOSIAL
A. Pembatasan Pengertian
Sebagaimana diketahui bahwa sosiologi juga membahas
dan meneliti proses-proses sosial (social processes). Masyarakat,
manusia itu terdiri dari dua aspek, ialah aspek strukturil dan
aspek fungsionil atau dengan kata lain aspek statis dan dinamis.
Aspek strukturil dari suatu masyarakat ialah berupa lembaga-
lembaga (institution). Sedang aspek funsional atau aspek dinamis
adalah segala hubungan kemanusiaan baik jasmaniah maupun
rohaniah dalam hidup bermasyarakat dan inilah yang disebut
sebagai proses-proses sosial/kemasyarakatan. Kedua aspek
tersebut tidaklah muda ditarik yang garis konkrit, terlebih pula
karena keduanya erat terjalin sehingga sukar untuk
membicarakan satu aspek tanpa membicarakan yang lain.
Para ahli sosiologi merasakan betapa perlunya
pengetahuan tentang proses-proses sosial tersebut, karena
pengetahuan mengenai struktur masyarakat saja tidaklah
memadai untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai
kehidupan bersama dari manusia (masyarakat). Pengetahuan
tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang untuk
memperoleh pengertian mengenai segi dinamika dari masyarakat
atau dengan kata lain gerak dari masyarakat.
Proses-proses sosial adalah proses kelompok-kelompok
dan individu-individu yang saling berhubungan, yang merupakan
bentuk-bentuk antar aksi dan interaksi sosial. Interaksi sosial
ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok
manusia atau individu-individu mengadakan hubungan satu sama
lain. Bentuk-bentuk hubungan itu berbeda-beda antara yang satu
dengan yang lainnya dan menunjukkan ciri-ciri khas.
Jadi masyarakat yang dikenal sehari-hari, terdiri dari
rangkaian proses-proses sosial atau proses-proses
kemasyarakatan yang terus menerus bergerak (secara dinamis).
Suatu proses sosial adalah rangkaian human action (sikap dan
tindakan manusia) yang merupakan aksi dan reaksi atau
70
chalenges and response) di dalam hubungannya satu sama lain.
Jadi dapat pula dikatakan bahwa proses-proses sosial adalah
pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.
Para ahli sosiologi menggambarkan proses sosial itu
seakan-akan suatu bentuk spiral, yaitu dimulai suatu aksi
(challenge) yang menimbulkan reaksi (response) dan response itu
menimbulkan challenge baru, yang kemudian menimbulkan
response lagi dan seterusnya. Pengaruh timbal balik antar
pelbagai segi kehidupan bersama, jelas dapat dilihat pada bentuk-
bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuk yang tampak apabila
individu atau kelompok-kelompok manusia/sosial mengadakan
hubungan satu sama lain dengan terutama mengetengahkan
interaksi sosial sebagai unsur-unsur pokok dan fungsi masyarakat
atau segi dinamika dari masyarakat.
Pengertian interaksi sosial ini sangat berguna dalam
memperhatikan dan mempelajari banyak masalah di dalam
masyarakat. Dalam buku yang berjudul “sosiologi and social life”
yang dikemukakan oleh Kimbal Young-Raymond W.Mack
menyatakan “interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan
sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada
kehidupan bersama”.
Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila
individu atau kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara
dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan
kerja sama, persaingan ataupun pertentangan dan sebagainya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi sosial
adalah dasar pokok proses-proses sosial, pengertian mana dan
menunjuk pada segi dinamika dari masyarakat.
B. Interaksi Sosial (social interaction)
Sebagaimana diketahui bahwa interaksi sosial
adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan
bersama. Atau dengan kata lain apa yang akan terjadi apabila ada
perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara
hidup atau bentuk-bentuk yang telah ada. Interaksi sosial
menunjuk pada pengaruh timbal balik (memberi dan menerima
atau challenge dan response) dari kegiatan-kegiatan individu atau
71
kelompok-kelompok, yang biasanya dinampakkan dalam
berkomunikasi.
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial
yang dinamis, sebagai contoh misalnya; bila dua orang
berpapasan, maka interaksi sosial dimulai. Pada saat itu mereka
mungkin saling menegur, saling berjabat tangan, saling
tersenyum, saling memeluk bahkan mungkin pula saling bertinju
karena berkelahi. Aktivitas seperti itu merupakan bentuk-bentuk
interaksi sosial.
C. Syarat-syarat Interaksi sosial
Interaksi sosial secara sederhana dan secara singkat
dapat dikatakan bahwa semua bentuk hubungan antar manusia,
baik individu terhadap individu, maupun individu terhadap
kelompok sosial, ataupun kelompok sosial terhadap kelompok
sosial.
Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak
terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Adanya kontak sosial (social conteck)
2. Adanya komunikasi (communication)
Kalau kita berbicara mengenai etimologi dari kata
kontak, maka hal tersebut berasal dari bahasa latin, yang
terdiri dari dua suku kata con dan tango. Con artinya
bersama-sama dan tango artinya menyentuh. Jadi arti
logikanya adalah bersama-sama menyentuh. Kontak secara
fisik baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Akan
tetapi sebagai gejala sosial, hal tersebut tidak perlu adanya
hubungan badaniah, oleh karena orang dapat mengadakan
hubungan dengan pihak lain tanpa sentuhan secara badaniah
seperti misalnya dengan cara berbicara dengan pihak lain
tersebut. Juga dengan perkembangan alat-alat elektronika
dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu dengan
lainnya melalui telepon, radio, telegrap, surat dan
sebagainya, tanpa memerlukan hubungan badaniah.
Sebagai contoh dapat dikatakan: kontak antara
pasukan kita dengan pasukan musuh. Berita tersebut berarti
bahwa masing-masing pasukan telah mengetahui dan sadar
72
akan posisi masing-masing, dan tealah siap untuk saling
menembak. Contoh lain ; suatu patroli polisi yang sedang
mengejar perusuh, mengadakan kontak dengan markas besar
kepolisian; hal tersebut berarti masing-masing pihak siap
untuk mengadakan interaksi sosial.
Suatu permasalahan pokok yang penting, bahwa
terjadinya suatu kontak, tidak semata-mata tergantung dari
tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindak
tersebut, sebagai contoh : seorang dapat saja bersalaman
dengan sebuah patung, atau bermain mata dengan seorang
buta,tanpa menghasilkan suatu kontak.
Kontak sosial tersebut dapat bersifat positif, akan
tetapi dapat pula bersifat positif mengarah kepada suatu kerja
sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu
pertentanga, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan
suatu interaksi sosial.
Suatu kontak dapat bersifat primer, akan tetapi dapat
pula bersifat sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang
mengadakan hubungan langsung bertemu, sebagai contoh
misalnya orang tersebut berjabat tangan atau saling
tersenyum. Sebaliknya kontak sekunder memerlukan suatu
perantara.
D. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial
Para ahli sosiologi telah membagi bentuk-bentuk
interaksi sosial ke dalam 4 bentuk pokok, sebagai berikut ;
a. Kerjasama (co operation)
b. Persaingan (compotition)
c. Pertentangan (conflict)
d. Akomodasi (accomodation)
ad.1. beberapa orang sosiolog menganggap bahwa kerjasama
merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya
sosiolog lain menganggap bahwa kerjasamalah yang merupakan
proses utama. Kerjasama disini yang dimaksudkan sebagai suatu
usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia
untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.
Adapun lima bentuk kerja sama yaitu;
73
a. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong
menolong
b. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai
pertukaran barang- barang dan jasa-jasa antara dua organisasi
atau lebih
c. Ko-optasi (co-optation), yaitu proses penerimaan unsur-unsur
baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan polotik dalam
suatu organisasi.
d. Koalisi (coalition), yakni kombinasi antara dua organisasi
atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama
e. Join-venture, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek-
proyek tertentu misalnya pemboran minyak, pertambangan
batubara, perfilman, perhotelan dan sebagainya.
Ad.2. Persaingan atau compotition dapat diartikan sebagai suatu
proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia
yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang
kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian
umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam
prasangka yang ada tanpa mempergunakan ancaman atau
kekerasan.
Adapun bentuk-bentuk persainganantara lain :
1. Persaingan ekonomi
2. Persaingan kebudayaan
3. Persaingan kedudukan dan peranan
4. Persaingan ras, sebenarnya juga merupakan persaingan di
bidang kebudayaan.
Ad.3. Pertentangan (pertikaian atau conflict). Pribadi maupun
kelompok yang menyadari adanya perbedaan-perbedaan misalnya
dalam ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-
pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut
dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu
pertentangan atau pertikaian (conflict)
Ad.4. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.
Apabila kekuatan pihak-pihak yang bertentangan seimbang, maka
mungkin timbul akomodasi. Ketidakseimbangan antara kekuatan-
kekuatan fihak-fihak yang mengalami bentrokan, akan
menyebabkan dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lawannya,
74
kedudukan pihak yang didominasi tadi adalah sebagai pihak yang
takluk terhadap kekuasaan lawannya secara terpaksa.
75
BAB VII
SOSIOLOGI KESEHATAN
Sebagai salah satu ilmu sosial, sosiologi dikelompokkan
sebagai ilmu baru. Hal ini terkait dengan kelahiran ilmu sosiologi
dimulai semenjak adanya usaha pemisahan sosiologi dari filsafat.
Dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya sosiologi mempunyai runag
lingkup sangat luas. Seorang dapat melakukan kajian terhadap
fenomena sosial apapun sepanjang mampu menunjukkan kemampuan
riset ilmiah sesuai dengan pengembangan sosiologi. Di sisi lain
seorang sosiolog dapat mengarahkan pisau analisisnya terhadap
program kesehatan yang diluncurkan pemerintah, perilaku masyarakat
dalam menumbuhkembangkan budaya sehat, sampai pada maslah
konplik sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ini membuktikan
bahwa ruanglingkup sosiologi sangatlah luas.
Penyebaran sosiologi sebagai ilmu baru karena dihitung
semenjak masa pemisahan sosiologi dari filsafat merupakan sesuatu
yang kurang tepat karena ilmu ini dapat dikaji dari sumber yang lebih
awal. Misalnya pemikiran Ibnu Khaldum (1332-1406) yang pada
masa itu menyebut sebagai “ilmu perkotaan” atau “ilmu peradaban”
(ilmu murni) sehingga beberapa kalangan menyebut Ibnu Khaldum
sebagai “bapak sosiologi”. Namun demikian bagi masyarakat barat,
bapak sosiologi itu lebih banyak dirujuk pada pemikiran “August
Comte” (1798-1857) yang dianggap sebagai orang pertama yang
menyebut ilmu tentang masyarakat disebut istilah sosiologi.
Sebagain masyarakat menyatakan bahwa makna sosiologi itu
diambil dari konsep awalnya semata. Misalnya sosiologi dipandang
sebagai pecahan dari kata socius dan logos yang masing-masing
mengandung makna “masyarakat” dan “ilmu”. Oleh karena itu
sosiologi dimaknai sebagai ilmu masyarakat. Namun, menurut Bieren
de Hans pengertian ini memang masih terlampau umum dan bersifat
abstrak sebab ilmu sosiol yang mempelajari masalah masyarakat itu
bukan hanya sosiologi. Misalnya antropologi dan psikologipun
disebut sebagai ilmu sosial yang mempelajari masyarakat.
Sosiologi dibagi dalam beberapa bidang seperti perilaku
kolektif; sosiologi komparatif, kejahatan dan kenakalan; sosiologi
budaya, demografi, perilaku yang menyimpang, organisasi formal dan
76
kompleks, ekologi manusia, sosiologi industri, hukum dan msyarakat,
perkawinan dan keluarga, sosiologi matematis; sosiologi militer;
sosiologi perkotaan; sosiologi pedesaan; sosiologi kelompok kecil;
sosiologi pendidikan dan lain-lain sebagainya.
Topik-topik itu bukan bidang khusus kajian ilmu sosiologi.
Artinya bisa jadi bidang kajian tersebut ditelaah pula oleh disiplin
ilmu lain. Namun demikian, kajian tersebut dapat dikatakan sebagai
sosiologi manakah si penelaah tersebut mampu menggunakan metode
dan teknik riset sosiologi.
Seiring dengan hal ini maka yang dimaksud dengan sosiologi
kedokteran adalah disiplin intelektual mengenai pengembangan
pengetahuan yang sistematis dan terandalkan hugungan sosial
manusia dalam kaitannya dengan masalah kesehatan dan tentang
produk dari hubungan tersebut. Oleh karena itu pula, sosiologi
kedokteran dapat dikatakan sebagai sosiologi terapan dari ilmu
sosiologi itu sendiri, atau menurut istilah Solita Sarwono (2004)
sosiologi kedokteran sebagai sub disiplin (bidang keahlian khusus)
dari bidang ilmu sosiologi.
Sosiologi kedokteran (medical sosiologi) merupakan cabang
sosiologi yang menfokuskan pada pelestarian ilmu kedokteran dalam
masyarakat modern. Subjek ini berkembang begitu pesat sejak tahun
1950-an hingga sekarang menjadi salah satu bidang spesialisasi
terbesar dalam sosiologi. Perkembangan ini tidak bisa dipungkiri, hal
ini diakibatkan oleh adanya kesadaran bahwa banyak isu yang
terkandung dalam perawatan kesehatan modern yang pada dasarnya
merupakan masalah sosial. Namun ini juga mencerminkan adanya
peningkatan minat terhadap pengobatan itu sendiri dalam aspek-aspek
sosial dari kondisi sakit (illnes), terutama berkaitan dengan psikiatri,
pediatrik, praktek umum (atau pertolongan keluarga) dan pengobatan
komunitas.
Sosiologi kedokteran mencakup studi tentang faktor-faktor
sosial dalam etiologi (penyebab), prevalensi (angka kejadian), dam
interpretasi (penafsiran) dari penyakit tentang profesi kedokteranitu
sendiri serta hubungan dokter dengan masyarakat pada umumnya.
Sementara sosiologi kesehatan, yaitu ; Selain topik-topik
dalam sosiologi kedokteran, sosiologi kesehatan membahas pula peri
laku kesehatan, pengaruh normal sosial terhadap perilaku kesehatan,
77
serta interaksi antar petugas kesehatan (dokter dengan petugas
kesehatan lainnya) dan antara petugas kesehatan dengan masyarakat.
Bila tinjauan ini dikembangkan lebih lanjut, maka bagi
seorang mahasiswa keperawatan, mereka dituntut untuk memahami
sosiologi keperawatan yang merupakan sudisiplin sosiologi
kesehatan. Demikian pula bagi mereka yang bercita-cita untuk
berprofesi sebagai tenaga apoteker, bidan, tenaga kesehatan
masyarakat, atau tenaga pendidik kesehatan masyarakat.
Untuk lebih memudahkan pemahaman ini, dapat dirumuskan
kesimpulan analisi sebagai beriku:
a. Sosiologi kesehatan merupakan subdisiplin ilmu dari bidang
sosiologi. Disiplin ilmu ini merupakan ilmu terapan (applied
science) dari kajian sosiologi dalam konteks kesehatan.
b. Prinsip dasar disiplin sosiologi kesehatan adalah penerapan
konsep dan metode disiplin sisiologi dalam mendeskripsikan,
menganalisis dan memecahkan masalah kesehatan.
c. Ruang lingkup kajian sosiologi terapan tergantung pada ruang
lingkup objek kajian itu sendiri. Hemat kata, sosiologi kedokteran
adalah ilmu sosiologi dalam mengkaji hal-hal yang terkait dengan
ilmu kedoktertan, sosiologi keperawatan adalah ilmu yang
mengkaji masalah layanan keperawatan dan begitu pula bidang
kajian kesehatan lainnya.
Teori implisit dan eksplisit
Bagi Doyle Paul Johnson dalam teori sosiologi ada dua
kemungkinan yang dapat terjadi yaitu berkembangnya teori implisit
dan teori eksplisit. Sebagaimana sering dilihat, bahwa banyak orang
tidak sadar akan asumsi-asumsi teoritis atau struktur pemikirannya
dalam melakukan interaksi sosial. Misalnya seorang ibu akan
merawat bayinya dengan cara dan perlakuan yang berbeda seperti
ketika dia merawat ibu mertua atau orang tuanya sendiri. Bgitu pula
halnya dengan gadis remaja, cara mengobati luka adik bungsunya
tentu akan berbeda dibandingkan dengan cara mengobati luka
tetangganya. Perilaku seperti ini, dalam pandangan Johnson adalah
sebuah tindakan sosial yang dilandasi oleh asumsi bahwa setiap orang
memiliki keunikan dan membutuhkan perlakuan yang berbeda.
Kesadaran seperti ini merupakan kesadaran teori sosiologis,
78
kendatipun untuk kategori teori implisit.
Teori-teori implisit mewarnai sikap dan tindakan masyarakat
dalam melakukan interaksi dengan sesama anggota masyarakat yang
lainnya. Ada orang yang sinis atau skeptis terhadap orang yang baru
bertemu atau berdialog dengan anggota masyarakat dari suku bangsa
yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa teori implisit kerap
muncul dalam benak dan jiwa seseorang.
Dengan hadirnya sosiologi, para ilmuwan merupakan sebuah
usaha untuk mengumpulkan apa yang diketahui setiap orang dan
menuangkannya dalam kata-kata yang tidak dapat dipahami siapapun.
Dengan kata lain ilmu sosiologi ini adalah upaya untuk men-
verbalkan (meng-kata-kan) apa yang dilakukan manusia dalam
berinteraksi dengan sesama manusianya. Sehingga pada akhirnya dari
teori implisit dapat berubah menjadi teori eksplisit.
Dengan mengeksplesitkan teori berinteraksi ini, diharapkan
dapat melahirkan kesadaran hidup yang lebih baik dan dapat
memaknai hidup dengan lebih baik. Dengan belajar sosiologi ini
diharapkan orang akan lebih mengerti apa dan mengapa orang
melakukan tindakan tertentu dibandingkan tindakan lain.
Peran Sosiologi dalam Praktik Kesehatan
Berdasarkan hal tersebut, secara teori dapat dikemukakan
beberapa peran umum sosiologi/sosiolog dalam pengembangan ilmu
maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
a. Sosiologi sebagai ahli riset.
Sebagai seorng ilmuwan, seorang sosiolog memiliki tanggung
jawab untuk melakukan penelitian ilmiah, sosialisasi keilmuwan
dan juga pembinaan pola pikir terhadap masyarakat.
Dalam peran sebagai ahli riset ini, sosiolog juga berkewajiban
untuk meluruskan berbagai pendapat masyarakat awam atau
kalangan tertentu yang lebih disebabkan karena salah informasi
atau takhayul yang dapat menghancurkan pola pikir manusia.
Misalnya mengenai pengaruh gerhana bulan terhadap kesehatan
anak yang dikandung.
Hal yang tidak kalah penting lagi, sosiolog pun dapat
menunjukkan peran untuk memberikan ramalan-ramalan
sosiologisnya terhadap data statistik atau tren perubahan sosial
79
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan publik.
b. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan
Sosiologi memiliki kemampuan untuk menganalisis faktor sosial,
dinamika sosial dan kecenderungan proses, serta perubahan
sosial. Dalam skala jangka panjang, sosiologi memiliki
kemampuan untuk meramalkan pengaruh dari sebuah kebijakan
terhadap kehidupan sosial.
c. Sosiolog sebagai teknisi.
Seorang sosiolog dapat terlibat dalam perencanaan dan
pelaksanaan progaram kegiatan masyarakat untuk memberi saran-
saran dalam masalah mora, hubungan masyarakat, hubungan
antar karyawan, hubungan antar kelompok dalam suatu
organisasi, dan penyelesaian berbagai masalah mengenai
hubungan antar manusia. Para sosiolog sering mengambil
keahlian khusus dalam bidang psikologi sosial, sosiologi industri,
sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, atau sosiologi organisasi
yang majemuk.
d. Membantu dalam meningkatkan peran sebagai guru/pendidik
kesehatan.
Dengan belajar sosiologi. Seorang tenaga kesehatan dapat
memahami sifat, karakter, atau norma masyarakat yang berlaku,
sehingga pada akhirnya program promosi kesehatan atau agenda
pembangunan kesehatan pada suatu masyarakat akan dapat
berjalan dengan efektif. Kealpaan kita dalam memahami karakter
atau nilai dan norma masyarakat, dapat menyebabkan resistensi
dari masyarakat terhadap program pembangunan kesehatan. Oleh
karena itu, sosiologi dapat memberikan konstribusi wawasan dan
pemahaman terhadap tenaga kesehatan atau para pengambil
kebijakan dalam bidang kesehatan.
80
BAB VIII
KONSEP DASAR SOSIOLOGIS:
NILAI DAN NORMA KESEHATAN
Dalam pandangan antropologi, sesuatu memiliki nilai.
Kendati sudut pandang nilai merupakan pengalaman subjektif
(pribadi), namun bila pengalaman subjektif ini disosialisasikan maka
akan menjadi nilai kolektif (diakui oleh masyarakat) sehingga pada
akhirnya akan menjadi budaya.
Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma
yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka yang bertujuan agar
terjadi keseimbangan antar masing-masing kepentingan di dalam
masyarakat. Norma ini merupakan aturan atau kaidah yang dipakai
sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.
Pengertian Nilai dan Norma
Terdapat banyak pengertian mengenai nilai. Bahkan antara
satu pengertian dengan pengertian lainnya kadangkala memiliki
penekanan yang berbeda. Tergantung dari sudut pandang pemikiran
itu sendiri.
Salah satu pemikiran yang menunjukkan perbedaan
mengenai pengertian nilai dikemukan Rokeach yang membedakan
nilai sebagai:
1. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang (a person has a value)
2. Sebagai sesuatu yang berkaitan dengan objek (an object has a
value).
Pandangan pertama: yang menyatakan bahwa manusia memiliki
nilai berpendapat bahwa nilai adalah sesuatu
yang ada pada manusia, sesuatu yang ia
berikan atau dijadikan ukuran baku bagi
persepsinya mengenai dunia luar. Mengenai
hal ini, Robin Williams menyatakan bahwa
nilai adalah kriteria atau standar yang dibuat
untuk melakukan penilaian.
Yudistira K. Garna mengatakan bahwa nilai
bukanlah suatu objek. Oleh karena itu nilai
tidak memiliki sifat yang objektif. Nilai
81
merupakan suatu konsep yaitu hasil dari
pembentukan mental yang dirumuskan dari
tingkah laku manusia sehingga menjadi
anggapan yang hakiki, baik dan perlu
dihargai sebagaimana mestinya. Secara
ekstrim nilah adalah sesuatu yang dimiliki
hanya oleh manusia dan manusialah yang
memberikan nilai atau menilai dunia luarnya,
yang pada dasarnya tidak bernilai.
Pandangan kedua : menganggap nilai sebagai sesuatu yang ada
pada objek. Pandangan ini lebih menekankan
nilai sebagai milik (property of) oleh objek.
Nilai tersebut dapat diletakkan dalam suatu
dimensi yang merupakan komitmen dari
positf ke negatif. Pandangan ini dikemukakan
B.F.Skinner yang menyangkal bahwa
manusia memiliki nilai-nilai.
Kategorisasi Nilai
Dalam kajian sosio-antropologi, banyak sumber yang bisa
digunakan sebagai sumber nilai. Diatara sejumlah sumber nilai tersbut
yakni orang tua, guru, teman sebaya, dan dirinya sendiri. Dalam
proses perkembangan dan pengembangannya, depengaruhi oleh
lingkungan sosial dan lingkungan alam.
Menurut Sutan Takdir Alisyahbana (1982) ketika
menjelaskan kebudayaan asli Indonesia menyebutkan ada enam nilai
budaya dan pelayanan kesehatan yaitu :
1. Ekonomi (nilai budaya)
Pelayanan kesehatan : Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
dibutuhkan biaya, alat produksi atau imbalan jasa. Kebutuhan
terhadap layanan medis atau obat senantiasa menyertakan
kebutuhan akan biaya (ekonomi). Pada konteks ini layanan
kesehatan mengandung nilai ekonomi.
2. Estetis (nilai budaya)
Pelayanan kesehatan : lingkungan yang bersih serta ruangan yang
nyaman dan harum memberikan dukungan emosional terhadap
proses penyembuhan kesehatan.
82
3. Solidaritas (nilai budaya)
Pelayanan kesehatan : Dalam menjalankan tugas profesinya,
seorang perawat dapat bekerja sama dengan pasien, keluarga
pasien, dokter, atau pihak lain yang berkepentingan. Sebagai
manusia pasien sesungguhnya memerlukan teman untuk berkeluh
kesah.
4. Kuasa (nilai budaya)
Pelayan kesehatan :Seorang dokter memiliki peran dan fungsi
yang berbeda, demikian pula perawat dan bidan. Terdapatnya
struktur pengelola rumah sakit dari direktur, dokter, perawat,
bidan, apoteker dan sebagainya.
5. Teori (nilai budaya)
Pelayanan kesehatan: Dalam melaksanakan tugasnya seorang
dokter, perawat dan bidan dituntut untuk memiliki pengetahuan
tentang kesehatan. Sebelum melaksanakan praktik, setiap lulusan
pendidikan kesehatan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan
profesi.
6. Agama (nilai budaya)
Pelayanan kesehatan: Bagi masyarakat yang beragama, praktik
pelayanan merupakan bagian dari pelayanan kepada umat.
Selaras dengan kode etik, ilmu penegtahuan dan keterampilan
profesi yang dimilikinya merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa. Oleh karena itu pelayanan kesehatan pun perlu dianggap
sebagai bagian dari ibadah.
Fungsi Nilai Budaya
Rokeach melihat ada tiga fungsi nilai yaitu :
1. Ukuran baku untuk mengarahkan perilaku
2. Roncana global dalam menyelesaikan masalah
3. Motivasi
George England melihat ada dua fungsi nilai yaitu :
1. Penyalur perilaku (behavior channeling)
2. Penyaring persepsi (perceptual screnning)
Norma Sosial Masyarakat Indonesia
Nilai atau value lebih tinggi daripada norma atau moral.Nilai
merupakan keyakinan (belief) yang sudah merupakan milik diri dan
83
akan menjadi barometer actions and will,sedangkan norma baru
merupakan keharusan yang lebih bersifat operasional karena adanya
sanksi.Sementara moral menurut Piaget lebih bersifat tuntutan dari
luar (masyarakat/kehidupan) karena kiprah umum dan/atau praktika
nyata.Namu demikian keseluruhannya memuat hal yang
dianggap/dinyatakan baik atau berharga atau positif.Normal sosial
(social norma) adalah suatu ukuran atau pandangan tentang suatu atau
sejumlah tingkah laku yang diterima dan disepakati secara umum oleh
warga suatu masyarakat.Sumber-sumber norma sosial dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Ajaran Agama.Umumnya mengajarkan kepada pemeluknya
untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang berbuat yang
tidak baik.Perbuatan baik atau tidak baik yang berkaitan dengan
tata kehidupan.Agama memiliki aturan mengenai makanan,
perilaku, dan cara pengobatan yang dibenarkan secara hukum
agama.
Sumber agama merupakan dasar dalam memberikan pelayanan
kepada pasien. Agama dianggap mampu memberikan arahan dan
menjadi sumber moralitas untuk tindakan yang akan
dilaksanakan.
b. Ajaran moral. Moral tumbuh dari hati nurani hati manusia untuk
menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia sehingga berbeda
dengan mahluk lain. Sekedar contoh berdasarkan undang-undang
kesehatan, tidak ada pasal atau ayat yang menjelaskan
berkewajiban bagi seorang dokter untuk menolong orang yang
terkena musibah tabrakan. Artinya jika dirinya tidak menolong
korban tabrakan tersebut tidak akan dikenai sanksi hukum. Tetapi
secara moral dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat
akan mendorong dirinya untuk bertindak cepat dalam membantu
orang sakit,
c. Ajaran adat istiadat. Setiap kelompok masyarakat memiliki adat
istiadat dan kebiasaan yang menjadi nilai-nilai yang dianggap
baik atau buruk dan berlaku bagi kelompok tersebut. Setiap
tenaga medis dituntut untuk menjunjung tinggi nilai dan norma
yang bersumber dari adat atau budaya masyarakat.
d. Aspek hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang
berlaku dan dibuat oleh yang berweng wajib dipatuhi oleh semua
84
warga. Namun hukum yang perlu dipahami itu, baik norma
hukum secara umum, maupun norma hukum dalam bidang
kesehatan pada khususnya.
e. Kode etik profesi. Selain keempat sumber diatas, ada satu sumber
lagi yang dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan nilai
dan norma profesi kesehatan yaitu kode etik profesi. Jika keempat
sumber norma sebelumnya itu lebih cenderung berasal dari luar
orang yang melaksanakan layanan kesehatan, sumber yang
terakhir ini bersumber dari posisi dan profesi dirinya sendiri.
Oleh karena itu kendatipun ada tuntutan untuk menghormati nilai
dan norma masyarakat yang berlaku, pelaku layanan kesehatan
tidak boleh melanggar kode etik profesinya sendiri.
Urgensi Memahami Nilai dan Norma dalam Prektik Pelayanan
Kesehatan.
Indonesia adalah masyarakat beragam (plural society) atau
Bhinneka Tunggal Ika yaqng mengandung makna perbedaan dan
persatuan. Keanekaragaman ini menurut Fischer dapat dilihat dalam
tiga hal utama yakni geografik, induk bangsa dan persentuhan.
Persentuhan budaya terjadi antar beberapa beberapa kelompok yaitu
asli daerah, kaum penjajah, para pedagang dan kaum imigram.
Dalam bidang pelayanan kesehatan. Jika ditelaah pelayanan
kesehatan di Indonesia menunjukkan gejala adanya perpaduan antara
moder dan tradisional. Berdasarkan pertimbangan ini kendati
demikian, seorang tenaga profesi kesehatan harus tetap menjunjung
tinggi kode etik profesi, namun dalam proses layanan kesehatan di
masyarakat perlu untuk memperhatikan keanekaragaman budaya
dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas layanan kesehatan.
Etika keperawatan adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang
diyakini oleh profesi keperawatan dalam melaksanakan tugasnya yang
berhubungan dengan pasien, dengan masyarakat, hubungan perawat
dengan teman sejawat maupun dengan organisasi profesi dan juga
dalam pengaturan praktik keperawatan itu sendiri (Berger dan
Bagi profesi keperawatan, etika keperawatan merupakan suatu
acuan dalam melaksanakan praktik keperawatan. Etika keperawatan
berguna untuk pengawasan terhadap kompetensi profesional,
85
tanggungjawab, tanggung gugat dan untuk pebgawasan umum dari
nilai positif profesi keperawatan (Berger dan Williams, 1999).
Prinsip-prinsip etika ini oleh profesi keperawatan secara formal
dituangkan dalam suatu kode etik yang merupakan komitmen profesi
keperawatan akan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan
oleh masyarakat.
Pertama, seorang perawat tidak membeda-bedakan pasien. Prinsip
tersebut merupakan prinsip perawatan untuk memberikan
pelayanan kesehatan tanpa melakukan diskriminasi.
Kedua. Mendapatkan persetujuan melakukan tindakan.
Ketiga, mengakui otonomi pasien.
Keempat, mendahulukan tindakan sesuai prioritas masalah.
Prinsip melakukan tindakan sesuai dengan prioritas masalah
ini juga menekankan untuk bersikap adil terhadap pasien
dengan tidak dengan tidak membedakan pasien berdasarkan
status yang menyertainya, tetapi berdasarkan prioritas
kebutuhan dari pasien. Dengan melakukan prioritas tindakan
dengan tepat maka dapat pula terdeteksi adanya suatu
masalah lebih dini sehingga dapat mencegah terjadinya
kondisi yang lebih buruk atau mencegah terjadinya hal yang
membahayakan.
Kelima, melakukan tindakan untuk kebaikan, menghindari hal yang
membahayakan.
86
BAB IX
MODEL-MODEL PERUBAHAN PERILAKU
Layanan kesehatan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan
kualitas kesehatan individu. Lebih jauh dari itu, layanan kesehatan
prima lebih menekankan pada usaha untuk melakukan tindakan
layanan kesehatan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap
perilaku individu, sehingga perilaku individu, sehingga perilaku
individu tersebut mampu menunjukkan sikap dan budaya hidup sehat.
Menurut sebagian psikolog, perilaku manusia berasal dari
dorongan yang ada dalam diri manusia dan dorongan itu merupakan
salah satu usaha u ntuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri
manusia. Dengan adanya dorongan tersebut, menimbulkan seseorang
melakukan sebuah tindakan atau perilaku khusus yang mengarah pada
tujuan.
Sementara itu. Para sosiolog melihatnya bahwa perilaku
manusia tidak bisa dipisahkan dari konteks atau setting sosialnya.
Untuk sekedar contoh, dorongan dalam diri manusia untuk makan
bisa disebabkan karena adanya rasa lapar. Pada konteks aktualnya,
usaha manusia untuk makan ini menunjukkan cara dan pola yang
berbeda, sesuai dengan situasi sosialnya masing-masing. Pada konteks
itulah maka dorongan dalam diri, dipengaruhi pula oleh setting sosial
yang berkembang di seputar individu tersebut. Dengan demikian,
perilaku manusia itu perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas.
Dalam kaitannya dengan perilaku kesehatan atau lebih
spesifik lagi yaitu derajat kesehatan, perilaku manusia merupakan
salah faktor utama dalam terwujudnya derajat kesehatan individu
secara prima. Henrik L.Blum memetakan bahwa derajat kesehatan
manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah
perilaku manusia itu sendiri.
Dari peta pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa Blum
meyakini bahwa perilaku individu memiliki pengaruh yang lebih
besar dibandingkan dengan layanan kesehatan sementara faktor
genetis hanya berpengaruh sebesar 5%. Teori dari Blum ini seolah
ingin menegakkan bahwa layanan kesehatan hanya faktor kecil dalam
meningkatkan derajat kesehatan. Sedangkan faktor perilaku dan
87
lingkungan merupakan faktor yang sangat besar dalam mendukung
derajat kesehatan manusia.
Pada konteks inilah, pendidikan kesehatan atau promosi
kesehatan memiliki peranan penting dalam mendukung angka
partisipasi kesehatan masyarakat atau dalam mendukung akselerasi
kualitas kesehatan masyarakat. Secara umum, tujuan dari pendidikan
kesehatan ini adalah perubahan perilaku individu dan budaya
masyarakat sehingga mampu menunjukkan perilaku dan budaya yang
sehat.
Derajat Kesehatan Menurut Henrik L.Blum
(sumber :Soekidjo Notoatmodjo 203b.hlm 146)
Berdasarkan landasan pemikiran dari teori seperti itu, maka
perilaku manusia akan lebih luas lagi, model perilaku manusia perlu
mendapat perhatian saksama, baik dari kalangan psikologi kesehatan,
sosiologi kesehatan atau tenaga kesehatan itu sendiri. Soekidjo
Notoatmodjo memperhatikan bentuk respons terhadap stimulus,
membedakan perilaku manusia menjadi dua bentuk, yaitu
a. Perilaku tertutup (covert behavior). Hal ini ditunjukkan dalam
bentuk perhatian, persepsi, pengetahuan kesadaran dan reaksi
lainnya yang tidak tampak
b. Perilaku terbuka (oven behavior) yaitu dalam bentuk tindakan
nyata misalnya meminum obat ketika dirinya merasa sakit.
Berdasarkan pandangan ini, maka yang dimaksud perilaku
kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo mendasarkan pada
teori Skinner, mengatakan bahwa perilaku kesehatan yaitu suatu
respons seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang
Lingkungan 45%
Perilaku 30%
Ke Tu Ru Nan 5%
Pela Ya Nan Kes Hatan 20%
DERAJAT KESEHATAN Morbiditas dan Mortalitas
88
berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan,
makanan dan minuman, serta lingkungan. Dari defenisi tersebut,
kemudian dirumuskan bahwa perilaku kesehatan itu terkait
dengan :
1. Perilaku pencegahan, penyembuhan penyakit serta pemulihan
dari penyakit
2. Perilaku peningkatan kesehatan
3. Perilaku gizi (makanan dan minuman)
Model Pengelolaan Rasa Sakit
Setiap orang selalu ingin sehat dan tidak mau sakit,
kendatipun tak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan rasa
sakit. Sakit memang menjadi bagian hidup kita. Seiring hal ini
seorang pasien atau pesakit sesungguhnya yang paling banyak
dikeluhkan itu adalah rasa sakit yang ada dalam dirinya.
Sehubungan dengan rasa sakit Lehndorff memberikan
pengalamannya selama memberikan layanan penanganan rasa sakit.
Bagi dirinya rasa sakit bisa dikelola, baik untuk sekedar pengendalian
rasa sakit maupun untuk mencapai penyembuhan diri dan penyakit
yang sedang dideritanya. Dalam pengalamannya tersebut, dapat
disimpulkan bahwa faktor utama yang menunjang kemajuan derajat
kesehatan pasien adalah keinginan dan kehendak yang besar untuk
mengalami kemajuan.
Potensi fikiran pun perlu diperhatikan guna meraih efek
manajemen sakit yang lebih baik. Pikiran memiliki kekuasaan yang
besar. Setiap orang memiliki potensi kemampuan untuk mengelola
pikiran secara baik sehingga dapat mengelola rasa sakit. Oleh karena
itu seorang pasien perlu diprovokasi sehingga memiliki sikap optimis.
Dalam pandangan Lehndorff Tracy (2005) sikap optimis itudapat
diwujudkan dengan :Yaitu memiliki rasa ingin menjadi lebih baik
a. Memiliki harapan untuk menjadi lebih baik
b. Mau berusaha untuk menjadi lebih baik dan
c. Mereka belajar metode-metode cepat untuk memotivasinya.
Dari teori yang dikembangkan Lehndorff dan Tracy
sesungguhnya dapat dipetakan ulang mengenai model perilaku sakit
dilihat dari sudut kemampuan mengelola rasa sakit.
89
Peta Konsep Perilaku Sakit Lehndorff dan Tracy
Kemauan (+)
Ke ke
Mam mam
Pu (-) pu (+)
An an
Kempuan (-)
Sumber : modifikasi dari Lehndorff dan Tracy, 205,hlm. xii
Kuadran I merupakan kuadran yang ideal. Karena seorang
pasien memiliki kemampuan dan sekaligus kemampuan untuk
mengelola rasa sakit. Tenaga medis mungkin tidak memiliki peran
yang besar, bahkan dalam potensi perilaku sakit yang akan muncul,
yaitu adanya keinginan pasien untuk mengembangkan model self-
healing (pemyembuhan diri oleh diri sendir).
Kuadran II sudah memiliki keinginan untuk mengelola rasa
sakitnya namun dia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan
untuk melakukan pengelolaan rasa sakit.
Kuadran III seorang tenaga medis dituntut untuk mampu
memprovokasi pasien yang kehilangan semangat hidup, sehingga
pasrah terhadap kondisi yang ada, padahal dirinya memiliki
kemampuan untuk meraih kesembuhan atau minimalnya mendapat
kan kondisi rasa sakit yang kecil.
Kuadran IV yaitu menjadi pasien yang pesimis. Dari dalam
dirinya sudah tidak ada rasa ingin untuk mendapatkan kualitas
kesehatan yang lebih baik dan kemudian dipengaruhi pula oleh
adanya ketidakmampuan untuk mengelola rasa sakit.
Model Suchman
Yang penting dalam model Suchman adalah menyangkut
pada sosial dari perilaku sakit yang tampak pada cara orang mencari,
menemukan dan menemukan perawatan medis. Pendekatan yang
digunakan berkisar pada empat unsur yang merupakan faktor utama
90
dalam perilaku sakit, yaitu :
1. Perilaku itu sendiri
2. Sekuensinya
3. Tempat atau ruang lingkup
4. Variasi perilaku selama tahap-tahap perawatan medis.
Dari keempat unsur tersebut dapat dikembangkan 5 konsep
dasar yang berguna dalam menganalisis perilaku sakit, yaitu
1. Mencari pertolongan medis dari berbagai sumber tau pemberi
layanan
2. Fragmentasi pelayanan medis di saat orang menerima pelayanan
dari berbagai unit tetapi pada lokasi yang sama
3. Menangguhkan atau menangguhkan upaya mencari pertolongan
meskipun gejala sudah dirasakan.
4. Melakukan pengobatan sendiri (self-medication)
5. Membatalkan atau menghentikan pengobatan (discontinuity)
Model Mechanic
Charles Abraham dan Eamon Shanley Mechanic (1978) telah
mengembangkan suatu model perilaku pencarian bantuan yang
mempertimbangkan konteks budaya dari penyakit dan model ini
memiliki keuntungan dari penggabungan sejumlah komponen HBM
(health believe model). Landasan pemikiran model Mechanic yaitu
mengembangkan suatu model mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi perbedaan cara orang melihat, menilai serta bertindak
terhadap suatu gejala penyakit. Teori ini menekankan pada 2 faktor :
a. Persepsi dan defenisi oleh individu pada suatu situasi
b. Kemampuan individu melawan keadaan yang berat.
Faktor-faktor tersebut digunakan untuk menjelaskan
mengapa seseorang dengan kondisi tertentu dapat mengatasi sebuah
penyakit, sedangkan pada orang lain yang memiliki derajat sakit lebih
ringan mengalami keseulitan dalam mengatasi penyakitnya.
Model Anderson
Anderson (1974) termasuk salah seorang yang
mengembangkan model sistem kesehatan (health system model) yang
berupa model kepercayaan kesehatan. Kerangka asli model ini yaitu
menggambarkan suatu sekuensi determinan individu terhadap
91
pemamfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga dan dinyatakan
bahwa hal ini bergantung pada :
a. Predisposisi keluarga untuk menggunakan jasa pelayanan
kesehatan misalnya saja variabel demografi (umur, jumlah, status
perkawinan), variabel struktur sosial (pendidikan, pekerjaan suatu
bangsa), kepercayaan terhadap medis.
b. Kemampuan untuk melaksanakannya, yang terdiri atas persepsi
terhadap penyakit serta evaluasi klinis terhadap klinis.
c. Kebutuhan terhadap jasa pelayanan. Faktor predisposisi dan
faktor yang memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat
terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai
kebutuhan.
92
BAB X
LAYANAN KESEHATAN DAN TANTANGAN
PERUBAHAN SOSIAL
Kehidupan manusia senantiasa menunjukkan adanya
perubahan sosial. Oleh karena itu tidak mengherankan bila para
filosuf mengatakan bahwa tidak ada yang tetap dalam kehidupan ini,
kecuali perubahan. Perubahan adalah kenyataan sosial yang masih
tetap ada dari dulu sampai sekarang. Hidup dan kehidupan manusia,
senantiasa berada dalam “alur” dan atau “aliran” perubahan sosial.
Seiring dengan hal tersebut, August Comte mengatakan
bahwa realitas sosial ini dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek
statik dan dinamis. Khusus yang berkaitan dengan aspek dinamis,
masyarakat ini merupakan fokus perhatian kalangan sosiolog dalam
memahami arah dan “perkembangan” perubahan sosial masyarakat.
Yusuf Alam Ramadhan (2006) menyebutkan ada 6 (enam)
lingkungan eksternal yang berubah, yang menuntut perubahan mind-
set tenaga kesehatan yaitu;
1. Globalisasi dan tehnologi informasi
2. Keadaan hiperkompotitif, terutama di perkotaan
3. Enam belas juta warga Indonesia berstandar sama dengan kelas
atas penduduk Singapora
4. Pemain asing yang efisien, reputasi tinggi, berpengalaman, dan
dipersepsi excellent
5. Konsumen makin cerdas dan tercerahkan, serta
6. Tuntutan dokter lebih bisa diakses, terutama olrh menengah
bawah.
Dengan adanya perubahan-perubahan dari sisi eksternal
lembaga atau layanan kesehatan ini menyebabkan respon atau reaksi
masyarakat terhadap pelayanan kesehatanpun turut berubah. Tidak
mengherankan efek dari reformasi politik ini menyebabkan
masyarakat Indonesia memiliki keberanian untuk mengemukakan
apresiasi atau penilaiannya terhadap kualitas layanan kesehatan.
Pengertian Dasar Perubahan Sosial
Oleh Selo Soemardjan mengatakan perubahan sosial adalah
perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu
93
masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk
didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantaranya
kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat bersumber
pada sebab-sebab yang berasal dari dalam dan dari luar masyarakat
antara lain :
1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di
sekitar manusia
2. Peperangan
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu ;
a. Kontak dengan kebudayaan lain
b. Sistem pendidikan formal yang maju
c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-
keinginan untuk maju
d. Toleransi terhadap perubahan-perubahan menyimpang
(deviation) yang bukan merupakan delik hukum
e. Sistem lapisan terbuka masyarakat yang memungkinkan
adanya gerak sosial vertikal yang luas atau memberi
kesempatan para individu untuk maju atas dasar keampuan
sendiri.
f. Penduduk yang heterogen
g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu
h. Berorientasi ke masa depan
i. Nilai budaya manusia harus senantiasa berihtiar untuk
memperbaiki kehidupannya.
Beberapa Tinjauan Tentang Perubahan Sosial
a. Teori Siklus
Terdapat banyak sosiolog yang berusaha keras untuk menjelaskan
irama perubahan dengan model teori siklus. Di antara sosiolog
tersebut yaitu Ibnu Khaldum, Oswald Spengler, Arnold Toynbee,
dan Pitirin Sorokin.
Ibn Khaldum (1332-1406) seorang sosiolog Arab yang
melukiskan bahwa peradaban manusia berkembang dalam lima
tahap, yaitu :
1. Tahap modern yang kemudian menghancurkan seluruh
94
penentangnya dan mendirikan kerajaan baru
2. Tahap konsolodasi kekuatan dengan tujuan memperkokoh
pengendalian atas kawasan yang baru dikuasai.
3. Tahap kesenangan dan kesentosaan, yang ditandai dengan
kemewahan materi dan kebudayaan lainnya.
4. Tahap kedamaian berlanjut sehingga menjadi sebuah taradisi
baru
5. Tahap kehancuran yang dimulai dari hura-hura, pemborosan
dan kehilangan simpati. Dengan teori ini Lauer berpendapat
bahwa Ibn Khaldum adalah “genius Arab” perintis dan
peletak pengetahuan Sosiologi.
b. Teori Psikologi
Jika dilihat dari sudut Teori David McClelland, perubahan sosial
itu terjadi karena adanya pertumbuhan dan/atau perkembangan
motif berprestasi dari individu atau masyarakat tersebut.
McClelland menyebutkan bahwa need for achevement
merupakan daya dorong bagi seseorang untuk meraih prestasi
yang lebih baik dari hari ini.
Teori yang relevan dengan sudut pandang psikologi dapat dilihat
dalam pandanga Everette Hagen. Hagen menjelaskan bahwa
perubahan sosial akan terjadi bergantung pada pola reaksi atau
kualitas pengaruh dari hasil inovasi terhadap masyarakat itu
sendiri. Dalam konteks ini dikemukan ada lima hukum perubahan
sosial, yaitu:
Hukum penundukan, kelompok, penolakan nilai, rintangan sosial,
perlindungan kelompok, dan kepemimpinan yang tidak memihak.
c. Teori Materialisme Dialetika
Pada kota-kota besar di Indonesia masyarakat kelas
menengah atas sudah terbiasa melakukan kunjungan kesehatan ke
negara-negara tetangga hanya untuk melakukan general chek-up.
Baik kalangan selebriti maupun pejabat yang memiliki dana
cukup besar sudah terbiasa memeriksakan kesehatannya keluar
negeri. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti ;
1. Anggapan bahwa pelayanan dan teknologi kesehatan di
dalam negeri kurang memuaskan
2. Adanya perubahan ketahanan ekonomi dalam dirinya untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik walaupun
95
harus keluar negeri.
Seiring dengan hal ini, menurut teori Karl Marx struktur
ekonomi berpengaruh pada perilaku. Dalam teori ini, setiap
kelompok dikategorikan dalam satu kelas sosial dan kelas sosial
terbesar itu sendiri atas dua kelompok, yaitu proletariat
(kelompok orang papa atau tidak berpunya) dan borjuis
(kelompok orang berpunya). Setiap kelompok tersebut
menunjukkan perilaku yang berbeda sesuai dengan apa yang
dimilikinya.
d. Teori Fungsionalisme Struktural
Bagi kalangan fungsionalisme, setiap masyarakat
diposisikan sebagai satu kondisi yang relatif stabil. Kestabilan ini
terbentuk akibat adanya konsensus antar komponen sehingga
terbentuk masyarakat yang terpadu. Pada sisi lain proses
perubahan sosial merupakan suaru bentuk adaptasi manusia dan
masyarakat terdapat berbagai anomalia (penyimpangan) yang
terjadi di masyarakat. Dengan adanya proses adaptasi ini maka
akan terjadi keseimbangan ulang (aqualibrium) di masyarakat
dan pada akhirnya individu dan/atau masyarakat tersebut dapat
mempertahankan kualitas peradabannya sendiri.
e. Teori Modernisasi.
Kendatipun banyak defenisi mengenai istilah
modernisasi, namun ciri dasar dari modernisasi ini dapat dikenal
secara seksama yaitu adanya industri dan penggunaan akal
(rasionalisasi)sebagai landasan untuk melakukan tindakan sosial.
Masyarakat Indonesia masih mengenal adanya
pengobatan tradisional yaitu pengobatan yang menggunakan
pendekatan metafisik seperti memercayai dukun dan/atau
penyebab di luar masalah fisik. Dengan adanya perkembangan
ilmu pengetahuan dan industri serta teknologi, maka dalam
menyelesaikan masalah kesehatan digunakan cara-cara yang
modern seperti menggunakan teknologi medis yang lebih
modern.
Proses Perubahan Sosial
Perubahan sosial tidak terjadi begitu saja, ada beberapa
saluran yang dapat digunakan sebagai saluran perubahan sosial.
Namun demikian, untuk perkembangan dalam dunia kesehatan ini,
96
saluran perubahan kesehatan ini lebih banyak terjadi dan dilakukan
oleh :
a. Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan dan sekaligus sarana
pemberian layanan kesehatan.
b. Pendidikan, setiap calon tenaga kesehatan, baik perawat, dokter,
bidan, atau yang lainnya duperkenalkan dengan berbagai hal yang
terkait dengan perubahan sosial. Hal yang tidak bisa dilupakan
lagi yaitu media informasi baik media elektronik maupun media
cetak memiliki peran yang nyata dalam memberikan informasi
atau memengaruhi perubahan layanan kesehatan dan teknologi
kesehatan di masyarakat.
Dalam proses perubahan sosial ini, ada beberapa tahapan
perubahan sosial yang potensial terjadi di masyarakat antara lain
sebagai berikut,
a. Difusi.
Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari
individu kepada individu lain serta dari satu masyarakat ke
masyarakt lain. Unsur-unsur penyebaran budaya bersamaan
dengan migrasinya kelompok manusia dari satu daerah ke daerah
lain. Misalnya berkembangnya teknik pengobatan bekam, seiring
dengan penyebaran umat Islam dari Timur Tengah ke berbagai
penjuru dunia, perkembangan ilmu dan teknologi pengobatan
Ayurveda seiring dengan menyebarnya agama Hindu dan orang
India ke seluruh dunia, demikian pula teknologi pengobatan
akupuntur atau akupresur dari Cina.
Difusi antar masyarakat dipengaruhi oleh :
a. Kontak budaya
b. Kemampuan memodernisasikan
c. Pengakuan
d. Ada tidaknya pesaing
e. Peran masyarakat dalam menyebarkan unsur baru serta
f. Ada tidaknya unsur paksaan terhadap unsur baru.
Difusi bisa terjadi melalui :
a. Penetrasi atau perembesan nilai-nilai baru
b. Simbiosis mutualistik atau hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan.
97
b. Inovasi
Inovasi adalah proses pembaruan dari penggunaan
sumber-sumber alam, dan modal serta penataan kembali dari
tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk
suatu sistem produksi dari produk-produk baru.
Proses inovasi menurut Koentjaraningrat, berkaitan erat
dengan proses penemuan baru dalam bidang teknologi yang
biasanya merupakan tahap dari discovery dan invention.
Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik
dari individu atau kelompok. Jika discovery ini sudah dikenal
masyarakat maka disebut dengan istilah inovation.
c. Akulturasi.
Pada masa kini, masyarakat dengan sangat mudah
menemukan pelayanan kesehatan yang memadukan antara
teknologi modern dengan teknologi alternatif. Ada rumah sakit
umum yang mengadopsi teknik pengobatan akupuntur sebagai
bagian dari pelayanan kesehatanmodern. Contohnya klinik
alternatif Rumah Sakit panti Rapih yang hadir di Jakarta sejak
tahun 1993, pada mulanya hanya bertumpu pada pengobatan
akupuntur yang telah diakui di dunia kedokteran barat atau
konvensional.
Penomena itulah yang dapat disebut sebagai sebuah
perubahan sosial dari sudut akulturasi. Artinya, proses sosial
timbul apabila sekelompok manusia dihadapkan dengan unsur-
unsur suatu kebudayaan asing. Sehingga unsur-unsur asing itu
lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri
tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.
d. Asimilasi
Asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada
berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan
yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif sehingga
sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu
masing-masing berubah menjadi unsur kebudayaan campuran.
Urgensi Perubahan Mengenai Perubahan Sosial bagi Tenaga
Kesehatan
Setelah memahami pengertian perubahan sosial, perspektif
98
sosiologi mengenai perubahan sosial dan beberapa konsep dasar
perubahan sosial, sampailah pada pertanyaan, apa urgensinya
pemahaman tersebut bagi seorang tenaga kesehatan? Sebagaimana
telah dikemukakan sebelumnya, fungsi hadirnya tebaga kesehatan
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
kesehatan. Tujuan dasar dari pelayanan kesehatan ini adalah
memberikan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas
hidup dan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, pelayanan kesehatan ini perlu disandarkan
pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bila
masyarakat memiliki kebutuhan dan/atau tuntutan tertentu terhadap
layanan kesehatan, maka seorang tenaga kesehatan perlu memberikan
pelayanan kesehatan sebagaimana tuntutan dan kebutuhan masyarakat
itu sendiri.
Munculnya gejala masyarakat kelas menengah atas di
Indonesia untuk berobat ke luar negeri merupakan indikasi awal
bahwa kebutuhan dan tututan masyarakat tersebut sudah sangat tinggi,
dan mungkin kurang terpenuhi kepuasannya oleh layanan kesehatan
di dalam negeri, sehingga mereka lebih baik mengeluarkan biaya
lebih besar untuk mendapatkan kepuasan dalam layanan kesehatan.
Selain perubahan income, interaksi-ideologi pun
menyebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Masuknya
ideologi pasar menyebabkan seorang dokter harus mampu
menunjukkan semangat pemasaran (marketing) dalam melaksanakan
praktik. Seiring dengan ini, Yusuf Alam Romadhan mengatakan
bahwa dalam situasi peubahan sosial seperti ini seorang dokter
dituntut untuk mampu memasarkan diri (market yourself) supaya
dapat mempertahankan posisi dirinya sebagai profesi kesehatan yang
dapat eksis di lokasinya sendiri. Artinya bila seorang dokter tidak
mampu memasarkan diri, maka praktik kedokterannya itu tidak akan
kalah saing oleh para tenaga medis dari negara asing.
Seiring dengan hal ini, kompetensi apa yang harus
dikembangkan supaya pelayanankesehatan di Indonesia dapat
berkembang dengan baik? Hal yang pertama, nilai lebih dari
pelayanan kesehatan itu adalah mampu memberikan kepuasan pada
pelanggan. Mau tidak mau, seorang tenaga medis harus secara empiris
mengakui bahwayang dilakukannya selama ini adalah memberikan
99
jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimana masyarakat
berpotensi sebagai konsumen atau pelanggan kesehatan. Oleh karena
itu, hal yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada
konsumen pelayanan kesehatan.
Pelayanan prima menjadi satu tuntutan penting bagi seorang dokter
di era modern. Daldiyono menyebutnya dengan istilah dokter yang
bijak. Bila kita mengembangkan konsep ini dapat dikatakan bahwa
di era modern ini dibutuhkan tenaga kesehatan yang bijak. Tidak
sederhana untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang baik, apalagi
menunjuk siapa dan bagaimana tenaga kesehatan yang bijak. Untuk
panduan awal, Daldiyono mengembangkan konsep tentang tenaga
kesehatan yang bijak yaitu:
a. Memiliki pengalaman pendidikan kesehatan
b. Kompoten dalam melaksanakan praktik kesehatan yang bermutu
dan manusiawi (good clinical practice)
c. Menerapkan sistem dan cara pelayanan kesehatan yang bermutu
serta beretika (good clinical governance)
100
BAB XI
MAKANAN : MAKNA BUDAYA
DAN KESEHATAN
Setiap mahluk hidup membutuhkan makanan. Sebagai
mahluk hidup manusia pun membutuhkan makanan untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, setiap
orang akan senantiasa berusaha mencari makanan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Kelompok tertentu berpendirian bahwa hakikat hidup
adalah bekerja untuk mencari makanan. Sehingga wajar jika
kelompok Darwinian mengatakan bahwa perjuangan hidup adalah
perjuangan untuk mendapatkan makanan. Hanya mereka yang
mampu mendapatkan akses makanan sajalah yang dapat
mempertahankan hak hidupnya. Sementara orang yang tidak
mendapatkan akses pada makanan, dia akan mengalami
ketersisihan dari kehidupan ini. Dalam hukum rimba, siapa yang
dapat menguasai sumber-sumber produksi, maka dia yang
memiliki peluang untuk mempertahankan hidup lebih baik.
Berdasarkan pertimbangan ini, keberadaan makanan
ternyata memberikan warna-warna kehidupan yang berbeda antara
satu kelompok dengan kelompok lainnya. Makanan bukan lagi
sekedar benda ekonomi yang “hampa makna”. Makanan justru
merupakan entitas budaya yang tumbuh dan berkembang dalam
tatanam kehidupan manusia. Dengan kata lain, bila dikaitkan
dengan konteks sosial budaya, maka makanan itu ternyata
m,engandung makna yang lebih luas dibandingkan sekedar bahan
konsumsi manusia.
Persepsi Budaya dan Makanan
Dalam catatan antropologi, peradaban manusia dibedakan
berdasarkan mata pencaharian masyarakat.
Pada tahap pertama (gelombang hidup manusia) ditandai dengan
adanya peradaban manusia yang didominasi oleh tradisi memburu
dan meramu. Pola konsumsi manusia pada waktu itu dengan
makan makanan hasil ramuan bahan tumbuhan yang dikumpulkan
dari hutan dan/atau memakan hasil hutan (hewan atau tumbuhan)
101
yang diburu dan kemudian dibakar.
Setelah terjadi revolusi atau gelombang peradaban yang
pertama manusia beranjak pada tahapan agrikultur. Mata
pencaharian manusia bukan lagi memburu dan meramu, melainkan
sudah pada tahap bercocok tanam. Pada tahap ini pola dan jenis
makanan yang dikonsumsi pun adalah makanan hasil olahan.
Namun setelah adanya revolusi industri atau gelombang
ketiga, olahan manusia ini berkembang dengan pesat. Dengan
bantuan tehnologi dan industrialisasi, berbagai jenis makanan, baik
yang merupakan olahan dari bahan dasar tumbuhan dan hewan,
maupun dengan bahan kimiawi bwrmu8nculan ke permukaan.
Pada saat ini manusia sudah bukan lagi hanya memakan hasil
tanaman melainkan hasil olahan industri.
Setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda mengenai
benda yang dikonsumsi. Perbedaan persepsi ini sangat dipengaruhi
oleh nilai dan norma budaya yang berlaku di masyarakatnya.
Pola makan masyarakat modern cenderung mengkonsumsi
makanan siap saji (fast food). Hal ini mereka lakukan karena
tingginya jam kerja atau tingginya kompotisi hidup yang
membutuhkan kerja keras. Padahal dibalik pola makan tersbut,
misalnya hasil olahan siap santap memiliki kandungan garam yang
sangat tinggi.
Makanan dan Identitas Budaya
Melanjutkan kajian tersebut, maka telaah mengenai makna
budaya dari sebuah makanan menjadi sangat penting untuk
dipahami oleh berbagai kalangan. Pengetahuan seperti ini, selain
dapat bermanfaat un tuk mengembangkan sikap bijak terhadap
persepsi masyarakat lain, juga untuk menghindari gizi buruk akibat
adanya kesalah persepsi terhadap satu jenis nakanan tertentu.
Terkait dengan masalah ini, ada beberapa nilai budaya makanan
yang perlu diperhatikan.
Kebutuhan Fisiologis
David Morely adalah seorang pertama yang memperkenalkan
penggunaan grafik tumbuh kembang fisik anak sebagai alat untuk
memantau secara logitudinal kecukupan gizi anak dan mulai
102
diadopsi di Indonesia sejak tahun 1974 dengan sebutan Kartu
Menuju Sehat (KMS).
Setiap tahap tumbuh kembang anak membutuhkan asupan
gizi yang berbeda. Oleh karena itu, setiap orang tua atau tenaga medis
perlu memperhatikan aspek asupan gizi bagi setiap tahap tumbuh
kembang anak. Untuk sekedar contoh, kebutuhan akan garam dapur
mengandung unsur sodium dan chlor (NaCl). Unsur sodium penting
untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, selain bertugas
dalam transmisi saraf dan kerja otot..
Kesimpulan pemikiran ini menekankan bahwa mengonsumsi
makanan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan fisiologis seseorang. Oleh karena itu, usaha menjaga
keseimbangan gizi dan/atau konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna
merupakan usaha untuk mendukung pada tuntutan makanan dari sisi
fisiologis.
Makanan Sebagai Identitas Kelompok
Nasi adalah satu komoditas makanan utama bagi
masyarakat Sunda-Jawa. Sementara jagung menjadi komoditas
makanan utama bagi masyarakat Madura. Bagi orang Barat mereka
tidak membutuhkan nasi setelah mengonsumsi roti karena roti
merupakan makanan utama dalam budaya Barat. Persepsi dan
penilaian seperti ini merupakan makna makanan sebagai budaya
utama sebuah masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila
orang sunda , kendati sudah makan roti kadangkala masih berkata
belum makan karena dirinya belum menyantap nasi.
Karena adanya kesangsian terhadap makanan hasil olahan
atau makanan instan, banyak diantara masyarakat kota yang sudah
mulai berpindah ke tradisi vegetarian. Bagi kelompok “gang”
menghirup ganja, narkoba, dan merokok merupakan ciri
kelompoknya. Kacang diidentikkan sebagai makanan yang bisa
menemani orang untuk nonton sepak bola. Merokok menjadi teman
untuk menghadirkan inspirasi atau kreativitas. Pemahaman dan
persepsi seperti ini lebih merupakan sebuah persepsi budaya
tandingan (counter-culture) terhadap budaya dominan.
Berdasarkan telaahan ini, makanan mengandung makna
sebagai :
103
a. Identitas arus budaya utama (dominan culture), artinya harus
ada dan menjadi kebutuhan utama masyarakat.
b. Budaya tandingan (counterculture), yaitu menghindari arus
utama akibat adanya kesangsian atau ketidaksepakatan
denganbudaya arus utama.
c. Makanan sebagai identitas budaya bagi sekelompok tertentu
(subculture).
Makanan Sebagai Nilai Sakral
Di luar makna budaya, dalam kehidupan masyarakat
Indonesia makanan pun ada yang mengandung nilai sakral dan ada
yang mengandung nilai profan. Khusus untuk makanan yang memiliki
nilai sakral, diantaranya dapat ditemukan dalam beberapa agama atau
budaya daerah Indonesia.
Daging kambing kurban dan beras zakat merupakan
makanan sakral dalam kehidupan bagi kalangan muslim. Kue
sakramen merupakan makanan sakral bagi kalangan nasrani. Sapi
adalah hewan sakral bagi masyarakat Hindu. Rokok cerutu
merupakan komoditas sakral bagi masyarakat Jawa karena biasa
digunakan sebagai bagian dari sesaji bagi nenek moyangnya.
Makanan Sebagai Keunggulan Etnik
Bila orang mendengarkan kata gudeg, maka akan terbayang
kota Yogyakarta. Mendengar kata pizza akan terbayang Italia.
Mendengar kata dodol dan jeruk terbayang kota Garut. Tetapi bila
mendengar kata jeruk bangkok, ayam bangkok sudah tentu terbayang
Bangkok Thailand.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa makanan merupakan
unsur budaya yang membawa makna budaya komunitasnya. Di dalam
makanan itu orang tidak hanya mengonsumsi material makanannya
melainkan ‘mengonsumsi” kreatifitas dan keagungan nilai budaya.
Tidak mengeherankan bila ada orang yang makan tahu Sumedang
terasa hampa makna bila tahu itu dibeli di luar Sumedang dan dirinya
pun tidak pergi ke Sumedang. Begitu pula sebaliknya, masyarakat
akan memiliki kebanggaan tertentu bila mengonsumsi moci yang
dibeli asli dari Cianjur.
104
Makanan Sebagai Kebutuhan Medis
Seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan sekarang
sudah banyak buku dan temuan penelitian yang mengulas mengenai
manfaat makanan bagi peningkatan kesehatan. Kebutuhan vitamin
atau gizi dapat dipenuhi jika seseorang mengonsumsi makanan 4
sehat 5 sempurna. Hembing telah mengembangkan pengobatan
alternatif yang bersumber dari makanan atau ramuan. Hal ini
menunjukkan bahwa memakan suatu makanan memiliki nilai medis.
Nilai Norma Makanan
Sebelum menjelaskan beberapa kasus perilaku kesehatan
yang terkait dengan masalah ekonomi, ada baiknya dikemukakan
terlebih dahulu mengenai norma sosial yang berkembang di
masyarakat.
Norma sosial ini kita kembangkan dalam lima kategori
norma :
a. Makanan yang memiliki nilai pokok (wajib), yang dimaksud
wajib ini, yaitu makanan pokok dari sebuah komunitas.
Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, nasi merupakan
makanan pokok masyarakat Sunda-Jawa, jagung menjadi
makanan pokok masyarakat Madura.
b. Makanan yang memiliki nilai anjuran (sunnah) yaitu komoditas
makanan yang merupakan tambahan (suplemen). Di era modern
ini banyak produksi makanan yang berfungsi sebagai
makanan/minuman suplemen.
c. Makanan yang memiliki nilai mubah. Kelompok makanan ini
sesungguhnya belum diketahui efek positif atau negatifnya bagi
kesehatan. Informasi yang baru diketahui itu, yang kandungan
gizi makanan dari komoditas tersebut sangat rendah sehingga
tidak dianjurkan dan juga tidak menjadi sebuah pantangan.
d. Makanan yang memiliki nilai pantangan. Sebuah masyarakat atau
individu kadang memiliki pantangan. Karakter pantangan ini,
lebih bersifat sementara. Bagi mereka yang akan dioprasi pantang
makan, orang yang sedang sakit tipus dilarang makan makanan
yang keras.
e. Dalam kategori yang terakhir, yaitu pantangan mengonsumsi
sebuah makanan yang bersifat permanen. Dalam agama, terdapat
105
beberapa jenis makanan-minuman yang dilarang dikonsumsi
secara permanen.
Frustasi Ekonomi dan Perilaku Konsumsi
Tekanan hidup dan tantangan hidup menyebabkan
seseorang dapat melakukan perilaku yang menyimpang dari norma
masyarakat arus utama. Salah satu perilaku menyimpang ini, yaitu
munculnya perilaku masyarakat dalam memperdagangkan makanan
yang sudah tidak layak jual dan layak konsumsi secara medis.
Gejala keracunan karena makanan hampir menjadi bagian
dari berita bagi bangsa kita. Keracunan makanan di pesantren, di
rumah penduduk yang sedang mengadakan syukuran, di pabrik, di
kampus dan lain sebagainya. Bila kejadian keracunan makanan
tersebut terjadi hanya satu kali mungkin tidak menarik untuk
diperhatikan. Namun, bila kejdian ini berulang dan terjadi di berbagai
tempat, maka peristiwa keracunan makanan secara kolektif tersebut
menjadi fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian yang
seksama dari kita semua. Dengan kata lain ada apa dengan pola
konsumsi masyarakt kita?
Dalam suasana frustrasi ekonomi, seorang produsen akan
mengerahkan seluruh strateginya guna menjual produk makananya.
Mereka tidak peduli tanggal kadaluarsa. Sementara anggota
masyarakat yang sedang mengalami frustrasi secara ekonomi tidak
akan memedulikan masalah kesehatan makanan atau kandungan gizi
makanan. Dalam benak mereka, yang penting bisa makanan atau yang
penting terjangkau (murah meriah).
Gaya Hidup dan Gaya Makan
Perkembangan tehnologi informasi dan industri, tidak
hanya memberikan pengaruh terhadap dunia ekonomi. Efek langsung
dan tidak langsung dari kemajuan peradaban manusia ini, terasa pula
dalam bentuk perubahan gaya hidup. Bila 10 tahun yang lalu, masih
banyak terlihat para pengusaha atau karyawan makan di rumahnya
sendiri serta seorang mahasiswa atau seorang anak kecil sarapan di
rumah bersama keluarga. Dalam situasi zaman seperti ini, makan
bersama keluarga itu menjadi sesuatu yang istimewa dan didapatnya
pada hari-hari istimewa misalnya pada hari libur bersama.
106
Pada suatu saat, mungkin sempat melihat ada seorang istri
dalam mobilnya duduk di samping suaminya yang sedang memegang
setir mobil menyuap suami untuk makan pagi. Dalam satu waktu
tertentu, mungkin sempat melihat anak kecil yang mau berangkat ke
sekolah disuap makan dalam kendaraan sepanjang jalan menujmu
lokasi sekolah. Inilah sebagian dari realitas gaya hidup di zaman
modern, yang terkait dengan makanan.
Berbeda dengan makanan sebagai keunggulan etnik, dalam
gaya hidup modern ini, ada makanan yang dianggapnya sebagai
budaya unversal. Makanan cepat saji di restoran-restoran cepat saji
(fast food) merupakan satu diantara sekian banyak jenis makanan
yang muncul kepermukaan sebagai makanan global.
107
BAB XII
SIKLUS HIDUP, KESEHATAN, DAN
PERAN SOSIAL
Salah satu upaya untuk menjelaskan persoalan-persoalan
kesehatan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan
pendekatan siklus hidup. Dari siklus hidup ini dapat dirinci
perkembangan psikologis dan sosiologis serta kebutuhan kesehatan
individu tersebut.
Asumsi yang dianut dalam wacana ini, dapat dirinci
perkembangan individu akan maksimal serta potensi genetiknya
akan berkembang dengan baik jika kepadanya diberikan lingkungan
berkualitas, baik diri gizi maupun lingkungan sosialnya. Sehingga
pada akhirnya dapat membangun pribadi manusia yang sehat baik
secara jasmaniah, emosi, spiritual, sosial dan ekonomi.
Dari asumsi tersebut, dapat dirumuskan dan/atau telaah
mengenai peran-peran sosial yang dikembangkan individu dalam
setiap tahap siklus kehidupannya masing-masing. Kalangan ilmuwan
psikologi sudah berusaha keras untuk menunjukkan tahap-tahap
perkembangan dari setiap tugas perkembangan (development task)
psikologis. Berdasarkan temuan saat ini, ternyata dalam setiap tahap
perkembangan tersebut, memiliki resiko kesehatan yang khusus dan
peran sosial yang berbeda antara tahap yang satu dengan tahap
lainnya. Oleh karena itu memahami peran sosial dan kesehatan
individu dapat dipantau dari perspektif siklus hidup individu.
Pendekatan yang digunakan ini, dikembangkan dari model
yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan RI saat
menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Bila disederhanakan,
pendekatan siklus yang dikembangkan tersebut dapat diformulasikan
ulang sebagai berikut :
108
Siklus Hidup Individu
Masa Kehamilan
Kehamilan merupakan sesuatu hal yang membahagiakan,
penyebabnya karena mereka akan mendapatkan anggota baru dalam
sebuah keluarga. Oleh karena itu kehamilan ini kerap kali menjadi
perhatian serius bagi anggota keluarga maupun masyarakat. Ada
beberapa aspek sosial yang terkait dengan masa kehamilan ini.
Pertama, peran kehamilan dapat dimaknai dengan peran
awal perekat sosial. Dalam penelitian Evi (2005) menyebutkan bahwa
perempuan yang cenderung infertil, terancam diceraikan. Oleh karena
itu, kehamilan atau lebih khusus lagi kehadiran anak merupakan
perekat sosial dalam sebuah masyarakat.
Kedua, tingginya harapan (ekspektasi) suami atau anggota
keluarga terhadap bayi yang ada dalam kandungan, menyebabkan
tingginya perlakuan anggota keluarga terhadap ibu hamil. Oleh karena
itu, seorang ibu hamil diposisikan setara dengan orang sakit sehingga
peran sosial dihapuskan dari tanggung jawab si ibu hamil.
Ketiga, dalam konteks ini ngidam merupakan instrumen
khusus yang menjadi alat ukur dalam membangun kewjiban baru
orang lain untuk memosisikan ibu hamil sebagai ratu dalam
kehidupan.
Keempat, ada yang berpendapat bahwa bila seorang ibu
hamil memiliki kebutuhan makan yang lebih, karena dia
mengonsumsi makan untuk dua orang.
meninggal Masa konsepsi, ibu hamil
Manula
Dewasa
Remaja
balita
Anak-anak
109
Adapun masalah kesehatan spesipik dari ibu hamil
diantaranya :Mendapatkan pelayanan antenatal dengan baik dan
teratur
a. Memperoleh makanan bergizi dan cukup istirahat
b. Mendapatkan ketenangan dan kebahagian
c. Memperoleh persediaan biaya persalinan dan rujukan ke rumah
sakit bila terjadi komplikasi.
Seiring terjadi kematian, pada persalinan, lebih banyak
disebabkan karena tingginya pendarahan. Selain itu, ada pula
penyebab lain yang biasa menimbulkan kematian pada ibu hamil,
yaitu adanya 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu
banyak). Kondisi ini didung oleh 3 tarlambat (terlambat mengenali
tanda-tanda, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat
mendapat pertolongan).
Masa Balita
Tahap perkembangan selanjutnya yaitu memasuki tahap
anak-anak. Pada masa ini, pendidikan sosial yang terjadi pada masa
balita, memiliki peran nyata dalam pertumbuhan dan perkembangan
selanjutnya.
Ada beberapa peran sosial yang dimunculkan anak-anak
dalam kehidupan di masyarakat.
Pertama, dalam mengembangka kepribadiannya secara utuh
setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan ruang main dan ekspresi
yang sesuai dengan dirinya. Ketiadaan akses untuk mendapatkan
ruang main seperti ini akan berpengaruh terhadap optimasi
pertumbuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat.
Kedua, anak adalah tanda sosial dari keluarga, khususnya ibu
dan anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan sosial anak,
dibaca sebagai bagian dari peran nyata orang tua dalam memberikan
pelayanan kepada anak-anaknya. Seorang anak yang kurang gizi,
sesungguhnya menjadi bukti lemahnya peran orang tua dalam
memberikan asupan yang seimbang dan berkualitas. Demikian pula,
bila hadir seorang anak yang sehat dan cerdas dapat menunjukkan diri
sebagai tanda sosial bagi keluarganya.
Ketiga, anak adalah kandidat dari pemegang amanah harapan
atau impian orang tuanya. Berbagai aktivitas orang tua, baik yang
110
terkait dengan masalah ekonomi maupun prestise hidup, diharapkan
dapat ditindaklanjut oleh anak-anaknya.
Keempat, sebagaimana yang terjadi pada peran bayi,
kehadiran anak ini memperkuat nilai solidaritas dalam keluarga.
Hubungan suami istri, akan semakin tinggi dan rekat bila didukung
oleh kehadiran anak yang berkualitas.
Kelima, memiliki nilai sosial yang tinggi, baik untuk nilai
ekonomi, maupun nilai sosial. Kehadiran anak bagi keluarga
merupakan tambahan tenaga kerja baru bagi keluarganya.
Masa Remaja
Pada masa remaja (adolescens), selain pertumbuhan yang
cepat (growth spurt), juga timbul tanda-tanda seks sekunder, serta
diakhiri dengan berhentinya pertumbuhan. Khusus pada perempuan,
masa ini merupakan masa persiapan untuk menjadi calon ibu.
Keberadaan gizi pada masa ini berpengaruh terhadap kehamilan
mereka kelak dan juga terhadap bayi yang akan dilahirkannya.
Aktivitas mereka pun meningkat, sehingga kebutuhan
gizinya juga bertambah. Nafsu makan mereka umumnya baik. Mereka
sering mencari makanan tambahan atau jajan di luar waktu makan.
Masalahnya apabila jajan itu berkalori tinggi, kegemukan dengan
segala akobatnya bisa terjadi. Maka diantara mereka ada yang
berusaha mengurangi dampak negatif dari kegemukan atau berusaha
menghindari kegemukan. Beberapa masalah kesehatan yang dapat
berpengaruh terhadap kesehatan remaja termasuk kesehatan
reproduksi kalangan remaja adalah sebagai berikut :
a. Masalah gizi, yang meliputi anemia atau kurang gizi dan
pertumbuhan yang terhambat. Khusus pada kalangan putri, bila
pertumbuhan panggul sempit dapat berisiko pada proses
melahirkan bayi berat dikemudian hari.
b. Masalah seks dan seksual, meliputi pengetahuan yang lengkap
terhadap mitos dan informasi berbagai hal tentang seks dan
seksualitas, penyalahgunaan peran seks dan seksualitas, serta
penanganan kehamilan remaja.
c. Hal yang tidak boleh dilupakan pula, ada munculnya aneka ragam
pola atau gaya hidup remaja. Gaya hidup ini, baik yang terkait
dengan kesehatan reproduksi maupun dengan pola konsumsi
111
dapat berpengaruh tinggi terhadap masalah kesehatan remaja.
Masa Dewasa
Secara psikologis tahap perkembangan ini dikategorikan
sebagai tahap kematangan (maturity), dewasa dalam arti
pengembangan diri maupun dalam konteks sosial. Seiring dengan hal
ini, ada beberapa peran sosial yang dikembangkan dalam masa
dewasa.
Pertama orang dewasa sudah memiliki tugas dan kewajiban
diri dalam membangun komunitas, baik dalam skala kecil (keluarga),
pertemanan, maupun dalam konteks keamsyarakatan. Dengan tugas
seperti ini, baik seorang perempuan maupun laki-laki, tampil percaya
diri dalam mengembangkan komunikasi sosial.
Kedua, dalam masyarakat timur, seseorang yang sudah
dewasa sudah mulai memikirkan mengenai masa depan, baik masa
depan ekonomi maupun masa depan sosialnya. Bekerja dan
mengumpulkan kekayaan adalah salah satu upaya untuk menjaga
keberlangsungan hidup dirinya.
Ketiga, pada sisi kesehatan, masa ini termasuk dalam
kategori matang, kendati demikian , perlu diperhatikan
perkembangan ke arah meno-andropause, penyakit degenatif
termasuk rabun, gangguan mobilitas dan osteoporosis, serta perlu
adanya deteksi dini terhadap kanker rahim dan kanker prostat, yang
akan muncul diakhir penghujung usia dewasa.
Keempat, dalam sosiologi pada umumnya, telah banyak
dikenal bahwa, pada masa dewasa ini merupakan masa perkawinan
atau berkeluarga. Fungsi keluarga menurut sosiologi yaitu :
a. Fungsi apeksi yaitu membangun dan mengembangkan nilai dan
norma masyarakat.
b. Fungsi reproduksi, yaitu berfungsi untuk memmiliki keturunan.
c. Fungsi sosialisasi, artinya keluarga mmenjadi lembaga pertama
dan utama untuk bermasyarakat.
d. Pengaturan seksual, artinya bagi seorang remaja yang sudah
dewasa mereka mulai meyakini dan menunjukkan peran
seksualnya dihadapan orang lain.
e. Fungsi penentuan status, artinya di lingkungan keluarga ini setiap
anak khususnya mendapat pembelajaran mengenai status diri dan
112
status sosial.
f. Fungsi perlindungan, artinya dalam keluarga itu ada upaya untuk
membangun perlindungan antara satu dengan yang lainnya.
g. Fungsi ekonomi, artinya para anggota keluarga khususnya orang
tua memiliki peran sosial untuk memberikan layanan kesehatan
ekonomi kepada anggota keluarganya.
Masa Usia Lanjut
Menurut teori penarika diri (desengagement theory), usia
lanjut merupakan proses yang bergerak secara perlahan dari individu
untuk menarik diri dari peran sosial atau dari konteks sosial. Keadaan
ini menyebabkan interaksi individu yang lanjut usia mulai menurun,
baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pada usia lanjut sekaligus
terjadi triple loss, yaitu:
a. Kehilangan peran (loss of role)
b. Hambatan kontak sosial (restriction of contacts of relationships)
dan
c. Berkurangnya komitmen (reduced commitment to sosial mores
and values)
Menurut Hardywinoto dan Tony Setiabudi (2005:112) tidak
semua lanjut usia mengeluh maca-macam dan bila ada keluhan yang
dikemukakan individu lanjut usia, perlu diinterpretasikan
secaraberbeda. Karena setiap keluhan tersebut, kendatipun memiliki
masalah penyakit yang sama, namun akan muncul secara berbeda
bergantung pada kematangan pribadi dan situasi sosial ekonomi lanjut
usia masing-masing. Untuk merinci ulang, peran individu usia lanjut
ini dapat ditemukan dalambeberapa hal sosial berikut:
Pertama, menjadi orang yang lanjut usia memiliki hak untuk
menarik diri dari peran-peran sosial. Kewajiban sosial seperti bekerja,
bergaul di masyarakat, partisipasi pembangunan merupakan beberapa
contoh nyata yang kemudian dilepaskan dari peran dirinya.
Kedua, memunculkan peran orang lain untuk menunjukkan
peran dan kepeduliannya terhadap individu lanjut usia. Kendatipun
masi kontroversi, namun sikap dan peran orang lain terhadap lanjut
usia ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.
Ketiga, setelah menginjakkan diri pada usia lanjut, seorang
individu akan memulai untuk melepaskan hak dan kepemilikannya
113
terhadap berbagai sumber produksi. Hukum waris merupakan hukum
pemindah hak secara menyeluruh (menjelang kematian) kepada
generasi berikutnya.
114
BAB XIII
BUDAYA DALAM PERSALINAN
Dalam kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari budaya dan adat
istiadat. Keberadaan budaya amatlah penting, karena berfungsi
sebagai identitas dan ciri khas. Tidak heran, setiap kelompok atau
golongan masyarakat tertentu memiliki budaya yang berbeda-beda.
1. Budaya
Pengertian budaya
a. Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”,
yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah
segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata
budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi
budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan
karsa. (Gunawan, AH,2000)
b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya
pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah
menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Departemen
Pendidikan Nasional (2000)
c. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-
kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota
masyarakat. Soekanto, S. (2009)
d. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta
masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan
kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material
culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam
sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk
keperluan masyarakat. Soemardjan, S dan Soemardi,S. (1964)
e. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan
berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia
terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang
merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi
berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan
penghidupannya guna mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
115
2. Tradisi
Pengertian Tradisi
a. Tradisi (Bahasa Latin: traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan,
dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang
telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari
kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu
negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang
palin mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang
diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun
(sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu teradisi
dapat punah.
b. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang
berasal dari masa lalu namun masi ada hingga kini dan belum
dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai
warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian
tradisi yang menjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan
secara kebetulan atau disengaja. Sztompka,P.(2007)
c. Dari pemahaman tersebut apapun yang dilakukan oleh
manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya
yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia
dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti hal tersebut
adalah manjadi bagian dari kebudayaan.
d. Secara khusus tradisi oleh C.A.Van Peurse diterjemahkan
sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat
istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, Tradisi dapat dirubah
diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam
perbuatan manusia. Perursen, CAV.(1998)
Kebiasaan yakni sesuatu yang kamu lakukan secara
periodik (presen tense/saat ini). Dulunya, (past tense) hal itu
nggak pernah kamu lakukan, tapi sekarang jadi
melakukannya secara periodik. Defenisi lain di jelaskan
bahwa kebiasaan atau tradisi adalah sesuatu yang sudah
dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan
sebuah sekelompok masyarakat, untuk pelestariannya pada
generasi berikutnya dengan cara lisan atau pembinaan,
maupun tulisan.
Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya
116
dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat
walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah
tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-
ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap
sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering
disamakan dengan adat istiadat. Jadi dapat disimpulkan
bahwa adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang
sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur
tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai
peraturan sopan santun yang turun temurun pada umumnya
adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu
yang suci (sakral) danj berhubungan dengan tradisi rakyat
yang telah turun-temurun.
Menurut arti yang laengkap bahwa tradisi mencakup
kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar
menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan
dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti
warisan, apa yangt benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini
senada dengan apa yang dikatakan Shils. Keseluruhan benda
material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun
benar-benar masi ada kini belum dihancurkan.”Segala
sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke
masa kini merupakan suatu tradisi”.
3. Persalinan
Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu sebagai berikut :
a. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi
yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar
(Prawirohardjo, S 2002).
b. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran
janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37–42
minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala
yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada
ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, S 2002).
c. Persalinan adalah suatu proses dimana seorang wanita
melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang
teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai
dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses
117
persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam
(Bennett, V. et all. 1996).
d. Persalinan adalah suatu proses fisiologis yang
memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu
untuk dapat melahirkan janinnya melaui jalan lahir (Moore,
2001).
e. Persalinan adalah suatu proses dimana seorang wanita
melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang
teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai
dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses
persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam
(Kurniarum, 2016). Menurut Mochtar.R (2012) persalinan
atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran
hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui
vagina ke dunia luar (Mochtar, 2012)
Macam- macam persalinan:
a. Persalinan Spontan Yaitu persalinan yang berlangsung
dengan kekuatan ibu sendiri, melalui jalan lahir ibu tersebut.
b. Persalinan Anjuran Persalinan yang tidak dimulai dengan
sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan
ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin.
c. Persalinan Buatan Bila persalinan dibantu dengan tenaga
dari luar misalnya ekstraksi forceps, atau dilakukan operasi
Sectio Caesaria.
Persalinan berdasarkan umur kehamilan :
a. Abortus Pengeluaran buah kehamilan sebelum kehamilan 22
minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gr.
b. Partus immaturus Pengeluaran buah kehamilan antara 22
minggu dan 28 minggu atau bayi dengan berat badan antara
500 gram dan 999 gram.
c. Partus prematurus Pengeluaran buah kehamilan antara 28
minggu dan 37 minggu atau bayi dengan berat badan antara
1000 gram dan 2499 gram.
d. Partus maturus atau a’terme Pengeluaran buah kehamilan
antara 37 minggu dan 42 minggu atau bayi dengan berat
badan 2500 gram atau lebih.
118
e. Partus postmaturus atau serotinus Pengeluaran buah
kehamilan setelah kehamilan 42 minggu
Tanda-tanda bahwa persalinan sudah dekat
a. Lightening
Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa
bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang
sesak, tetapi sebaliknya ia merasa bahwa berjalan sedikit
lebih sukar, dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada
anggota bawah.
b. Pollikasuria
Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan didapatkan
epigastrium kendor, fundus uteri lebih rendah dari pada
kedudukannya dan kepala janin sudah mulai masuk ke dalam
pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung
kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering
kencing yang disebut Pollakisuria.
c. False labor
Tiga (3) atau empat (4) minggu sebelum persalinan, calon ibu
diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya
merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. His
pendahuluan ini bersifat:
1) Nyeri yang hanya terasa di perut bagian bawah
2) Tidak teratur
3) Lamanya his pendek, tidak bertambah kuat dengan
majunya waktu dan bila dibawa jalan malah sering
berkurang
4) Tidak ada pengaruh pada pendataran atau pembukaan
cervix
d. Perubahan cervix
Pada akhir bulan ke-IX hasil pemeriksaan cervix
menunjukkan bahwa cervix yang tadinya tertutup, panjang
dan kurang lunak, kemudian menjadi lebih lembut, dan
beberapa menunjukkan telah terjadi pembukaan dan
penipisan. Perubahan ini berbeda untuk masingmasing ibu,
misalnya pada multipara sudah terjadi pembukaan 2 cm
namun pada primipara sebagian besar masih dalam keadaan
tertutup.
119
e. Energy Sport
Beberapa ibu akan mengalami peningkatan energi kira-kira
24-28 jam sebelum persalinan mulai. Setelah beberapa hari
sebelumnya merasa kelelahan fisik karena tuanya kehamilan
maka ibu mendapati satu hari sebelum persalinan dengan
energi yang penuh. Peningkatan energi ibu ini tampak dari
aktifitas yang dilakukannya seperti membersihkan rumah,
mengepel, mencuci perabot rumah, dan pekerjaan rumah
lainnya sehingga ibu akan kehabisan tenaga menjelang
kelahiran bayi, sehingga persalinan menjadi panjang dan
sulit.
f. Gastrointestinal Upsets
Beberapa ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda seperti
diare, obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan
hormon terhadap sistem pencernaan.
Tanda pasti dari persalinan adalah :
a. Timbulnya kontraksi uterus
Biasa juga disebut dengan his persalinan yaitu his pembukaan
yang mempunyai sifat sebagai berikut :
1) Nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian
depan.
2) Pinggang terasa sakit dan menjalar kedepan
3) Sifatnya teratur, inerval makin lama makin pendek dan
kekuatannya makin besar
4) Mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau
pembukaan cervix.
5) Makin beraktifitas ibu akan menambah kekuatan
kontraksi. Kontraksi uterus yang mengakibatkan
perubahan pada servix (frekuensi minimal 2 kali dalam 10
menit). Kontraksi yang terjadi dapat menyebabkan
pendataran, penipisan dan pembukaan serviks.
b. Penipisan dan pembukaan servix
Penipisan dan pembukaan servix ditandai dengan adanya
pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula.
c. Bloody Show (lendir disertai darah dari jalan lahir)
Dengan pendataran dan pembukaan, lendir dari canalis
cervicalis keluar disertai dengan sedikit darah. Perdarahan
120
yang sedikit ini disebabkan karena lepasnya selaput janin
pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa
capillair darah terputus.
d. Premature Rupture of Membrane Adalah keluarnya cairan
banyak dengan sekonyong-konyong dari jalan lahir. Hal ini
terjadi akibat ketuban pecah atau selaput janin robek.
Ketuban biasanya pecah kalau pembukaan lengkap atau
hampir lengkap dan dalam hal ini keluarnya cairan
merupakan tanda yang lambat sekali. Tetapi kadang-kadang
ketuban pecah pada pembukaan kecil, malahan kadang-
kadang selaput janin robek sebelum persalinan. Walaupun
demikian persalinan diharapkan akan mulai dalam 24 jam
setelah air ketuban keluar. (Kurniarum A, 2016).
4. Budaya dalam persalinan
Interaksi antara kondisi kesehatan ibu hamil dengan
kemampuan penolong persalinan sangat menentukan hasil
persalinan yaitu kematian atau bertahan hidup. Secara medis, .
penyebab klasik kematian ibu akibat melahirkan adalah
perdarahan, infeksi dan eklamsia (keracunan kehamilan).
Kondisi-kondisi tersebut bila tidak ditangani secara tepat dan
profesional dapat berakibat fatal bagi ibu dalam proses
persalinan. Namun, kefatalan ini sering terjadi tidak hanya
karena penanganan yang kurang baik tepat tetapi juga karena
ada faktor keterlambatan pengambilan keputusan dalam
keluarga. Umumnya, terutama di daerah pedesaan, keputusan
terhadap perawatan medis apa yang akan dipilih harus dengan
persetujuan kerabat yang lebih tua; atau keputusan berada di
tangan suami yang seringkali menjadi panik melihat keadaan
krisis yang terjadi.
Kepanikan dan ketidaktahuan akan gejala-gejala tertentu
saat persalinan dapat menghambat tindakan yang seharusnya
dilakukan dengan cepat. Tidak jarang pula nasehat-nasehat yang
diberikan oleh teman atau tetangga mempengaruhi keputusan
yang diambil. Keadaan ini seringkali pula diperberat oleh faktor
geografis, dimana jarak rumah si ibu dengan tempat pelayanan
kesehatan cukup jauh, tidak tersedianya transportasi, atau oleh
faktor kendala ekonomi dimana ada anggapan bahwa membawa
121
si ibu ke rumah sakit akan memakan biaya yang mahal. Selain
dari faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan, faktor
geografis dan kendala ekonomi, keterlambatan mencari
pertolongan disebabkan juga oleh adanya suatu keyakinan dan
sikap pasrah dari masyarakat bahwa segala sesuatu yang terjadi
merupakan takdir yang tak dapat dihindarkan.
Pada dasarnya, peran kebudayaan terhadap kesehatan
masyarakat adalah dalam membentuk, mengatur dan
mempengaruhi tindakan atau kegiatan individuindividu suatu
kelompok sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan
kesehatan. Memang tidak semua praktek/perilaku masyaiakat
yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga kesehatan dirinya
adalah merupakan praktek yang sesuai dengan ketentuan
medis/kesehatan. Apalagi kalau persepsi tentang kesehatan
ataupun penyebab sakit sudah berbeda sekali dengan konsep
medis, tentunya upaya mengatasinya juga berbeda disesuaikan
dengan keyakinan ataupun kepercayaankepercayaan yang sudah
dianut secara turun-temurun sehingga lebih banyak
menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi kesehatan.
Dan untuk merubah perilaku ini sangat membutuhkan waktu dan
cara yang strategis. Dengan alasan ini pula dalam hal
penempatan petugas kesehatan dimana selain memberi
pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi sebagai
agen perubah (change agent) maka pengetahuan dan
kemampuan berkomunikasi dari petugas kesehatan sangat
diperlukan disamping kemampuan dan ketrampilan memberi
pelayanan kesehatan. Tim PKRS Kariadi, (2021).
Kelahiran merupakan keajaiban Tuhan yang terjadi setiap
hari. Bagi tenaga kesehatan profesional khususnya
Bidan,kelahiran merupakan pelajaran yang tak pernah selesai
dipelajari, keran memiliki karakterisasi yang bervariasi dan terus
berubah . Kehamilan merupakan sebuah misteri kehidupan, kita
hanya dapat memprediksi. Kelahiran merupakan suatu
kegembiraan bagi anggota keluarga. Pemilihan fasilitas dan
tenaga professional dilakukan oleh ibu dan keluarga dengan
harapan ibu dan anak lahir sehat dan selamat. Pelayanan di
fasilitas kesehatan petugas melakukan intervensi terhadap semua
122
kasus – juga pada kondisi normal, sehingga pada banyak kasus
konsep persalinan normal terganggu. Berdasarkan pengalaman
dan Evidence Based, intervensi yang tidak perlu ternyata
membahayakan perempuan dan bayinya. Untuk itu Bidan
sebagai provider diharapakn dapat kembali kepada Konsep
Fisiologis Persalinan Normal.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang banyak membawa perubahanterhadap kehidupan
manusia baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan
social termasuk dalam bidang kesehatan yang sering dihadapkan
dalam suatu hal yang berhubungan langsungdengan norma dan
budaya yang dianut oleh masyarakat yang bermukim dalam
suatu tempat tertentu. Pengaruh social budaya dalam masyarakat
memberikan peran penting dalam mencapai derajatkesehatan
yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial budaya dalam
masyarakat merupakansuatu tanda bahwa masyarakat dalam
suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahandalam
proses berfikir.
Perubahan sosial dan budaya bisa memberikan dampak
positif maupunnegative.Hubungan antara budaya dan kesehatan
sangatlah erat hubungannya sebagai salah satu contoh suatu
masyarakat desa yang sederhana dapat bertahan dengan cara
pengobatan tertentu sesuai dengan tradisi mereka. Kebudayaan
atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respons terhadap
kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa
memandang tingkatannya. Karena itulah penting bagi tenaga
kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan kesehatan, tapi
juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu
penyakit dan bagaimana meluruskan keyakinan atau budaya
yang dianut hubungannya dengan kesehatan.
Kebudayaan merupakan sikap hidup yang khas dari
sekelompok individu yang dipelajari secara turuntemurun, tetapi
sikap hidup ini ada kalanya malah mengundang resiko bagi
timbulnya suatupenyakit. Kebudayaan tidak dibatasi oleh suatu
batasan tertentu yang sempit, tetapi mempunyai struktur-struktur
yang luas sesuai dengan perkembangan dari masyarakat itu
sendiri. Kebudayaan yaitu sesuatu yang akan mempengaruhi
123
tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang
terdapat dalam pikiran manusia,sehingga dalam kehidupan
sehari-harikebudayaan bersifat abstrak. Kebudayaan (budi atau
akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan
akal manusia. Definisi dari budaya yaitu suatu cara hidup yang
berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah sekelompok
orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.
Di dalam masyarakat sederhana kebiasaan hidup dan adat
istiadat dibentuk untuk mempertahankan hidup diri sendiri dan
kelangsungan hidup suku mereka. Berbagai kebiasaan dikaitkan
dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi yang
bertujuan supaya reproduksi berhasil ibu dan bayi selamat.
Dari sudut pandang modern tidak semua kebiasaan itu
baik. Ada beberapa yang kenyataannya malah merugikan.
Contoh pada kebiasaan menyusukan bayi yang lama pada
beberapa masyarakat merupakan contoh yang baik kebiasaan
yang bertujuan melindungi bayi. Tetapi bila air susu ibu sedikit
atau pada ibu-ibu lanjut usia, tradisi budaya ini dapat
menimbulkan masalah tersendiri. Dia berusaha menyusukan
bayinya dan gagal. Bila mereka tidak mengetahui nutrisi mana
yang dibutuhkan bayi (biasanya demikian) bayi
dapat mengalami malnutrisi dan mudah terserang infeksi.
Permasalahan yang sebenarnya cukup besar pengaruhnya
yaitu tepatnya pada masalah gizi. Hal ini disebabkan karena
adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan
terhadap beberapa makanan. Sementara, kegiatan mereka sehari-
hari tidak berkurang ditambah lagi dengan pantangan-pantangan
terhadap beberapa makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan
oleh wanita hamil, bersalin dan setelah melahirkan, tentunya
akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak
heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup
tinggi terutama di daerah pedesaan. Dikatakan pula bahwa
penyebab utama dari tingginya angka anemia pada wanita hamil
disebabkan karena kurangnya zat gizi yang dibutuhkan untuk
pembentukan darah.
a. Budaya persalinan di Jawa Tengah
Ada kepercayaan di Jawa Tengah bahwa ibu hamil
124
pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan
dan pantang makan daging karena akan menyebabkan
perdarahan yang banyak. Tradisi Masyarakat Jawa Ibu
melahirkan Babaran, mbabar dapat diartikan: sudah selesai,
sudah menghasilkan dalam wujud yang sempurna. Babaran
juga menggambarkan selesaianya proses karya batik
tradisional. Istilah babaran juga dipakai untuk seorang ibu
yang melahirkan anaknya. Ubarampe yang dibutuhkan
untuk selamatan kelahiran adalah Brokohan. Ada macam
macam ubarampe Brokohan. Pada jaman ini Brokohan
basanya terdiri dari: beras, telur, mie instan kering,gula, teh
dan sebagainya. Namun jika dikembalikan kepada makna
yang terkandung dalam selamatan bayi lahir, brokohan
cukup dengan empat macam ubarampe saja
lnteraksi antara kondisi kesehatan ibu hamil dengan
kemampuan penolong persalinan sangat menentukan hasil
persalinan yaitu kematian atau bertahan hidup. Secara
medis, . penyebab klasik kematian ibu akibat melahirkan
adalah perdarahan, infeksi dan eklamsia (keracunan
kehamilan). Kondisi-kondisi tersebut bila tidak ditangani
secara tepat dan profesional dapat berakibat fatal bagi ibu
dalam proses persalinan. Namun, kefatalan ini sering terjadi
tidak hanya karena penanganan yang kurang baik tepat
tetapi juga karena ada faktor keterlambatan pengambilan
keputusan dalam keluarga. Umumnya, terutama di daerah
pedesaan, keputusan terhadap perawatan medis apa yang
akan dipilih harus dengan persetujuan kerabat yang lebih
tua; atau keputusan berada di tangan suami yang seringkali
menjadi panik melihat keadaan krisis yang terjadi.
Kepanikan dan ketidaktahuan akan gejala-gejala
tertentu saat persalinan dapat menghambat tindakan yang
seharusnya dilakukan dengan cepat. Tidak jarang pula
nasehat-nasehat yang diberikan oleh teman atau tetangga
mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadaan ini
seringkali pula diperberat oleh faktor geografis, dimana
jarak rumah si ibu dengan tempat pelayanan kesehatan
cukup jauh, tidak tersedianya transportasi, atau oleh faktor
125
kendala ekonomi dimana ada anggapan bahwa membawa si
ibu ke rumah sakit akan memakan biaya yang mahal. Selain
dari faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan,
faktor geografis dan kendala ekonomi, keterlambatan
mencari pertolongan disebabkan juga oleh adanya suatu
keyakinan dan sikap pasrah dari masyarakat bahwa segala
sesuatu yang terjadi merupakan takdir yang tak dapat
dihindarkan.
Pada dasarnya, peran kebudayaan terhadap kesehatan
masyarakat adalah dalam membentuk, mengatur dan
mempengaruhi tindakan atau kegiatan individuindividu
suatu kelompok sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan
kesehatan. Memang tidak semua praktek/perilaku
masyaiakat yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga
kesehatan dirinya adalah merupakan praktek yang sesuai
dengan ketentuan medis/kesehatan. Apalagi kalau persepsi
tentang kesehatan ataupun penyebab sakit sudah berbeda
sekali dengan konsep medis, tentunya upaya mengatasinya
juga berbeda disesuaikan dengan keyakinan ataupun
kepercayaankepercayaan yang sudah dianut secara turun-
temurun sehingga lebih banyak menimbulkan dampak-
dampak yang merugikan bagi kesehatan. Dan untuk
merubah perilaku ini sangat membutuhkan waktu dan cara
yang strategis. Dengan alasan ini pula dalam hal
penempatan petugas kesehatan dimana selain memberi
pelayanan kesehatan pada masyarakat juga berfungsi
sebagai agen perubah (change agent) maka pengetahuan dan
kemampuan berkomunikasi dari petugas kesehatan sangat
diperlukan disamping kemampuan dan ketrampilan
memberi pelayanan kesehatan.
b. Budaya di Jawa Barat
Ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja
harus mengurangi makannya agar bayi yang dikandungnya
kecil dan mudah dilahirkan/persalinannya tidakmengalami
hambatan kelak. Tradisi persalinan dengan praktik ritual
parajidi wilayah Pameungpeuk, Garut Selatan sangat erat
hubungannya dengan masyarakatnya yang masih percaya
126
pada kemujaraban tradisi praktik ritual paraji tersebut.
Masyarakat percaya bahwa paraji mampu memberikan
pertolongan pada masalah kesehatan ibu hamil hingga
masa persalinan serta dalam perawatan bayi. Merunut
pada tradisi persalinan masyarakat Pameungpeuk, paraji
merupakan sosok yang memiliki kamampuan komunikasi
dengan pasien, bagi ibu muda yang baru mengalami fase
kehamilan, paraji mampu memberikan efek ketenangan
pada ibu hamil sampai melalui fase persalinan. Paraji
mampu melibatkan suami dan anggota keluarga yang
lain dalam proses kehamilan sampai persalinan. Suami
dan keluarga biasanya memiliki tugas membantu sang
ibu hamil untuk mematuhi pantangan-pantangan yang
diberikan paraji demi kelancaran proses kehamilan
sampai persalinan. Tanpa disadari, konteks tersebut
memberikan rasa tanggung jawab bagi sang suami untuk
senantiasa siaga menjaga ibu dan calon bayi. Pada masa
pasca persalinan, paraji merupakan sosok yang setia
dalam melakukan perawatan bagi ibu dan bayi selama
masa 40 hari masa nifas tanpa adanya ketentuan tarif
yang memberatkan pasiennya. Paraji dikenal memiliki
kemampuan supranatural yang mampu memberikan
kesembuhan dan kemujaraban tanpa penggunaan alat-alat
medis yang menakutkan bagi mereka. Praktik ritual paraji
sangat erat hubungannya dengan penggunaan jangjawokan.
Paraji menggunakan jangjawokan mulai dari pemeriksaan
kehamilan, proses persalinan hingga perawatan ibu dan bayi
pasca persalinan. Setiap fase pertolongan yang dilakukan
paraji pada pasiennya disertai jangjawokan sebagai
permohonan keselamatan pada setiap usaha penyembuhan
yang dilakukan. Kepercayaan ini dilandasi oleh tradisi yang
kuat yang telah diwariskan secara turun temurun. Praktik
paraji dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun
perempuan berumur di atas 40 tahun yang dianggap terampil
dan dipercaya secara turun temurun dalam memberikan
layanan pada masa kehamilan, proses persalinan dan
perawatan ibu dan bayi sesudah persalinan. Bahkan praktik
127
paraji persalinan tidak dapat dipisahkan dari istilah
jangjawokan.
Jangjawokan merupakan mantra yang ditujukan guna
berbagai keperluan meminta keselamatan dari gangguan
makhluk halus. Meskipun jangjawokan sering menyebut
Asma Allah dan Nabi Muhammad, namun bersamaan
dengan disebutkannya kepercayaan terhadap dewa-dewa,
makhluk-makhluk halus, arwah nenk moyang dan lain
sebagainya.
Tradisi paraji persalinan pada masyarakat
Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat merupakan
tradisi turun temurun yang diwariskan hingga saat ini.
Eksistensi paraji di desa -desa di Kecamatan
Pameungpeuk menandakan adanya pemertahanan praktik
paraji persalinan di daerah ini meskipun ada perubahan
pada peran paraji yang kini menjadi mendamping bidan
desa. Meskipun demikian masyarakat Pameungpeuk
masih percaya bahwa paraji adalah sosok yang mampu
membantu proses persalinan dengan kekuatan supranatural
dan jangjawokan (Mutiarani, 2020)
Ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring
yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga
akan mempersulit persalinan. Dan memang, selain ibunya
kurang gizi, berat badan bayi yang dilahirkan juga rendah.
Tentunya hal ini sangat mempengaruhi daya tahan dan
kesehatan si bayi. Selain itu, larangan untuk memakan buah-
buahan seperti pisang, nenas, ketimun dan lain-lain bagi
wanita hamil juga masih dianut oleh beberapakalangan
masyarakat terutama masyarakat di daerah pedesaan.
(Wibowo, 1993).
c. Budaya di masyarakat Betawi
berlaku pantangan makan ikan asin, ikan laut, udang
dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin
d. Budaya persalinan di jawa timur
Madura menjadi wilayah Propinsi Jawa Timur yang dibagi
menjadi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang,
Pamekasan, dan Sumenep. Pada masyarakat Madura,
128
ramuan jamu memiliki kekhasan lokal sehingga dipercaya
sebagai penyeimbang kesehatan badan dan batin.Ciri tradisi
jamu mampu mengangkat citra dan identitas masyarakat
Madura secara nasional dan internasional. Satu yang paling
menonjol dalam tradisi Madura adalah jamu pasca
melahirkan yang harus diminum setiap hari oleh ibu yang
baru melahirkan bayi selama 40 hari. Selain untuk
memulihkan kesehatan badan setelah melahirkan, jamu ini
diramu pula untuk tetap membuat ibu yang baru melahirkan
tersebut awet muda dan bergairah. Pada zaman dahulu
tumbuhan langka seperti bunga Padma ( Rafflesia
zollingeriana) banyak dipakai dalam ramuan jamu – jamu
pasca melahirkan. Kabupaten Banyuwangi memiliki suku
asli yaitu Suku Using dimana Suku osing mempunyai
budaya yang mempengaruhi pola kehidupan, aturan dan
aktivitas sehari-hari. Suku Using memiliki ragam budaya
yang terealisasi dalam aneka upacara adat atau ritual.
Hampir di semua kawasan suku Using masih ditemui
pengobatan dengan menerapkan pijat, mantra dan
pengobatan herbal menggunakan tanaman. Suku Using ini
memiliki berbagai kebudayaan, dari segi bahasa dan tradisi
pengobatannya yang terkenal. Pengobatannya dapat berupa
pengobatan gaib, doa, dan pengobatan herbal Bagian
tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, buah, getah, dan
sebagainya. Suku Using masih memanfaatkan tumbuhan
sebagai perawatan untuk ibu pasca melahirkan diantaranya
tumbuhan Dadap serep/dadapsrep (Erythrina Subumbrans)
ini yang diguanakn adalah bagian daunnya dengan cara
direbus lalu diminum, Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang
diguanakan bagian buahnya dengan cara diperas dan
diambil sarinya, Kencur/Kencor (Kaempferia galangal L)
bagian yang digunakan yaitu rimpangnya (Nurcahyati,
2018, p. 41). Ibu hamil di Banyuwangi rata-rata
menyebutkan bahwa mereka tidakdiperbolehkan
mengonsumsi buah nanas, buah durian, dan buah semangka
karenabuah-buahan tersebut mengandung unsur gas yang
bisa membahayakanjanin, serta dilarang mengonsumsi
129
buahsemangka karena mereka meyakini buah semangka
dapat membahayakan ibu ketika proses persalinan. (No
Name, 2021).
e. Budaya Kehamilan Dan Persalinan Pada Masyarakat Baduy,
Di Kabupaten Lebak
Masyarakat Baduy Luar bertempat tinggal di sekitar
pegunungan Kendeng, Desa Kanekes Kecamatan
Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kondisi
geografi menuju wilayah tempat tinggal masyarakat Baduy
Luar di Desa Kanekes di perbukitan yang penuh dengan
bebatuan dan terjal, menyebabkan akses ke fasilitas
pelayanan kesehatan menjadi sulit dijangkau. Desa Kanekes
merupakan tanah ulayat yang dilindungi haknya oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Ada dua sistem
pemerintahan yang berlaku di kalangan masyarakat Baduy
Luar, yaitu sistem nasional dan sistem adat yang mengikuti
kepercayaan masyarakat adat Baduy. Pemimpin Desa
Kanekes adalah kepala desa yang disebut sebagai “Jaro
Pamarentah”, sedangkan kepala adat dipimpin oleh seorang
yang disebut “Puun” (Makmur & Purwanto, 2002). Sebagian
besar masyarakat Baduy menggantungkan hidupnya pada
pertanian tradisional dengan melakukan kegiatan
perladangan yang berpindah-pindah. Selain menanam padi,
kehidupan mereka digunakan untuk bercocok tanam dan
berladang kopi, cengkeh, jahe merah dan hasil bumi lainnya
(Bintari, 2012; Senoaji, 2010) Masyarakat Baduy sangat
konsisten dalam konservasi alam terutama dalam menjaga
kebersihan aliran sungai dan mandiri dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari dan bergantung pada alam termasuk
dalam menjaga kesehatan. Apabila dilanda sakit, Masyarakat
Baduy tidak akan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
sepanjang masih bisa ditangani sendiri karena mereka
meyakini pengobatan dengan menggunakan tumbuh-
tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya atau melalui dukun
penyembuh baik medis maupun non-medis (Ipa et al., 2014).
Budaya persalinan di masyarakat Baduy yang saat ini
masih terjadi adalah persalinan yang dilakukan sendiri tanpa
130
bantuan penolong persalinan. Saat proses persalinan sudah
selesai, penolong persalinan baru diperlukan perannya untuk
memotong tali pusar, membersihkan bayi atau saat ibu
bersalin mengalami kesulitan dalam proses persalinan
(Lestari & Agustina, 2018).
Selain budaya persalinan sendiri, masyarakat Baduy
juga masih lebih mempercayai dukun paraji sebagai
penolong persalinannya. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar masyarakat Baduy masih percaya bahwa bayi sebelum
keluar dari perut ibu tidak diperbolehkan ditolong oleh
tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setelah bayi lahir,
biasanya suami atau keluarga lebih sering memanggil dukun
paraji sebagai penolong dalam membantu menyelesaikan
proses persalinan. Masyarakat Baduy menganggap dukun
paraji merupakan orang yang dipercaya dapat memberikan
doa-doa sehingga memberikan rasa nyaman pada ibu
(Batubara, 2012).
Di semua aspek kehidupan masyarakat Baduy
diselimuti oleh nilai budaya yang diwarisi dari leluhur secara
turun menurun. Masyarakat Baduy masih mengacu pada
pengobatan tradisional untuk merawat dan menjaga
kesehatan kehamilan dan persalinan, sehingga perlu
pendekatan dari tenaga kesehatan secara intens agar mereka
bersedia melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan
di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan
tersebut dilakukan sebagai kegiatan penelitian intervensi
dengan maksud agar para ibu hamil tidak lagi memeriksakan
kehamilan dan melahirkan dengan ditolong oleh dukun
paraji. Kesepakatan kemitraan bidan dan dukun paraji harus
secara nyata untuk memperjelas peran dan tanggungjawab
masing-masing. Pengetahuan perempuan Baduy tentang
kesehatan pada saat kehamilan dan persalinan masih rendah.
Tidak adanya pendidikan formal yang diperbolehkan pada
masyarakat Baduy menyebabkan pengetahuan yang dimiliki
perempuan Baduy juga rendah. Pengetahuan mengenai
kesehatan kehamilan dan persalinan merupakan pengetahuan
yang diperoleh secara turun temurun dan dipengaruhi oleh
131
aspek sosial budaya yang selalu dilakukan seperti para
leluhurnya. Budaya persalinan sendiri di Baduy sudah
terbiasa dilakukan oleh ibu hamil pada saat di huma. Proses
persalinan dilakukan sendiri dan pertolongan persalinan oleh
dukun paraji merupakan ritual yang harus ditaati dan dijalani
secara turun temurun sampai saat ini. Kepatuhan dan
ketaatan pada budaya berakibat pada keterbatasan
kesempatan pada ibu hamil Baduy untuk mendapat
pertolongan secara medis jika ada penyulit pada
persalinannya. Untuk mewujudkan keselarasan antara adat
istiadat masyarakat Baduy dengan kebijakan terutama yang
berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan modern guna
meningkatkan tingkat kesehatan seluruh masyarakat Baduy
dapat dilaksanakan dengan kerjasama yang sinergis antar
lintas program dan lintas sektor terkait dari SKPD di tingkat
pusat maupun daerah. (Kartika, V., et all, 2019)
f. Budaya persalinan di Bali
Masyarakat Bali Aga di desa Trunyan, Bali memandang
kelahiran sebagai hal yang wajar dan bersifat” publik”.
Kelahiran dianggap sebagai urusan laki-laki, karena dukun
bayi npria dan suami merupakan pemeran utama dari
penolong persalinan.Berbeda dengan masyarakat Krikati di
brazilia tengah, handai tolan termasuk anak-anak bisa
berkerumun di depan pintu yang dibiarkan terbuka, untuk
menyaksikan proses kelahiran tersebut di luar ruangan.
Meski demikian hanya dukun pria, suami, ibu kandung sang
wanita melahirkan, dan ank-anaknya yang lahir terdahulu
saja yang berada di ruangan, ditambah satu orang wanita
lainnya atau lebih, yang, mempunyai fungsi sebagai
pembantu persalinan apabila tenaganya diperlukan.
Para penolong dan cara-cara menolong persalinan
merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, karena diikat oleh
kesaman pemahaman mengenai sifat dari proses kelahiran
itu dengan pengaruhnya terhadap kondisi bayi dan ibunya.
Dalam proses persalinan di lingkungan di masyarakat Bali
Aga, wanita akan melahirkan duduk dengan posisi bersandar
pada dada balian tekuk (dukun beranak) di atas bangku.Sang
132
suami duduk tepat di hadapan isterinya, karena berfungsi
sebagai penerima bayi pada saat lahirnya. Diantara suami
isteri terdapat lubang dangkal yang diberi alas untuk
menampung plasenta, air tembuni, dan darah yang keluar
dari tubuh wanita yang melahirkan. Disisi wanita itu, berdiri
seorang gadis yang berfungsi untuk menarik rambutnya, agar
sang wanita yang melahirkan dapat tetap dalam posisi duduk
tegak.Tujuannya adalah untuk menjaga agar jiwanya dapat
tetap diam dalam tubuhnya dan tidak akan meninggalkannya.
Sang balian tekun akan mengurutnya untuk membetulkan
posisi bayi bila terasa sungsang dalam perut ibunya. Namun
bila proses kelahirran tampak berjalan normal, ia tak kan
berbuat apa-apa kecuali berfungsi sebagai tempat bersandar
sang wanita melahirkan dan memberikan ketenangan
psikologis.Seorang pelaku lain, balian usada hanya berperan
apabila terjadi proses persalinan yang sulit.Ia akan
membacakan mantera-mantera dan doa, serta memberikan
minuman air suci kepada si ibu, lalu menyemburnya dengan
ludah yang dicampur kunyahan daun sirih.
Para pelaku, khususnya sang gadis, senantiasa
mengusahakan agar si ibu tidak pingsan, karena hal itu
dianggap dapat menyebabkan kematiannya.Sementara itu,
ibu dari wanita yang melahirkan turut berada di ruangan
yang sama untuk memberikan ketenangan bathin bagi
putrinya yang sedang dalam proses melahirkan.Selama
proses pertolongan persalinan, diyakini oleh semua pelaku
bahwa selama ari-ari belum keluar, tali pusat tak boleh
dipotong karena kuatir akan tertarik kembali ke dalam rahim
sang ibu.
Dari segi kedokteran hal dianggap membahayakan
karena pedarahan pada ari-ari dapat menyebabkan
perdarahan pada bayi pula.Setelah ari-ari keluar, ayah sang
bayi memotong tali pusat anaknya dan para pelaku lain
mulai sibuk mengambil air hangat dan rempah-
rempah.Sementara itu tugas dukun bayi dan ayah sang bayi
masih berlanjut dengan upacara untuk merawat dan
membungkus plasenta, darah, air tembuni dan tali pusat sang
133
bayi, untuk digantungkan pad tempat khusus yang
disediakan untuk keperluan itu, di bagian selatan induk
trunyan. Uraian tersebut menunjukkan interaksi antara aspek
budaya dan aspek sosial yang terwujud dalam kegiatan
menolong persalinan yang dilakukan oleh para pelaku,
masing-masing dengan peran dan tugasnya selama proses
persalinan berlangsung, tidak saja bagi sang bayi, melainkan
juga bagi perawatan plasentanya. Kerjasama yang terpola itu
dilandasi oleh pengetahuan budaya yang sama mengenai
sifat-sifat dan fisiologi kelahiran.
g. Perilaku Budaya dalam Perawatan Persalinan suku Talang
Mamak Indragiri
1) Istilah-istilahn yang berhubungan dengan persalinan
suku Talang Mamakantara lain : kandung babai
(serotinus), air selusuh (air putih yang sudah dibaca doa
dan mantera tertentu untuk penawar agar persalinan
menjadi mudah), piying nutu (pecah air ketuban), kakak
bayi/ari (plasenta), bantal budak (kontraksi rahim)
2) Pengetahuan masyarakat tentang tanda persalinan
tergolong baik. Penegetahuan mengenai penolong
persalinan yang aman masyrakat Talang Mamak adalah
bidan kampong. Pengetahuan mengenai tempat
persalinan yang aman adalah dapur dan pengetahuan
tentang tanda bahaya persalinan cukup baik. Pengetahuan
ini mereka peroleh dari inner proses pada pengalaman
pribadi dan disekitarnya juga dari informasi keluarga dan
bidan desa.
3) Kepercayaan masyarakat suku Talang Mamakdalam
perawatan persalinan suku Talang Mamak adalah
pantang bagi seorang laki-laki termasuk suami melihat
dan mendampingi persalinan. Anjuran selama kehamilan
adalah ibu yang akan bersalin memakai gelang jeringau,
meminum air kapor dan sirih setelah ada tanda
persalinan, suami membuka semua yang tertutup,
menghidupkan dammar selama proses persalinan.
Pemotongan tali pusat harus dengan sembilu jika
dilanggar akan dikenai denda adat.
134
4) Pemeriksaan persalinan dan pengobatan selama
persalinan dilakukan oleh bidan kampong dengan
membuat ramuan rempah ((kencur, jahe, kunyit) dan air
yang sudah dibaca doa dan mantra. Pengobatan untuk
bayi baru lahir adalah membalur tali pusat yang sudah
dipotong sembilu dengan abu akar dan kunyit.
5) Nilai yang terkandung dalam perilaku perawatan
persalinan adalah anggapan bahwa persalinan adalah
sesuatu yang kotor sehingga pantang laki-laki melihat
perempuan yang sedang dalam keadaan kotor. Kotor
identik dengan dapur sehingga persalinan juga harus
berlangsung didapur. Kehamilan adalah hal alamiah
sedangkan persalinan dianggap lebih membahyakan
karena roh halus mendekati orang yang akan melahirkan
sehingga beresiko mengalami penyakit bahkan kemayian.
Sama halnya dengan kehamilan, persalinan juga urusan
sesame perempuan sehingga suami tidak ikut mengurus
keperluan selama kehamilan kecuali diminta bidan
kampong.
6) Perilaku budaya yang membahayakan kesehatan adalah
penolong persalinan adalah bidan kampong yang hanya
mengandalkan pengalaman dalam menolong persalinan,
tali pusat dipotong dengan sembilu sehingga beresiko
infeksi, persalinan didapur beresiko infeksi., tali pusat
yang dikompres dengan abu akar dan kunyit juga bersiko
infeksi. Perilaku yang tidak mendukung kesehatan adalah
tidak adanya pendampingan suami dalam proses
persalinan untuk psikis ibu menjadi lebih nyaman.
Perilaku yang menguntungkan kesehatan sebenarnya
adalah wanita Talang Mamak bebas memutuskan dengan
siapa dia akan bersalin namun karena aturan adat dan
keterbatasan pengetahuan sehingga keputusan ibu
menjadi tidak tepat. (no name, 2021)
h. Praktik Budaya Persalinan pada Suku Dayak Sanggau
Kepercayaaan masyarakat tentang pantang dan anjuran
pada saat persalinan tidak sebanyak seperti pada saat hamil.
Pantangan tentang makanan tidak ada, sedang pantang
135
perbuatan biasanya untuk pihak suami yaitu sama dengan
pantangan waktu hamil. Anjuran yang diyakini harus
dilakukan adalah membuka semua yang tersumbat atau
tertutup, misalnya membuka tutup tempayan mengosongkan
peluru dalam senapan, membuka bendungan air sawah.
Masyarakat Suku Dayak Sanggau mempunyai pandangan
tersendiri terhadap bahaya persalinan. Menurut sebagian
besar informan saat yang berbahaya adalah saat melahirkan
karena pada saat itu ibu bisa mengalami perdarahan,
persalinan macet, sedangkan pada saat hamil dan nifas tidak
berbahaya karena hamil dan nifas bersifat alami. Tetapi ada
sebagian kecil informan yang mengatakan bahwa hamil,
bersalin dan nifas berbahaya. Menurut mereka pada saat
hamil jika ibu tidak sehat nantinya susah melahirkan,
sedangkan pada saat melahirkan bahaya jika terjadi
perdarahan, partus macet.
Pada masa persalinan berlaku hanya anjuran perbuatan
pada suami. Anjuran tersebut bertujuan untuk memperlancar
proses persalinan. Pantangan pada masa persalinan secara
tidak berdampak langsung pada kesehatan ibu. Bidan
kampung akan berupaya mengetahui pelanggaran pantang
yang dilakukan oleh suami apakah selama kehamilan. Jika
hal tersebut terjadi, maka suami wajib menghilangkannya,
misalnya membongkar kembali tambalan pada perahu.
Kewajiban suami mendampingi istri saat melahirkan akan
meringankan beban psikis istri sehingga merasa lebih tenang.
(Suprabowo,E.2006)
i. Budaya persalinan di makassar
Sanro pamana‟ (dukun bayi) memaparkan bahwa salah
satu bentuk perawatan kehamilan ibu hamil yaitu dengan
mengadakan upacara adat tujuh bulanan (appassili). Tujuan
utama pelaksanaan acara appassili yaitu untuk
menghilangkan sial yang ada dalam diri ibu hamil dan
mendoakan agar ibu dan bayi selamat dalam proses
persalinan yang akan dijalaninya. (Pamita, D, 2021)
Di daerah pedesaan, kebanyakan ibu masih
mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan
136
yang biasanya dilakukan di rumah. Data Survei Kesehatan
Rumah Tangga tahun 1992 rnenunjukkan bahwa 65%
persalinan ditolong oleh dukun beranak. Beberapa penelitian
yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa masih
terdapat praktek-praktek persalinan oleh dukun yang
dapatmembahayakan si ibu. Penelitian Iskandar dkk (1996)
menunjukkan beberapa tindakan/praktek yang membawa
resiko infeksi seperti “ngolesi” (membasahi vagina dengan
rninyak kelapa untuk memperlancar persalinan),“kodok”
(memasukkan tangan ke dalam vagina dan uterus untuk
rnengeluarkan placenta) atau“nyanda” (setelah persalinan,
ibu duduk dengan posisi bersandar dan kaki diluruskan ke
depan selama berjam-jam yang dapat menyebabkan
perdarahan dan pembengkakan).
Pemilihan dukun beranak sebagai penolong persalinan
pada dasarnya disebabkan karena beberapa alasan antara lain
dikenal secara dekat, biaya murah, mengerti dan dapat
membantu dalam upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran
anak serta merawat ibu dan bayi sampai 40 hari. Disamping itu
juga masih adanya keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan
yang ada. Walaupun sudah banyak dukun beranak yang dilatih,
namun praktek-praktek tradisional tertentu rnasih dilakukan.
lnteraksi antara kondisi kesehatan ibu dengan kemampuan
penolong persalinan sangat menentukan hasil persalinan yaitu
kematian atau bertahan hidup. Secara medis penyebab klasik
kematian ibu akibat melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan
eklamsia (keracunan kehamilan). Kondisi-kondisi tersebut bila
tidak ditangani secara tepat dan profesional dapat berakibat fatal
bagi ibu dalam proses persalinan. Namun, kefatalan ini sering
terjadi tidak hanya karena penanganan yang kurang baik, kurang
tepat tetapi juga karena ada faktor keterlambatan pengambilan
keputusan dalam keluarga. Umumnya, terutama di daerah
pedesaan, keputusan terhadap perawatan medis apa yang akan
dipilih harus dengan persetujuan kerabat yang lebih tua; atau
keputusan berada di tangan suami yang sering kali menjadi
panik melihat keadaan krisis yang terjadi. Kepanikan dan
ketidaktahuan akan gejala-gejala tertentu saat persalinan dapat
137
menghambat tindakan yang seharusnya dilakukan dengan cepat.
Tidak jarang pula nasehat-nasehat yang diberikan oleh teman
atau tetangga mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadaan
ini seringkali pula diperberat oleh faktor geografis, dimana jarak
rumah si ibu dengan tempat pelayanan kesehatan cukup jauh,
tidak tersedianya transportasi, atau oleh faktor kendala ekonomi
dimana ada anggapan bahwa membawa si ibu ke rumah sakit
akan memakan biaya yang mahal.
Selain dari faktor keterlambatan dalam pengambilan
keputusan, faktor geografis dan kendala ekonomi, keterlambatan
mencari pertolongan disebabkan juga oleh adanya suatu
keyakinan dansikap pasrah dari masyarakat bahwa segala
sesuatu yang terjadi merupakan takdir yang tak dapat
dihindarkan.
faktor sosial budaya masyarakat dan tenaga kesehatan
yang berkompeten masih menjadi masalah terkait persalinan
aman. Masyarakat memiliki konsep dan nilai sendiri tentang
kehamilan, persalinan, penolong persalinan dan tentang nilai
anak dalam suatu keluarga. Kesimpulan: Persalinan aman dalam
konteks budaya masyarakat adalah bersalin sesuai kenyamanan
ibu dan keluarga, serta tidak melanggar nilai-nilai budaya
setempat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada tenaga
kesehatan dikarenakan faktor kurangnya hubungan interpersonal
antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, faktor senioritas
dan tabu memperlihatkan organ intim pada orang lain, serta
ketiadaan tenaga kesehatan di wilayah masyarakat karena akses
yang terpencil. Saran: Rekayasa sosial (social engineering)
dapat dilakukan dalam intervensi kesehatan ibu dan anak
berbasis budaya lokal, dengan melibatkan masyarakat dan
dukun bayi, serta perlu memberi pelatihan yang
berkesinambungan tentang pemahaman lintas budaya,
komunikasi budaya, dan perilaku kesehatan masyarakat kepada
tenaga kesehatan yang bertugas. (Lestari, W dan Agustina, ZA,
2018)
Citra tentang wanita, pandangan budaya mengenai organ
reproduksi dan penanganan plasenta. Dalam banyak kebudayaan
di berbagai penjuru dunia citra tentang wanita dan pandangan
138
budaya mengenai bentuk, sifat dan fungsi organ reproduksi
maupun pandangan budaya mengenai plasenta mendorong
berbagai perilaku tertentu dalam menghadapi kehamilan dan
kelahiran bayi. Citra tentang wanita : Ibu dan istri. Banyak suku
bangsa di dunia khususnya dunia ketiga beranggapan bahwa
kemampuan melahirkan bayi merupakan suatu tolok ukur bagi
seorang istri untuk menunjukkan keberhasilannya dalam tugas
budayanya untuk mempersembahkan keturunan bagi suaminya.
Di lingkungan yang mempunyai budaya seperti itu, mempunyai
anak segera setelah pernikahan merupakan tujuan utama dari
perkawinan. Di Bangladesh pandangan serupa juga ditemukan,
pengantin baru diharapkan untuk segera mempunyai anak untuk
membuktikan kesuburan mereka dan untuk mengesahkan
mereka dalam keluarga, karena status sebagai ibu lebih tinggi
dari status sebagai istri. Di samping itu status sebagai ibu
memberikan lebih banyak kebebasan untuk keluar rumah dan
mempraktekkan hak-hak mereka. Keinginan untuk segera
memiliki anak mendorong terwujudnya cara-cara budaya dalam
mengupayakan kelahiran anak. Lucille Newman menghimpun
sejumlah tulisan mengenai berbagai kebudayaan di Asia,
Amerika Tengah dan Selatan, yang berkenaan dengan
pengetahuan dan cara-cara budaya untuk mengatur kesuburan
dengan tujuan mendapatkan bayi, membatasi kelahiran bayi dan
berbagai pertimbangan tertentu. Di pihak lain citra tentang
wanita dalam kaitannya dengan tugas budaya mereka tidak
selalu mendorong disukainya kelahiran anak tambanhan, setelah
lahirnya beberapa anak. Tidak disukainya tambahan anak tidak
selalu disebabkan oleh faktor sosial ekonomi yang dari segi
tenaga dan biaya tidak menguntungkan untuk merawat seorang
bayi lagi. (Handayani, S. 2010)
139
BAB XIV
BUDAYA PERSALINAN DI LUAR NEGERI
Peninjauan budaya persalinan dari berbagai negara di dunia
akan menambah khasanah pengetahuan kita tentang perkembangan
tradisi wanita di dunia dalam melewati proses persalinannya.
Persalinan merupakan pengalaman persitiwa biologis yang dilalui
wanita dimana metodenya dapat dipengaruhi oleh adanya konstruksi
social yang dibentuk dengan adanya praktik budaya, persepsi
masyarakat dan kebijakan pemerintah setempat. (Kaphle, Hancock
and Newman, 2013)
Selain daripada itu, adanya gambaran budaya persalinan ini
dapat memberikan standar global dimana setiap negara dapat
mengidentifikasi kekurangan dari apa yang telah diimplementasikan
di wilayah mereka dan mengadaptasikan hal-hal baru dari negara lain
yang dapat mendukung suatu program pemerintahan dalam upaya
menurunkan angka kematian ibu khusunya pada saat persalinan.
Berikut Gambaran Budaya Persalinan dari Berbagai Negara di
belahan dunia:
1. Jepang
Kemajuan bidang teknologi di negara Jepang turut membawa
perubahan pada metode persalinan. Persalinan yang dahulu lebih
bayak dilakukan di rumah, kini bergeser ke pusat pelayanan
kesehatan seperti Rumah sakit, klinik dan Praktik Mandiri Bidan.
Rendahnya angka kelahiran di Jepang menjadi topik penting
bagi pembuat kebijakan di negara tersebut karena terkait dengan
pengurangan jumlah populasi. Jika dibandingkan dengan negara
maju lainnya, biaya proses persalinan di Jepang tergolong cukup
mahal. Bukan hanya biaya persalinan yang menjadi pemicu
rendahnya kelahiran di Jepang namun juga berkurangnya
pendapatan, kemunduran karir bahkan risiko kehilangan pekerjaan
bagi wanita yang aktif bekerja. (Nagase and Brinton, 2017)(Nagase
and Brinton, 2017)
Selain itu, Wanita hamil di Jepang juga akan menghadapi tantangan
baru pada saat akan menjalani proses persalinan yakni kurangnya
ketersediaan obat analgetik. Padahal data menunjukkan bahwa
Jepang merupakan salah satu negara paling aman untuk wanita
140
melahirkan. Tercatat pada tahun 2017 kematian bayi adalah 1,9 per
1000 kelahiran hidup dan kematian bayi baru lahir adalah o,9 per
1000 kelahiran hidup.(‘Health indicators’, 2017)
Jepang kekurangan Ahli Kandungan
Unit pelayanan kesehatan di Jepang mengalami kekurangan
tenaga kesehatan wanita yang berprofesi sebagai spesisalis. Jepang
memiliki jumlah dokter wanita yang sangat sedikit jika
dibandingkan dengan negara industri lainnya. Hal ini kemudian
membuat Organisasi Obstetri dan Ginekologi Jepang melakukan
upaya penerimaan tenaga kesehatan dengan spesifikasi ahli
kandungan wanita dan berusaha untuk mempertahankan keberadaan
ahli kandungan untuk melakukan praktik di berbagai fasilitas
kesehatan. (Maeda et al., 2019)
Beberapa tahun lalu, penurunan jumlah klinik bersalin di Jepang
menjadi perbincangan nasional yang serius karena ditemukan
banyak ibu mengalami kesulitan menemukan tempat yang aman
dan nyaman untuk melakukan persalinan. (Koike et al., 2016)
Di Jepang, unit pelayanan kesehatan yang mempunyai 20 buah
atau lebih tempat tidur pasien disebut rumah sakit sedangkan
fasilitas kesehatan dengan tempat tidur kurang dari 20 buah maka
disebut sebagai Klinik. Adapun pelayanan pemeriksaan kehamilan
dan persalinan hanya tersedia di rumah sakit maupun klinik dimana
dokter kandungan dan bidan selalu siaga. Pemerintah pusat di
negara ini turut menentukan jenis fasilitas kesehatan yang
disediakan di rumah sakit bersalin sehingga beberapa rumah
bersalin hanya melayani pemeriksaan kehamilan. Kebanyakan
wanita Jepang memilih melewati proses persalinannya di rumah
sakit ataupun klinik dan hampir 50% wanita Jepang melahirkan di
tempat Praktik Mandiri yang umumnya dikelola oleh dokter
kandungan berusia 50 sampai 60 tahun. (Gynecologists and
Gynecologists, 2018). Tenaga kesehatan di klinik yang memiliki
beban kerja lebih besar dan usia pengelola klinik yang cukup tua
menyebabkan penutupan beberapa klinik sehingga wanita Jepang
yang akan melahirkan harus mencari rumah sakit.(Koike et al.,
2016). Hal teersebut berdampak pada kondisi dimana Ibu hamil di
Jepang harus menempuh perjalanan lebih dari 100km agar dapat
141
melakukan pemeriksaan kehamilan dan perawatan medis selama
proses persalinan.(Maeda et al., 2019)
Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh
pemerintah Jepang adalah dengan mengalihkan beban kerja dokter
dan bidan kepada tenaga kesehata lainnya. Wewenang Bidan di
Jepang dalam memberikan asuhan secara historis sudah dibatasi
sejak dahulu. Misalnya bidan tidak boleh melakukan episiotomy,
melakukan heacting perineum, ataupun meresepkan obat. Bidan
hanya boleh menangani wanita hamil normal dan beresiko rendah
sehingga persalinan yang dilakukan di rumah atau Praktik Mandiri
Bidan menjadi berkurang drastis. Labour and welfare.(‘Vital
statistics of population’, no date)
Pada tahun 2016 rata-rata usia ibu hamil di Jepang dengan
kelahiran anak pertama adalah 30 tahun. Usia ini mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 1996 yakni sekitar 27
tahun. Meskipun Jepang termasuk negara maju, wanita hamil di
negara ini juga tidak luput dari komplikasi penyakit seperti
preeklampsia dan diabetes melitus gestasional. Jepang sangat
membutuhkan dokter ahli kandungan untuk mendukung penyediaan
layanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif dan optimal.
(Maeda et al., 2019)
Pengobatan Analgetik
Salah satu kecemasan wanita saat menjalani proses persalinan
adalah rasa sakit terllebih pada ibu yang melahirkan anak pertama.
Para wanita di Jepang tahu bahwa obat analgetik tidak dapat
diperoleh dengan gampang. Analgetik atau penghilang rasa sakit
yang popular adalah anestesi epidural. Permintaan obat analgetik ini
cukup banyak dilakukan oleh ibu yang akan melalui proses
persalinan, namun sangat sedikit unit pelayanan kesehatan yang
menyediakannya.
Sampai pada abad pertengahan ke-18, nyeri persalinan dianggap
sebagai bagian dari proses alamiah yang harus dilalui oleh seorang
wanita. Namun pada abad ke-19 obat anakegetik mulai
diperkenalkan kepada masyarakat dan cukup diminati. Lalu sekitar
tahun 1940, anestesi epidural mulai digunakan secara luas karena
keefektifitasannya.(Skowronski, 2015)
142
Inovasi masyarakat Jepang pada bidang kesehatan juga selalu
dikembangkan. Adanya keterbatsaan bidan melakukan tindakan dan
minimnya persediaan obat analgetik mendorong upaya non
farmakologis dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan
masyarakat akan penghilang rasa sakit saat persalinan. Upaya non
farmakologis tersebut dilakukan melalui pendekatan piskologi,
emosional dan spiritual seperti latihan pernapasan, pijat, akupresur,
yoga, dan hidroterapi. Dengan menggunakan pendekatan non-
farmakologis ini, wanita berusaha beradaptasi mengatasi nyeri
persalinan mereka dan mampu mengontrol diri terhadap nyeri
persalinan. Asuransi kesehatan di Jepang menanggung pengobatan
tradisional dan farmakologis selama perawatan persalinan sehingga
para dokter di Jepang pun terlatih dalam pemberian kedua jenis
pengobatan tersebut.
Jepang berhasil mengembangkan pengobatan tradisional yang
disebut dengan Kampo. Kampo adalah hasil olahan herbal yang
dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi ibu pada masa
kehamilan, persalinan dan nifas. Kampo kemudian dintegrasikan
dengan pengobatan farmaklogis di klinik maupun rumah sakit
menyebabkan kampo menjadi pilihan banyak wanita karena minim
efek samping apabila dibandingkan dengan obat farmakologis.
(Gynecologists and Gynecologists, 2018)
Kuatnya kebudayaan masyarakat Jepang turut membawa implikasi
pada kepercayaan wanita hamil Jeppng terhadap nyeri persalinan.
Mereka memilih untuk tidak menggunakan analgesia karena alasan
berikut:
a. Mereka meyakini bahwa nyeri persalinan merupakan hal
fisiologis yang harus dilalui seorang ibu. Norma dan stigma
masyarakat terdahulu mendukung kelahiran bayi secara normal
membuat wanita hingga dokter kandungan tidak mengharapkan
intervensi medis selama persalinan. Selain itu, generasi tua
wanita Jepang meyakini bahwa proses persalinan dengan nyeri
yang dirasakan merupakan proses bonding untuk memperkuat
ikatan batin antara ibu dan anak.
b. Pemberian obat analgesia diyakini dapat menyebabkan bayi
baru lahir menjadi lemah dan tidak sehat
143
Rendahnya penggunaan analgesia persalinan tidak hanya
dipengaruhi oleh budaya persalinan Jepang namun juga karena
factor sedikitnya tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter
ahli anestesi. (Behruzi et al., 2010)
Pendekatan dengan melakukan pendelegasian tindakan anestesi ke
petugas kesehatan lain seperti bidan, perawat dan dokter kandungan
tidak bisa diterapkan karena aturan yang membatasi wewenang
mereka dalam berpraktik dan tidak adanya petugas yang
mempunyai keterampilan dan kualifikasi untuk pemberian anestesi.
Kurangnya ahli anestesi dan ketiadaan pengalihan tugas tersebut
alhirnya menyebabkan sedikitnya pelayanan persalinan yang aman
dan bebas rasa sakit di Jepang.(Mavalankar and Sriram, 2009)
2. Ethiopia
Kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan menyumbang sekitar
80% angka kematian ibu dan anak secara global. Setiap 1 dari 37
perempuan di Afrika Sub-Sahara menghadapi risiko sepanjang
hidup terjadi kematian saat kehamilan atau kelahiran. Jika
dibandingkan, risiko sepanjang hidup yang sama yang dihadapi
perempuan di Eropa adalah 1 dalam 6500 orang.
Di Ethiopia kematian ibu masih menjadi tantangan besar bagi
negara berkembang termasuk Ethiopia dimana rasio kematian ibu
dilaporkan sebanyak 412 per 100000 kelahiran hidup di tahun 2015.
Menurut survey nasional petugas di fasilitas kesehatan Ethiopia
kurang bersikap sopan dan mengahargai hak pasien. Hal tersebut
mengindikasikan pelayanan kesehatan maternal yang buruk di
negara ini. Selain dari itu, sikap petugas yang tidak ramah, tidak
memberikan kesempatan kepada keluarga ibu untuk mendampingi
saat persalinan, hak pasien diabaikan serta fasilitas kesehatan yang
tidak memadai. (Asefa et al., 2018)
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Ethiopia
mengeluarkan kebijakan yang mendorong wanita melahirkan di unit
pelayanan kesehatan diamana mereka akan memperoleh pelayanan
kegawatdaruratan. Terlepas dari kebijakan tersebut, Ethiopia saat
ini merupakan negara dengan fasilitas persalinan yang buruk
diantara negara Sub Sahara Afrika lainnya. Sebesar 28% persalinan
ditolong oleh tenaga professional yang tersebar di perkotaan dan
pedesaan. sejumlah penelitian melaporkan bahwa alasan wanita
144
Ethiopia tidak menggunakan jasa tenaga professional saat bersalin
adalah jarak unit pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, kendala
biaya, tingkat Pendidikan wanita serta pengaruh kebidayaan yang
menjadi faktor utama ketidak hadiran tenaga terlatih dalam proses
persalinan. (Fikre and Demissie, 2012)
Di Ethiopia, kepercayaan yang bekembang ditengah masyarakat
adalah pelayanan medis tidak dibutuhkan saat persalinan sehingga
tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tidak
menjadi pilihan. Kepercayaan ini dari turun temurun diyakini dan
diperkuat eksistensinya oleh anggota keluarga yang lebih tua.
Sebuah penelitian memberikan ilustrasi kompleksnya persepsi
wanita mengenai kehadiran seorang tenaga terampil untuk
membantu proses persalinan. Wanita dua generasi saat itu
mengakui bahwa pelayanan medis diperlukan hanya untuk beberapa
kasus persalinan yang tidak bisa ditangani dirumah tetapi merasa
lebih nyaman jika mereka dibiarkan melahirkan di rumah mereka.
Jarak fasilitas kesehatan tidak menjadi halangan bagi mereka.
Namun ketakutan terhadap petugas kesehatan justru menjadi
penyebab utama mereka tidak mendatangi klinik ataupun rumah
sakit untuk melakukan proses persalinan.
Persepsi orangtua tentang riwayat kesehatan reproduksi mereka
setelah melahirkan d rumah dan pandangan terhadap pelayanan
medis mempengaruhi keputusan wanita muda yang tinggal di
perkotaan untuk lebih cenderung memilih untuk melahirkan di
fasilitas kesehatan. Meskipun pengaruh budaya melahirkan di
rumah masih ada namun mereka akhirnya memilih melewati proses
persalinan mereka di fasilitas kesehatan sehingga jarak ke fasilitas
kesehatan tidak terlalu menjadi hambatan.
Pemerintah Ethiopia terus melakukan pembaruan terhadap
kebijakan yang dikeluarkan terkait proses persalinan yang aman.
Adanya kebudayaan melahirkan di rumah sampai saat ini masih
ditoleransi. Salah satu upaya pemerintah Ethiopia untuk
mengimbangi hal tersebut adalah dengan menugaskan petugas
kesehatan mendatangi rumah ibu yang akan melahirkan di daerah
pedesaan. Kebanyakan wanita yang tinggal di desa sebenarnya
berencana melahirkan di klinik. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan minat masyarakat pedesaan untuk melahirkan di
145
klinik atau rumah sakit maka pemerintah Ethiopia berupaya
melengkapi instrument pendukung persalinan yang sehat dan aman.
Dengan upaya ini diharapkan agar keengganan untuk
menggunakan jasa tenaga professional di kalangan wanita kelas
menengah kebawah baik di desa ataupun kota bisa diminimalisir.
Sehingga norma budaya bersalin di rumah bisa bergeser kepada
norma baru yakni keyakinan dan kemauan untuk bersalin di unit
pelayanan kesehatan dengan didampingi tenaga kesehatan yang
terampil.(Weis, 2017)
3. Laos
Pada tahun 2015 rasio kematian maternal di Laos sebesar
185/100000 kelahiran hidup dengan target nasional pada tahun
2020 mengalami penurunan sebesar 166/100000 kelahiran
hidup.(UNICEF:, 2008)
Posisi ibu saat proses persalinan adalah factor penting yang
menjadi pertimbangan wanita di Laos sehingga mereka lebih suka
melahirkan di rumah. Di rumah wanita bisa melahirkan dengan
posisi duduk dengan lutut ke mendekati dada, lalu memegang tali
yang tergantung di langit-langit sementara dukun bersalin
meletakkan tangan sambil memberi tekanan pada perut wanita saat
melahirkan. Posisi duduk seperti ini lebih nyaman oleh kebanyakan
wanita Laos dibandingkan dengan posisi tengkurap yang disarankan
oleh petugas di klinik ataupun rumah sakit.
Melahirkan di rumah juga memberi kesempatan pada wanita
untuk mandi air hangat dan berbaring diatas bara api untuk
menghangatkan tubuh selama masa postpartum. Nilai-nilai
tradisional yang diterapkan di rumah dianggap dapat membantu
proses penyembuhan tubuh setelah persalinan.
Wanita Laos beranggapan bahwa jika orangtua mereka berhasil
melahirkan di rumah dengan mudah dan nyaman lalu kenapa
mereka harus mencari cara lain untuk melakukannya. Apalagi
ketika ada wanita yang tiba-tiba ingin melahirkan saat malam hari
maka keputusan untuk melahirkan di klinik atau rumah sait bukan
merupakan pilihan yang tepat.
Ada beberapa factor yang kemudian menjadi aspek yang
dipertimbangkan oleh wanita Laos untuk melakukan proses
persalinannya di rumah daripada ke unit pelayanan kesehatan.
146
Diantaranya: Factor ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan
keluarga yang rendah sedangkan biaya pengobatan tergolong masih
cukup mahal bagi warga negara Laos
Factor akses ke unit pelayanan kesehatan berhubungan dengan
kondisi jalanan yang jelek dan biaya transport yang mahal dari desa
menuju kota dimana fasilitas kesehatan berada
Factor kualitas pelayanan ini berkaitan dengan sikap petugas,
ketersediaan obat-obatan dan tindakan petugas saat membantu
proses persalinan. Ketidaknyamanan yang dirasakan wanita Laos
terhadap tindakan petugas saat di rumah sakit seperti adanya
tindakan episiotomy, kehadiran petugas laki-laki serta mengekspos
genitalia adalah aspek yang sering dikeluhkan karena merasa
privasi mereka diabaikan.(Sychareun et al., 2012)
4. Turki
Turki merupakan salah satu negara berkembang dimana budaya
masyarakat juga turut mengikuti budaya dunia saat ini termasuk
dalam dunia kesehatan wanita yang terkait dengan peran wanita di
tengah masyarakat. Di negara ini peran dan tanggung jawab
tambahan seorang wanita adalah melahirkan keturunan. Dengan
adanya system reproduksi yang dianugrahkan oleh Tuhan ini wanita
bertanggujawab pada negara untuk melahirkan calon generasi
penerus bangsa yang berkualitas. Warga negara ini mempercayai
bahwa system reproduksi wanita meliputi keperawanan dan
kesucian yang menandakan kehormatan keluarga mereka.
(Cindoğlu et al., 2008)
Memasuki abad ke-20, kehidupan reproduksi wanita di Turki
mengalami peningkatan medikalisasi dimana pertolongan
persalinan secara tradisional digantikan dengan persalinan medis
dan persalinan yang dahulu dilakukan di rumah beralih ke
persalinan di rumah sakit. Namun ternyata Salah satu alasan
terjadinya medikalisasi fase kehamilan dan persalinan adalah
karena adanya stigma yang dibangun oleh para dokter di negara ini
bahwa kehamilan dan persalinan merupakan sesuatu yang bersesiko
bahkan cenderung mengarah ke patologis. Wanita yang memilih
metode section cesarea dan bersalin di rumah sakit lebih
dikarenakan kekhawatiran mereka akan persalinan yang aman
147
untuk diri mereka. Sehingga para wanita bersikap pasif dan
menyerahkan sepenuhnya keselamatan persalinan mereka pada
dokter. Selain itu, wanita juga merasa tertekan oleh rasa takut akan
disalahkan jika terjadi hal yang tidak diigingkan terhadap
kehamilan dan persalinannya karena tidak mengikuti saran dokter.
(Riessman, 1992)
Alasan lainnya adalah bagi para wanita yang tinggal dengan
keluarga besar memilih untuk melahirkan di rumah sakit karena
mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat setelah melahirkan.
Karena jika mereka melahirkan di rumah, mereka dituntut untuk
bisa segera bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Bagi wanita berpendidikan di Turki, menjalani proses persalinan
di rumah sakit justru menyediakan mekanisme persalinan yang
lebih aman karena mereka bisa melakukan konsultasi dan negosiasi
jika terjadi kesalahan dalam proses persalinan mereka. Oleh
karenanya section cesarea manjadi symbol modernisasi dan
kecanggihan teknologi di negara tersebut. Menurut survey
Demografi dan Kesehatan Turki ada beberapa hal terkait
peningkatan permintaan section cesarea dari tahun 1993 hingga
2013 yakni sebesar 14,3% meningkat menjadi 51,9% . Hal tersebut
disebabkan karena:
1. Section cesarea banyak dipilih oleh wanita yang memiliki
asuransi perlindungan kesehatan (Santas and Santas, 2018)
.Wanita yang memiliki asuransi tentunya lenih siap untuk
menghadapi proses persalinan kapanpun tanpa harus
mengeluarkan uang cash.
2. Sectio cesarea dilakukan paling banyak pada kelahiran anak
pertama
Ketakutan melewati proses persalinan menjadi hal yang masih
dirasakan oleh ibu muda di Turki sehingga lebih memilih
persalinan dengan metode operasi daripada persalinan
pervaginam.
3. Keputusan untuk menjalani persalinan di rumah bersalin swasta.
Sehingga pihak swasta lebih potensial menghasilkan pendapatan
yang lebih besar dibanding rumah bersalin milik pemerintah.
4. Wanita yang tinggal di daerah perkotaan
5. Wanita yang memiliki kekayaan
148
DAFTAR PUSTAKA
Abraham, J.H., 1973. The Study Of Human Society, London, Tehe
English University Press.
Abraham, Charles dan Eamon Shanley.1997, “Psikologi Sosial Untuk
Perawat”, Jakarta, EGG.
Achmadi, Umar Fahmi.2005.”Manajemen Penyakit Berbasis
Wilayah”, Jakarta, Gramedia Kompas
Alamsyah, M. 1987. “Budi Nurani Filsafat Berfikir”, Jakarta, Titik
Terang.
Alisyahbana, Sutan Takdir. 1982. “Sejarah kebudayaan Indonesia di
lihat Dari Segi nilai-Nilai”, Jakarta , Dian Rakyat.
Asefa, A. et al. (2018) ‘Service providers’ experiences of
disrespectful and abusive behavior towards women during
facility based childbirth in Addis Ababa, Ethiopia’,
Reproductive health, 15(1), p. 4. doi: 10.1186/s12978-017-
0449-4.
Batubara, S. T. (2012). Aspek Sosial Budaya yang Mempengaruhi
Kematian Ibu Akibat Perdarahan pada Masa Kehamilan dan
Kelahiran Tahun 2012: Studi Pengalaman Perempuan Baduy.
Universitas Indonesia
Bennett, V. Ruth, BROWN, Linda K. (1996). Myles textbook for
midwives. Churchill Livingstone.
Bintari, R. (2012). Sejarah Perkembangan Sosial Ekonomi
Masyarakat Baduy Pasca Terbentuknya Propinsi Banten Tahun
2000. Journal of Indonesian History, 1(1), 18–22.
Behruzi, R. et al. (2010) ‘Facilitators and barriers in the humanization
of childbirth practice in Japan’, BMC pregnancy and
childbirth, 10(1), pp. 1–18.
149
Becker, Marshall H. dan Lois A.Maiman, 1995, “Model-Model
Perilaku Kesehatan” Dalam Muzaham Fauzi 1995.
Memperkenalkan Sosiolodi Kesehatan, Jakarta : UI Pres.
Cindoğlu, D. et al. (2008) ‘The family in Turkey: The battleground of
the modern and the traditional’, in Families in a global context.
Routledge, pp. 235–263.
Coulson, Margaret A.,1984.,Approaching Sosiology.Boston:
Routledge & Kegan Paul.
Departemen Pendidikan Nasional (2000). Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), Edisi ke-3. Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 169
Faisal, Sanapiah dan Mappiare. Tanpa tahun, “Dimensi-Dimensi
Psikologi, Surabaya, Usaha Nasional.
Fikre, A. A. and Demissie, M. (2012) ‘Prevalence of institutional
delivery and associated factors in Dodota Woreda (district),
Oromia regional state, Ethiopia’, Reproductive health, 9(1), pp.
1–6
Gunawan, AH. (2000) Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi
tentang Pelbagai Problem Pendidikan. Rineka Cipta, Jakarta.
Hal. 16
Gynecologists, J. A. of O. and and Gynecologists (2018) ‘No Title’.
Available at:
Handayani, S. (2010). Aspek Sosial Budaya Pada Kehamilan,
Persalinan Dan Nifas Di Indonesia. Infokes, Vol. 1 No. 2
Harsojo, 1982., “Pengantar Antropologi”, Binacipta
Handayani, S. (2010). Aspek Sosial Budaya Pada Kehamilan,
Persalinan Dan Nifas Di Indonesia. Infokes, Vol. 1 No. 2
Health indicators’ (2017). Available at:
https://data.worldbank.org/topic/health.
150
http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Mat%20Syuroh%20SOSI
AL%20&%2
0KEBUDAYAAN%20_Revisi%20terbaru_%20mda.pdf
https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/98/81
http://www.jaog.or.jp/wp/wp-
content/uploads/2017/08/botai_2016_2.pdf ) .
Ipa, M., Prasetyo, J. A., Arifi n, J., & Kasnodihardjo. (2014). Balutan
Pikukuh Persalinan Baduy. (Kasnodihardjo, Ed.) (1st ed.).
Surabaya: Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kaphle, S., Hancock, H. and Newman, L. A. (2013) ‘Childbirth
traditions and cultural perceptions of safety in nepal: Critical
spaces to ensure the survival of mothers and newborns in remote
mountain villages’, Midwifery, 29(10), pp. 1173–1181. doi:
10.1016/j.midw.2013.06.002.
Kartika, V., Agustiya,RI & Kusnali, A. (2019). Budaya Kehamilan
Dan Persalinan Pada Masyarakat Baduy, Di Kabupaten Lebak.
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 22 No. 3 Juli 2019:
192–199
Ki Hajar, Dewantara. (1994). Kebudayaan Penerbit Majelis Luhur
Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.
Koike, S. et al. (2016) ‘The effect of concentrating obstetrics services
in fewer hospitals on patient access: a simulation’, International
journal of health geographics, 15(1), pp. 1–10.
Koentjaraningrat, 1984., “Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan”,
Jakarta, Gramedia
Koentjaraningrat, 2000. “Pengantar Ilmu Antropologi”, Jakarta,
Rineka Cipta
Kurniarum A.(2016). Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru
Lahir. Kemenkesri, BPSDM. Jakarta.
151
Lestari, W., & Agustina, Z. A. (2018). Meta Etnografi Budaya
Persalinan Di Indonesia. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 20(1).
Maeda, Y. et al. (2019) ‘Factors affecting the provision of analgesia
during childbirth, Japan’, Bulletin of the World Health
Organization, 97(9), p. 631.
Makmur, A., & Purwanto, A. (2002). Pamarentahan Baduy di Desa
Kanekes: Perspektif Kekerabatan. Jurnal Sosiohumaniora, 4(2),
104–115.
Mavalankar, D. and Sriram, V. (2009) ‘Provision of anaesthesia
services for emergency obstetric care through task shifting in
South Asia’, Reproductive health matters, 17(33), pp. 21–31.
Mutiarani (2020). Kepercayaan Dan Tradisi Paraji Pada Persalinan
Masyarakat Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat. Jember
University Press E Prosiding. Vol.1, No. 1, Oktober 2020
Moore.KL.(2001).Asuhan Persalinan Konsep Persalinan Secara
Komprehensif . EGC. Jakarta
Mochtar, R.(2012) Buku Sinopsis Obstetri Fisiologi dan Patologi
edisi 3 jilid1 2012 EGC.Jakarta
Nagase, N. and Brinton, M. C. (2017) ‘The gender division of labor
and second births: Labor market institutions and fertility in
Japan’, Demographic Research, 36(1), pp. 339–370. doi:
10.4054/DemRes.2017.36.11.
No name. (2021) Budaya Persalinan Suku Talak. available
from;http://scholar.unand.ac.id/ 14524 /3/BAB%20VII.pdf.
diakses tanggal 12/12/2021.
No Name,(2021). Budaya persalinan.
http://repository.unmuhjember.ac.id diakses tanggal 12/12-2021
152
Obstetrics and Gynaecology, 38(5), pp. 658–662. doi:
10.1080/01443615.2017.1400525.
Pamita, D, 2021Uniknya Kepercayaan Perawatan Ibu Hamil di
Makassar https:// chatnews.id/read/uniknya-kepercayaan-
perawatan-ibu-hamil-di-makassar
Perursen, CAV.(1998). Strategi Kebudayaan. Kanisisus. Yogyakarta.
Hal 11
Poedjawijatma,L. 1986. Etika, Filsafat Tingkah laku,Jakarta, B.Aksar
Prawiroharjo. S. (2002). Ilmu kebidanan. Yayasan sarwono
rawirohardjo. Jakarta
Reinterprestasi Dari Program Pembinaan Kepemberdayaan Dalam
Pelestarian Ekologi Suku Terasing Di Indonesia (Studi Kasus
Suku Kubu di Sumatera), Yogyakarta.
Riessman, C. K. (1992) Women and medicalization: A new
perspective. na.
RSUP Dr Kariadi.(2021). Pengaruh Budaya Pada Persalinan Ibu.
Available from; https://www.rskariadi.co.id/news/97/Pengaruh-
Budaya-Pada-Persalinan-Ibu/Artikel. Diakses tanggal
12/12/2021.
Santas, G. and Santas, F. (2018) ‘Trends of caesarean section rates in
Turkey’, Journal of
Saparinah Sadli, 1987. “Metode-Metose Penelitian Masyarakat”
Jakarta, P.T. Gramedia.
Senoaji, G. (2010). Masyarakat Baduy, Hutan dan Lingkungan. Jurnal
Manusia Dan Lingkungan, 17(2), 113–123.
Soekanto, S. (2009). Sosiologi suatu Pengantar. Rajawali Pers,
Jakarta. Hal: 150-151
Soemardjan, S dan Soemardi,S. (1964). Setangkai Bunga Sosiologi.
Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. Hal.
115
153
Soejono Soekanto, 1990, “Pengantar Sosiologi”, Jakarta, Rajawali
Pers.
Sztompka,P.(2007). Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada Media
Grup. Jakarta. Hal 30.
Suprabowo, E. (2006). Praktik Budaya dalam Kehamilan, Persalinan
dan Nifas pada Suku Dayak Sanggau, jurnal Kesehatan
Masyarakat Nasional Vol. 1, No. 3, Desember 2006
Sudarmo Momon, 2009.”Sosiologi Kesehatan”, Jakarta, Salemba
Medika.
Skowronski, G. A. (2015) ‘Pain relief in childbirth: changing
historical and feminist perspectives’, Anaesthesia and intensive
care, 43(1_suppl), pp. 25–28.
Supartono W., 1995. “Ilmu Dudaya dasar “, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Sychareun, V. et al. (2012) ‘Reasons rural Laotians choose home
deliveries over delivery at health facilities: a qualitative study’,
BMC pregnancy and childbirth, 12(1), pp. 1–10.
Syuroh,M (2011) Sosial dan Kebudayaan Kelompok Minoritas di
Indonesia (Studi Kasus Kelompok “Batin Sembilan” di Provinsi
Jambi) vol 24:17-23. Syuroh,M (2010)
Tim PKRS Kariadi, (2021). Budaya-budaya persalinan.
https://www.rskariadi.co.id/ news/97/Pengaruh-Budaya-Pada-
Persalinan-Ibu/Artikel
UNICEF: (2008) ‘Progress for Children 2008. A Report Card on
Maternal Mortality’. Available at:
www.unicef.org/childsurvival.‘Vital statistics of population’ (no
date), 2017. Available at:
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei17/inde
x.html.
154
Weis, J. (2017) ‘Longitudinal Trends in Childbirth Practices in
Ethiopia’, Maternal and Child Health Journal, 21(7), pp. 1531–
1536. doi: 10.1007/s10995-017-2279-y.
155
SOAL LATIHAN
Pertanyaan I
1. Jelaskan Pengertian Antropologi ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Terangkan Ruang Lingkup Kajian Antropologi Sosiologi ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Bagaimana Hubungan Antropologi Dan Sosiologi ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Sebutkan Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Berikan suatu contoh tentang “Suku Terasing”di Indonesia ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 1
156
Pertanyaan 2
1. Jelaskan Pengertian Kebudayaan ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Sebutkan dan Jelaskan wujud kebudayaan ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Sebutkan Unsur-Unsur Kebudayaan ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Apa yang dimaksud kepribadian dan bagaimana susunan
kepribadian itul ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Sebutkan unsur-unsur pembentukan kepribadian ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 2
157
Pertanyaan 3
1. Jelaskan Pengertian struktur sosial ?
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
2. Sebutkan unsur-unsur struktur sosial ?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Apa fungsi struktur sosial itu ?
...........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
4. Jelaskan fase konsep tentang “diri sendiri”?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
5. Sebutkan ciri-ciri masyarakat ?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Catatan baca buku bab 3
158
Pertanyaan 4
1. Sebutkan faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. Jelaskan faktor pendorongperubahan sosian dan kebudayaan
dan berikan contoh ?
......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Jelaskan faktor pendorongperubahan sosian dan kebudayaan
dan berikan contoh?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4. Bagaiman dampak Perubahan sosial dan kebudayaan terhadap
masyarakat?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
catatan baca Bab 4
159
Pertanyaan 5
1. Jelaskan pengertian Lembaga Sosial?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Jelaskan proses pertumbuhan Lembaga Sosial?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
3. Kapan suatu norma dikatakan melembaga?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Apa fungsi Lembaga Sosial?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Sebutkan ciri-ciri dan tipe-tipe Lembga Kemasyarakatan?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 5
160
Pertanyaan 6
1. Jelaskan pengertian Proses Sosial, Interaksi Sosial ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Sebutkan Syarat-syarat Interaksi Sosial?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Sebutkan bentuk-bentuk Interaksi Sosial ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 6
161
Pertanyaan 7
1. Apa ang dimaksud: Sosiologi Kedokteran, Sosiologi Kesehatan
?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Jelaskan pengertian teori implisit dan eksplisit ?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Sebutkan peran sosiologi dalam praktek kesehatan ?
...........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Catatan baca buku bab 7
162
Pertanyaan 8
1. Jelaskan pengertian nilai, norma ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Kemukakan kategori nilai menurut Sutan Takdir Alisyahbana ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Jelaskan fungsi nilai?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Apa yang dimaksud Etika keperawatan ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 8
163
Pertanyaan 9
1. Gambarkan dan jelaskan peta Perilaku sakit Lehndorff dan
Tracy ?
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
2. Sebutkan Model-model perilaku sakit ?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Sebutkan empat unsur yang merupakan faktor utama di dalam
perilaku sakit ?
...........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Catatan baca buku bab 9
164
Pertanyaan 10
1. Sebutkan teori tentang Perubahan Sosial ?
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
2. Jelaskan pengertian difusi, akulturasi, inovasi?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi ?
...........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Catatan baca buku bab 10
165
Pertanyaan 11
1. Jelaskan makna budaya makanan dan kesehatan?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Gambarkan tahap pertama gelombang hidup manusia ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 11
166
Pertanyaan 12
1. Gambarkan siklus hidup manusia ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Kemukakan penjelasan?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 12
167
Pertanyaan 13
1. Kemukakan contoh budaya persalinan manyarakat di
Indonesia??
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Sebutkan macam-macam persalinan?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Jelaskan tanda-tanda persalinan sudah dekat?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Jelaskan tanda-tanda persalinan sudah pasti?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Jelaskan perbedaan persalinan budaya Indonesia dan luar
negeri?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Catatan baca buku bab 13 dan bab 14
168
BIOGRAFI PENULIS
Dra. Nurbaeti, M.Kes lahir di Salah satu kabupaten di
Sulawesi Selatan yaitu Kepulauan Selayar pada tanggal
20 Juni 1964 adalah staf dosen di Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Muslim Indonesia . Menempuh
pendidikan Sarjana strata satu di Fakultas Ilmu Sosial
Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Lulus
tahun 1988. Kemudian melanjutkan ke jenjang Magister
Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Universitas Hasnuddin lulus pada tahun 2010. Pengalaman
menngajar; menjadi dosen LB di Universitas Muslim Indonesia mulai
tahun 1991, masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea
sebagai dosen tetap yayasan pada tahun 2004, mendapat NIDN pada
tahun 2006, pindah ke Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen
tetap yayasan tahun 2017 sampai sekarang.
169
Dr. Sundari, SST., MPH, lahir di Pelitakan tanggal
12-12 -1976. Sekolah dikesehatan dimulai dari SPK
Depkes Majene 1996, D1 Kebidanan (PPBA) di
Muhammadiyah Makassar tahun 1998, D3
Kebidanan di Poltekkes Makassar tahun 2003, D4 pendidik kebidanan
di Fakultas kedokteran Universitas Padjajaran Bandung tahun 2004,
S2 MCH Reproduction di Fakultas Kedokteran UGM Jogjakarta
2010, S3 Biomedik Fakultas Kedokteran UNHAS Makassar. Pernah
menjadi Ketua Program Studi di Stikes Bina Bangsa mulai tahun
2004-2014. Sekarang bekerja di Universitas Muslim Indonesia
Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi D3 Kebidanan sejak tahun
2015- sekarang. Saat ini di amanahi sebagai Ketua Program Studi di
D3 Kebidanan FKM UMI. Mengajar Asuhan Kehamilan, Asuhan
Persalinan, asuhan nifas dan asuhan komunitas serta pernah mengajar
kegawat daruratan obstetric, metodologi penelitian, Komunikasi dan
Konseling dalam praktek Kebidanan. Mengajar di Pasca Sarjana UMI
matakuliah Metode kontrasepsi Update, Promosi Kesehatan,
Kesehatan Wanita, Program KIA Kespro.
170
Nurlina Akbar, S.ST, M.Kes. Lahir di Sinjai tanggal 31
Desember 1989 menyelesaikan Pendidikan DIII
Kebidanan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Muslim Indonesia, DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes
Makassar dan Magister Ilmu Biomedik di Fakultas
Kedokteran Univeristas Hasanuddin. Saat ini mengabdikan diri di
Prodi D3 Kebidanan FKM Universitas Muslim Indonesia sejak tahun
2014