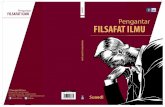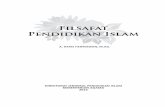Filsafat Pendidikan
Transcript of Filsafat Pendidikan
PENGERTIAN FILSAFAT PENDIDIKAN Ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat atau filsafat yang diterapkan dalam usaha memcahkan masalah dan problem pendidikan
Filsafat pendidikan adalah filsafat umum yang diterapkan pada pendidikan sebagai sebuah wilayah spesifik dari usaha serius manusia
TUJUAN FILSAFAT PENDIDIKAN Untuk membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan.
Memungkinkan mereka untuk bisa mengevaluasi lebih baik tawaran-tawaran yang sedemikian banyak sebagai solusi bagi persoalan-persoalan pendidikan.
Untuk membekali guru berfikir yang klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan.
MENURUT RICHARD KNOWLES MORRIS Filsafat pendidikan, sebagai suatu kerangka teori untuk melakukan refleksi atas pemikiran pendidikan, meliputi;
epistemologi sebagai alat untuk menganalisis suatu bangunan teori ataupun evaluasi teori. a. Epistemologi menempatkan problem pengetahuan sebagai inti dari proses edukasi. b. Epistemologi juga memahami secara mendalam disiplin keilmuan berikut implikasi-implikasi edukasinya.
metafisika merupakan suatu alat untuk menelusuri prinsip-prinsip dasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses rumusan, perubahan, dan implikasi-implikasi pendidikan.
Aksiologi atau nilai dalam pendidikan atau etika pendidikan yang amat diperlukan dalam konteks seringnya terjadi eskalasi atas apa yang ada di lapangan dengan apa yang ada dalam dataran idealitas..[1]
[1]Richard Knowles Morris, “The Philosophy of Education: A Quality of its Own”, dalam Christopher J. Lucas (ed.), What is Philosophy of Education? (London: Macmillan, 1969), hlm. 134-135.
ONTOLOGI kajian tentang yang ada. Ontologi pendidikan berarti kajian tentang hakikat keber“ada”an pendidikan. Keberadaan pendidikan tidak lepas dari keberadan manusia (baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat), agama, dan alam/kosmos.
AGAMA DAN TUHAN Pendidikan direpresentasikan dalam kepentingan-kepentingan agama atau keyakinan tertentu. Jelasnya, pendidikan bisa jadi merupakan representasi dari agama atau sebaliknya bahwa agama selalu mereprenstasikan eksistensinya dalam pendidikan.
Bagi al-Attas, kreastivitas dalam pendidikasn secara ontologis merupakan kreativitas manusia sebagai mahluk sosial. Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari hakikat manusia beragama karena beragama (al-dīn) adalah berperadaban (al-tamaddun). Sedangkan peradaban tidak bisa dilepaskan dari aspek pendidikan. Tidak ada perdaban yang tidak didorong dan oleh pendidikan karena pendidikan merupakan ‘jantung’ yang memompa seluruh gerak energi suatu peradaban.
KOSMOS ATAU ALAM Secara etimologis, kosmos berasal dari bahasa Inggris cosmos, yang berarti keteraturan.
Kosmos merupakan sistem yang teratur atau berada dalam keteraturan.
Kosmos juga sering diartikan dengan universe atau alam.
KOSMOLOGI TERBAGI DUA Physical cosmologi.
Kosmologi fisik lebih menitik beratkan pada pemahaman tentang alam sebagai suatu entitas yang bersifat fisik fisik dan astro fisik
Metaphysical cosmologi
Kosmologi metafisik lebih menitikberatkan pada ruang manusia didalam jagat raya ini dalam konteks keterkaitannya dengan entitas lain.
KOSMOS DAN PENDIDIKAN Kosmos menjadi bagian dari dimensi-dimensi metafisika oleh karena kosmos bukan sekedar alam dalam arti fisik tetapi kosmos merupakan ruang dimana manusia berada didalamnya berikut keterkaitannya dengan hal lain (pendidikan).
MANUSIA Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan, sebagaimana juga pendidikan tidak bisa lepas dari manusia. Oleh karena itu, hakikat pendidikan adalah pemanusiaan manusia, hakikat pemanusiaan adalah pemberian pencerahan manusia melalui pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua wajah dalam kepingan mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
pemikiran al-Attas tentang manusia adalah bahwa manusia merupakan subjek dalam pendidikan. Manusia secara otomatis akan melakukan aktiftas-aktifitas edukasinya karena secara fitri ia adalah mahluk yang selalu mewujud dalam dunia pengetahuan karena eksistensinya. manusia sebagai al-nafs al-natiqah daripada al-nafs al-hayawaniyyah, yang disinonimkan dengan dunia fisik.
EPISTEMOLOGI DAN PENDIDIKAN Epistemologi disebut juga dengan filsafat pengetahuan.
Cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.
Epistemologi dalam konteks yang paling sederhana adalah menelaah tentang kriteria pengetahuan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Morris, epistemologi mengawal proses pendidikan, proses pemaknaan dan pemahaman tentang pengetahuan dalam pendidikan
EPISTEMOLOGI Cabang filsafat yang mengkaji hakekat, sumber dan validitas (keabsahan) pengetahuan.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan apa itu kebenaran?
Bagaimana kita mengetahui?
DIMENSI-DIMENSI PENGETAHUAN Apakah kebenaran itu bersifat relatif ataukah absolut?
Apakah pengetahuan itu subjektif ataukah objektif?
Apakah terdapat kebenaran yang independen dari pengalaman manusia?
APAKAH PENGETAHUAN ITU SUBJEKTIF ATAUKAH OBJEKTIF?
Pertanyaan ini terkait erat dengan relativitas.
Van Cleve Morris mencatat bahwa ada tiga pendapat tentang objektivitas pengetahuan.
1. Beberapa orang berpendapat bahwa pengetahuan itu sesuatu yang datang pada kita dari luar dan masuk ke dalam akal pikiran dan sistem saraf kita. Ini dianut oleh matematikawan dan fisikawan.
2. Subjek yang mengetahui menyumbangkan sesuatu pergumulannya dengan dunia ini sehingga
APAKAH KEBENARAN ITU BERSIFAT RELATIF ATAUKAH ABSOLUT?
Kebenaran absolut merujuk pada kebenran (menggunakan ‘K’ besar) yang secara abadi dan universal adalah benar tanpa melihat waktu dan tempat.
Keterkaitan epistemologi dengan pendidikan terdapat dalam persoalan bagaimana epistemologi memandang usaha-usaha pendidikan sebagai suatu yang sah dan benar. Atau bisa juga dibalik, bahwa usaha-usaha pendidikan jika menggunakan sebuah kerangka epistemologi tertentu juga akan mempengaruhi format pendidikan itu sendiri.
PANCA INDRA Empirisme adalah paham yang menganggap pengetahuan dicapai melalui indra.
Manusia membangun gambaran tentang dunia di sekeliling mereka dengan melihat, mendengar, membau, meraba, dan mengecap.
WAHYU Wahyu adalah komunikasi tuhan yang berisi tentang kemauan tuhan.
Kebenaran yang diperoleh melalui wahyu ini dipercayai absolut dan tidak tercampuri.
Penyimpangan dari kebenaran yang diwahyukan terletak proses interpretasi manusia.
Beberapa orang beranggapan bahwakelemahan utama pengetahuan melalui wahyu adalah harus diterima atas dasar iman dan tidak bisa dibuktikan secara empiris.
OTORITAS Berasal dari para ahli. Sebagai sebuah tradisi. Semisal didalam kelas sebagian besar sumber informasi adalah otoritas, semisal buku pelajaran, guru, atau buku rujukan.
INTUISI Penangkapan langsung pengetahuan yang bukan berasal dari penalaran dan indrawi.
Bersifat personal. Pengetahuan yang disertai dengan kuatnya rasa yakin.
KEABSAHAN PENGETAHUAN Para filosof bertumpu pada tiga alat uji kebenaran;Teori korespodensiTeori KoherensiTeori pragmatis.
TEORI KORESPODENSI alat uji yang menggunakan kesesuaian dengan fakta sebagai standar penilian.
Contoh ada seekor singa dirungan kelas, dapat diuji kebenarannya dengan investigasi (penelitian dan pembuktian) empiris.
TEORI KOHERENSI Kebenaran adalah adanya keselarasan seluruh pernyataan-pernyataannya.
Contoh, bahwa sebuah pernyataan seringkali diputuskan sebagai benar atau salah atas dasar sesuai tidaknya dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran.
TEORI PRAGMATIS Kebenaran adalah apa yang bekerja (berfungsi)
Kebenaran adalah apa yang membawa hasil.
Suatu pertimbangan itu “benar” jika dengan menggunakannya dan mencapai hasil yang berguna.
Suatu pertimbangan itu “salah” kalau dengannya dihasilkan hal yang merugikan.
MANUSIA SEBAGAI SUBJEK MENGETAHUI Dalam seluruh proses pendidikan, manusia pada hakikatnya adalah subjek pendidikan dan manusia bukan objek pendidikan, tetapi manusia merupakan pendidik dirinya sendiri. Jelasnya, relasi manusia dan proses mengetahui yang menjadi tugas pokok bidang pendidikan adalah relasi fundamental. Manusia dan proses mengetahui merupakan kesatuan esensi dan proses mengeksistensi diri manusia baik sebagai subjek pendidik maupun objek terdidik.
Begitu pentingnya posisi manusia dalam pengetahuan, proses penanaman pengetahuan terhadap diri manusia yang diusung oleh dunia pendidikan selalu berjalan seiring antara proses pendidikan dan kesadaran akan konsep manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep manusia sebagai subjek yang mengetahui, dalam konteks diskursus epistemologi pendidikan, merupakan sumbangan pemikiran kedua tokoh tersebut yang sangat berharga. Manusia sebagai subjek yang mengetahui, menurut Driyarkara merupakan prinsip fundamental dalam pendidikan atau prinsip hakiki dalam pandangan al-Attas.
KONSEP PENGETAHUAN Konsep pengetahuan selalu terkait dengan realitas, penalaran, logika atau metode, dan nilai atau perspektif. Dalam kaitannya dengan realitas, pengetahuan berujung pada persoalan empirisisme atau realisme. Kaitan antara pengetahuan dan penalaran berujung pada idealisme atau rasionalisme. Keterkaitan antara logika atau metode dan pengetahuan berujung pada positivisme. Sedangkan kaitan antara nilai atau perspektif dengan pengetahuan berujung pada ideologisme.
PEMBIDANGAN ILMU Pembidangan ilmu adalah salah satu elemen yang sangat kompleks dalam bidang pendidikan. Pembidangan ilmu tidak sekedar persoalan kurikulum, pembidangan ilmu juga termasuk bagian dari tafsir atas orientasi pendidikan, secara khusus dan orientasi sosial pada umumnya. Entah karena apa persoalan pembidangan ilmu ini tidak banyak mendapat perhatian di kalangan pendidik atau pengamat pendidikan.
Aksiologi pendidikan tidak sekedar kajian baik dan buruknya suatu pendidikan, namun yang lebih penting justru kajian tentang realitas suatu pemahaman tentang nilai (aksiologi) yang selalu mewarnai pola-pola yang diusung dalam pendidikan baik dari segi latar belakang pemikiran, rumusan, proses, maupun praktek pendidikan
AKSIOLOGI Aksiologi: secara harfiah, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Secara terminologi, aksiologi merupakan telaah filosofis yang menaruh perhatian tentang teori nilai, tentang cara dan tujuan, dan tentang kebaikan dan kebenaran.
aksiologi merupakan kerangka dasar atau point of view yang melahirkan rumusan, proses dan tujuan pendidikan
Ruang kelas merupakan teater aksiologis
Guru tidak bisa menyembunyikan moral dirinya.
Para guru selalu mengajar kepada subjek didik yang masih sangat mudah menerima pengaruh.
Peserta didik mengasimilasi dan mengimitasi struktur nilai para guru hingga ke tingkat yang signifikan.
John Dewey menyinggung keterkaitan yang tidak terpisahkan antara dimensi nilai-nilai pendidikan dengan persoalan perumusan, proses dan tujuan pendidikan. Dewey menulis:
Pertimbangan-pertimbangan yang dimasukaan dalam nilai-nilai pendidikan telah disinggung juga dalam diskusi-diskusi tentang tujuan dan kepentingan-kepentingan (pendidikan).
Nilai-nilai khusus yang biasanya didiskusikan dalam teori-teori pendidikan serupa dengan tujuan yang juga penting. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi kegunaan, budaya, informasi, persiapan untuk efesiensi sosial, disiplin mental atau kekuatan, dan lainnya.
Aspek tujuan-tujuan tersebut dalam apa yang dianggap bernilai telah dipaparkan dalam analisis kami tentang realitas kepentingan, dan memang tidak ada perbedaan antara membicarakan tentang seni sebagai suatu kepentingan/kepedulian atau perhatian dan menempatkanya sebagai suatu nilai.
Hal demikian itu, bagaimanapun, bahwa diskusi tentang nilai biasanya terfokus pada pertimbangan prihal berbagai hasil akhir yang ditundukkan oleh subjek kurikulum tertentu.
Suatu diskusi tentang nilai-nilai pendidikan, dengan demikian, membuka suatu peluang untuk melihat kembali diskusi-diskusi yang telah terdahulu tentang tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentinan di satu sisi dan tentang kurikulum, di sisi lain, dengan menempatkannya ke dalam suatu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Karena penanaman nilai-nilai merupakan bagian hakiki pendidikan sendiri, maka bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik merupakan suatu kewajiban untuk mendalami aksiologi atau ilmu tentang nilai-nilai, baik itu nilai estetis (estetika), nilai moral (etika) maupun nilai spiritual (teologi). Pertanyaan pokok yang muncul di sini adalah nilai-nilai mana yang seharusnya atau paling tidak selayaknya ditanamkan dalam proses pendidikan? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja ada berbagai macam sesuai dengan filsafat hidup yang dianut oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Ada dua kategori dasar aksiologi: pertama objectivism dan kedua subjectivism. Baik objectivism maupun subjectivism berangkat dari satu pertanyaan, apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia? Pertanyaan ini dijawab oleh; (1) teori nilai intuitif, teori ini berpandangan bahwa cukup sulit untuk mendefinisikan suatu perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut. (2) Teori rasional, teori ini berpendangan bahwa nilai merupakan hasil dari penalaran manusia. (3) teori alamiah, teori ini berpandangan bahwa nilai itu diciptakan oleh manusia bersamaan dengan kebutuhan dan hasrat-hasrat alamiahnya. (4) teori nilai emotif. Teori ini berpandangan bahwa nilai itu merupakan ekspresi-ekspresi emosi atau tingkah laku. Dua yang pertama merupakan kategori objectivism sedang dua yang terakhir merupakan kategori subjectivism. Selain objectivism dan subjectivism juga terdapat aliran pragmatism. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 33-34.
Ada dua kategori dasar aksiologi: pertama objectivism dan kedua subjectivism. Baik objectivism maupun subjectivism berangkat dari satu pertanyaan, apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia? Pertanyaan ini dijawab oleh; (1) teori nilai intuitif, teori ini berpandangan bahwa cukup sulit untuk mendefinisikan suatu perangkat nilai yang bersifat ultim atau absolut. (2) Teori rasional, teori ini berpendangan bahwa nilai merupakan hasil dari penalaran manusia. (3) teori alamiah, teori ini berpandangan bahwa nilai itu diciptakan oleh manusia bersamaan dengan kebutuhan dan hasrat-hasrat alamiahnya. (4) teori nilai emotif. Teori ini berpandangan bahwa nilai itu merupakan ekspresi-ekspresi emosi atau tingkah laku. Dua yang pertama merupakan kategori objectivism sedang dua yang terakhir merupakan kategori subjectivism. Selain objectivism dan subjectivism juga terdapat aliran pragmatism. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 33-34.
IDEALISME Bagi kaum idealis nilai-nilai bersifat mutlak dan tetap, maka mereka menolak pandangan yang menyatakan bahwa kebaikan dan keindahan itu bersifat subjektif dan berubah-ubah sesuai dengan selera yang mengamati.
REALISME Semua penganut paham realisme menyakini adanya nilai-nilai yang tetap dan objektif.
Semua Realis setuju bahwa setiap sistem pendidikan mesti diarahkan untuk mengajar nilai-nilai- tertentu yang sebelumnya sudah dapat ditetapkan.
Karena nilai-nilai sejati bersifat objektif dan tetap, maka tujuan-tujuan pendidikan juga relatif tetap.
Tolak ukur moral yang diajarkan kepada peserta didik tidak tergantung dari siapa yang menjadi pendidik dan pengajarnya.
PRAGMATISME Bagi kaum pragmatis nilai bersifat relatif, tidak ada nilai yang bersifat mutlak.
Semua nilai dilihat dari akibatnya dalam praksis kehidupan manusia yang konkret.
Semua nilai berubah-ubah sesuai dengan perkembangan manusia dan masyarakat.
ETIKA Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat, cara bertindak, tempat tinggal, kebiasaan.
Kajian tentang nilai-nilai dan prilaku moral. Etika berusaha menjawab pertanyaan;
Apakah ukurannya sehingga suatu prilaku itu bernilai baik?
Apa yang yang harus kulakukan?Apakah kebaikan itu relatif atau mutlak?Apakah tujuan itu membenarkan sarana (alat)?Dapatkah moralitas dipisahkan dari agama?Apakah baik sesorang mencuri obat untuk kesembuhan seorang anggota keluarganya yang sakit parah dengan alasan tidak punya uang?
Sejauhmana memberi sedekah kepada pengemis dinilai baik?
SASARAN ETIKA PENDIDIKAN Menumbuhkembangkan nilai kebaikan dalam prilaku sehingga bisa menjadi matang dan cerdas (kecerdasan emosional).
Etika pendidikan merupakan bagian integral dari aspek epistemologi dan ontologi, maka pencerdasan emosional dilakukan menurut pencerdasan intelegensi dan berdasar kepada pencerdasan spritual.
ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN Progresivisme Perennialisme Essensialisme Rekonstruksionisme Eksistensialisme
PROGESIVISME Pendidikan merupakan proses penggalian pengalaman secara terus menerus.
Pendidik harus senantiasa siap untuk sellu melakukan perubahan baik metode dan kebijakan pendidikan sesuai dengan perubahan zaman.
Merekontruksi (menyusun ulang) secara terus menerus pengalaman hidup.
Guru berfungsi sebagai pembimbing. Masing-masing orang akan menghasilkan lebih banyak bila saling bekerjasama
Sekolah-sekolah mesti diatur secara demokratis
KRITIK TERHADAP PROGESIVISME Konsep “pertumbuhan” berdasarkan aktivitas diri anak merupakan konsep yang kabur
Prinsip bahwa anak harus dididik sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri serta guru hanya berfungsi sebagai pendamping merupakan prinsip yang tidak realistik.
Pernyataan progresivisme bahwa cara belajar dengan memecahkan masalah yang secara langsung dialami oleh anak merupakan cara belajar yang efektif perlu diuji secara empiris.
Tidak ada kaitan langsung antara sistem pendidikan progressive dengan demokrasi.
PERENNIALISME Berasal dari kata latin “perennis” yang berarti “abadi” atau “kekal”.
Perennialis berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar filsafat pendidikan itu bersifat abadi atau tetap tak berubah sepanjang jaman.
Apa yang disebut benar dan baik akan tetap benar dan baik entah di mana dan kapan saja.
Pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip yang bersifat abadi.
PRINSIP-PRINSIP PERENNIALISME Manusia pada dasarnya sama, maka pendidikan semestinya sama untuk semua orang.
Karena kenalaran (rasionalitas) merupakan sifat tertinggi manusia, maka ia harus menggunakannya untuk membimbing kodrat alamiahnya yang instinktif sesuai dengan tujuan-tujuan yang dengan sadar dan bebas dipilih.
Pendidikan bertugas untuk menyelaraskan manusia dengan tuntutan kebenaran yang bersifat tetap dan bukan dengan keadaan dunia dewasa ini yang senantiasa berubah.
Pendidikan bukanlah suatu tiruan hidup di tengah masyarakat, tetapi suatu persiapan untuk itu.
Siswa/mahasiswa perlu dididik untuk mengetahui bidang-bidang pokok tertentu yang akan mengenalkan mereka dengan hal-hal yang bersifat tetap.
Pendidikan harus memperkenalkan siswa/mahasiswa dengan pa yang menjadi cita-cita dan keprihatinan umat manusia pada umumnya sebagaimana terungkap dalam karya-karya sastra klasik, filsafat, sejarah, dan sains.
ESSENSIALISME Berasal dari kata latin “essentia” yang berarti hal yang pokok/hakiki.
Pentingnya penyampaian hal-hal yang essensial (hakiki) dalam pendidikan.
Peneinjaun kembali isi kurikulum, mana yang essensial dan mana yang sekedar tambahan.
BEBERAPA PRINSIP DASAR ESSENSIALISME Kegiatan belajar pada dasarnya menuntut kerja keras dan latihan yang kadang membosankan.
Inisiatif pokok dalam pendidikan tidak terletak pada murid tapi pada guru.
Inti pokok pendidikan adalah dikuasainya bahan yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Sekolah mesti mempertahankan metode tradisional yang menekankan disiplin mental.
BEBERAPA KRIRK TERHADAP ESSENSIALISME Terlalu statis. Kurang merangsang inisiatif intelektual anak didik.
REKONSTRUKSIONISME Berasal dari bahasa latin “reconstructio” yang berarti “penataan kembali”.
Tujuan pokok pendidikan adalah untuk menata kembali masyarakat agar bisa memenuhi tuntutan zaman secara terus menerus.
Merupakan kelanjutan dari aliran progesivisme
EKSISTENSIALISME DAN PENDIDIKAN Pandangan utama kalangan eksintensialis adalah pada upaya membantu kehadiran individu untuk sampai pada realisasi yang lebih utuh untuk mengungkapkan proporsi-proporsi sebagai berikut;
1. Aku adalah subjek yang memilih, 2. Aku adalah subjek yang bebas, sepenuhnya bebas untuk mencanangkan tujuan-tujuan kehidupanku sendiri.
3. Aku adalah subjek yang bertanggung jawab, secara pribadi mempertanggungjawabkan akan pilihan-pilihan bebasku, karena hal itu terungkapkan dalam bagaimana aku menjalani kehidupanku.
PERAN GURU Berkemauan untuk membantu para subjek didik mengeksplorasi jawaban-jawaban yang mungkin.
Guru bersedia memperhatikan keunikan individualitas masing-masing subjek didik.
Guru memperlakukan peserta didik individu dan mengenali secara personal.
Guru sebagai fasilitator.
KURIKULUM Kurikulum terbuka bagi perubahan. Konsepnya tentang kebenaran selalu berkembang dan berubah.
Kajian humanities dianggap penting, kerena memberikan pencerahan yang besar akan persoalan-persoalan berat eksistensi manusia.