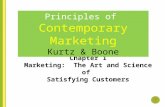Jejak kelahiran filsafat komunikasi
-
Upload
bundamulia -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Jejak kelahiran filsafat komunikasi
JEJAK KELAHIRAN FILSAFAT KOMUNIKASI
1. Zaman Yunani Kuno
Filsafat Yunani dimulai sejak abad ke-6 SM. Namun demikian,
jauh sebelum filsafat lahir, bangsa Yunani telah mengenal
mitos-mitos yang berkembang subur di tengah-tengah mereka.
Mitos-mitos tersebut berfungsi sebagai jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri alam
semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh bangsa Yunani
pada saat itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain
mengenai asal-usul alam semesta, penyebab bencana (gempa bumi,
gunung meletus, dan lain-lain), sebab-sebab gerhana, dan lain
sebagainya. Salah satu contoh mitos yang paling terkenal
adalah mengenai sebab-sebab terjadinya gempa bumi.
Menurut bangsa Yunani pada saat itu, kejadian gempa bumi
disebabkan oleh kemarahan dewa Poseidon (dewa penjaga bumi dan
laut) yang ingin memberi hukuman kepada penghuni bumi
(manusia) dengan cara menggoyang-goyangkan bumi. Mitos-mitos
seperti itu merupakan upaya bangsa Yunani untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang misteri alam
semesta. Filsafat Yunani yang pertama tidak lahir di tanah
airnya sendiri, tapi lahir di Ionia (pesisir Barat Asia
Kecil), sebuah daerah yang pernah menjadi koloni bangsa
Yunani. Di Ionia inilah orang-orang Yunani mencapai kemajuan
besar, menjadi masyarakat yang makmur dalam bidang ekonomi dan
maju secara budaya. Kemakmuran tersebut banyak memberi
kesempatan kepada bangsa Yunani untuk berpikir dan membahas
hal-hal lain selain dari kepentingan penghidupan. Sejarah
filsafat Yunani diawali dengan zaman filsafat pra-Socrates
dengan tokohtokohnya yang dikenal dengan nama filsuf pertama
atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk (arcbe) yang
dianggap sebagai asal mula segala sesuaru. Para filsuf yang
terkenal pada masa ini di antaranya adalah Thales,
Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos,
Parmenides, Zeno, Empedokles, Anaxagoras, dan Demokritos.
1. Thales (±625-545 SM)
Nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Hcrodotus
pada abad ke-5 SM. Thales adalah salah satu dari tujuh
orang bijaksana (seven wise mm ofgvece). Salah satu
jasanya yang besar adalah meramal gerhana matahari pada
tahun 585 SM. Thales mengembangkan filsafat alam yang
mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur
komposisi alam semesta. Sebagai ilmuwan pada masa itu,
Thales mempelajari magnetisme danlis-u ik yang merupakan
pokok soal fisika. Thales merupakan ahli matematika yang
pertama dan juga sebagai the father of deductive reasoning (bapak
penalaran deduktif).
2. Anaximandros(±610-540SM)
Anaximandros adalah salah satu murid Thales. Ia adalah
orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam
kesusateraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi
dan geografi. Anaximandros adalah orang pertama yang
membuat peta bumi. Sama halnya dengan sang guru,
Anaximan-dros juga ingin mencari asal dari segalanya. Ia
tidak menerima begitu saja apa yang dipahami oleh
gurunya. Ia beranggapan jika yang asal itu satu, namun
yang satu itu bukan air atau sesuatu yang dapat diamati
oleh panca indera. Menurutnya, segala sesuatu itu berasal
dari toapeiron, yang bisa diartikan tidak terhingga,
tidak terbatas, atau tidak tersusun.
3. Anaximenes (+ 538 - 480 SM)
Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal usul
segala sesuatu. Udara melahirkan semua benda dalam alam
semesta karena suatu proses pemadatan dan pengenceran.
Jika udara semakin bertambah maka muncullah berturut-
turut angin, air, tanah dan akhirnya batu. Sebaliknya,
jika udara menjadi encer maka yang timbul adalah api.
4. Pythagoras (± 580 - + 500 SM)
Pythagoras dilahirkan di Pulau Samos, Ionia. Tanggal dan
tahunnya tidak diketahui secara pasti. Ia dikenal sebagai
filsuf dan ahli ukur Ia mengembalikan segala sesuatu
kepada bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan
bilangan (kuantitas). Karena itu, ia berpendapat bahwa
bilangan adalah unsur pertama dari alam dan sekaligus
menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan
bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan
gabungan antara dua hal yang berlawanan.
5. Xenophanes (± 570 - + 480 SM)
Xenophanes adalah seorang filsuf yang hidup sezaman
dengan Anaxago-ras dan Pythagoras. Xenophanes mencoba
melihat kesatuan sebagai asas dari setiap kenyataan yang
ada. Ia dengan tegas menolak politeisme, menentang orang-
orang yang menyamakan "yang ilahi" dengan manusia yang
dilahirkan, yang berpakaian, dan lainlain. Bagi
Xenophanes, "yang ilahi" itu tiada awalnya; "yang ilahi"
itu bersifat kekal, esa, dan universal.
6. Herakleitos (±540 - 475 SM)
Herakleitos hidup antara tahun 540-480 SM. Ia dilahirkan
di Ephcsos dari kalangan aristokrat. Herakleitos memiliki
watak yang tidak kenal kompromi dan sangat ekstrem dalam
menentang demokrasi. Herakleitos terkenal sangat bebas
dalam mengemukakan pendapatnya. Herakleitos sangat
terpengaruh oleh kenyataan bahwa alam mengalami perubahan
yang terus menerus, sehingga terjadilah pluralitas dalam
alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satu pun di
alam ini yang bersifat permanen. Apa yang terlihat tetap
sebenarnya tengah mengalami proses pembahan yang tanpa
henti. Ia juga berkeyakinan bahwa api adalah elemen utama
dari segala sesuatu yang timbul.
7. Parmenides (± 540 - + 475 SM)
Parmenides lahir tahun 540 SM. Ia adalah seorang ahli
pikir yang melebihi siapa saja pada masanya. Filsafatnya
adalah "yang realitas dalam alam ini hanya satu, tidak
bergerak dan tidak berubah". Dasar pernikirannya adalah
bahwa yang ada itu ada, mustahil tidak ada. Pembahan dari
ada menjadi tidak ada adalah hal yang mustahil, dan
begitu pun sebaliknya.
8. Zeno(±490SM)
Zeno adalah murid dari Parmenides, yang mencoba
membuktikan bahwa gerak adalah suatu khayalan, dan baliwa
tiada kejamakan dan tiada ruang kosong. Untuk membuktikan
tiada ruang kosong, Zeno mengemukakan bahwa seandainya
ada ruang kosong, ruang kosong im tentu mengambil tempat
dalam ruang yang lain, dan ruang yang lain itu mengambil
tempatnya lagi dalam ruang yang lainnya. Demikian
seterusnya, tiada henti-hentinya. Oleh karena hal yang
demikian itu tidak mungkin, maka harus disimpulkan bahwa
tidak ada ruang kosong.
9. Empedokles(492-432SM)
Empedokles setuju dengan pendapat Parmenides, bahwa di
dalam alam semesta tiada satu pun yang dilahirkan sebagai
hal yang baru dan dapat dibinisakan sehingga tiada lagi.
Ia juga setuju dengan Parmenides bahwa tiada ruang kosong
Namun demikian, ia menentang pendapat Parmenides yang
menyatakan bahwa kesaksian indera adalah palsu. Baginya,
segala yang ada terdiri dari empat anasir : air, udara,
api dan tanah. Keempat anasir tersebut mempunyai kualitas
yang sama, yaitu tidak berubah. Perbedaan-perbedaan yang
ada di antara benda-benda disebabkan campuran atau
penggabungan dari keempat anasir tersebut berbeda-beda.
10. Anaxagoras (499-420 SM)
Seperti halnya Empedokles, Anaxagoras juga menolak ajaran
Parmenides. Menurut Anaxagoras, kenyataan bukanlah satu,
sebab kenyataan terdiri dari banyak anasir, masing-masing
memiliki kualitas yang sama dengan kualitas "yang ada",
yaitu: tidak dijadikan, tidak berubah, dan berada di
ruang yang kosong Pokok terpenting dalam ajaran
Anaxagoras adalah teorinya tentang nous (roh, rasio),
yang membedakan antara roh (nous) dan benda. Baginya, roh
adalah yang terhalus dan tersempurna dari segala sesuatu.
11. Demokritos (+460-370 SM)
Demokritos lahir di Abdera, daerah pesisir di Yunani
Utara. Demokritos dipandang sebagai seorang ahli pikir
yang menguasai banyak bidang Dari karyakaryanya, ia telah
mewariskan sebanyak 70 karangan tentang beragam
persoalan, seperti kosmologi, matematika, astronomi,
logika, etika, teknik, musik, puisi dan lain sebagainya.
Menurut Demokritos, atom-atom itu selalu bergerak dan itu
berarti harus ada ruang kosong. Karena satu atom hanya
dapat bergerak dan menduduki satu tempat saja. Dengan
demikian, Demokritos berpendapat bahwa realitas itu ada
dua: atom itu sendiri (yang penuh) dan mang tempat atom
bergerak (yang kosong).
Demikianlah pokok pemikiran para filsuf alam yang berusaha
mencari unsur induk (arebe) yang dianggap sebagai asal muk dari
segala sesuatu. Periode filsafat Yunani yang selanjurnya adakh
masa keemasan dari filsafat Yunani yang dikenal sebagai Zaman
Yunani Klasik. Pada masa ini, kecenderungan pemikiran filsafat
yang berkembang lebih ditujukan kepada manusia (antroposentris).
Para filsuf yang mewarnai zaman keemasan filsafat Yunani ini
adalah : Socrates, yang mengembangkan teori moral; Plato, yang
mengembangkan teori tentang ide; dan Aristoteles, yang
mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda.
1. Socrates (470-400 SM)
Socrates mengarahkan kajian-kajian filsafat yang semula
sangat abstrak dan jauh dari praksis kehidupan seharis-hari
menjadi lebih praktis dan kongkrit. Oleh Socrates filsafat
diarahkan pada penyelidikan tentang manusia, etika, dan
pengalaman hidup sehari-hari, baik dalam konteks individu
(psikologis), sosial, maupun politik. Menurut Socrates,
kebenaran bukanlah sesuatu yang bersifat subyektif dan
rektif. Seseorang dapat menangkap adanya kebenaran obyektif
yang tidak tergantung pada individu yang memikirkan atau
menggapainya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada perilaku yang
baik dan tidak baik, yang pantas dan yang tidak pantas untuk
dilakukan. Penentuan baik dan buruk, pantas dan tidak
pantas, tidak terletak pada kekuatan argumentasi orang
perorang, melainkan pada sesuatu yang sifatnya universal.
Berbuat jahat di mana pun adalah buruk, sedangkan berbuat
baik pasti merupakan kebaikan. Kebaikan bukan saja akan
membawa kebahagiaan pada pelakunya, tetapi juga karena dalam
dirinya memang baik. Socrates menyampaikan ajaran-ajarannya
dengan metode dialektika, yaitu metode pencarian kebenaran
secara ilmiah melalui percakapan dan dialog. Socrates selalu
bertanya-tanya: Apakah itu salah atau tidak salah? Apakah
itu adil atau tidak adil? Apakah itu pemberani atau tidak
berani? Demikian seterusnya. Socrates berpendapat jawaban
pertama dari pertanyaan itu adalah hipotesis, dan dengan
pertanyaanpertanyaan berikutnya ia menarik segala
konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban itu.
Socrates juga meramalkan masa depan yang ideal dari negara
yang sempurna, yaitu republik yang diperintah oleh para
filsuf. Filsafat Socrates banyak membahas masalah etika.
Socrates beranggapan bahwa yang paling utama dalam kehidupan
bukanlah kekayaan atau kehormatan, melainkan kesehatan jiwa.
Prasyarat utama di dalam hidup manusia adalah kesehatan
jiwa. Jiwa manusia harus sehat terlebih dulu agar tujuan-
tujuan hidup yang lainnya (dan lebih utama) dapat diraih.
Tujuan hidup yang paling utama adalah kebahagiaan
(eudaimonia). Namun, kebahagiaan dalam bahasa Yunani
memiliki pengertian yang berbeda dengan arti kebahagiaan
pada masa sekarang yaitu mencari kesenangan. Kebahagiaan
dalam bahasa Yunani berarti kesempurnaan. Dalam konteks
kebahagiaan di atas, Plato dan Aristoteles setuju dengan
pendapat Socrates bahwa eudaimonia merupakan tujuan utama
kehidupan. Jalan atau cara yang utama untuk mencapai
kebahagiaan adalah dengan melakukan kebajikan (arete).
Dengan demikian, orang yang bajik adalah orang yang mampu
hidup bahagia.
2. Plato (428-348 SM)
Plato adalah pengikut Socrates yang taat di antara para
pengikut Socrates yang lainnya. Selain dikenal sebagai ahli
pikir, Plato juga dikenal sebagai sastrawan. Ia lahir di
Athena, dengan nama asli Aristocles. Semenjak kanak-kanak
Plato telah mengenal Socrates yang kemudian menjadi gurunya
selamanya 8 tahun Filsafat Plato dikenal sebagai idealisme,
karena meyakini bahwa kenyataan itu tidak lain adalah
proyeksi atau bayang-bayang dari dunia "ide" yang abadi.
Oleh karena itu, bagi Plato, yang ada dan nyata adalah "ide"
itu sendiri. Bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya
terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subyektif. Ide
ini bukan gagasan yang dibuat manusia atau yang ditemukan,
sebab ide ini bersifat obyektif, yang artinya berdiri
sendiri, lepas daripada subyek yang berpikir, tidak
tergantung kepada pemikiran manusia; justru sebaliknya,
idelah yangmemimpin pikiran manusia, Namun demikian, ide ini
tidak dapat diungkapkan secara sempurna pada tiap manusia.
Segala sesuatu yang diketahui melalui pengamatan yang
beraneka ragam dan serba berubah itu adalah pengungkapan
ide-idenya, yang adalah gambar aslinya, atau pola aslinya.
Dengan demikian, filsafat Plato adalah suatu usaha untuk
menjembatani pertentangan yang terdapat di antara para
filsuf terdahulu dengan mencoba keluar dari pemilihan yang
sulit yang dihadapi oleh Herakleitos dan Parmenides, yaitu
dengan memberi bentuk tersendiri kepada hal-hal yang berubah
dan tidak berubah, dan jembatan tersebut terdapat di dalam
ajarannya tentang ide. Dengan demikian, Plato menganjurkan
agar manusia menggunakan rasionya untuk menemukan kebenaran.
Keyakinannya pada keberadaan jiwa dan ide membawa Plato pada
penyusunan metode dalam mendapatkan pengetahuan
(epistemologi). Plato mengembangkan metode deduktif, yaitu
suatu cara berpikir yang dimulai dari premis-premis umum
atau mayor untuk kemudian diperoleh kesimpulan-kesimpulan
yang lebih khusus atau kesimpulan-kesimpulan yang tidak
melampaui premis-premis mayornya. Dalam karyanya yang paling
terkenal yaitu Republic, Plato mengemukakan pemikirannya
tentang negara ideal (utopis) yang dipimpin oleh para filsuf
sebagai raja. Pemimpin negara ideal ini bercirikan: cerdas,
rasional, mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi,
mampu membuat keputusan yang adil bagi semua warga negara,
dan tentu saja cinta pada kebijaksanaan. Karena sifat-
sifatnya tersebut, sang raja yang sekaligus filsuf ini
menempati kelas atas dalam pemerintahan. Kelas berikutnya
adalah kelas prajurit (mrriors). Mereka adalah kelas yang
sangat pemberani, kuat dan terorganisir. Kelas selanjutnya
adalah kelas pekerja (workers), di antaranya adalah para
petani, pedagang, peternak, dan lain sebagainya.
3. Aristoteles (384-322 SM)
Aristoteles dilahirkan di Stageira, Yunani Utara, pada tahun
384 SM. Pada usia 17 tahun, Aristoteles clikirim ke Athena
untuk belajar di Academia Plato. Di sana, ia belajar di
bawah bimbingan Plato selama kurang lebih 20 tahun lamanya
hingga Plato meninggal. Aristoteles juga sempat mengajar
logika dan retorika di Academia selama beberapa waktu.
Berbeda dengan Plato, Aristoteles berpendapat bahwa "ide"
tidak terletak dalam dunia "abadi" sebagaimana yang
dikemukakan Plato, tetapi justru terletak pada
kenyataan/benda-benda itu sendiri. Aristoteles sendiri telah
menulis banyak bidang pengetahuan yang meliputi logika,
etika, politik, metafisika, psikologi dan ilmu alam.
Pemikiran-pemikirannya yang sistematis tersebut banyak
memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil-
hasil pemikiran Aristoteles dapat dikelompokkan menjadi
delapan bagian yang mencakup: logika, filsafat alam,
psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi,
retorika dan poctika. Selain mengembangkan cara berpikir
deduktif, Aristoteles juga me-ngembangkan cara berpikir atau
metode berpikir induktif. Berbeda dengan metode deduktif,
metode induktif dimulai dari pengamatan-pengamatan empiris
dan ditarik kesimpulan yang isinya melampaui obyek-obyek
yang diamati. Dengan demikian, dalam metode induktif ada
proses generalisasi, yaitu menarik kesimpulan yang lebih
umum daripada obyekobyek yang diamatinya. Melalui metode ini
Aristoteles mengembangkan sejumlah kajian yang menjadi
cikal-bakal sejumlah ilmu pengetahuan modern, misalnya
biologi, geologia, fisika, astronomi, dan lain sebagainya.
Dalam filsafat Aristoteles, etika mendapat tempat yang
khusus dan tersendiri. Hukum-hukumnya bukan diarahkan pada
suatu cita-cita yang kekal, mutlak dan tanpa syarat di dalam
dunia yang mengatasi penginderaan manusia, tetapi diarahkan
ke dunia. Hukum-hukum kesusilaan ditiirunkan dari pengamatan
perbuatan-perbuatan kesusilaan dan dari pengalaman angkatan
yang susul-menyusul. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai
adalah "kebahagiaan" (eudamonia). Kebahagiaan ini bukan
kebahagiaan yang subyektif namun suatu keadaan yang
sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang termasuk
keadaan bahagia itu terdapat pada manusia.
2. Abad Pertengahan
Filsafat pada Abad Pertengahan memiliki corak pemikiran yang
berbeda dengan filsafat yang berkembang di Yunani. Filsafat
pada Abad Pertengahan didominasi oleh pemikiran keagamaan
(Kristiani). Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan
atas dogma agama, sehingga corak pemikiran filsafatnya
bersifat teosentris. Pada masa ini, dapat dikatakan bahwa
era filsafat yang berlandaskan pada akal-budi "diabdikan"
untuk dogma agama. Filsafat yang baru ini disebut Skolastik,
(dari bahasa Latin "scbo/asticus" yang berarti guru) karena
dalam periode ini filsafat diajarkan di sekolah-sekolah
biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum
yang baku dan bersifat internasional Adapun pokok ajaran
kaum skolastik adalah adanya keterkaitan (hubungan) antara
iman dengan akal budi, hakikat tuhan, etika, dan politik.
Masa skolastik mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-I 3.
Salah satu filsuf yang pemikirannya memberi corak tersendiri
pada masa ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274), yang
berpendapat bahwa pembuktian tentang adanya Tuhan hanya
dapat dilakukan secara aposteriori. Dalam hal ini, Thomas
Aquinas mengajukan lima argumen sebagai dasar pembuktian
keberadaan Tuhan:
a. Argumen Pertama : Gerak Tidak ada sesuatu pun yang mampu
bergerak dengan senelirinya. Sesuatu yang bergerak
dipastikan memiliki sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang
menggerakkan pasti juga mempunyai penggerak, dan demikian
seterusnya. Namun, ada akhir dari penyebab yang menggerakkan
itu. Penyebab yang menggerakkan semua itu disebut Penggerak
Pertama. Penggerak Pertama itu harus berupa kekuatan yang
maha besar, jadi pasti bukan manusia atau mahluk serupa
manusia. Penggerak Pertama itu adalah Tuhan.
b. Argumen Kedua : Sebab-Akibat Tidak ada sesuatu pun yang
eksistensinya disebabkan oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin
sesuatu menjadi sebab sekaligus akibat bagi eksistensinya
sendiri. Suatu kejadian adalah akibat dari suatu penyebab
dan penyebab itu pun merupakan akibat dari penyebab-penyebab
Lainnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan penyebab awal.
Jika tidak ada penyebab awal, tidak akan terjadi rangkaian
akibat sesudahnya. Atau, rangkaian kejadian tersebut tidak
mungkin tanpa penyebab awal. Penyebab awal itu adalah Tuhan.
c. Argumen Ketiga : Ada dan Tiada Segala sesuatu yang
terdapat dalam alam semesta ini datang dan pergi, lahir dan
mati, ada dan tiada. Sesuatu yang bisa ada dan tiada berarti
ada di dalam waktu, terkena arus waktu, jadi tidak mungkin
selamanya ada. Dengan begitu, ada masa di mana alam semesta
ini belum ada. Keberadaan alam semesta dengan demikian
bersifat kontingen (contingent being). Sangat tidak masuk
akal jika ketika alam semesta ini belum ada, belum ada
sesuatu yang niscaya ada. Dipastikan bahwa ada sesuatu yang
niscaya ada sepanjang masa. Sesuatu yang niscaya ada itu
adalah Tuhan.
d. Argumen Keempat: Kelas Kualitas ada beragam kualitas yang
melekat pada suatu obyek, mulai dari kualitas yang lebih
baik sampai pada kualitas yang lebih buruk. Penilaian
kualitas tersebut membutuhkan acuan yang paling absolut dan
sempurna. Acuan paling absolut dan sempurna itu tidak lain
adalah Tuhan.
e. Argumen Kelima : Keteraturan Perencanaan Alam semesta
berjalan secara teratur dan keteraturan itu pasti bukan
sesuam yang kebetulan. Keteraturan itu geraknya mengikuti
suatu pola, berjalan seperti sebuah anak panah menuju tujuan
tertentu yang dikehendaki pemanahnya. Pemanahnya itu adalah
Tuhan.
Meskipun pada masa ini filsafat masih dikaitkan dengan
teologi, namun filsafat sudah menemukan tingkat kemandirian
dalam hal tertentu. Penyebabnya adalah dibukanya
universitas-universitas baru, berkembangnya ordo-ordo baru,
dan disebariuaskannya karyakarya filsafat yunani. Sementara
itu, di kalangan ahli pikir Islam, pada Abad Pertengahan ini
muncul pemikir-pemikir Islam kenamaan seperti Al-Kindi, Al-
Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Bajjah, Ibn Tufail dan Ibn
Rusyd. Periode ini berlangsung pada tahun 850-1200 M, dimana
pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu
pengetahuan berkembang pesat sampai runtuhnya kerajaan Islam
di Granada (Spanyol) pada tahun 1492.
3. Zaman Renaissance (Masa Peralihan)
Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari Abad
Pertengahan ke Zaman Modem. Kebudayaan Renaissance pada
mulanya berkembang di Italia ak ibat kemaj uari dalam bidang
perdagangan dan pelayaran. Kota-kota bandar di Ttalia
seperti Genua dan Venesia, menjadi pusat monopoli dari
perdagangan antara Timur dan Barat. Hubungan antara Timur
dan Barat menambah luasnya pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan
dan filsafat Islam di Eropa Barat.
Kekuasaan kota-kota jatuh ke tangan para bankir dan
pemilik uang; kedudukan para bankir dan pemilik uang ini
seringkali memberi manfaat bagi perkembangan kesenian.
Selain itu, berkembang pula kesadaran nasional dan arti
kewarganegaraan. Dari Italia, gerakan Renaissance ini
kemudian melebarkan sayapnya ke Perancis, Belanda, Inggris,
dan akhirnya Jerman.
Kata Renaissance sendiri berarti Kelahiran Kembali.
Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang
meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah
dilahirkan kembali dalam keadaban. Di dalam kelahiran
kembali itu orang kembali kepada sumber-sumber yang murni
bagi pengetahuan dan keindahan. Dalam Zaman Renaissance ini
dunia diterima seperti apa adanya, sebab orang merasa
kerasan (athome) di dunia dan menghargai sekali kepada hal-
hal yang baik dari kehidupan ini. Hal ini diperkuat lagi
dengan banyaknya penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
penemuan-penemuan benua baru, yang mengakibatkan timbulnya
pikiran-pikiran baru di segala bidang kehidupan.
Pada zaman ini, lahir suatu gerakan intelektual dan
kesusasteraan yang bermula di Italia dan kemudian menyebar
ke segenap penjuru Eropa. Gerakan yang dimaksud adalah
humanisme. Gerakan kaum humanis ini bertujuan untuk
melepaskan diri dari belenggu kekuasaan gereja dan
membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat.
Melalui pendidikan liberal, kaum humanis mengajarkan bahwa
manusia pada prinsipnya adalah mahluk bebas dan berkuasa
penuh atas eksistensinya sendiri dan masa depannya.
Meskipun kebebasan merupakan tema terpenting dari
humanisme, tetapi kebebasan yang diperjuangkan bukan
kebebasan yang absolut, atau kebebasan sebagai antitesis
dari determinisme abad pertengahan. Kebebasan yang
diperjuangkan kaum humanis adalah kebebasan yang berkarakter
manusiawi, yaitu kebebasan manusia dalam batas-batas alam,
sejarah dan masyarakat. Istilah "humanisme" sendiri berasal
dari bahasa Latin humanitas (pendidikan manusia) yang di
dalam bahasa Yunani disebut paideia, yaitu pendidikan yang
didukung oleh manusiamanusia yang hendak menempatkan seni
liberal sebagai materi atau sarana utamanya.
Alasan utama seni liberal dijadikan sebagai sarana
terpenting dalam pendidikan pada waktu itu (disamping
retorika, sejarah, etika dan politik) adalah kenyataan bahwa
hanya dengan seni liberal manusia akan tergugah untuk
menjadi manusia, menjadi mahluk bebas yang tidak terkungkung
oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Mereka percaya bahwa
hanya dengan seni liberal manusia dapat dibangunkan dari
tidurnya yang sangat panjang pada Abad Pertengahan.
Model pendidikan ini adalah model pendidikan yang
didorong oleh semangat zaman antik (Yunani Kuno), yang
ditandai adanya kehidupan demokratis, yang pada Abad
Pertengahan dianggap sebagai semangat kaum kafir. Pada zaman
antik, ldaim atas otonomi manusia dijunjung tinggi, dan
dalam batas-batas tertentu manusia mempunyai kewenangan
sendiri dalam keterlibatannya dengan alam dan dalam
penentuan arah sejarah manusia. Sementara itu, dalam bidang
filsafat muncul kecenderungan untuk menggali akar-akar
pengetahuan (epistemologi).
Berkembangnya ilmu-ilmu alam (filsafat alam) mendorong
para filsuf untuk mempertanyakan tentang apakah sebetulnya
pengetahuan itu? Dari mana sebetulnya sumber pengetahuan?
Apakah pengetahuan berasal dari pengalaman atau dari rasio
manusia? pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam perkembangan
selanjurnya memunculkan aliran-aliran seperti rasionalisme
dan empirisme. Adapun para filsuf yang memberi sumbangan
berharga bagi perkembangan ilmu-ilmu alam pada Zaman Re-
naissance ini adalah Nicolaus Copernicus (1473-1543),
Johanes Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), dan
Francis Bacon (1561-1626).
Namun demikian, berkembangnya ilmu-ilmu alam pun
mendorong para filsuf untuk bertanya tentang hakikat
manusia. Apakah manusia itu berupa materi (alam fisik) atau
berupa jiwa? Apakah proses kimiawi dan gerak mekanis yang
terjadi pada alam juga terjadi dalam diri manusia? Atau
manusia adalah pengecualian, sehingga tidak bisa dikenai
proses kimiawi dan mekanis seperti itu? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut menimbulkan beragam jawaban.
Materialisme mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya
adalah materi, jadi tidak berbeda dari materi-materi lain
yang ada dalam alam semesta. Sebaliknya, idealisme
mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya bukan materi,
melainkan jiwa yang merupakan intisari manusia, sehingga
semua gerak-gerik badan manusia adalah bersumber dari
kekuatan yang bersifat rohani, yaitu Yang Ilahi dan jiwa
manusia.
4. Zaman Modern
Meskipun terdapat perubahan-perubahan yang begitu
asasi, Zaman Renaissance (abad ke-14 M sampai ke-I 6 M)
tidaklah secara langsung menjadi tanah subur bagi
pertumbuhan filsafat. Baru di abad ke-17 daya hidup yang
kuat, yang telah timbul pada Zaman Renaissance mendapatkan
pengungkapannya yang serasi dalam bidang filsafat Dengan
demikian, berbagai peristiwa yang terjadi pada abad ke-15
dan ke-I 6 merupakan tahap persiapan bagi pembentukan
filsafat modem pada abad ke-17 yang diawali Descartes (1597-
1650), yang ingin menunjukkan kepada manusia jalan menuju
suatu kepastian.
Obsesi Descartes adalah menjawab pertanyaan tentang
bagaimana ilmu-ilmu nonmatematik dapat memiliki kepastian
yang sama dengan hasil-hasil yang diraih oleh geometri
analitis. Jawaban Descartes adalah: dengan menerapkan cara
berpikir geometrispada seluruh bidangpengetahuan, tanpa
terkecuali. Cara seperti ini, menurut Descartes, bisa
diterapkan pada ilmu-ilmu lainnya diluar geometri, yang
dimulai dari data-data yang jelas, tegas dan tidak bisa
diragukan lagi. Bagi Descartes, jalan menuju kepastianitu
adalah dengan meragukan segala hal, dan kemudian mengambil
sebagai aksioma apa pun yang terbukti tidak dapat
(diragukan. Bagi Descartes, hanya ada satu hal yang tidak
dapat diragukan. Mengenai satu hal ini tidak ada seorang pun
yang dapat menipu, yaitu bahwa aku ragu-ragu (aku meragukan
segala sesuam). Aku ragu-ragu, atau aku berpikiran oleh
karena aku berpikir, maka aku ada (cogito ergo sutn). Inilah
pengetahuan langsung yang disebut kebenaran filsafat yang
pertama (primumphihsophicum).
Dalam membangun filsafatnya, Descartes membuat
pertanyaanpertanyaan sebagai patokan dalam menentukan
kebenaran dan keluar dari keraguan yang ada. Adapun
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Descartes adalah:
a) Apakah mungkin memperoleh suatu pengetahuan yang benar?
b) Metode apa yang digunakan untuk mencapai pengetahuan
pertama?
c) Bagaimana memperoleh pengetahuan-pengetaliuan yang
selanjutnya?
d) Apa tolak ukur kebenaran pengetahuan?
Selanjutnya, untuk mendapat pengetahuan yang pasti dan
jelas, Descartes mengajukan empat prinsip berikut ini:
a. Jangan pernah menerima ide sebagai hal yang benar,
kecuali ide yang diyakini kebenarannya itu sudah tidak
dapat diragukan lagi.
b. Untuk mencapai kesimpulan yang pasti, pilah-pilahlah
suatu persoalan menjadi bagian-bagian kecil dan
sederhana, lalu ujilah tiap-tiap bagian tersebut secara
hati-hati dan menyeluruh.
c. Pengujian dilakukan dari bagian paling sederhana sampai
bagian paling kompleks secara bertahap; jangan pernah
melompati satu tahapan pun dalam pengerjaannya.
d. Catatlah secara detil dan menyeluruh setiap hasil
pengujian tersebut dan jangan sampai ada yang terlewat
atau tercecer sedikit pun.
Selain Descartes, dua filsuf lainnya yang turut memberi
sumbangan bagi perkembangan aliran rasionalisme adalah
Blaise Pascal (1623-1662) dan Baruch Spinoza (1632-1677).
Sementara itu, para pemikir di Inggris seperti Thomas
Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704), bergerak ke
arah berbeda dengan tema yang dirintis Descartes. Mereka
lebih memilih mengikuti jejak Francis Bacon, yaitu aliran
empirisme, yang memberi tekanan pada pengalaman sebagai
sumber pengetahuan. John Locke berkeyakinan bahwa semua
pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman dan alat-
alat indera (penglihatan, penciuman, peraba, dan lain
sebagainya) merupakan pinta masuk bagi pengalaman tersebut
Menurut Locke, semua pengetahuan manusia pada dasarnya
merupakan ide-ide yang disajikan pikiran manusia melalui
pengalaman yang pernah dialaminya. Ada dua tingkatan ide,
yaitu yang sederhana dan yang kompleks.
Ide-ide sederhana adalah berupa ide-ide yang langsung
diperoleh melalui indera, seperti warna merah, rasa manis,
bau harum, suara merdu, dan lain sebagainya. Sedangkan ide-
ide yang kompleks adalah ide-ide hasil penggabungan dari dua
atau lebih ide-ide yang sederhana yang diolah oleh pikiran.
Misalnya konsep kuda, kursi, binatang, manusia, lakilaki,
perempuan, dan lain sebagainya. Ide-ide kompleks pun tidak
selalu harus nyata. Contohnya adalah kuda terbang, yang
merupakan gabungan antara kuda dan hewan lain yang punya
sayap.
Memasuki abad ke-18, dimulailah suatu zaman baru yang
berakar pada Renaissance serta yang mewujudkan buah pahit
rasionalisme dan empirisme. Abad ke-I 8 disebut juga Zaman
Pencerahan (Aufklarung). Menurut Immanuel Kant, Zaman
Pencerahan adalah zaman dimana manusia keluar dari keadaan
tidak akil balik, yang disebabkan karena kesalahan manusia
sendiri. Kesalahan itu adalah akibat dari keengganan manusia
menggunakan akalnya. Dahulu, filsafat mewujudkan suatu
pemikiran yang hanya menjadi hak istimewa beberapa ahli
saja, tetapi sekarang orang berpendapat, bahwa seluruh umat
manusia berhak turut menikmati hasil-hasil pemikiran
filsafat Gerakan Zaman Pencerahan sendiri berasal dari
Inggris. Hal ini disebabkan karena pada akhir abad ke-17 di
Inggris berkembang suatu tata negara yang liberal. Dari
Inggris, gerakan ini dibawa ke Perancis dan dari sana
tersebar ke seluruh Eropa.
Tokoh-tokoh yang terkenal sebagai ahli pikir di Zaman
Pencerahan ini di antaranya adalah: George Berkeley dan
David Hume (keduanya dari Inggris), Voltaire danjean Jacques
Rousseau (keduanya dari Perancis), dan Immanuel Kant
(Jerman). Tradisi empirisme yang telah dibangun oleh Thomas
Hobbes dan John Locke pada abad ke-17 kemudian dilanjutkan
oleh George Berkeley. Namun demikian, kesimpulan-kesimpulan
yang diajukan oleh Berkeley lebih tajam dan bahkan saling
bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan Locke.
Pemikiran Locke dan Berkeley kemudian dilanjutkan oleh
filsuf Zaman Pencerahan lainnya, yaitu David Ilume (1711 -
1776), yang corak pemikirannya cenderung analitis, kritis
dan skeptis. Pendapat yang diajukan oleh Ilume berpangkal
pada keyakinan bahwa hanya kesan-kesan yang dapat bersifat
pasti, jelas, dan tidak dapat diragukan. Hume sampai pada
kesimpulan bahwa dunia hanya terdiri dari kesan-kesan yang
terpisah-pisah, yang tidak dapat disusun secara obyektif dan
sistematis, karena di antara kesan-kesan itu tidak ditemukan
hubungan sebab-akibat.
Dalam perkembangan selanjutnya, pertentangan tajam
antara rasionalisme dan empirisme didamaikan oleh Immanuel
Kant Pertentangan tersebut mendorong Kant untuk memikirkan
unsur-unsur mana di dalam pemikiran manusia yang berasal
dari pengalaman dan unsur-unsur mana yang telah terdapat di
dalam akal manusia. Kant bermaksud membedakan antara
pengenalan yang murni dan yang tidak murni, yang tidak
mengandung kepastian. Kant ingin membersihkan pengenalan
dari keterikatannya kepada segala penampakan yang bersifat
sementara. Dengan demikian, filsafatnya dimaksudkan sebagai
sintetis apriori, (a) Pengetahuan yang analitis aposteriori,
dan (b) Pengetahuan yang sintetis aposteriori.
Pengetahuan apriori adalah pengetahuan yang tidak
tergantung pada adanya pengalaman atau yang ada sebelum
pengalaman. Pengetahuan aposterioriterjadi sebagai akibat
adanya pengalaman. Pengetahuan analitis merupakan hasil
analisa, sementara pengetahuan sintetis merupakan hasil
keadaan yang mempersatukan dua hal yang biasanya terpisah.
Memasuki abad ke-19, filsafat menjadi terpecah-pecah
menjadi filsafat Jerman, filsafat Perancis, filsafat
Inggris, filsafat Amerika dan filsafat Rus-sia. Selain itu,
pada masa ini ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang
pesat, terutama di bidang geologi, biologi dan kimia
organis. Selain itu, kehadiran mesin-mesin produksi
findustrialisasi) telah mengubah struktur masyarakat dan
memberikan kepada manusia suatu konsepsi baru mengenai kuasa
dalam hubungannya dengan alam semesta. Dalam ranah
pcrnikiran, jika di abad ke-I 7 dikuasai pemikiran Galileo
dan Newton, maka abad ke-19 dipengamhi secara signifikan
oleh Charies Darwin. Beberapa aliran filsafat yang turut
memberi warna pada abad ini di antaranya Idealisme (J.C.
Fiehte, F.WJ. Schelling, dan G.WF. Hegel), Positivisme
(Auguste Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer),
Materialisme (LudwigFeurbach dan Kari Marx), dan
Eksistensialisme (Soren Kierkegaard dan Friedrich
Nietzsche).
5. Zaman Kontemporer
Filsafat kontemporer, yang diawali pada awal abad ke-
20, ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat
beragam dan kaya. Mulai dari analisis bahasa, kebudayaan
Etika dan Filsafat Komunikasi 23 (antara lain,
postmodemisme), kritik sosial, metodologi (fenomenologi,
hermeneutika, strukturalisme), filsafat hidup
(eksistensialisme), filsafatilmu, sampai filsafat tentang
perempuan (feminisme).
Tema-tema filsafat yang banyak dibahas oleh para filsuf
dari periode ini antara lain tentang manusia dan bahasa
manusia, ilmu pengetahuan, kesetaraan gender, kuasa dan
struktur yang mengungkung hidup manusia, dan isu-isu aktual
yang berkaitan dengan budaya, sosial, politik, ekonomi,
teknologi, moral, ilmu pengetahuan, dan hak asasi manusia.
Ciri lainnya adalah filsafat dewasa ini ditandai oleh
profesionalisasi disiplin filsafat Maksudnya, para filsuf
bukan hanya profesional di bidangnya masing penyadaran atas
kemampuan-kemampuan rasio secara obyektif dan menentukan
batas-batas kemampuannya. Kant membagi realitas ke dalam dua
bagian, yaitu dunia fenomenal (phertomnon, atau dunia
sebagaimana menampakkan diri pada pengamat) dan dunia
noumenal (noumenon, atau dunia yang sesungguhnya, yang
berada di dalam diri realitas itu sendiri). Meskipun dunia
noumenal itu ada, tetapi keberadaannya di luar pengetahuan
manusia dan tidak dapat dijangkau. Kant memberinya nama
Ding-an-sich (ada-dalam-dirinya-sendiri).
Pengetahuan manusia terbatas hanya pada dunia
fenomenal, dunia pengalaman. Manusia tak mengetahui apa pun
diluar dunia pengalaman. Dalam dunia fenomenal, pengetahuan
merupakan campuran dari apa yang diterima (dialami) dari
luar dengan proyeksi-proyeksi dan harapan-harapan: mang dan
waktu adalah "kondisi subyektif dari sensibilitas" atau
"bentuk dari intuisi". Di pihak lain, pemahaman
menyumbangkan prinsip-prinsip organisasi pada kualitas
murni, yaitu prinsipprinsip yang diberi nama "kategori-
kategori" atau "konsep-konsep murni" seperti kesatuan,
pluralitas, substansi, sebab-akibat, kemungkinan, atau
keniscayaan.
Bentuk-bentuk intuisi dan konsep-konsep murni tersebut
merupakan bahan-bahan formal pengalaman. Dengan filsafatnya,
Kant bermaksud memugar sifat obyektivisme dunia dan ilmu
pengetahuan. Agar tujuan tersebut tercapai, orang harus
menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan sifat
sepihak empirisme Rasionalisme beranggapan telah menemukan
kunci bagi pembukaan realitas pada diri subyeknya, lepas
dari segala pengalaman, sementara empirisme beranggapan
bahwa pengenalan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman.
Menurut Kant, syarat dasar bagi segala ilmu pengetahuan
adalah :
(a) bersifat umum dan bersifat perlu mudak; dan
(b) memberi pengetahuan yang baru. Dalam konteks ini,
empirisme memberikan putusan-putusan yang sintetis, dan
karenanya tidak mungkin empirisme memberi pengetahuan yang
bersifat umum dan perlu mutlak. Sebaliknya, rasionalisme
memberikan putusan-putusan yang bersifat analitis, dan
karenanya tidak mungkin memberi pengetahuan yang baru.
Dengan demikian, baik empirisme maupun rasionalisme tidak
memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh ilmu pengetahuan.
Kant sendiri membedakan empat macam pengetahuan yang ia
golongkan sebagai berikut:
(1) Pengetahuan yang analitis apriori;
(2) Pengetahuan yang masing, tetapi juga telah
membentuk komunitas-komunitas dan asosiasi-asosiasi
profesional di bidang-bidang tertentu berdasarkan pada minat
dan keahlian masing-masing.
Oleh sebab itu, dewasa ini ada batasbatas yang jelas
untuk menentukan mana filsuf yang memiliki kualifikasi dan
mana yang tidak. Profesionalisasi di bidang filsafat pun
tampak dengan jelas dari munculnya jurnaljurnal terkemuka
dalam bidang filsafat seperti Philosophical Review, Journal
of Philosophy, Philosophy and Phenomenological Research,
Philosophical'Quarterly, dan lain sebagainya. Beberapa
aliran filsafat yang berkembang pada masa kontemporer ini di
antaranya adalah Pragmatisme (William James dan John Dewey),
Fenomenologi (Edmund Husseri, Max Scheler, dan Martin
Heidegger), Eksistensialisme (Jean Paul Sartre, Kari
Jaspers, Gabriel Marcel, Albert Camus, dan Simone de
Beauvoir), Strukturalisme (Ferdinand de Saussure, Claude
Levi-Strauss, Mchel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes,
dan Jacques Derrida), Positivisme Logis (Rudolph Carnapp,
Alfred Ayer, CL Stevenson, Gilbert Ryle, Susan Stebbing,
John Wisdom, Bertrand Russell, dan Ludwig Wittgen-stein),
PostPositivisme (Kad R. Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend, dan
Richard Rony), dan Pernikiran Kritis Mazhab Frankfurt (Max
Horkhedmer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jurgen
Habermas, dan Erich Fromm).
BUKU ; KHAERUL AZMI, 2013, FILSAFAT ILMU KOMUNIKASI, EMPAT
PENA PUBLISHING, BANTEN