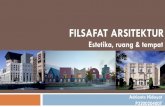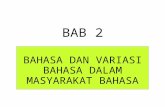Filsafat Bahasa
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Filsafat Bahasa
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Filsafat sebagai buah pemikiran manusia, yang pada
hakekatnya adalah makhluk yang berpikir, terus
berkembang secara perlahan tapi pasti, yaitu untuk
menemukan suatu kebenaran yang hakiki.
Filsafat merupakan induk dari semua bidang ilmu
khusus. Dan tentunya sejalan dengan perkembangan
peradaban manusia, filsafat sebagai buah pikiran itupun
berkembang sesuai dengan fitrah manusia yang selalu
berubah dan dinamis. Tentu saja diperlukan sarana yang
menampung semua buah pemikiran tersebut agar dapat
disosialisasikan atau sekedar diekspresikan. Sarana
yang sangan fital ini adalah bahasa.
Di bumi ini semua manusia mempunyai bahasa.
Pemilikan bahasa konseptual membedakan manusia dari
makhluk lainnya di alam semesta ini. Dalam kehidupan
manusia, fungsi bahasa yang paling dasar adalah
menjelmakan pemikiran konseptual ke dalam dunia
kehidupan.
Pada abad ke 20 perhatian terhadap persoalan-
persoalan filsafat yang bertumpu pada bahasa semakin
berkembang. Penyelidikan tentang arti, prinsip-prinsip
serta aturan bahasa merupakan problem yang fundamental
dalam filsafat. Karena dengan bahasa, para filsuf dapat
mengungkapkan pemikiran filosofisnya.
Memberi nama adalah langkah pertama untuk
mendapatkan pengetahuan. Ketika kita mendapat pelajaran
baru tentang suatu benda misalnya, kita tidak akan tahu
benda apakah itu, kecuali jika kita dapat menamakannya,
mengklasifikasikannya serta menempatkannya dalam suatu
konteks yang berarti. Dengan kata lain, bahasa adalah
alat untuk mengungkapkan pikiran, ekspresi, serta
perasaan manusia.
Dalam buku Filsafat Analitika Bahasa, Dr. Kaelan,
MS., mengungkapkan bahwa mungkin saja diantara
problema-problema besar yang dihadapi manusia sekarang
ini berasal dari kekaburan yang terdapat dalam bentuk-
bentuk dan pemakaian-pemakaian linguistik kita, dan
bahwa penjelasan tentang bahasa akan memecahkan
problema-problema tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di
atas, maka dalam makalah ini penulis mengambil rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Apakah hubungan filsafat dengan bahasa ?
2. Apakah yang dimaksud dengan Filsafat Analitika
Bahasa ?
3. Apa saja aliran-aliran dalam filsafat analitik ?
4. Apakah pengaruh filsafat analitika bahasa terhadap
ilmu pengetahuan ?
C. TUJUAN
Penulisan laporan buku ini bertujuan untuk :
1. Menjelaskan apa peran bahasa dalam perkembangan
filsafat
2. Menjelaskan apa peran filsafat dalam bahasa
3. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat
analitika bahasa
4. Memaparkan aliran-aliran filsafat analitik
5. Mengkaji pengaruh filsafat analitika bahasa
terhadap ilmu pengetahuan
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Makalah ini disusun dengan organisasi penulisan
sebagai berikut :
Bab I memuat latar belakang penulisan, rumusan
masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.
Bab II memuat pembahasan masalah
Bab III memuat kesimpulan
BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
A. HUBUNGAN FILSAFAT DAN BAHASA
Sebagaimana telah disampaikan pada bab I latar
belakang penulisan, bahwa bahasa sangat berperan
penting dalam menerjemahkan buah pemikiran manusia
pada umumnya, dan para filsuf pada khususnya.
Alwasilah seperti yang dikemukakan oleh Sauri
(2006 : 33) mengemukakan bahwa bahasa memiliki ciri-
ciri umum sebagai berikut :
a. Sistematik, yaitu bahasa mempunyai aturan atau
pola antara lain sistem bunyi dan sistem makna
b. Arbitrer (manasuka), artinya bahasa itu dipilih
secara acak tanpa alasan atau manasuka, tidak ada
hubungan logis dengan kata-kata sebagai symbol
c. Ucapan / vokal, artinya bahasa itu ujaran, berarti
media bahasa yang terpenting adalah dengan bunyi-
bunyi
d. Simbol, bahwa bahasa itu simbol dari perasaan,
keinginan, dan harapan
e. Bahasa itu mengacu kepada dirinya, artinya bahasa
itu mampu digunakan untuk menganalisis bahasa itu
sendiri
f. Manusiawi, artinya bahasa itu adalah kekayaan yang
hanya dimiliki oleh manusia
g. Komunikasi, artinya bahasa itu alat komunikasi dan
interaksi antar manusia dan menjadi pelekat dalam
menyatupadukan keluarga, masyarakat, dan berbagai
kegiatan sosialisasi
Intinya adalah bahwa bahasa merupakan media wacana
segala ilmu dan sekaligus metabudaya.
Selanjutnya Devitt (1987 : 124) menyebutkan adanya
empat lingkaran makna dalam bahasa, yaitu :
1. Makna pembicara dijelaskan oleh isi muatan pikiran
2. Isi itu dijelaskan oleh makna kalimat pikiran
3. Makna itu dijelaskan oleh makna konvensional
4. Makna konvensional dijelaskan oleh makna pembicara
Untuk menemukan makna, filsafat memberikan
analisis sehingga makna tersebut dapat diterima
secara logis, objektif dan sistematis.
Sedangkan peran filsafat terhadap bahasa adalah
bahwa analisis filsafat merupakan salah satu metode
yang digunakan oleh para filosof dan ahli filsafat
dalam memecahkan problematika kebahasaan. Aliran-
aliran dalam filsafat dapat mewarnai pandangan para
ahli bahasa dalam mengembangkan teori-teorinya.
B. PERKEMBANGAN FILSAFAT ANALITIS
Filsafat setidaknya mengalami 4 (empat) fase
perkembangan pemikiran filsafat, yaitu :
1. Kosmosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang
meletakan alam sebagai objek pemikiran dan wacana
filsafat, yang terjadi pada zaman kuno.
2. Teosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang
meletakan Tuhan sebagai pusat pembahasan filsafat,
yang berkembang pada zaman abad pertengahan.
3. Antroposentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang
meletakan manusia sebagai objek wacana filsafat,
hal ini terjadi dan berkembang pada zaman modern.
4. Logosentris, yaitu fase perkembangan pemikiran
filsafat yang meletakan bahasa sebagai pusat
perhatian pemikiran filsafat, yang berkembang
setelah abad modern sampai sekarang.
Perhatian filsafat terhadap bahasa sebenarnya
telah berlangsung sejak zaman pra Sokrates, yaitu
ketika Herakleitos membahas tentang hakikat segala
sesuatu termasuk alam semesta. Menurut Herakleitos,
dalam dunia manusiasi ini kemampuan bicara menduduki
tempat sentral. Dalam pengertian ini Herakleitos
mengungkapkan bahwa “kata” (logos) bukan semata-mata
gejala antropologi.
Pada zaman Sokrates, bahasa bahkan menjadi pusat
perhatian filsafat ketika retorika menjadi medium
utama dalam dialog filosofis.
Pada abad pertengahan kekhusukan manusia dalam
mengagungkan sang Maha Kuasa pun diungkapkan melalui
bahasa. Bahkan Thomas Aquinas telah mengangkat
teologi ke tingkat ilmiah filosofis, sehingga mampu
menjembatani antara realitas Tuhan yang bersifat
adikodrati dengan realitas makhluk yang bersifat
terbatas.
Filsafat abad modern memberikan dasar-dasar yang
kokoh terhadap timbulnya filsafat analitika bahasa.
Aliran rasionalisme, empirisme, imaterialisme dan
kritisisme Immanuel Kant menjadi sangat penting
pengaruhnya terhadap tumbuhnya filsafat analitika
bahasa terutama dalam pengungkapan realitas segala
sesuatu melalui ungkapan bahasa.
Secara terminologi istilah analitika bahasa baru
dikenal dan popular pada abad XX, namun demikian
pengertian filsafat analitik adalah pemecahan dan
penjelasan problem-problem serta konsep-konsep
filsafat melalui analisis bahasa, maka sebenarnya
berdasarkan isi materi dan metodenya filsafat
analitik bahasa itu telah berkembang sejak zaman
Yunani. Secara diakronis, filsafat analitika bahasa
pada abad XX ini tidak terbatas pada timbulnya
aliran-aliran filsafat di Inggris saja, namun lebih
luas antara lain di Jerman selain mempengaruhi
tumbuh berkembangnya aliran positivism logis dan
lingkungan Wina, juga terhadap filsuf-filsuf
kontemporer yang menggunakan analisis bahasa melalui
gejala-gejala untuk sampai pada suatu kebenaran yang
hakiki.
C. FILSAFAT SEBAGAI ANALISIS BAHASA
Analitika bahasa adalah suatu metode yang khas
dalam filsafat untuk menjelaskan, menguraikan dan
menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis.
Aliran filsafat analitika bahasa memandang bahwa
problema-problema filosofis akan dapat menjadi jelas
apabila menggunakan analisis terminologi gramatika,
bahkan kalangan filsuf analitika bahasa menyadari
banyak ungkapan-ungkapan filsafat yang sama sekali
tidak menjelaskan apa-apa. Berdasarkan hal
tersebutlah banyak kalangan filsuf, terutama tokoh
filsafat analitika bahasa menyatakan bahwa tugas
utama filsafat adalah analisis konsep-konsep.
D. ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT ANALITIK
Pada dasarnya perkembangan filsafat analitika
bahasa itu meliputi tiga aliran yang pokok yaitu :
Atomisme logis (logical atomism)
Positivisme logis (logical positisme) atau
biasa disebut empirisme logis (logical
empirism)
Filsafat bahasa biasa (ordinary language
philosophy)
Atomisme logis (logical atomism)
Pusat dari gerakan pemikiran filsafat ini yaitu di
Cambridge, Inggris. Perintisnya adalah G.E. Moore
(1873-1958), dengan tokoh-tokoh utama yaitu Bertrand
Russell (1872-1970) dan Ludwig Wittgestein (1889-
1951).
Istilah atomisme logis sendiri dicetuskan oleh
Bertrand Russel dalam salah satu artikelnya yang
dimuat dalam “Contemporary British Philosophy’ yang
terbit tahun 1924, ia mengatakan sebagai berikut :
“I hold that logic is what is fundamental in philosophy and
that schools should be characterized rather by their logic than
by their metaphysics. My own logic is atomic and it is this
aspect upon which I shoud mish to lay stress. Therefore I
prefer to describe my philosophy as logicat atomism rather
than as realism. Whether with or without some prefixed
adjective”
“Saya menganggap bahwa logika itu adalah apa
yang fundamental di dalam filsafat, dan bahwa
mahzab-mahzab (aliran-aliran) itu seharusnya
diwarnai oleh logikanya daripada oleh
metafisikanya. Logika saya sendiri bersifat
atomis, dan aspek (segi) inilah yang ingin
saya tekankan. Oleh karena itu lebih suka
menyebut filsafat saya dengan nama atomisme
logis daripada realisme, baik dengan atau
tanpa awalan kata sifat.”
Ia menamakan pemikiran filsafatnya ‘atomisme
logis’ karena atom-atom yang ingin dicapai Russell
sebagai hasil analisis terakhir bukan merupakan
suatu atom fisik, melainkan atom logis.
Misalnya dalam kalimat :
1. Lions are yellow
2. Lions are real
Kedua kalimat itu memiliki struktur gramatikal
yang sama namun keduanya memiliki struktur logis
yang berbeda.
‘Lions’ pada kalimat 1 dan 2 bersama-sama
berfungsi sebagai subyek, adapun ‘yellow’ dan
‘real’ pada kedua kalimat tersebut sama-sama
merupakan predikat, jadi secara gramatikal
memiliki struktur yang sama, namun struktur
logisnya tidak sama.
Menurut Russell bahwa dua pengertian memiliki
suatu formulasi logis yang sama bilamana dua hal
itu mengandung kesesuaian. Misalnya X dan Y
memiliki formulasi logis yang sama jika unsur X
mengandung kesesuaian dengan unsur Y, sehingga
akibat atau lawan bagi Y dapat digantikan pada X.
Misalnya Sokrates dan Aristoteles memiliki
formulasi logis yang sama, karena keduanya adalah
seorang filsuf.
Melalui penentuan formulasi logis ini nampaknya
Russell berhasil memecahkan sejumlah paradoks yang
seakan-akan tampak mustahil untuk dikatakan
sebagai benar yang telah membingungkan para filsuf
Yunani.
Selain Russell, George Edward Moore, seorang
filsuf kelahiran Upper Nortwood London, juga
memiliki pengaruh yang besar terhadap aliran
filsafat atomisme logis.
Russell dan Moore sama-sama berpendapat bahwa
tugas filsafat adalah memberikan analisis konsep-
konsep dan oleh karena konsep-konsep itu
diungkapkan melalui bahasa, maka analisis bahasa
memegang peranan penting.
Positivisme logis (logical positisme)
Aliran positivisme logis berkembang pada tahun
1922 di Wina oleh perintisnya yaitu Moritz Schlik
(1882-1936). Pandangan ini menguraikan tentang
pendirian filosofis kelompok lingkungan Winga yang
sangat diwarnai oleh ilmu-ilmu pengetahuan positif.
Anggota-anggola lingkungan Wina ini antara lain :
- Kurt Goedel, Hans Hahn, Karl Menger, ahli
matematika
- Philip Frank, ahli fisika
- Rudolf Carnap, ahli matematika dan fisika
- Beberapa mahasiswa antara lain : Frederich
Wismann, Herbert Feigl
Aliran ini sangat dipengaruhi oleh tradisi
empirisme yang melanjutkan garis tegas pada
leluhurnya yaitu David Hume, John Stuart Mill dan
Ernest Mach.
Positivisme logis menggunakan teknik analisis
untuk dua macam tujuan :
1. Untuk menghilangkan metafisika.
Karena ungkapan-ungkapan metafisis pada hakikatnya
tidak menyatakan apa-apa sehingga bersifat
‘nirarti’ atau tidak bermakna.
2. Menggunakan teknik analisis demi penjelasan ilmiah
dan bukan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan
fakta ilmiah.
Sebab dengan analisis filsafat kita tak dapat
menentukan apakah sesuatu itu nyata (real), tetapi
hanya apa artinya apabila kita menyatakan bahwa
sesuatu itu nyata.
Secara prinsip positivisme logis menerima konsep-
konsep atomisme logis terutama dalam hal analisis
logis melalui bahasa, walaupun menolak visi dasar
metafisisnya.
Aliran ini terutama memperhatikan dua masalah,
yaitu :
1. Analisis pengetahuan
2. Pendasaran matematika dan ilmu pengetahuan alam,
demikian juga terhadap psikologi dan sosiologi
Menurut aliran ini filsafat tidak memiliki suatu
wilayah ilmiah sendiri yang terletak di samping
suatu wilayah lain yang menjadi objek ilmu
pengetahuan. Tugas filsafat adalah analisis logis
terhadap pengetahuan ilmiah.
Atas dasar pemikiran tersebut maka kaum
positivisme logis menentukan sikap bahwa agar tidak
terjadi kekacauan maka analisis terhadap bahasa yang
digunakan dalam ilmu pengetahuan dalam filsafat
adalah langkah yang paling tepat. Hal itu didasarkan
pada suatu kenyataan bahwa hakikat bahasa adalah
menggambarkan realitas dunia.
Filsafat bahasa biasa (ordinary language
philosophy)
Berkembangnya konsep pemikiran filsafat analitik
sebagai reaksi ketidakpuasan dunia pemikiran
filsafat pada saat itu yang didominasi oleh tradisi
idealism terutama kalangan teolog, yang sangat
mengagungkan pentingnya metafisika.
Para tokoh filsafat analitika bahasa menyadari
bahwa dalam kenyataannya banyak problem-problem
filsafat dapat diselesaikan melalui analisis bahsa.
Para tokoh ini memusatkan perhatian pada aspek
semantic bahasa, sehingga melalui kategori-kategori
logika mereka menentukan bahasa yang berkeyakinan
kuta menyatakan bahwa berdasarkan logika bahasa
ungkapan-ungkapan metafisika dari kalangan penganut
idealism terutama bidang teologi, etika, aksiologi,
estetika dan terutama ontology pada hakikatnya tidak
bermakna.
Philosophical Investigations, yang merupakan
konsep pemikiran filsafat Wittgenstein, adalah suatu
bentuk filsafat biasa yang paling kuat. Esensi dari
pandangannya adalah bahwa :
“makna sebuah kata itu adalah penggunaannya dalam
bahasa dan bahwa makna bahasa itu adalah
penggunaannya di dalam hidup”
Ada dua hal yang dikemukakan oleh Wittgenstein
berkaitan dengan bahasa filsafat, yaitu :
1. Kekacauan bahasa filsafat timbul karena penggunaan
istilah atau ungkapan dalam bahasa filsafat yang
tidak sesuai dengan aturan permainan bahasa.
2. Adanya kecenderungan untuk mencari pengertian yang
bersifat umum dengan merangkum pelbagai gejala
yang diperkirakan mencerminkan sifat keumumannya.
Kelemahan yang seperti ini menurut Wittgenstein
disebut dengan istilah “Craving for Generality”
yaitu suatu kecenderungan untuk mencari sesuatu
yang umum pada semua satuan-satuan kongkrit
(entities) yang diletakkan di bawah istilah yang
bersifat umum.
Filsafat bahasa biasa yang mendasarkan pada suatu
konsep bahwa masalah-masalah filsafat dapat
diselesaikan dan dijelaskan melalui analisis bahasa.
Mereka lazimnya mendasarkan bahwa bahasa biasa,
yaitu bahasa sehari-hari pada hakikatnya telah cukup
untuk melakukan analisis filsafat.
Namun menurut Ryle perlu dibedakan antara
‘penggunaan dari bahasa biasa’ (the use of ordinary
language) dan ‘penggunaan bahasa yang biasa’ (the
ordinary linguistic usage), dan antara ‘penggunaan
yang biasa dari ungkapan’ (the ordinary use of the
expression).
Bilamana kita membahas penggunaan bahasa biasa,
maka perlu diperjelas pengertian ‘luar biasa’,
‘esoteris’, dan ‘teknis’, ‘puitis’, ‘notasional’
atau bahkan yang dimaksud dengan ‘bahasa kuno’.
Pengertian ‘biasa’ (ordinary) dapat berarti ‘umum’
(common) atau yang sedang berlangsung (current),
bahasa pergaulan sehari-hari (colloquial), atau
bahasa harian, bahasa yang sederhana (vernaculler),
bahasa alamiah (natural language) dan hal inilah
yang harus dijernihkan dalam penggunaan bahasa.
Filsafat bahasa biasa menurut Ryle pada hakikatnya
memperhatikan penggunaan yang biasa dari bahasa,
atau penggunaan bahasa yang baku, standar, dan
bukannya penggunaan bahasa yang dipakai dalam
komunikasi sehari-hari (colloquial language).
Oleh karena itu tugas filsafat adalah berkaitan
dengan analisis penggunaan yang biasa dari ungkapan-
ungkapan tertentu dan bukannya menganalisis bahasa
yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
E. PENGARUH FILSAFAT ANALITIK TERHADAP ILMU PENGETAHUAN
Lingkungan Wina berpendapat bahwa filsafat tidak
dapat diharapkan untuk memecahkan masalah-masalah,
melainkan hanya menganalisis masalah-masalah dan
dengan itu menjelaskannya.
Schlick pernah mengatakan bahwa filsafat tidak
mempunyai tugas lain, kecuali menjelaskan kata-kata
serta ucapan-ucapan dan dengan demikian
menyingkirkan ucapan-ucapan yang tidak bermakna.
Ilmu pengetahuan memverifikasi ucapan-ucapan,
sedangkan filsafat meneropong makna ucapan-ucapan.
Tentunya hal ini sekaligus mempertegas kenyataan
bahwa filsafat analitika bahasa sangat diperlukan
untuk memaparkan makna-makna ucapan yang ada
sehingga tidak terjadi kekaburan dalam menerjemahkan
teori-teori ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh
para ilmuwan.
BAB III
KESIMPULAN
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
Bahasa sangat berperan penting dalam menerjemahkan
buah pemikiran manusia pada umumnya, dan para filsuf
pada khususnya.
Bahasa merupakan media wacana segala ilmu dan
sekaligus metabudaya.
Dalam perkembangannya filsafat terbagi atas 4 (empat)
fase, yaitu :
1. Kosmosentris, yaitu fase pemikiran filsafat
yang meletakan alam sebagai objek pemikiran dan
wacana filsafat, yang terjadi pada zaman kuno.
2. Teosentris, yaitu fase pemikiran filsafat yang
meletakan Tuhan sebagai pusat pembahasan filsafat,
yang berkembang pada zaman abad pertengahan.
3. Antroposentris, yaitu fase pemikiran filsafat
yang meletakan manusia sebagai objek wacana
filsafat, hal ini terjadi dan berkembang pada zaman
modern.
4. Logosentris, yaitu fase perkembangan pemikiran
filsafat yang meletakan bahasa sebagai pusat
perhatian pemikiran filsafat, yang berkembang
setelah abad modern sampai sekarang.
Analitika bahasa adalah suatu metode yang khas dalam
filsafat untuk menjelaskan, menguraikan dan menguji
kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis.
Aliran-aliran filsafat analitik terdiri atas 3 (tiga)
aliran, yaitu :
o Atomisme logis (logical atomism)
o Positivisme logis (logical positisme) atau biasa
disebut empirisme logis (logical empirism)
o Filsafat bahasa biasa (ordinary language philosophy)
Hubungan antara ilmu pengetahuan dengan bahasa pada
umumnya adalah bahwa Ilmu pengetahuan memverifikasi
ucapan-ucapan, sedangkan filsafat meneropong makna
ucapan-ucapan.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. (2006). Filsafat Analitika Bahasa.
Yogyakarta : Paradigma
Sauri, S. (2006). Pendidikan Berbahasa Santun.
Bandung :