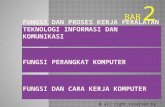BAB II - PROPOSAL
-
Upload
univpancasila -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of BAB II - PROPOSAL
6
UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS FARMASI
PROPOSAL SKRIPSI
UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN UJI
TOKSISITAS PADA EKSTRAK KENTAL DAN
KERING ETANOL BERBAGAI KONSENTRASI DARI
DAUN KELADI TIKUS (Typhonium flagelliforme LODD)
Diajukan oleh:
Erma Wanda Mundari
NPM : 2010210090
UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS FARMASI
JAKARTA
Oktober 2013
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Botani
1. Klasifikasi tanaman
Nama Latin : Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Magnoliophytina
Kelas : Liliaceae/Monocotyledone
Bangsa : Arales
Suku : Araceae
Marga : Typhonium
Spesies : Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume
2. Sinonim
Typhonium divaricatum (Lodd.) Blume
3. Nama Umum
Keladi tikus, Rodent tuber (1,17,18)
Gambar II.1. Typhonium flagelliforme
8
4. Nama daerah
Melayu : Bira kecil, Daun panta susu, Kalamoyang
Sunda : Ileus, Ki babi
Jawa : Tringgiling mentik
Ternate : Gofu sepa
5. Nama asing
Inggris : Rodent tuber
Cina : Sek su (1,10)
6. Deskripsi botani
Habitu : Tanaman keladi tikus ini berupa herba dengan tinggi
10 – 45 cm, tanpa ada batang diatas tanah, tumbuh
berumpun diantara rumput-rumput liar, tanaman ini
menyukai tanah yang gembur, lembab serta teduh.
Batang : Batang daunnya berwarna hijau keputihan.
Daun : Berwarna hijau halus, sedangkan ujung daun
berbentuk ujung anak panah yang membesar.
Bunga : Bunga keladi tikus ini berkelompok, bunganya
menyerupai tikus beserta ekor panjangnya pada
waktu mekar berwarna putih.
Akar : Melebar seperti umbi (tuber), berwarna putih (1,
17,18).
7. Ekologi dan penyebaran
Di Jawa tumbuhan mulai dari dataran rendah hingga lebih kurang 1000
m di atas permukaan laut ditempat terbuka (terkena sinar matahari)
maupun ditempat yang agak rindang dan tidak begitu kering (1,18).
8. Budidaya
Memperbanyak tanaman dengan menggunakan umbil pemeliharaan
tanaman dengan penyiraman atau menjaga kelembaban tanaman dan
pemupukan, terutama pupuk dasar. Tanaman ini menghendaki tempat
yang sedikit naungan (1,17).
9
9. Kandungan kimia
Menurut pustaka, kandungan kimia dari tanaman keladi tikus berupa
fitol, asam heksadekanoat, asam oktadekanoat, koniferin, beta-sitosterol,
beta-daukosterol, serebrosida, asam laurat, asam kaprat, terpenoid,
stigmasterol, pavetannin dan prosianidin B2 atau B5 (17,19).
10. Khasiat dan kegunaan
Seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit.
Tanaman ini sebaiknya digunakan dalam bentuk segar, diolah menjadi
jus (sari buah), dan langsung diminum setelah diolah. Beberapa penyakit
yang dapat diobati dengan keladi tikus diantaranya sebagai berikut:
borok, luka dan koreng, frambusia, kanker: payudara, tulang,
tenggorokan, otak, paru-paru, usus besar, rektum, lever, prostat, ginjal,
limpa, leukemia, empedu dan pankreas, menetralisir racun narkoba serta
ekstrak air dan alkhohol mempunyai efek mencegah batuk,
menghilangkan dahak, analgesik, bersifat sedatif dan anti inflamasi
(1,20,21).
11. Bagian tanaman yang digunakan
Hampir seluruh bagian tanaman seperti umbi, daun, batang dan getah
(17,18,20)
B. Ekstraksi
1. Definisi Ekstraksi
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut
sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair.
Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan
senyawa yang tidak dapat larut, kemudian semua atau hampir semua pelarut
diuapkan hingga ekstrak menjadi kental. Struktur kimia yang berbeda-beda
akan mempengaruhi kelarutan dan stabilitas senyawa tersebut terhadap
pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman.
Dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung simplisia akan
mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Ekstraksi
10
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kondisi atau keadaan bahan
yang diekstraksi, ukuran partikel bahan, suhu, tekanan, jenis cairan penyari
serta peralatan ekstraksi. Semua faktor tersebut harus diperhatikan agar hasil
ekstraksi yang didapat sesuai dengan yang diinginkan (22).
2. Definisi Ekstrak Kental dan Kering
Ekstrak kental adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi
senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang
sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau
serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang
telah ditetapkan (22).
Ekstrak kering adalah sediaan yang diperoleh dengan cara pemekatan dan
pengeringan ekstrak cair sampai mencapai konsentrasi yang diinginkan
menurut cara-cara yang memenuhi syarat dan ketentuan. Pengaturan biasanya
dilakukan berdasarkan kandungan bahan aktif dengan cara penambahan
bahan inert. Ekstrak kering biasanya sangat higroskopis. Oleh sebab itu, harus
digerus dan dicampur di bawah kondisi kelembaban udara seminimal
mungkin. Produk antara dan produk akhir harus disimpan dalam keadaan
kering. Jadi, harus diperhatikan pengemasan serta penyimpanannya (23).
3. Metode Ekstraksi
Beberapa metode ekstraksi yang sering digunakan untuk memperoleh ekstrak
diantaranya sebagai berikut (22):
a. Cara dingin
1) Maserasi
Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut
dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur
ruangan.
2) Perkolasi
Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai
proses ekstraksi sempurna (exhaust extraction) yang umumnya
dilakukan pada suhu ruangan.
11
b. Cara panas
1) Refluks
Refluks adalah ekstraksi menggunakan pelarut pada titik didihnya
selama waktu tertentu dengan jumlah pelarut yang terbatas yang
relatif konstan dengan adanya pendingin balik.
2) Soxhletasi
Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru,
umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi
kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya
pendingin balik.
3) Digesti
Digesti adalah maserasi kinetik yaitu ekstraksi dengan pengadukan
kontinyu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur 400-50
0C.
4) Infus
Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur tangas air
(bejana infus tercelup dalam tangas air mendidih, temperatur terukur
960-98
0C) selama waktu tertentu (15-20 menit).
5) Dekok
Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (>30 menit) dan
temperatur sampai titik didih air.
4. Jenis Ekstrak
a. Ekstrak cair
Ekstrak cair merupakan sediaan cair. Namun ekstrak cair lebih padat.
b. Ekstrak kental
Ekstrak diperoleh dari ekstrak cair yang diuapkan larutan penyarinya
secara hati-hati
c. Ekstrak kering
Ekstrak kering adalah ekstrak tanaman yang diperoleh secara
pemekatan dan pengeringan ekstrak cair di bawah kondisi lemah
(temperatur dan tekanan rendah). Ekstrak kering mempunyai kadar air
yang tidak lebih dari 5% (23,24).
12
d. Tingtur
Tingtur adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau
perkolasi simplisia. Sediaan ini merupakan ekstrak yang dibuat dari
simplisia tanaman obat dengan penyari berbagai konsentrasi etanol
dengan bahan tambahan sedemikian rupa. Satu bagian simplisia disari
dengan 2-10 bagian menstruum.
C. Metode Pengeringan
Pengeringan adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi kadar air yang
ada dalam bahan dengan menggunakan panas dan dilakukan dengan cara
memindahkan cairan dari permukaan ke dalam fase upa yang belum jenuh
(25).
1. Kegunaan pengeringan
a. Daya simpan bahan lebih lama karena kadar air dalam bahan relatif
rendah sehingga kerusakan enzim maupun mikroorganisme dapat
ditekan.
b. Menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
c. Mempermudah distribusi karena umumnya bahan yang telah
dikeringkan mempunyai berat yang lebih ringan dan bentuk yang
lebih ringkas (25).
2. Jenis Pengeringan
a. Pengeringan di bawah sinar matahari dan di tempat teduh
Bahan disebarkan rata di atas nampan, lemari atau kotak kemudian
dikeringkan dengan udara atau dengan mengeringkannya di tempat
yang teduh, misalnya pengeringan tumbuhan obat.
b. Pengeringan dengan sinar infra merah
Pengeringan dengan sinar infra merah sangat menguntungkan,
keberhasilannya telah dikenal dalam skala teknik yang lebih besar.
Pada proses pengeringan bahan yang mengandung air dengan panas
penyinaran akan diperolah kondisi yang ideal. Energi dalam jumlah
besar dapat menembus sampai mendekati bidang dasar sehingga
13
absorbsi inframerah berlangsung di dalam seluruh lapisan yang
dikeringkan.
c. Pengeringan dengan bahan pengering
Pengeringan bahan dengan kualitas kecil digunakan esikator yang
berisikan bahan pengering, umumnya digunakan silika gel terutama
silika biru. Bahan yang akan dikeringkan diletakkan dalam lapisan
setipis mungkin pada perlengkapan desikator yang sesuai.
d. Lemari pengering
Pengeringan pada suhu tinggi digunakan lemari pengering yang
memiliki alat pengukur suhu. Dimana udara panas akan bergerak ke
ruang sebelah dalam di atas nampan berisi bahan yang akan
dikeringkan. Bahan yang peka terhadap suhu sering kali mengalami
kerusakan akibat panas yang digunakan juga dapat menyebabkan sifat
senyawa mudah teroksidasi.
e. Pengeringan di dalam kanal, drum dan silinder pejal
Industri besar menggunakan proses pengeringan yang berlangsung
secara kontinu dengan cara bahan basah diserakkan di atas nampan,
bergerak maju secara mekanis melintasi kanal yang dipanaskan
dengan uap, air panas, atau udara kemudian bahan setelah kering
diambil bagian ujung kanal lainnya.
f. Freeze drying atau pengering beku
Freeze drying ditujukan untuk membebaskan bahan obat termolabil
dari air. Prinsip dasar pengeringan beku adalah bahwa air dalam
kondisi membeku masih memiliki tekanan uap, kemudian dapat
dihilangkan dari sistem melalui cara sublimasi dimana akan terjadi
sesuatu perubahan langsung dari fase padat tanpa melalui fase cair
menjadi fase bentuk gas. Metode ini khususnya untuk mengeringkan
antibiotika, vitamin, hormon, plasma, darah, serum, bagian tumbuhan
yang peka terhadap panas.
14
g. Pengeringan melalui frekuensi tinggi
Obat yang akan dikeringkan pada sebuah bidang ganti kondensor
elektris, dimana terjadi aliran geser elektris di dalam bahan yang akan
dikerjakan dan secara teratur akan dipanaskan.
h. Pengeringan semprot
Pengeringan semprot dapat digunakan untuk mengeringkan bahan
yang peka terhadap panas atau oksidasi tanpa merusak bahan tersebut,
meskipun menggunakan udara bertemperatur tinggi. Pengeringan
semprot memungkinkan suatu pengeringan yang sangat singkat hanya
dalam beberapa detik dengan menyemburkan cairan sampai larutan
sejenia pasta dan bahan basah dalam bentuk tetesan halus ke dalam
aliran udara panas. Bahan akan membentuk serpihan yang dalam
waktu sedetik berubah menjadi serbuk halus dan kemudian dalam
ruang khusus untuk diambil dan dipergunakan.
3. Pengeringan semprot (Spray drying)
Pengeringan semprot merupakan alat pengering yang menggunakan
medium pemanas berupa udara kering dan alat ini sering kali digunakan
untuk membuat produk bubuk atau instan. Cairan terdispersi sebagai
tetesan halus ke dalam suatu gerak aliran dari gas panas, yang mana
cairan akan segera menguap sebelum mencapai dinding ruang kering.
Produk mengering menjadi serbuk halus yang dibawa oleh aliran gas dan
gaya berat ke dalam suatu sistem pengumpul (14).
Keuntungan metode pengeringan semprot:
a. Proses pengeringan dapat berjalan secara sinambung
b. Operasi alat dapat secara otomatis
c. Cocok untuk mengeringkan bahan yang sensitive terhadap panas,
maupun bahan yang tahan panas.
15
Kerugian dari metode pengeringan semprot
a. Peralatan yang digunakan membutuhkan tempat yang luas dan
memerlukan peralatan tambahan yang mahal, seperti pemanas,
pemisah dan lain-lain. Pada instalasi besar, ruang pengeringannya saja
dapat mencapai tinggi 15 m dengan diameter 6 m.
b. Biaya investasi alat yang cukup tinggi. (14)
Tahapan yang terjadi pada proses pengeringan dengan spray drying dapat
dibagi menjadi:
a. Pengkabutan (atomization) adalah proses untuk merubah bahan yang
semula cair atau pasta menjadi tetes-tetes kecil (droplet).
b. Kontaknya antara tetes bahan dengan medium pemanas (udara panas)
yang terjadi di dalam ruang pengering (drying chamber).
c. Penguapan air dari bahan sampai diperoleh kandungan air sesuai
dengan yang diinginkan. Kecepatan penguapan dipengaruhi oleh
komposisi bahan utama total padatan bahan, semakin tinggi total
padatan bahan, semakin cepat proses penguapan berlangsung.
d. Pengambilan produk dari alat
Untuk menjamin produk yang diperoleh bersih dan tidak
terkontaminasi oleh kotoran, maka pada saluran udara masuk dipasang
filter atau penyaring dan alat terbuat dari bahan yang memenuhi syarat
sanitasi. Hasil penyaringan setelah keluar dari alat kemudian
ditampung dan dipisahkan lewat separator (14).
Umumnya produk yang dihasilkan berbentuk bola-bola berongga (20-
200µm) dan menunjukkan kelarutan yang cepat. Pengeringan ini
umumnya dilakukan untuk bahan-bahan yang peka seperti hormon-
hormon, enzim, vitamin, glikosida, bahan obat yang bersifat polimorf,
pengeringan semprot merupakan metode yang dipilih (26).
16
D. Radikal Bebas
1. Radikal Bebas
Radikal bebas adalah molekul yang memilki elektron yang tidak
berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri (27). Dalam
jumlah yang normal radikal bebas penting untuk fungsi biologis, seperti
sel darah putih yang menghasilkan H2O2 untuk membunuh beberapa jenis
bakteri dan jamur serta pengaturan pertumbuhan sel, namun radikal bebas
tersebut tidak menyerang sasaran secara spesifik, sehingga ia juga akan
menyerang asam lemak tidak jenuh ganda dari membran sel, organel sel,
atau DNA, sehingga dapat menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi
sel (28). Namun tubuh diperlengkapi oleh seperangkat sistem pertahanan
untuk menangkal serangan radikal bebas atau oksidan sehingga dapat
membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Sistem
pertahanan antioksidan ini antara lain adalah enzim Superoxide
Dismutase (SOD) yang terdapat di mitokondria dan sitosol, Glutathione
Peroxidase (GPX), Gluthathione Reductase, dan catalase. Selain itu
terdapat juga sistem pertahanan atau antikosidan berupa mikronutrien
yaitu ß-karoten, vitamin C dan vitamin E (28). Sistem pertahanan ini
bekerja dengan beberapa cara antara lain berinteraksi langsung dengan
radikal bebas, oksidan atau oksigen tunggal, mencegah pembentukan
senyawa oksigen reaktif, atau mengubah senyawa reaktif menjadi kurang
reaktif (18). Namun dalam keadaan tertentu, pada saat tubuh terlalu
banyak terpapar radikal bebas akibat meningkatnya kadar polutan di
udara sehingga sistem kekebalan tubuh tidak mampu menetralisir radikal
bebas tersebut maka tubuh akan mengalami kondisi stres oksidatif (29).
Selain akibat paparan polutan, radikal bebas dapat terbentuk selama dan
setelah latihan oleh otot yang berkontraksi serta jaringan yang mengalami
iskemik-perfusi (29).
Radikal bebas yang menarik perhatian dari sudut medis adalah radikal
hidroksil (-OH) dan radikal superoksida yang terdiri atas ikatan dua atom
oksigen (O2) dengan satu elektron yang tidak berpasangan karena reaksi
17
dari dua jenis radikal bebas ini berlangsung cepat dan sangat merusak
pada jaringan. Akan tetapi, radikal bebas hidroksil biasanya tidak terjadi
pada sistem yang hidup karena kuatnya ikatan antara atom-atom hidrogen
dan oksigen di dalam molekul air. Apabila seseorang terpajan radiasi
ionisasi, ikatan ini dapat dipecah oleh radiasi sehingga terbentuk radikal
hidroksil. Proses tersebut mendasari penyakit radiasi yang mengakibatkan
kerusakan yang mengerikan, sering kali mematikan, yang terjadi pada
orang-orang yang terkena radiasi dalam dosis besar. Jika radikal hidroksil
menyerang DNA, reaksi berantai terjadi di sepanjang molekul DNA dan
menimbulkan kerusakan serta mutasi pada bahan genetik. Reaksi berantai
ini bahkan bisa menyebabkan putusnya tali DNA. Tubuh memang akan
berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kerusakan ini dengan
proses replikasi perbaikan DNA yang alami, tetapi perbaikan yang tidak
sempurna akan menghasilkan DNA yang telah berubah dan bisa
menimbulkan kanker (30).
Selain radikal hidroksil, radikal bebas yang berbahaya adalah radikal
superoksida yang dapat mudah terbentuk akibat dari proses penyakit,
racun, obat-obatan, logam,asap rokok, panas, polutan, kekurangan
oksigen bahkan cahaya matahari.
2. Radikal Bebas DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil)
a. Struktur kimia
1) Rumus bangun
N
N
NO2
NO2
NO2
Gambar II.2. Rumus bangun DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil)
18
b. Sifat fisika-kimia
Pemerian : Kristal prisma besar berwarna ungu gelap
Kelarutan : mudah larut dalam etanol dan metanol
c. Mekanisme
Reaksi penangkapan hidrogen dari antioksidan oleh radikal bebas
DPPH (warna ungu) dan diubah menjadi 1,1-difenil-2-pikrihidrazin
(warna kuning) yang kemudian diukur intensitasnya pada panjang
gelombang 515 nm (31).
N
N
NO2
NO2
NO2+ A H
N
N H
NO2NO2
NO2
E. Antioksidan
Antioksidan adalah bahan yang dapat menghambat atau mencegah
keruntuhan, kerusakan atau kehancuran akibat reaksi oksidasi yang berlebih
sehingga membentuk radikal bebas (30). Antioksidan merupakan inhibitor
penting dalam tubuh yang bermanfaat untuk mencegah reaksi oksidasi yang
timbul oleh radikal bebas baik berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor
eksternal lainnya.(32)
Mekanisme kerja antioksidan secara umum menghambat oksidasi substrat
yang terjadi dalam tiga tahap utama, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi
(32). Tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal substrat, yaitu turunan
substrat yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat hilangnya satu
atom H. Radikal substrat akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal
Gambar II.3. Reaksi penangkapan hidrogen dari antioksidan oleh radikal bebas
19
peroksi pada tahap propagasi. Radikal peroksi lebih lanjut menyerang substrat
menghasilkan hidroperoksida dan radikal substrat baru.
Reaksi Inisiasi:
Reaksi inisiasi, yaitu senyawa lipid yang diserang oleh radikal bebas dengan
cara mengambil atau memberikan satu elektron bebas tidak berpasangan
sehingga terbentuk senyawa radikal baru (32).
Reaksi Propagasi
Propagasi, yaitu senyawa radikal yang baru terbentuk menyerang molekul
lipid lain dan di dalamnya membentuk senyawa radikal peroksil dan
menyebabkan suatu reaksi berantai. Senyawa radikal peroksil bersama atom
hidrogen dari rantai karbon lain membentuk peroksida dan radikal bebas
baru.(32)
Reaksi Terminasi
Reaksi terminasi, yaitu peristiwa penstabilan senyawa radikal dengan ikatan
rantai samping asam lemak antara 2 senyawa radikal lipid membentuk
senyawa yang tidak radikal. (32)
ROO*
+ ROO* ROOR+ O2
ROO* + R
* ROOR
ROO* + RH
ROOH + R
*
R* + O2 ROO
*
RH R*
+ H*
20
Berdasarkan mekanisme kerjanya , antioksidan digolongkan menjadi 3
kelompok (33,34,35):
1. Antioksidan Primer
Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase (SOD),
katalase, dan glutation peroksidase (GSHPx). Antioksidan primer disebut
juga antioksidan enzimatis. Suatu senyawa disebut antioksidan primer,
apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa
radikal, kemudian radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah
menjadi senyawa yang lebih stabil.
Sebagai antioksidan, enzim-enzim tersebut menghambat pembentukan
radikal bebas, dengan cara memutus reaksi berantai (polimerisasi),
kemudian mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Antioksidan
dalam kelompok ini disebut chain-breaking-antioxidant.
2. Antioksidan Sekunder
Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus atau non
enzimatis. Antioksidan dalam kelompok ini juga disebut sistem
pertahanan preparatif. sistem pertahanan tersebut akan terbentuk senyawa
eksogen reaktif yang dihambat dengan cara pengkelatan metal, atau
dirusak pembentukannya. Kerja sistem antioksidan non enzimatik, yaitu
dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau
dengan cara menangkapnya. Akibatnya, radikal bebas tidak akan bereaksi
dengan komponen seluler.
Antioksidan sekunder meliputi vitamin E, vitamin C, beta karoten,
flavonoid, asam urat, bilirubin, dan albumin. Asam lipoat yang ditemukan
dalam kentang, wortel, brokoli, kapang, dan daging juga bersifat
antioksidan. Vitamin C dan karatenoid banyak terdapat dalam sayuran
dan buah-buahan.
21
3. Antioksidan tersier
Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair dan
metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam
perbaikan biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas.
F. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH
Uji aktivitas antioksidan merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan
keaktifan suatu senyawa dalam menghambat radikal bebas.
Aktivitas antioksidan tidak dapat diukur secara langsung, melainkan
melalui efek antioksidan dalam mengontrol proses oksidasi. Setiap metode
memiliki mekanisme yang berbeda, sesuai dengan kandungan senyawa
antioksidannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
peredaman radika bebas DPPH. DPPH (α,α-diphenyl-ß-picrylhidrazyl)
merupakan radikal bebas yang stabil dalam larutan berair atau metanol dan
memiliki warna ungu yang ditunjukkan oleh pita absorbsi dalam pelarut
metanol pada panjang gelombang 515-520 nm. DPPH bersifat peka terhadap
cahaya, oksigen, dan pH. Bentuk radikal DPPH merupakan bentuk stabil
sehingga mungkin dilakukan pengukuran aktivitas antioksidan yang cukup
akurat. DPPH dapat menangkap atom hidrogen dari komponen ekstrak yang
dicampurkan, kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya dan ditandai
dengan berkurangnya intensitas warna ungu larutan DPPH (32). Prinsip
reaksi dari metode ini adalah penangkapan hidrogen dari antioksidan oleh
radikal bebas DPPH.
Aktivitas antioksidan dari ekstrak terhadap radikal bebas DPPH diukur
menurut metode Blois (1958) dan Molyneux (2004), perubahan serapan yang
dihasilkan dalam reaksi ini digunakan untuk mengevaluasi kandungan
antioksidan dalam ekstrak (36).
22
Pola distribusi antioksidan dalam ekstrak yang diuji, dapat dinyatakan
sebagai berikut (37):
INTENSITAS NILAI IC50
Sangat Aktif < 50 ppm
Aktif 50-100 ppm
Sedang 101-250 ppm
Lemah 250-500 ppm
Kemampuan suatu senyawa untuk menangkap radikal bebas dinyatakan
dalam nilai IC50 (Inhibitor Concentration 50%). IC50 adalah besarnya
konsentrasi senyawa uji yang dapat menangkap radikal bebas sebesar 50%.
Nilai IC50 diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi linier yang
menyatakan hubungan antara konsentrasi senyawa uji dengan aktivitas
penangkap radikal rata-rata. Semakin kecil nilai IC50 maka senyawa uji
tersebut mempunyai keefektifan sebagai penangkal radikal bebas yang lebih
baik (38).
G. Uji Toksisitas dengan Metode BSLT (Brine Shrimp Letality Test)
Senyawa Bioaktif hampir selalu toksik pada dosis tinggi. Oleh karena itu,
daya bunuh in vivo dari senyawa terhadap organisme hewan dapat digunakan
untuk menapis ekstrak tumbuhan yang mempunyai bioaktivitas dan juga
untuk memonitor fraksi bioaktif selama fraksinasi dan pemurnian (39).
Salah satu organisme yang sangat sesuai untuk hewan uji tersebut adalah
brine shrimp (udang laut). Udang laut yang digunakan adalah Artemia salina
Leach. Artemia salina Leach adalah sejenis udang air asin. Telurnya
merupakan makanan ikan tropis, telur ini dapat bertahan selama bertahun-
tahun dalam keadaan kering. Jika dimasukkan dalam larutan air laut, telur-
telur akan menetas dalam waktu 48 jam dan menghasilkan sejumlah nauplii.
Nauplii Arteia salina Leach ini dapat digunakan sebagai alat yang baik untuk
mendeteksi senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas biologi (39).
Tabel II.1. Tingkat kekuatan antioksidan dengan metode DPPH
23
Keunggulan penggunaan udang Artemia salina Leach untuk uji BSLT
adalah sifatnya yang peka terhadap bahan uji, siklus hidup yang cepat, mudah
dibiakkan dan harganya yang murah (40).
Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) merupakan salah satu metode uji
toksisitas yang banyak digunakan dalam penelusuran senyawa bioaktif yang
bersifat toksik dari bahan alam. Metode ini dapat digunakan sebagai Bioassay
guided fractionation dari bahan alam karena mudah, cepat, murah dan cukup
reprodusibel. Beberapa senyawa bioaktif yang telah berhasil diisolasi dan
aktivitasnya dimonitor dengan BSLT menunjukkan adanya korelasi terhadap
suatu uji spesifik antikanker (41).
Penggunaan BSLT sebagai bioassay pertama kali dilaporkan oleh Tarpley
untuk menentukan keberadaan residu insektisida, menentukan senyawa
anestetik, serta menentukan tingkat toksisitas air laut. Selanjutnya Meyer dan
kawan-kawan menggunakan BSLT dalam penapisan senyawa-senyawa aktif
yang terdapat dalam ekstrak tanaman yang ditunjukkan sebagai toksisitas
terhadap larva Artemia salina Leach (41).
Metode BSLT untuk menentukan tingkat toksisitasnya ditentukan dengan
melihat harga LC50 yang dihitung berdasarkan analisis probit. LC50 adalah
konsentrasi senyawa yang memberikan tingkat mortalitas sebesar 50%.
Prinsip metode BSLT adalah menghitung jumlah larva yang mati pada
pengujian setelah 24 jam. Nilai presentasi kematian selanjutnya diolah
dengan Probit Analisis Ekstrak yang dirumuskan oleh Finney (1971) untuk
menentukan nilai LC50. Semakin kecil nilai LC50 maka semakin besar nilai
toksisitasnya. Menurut Meyer et.al (1982), uji bioaktivitas dengan
menggunakan larva udang Artemia salina Leach memiliki spektrum aktivitas
farmakologi, mudah dilakukan, sederhana, cepat dan tidak memerlukan biaya
yang terlalu besar dengan tingkat kepercayaan 95%. (16).
24
H. Spektrofotometri
Metode spektroskopi merupakan salah satu metode analisis yang berdasar
atas pengukuran radiasi elektromagnetis yang dihasilkan atau diabsorpsi oleh
suatu analit. Metode emisi menggunakan radiasi yang dikeluarkan/dihasilkan
pada saat analit mendapatkan energy panas maupun elektrik. Metode
fluoresensi juga berdasarkan radiasi yang diemisikan oleh analit yang mana
energi emisi dibangkitkan dengan cara memberikan energi radiasi
elektromagnetik dari suatu sumber cahaya kepada sampel yang bersangkutan.
Metode absorpsi (serapan) merupakan kebalikan dari metode emisi yaitu
berdasarkan penurunan radiasi elektromagnetik dari suatu sumber cahaya
sebagai akibat dari hasil interaksi dengan suatu analit (42).
Metode spektroskopi juga diklarifikasikan berdasar daerah spektrum dan
radiasi elektromagnetik. Daerah itu meliputi sinar-X, ultraviolet, cahaya
tampak, infra merah, gelombang mikro dan frekuensi radio. Menurut sejarah,
metode spektroskopi pada awalnya terbatas pada penggunaan radiasi cahaya
tampak dan atas dasar itu diberi istilah metode optic. Namun pada
perkembangan selanjutnya, penggunaan instrument yang sama dikembangkan
pada daerah radiasi ultraviolet dan inframerah, walaupun syaraf penglihatan
tak sensitive terhadap kedua radiasi tersebut (42).
1. Spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak (UV-Vis)
Pada spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak, pengukuran
serapan dilakukan pada daerah panjang gelombang ultraviolet (190 nm-
380 nm) dan pada daerah cahaya tampak (380 nm-780 nm). Pada
spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak, energi yang diabsorbsi
oleh molekul dapat menyebabkan elektron tereksitasi yaitu berpindah ke
tingkat energi yang lebih tinggi.
Meskipun spektrum ultraviolet dan cahaya tampak tidak khas, tetapi
sangat cocok untuk penetapan kuantitatif dan untuk beberapa zat berguna
untuk identifikasi. Bagian molekul yang mengabsorpsi dalam daerah
ultraviolet dan cahaya tampak dinyatakan sebagai kromofor. Dalam satu
25
molekul dapat mengandung beberapa kromofor. Kromofor biasanya
merupakan bagian molekul yang mempunyai ikatan tidak jenuh
terkonjugasi dan ikatannya mengandung senyawa hetero atom seperti
nitrogen, oksigen dan elektron tak jenuh (42,43).
Skema instrumentasi spektrofotometer ultraviolet dan cahaya tampak
ditunjukan gambar II.4.
Gambar II.4. Skema spektrofotometer ultraviolet dan cahaya tampak
Keterangan :
1. Sumber cahaya
2. Monokromator
3. Sel
4. Detektor
5. Amplifier
6. Pencatat
Alat spektrofotometer ultraviolet dan cahaya tampak pada dasarnya
terdiri atas :
a. Sumber cahaya
Spektrofotometer serapan molekuler memerlukan sumber energi yang
bersifat kontinyu yang mempunyai energi relatif linear pada daerah
panjang gelombang yang diinginkan. Khusus pada spektrofotometer
UV-Vis masing-masing menggunakan lampu deuterium untuk cahaya
UV dan lampu tungsten untuk cahaya tampak.
1) Lampu deuterium (hidrogen)
Lampu deuterium dapat menghasilkan spektrum kontinyu
dalam daerah ultraviolet yang dihasilkan oleh eksitasi elektrik
dari deuterium atau hidrogen pada tekanan rendah. Lampu ini
menghasilkan spektrum kontinyu dalam daerah panjang
gelombang antara 180 – 375 nm.
1 2 3 4 5 6 7 8
26
2) Lampu tungsten
Sumber radiasi kontinyu yang umum digunakan pada daerah
tampak dan inframerah dekat adalah lampu pijar dari kawat
tungsten. Lampu ini dapat memberikan spektrum kontinyu
antara 320 – 2500 nm. Energi yang dipancarkan sangat
bervariasi sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan.
b. Monokromotor
Monokromator merupakan peralatan optik yang berfungsi menseleksi
berkas radiasi dari sumber yang kontinyu dengan kemurnian spektra
yang sangat tinggi untuk panjang gelombang manapun. Alat ini dapat
diatur secara manual maupun secara otomatis sampai diperoleh pita
spektra yang diinginkan. Unsur terpenting dari suatu monokromator
adalah sistem celah dan unsur pendispersif.
c. Sel
Wadah untuk analit yang akan diukur serapannya dinamakan sel atau
kuvet, terbuat dari bahan yang transparan (tembus pandang) pada
daerah spektrum yang digunakan.
Kuvet yang ideal adalah kuvet yang mempunyai jendela yang
searah dengan cahaya agar dapat mengurangi kehilangan radiasi
karena efleksi. Kebanyak kuvet yang lazim digunakan mempunyai
panjang jalan optik dan faktor refleksi pada permukaan.
d. Detektor
Detektor merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah
energi radiasi manjadi sinyal listrik. Tranduser merupakan tipe
detektor yang merubah berbagai sinyal seperti intensitas cahaya, pH
dan panas menjadi sinyal elektrik, sesudah itu dikuatkan, dimanipulasi
sedemikian hingga sinyal itu mudah terbaca dan jumlah
proposionalnya dengan radiasi yang mengenainya.
e. Amplifier
Amplifier merupakan alat untuk memperkuat sinyal listrik yang
ditangkap oleh detektor.
27
f. Pencatat
Pencatat atau rekorder berfungsi untuk merekam sinyal elektronis
yang dihasilkan oleh detektor menjadi bentuk yang dapat
diinterpretasikan (42).
I. Landasan Teori
Kanker merupakan penyakit degeneratif dengan jumlah penderita makin
meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan pengobatan kanker sangat
dibutuhkan karena jumlah penderita yang meningkat, namun pengobatan
modern (kemoterapi) yang dipercaya saat ini memiliki efek samping yang
tidak sedikit, sehingga pasien kurang mendapatkan kesembuhan yang
optimal. Disamping itu, produksi obat konvensional yang sering mengalami
kesulitan bahan baku menbuat peneliti untuk meneliti bahan obat yang dapat
digunakan untuk pengobatan dengan efek samping rendah dan berefek sama
dengan obat konvensional. Indonesia yang merupakan negara agraris, kaya
dengan keanekaragaman hayati memberikan kesempatan pada peneliti untuk
menciptakan obat baru yang berasal dari bahan alam. Salah satunya yang
memiliki khasiat sebagai antikanker adalah tanaman keladi tikus (Thyponium
flagelliforme). Seperti yang diketahui salah satu pemicu kanker adalah
adanya radikal bebas dalam tubuh yang berlebih sehingga memicu
pertumbuhan sel yang abnormal. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk
mengetahui aktivitas antioksidan menggunakan metode peredaman radikal
bebas DPPH dan uji toksisitas secara BSLT pada daun keladi tikus dengan
perbandingan berbagai konsentrasi pelarut etanol yang kemudian dilakukan
uji antioksidan DPPH dan toksisitas BSLT.
J. Hipotesis
Ada perbedaan tingkat aktivitas antioksidan dan toksisitas antara ekstrak
kental dan kering etanol daun keladi tikus.