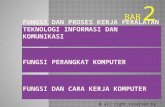BIOLISTRIK BAB II
Transcript of BIOLISTRIK BAB II
BAB II
PEMBAHASAN
A.Atom dan Ion, Muatan Listrik, Potensial Listrik,
Arus dan Hambatan Listrik.
1. Atom
Tubuh, layaknya semua materi lain terdiri dari atom. Atom
merupakan susunan materi pembangun. Walaupun awalnya
kata atom berarti suatu partikel yang tidak dapat dipotong-
potong lagi menjadi partikel yang lebih kecil, dalam
terminologi ilmu pengetahuan modern, atom tersusun atas
berbagaipartikel subatom. Partikel-partikel penyusun atom ini
adalah elektron, proton, dan neutron. Namun hidrogen-1 tidak
mempunyai neutron. Demikian pula halnya pada ion
hidrogen positif H+.
Dari kesemua partikel subatom ini, elektron adalah yang
paling ringan, dengan massa elektron sebesar 9,11 × 10−31 kg
dan mempunyai muatan negatif. Ukuran elektron sangatlah kecil
sedemikiannya tiada teknik pengukuran yang dapat digunakan
untuk mengukur ukurannya. Proton memiliki muatan positif dan
massa 1.836 kali lebih berat daripada elektron
(1,6726 × 10−27 kg). Neutron tidak bermuatan listrik dan
bermassa bebas 1.839 kali massa elektron atau
(1,6929 × 10−27 kg).
Atom dari unsur kimia yang sama memiliki jumlah proton
yang sama, disebut nomor atom. Suatu unsur dapat memiliki
jumlah neutron yang bervariasi. Variasi ini disebut
sebagai isotop.
2. Ion
Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan
listrik. Ion bermuatan negatif, yang menangkap satu atau
lebih elektron, disebut anion, karena dia tertarik
menuju anoda. Ion bermuatan positif, yang kehilangan satu atau
lebih elektron, disebut kation, karena tertarik ke katoda.
Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Atom atau kelompok
atom yang terionisasi ditandai dengan tikatas n+ atau n-, di
mana n adalah jumlah elektron yang hilang atau diperoleh. Ion
juga merupakan pembawa muatan sehingga mampu menghantarkan
arus listrik yang merupakan salah satu alasan mengapa kita
mudah sekali tersetrum,dikarenakan arus listrik yang
dihantarkan oleh tubuh jauh lebih besar daripada arus listrik
yang kita perlukan untuk melaksanakan fungsei normal tubuh di
jantung. Akibatnya impuls listrik tersebut mengalahkan impuls
listrik normal yaang menyebabkan jantung berdetak sehingga
jantung sama sekali berhenti berdetak atau mungkin berdetak
secara abnormal.
Ion pertama kali disajikan dalam bentuk teori
oleh Michael Faraday pada sekitar tahun 1830, untuk
menggambarkan mengenai bagian melekul yang bergerak ke
arah anoda atau katoda dalam suatu tabung hampa udara.
3. Muatan Listrik
Muatan listrik, Q, adalah muatan dasar yang dimiliki
suatu benda. Satuan Q adalah coulomb, yang merupakan 6.24 x
1018 muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang dimiliki
oleh materi baik itu berupa proton (muatan positif)
maupun elektron (muatan negatif). Muatan listrik total suatu
atom atau materi ini bisa positif, jika atomnya kekurangan
elektron. Sementara atom yang kelebihan elektron akan
bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan
atau kekurangan elektron ini, oleh karena itu muatan
materi/atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam
atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah
elektron yang mengelilinginya (membentuk muatan total yang
netral atau tak bermuatan).
Muatan listrik dalam tubuh dibagi menjadi 2 :
Muatan listrik negatif terdapat di permukaan dalam
membran.
Muatan listrik positif terdapat di permukaan luar
membran.
4. Arus Listrik
Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang
mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan
waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb /
detik atau Ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-
hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroAmpere
(μA) seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat
kuat 1-200 kiloAmpere (kA) seperti yang terjadi
pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit arus searah dapat
diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan
sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung
pada voltase dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm.
Arus listrik merupakan satu dari tujuh besaran pokok
dalam satuan internasional. Satuan internasional untuk arus
listrik adalah Ampere (A). Secara formal satuan Ampere
didefinisikan sebagai arus konstan yang, bila dipertahankan,
akan menghasilkan gaya sebesar 2 x 10-7 Newton/meter di antara
dua penghantar lurus sejajar, dengan luas penampang yang dapat
diabaikan, berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa
udara.
5. Hambatan Listrik
Hambatan listrik suatu objek tindakan oposisi terhadap
bagian dari sebuah arus listrik .Sebuah objek penampang
seragam memiliki resistensi yang proporsional kepada
paratahanan dan panjang dan berbanding terbalik dengan cross-
sectional daerahnya. Semua bahan menunjukkan perlawanan
beberapa, kecuali untuk superkonduktor , yang memiliki
ketahanan dari nol.
Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan
listrik dari suatu komponen elektronik (misalnya resistor)
dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik yang
mempunyai satuan Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut:
R = V / I
di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listrik.
Alat untuk mengukur resistensi
disebut ohmmeter . Ohmmeter tidak bisa mengukur resistensi
rendah akurat karena hambatan lead mengukur, menyebabkan
penurunan tegangan yang mengganggu pengukuran. Untuk lebih
akurat menggunakan perangkat empat-terminal penginderaan.
6. Potensial Listrik
Potensial listrik dalam tubuh sering disebut sebagai
potensial saraf. Di permukaan (atau membran) setiap neuron,
terdapat beda potensial listrik (voltase) akibat muatan
negatif neto di permukaan dalam membran dan muatan positif
neto di permukaan luar. Muatan neto adalah hasil dari
interaksi rumit antara ion-ion negatif dan positif. Neuron di
katakan mengalami polarisasi. Bagian dalam sel biasanya lebih
negatif 60 sampai 90mV daripada bagian luar.
B. Potensial Listrik pada Berbagai Keadaan
1. Sistem saraf
Sistem saraf dibagi menjadi dua yaitu :
a) Sistem Saraf Pusat
Terdiri dari otak, medulla spinalis, dan saraf perifer.
Saraf perifer adalah serat saraf yang mengirim informasi
sensori ke otak atau ke medulla spinalis (saraf afferent).
Serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau
medulla spenalis ke otot dan kelenjar (saraf efferent).
b) Sistem Saraf Otonom
Serat saraf ang mengatur organ dalam tubuh misalnya
jantung, usus dan kelenjar – kelenjar. Pengontrolan ini
dilakukan secara sadar.
2. Neuron (Sel Saraf)
Merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf yang
berfungsi sebagai menerima, menginterpletasikan dan
menghantarkan aliran listrik/informasi. Sel saraf terdidiri
dari tubuh serta serabut yang menyerupai ranting. Serabut nya
terdiri dari 2 macam yaitu :
Dendrit
Fungsi : menerima informasi berupa rangsangan dan sensor
penerima maupun sel saraf yang lainnya.
Akson
Fungsi : menghantarkan informasi ke bagian sel saraf
lain.
Sel Saraf dalam Keadaaan Istirahat
Dalam suatu sel saraf maupun sel – sel hidup lainnya
membran sel mempertahankan kondiisi intraseluler yang berbeda
dengan lingkungan ekstraselulernya. Setiap sel saraf
menghasilkan sedikit ion negatif yang berada di dalam sel dan
ion positif yang berada di luar membran sel. Sel mempunyai
lapisan yang disebut membran sel dan di dalam sel ini terdapat
ion Na+, Ion K+, Ion Cl-.
Sel saraf menggunakan difusi pasif dan membran sel nya.
Suatu sel saraf berada dalam keadaan istirahat, saluran Na+
yang bergantung pada tegangan tertutup sehingga menjadi
ketidaksamaan distribusi Na+. Membran sel saraf yang berada
dalam keadaan istirahat (tidak adanya proses konduksi implus
listrik), konsentrasi ion Na+ lebih banyak di luar sel daripada
di dalam sel, di dalam sel akan lebih negatif dibandingkan
dengan di luar sel.
Dalam keadaan istirahat membran sel tidak pemiabel
terhadap anion yang besar. Dengan demikian kelebihan muatan
negatif terbentuk tepat di bagian dalam permukaaan membran
sel. Beda potensial pada membran sel sekitar 70mV dan
potensial listrik adalah nol. Dengan demikian beda potensial
di dalam mebran sel 70mV. Membrane sel ini disebut dalam
keadaan polirisasi. Ini adalah potensial sel saraf dalam
keadaan istrirahat.
1. Rangsangan sel saraf
Potensial sel saraf dalam keadaan istirahat dapat
diganggu oleh rangsangan listrik, kimia maupun fisis. Butir –
butir membrane sel akan berubah dan beberapa ion Na+ akan
masuk dari luar ke dalam sel. Di dalam sel akan menjadi kurang
negatif (lebih positif) dari pada di luar sel dan potensial
membran ini disebut dalam keadaan depolarisasi. Gangtguan ini
mungkin hanya sedikit mempengaruhi potensial membran pada
titik ransangan. Potensial membran dengan cepat kembali pada
noilai istirahatnya yaitu -70Mv. Jika ransangan cukup kuat
hingga menyebabkan depolarisasi dari piotensial istirahat.
Saluran membran karena adanya perubahan potensial akan
terbuka. Karena ada gradien konsentrasi dan gradien listrik,
ion Na+ mengalir melalui sel dalam waktu yangbcepat dan
jumlahyang banyak serta m3enimbulkan arus listrik. Pada bagian
dalam membran menghasilkan perubahan polaritas membran
danmenyebabkan potensial listrik. Setelah depolarisasi saluran
Na+ tertutup untuk waktu yang cukup singkat sampai membran sel
sarap tidakl dapat diransang lagi. Periode ini dinamakan
dengan periode pemulihan. Perubahan transien pada
potensial ;listrik diantara membran dinyatakan sebagai
potensial aksi. Potensial aksi merupakan penomena keseluruhan
yang berarti bahwa begitu nilai ambang tercapai, peningkatan
waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama tidak
perduli macam apapun intensitas dari ransangan.
2. Perambatan infuls saraf
Depolarisasi lokal pada titik mula ransangan menyebabkan
gerakan difusi pasif – ion yang berada pada daerah ransangan.
Karna adanya potensial aksi sebagian kecil membran mengalami
depolarisasi akibat adantya aliran ion dalam membran. Saat
poroses depolarisasi ini mencapai batas ambang potensial aksi
dihasilkan kembli pada bagian akson. Adanya periode pemulihan
yaitu selama sebagian membran mengalami depolarisasi dan tidak
dapat diransang lagi. Implus saraf hanya dapat merambat pada
satu arah tertentu saja danmenjauhi tubuh sel saraf. Impuls
akan terus bergerak hingga mencapai terminal.Dan menyebabkan
dilepaskannya neurottransmiter dari membran sel saraf. Proses
penghantaran implus saraf aliran listrik mengalir kedalam dan
keluar melalui membran serta tegak lurus searah perhambatan
impuls. Perambatan impuls melalui akson yang diselimuti
lapisan mylin sedikit berbeda dengan perambatan melalui akson
tanpa myelin. Aktivitas listrik pada sel saraf yang dilapisi
myelin hanya terbatas pada node ranvier karna adanya
konsentrasi yang cukup besar dari saluran ion yang bergantung
pada tegangan. Kecepatan rambat pada akson saraf dengan
lapisan myelin adalah 12m/s. Kecepatan rambat ini juga
bergantung pada hambatan dari akso plasma dan kapasitas
membran. Akson dengan lapisan myelin memiliki kapasitansi yang
lebih rendah dibandingkan akson tanpa lapisan myelin. Semakin
rendah kapasitansi membran semakin kecil muatannya, dan waktu
depolarisasinya semakin singkat.
C.Penghantar Impuls didalam Tubuh dan Transmisi
Sinapsis
Penghantaran Impuls
Dalam tubuh,ada banyak sekali impuls yang di hantarkan
impuls-impuls tersebut di transfer dari satu neuron ke neuron
yang lain,setiap neuron berhubungan dengan beribu neuron yang
lain. Di dalam tubuh ada sekitar 100 miliar neuron. Sinapsis
merupakan titik pertemuan antar neuron atau istilah awamnya
penghubung antara satu neuron dengan neuron lainnya.
Mekanisme Penghantar Impuls
Dalam mekanisme penghantaran impuls ini ada dua istilah,
yaitu prasinapsis dan postsinapsis (pascasinapsis).
Prasinapsis adalah akson dari neuron “sebelumnya” sedangkan
postsinapsis adalah dendrit dari neuron “berikutnya.”
Impuls yang diterima dendrit diteruskan melalui badan sel
dan diteruskan lagi ke bagian akson. Akson akan menghantarkan
impuls ke neuron berikutnya. Neuron tersebut (neuron
berikutnya) memanfaatkan dendritnya untuk menerima impuls,
kemudian meneruskan impuls ke badan sel lalu ke akson, hingga
akson pun siap untuk mengirimkan impuls ke neuron berikutnya.
Penghantaran Impuls
Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan
neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson
membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma
tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil
berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis.
Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut
neuron pre-sinapsis. Membran ujung dendrit dari neuron
berikutnya yang membentuk sinapsis disebut neuron post-
sinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron pre-sinapsis,
maka vesikula sinapsis bergerak dan melebur dengan membran
neuron pre-sinapsis. Kemudian vesikula sinapsis akan
melepaskan neurotransmitter.
Neurontransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat
menyeberangkan impuls dari neuron pre-sinapsis menuju neuron
post-sinapsis. Neurontransmitter ada bermacam-macam, misalnya
asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin
terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin
yang terdapat di otak.
Neurotransmitter yang dilekuarkan oleh vesikula sinapsis
kemudian berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada
situs reseptor yang terdapat pada membran neuron post-
sinapsis. Menempelnya neurotransmitter pada situs reseptor
mengikuti hukum kunci dan gembok . Artinya, tidak semua
neurotransmitter dapat menempel pada situs reseptor, hanya
neurotransmitter tertentu sajalah yang dapat menempel pada
situs reseptor (sebagaimana pasangan antara anak kunci dan
gembok, hanya anak kunci pasangannya sajalah yang dapat
membuka gembok).
Menempelnya neurotransmitter pada situs reseptor
menyebabkan perubahan pada membran neuron post-sinapsis
sehingga terjadilah potensial aksi dan menimbulkan impuls pada
neuron post-sinapsis. Setelah impuls berpindah menuju neuron
post-sinapsis, maka neurotransmitter yang menempel pada situs
reseptor akan dilontarkan kembali ke celah sinapsis oleh enzim
deaktivasi yang dihasilkan oleh membran neuron post-sinaptik.
Neurotransmitter yang telah dilontarkan ini bisa dalam bentuk
utuh atau dalam keadaan terurai. Neurotransmitter yang kembali
berada di celah sinapsis ini akan diserap oleh vesikula
sinapsis untuk disimpan dan akan digunakan kembali dalam
proses penghantaran impuls berikutnya.
Jenis-jenis sinapsis
Struktur sinapsis adalah tempat bertemunya akson dari
neuron pre-sinapsis dengan suatu bagian dari neuron post-
sinapsis. Akson pre-sinapsis bisa berhubungan dengan bagian
manapun dari neuron post-sinapsis. Karenanya, sinapsis bisa
dibedakan atas:
1) Dendritik sinapsis ( dendritic synapse )
Sinapsis jenis ini terbentuk akibat bertemunya akson dari
neuron pre-sinapsis dengan dendrit dari neuron post-
sinapsis.
2) Somatik sinapsis ( somatic synapse )
Sinapsis jenis terbentuk akibat bertemunya akson dari
neuron pre-sinapsis dengan badan sel dari neuron post-
sinapsis.
3) Akson sinapsis ( axonal synapse )
Sinapsis jenis ini terbentuk akibat bertemunya akson dari
neuron pre-sinapsis dengan akson dari neuron post-
sinapsis.
Transmisi Sinapsis
Transmisi (peleburan atau pelepasan neurontransmiter)
sinaps terjadi pada neuron guna menghantarkan senyawa-senyawa
kimia. Penghantaran zat-zat yang terkandung dalam
neurontransmiter dengan reseptornya bergantung pada
permeabilitas di neuron pascasinaps. Proses transmisi sinaps
terjadi melalui beberapa cara, antara lain :
a) Potensial End Plate
Didalam suatu sel saraf terdapat unit motor. Unit motor
adalah motoneuron bersama dengan axon dan seluruh serabut otot
yang diinervasinya. Pada saat sebuah motoneuron beraksi,
seluruh serabut otot yang diinervasinya berkontraksi. Karena
satu motoneuron mungkin menginervasi dari sangat sedikit
sampai seribu atau lebih serabut otot, maka ukuran unit motor
sangat bervariasi,.
Unit motor yang kecil terdapat pada otot-otot yang kecil,
misalnya otot ekstraokular dan otot tangan.Demikian juga, unit
motor yang kecil terdapat pada otot-otot yang melakukan
berbagai gerak yang halus, misalnya otot-otot kecil tangan,
otot larynx dan otot ekstraokular.
Unit motor yang besar misalnya terdapat pada m. tibialis
anterior, m. gastrocnemius. Serabut saraf unit yang kecil
umumnya juga berdiameter lebih kecil dibandingkan unit yang
besar. Satu serabut saraf dapat menginervasi banyak serabut
otot karena axon mempunyai banyak cabang. Serabut-serabut otot
yang berasal dari satu unit motor tersebar merata di otot.
Ujung cabang-cabang motoneuron bersama dengan membran
otot yang diinervasinya membentuk motor-end plate (junctio
neuromuscularis). Gambaran pokok dari sebuah motor end plate
adalah sbb. Motor end plate terdiri atas dua bagian, yaitu
saraf dan otot yang saling dipisahkan oleh celah. Jadi motor
end plate ini dalam beberapa hal mirip sinapsis di sistem
saraf sentral. Bagian otot mengandung beberapa nuklei dan
banyak mitokhondria serta miofibril. Bagian otot dilengkapi
dengan sejumlah benjolan seperti buah anggur, sangat mirip
benik terminal. Setiap benjolan “melesak” ke dalam serabut
otot dan mengandung vesikel sinapsis dan mitokhondria.
Telah diketahui bahwa substansi transmiter di end plate
adalah asetilkholin. Ia masuk ke dalam celah, berikatan dengan
membran otot, dan mengakibatkan perubahan permiabilitas
membran tersebut. Satu impuls saraf menghasilkan suatu
potensial end plate, dan apabila potensial ini mecapai ambang
maka terjadilah potensial aksi yang disebarkan ke sepanjang
serabut otot dan menimbulkan kontraksi. Asetilkholin yang
dilepaskan pada saat datangnya aksi potensial saraf akan
segara dipecah oleh asetilkholinesterase.
Transmisi impuls di junctio neuromuscularis dapat
dipengaruhi melalui beberapa cara. Curare, misalnya,
mengurangi potensial end plate, dengan demikian mencegah
timbulnya potensial aksi. Akbiatnya terjadi paralisis otot.
(Bandingkan dengan penggunaan substansi seperti curare untuk
memperoleh relaksasi pada anestesi).
Kerusakan yang terjadi pada miastenia gravis adalah adalah
kerusakan pada transmisi di end plate. Potensial yang direkam
pada EMG adalah aksi potensial serabut otot tersebut di atas.
Apabila serabut saraf dipotong, maka motor end plate dan
serabut saraf mengalami degenerasi. Pada umumnya satu serabut
otot diinervasi oleh satu axon dan mempunyai satu motor end
plate.
Setelah lahir ukuran motor unit mengecil, mungkin karena
pada mulanya satu serabut otot diinervasi oleh lebih dari satu
motoneuron. Setelah tercapai bentuk dewasa yaitu satu serabut
otot diinervasi oleh satu motoneuron, maka ukuran unit motor
menjadi konstan.
b) Excitatory Post Synaptic Potential (EPSP) & Inhibitor
Past Synaptic Potential (IPSP)
Adanya perbedaan potensial pada membran yang menyebabkan
terjadinya peristiwa Excitatory Post Synaptic Potential (EPSP)
dan Inhibitor Past Synaptic Potential (IPST). Potensial
pascasinaps eksitatorik (EPSP) adalah perubahan potensial
pascasinaps yang terjadi di sinaps eksitatorik (terbukanya
saluran-saluran gerbang perantara kimia apabila saluran Na dan
Ka terbuka) dimana fluks-fluks ion menyebabkan timbulnya
depolarisasi kecil yang membawa sel pascasinaps mendekati
ambang.
Potensial pascasinaps Inhibitor terjadi apabila saluaran-
saluran gerbang perantara kimia yang terbuka adalah saluran Ka
dan Cl, akibatnya akan terjadi hiperpolarisasi kecil sehingga
neuron pascasinaps akan mencapai ambang lenyap. Jalur-jalur
sinaps yang menghubungkan berbagai neuron sangatlah rumit
akibat adanya konvergensi masukan neuron dan divergensi
keluarannya. Biasanya banyak masukan para sinapsis yang
berkonvergensi ke sebuah neuron dan secara bersama-sama
mengontrol tingkat eksitabilitas neuro tersebut.
Suatu neuron dapat bereaksi dengan cara melepaskan
potensial aksi di sepanjang akson, tetap berada dalam keadaan
istirahat dan tidak meneruskan sinyal dengan cara menurunkan
tingkat eksitabilitasnya.
Frekuensi potensial aksi pada sinaps eksitatorik dan
sinaps inhibitor mencerminkan keadaan sinaps yang mempengaruhi
kerja membrane. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja
sinaps dan efektivitas sinaps, antara lain:
Modifikasi jumlah transmiter pada neuron
Perubahan mekanisme sinaps yang dipengaruhi oleh
pengaruh obat-obatan yang di konsumsi oleh individu.Ada
dua kemingkinan yang terjadi yaitu: penghantaran impuls
semakin cepat atau semakin lambat.
Faktor ketidaksengajaan. Dipengaruhi dan rentan
terhadap sejumlah proses penyakit dan racun yang ada di
dalam tubuh.
D.Penggunaan Listrik untuk Tubuh
Seiring dengan perkembangan kelistrikan, telah di
ciptakan peralatan yang mempergunakan energy listrik untuk
terapi pengobatan. Pada tahun 1890 jacques A.D. Arsonval telah
mengunakan listrik berfrekuensi rendah untuk menimbulkan efek
panas hal - hal yang menyakut soal listrik yaitu:
tegangangan(V), tahanan listrik, arus listrik serta frekuensi
listrik.
1. Frekuensi arus listrik .
Sesuai dengan efek yang ditimbulkan oleh listrik,maka arus
listrik di bagi dalam 2 bentuk:
a. Listrik berfrekuensi rendah
Listrik berfrekuensi rendah mempunyai batas antara 20 HZ
sampai dengan 500.000 HZ. Frekuensi rendah ini mempunyai efek
merangsang saraf dan otot sehinga terjadi kontraksi otot.
Selain frekuensi yang diperhatikan pengulangan dalam pemakaian
sangat penting serta pemilihan bentuk gelombang manakah yang
di pakai.untuk pemakaian dalam jangka waktu singkat dan yang
bersifat merangsang persaratan otot maka di pakai arus
faradic. Untuk pemakaian dalam waktu lama dan bertujuan untuk
merangsang otot yang telah kehilangan pensarafan maka di pakai
arus listrik yang interuptur atau terputus -putus atau arus
DC.
Selain arus DC ada pula mengunakan arus AC dengan
frekuensi 50 HZ.arus AC ini serupa dengan arus DC, DC
mempunyai kemampuan :
Merangsang saraf sensoris
Merangsang saraf motoris
Berefek kontraksi otot.
Walaupun kemampuan maupun efek yang di timbul kan arus AC
serupa dengan arus DC namun dalam pemakaian di klinik, arus AC
sudah banyak di tinggalkan.
b. Listrik berfrekuensi tinggi
Yang tergolong listrik berfrekuensi tinggi adalah
frekuensi arus listrik di atas 500.000 siklus perdetik
(500.000 HZ). Listrik berfrekuensi tinggi tidak mempunyai
sifat perangsang saraf motoris atau saraf sensoris.kecuali di
lakukan rangsangan dengan pengulangan yang lama. Frekuensi
tinggi ini mempunyai sifat memanaskan.
Berdasarkan sifat ini maka frekuensi tinggi digunakan
dalam bidang kedokteran, dibagi dalam 2 bagian:
a) Short wave diaterhermy (diathermy gelombang pendek)
Pada diathermy ini terdapat 2 metode yang dipakai untuk
memperoleh gelombang elektromaknetis agar masuk kedalam badan
yaitu:
Metoda capacitance (metode kondensor). Dengan cara
electrode di letak kan pada masing masing sisis yang akan
di obati dan dipisah kan dari kulit dengan bahan
isolator.apabila kedua electrode di aliri arus
listrik,maka akan tercipta medan listrik di antara kedua
electrode tersebut. Efek medan ini perlu diperhatikan
adalah ukuran electrode harus lebih besar dari pada
struktur yang di obati, dan jarak penematan electrode
harus sama terhadap kulit.
Metode induksi (metode kabel). Pada metode ini dapat
menimbulkan efek medan listrik dan medan magnet secara
bersamaan.metode ini dilakukan dengan cara melilitkan
kabel pada daerah yang di obati minsalnya pada daerah
abdoeman (perut).
Efek Diathermy Gelombang Pendek :
1. Menghasilkan panas dan peningkatan efek fisiologis
sebagai akibat dari peningkatan temperature yaitu:
Meningkatan metabolisme
Supley darah meningkat, sebagai akibat dari
meningkatnya metabolisme
Efek pada saraf, mengurangi eksitasi saraf apabila
kurang begitu panas.
Dengan meningkatnya mengurangi relaksasi otot dan
meningkatkan efesiensi usaha otot.
Oleh karena pemanasan maka terjadi koagulasi,
sehinga terjadi destruksi jaringan.
Penurunan tekanan darah yang disebabkan oleh
pelebaran pembuluh darah.
Meningkatkan aktifitas kelenjar keringat.
2. Mempunyai efek teraupetik
Terhadap daerah peradangan, dimana akan terjadi
pelebaran pembuluh darah sehinga dapat meningkatkan
oksigen dan pengakut makanan untuk sel - sel
Efek terhadap infeksi bakteri,disini peningkatan sel
darah putih dan antibody pada daerah infeksi.
Menghilangkan rasa sakit oleh karena panas
menyebabkan saraf sensoris mengalami sedaktife
Terhadap daerah yang patah,peningkatan absorpsi,
peningaktan aliran darah.
b) Mikro wave diathermy (diathermy gelombang mikro)
Gelombang mikro merupakan gelombang elektomagnektis
dengan panjang gelombang antara sinar merah inpra dan
gelombang yang dihasilkan diathermy gelombang pendek.
Efek yang di timbulkan oleh gelombang mikro
1) Efek fisiologis
Menimbulkan panas pada jarring jaringan yang banyak
mengandung air banyak pula mendefosit energy,gelombang mikro
oto lebih banyak menyerap energy gelombang mikro dari pada
jaringan lemak.
2) Efek pengobatan
Gelombang mikro dipakai untuk mengobati penderita yang
mengalami ruda paksa (trauma) dan peradangan.juga dipakai
dalam pengobatan terhadap penderita yang merasa nyeri dan
spasme otot, bisul, gelembung dan rematik.
Bahaya dan kontra indikasi
Gelombang mikro tidak dapat di pakai pada penderita
gangguan sirkulasi, dapat mengakibatkan pendarahan, thrombosis
dan flebitis. Pada penderita TBC dan tumor ganas, tidak di
perkenankan pengobatan dengan gelombang mikro.
2. Electrocauter dan Electrosurgery
Listrik berfrekuensi tinggi dipergunakan untuk mengontrol
perdarahan pada waktu operasi.searing (cauterisasi=
pembakaran) telah di gunakan 2000 tahun yang lalu untuk
menghentikan perdarahan pada luka menggagak yaitu dengan
mengunakan gulungan kawat panas diletak kan pada luka tanpa
mengunakan anastesi atau pembiusan. Jaringan yang terpotong
dengan electrosurgery cepat mengalami gelembung.
Electrosurgery biasanya digunakan pada operasi otak, limfa,
vesica felea(kantong empedu), prostat dan serviks.
Electrocauter dan electrosurgery kedua nya berbeda dalam
peralatan tetapi mengunakan probel serta buutt plate electrode
yang sama.
3. Defibrillator
Aktifitas irama jantung terletak pada permukaan jantung
dekat muara vena cava superior, pada puncak atrium kanan.
Vibrilasi dapat terjadi pada atrium maupun ventrikal. Pada
atrium dikenal sebagai fibrilasi atrium, sedangkan pada
ventrikal dikenal sebagai fibrilasi ventrikal.
Penderita yang mengalami fibrilasi telah dilakukan
pengobatan massage jantung (metode mekanik) namun akan sangat
berhasil apabila dilakukan shock listrik pada daerah jantung.
Pengunaan shcok listrik untuk mengsingkronisasikan ritme
jantung disebut countershock. Apabila penderita tidak
memberikan respon terhadap countershcok dapat dilakukan
pengulangan hingga terjadi defibrilasi.
Ada 4 tipe dasar defibrillator:
o AC defibrillator
o Capasitive-discharge defibrillator
o Capasitive-delay-defibrilator
o Square- wave defibrillator
E.HIPEREMIA
Hiperemia di tandai oleh peningkatan jumlah darah dalam
pembuluh darah. Jika dilihat dengan mata telanjang, maka
daerah jaringan atau organ yang mengalami kongesti berwarna
lebih merah (ungu) karena bertambahnya darah didalam jaringan.
Pada dasarnya terdapat 2 mekanisme dimana hyperemia dapat
timbul:
1. Kenaikan jumlah darah yang mengalir kedaerah.
2. Penurunan jumlah darah yang mengalir dari daerah.
Hiperemia aktif, yang memerlukan adanya dilatasi arteri
dan arteriol, biasanya terjadi pada peradangan, tetapi dapat
juga di timbulkan oleh rangsangan neurogenik (misal, blushing)
hiperaktivitas (misa, olah raga) atau panas (misal, mandi
matahari).
Secara histologis, pembuluh darah tampak melebar terisi
oleh darah. Hiperemia biasanya temporer dan bersifat
referesibel. Hiperemia yang berkepanjangan yang disebabkan
oleh peradangan dapat menyebabkan diapedesis sel darah merah
kedalam jaringan interstisium.
Hiperemia pasif, atau kongesti, dapat bersifat akut atau
kronik. Proses ini biasanya mencerminkan suatu gangguan aliran
darah vena. Gagal jantung kongestif yang didominasi oleh gagal
ventrikel kanan menimbulkan kongesti dihati, yang dapat akut
atau kronik (hati nutmeg). Gagal jantung ventrikel kiri
menyebabkan kongesti pasif di paru. Hemoglobin dari darah
intra-alveolus berubah menjadi hemosidering yang kemudian
difagosistosis oleh makrofag. Makrofag-makrofag ini dikenal
sebagai sel gagal jantung. Hemosidering mengandung besi feri,
yang secara histokimia dapat dideteksi dengan reaksi biru
Prussia.
F.EDEMA
Edema adalah penimbunan cairan secara berlebihan
diantara-antara sel-sel tubuh atau didalam berbagai rongga
tubuh.jika edema menggumpul dalam rongga, biasanya dinamakan
efusi, minsalnya efusi perikardium, efusi pleura. Penimbunan
cairan didalam rongga peritorenium biasanya diberi nama
asites. Edema umum yang masih sering disebut sebagai anasarka.
Hidrops dan dropsi adalah dua istilah yang dulu dipakai untuk
menyatakan edema.
Edema secara patogenis dibagi menjadi 3 kelompok:
1) Eedema hidrostatik(misalnya apada edema paru akibat gagal
jantung kiri)/edema kaki pada gagal jantung kanan
2) Edema onkotik akibat hipoproteinemia yang disebabkan oleh
proteinuria(misalnya pada sindrom nefrotik)/sintesis protein
yang inadekuat(misalnya pada hati kronik)
3) Edema yang berkaitan dengan peningkatan permeabilitas
vascular(misalnya pada stadium awal peradangan atau pada syok
septik)
Perubahan patologis khas disebabkan oleh edema di
berbagai organ di berbagai tubuh gambaran histologis edema
bevariasi dan bergantung pada organ yang terkena dan kandungan
protein cairan edema transudat, yang memiliki kandungan protein
rendah dan tidak berisi sel mungkin tidak tampak secar
histologis tetapi dikenali dengan melebarnya ruang antarsel
atau lumen organ. Eksudat mengandung lebih banyak protein dan sel
radang. Cairan ekstrasel yang banyak mengandung protein
bersifat eosinofilik.
Etilogi dan Patogenesis
Timbulnya edema dapat diterangkan dengan mempertimbangkan
berbagai gaya yang normal mengatur pertukaran cairan melalui
dinding pembuluh. Faktor-faktor lokal mencakup tekananan
hidrostastik dalam mikro sirkulasi dan permeablitas dinding
pembuluh. Kenaikan tekanan hidrostastik cendrung memaksa
cairan masuk kedalam ruang interstisial tubuh. Karena alasan
yang sederhana ini kongesti dan edema cenderung terjadi bersama
- sama karena itu edema adalah bagian yang menyolok dari
reaksi paradangan akut.
Penyebab lokal lain dari pembentukan edema adalah
obstruksi adalah saluran limfe yang normal bertanggung jawab
atas pengairan cairan interstisial. Jika saluran ini tersumbat
karena alasan apapun maka jalan keluar cairan yang penting ini
hilang. Mengakibatkan penimbunan cairan yang di sebut sebagai
limfe edema. Limfe edema terlihat pada berbagai peradangan yang
mengenai pembulu limfe, makin paling sering di jumpai di rumah
sakit setelah eksesi atau iradiasi pembuluh limfe lokal sebagai
bagian dari bagian terapi kanker.
Faktor faktor sistematik dapat juga mempermudah
pembentukan edema karena keseimbangan cairan yang bergantung
pada sifat sifat esmotik protein serum, maka keadaan yang
disertai oleh penurunan ini dapat mengakibatkan edema. Pada
sindrom netrofik sejumlah besar protein hilang dalam urin, dan
penderita menjadi hipoproteinnamea dan edema.
Morfologi Edema
Morfologi edema secara sederahana menyakut pembekakan
bagian yang terkena karena terlalu banyak cairan yang
terkandung dalam interstisial. Pembengkakan umumnya bersifat
lunak dan sebenarnya dapat digerakan, kecuali jika cairan
sebagian besar berada intraseluler. Ciri yang terahir ini
digunakan secara klinis dalam menentukan diagnosis derajat
edema yang tidak jelas. Walaupun mata kaki yang bengkak masih
mudah didiagnosis dengan inspeksi, tetapi mungkin saja ada
edema ringan yang tidak dapat terlihat mata. Pada keadaan ini
tekanan ringan pada ibu jari pada sisi mata kaki akan
memindahkan sedikit cairan edema untuk sementara dan jika ibu
jari dilepaskan akan terlihat lekukan pada jaringan yang
berlangsung selama beberapa saat. Keadaan ini disebut piting
edema. Mobilitas cairan edema yang sama di dalam jaringan
intertistian bertanggung jawab atas efek postural tertentu.
Namun jika penderita sudah berada ditempat tidur untuk
beberapa hari dimana ekstemitas bahwa tidak ada lagi berada
pada posisi rendah maka edema mata kaki akan mengecil dan
sebagaiu gantinya dapat terlihat edema disekitar sakrum.
Akibat Edema
Edema terutama penting sebagai petunjuk untuk mengetahui ada
sesuatu yang salah dengan kata lain, mata kaki yang membengkak
itu tidak membahayakan, mungkin hanya tidak indah dipandang,
tetapi keadaan ini dapat menjadi indikator akan adanya
kehilangan protein atau payah jantung kongestip. Pada tempat
tertentu edema itu sendiri sangat penting. Edema paru-paru
bila hebat, seperti pada payah jantung kiri merupakan keadaan
darurat medis akut. Jika cukup banyak ruangan udara didalam
paru-paru terisi cairan edema, maka secara harafiah penderita
ini akan mati tenggelam. Edema paru-paru yang masih dapat
mematikan dalam beberapa menit. Derajat edema paru-paru yang
lebih ringan yang dapat ditoleransi ventilasinya dapat
membahayakan penderita yang harus terlentang ditempat tidur.
Pada keadaan ini cairan dapat terkumpul diposterior basis
paru-paru dan berperanan sebagai fokus tombulnya pneumonia
bakteri, yang kadang-kadang disebut sebagai pneumonia statik.
Edema juga membahayakan jiwa jika mengenai otak. Keadaan ini
diakibatkan karena tengkorak merupakan suatu ruangan tertutup
tanpa ruangan cadangan. Waktu yang terjadi edema otak, otak
membengkak dan tertekan pada tulang pembatas otak. Pada
beberapa segi, pada kasus yang berat peningkatan tekanan
intraktanial akan membahayakan aliran darah dalam otak dan
mengakibatkan kematian.
G.TRANSUDAT DAN EKSUDAT
Eksudat mengandung lebih banyak protein dan sel radang.
Cairan ekstrasel yang banyak mengandung protein bersifat
eosinofilik.
1. Eksudat
Disebabkan :
a) Pleuritis karena virus dan mikoplasma : virus coxsackie,
Rickettsia, Chlamydia. Cairan efusi biasanya eksudat dan
berisi leukosit antara 100-6000/cc. Gejala penyakit dapat
dengan keluhan sakit kepala, demam, malaise, mialgia,
sakit dada, sakit perut, gejala perikarditis. Diagnosa
dapat dilakukan dengan cara mendeteksi antibodi terhadap
virus dalam cairan efusi.
b) Pleuritis karena bakteri piogenik: permukaan pleura dapat
ditempeli oleh bakteri yang berasal dari jaringan
parenkim paru dan menjalar secara hematogen. Bakteri
penyebab dapat merupakan bakteri aerob maupun anaerob
(Streptococcus paeumonie, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas, Hemophillus, E. Coli, Pseudomonas,
Bakteriodes, Fusobakterium, dan lain-lain).
Penatalaksanaan dilakukan dengan pemberian
antibotika ampicillin dan metronidazol serta mengalirkan
cairan infus yang terinfeksi keluar dari rongga pleura.
c) Pleuritis karena fungi penyebabnya: Aktinomikosis,
Aspergillus, Kriptococcus, dll. Efusi timbul karena
reaksi hipersensitivitas lambat terhadap organisme fungi.
d) Pleuritis tuberkulosa merupakan komplikasi yang paling
banyak terjadi melalui focus subpleural yang robek atau
melalui aliran getah bening, dapat juga secara hemaogen
dan menimbulkan efusi pleura bilateral. Timbulnya cairan
efusi disebabkan oleh rupturnya focus subpleural dari
jaringan nekrosis perkijuan, sehingga tuberkuloprotein
yang ada didalamnya masuk ke rongga pleura, menimbukan
reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Efusi yang
disebabkan oleh TBC biasanya unilateral pada hemithoraks
kiri dan jarang yang masif. Pada pasien
pleuritis tuberculosis ditemukan gejala febris, penurunan
berat badan, dyspneu, dan nyeri dada pleuritik.
e) Efusi pleura karena neoplasma misalnya pada tumor primer
pada paru-paru, mammae, kelenjar linife, gaster, ovarium.
Efusi pleura terjadi bilateral dengan ukuran jantung yang
tidak membesar. Patofisiologi terjadinya efusi ini diduga
karena :
Infasi tumor ke pleura, yang merangsang reaksi
inflamasi dan terjadi kebocoran kapiler.
Invasi tumor ke kelenjar limfe paru-paru dan
jaringan limfe pleura, bronkhopulmonary, hillus atau
mediastinum, menyebabkan gangguan aliran balik
sirkulasi.
Obstruksi bronkus, menyebabkan peningkatan tekanan-
tekanan negatif intra pleural, sehingga menyebabkan
transudasi. Cairan pleura yang ditemukan berupa
eksudat dan kadar glukosa dalam cairan pleura
tersebut mungkin menurun jika beban tumor dalam
cairan pleura cukup tinggi. Diagnosis dibuat melalui
pemeriksaan sitologik cairan pleura dan tindakan
blopsi pleura yang menggunakan jarum (needle
biopsy).
f) Efusi parapneumoni adalah efusi pleura yang menyertai
pneumonia bakteri, abses paru atau bronkiektasis. Khas
dari penyakit ini adalah dijumpai predominan sel-sel PMN
dan pada beberapa penderita cairannya berwarna purulen
(empiema). Meskipun pada beberapa kasus efusi
parapneumonik ini dapat diresorpsis oleh antibiotik,
namun drainage kadang diperlukan pada empiema dan efusi
pleura yang terlokalisir. Menurut Light, terdapat 4
indikasi untuk dilakukannya tube thoracostomy pada pasien
dengan efusi parapneumonik:
Mikroorganisme terlihat dengan pewarnaan gram pada
cairan pleura
Kadar glukosa cairan pleura kurang dari 50 mg/dl
Nilai pH cairan pleura dibawah 7,00 dan 0,15 unit
lebih rendah daripada nilai pH bakteri Adanya apusan yang terlihat secara makroskopis didalam
kavum pleura.
g) Penanganan keadaan ini tidak boleh terlambat karena efusi
parapneumonik yang mengalir bebas dapat berkumpul hanya
dalam waktu beberapa jam saja.
h) Efusi pleura karena penyakit kolagen: SLE, Pleuritis
Rheumatoid, Skleroderma
i) Penyakit AIDS, pada sarkoma kapoksi yang diikuti oleh
efusi parapneumonik.
2. Transudat
Disebabkan :
a) Gangguan kardiovaskular
Penyebab terbanyak adalah decompensatio cordis. Sedangkan
penyebab lainnya adalah perikarditis konstriktiva, dan
sindroma vena kava superior. Patogenesisnya adalah akibat
terjadinya peningkatan tekanan vena sistemik dan tekanan
kapiler dinding dada sehingga terjadi peningkatan filtrasi
pada pleura parietalis. Di samping itu peningkatan tekanan
kapiler pulmonal akan menurunkan kapasitas reabsorpsi pembuluh
darah subpleura dan aliran getah bening juga akan menurun
(terhalang) sehingga filtrasi cairan kerongga pleura dan paru-
paru meningkat.
Tekanan hidrostatik yang meningkat pada seluruh rongga
dada dapat juga menyebabkan efusi pleura yang bilateral. Tapi
yang agak sulit menerangkan adalah kenapa efusi pleuranya
lebih sering terjadi pada sisi kanan.
Terapi ditujukan pada parah jantungnya. Bila kelainan
jantungnya teratasi dengan istirahat, digitalis, diuretik dll,
efusi pleura juga segera menghilang. Kadang-kadang
torakosentesis diperlukan juga bila penderita amat sesak.
Rongga-rongga serosa dalam badan normal mengandung
sejumlah kecil cairan. Cairan itu terdapat umpama dalam rongga
perikardium, rongga pleura, rongga perut dan berfungsi sebagai
pelumas agar membran-membran yang dilapisi mesotel dapat
bergerak tanpa geseran. Jumlah cairan itu dalam keadaan normal
hampir tidak dapat diukur karena sangat sedikit. Jumlah itu
mungkin bertambah pada beberapa keadaan dan akan berupa
transudat atau eksudat.
Fungsi dari transudat dan eksudat adalah sebagai respon
tubuh terhadap adanya gangguan sirkulasi dengan kongesti pasif
dan oedema (transudat), serta adanya inflamasi akibat infeksi
bakteri (eksudat). Transudat terjadi sebagai akibat proses
bukan radang oleh gangguan kesetimbangan cairan badan (tekanan
osmosis koloid, stasis dalam kapiler atau tekanan hidrostatik,
kerusakan endotel, dsb), sedangkan eksudat bertalian dengan
salah satu proses peradangan.
Bila radang terjadi pada pleura, maka cairan radang juga
dapat mengisi jaringan sehingga terjadi gelembung, hal ini
misalnya terjadi pada kebakaran. Cairan yang terjadi akibat
radang mengandung banyak protein sehingga berat jenisnya lebih
tinggi daripada plasma normal. Begitu pula cairan radang ini
dapat membeku karena mengandung fibrinogen.
Cairan yang terjadi akibat radang ini disebut eksudat.
Jadi sifat-sifat eksudat ialah mengandung lebih banyak protein
daripada cairan jaringan normal, berat jenisnya lebih tinggi
dan dapat membeku. Cairan jaringan yang terjadi karena hal
lain dari pada radang, misalnya karena gangguan sirkulasi,
mengandung sedikit protein, berat jenisnya rendah dan tidak
membeku, cairan ini disebut transudat. Transudat misalnya
terjadi pada penderita penyakit jantung. Pada penderita payah
jantung , tekanan dalam pembuluh dapat meninggi sehingga
cairan keluar dari pembuluh dan masuk ke dalam jaringan.
Pemeriksaan cairan badan yang tersangka transudat atau
eksudat bermaksud untuk menetukan jenisnya dan sedapat-
dapatnya untuk mendapat keterangan tentang causanya. Berbagai
jenis eksudat : eksudat ialah cairan dan sel yang keluar dari
kapiler dan masuk ke dalam jaringan pada waktu radang. Bila
cairan eksudat menyerupai serum darah dan hanya sedikit
mengandung fibrin dan sel, maka eksudat bersifat cair sekali
dan dinamai eksudat bening/jernih. Eksudat bening sering
terjadi pada radang tuberculosis yang mengisi rongga pleura
dapat berjumlah satu liter atau lebih.
Eksudat fibrinosa mengandung banyak fibrin sehingga
melekat pada permukaan pleura, merupakan lapisan kelabu/kuning
yang ditemukan pada pneumonia. Mikroskopis eksudat ini
mengandung serabut fibrin dan dalam sela – sela diantara
serabut ini terdapat sel radang. Eksudat fibrinosa terjadi
bila permeabilitas kapiler bertambah banyak, yaitu karena
molekul – molekul fibrin besar dapat keluar dari kapiler dan
menjadi bagian daripada eksudat. Eksudat purulen ialah eksudat
yang terjadi daripada nanah. Nanah ini terjadi pada radang
akut yang mengandung banyak sel polinukleus yang kemudian
musnah dan mencair karena lisis. Sisa jaringan nekrotik yang
mengalami lisis bersama dengan sel polinukleus yang musnah dan
limfe radang menjadi cairan yang disebut nanah. Eksudat
hemoragik ialah eksudat radang yang berwarna kemerah–merahan
karena mengandung banyak eritrosit.
Ciri – Ciri Transudat dan Eksudat Secara Spesifik
1. TRANSUDAT :
1. Kejernihan : Jernih, serous, kuning.
2. Berat jenis : <1.018>1.018
3. Bekuan : Ada, spontan
4. Protein : >2,5 gr %
5. Tes Rivalta : Positif
6. Sel : Polimorfonukleat pada infeksi akut, limposit
kecil pada infeksi akut, sering terdapat eritrosit
7. Bakteri : Ada
Dalam praktek sering dijumpai cairan yang sifat-sifatnya
sebagian sifat transudat dan sebagian eksudat lagi sifat
eksudat, sehingga usaha untuk membedakan antara transudat dan
eksudat menjadi sukar.
PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS
a) Hitung Jumlah Sel Lekosit
Metode : Kamar hitung Improved Neubauer atau Fuchs
Rosenthal.
Tujuan : Untuk menghitung jumlah sel lekosit dalam cairan
dan mengetahui bahwa sampel cairan tubuh tersebut
transudat atau eksudat.
Prinsip : Jumlah sel lekosit dihitung berdasarkan
pengenceran dalam larutan Pengencer dan jumlah sel dalam
cairan dalam kamar hitung.
1) Alat :
1. Mikroskop
2. Kamar Hitung Improved Neubauer 3 mm x 3 mm x 0,1 mm atau
Kamar Hitung Fuchs Rosenthal 4 mm x 4 mm x 0,2 mm
3. Pipet Lekosit
4. Kaca Penutup
2) Reagensia :
1. Larutan pengencer NaCl 0,9 %
2. Antikoagulan Natrium Citrat atau Heparin steril.
Bahan Pemeriksaan : Berupa Cairan yang berasal dari rongga
perut, pleura, pericardium, sendi, kista, hydrocele, dsb yang
didapat dengan mengadakan fungsi.
3) Prosedur Kerja :
1. Sampel didapat dengan mengadakan pungsi dan campur dengan
antikoagulan.
2. Kocok dahulu sampel yang akan diperiksa supaya homogen.
3. Pipet NaCl 0,9 % dengan pipet lekosit sampai tanda 1
tepat.
4. Pipet sampel sampai tanda 11 tepat.
5. Kocok agar sampel dan larutan tercampur sempurna minimal
3 X selama +3 menit dengan putaran membentuk angka 8.
6. Bila segera dihitung buang beberapa tetes larutan dan
teteskan pada kamar hitung.
7. Biarkan mengendap 2-3 menit. Dan hitung didalam kamar
hitung di bawah mikroskop dengan pembesaran sedang (10 X
45), sebanyak 4 kotak besar.
4) Perhitungan :
1. Dengan Kamar hitung Improved Neubauer
PDP = Pengenceran dalam pipet
TKP = Tinggi Kaca Penutup
KBH = Kotak Besar yang dihitung
2. Dengan kamar hitung Fuchs Rosenthal
Jumlah sel Leukosit = PDP x TKP x selLeukosit KBH
Jumlah sel lekosit dalam 9 kotak
= a
Luas permukaan : 3 x 3 mm2 = 9 mm2
Dalam : 0,2 mm
Isi : 9 x 0,1 mm3 = 0,9 mm
Dalam 1 mm3 terdapat : 10/9 x a
sel
Catatan :
Kamar hitung dari Fuchs Rosenthal lebih teliti karena
volumenya lebih besar. Kalau cairan berupa purulen tidak ada
gunanya menghitung jumlah lekosit tindakan ini baiknya hanya
dilakukan dengan cairan yang jernih atau yang agak keruh saja.
Untuk cairan yang agak keruh, pilih pengenceran yang sesuai.
Bahan pengencer sebaiknya larutan NaCl 0,9 % jangan
menggunakan larutan turk, karena dapat menyebabkan
terbentuknya bekuan dalam cairan.Cairan yang berupa transudat
biasanya mengandung kurang dari 500 sel/ul. Semakin tinggi
angka itu semakin besar kemungkinan cairan tersebut bersifat
eksudat.
b) Hitung Jenis Sel Leukosit.
Metode : Giemsa atau Wright Stain
Prinsip : Endapan cairan dibuat hapusan, kemudian
diwarnai dengan pewarnaan tertentu (Giemsa/Wright) maka
sel lekosit akan mengambil warna zat.Lalu dihitung
dibawah mikroskop dengan pembesaran 1000X dalam 100 % sel lekosit.
Tujuan : Untuk mengetahui jenis sel lekosit dalam
cairan/sampel, sehingga dapat menentukan jenis cairan
tersebut (transudat/eksudat).
1) Alat :
1. Objek glass
2. Pipet tetes
3. Pipet ukur
4. Gelas ukur
5. Rak pewarnaan6. Mikroskop
2) Reagensia :
Giemsa, komposisi :
1 gr giemsa
100 ml Metanol absolute
Wright, komposisi :
0,1 gr Wright (digerus)
60 ml Methanol absolute
Buffer phospat pH 7,2 :
KH2PO4 6,63 gr
Na2HPO4 3,2 gr
Aquades add 1000 ml
Persiapan Reagen : 17 tetes stok larutan giemsa ditambah 5 ml aquades
3) Prosedur Kerja :
1. Sediaan apus dibuat dengan cara yang berlain-lainan
tergantung sifat cairan itu:
- Jika cairan jernih, sehingga diperkirakan tidak
mengandung banyak sel, pusinglah 10 Sampai 15 ml sampel
1500 rpm selama 10 menit
- cairan atas dibuang dan sediment dicampur dengan
beberapa tetes serum penderita sendiri. lalu dibuat
hapusan.
- Kalau cairan keruh sekali atau purulent, dibuat sediaan
apus langsung memakai bahan itu. Jika terdapat bekuan
dalam cairan, bekuan itulah yang dipakai untuk membuat sediaan tipis.
2. Difiksasi dengan metanol selama 2 menit, buang, cuci denganaquades
3. Digenangi dengan zat warna Giemsa atau Wright selama 15
menit, buang sisa zat warna dan cuci dengan aquades, keringkan diudara.
4. Dihitung jenis sel atas 100-300 sel, di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000X
4) Hasil :
Transudat : Hanya sel mononuklear (limposit)
Eksudat : Ditemukan sel mononukleaar dan polimorfonuklear/
segmen
Catatan :
Hitung jenis ini hanya untuk membedakan limposit dan
segmen. Hasil hitung jenis dapat memberi keterangan tentang
jenis radang, yang menyertai proses radang akut hampir semua
sel berupa segment. Semakin tenang proses itu semakin
bertambah limpositnya, sedangkan radang menahun menghasilkan
hanya limposit saja dalam hitung jenis. Perbandingan banyak
sel dalam golongan limposit dan sel polimorponuklear atau
segment memberi petunjuk kearah jenis radang yang menyebabkan
atau menyertai eksudat.
c) Pemeriksaan Bakteriologis (Gramstain)
Metode : Gram
Prinsip : Bakteri gram (+) akan mengikat warna ungu dari
carbol gentian violet dan akan diperkuat oleh lugol
sehingga pada saat pelunturan dengan alkohol 96 % warna
ungu tidak akan luntur, sedangkan gram (-) akan Luntur
oleh alkohol dan mengambil warna merah dari fuksin
Tujuan : Untuk mengetahui adanya kuman–kuman dalam sampel
sehingga dapat menentukan jenis cairan tersebut apakah transudat atau eksudat
1) Alat :
Objek Glass
Pipet tetes
Bak dan rak pewarnaan
Mikroskop
2) Reagensia :
Carbol gentian violet 1 %
Lugol 1 %
Alkohol 96 %
Air Fuchsin 1 %
3) Prosedur Kerja :
1. Setetes sampel yang telah disentrifuge dibuat hapusan
diatas objekglass, dan dikeringkan.
2. Diwarnai dengan karbol gentian violet selama 3 menit, dicuci
3. Ditambah lugol selama 1 menit, dicuci
4. Ditambah alkohol 96 %selama 30 detik, dicuci
5. Ditambah air fuchsin selama 2 menit, dicuci dan dikeringkan
6. Diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 x
Catatan :
Transudat : Tidak ditemukan bakteri. Eksudat : Ditemukan bakteri
Selain dengan pewarnaan gram, juga bisa dilakukan dengan
pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk menemukan adanya bakteri
clostridium. Kalau akan mencari fungi (jamur) campur setetes
sampel dengan KOH/NaOH 10% diatas objek glass, tutup dengan
kaca penutup, biarkan selama 20 menit, kemudian periksa
dibawah mikroskop.
Kesimpulan :
Dengan melakukan pemeriksaan mikroskopis antara lain
hitung jumlah dan hitung jenis sel lekosit serta adanya
bakteri dalam cairan/sampel yang diperiksa, dapat menentukan
jenis cairan tersebut apakah transudat atau eksudat, sehingga
perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan
diagnosa.
Hal – hal yang harus diperhatikan :
a) Pengambilan dan pengiriman sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara pungsi yang
berada disetiap rongga tubuh, dibentuk oleh kulit
bagian bawah (debris), pengambilan harus dalam
keadaan steril baik itu alat ataupun wadah sampel.
Pengiriman sampel dalam wadah tertutup rapat,
steril, dan diberi etiket yaitu nama, lamanya sakit,
waktu pengambilan, jenis peneriksaan yang diminta, bila
yang dikirim berupa preparat etiketnya ditempel
dibelakang preparatnya.
b) Kualitas Reagensia.
Reagensia tidak kadaluarsa, disimpan dalam botol
coklat, bertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari langsung.
Sebelum digunakan sebaiknya disaring terlebih
dahulu.
c) Teknik Pemeriksaan
Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan perlu ketelitian
Perlu juga diperhatikan alat – alat yang digunakan
dalam keadaan bersih dan kering, kondisi alat
seperti pipet tidak pecah pada ujungnya begitu juga dengan kamar hitung.
Lamanya waktu pewarnaan juga mempengaruhi terhadap
sel yang diwarnai, untuk itu pada saat pewarnaan
sesuai dengan waktunya.
H.Perdarahan (Hemorhagi)
Hemorhagi dapat terjadi pada kapiler, vena, arteri atau
jantung. Hemorhagi dapat terjadi karena darah keluar dari
susunan kardiovaskuler atau karena diapesis (artinya eritrosit
keluar dari pembuluh darah yang tampak utuh).
Istilah Hemorhagi internal, bila darah yang keluar dari
pembuluh darah tetap berada dalam tubuh. Sedang Hemorhagi
eksternal, bila darah yang keluar dari pembuluh darah tampak
keluar dari permukaan tubuh.
a. Tempat terjadinya perdarahan:
1) Kulit, dapat berupa:
a) Petechiae, yaitu perdarahan kecil-kecil dibawah
kulit yang terjadi secara spontan, biasanya
pada kapiler-kapiler;
b) Echymosis, yaitu perdarahan yang lebih besar dari
petechiae, yang terjadi secara spontan;
c) Purpura, yaitu perdarahan yang berbentuk bercak,
besarnya bercak antara petechiae dan echymosis.
2) Mukosa
3) Serosa
4) Selaput rongga sendi
b. Perdarahan mempunyai nama tersendiri tergantung lokasi,
seperti berikut:
1) Hematoa, yaitu penimbunan darah setempat, diluar
pembuluh darah, biasanya telah membeku, sering
menonjol seperti suatu tumor pada suatu jaringan.
2) Apopleksi, yaitu peninbunan darah yang dihubungkan
dengan perdarahan otak.
3) Hemopytesis, yaitu perdarahan pada paru-paru atau
salurannya kemudian di batukkan keluar.
4) Hematemesis, yaitu keluarnya darah dari saluran
pencernaan melalui muntahan (muntah darah).
5) Melena, yaitu keluarnya darah dari saluran
pencernaan malalui anus sehingga feces berwarna
hitam.
6) Hemathoraks, Hemopericard, Hemoperitonium, yaitu
perdarahan pada rongga toraks, pericard, peritonium.
7) Hemarthros, yaitu perdarahan dalam rongga sendi.
c. Etiologi perdarahan:
1) Kerusakan pembuluh darah
2) Trauma
3) Proses patologik
4) Penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembekuan
darah.
5) Kelainan pembuluh darah
6) Toksin, dapat berupa zat kimia, racun ular, infeksi
d. Perdarahan dapat bersifat local atau sistemik
1) Perdarahan local
Tergantung lokasi perdarahan, bila lokasinya tidak
vital maka tidak tampak gejala (tidak penting),
sedangkan bila lokasinya vital, seperti pada:
a) Medulla oblongata, akan timbul kematian
b) Otak, mengganggu fungsi otak sehingga dapat
terjadi kelumpuhan
c) Rongga Pericard, terjadi tamponade jantung
Bila perdarahan sedikit maka dapat direbsorbsi,
sedangkan bila perdarahan banyak maka sulit
direbsorbsi sehingga akan diganti oleh jaringan
ikat (terjadi fibrosis).
2) Perdarahan sistemik
Tergantung dari cepat dan banyaknya perdarahan.
Bila akut dan banyak maka dapat menyebabkan kollaps
sehingga semua organ tubuh akan iskhemi dan nampak
pucat. Bila KRONIS, sedikit-sedikit dan berulang
atau terus menerus akan timbul kekurangan zat besi
sehingga mengakibatkan anemia hipokhrom dan terjadi
pula kelainan sumsum tulang. Misalnya pada penderita
tukak lambung, tumor ganas disertai perdarahan dan
pada panderita wasir. Dengan hilangnya darah atau
bila terjadi perdarahan tiba-tiba maka akan
menimbulkan berbagai macam mekanisme kompensasi.
I.TROMBOSIS
Trombosis adalah terbentuknya masa dari unsur darah
didalam pembuluh darah vena atau arteri pada makluk hidup.
Trombosis merupakan istilah yang umum dipakai untuk sumbatan
pembuluh darah, baik arteri maupun vena.
Trombosis hemostatis mencegah hilangnya darah yang
berlebihan merupakan respon normal tubuh terhadap trauma akut
vaskuler.
Trombosis patologis seperti trombosis vena dalam (TVD),
emboli paru, trombosis arteri koroner yang menimbulkan infark
miokard, dan oklusi trombotik pada serebro vaskular merupakan
respon tubuh yang tidak diharapkan terhadap gangguan akut dan
kronik pada pembuluh darah dan darah.
Ahli bedah vaskular berperan untuk mengeluarkan trombus
yang sudah terbentuk yaitu dengan melakukan trombektomi.
Konsep trombosis pertama kali diperkenalkan oleh Virchow
pada tahun 1856 dengan diajukannya uraian patofisiologi yang
terkenal sebagai Triad of Virchow, yaitu terdiri dari :
Abnormalitas dinding pembuluh darah
Perubahan komposisi darah
Gangguan aliran darah
Ketiganya merupakan faktor-faktor yang memegang peranan
penting dalam patofisiologi trombosis. Dikenal 2 macam
trombosis, yaitu :
1. Trombosis arteri
2. Trombosis vena
Etiologi trombosis adalah kompleks dan bersifat
multifaktorial (banyak faktor). Meskipun ada perbedaan antara
trombosis vena dan trombosis arteri, pada beberapa hal
terdapat keadaan yang saling tumpang tindih. Trombosis dapat
mengakibatkan efek lokal adan efek jauh. Efek lokal tergantung
dari lokasi dan derajat sumbatan yang terjadi pada pembuluh
darah, sedangkan efek jauh berupa gejal-gejala akibat fenomena
tromboemboli. Trombosis pada vena besar akan memberikan gejala
edema pada ekstremitas yang bersangkutan. Terlepasnya trombus
akan menjadi emboli dan mengakibatkan obstruksi dalam sistem
arteri, seperti yang terjadi pada emboli paru, otak dan lain-
lain.
1. ATRIAL TROMBOSIS
Definisi
Trombosis arteri adalah pembekuan darah di dalam pembuluh
darah arteri terutama sering terbentuk pada sekitar orifisium
cabang arteri dan bifurkasio arteri.
Etiologi
Penyebab/ kausa dapat lokal di tempat yang bersangkutan
atau proksimalnya. Sebagian besar adalah kelainan jantung
seperti kelainan katup, Infark jantung, fibrilasi artrium dan
lain-lain. Dapat pula karena aneurisma aorta, bila trombusnya
lepas dan bergerak ke lokasi terjadinya trombosis. Trombus
yang bergerak ini disebut embolus. Sistem hemostatis terdiri
dari 6 komponen utama yaitu trombosit, endotel vaskular,
faktor protein plasma prokoagulan, protein antikoagulan,
protein fibrinoliti, dan protein anti fibrinolitik. Semua
komponen ini harus ada dalam jumlah yang cukup pada lokasi
yang tepat untuk mencegah hilangnya darah yang berlebihan
setelah trauma vaskular, dan pada saat yang sama mencegah
terjadinya trombosis yang patologis.
Ada 3 hal yang berpengaruh dalam pembentukan/ timbulnya
trombus ini (trias Virchow) :
Kondisi dinding pembuluh darah (endotel)
Aliran darah yang melambat/ statis
Komponen yang terdapat dalam darah sendiri berupa
peningkatan koagulabilitas
Gambaran Klinis
Gejala klinik yang ditimbulkan sangat bervariasi dari
yang ringan sampai yang berat. Gejala yang dapat muncul antara
lain :
1) Gejala awal biasanya adalah nyeri pada daerah yang
bersangkutan, bisa nyeri hebat apabila daerah yang
terkena cukup luas. Pada pasien muda biasanya kejadiannya
lebih akut, rasa nyeri lebi hebat, tetapi justru
prognosisnya lebih baik karena keadaan pembuluh darah
relatif lebih baik. Pada pasien yang lebih tua, dimana
sudah terjadi kelainan kronis arteri, bila timbul
trombosis akut biasanya tidak begitu jelas gejalanya dan
nyerinya tidak begitu hebat, pada pasien seperti ini
justru prognosisnya lebih buruk.
2) Mati rasa
3) Kelemahan otot
4) Rasa seperti ditusuk-tusuk.
Bila gejalnya lengkap/ komplit, maka di temukan “5 P”,
yaitu :
Pain
Paleness
Paresthesia
Paralysis
Pulsessness
Sebagai pegangan utama, bila ada pasien dengan keluhan
nyeri hebat pada daerah ekstremitas dan nadi tidak dapat
diraba, maka diagnosis trombosis akut arteri ini harus
ditegakkan dan ditindak lanjuti.
Penatalaksanaan
Garis besar rencana perawatan dari trombosis arteri
adalah :
a) Diagnosis dini dan tindakan segera.
Dari anamnesis dan gejala klinis kita harus bisa
menegakkan diagnosis. Bila ada fasilitas pemeriksaan
penunjang, dapat dikerjakan tetapi jangan terlalu memakan
banyak waktu yang mengakibatkan terapi/ tindakan menjadi
terlambat.
b) Pasien harus istirahat baring/ dirawat dan diberikan
analgetik.
Pemberian antikoagulan seperti heparin dan LMWH penting
untuk mencegah meluasnya proses trombosis, biasanya diberikan
selama 10 hari, sesudah itu berangsurangsur diganti per oral.
Pemberian terbaik adalah dengan pemberian langsung
intraarterial.
c) Tindakan bedah berperan penting, karena trombus yang
terjadi dikeluarkan melalui arteriotomi yang bisa
dilakukan dengan anestesi lokal.
Alat yang dipakai adalah kateter Fogarty yang mempunyai
balon diujungnya. Setelah kateter menembus trombus, balom
dikembangkan dan ditarik keluar untuk mengeluarkan trombus.
Tindakan ini berhasil sangat baik bila kejadiannya benar-benar
akut dan pasien yang relatif muda.
d) Setelah dilakukan trombektomi maka tindakan lain yang
terus dilakukan terutama heparinisasi.
2. TROMBOSIS VENA DALAM (TVD)
Definisi
Trombosis vena dalam adalah pembekuan darah di dalam
pembuluh darah vena terutama pada tungkai bawah.
Patofisiologi dan Faktor Risiko
Trombosis vena terjadi akibat aliran darah menjadi lambat
atau terjadinya statis aliran darah, sedangkan kelainan
endotel pembuluh darah jarang merupakan faktor penyebab.
Trombus vena sebagian besar terdiri dari fibrin dan eritrosit
dan hanya mengandung sedikit masa trombosit. Pada umumnya
menyerupai reaksi bekuan darah dalam tabung. Pasien dengan
faktor risiko tinggi untuk menderita trombosis vena dalam
yaitu apabila :
Riwayat trombosis, strok
Paska tindakan bedah terutama bedah ortopedi
Imobilisasi lama terutama paska trauma/ penyakit berat
Luka bakar
Gagal jantung akut atau kronik
Penyakit keganasan baik tumor solid maupun keganasan
hematologi
Infeksi baik jamur, bakteri maupun virus terutama yang
disertai syok.
Penggunaan obat-obatan yang mengandung hormon esterogen
Kelainan darah bawaan atau didapat yang menjadi
predisposisi untuk terjadinya trombosis.
Keadaan ini dapat menyerang semua usia, tersering setelah
usia 60 tahun, dan tidak terdapat perbedaan angka kejadian
antara laki-laki dan perempuan.
Gambaran klinis
Trombosis vena dalam merupakan keadaan darurat yang harus
secepat mungkin didiagnosis dan diobati, karena sering
menyebabkan terlepasnya trombus ke paru dan jantung. Tanda dan
gejala klinis yang sering ditemukan berupa :
Pembengkakan disertai rasa nyeri pada daerah yang
bersangkutan, biasanya pada ekstremitas bawah. Rasa nyeri
ini bertambah bila dipakai berjalan dan tidak berkurang
dengan istirahat.
Kadang nyeri dapat timbul ketika tungkai dikeataskan atau
ditekuk.
Daerah yang terkena berwarna kemerahan dan nyeri tekan
Dapat dijumpai demam dan takikardi walaupun tidak selalu
Diagnosis
Gejala klinis dari trombosis vena dalam bervariasi (90%
tanpa gejala klinis). Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang yang dapat dilakukan antara lain :
1) Anamnesis. Nyeri lokal, bengkak, perubahan warna dan
fungsi berkurang pada anggota tubuh yang terkena.
2) Pemeriksaan Fisik. Edema, eritema, peningkatan suhu lokal
tempat yang terkena, pembuluh darah vena teraba, Homan’s
sign (+) (Berdasarkan data tersebut diatas sering ditemukan
negatif palsu)
3) Pemeriksaan penunjang
a) Prosedur diagnosis baku adalah pemeriksaan venografi
b) Kadar antitrombin III (AT III) menurun (N: 85-125%)
c) Kadar fibrinogen degradation product (FDP) meningkat
d) Titer D-dimer meningkat
Penatalaksanaan
1) Non-farmakologis
Tinggikan posisi ekstremitas yang terkena untuk
melancarkan aliran darah vena
Kompres hangat untuk meningkatkan sirkulasi mikrovaskular
Latihan lingkup gerak sendi (range of motion) seperti
gerakan fleksi-ekstensi, menggengam, dan lain-lain.
Tindakan ini akan meningkatkan aliran darah di vena-vena
yang masih terbuka (patent)
Pemakaian kaus kaki elastis (elastic stocking), alat ini dapat
meningkatkan
aliran darah vena.
2) Farmakologis
a) Heparin
Terapi heparin harus diberikan dengan loading dose diikuti
dengan infus continous yang awalnya berkecepatan 1.000/jam.
Daosis ini harus dapat mempertahankan partial thromboplastin
time (PTT) antara 1,5-2 kontrol waktu. Manfaat setelah
pemberian heparin ini adalah menjaga tingkat kesamaan dari
antikoagulan dan memperkecil manifestasi perdarahan. Pada
pasien yang tidak dapat menerima terapi warfarin, heparin
dapat diberikan 10.000 unit subkutan selama > 12 jam untuk
mempertahankan PTT 1,5 kontrol waktu, 6 jam setelah pemberian
heparin.
Komplikasi yang dapat terjadi pada pemakaian heparin
termasuk perdarahan, osteopeni, reaksi hipersensitivitas, dan
trombositopenia. Reaksi heparin dapat dinetralisir/dihambat
oleh pemberian protamin sulfat intravena, 1 mg protamin sulfat
akan menetralisir sekitar 100 unit heparin.
b) Warfarin
Warfarin diberikan pada dosis 10 mg/hari dampai waktu
protombin memanjang. Kemudian dosis dapat diturunkan menjadi 5
mg/hari diberikan untuk mempertahankan waktu protrombin pada
1,2-1,5 kontrol waktu untuk trombosis vena. Warfarin biasanya
dilanjutkan penggunaannya selama 3 bulan, namun sebaiknya pada
kasus tanpa komplikasi.
Monitoring farmakologis obat sangat diperlukan pasien
yang memakai warfarin, karena banyak obat-obat lain yang dapat
mempengaruhi efek warfarin, baik yang menghambat maupun yang
memperkuat, seperti antibiotik, barbiturat, salisilat,
kontrasepsi oral, dan lain-lain.
c) Low Molecular Weight Heparin (LMWH)
LMWH merupakan hasil fraksinasi atau depolimerisasi
heparin. Perubahan berat molekul mengakibatkan beberapa
perubahan farmakodinamik bila dibanding dengan heparin
standar. Dibandingkan heparin standar, LMWH lebih aman, lebih
efektif, tidak/jarang menibulkan perdarahan akibat heparin
standar serta mudah cara pemberiannya dan tidak perlu
pemantauan laboratorium. Dosis lazim yang diberikan pada
trombosis vena dalam adala 1 mg/kgBB setiap 12 jam, rata-rata
diberikan selama 5 hari.
J.EMBOLISME
Definisi
Embolus adalah suatu benda asing yang tersangkut pada
suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut
terbawa oleh aliran darah yang berasal dari suatu tempat lain
dalam susunan sirkulasi darah. Prosesnya disebut Embolisme
(Embolism).
Biasanya embolus berasal dari suatu trombus dalam jantung
atau pembuluh vena atau suatu trombus dalam arteri yang
terlepas dari perlekatannya pada dinding pembuluh. Embolus
bersifat padat dapat berasal dari trombus, kelompok sel tumor,
kelompok bakteri, jaringan. Embolus bersifat cairan dapat
berupa zat lemak, cairan amnion. Embolus bersifat gas dapat
berupa udara, gas nitrogen, karbon dioksid.
Embolisme dapat berupa:
Benda padat yang berasal dari troumbus,sel tumor yang
lepas ataupun dari kelompok bakteri atau jaringan
Benda cair yang berasal dari zat lemak maupun cairan
amion.
Benda gas dapat berasal dari udara nitrogen dan CO2
Akibat akibat embolus,tergantung kepada besar dan jenis
embolus,pembuluh darah yang terkena serta ada tidaknya
kolateral, contoh:
Bila terjadi sumbatan dapat terjadi kematian
jaringan
Ada penyebaran sel tumor ganas yang terbawa oleh
limfe
Embolus dapat menyebabkan sarang sarang infeksi
baru.
Pembagian Embolus Berdasarkan Asalnya
1. EMBOLUS VENA
Sebagian besar embolus dalam vena berasal dari vena
profunda ditungkai dan panggul. Embolus tersebut mengikuti
pengaliran vena dan melewati pembuluh-pembuluh yang makin
melebar masuk dalam vena cava, jantung kanan, akhirnya
tersangkut dalam sirkulasi paru. Bila embolus cukup besar,
maka akan tersangkut dalam percabangan arteri pulmonalis dan
membentuk suatu saddle embolus. Embolus yang kecil akan
tersangkut dalam percabangan arteri pulmonalis yang kecil dan
lebih perifer.
2. EMBOLUS ARTERI
Berasal dari trombus mural dalam jantung atau dalam
aorta. Embolus arteri sering mengenai otak, ginjal, limpa dan
anggota tubuh bawah. Embolus dalam arteri mesentrika
menimbulkan infark usus. Embolus dalam arteri coronaria dapat
menimbulkan kematian mendadak.
3. EMBOLUS LEMAK
Embolus lemak paling sering terjadi akibat trauma tulang
atau jaringa lemak. Sering terjadi akibat fraktur tulang
panjang, terutama femur dan tibia, yang disertai kerusakan
sumsum tulang. Embolus lemak merupakan keadaan yang dapat
menjadi gawat dan dapat pula menimbulkan kematian. Kadang-
kadang embolus lemak juga dapat terjadi pada wanita dalam masa
nifas.
Selain itu emolus lemak dapat terjadi akibat luka bakar
pada kulit Pada radang yang mengenai tulang atau jaringan
lemak. Pada perlemakan hati akibat gizi buruk atau
alkoholisme.
4. EMBOLUS AMNION
Terjadi selama persalinan, akibat masuknya cairan amnion
ke dalam sirkulasi melalui vena endoservikal di daerah
uteroplasenta Kemungkinan dalam cairan amnion terdapat semacam
prostaglandin yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh
darah, juga adanya faktor trombogenik dalam cairan amnion yang
dapat merangsang terjadinya pembekuan intravaskuler.
5. EMBOLUS GAS
Gelembung udara bertindak sebagai massa fisik yang
menyebabkan obstruksi dan menghambat sirkulasi. Salah satu
keadaan seperti ini dinamakan penyakit Caisson. Penyakit
Caisson terjadi akibat dekompressi dari tekanan atmosfer yang
meningkat dikedalaman air, misalnya pada penyelam dan pekerja
konstruksi bawah air.
Pada tekanan tinggi akan terjadi kelarutan gas-gas
atmosfer dalam darah. Jika keadaan kembali pada tekanan yang
lebih rendah yang terjadi secara cepat, maka gas tadi akan
menjadi gelembung-gelembung yang dapat menyumbat sirkulasi.
Sehingga sering pasien ditemukan menjadi lumpuh.
Emboli gas juga terjadi pada ketidakcermatan dalam
pemberian suntikan intravena, trauma toraks, insisi vena pada
leher dan tindakan pembedahan lainnya.
Efek Embolisme
Kematian mendadak misalnya bila terjadi embolisme
pulmoner, embolisme cerebral dan embolisme coroner.
Infark : emboli dari pembuluh darah yang memasok pada
sebagian atau seluruh organ tanpa didukung oleh adanya
sirkulasi kolateral yang cukup sehingga jaringan mengalami
infark.
Gangren : Terjadi sumbatan pada pembuluh darah
ekstremitas, yang didukung oleh tidak cukupnya pembuluh
darah kolateral sehingga akan terjadi kematian dari anggota
gerak.
K.ISKEMIA
Definisi
Iskemia adalah suatu kondisi ketika aliran darah (dan
juga oksigen yang terkandung didalamnya) tidak dapat mencapai
ke bagian organ tubuh tertentu. Iskemia Kardiak adalah nama
bagi kondisi berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otot
jantung.
Iskemia adalah nama penyakit yang diberikan untuk masalah
jantung yang disebabkan oleh menyempitnya pembuluh-pembuluh
arteri jantung. Ketika arteri-arteri menyempit, maka hanya
sedikit aliran darah dan oksigen yang sampai ke otot jantung.
Keadaan ini disebut juga dengan penyakit arteri koroner
(coronary artery disease/CAD) dan penyakit jantung koroner.
Keadaan ini akhirnya dapat menyebabkan serangan jantung.
Iskemia seringkali menyebabkan sakit dada atau ketidaknyamanan
di dada yang dikenal sebagai angina pectoris.
Mereka yang mengalami iskemia tanpa disertai sakit,
memiliki kondisi jantung yang dikenal sebagai iskemia yang
tersembunyi (silent ischemia). Mereka dapat terkena serangan
jantung tanpa didahului dengan gejala-gejala. Mereka yang
menderita angina mungkin memiliki riwayat kondisi iskemia
tersembunyi yang tidak terdiagnosa/diketahui. Tes gerak badan
atau monitoring dengan elektrokardiogram portabel selama 24
jam (monitor Hoiter) adalah dua tes yang sering digunakan
untuk mendiagnosa keadaan ini. Tes-tes lainnya juga dapat
digunakan.
Iskemia Kardiak adalah istilah untuk berkurangnya aliran
darah dan oksigen ke otot jantung. Iskemia kardiak terjadi
ketika arteri menyempit atau tersumbat sesaat, menyebabkan
terhambatnya aliran darah penuh oksigen ke jantung. Bila
iskemia cukup parah atau terjadi cukup lama, maka akan
menyebabkan serangan jantung (infark miokardial) dan
menyebabkan kematian jaringan dari jantung. Dalam kebanyakan
kasus, berkurangnya aliran darah sesaat ke jantung dapat
menyebabkan sakit angina pectoris.
Iskemia yang tersembunyi juga dapat mengganggu irama
detak jantung. Irama abnormal seperti takikardi ventrikular
atau fibrilasi ventrikular dapat mengganggu kemampuan jantung
dalam memompa dan bahkan dapat menyebabkan pingsan atau
kematian jantung mendadak.
Iskemia yang tersembunyi tidak memiliki gejala-gejala.
Para peneliti menyatakan bahwa jika anda memiliki riwayat
merasakan sakit dada, kemungkinan anda juga memiliki riwayat
iskemia tersembunyi.
Penyebab Utama
Stroke merupakan salah satu dari gangguan
serebrovaskuler, yang terjadi ketika aliran darah ke otak
terganggu. Stroke dibagi menjadi dua jenis yaitu stroke iskemi
(85%) yaitu stroke yang disebabkan karena adanya sumbatan
pembuluh darah dan hipoperfusi jaringan otak yang signifikan,
dan stroke hemoragik (15%) yaitu stoke yang disebabkan karena
adanya perdarahan di otak (AHA, 2000). Walaupun terdapat
kemiripan diantara kedua jenis stroke, namun berbeda dalam hal
etiologi, patofisiologi, manajemen medis, dan asuhan
keperawatan.
Latar Belakang
Stroke iskemia merupakan stroke yang paling sering
terjadi (85%), yang disebabkan karena adanya gangguan aliran
darah yang disebabkan karena sumbatan pembuluh darah otak yang
mengakibatkan adanya hipoperfusi jaringan otak yang
signifikan. Secara terminologi stroke iskemia adalah hilangnya
fungsi otak yang disebabkan karena adanya gangguan suplai
darah ke bagian otak tertentu. Stroke iskemia biasa dikenal
dengan Brain Attack istilah yang dikenalkan agar petugas
kesehatan dan masyarakat menjadi waspada bahwa stroke
merupakan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan segera.
Penanganan yang cepat dan tepat dapat menurunkan risiko
gangguan fungsi tubuh dan kematian.
Menurut American Heart Association (2000) 8% pasien
stroke meninggal setelah perawatan selama 30 hari. Tulisan ini
bertujuan untuk menggambarkan jenis gangguan aliran darah yang
dapat menyebabkan stroke dan dampak gangguan aliran darah
tersebut terhadap sel sel otak.
Patofisiologi
Otak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi dari pembuluh
darah yang membentuk lingkaran arteri serebri yang disebut
circle of willis di bagian dasar otak. Pembuluh darah yang
memperdarahi jaringan otak melintang di permukaan otak dan
menembus ke bagian dalam yang dilapisi oleh lapisan piameter.
Pada orang dewasa, otak menggunakan 20% oksigen tubuh saat
istirahat. Meskipun gangguan aliran darah terjadi sangat
singkat dapat menyebabkan gangguan kesadaran, karena gangguan
aliran darah selama 1 -2 menit-pun dapat mempengaruhi sel
otak.
Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu.
Gangguan aliran darah tersebut dapat disebabkan oleh (1)
thrombosis arteri besar yang memperdarahi otak (20%), (2)
thrombosis arteri kecil yang memperdarahi otak (25%), (3)
emboli karena kelainan jantung (20%), (4) cryptogenic (30%)
dan (5) penyebab lain penyebab lain (5%).
Stroke karena thrombosis arteri besar, terjadi karena
adanya plak atherosklerosis di pembuluh darah arteri yang
memperdarahi otak. Pembentukan thrombus dan penyumbatan pada
area yang mengalami atherosklerosis menyebabkan aliran darah
ke otak menjadi terganggu sehingga menyebabkan iskemia dan
infarct jaringan otak.
Thrombosis arteri kecil yang memperdarahi otak dapat
terjadi pada salah satu atau beberapa artery, merupakan yang
paling sering terjadi. Disebut juga stroke lacunar (kosong)
karena pada jaringan otak yang iskemia, mengalami disintegrasi
membentuk rongga.
Emboli karena kelainan jantung biasanya dikarenakan
gangguan irama terutama atrial fibrilasi. Emboli berasal dari
jantung yang kemudian mengikuti sirkulasi ke pembuluh darah
serebri menyebabkan sumbatan, terutama di arteri serebri kiri
tengah.
Stroke cryptogenic belum diketahui penyebabnya, sedangkan
penyebab lain adalah pada pasien dengan penggunaan kokain,
koagulopati, migrain dan diseksi arteri karotis Gangguan
aliran darah ini menyebabkan rangkaian metabolisme kompleks
yang disebut ischemia cascade. Ischemia cascade terjadi ketika
suplai darah ke otak kurang dari 25 ml/100g/menit. Pada
kondisi ini neruon tidak bisa mempertahankan respirasi aerob,
sehingga mitokondria melakukan metabolisme anaerob yang
menghasilkan asam laktat dan membuat kondisi asam (pH menjadi
turun). Hal ini menyebabkan neuron tidak mampu untuk
menghasilkan ATP (Adenosine triphosphat) dalam jumlah yang
cukup untuk proses depolarisasi, sehingga pompa membran untuk
mempertahankan keseimbangan elektrolit menjadi gagal berfungsi
dan menyebabkan selpun menjadi gagal berfungsi.
Pada tahap awal cascade, area otak dengan aliran darah
yang rendah disebut area penumbra yang berada di sekitar area
infark. Area penumbra merupakan jaringan otak yang mengalami
iskemia yang bisa diselamatkan dengan intervensi yang segera.
Ischemic cascade mengancam sel di area penumbra karena
depolarisasi dinding sel menyebabkan peningkatan kalsium
intrasel dan pelepasan glutamat (Hock, 1999 dari Brunner &
Suddarth. 2001. Medical Surgical Nursing, hal. 1887). Area
penumbra bisa diperbaiki dengan pemberian tissue plasminogen
activator (t-PA) dan pemberian calcium blocker untuk membatasi
influx kalsium. Influx kalsium dan pelepasan glutamat yang
berlanjut mengaktivasi kerusakan membran sel, pelepasan
kalsium dan glutamat, vasokontriksi dan pembentukan radikal
bebas. Proses ini mememperluas area infark di sekitar penumbra
dan memperberat stroke.
Selain hal tersebut di atas, lisosom dari sel otak sangat
sensitif terhadap penurunan konsentrasi oksigen. Jika kondisi
kekurangan oksigen di otak berlangsung lama, lisosom akan
dikeluarkan oleh sel otak dan mengeluarkan enzim enzim yang
dapat menghancurkan neuron dan neuralgia yang memperberat
kondisi stroke.
Manifestasi Klinis
Stroke Iskemik dapat menyebabkan defisit neurologi yang
bervariasi, tergantung lokasi dari lesi (pembuluh darah yang
tersumbat), ukuran dari area yang mengalami perfusi yang tidak
adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral (sekunder atau
asesori). Pasien dapat menunjukkan tanda dan gejala sebagai
berikut:
Kebas atau kelemahan dari area wajah, lengan, kaki,
biasanya pada satu sisi dari tubuh
Kebingungan atau perubahan status mental
Kesulitan bicara atau mengerti pembicaraan
Gangguan penglihatan
Kesulitan untuk berjalan, berbicara, pusing, atau
kehilangan keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh
Sakit kepala hebat
Gangguan fungsi motorik, sensorik, saraf kranial,
kemampuan kognitif dan fungsi lainnya
Stroke merupakan salah satu dari gangguan
serebrovaskuler, yang terjadi ketika aliran darah ke otak
terganggu. Stroke iskemia merupakan stroke yang paling sering
terjadi (85%), yang disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh
darah otak dan adanya hipoperfusi jaringan otak yang
signifikan. Stroke iskemia disebabkan karena adanya gangguan
aliran darah ke otak karena adanya sumbatan di pembnuluh darah
otak. Gangguan aliran darah ini menyebabkan rangkaian
metabolisme kompleks yang disebut ischemia cascade. Pada
kondisi ini neuron tidak bisa mempertahankan respirasi aerob
dan menyebabkan sel menjadi gagal berfungsi.
Selain hal tersebut di atas, lisosom dari sel otak sangat
sensitif terhadap penurunan konsentrasi oksigen. Jika kondisi
kekurangan oksigen di otak berlangsung lama, lisosom akan
dikeluarkan oleh sel otak dan mengeluarkan enzim enzim yang
dapat menghancurkan neuron dan neuralgia. Apabila sel yang
tidak berfungsi bertambah luas maka stroke akan semakin berat
yang menyebabkan defisit neurologi sehingga terjadi gangguan
fungsi motorik, sensorik, saraf kranial, kemampuan kognitif
dan fungsi lainnya.
Iskemia dapat terjadi pada keadaan-keadaan antara lain :
Trombosis
Terbentuknya masa dari unsur darah didalam pembuluh darah
vena atau arteri pada makluk hidup.
Embolisme
Penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di berbagai bagian
tubuh oleh embolus (zat asing) yang di bawa ke tempat
tersebut oleh aliran darah.
Aterosklerosis
Radang pada pembuluh darah manusia yang disebabkan
penumpukan plak ateromatus.
Poliartritis nodosa
Thrombosis obliterans
Spasme arteri
Tekanan dari luar pembuluh darah atau torsi
Dampak dari daerah yang terkena iskemi, tergantung dari :
1. Cara terjadinya, mendadak atau perlahan-lahan
2. Komplit atau inkomplit
3. Organ atau jaringan yang terkena
4. Ada tidaknya susunan kolateral
L.INFARK
Definisi
Infark adalah proses rusaknya jaringan jantung akibat
suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner
berkurang. Pada sebagian besar keadaan, infrak disebabkan oleh
thrombus/ embolus. Infrak juga terjadi karena penurunan suplai
darah akibat penyempitan arteri koroner karena arterosklerosis
atau penyumbatan total arteri oleh emboli atau thrombus.
Infrak dapat bersifat anemic (putih) atau hemoragik (merah).
Infrak hemoragik biasanya terjadi pada penyumbatan vena
dan pada organ yang memiliki pasokan darah ganda (fungsional
dan nutrisional) misalnya, paru dan hati. Diotak atau usus-
organ dengan sirkulasi kolateral ekstensif dan anastomosis
antara arteri-arteri besar yang terbentuk sempurna. Infark
putih menjadi hemoragik sewaktu darah dari anastomosis
mencapai daerah nekrotik.
Nyeri dada yang tiba-tiba dan berlangsung secara terus
menerus terletak dibagian bawah sternum dan perut atas, adalah
gejala utama yang biasanya muncul. Nyeri akan terasa semakin
berat sampai tidak tertahankan. Rasa nyeri yang tajam dan
berat, bisa menyebar kebahu dan lengan biasanya lengan kiri.
Nyeri muncul secara spontan dan menetap selama beberapa jam
sampai beberapa hari dan tidak akan hilang dengan istrahat
maupun nitrogliserin. Beberapa kasus nyeri bisa menjalar
kedagu dan leher, disertai napas pendek, pucat, berkeringat
dingin, pusing, dan kepala ringan, mual serta muntah.
Macam - Macam Infark
1. Menurut bentuknya infark terdiri dari :
a. Infrak anemik biasanya terjadi pada jaringan padat
yang memiliki pasokan arteri terminal dan tidak
memiliki kolateral. Biasanya infrak semacam ini
terjadi di jantung, ginjal dan limpa.
b. Infrak hemoragik biasanya terjadi pada penyumbatan
vena dan pada organ yang memiliki pasokan darah
ganda (fungsional dan nutrisional) misalnya, paru
dan hati. Diotak atau usus- organ dengan sirkulasi
kolateral ekstensif dan anastomosis antara arteri-
arteri besar yang terbentuk sempurna. Infark putih
menjadi hemoragik sewaktu darah dari anastomosis
mencapai daerah nekrotik.
2. Menurut lamanya infark terbagi atas:
a. infark muda/baru
b. infark tua/lama
3. Menurut ada tidaknya hama, infark terbagi atas :
a. infark septic
b. infark suci hama(bland infark)
Patogenesis Terjadinya Infark
Setelah terjadinya oklusi pembuluh, baik arteri maupun
vena akan terjadi hiperemi setelah berlangsung beberapa jam
karena stagnasi darah akan timbul oedem dan perdarahan.
Setelah 24 jam pada alat tubuh yang padat seperti jantung dan
ginjal tampak pucat, sedangkan pada alat tubuh yang terdiri
dari jaringan longgar seperti paru dan limpa jaringan yang
terkena tetap hemoragik sehingga berwarna merah.
Setelah beberapa hari untuk infark pucat akan Nampak
kuning putih, berbatas tegatelah sedangkan infark merah tidak
berubah banyak. Berbatasan daerah infark dan jaringan normal
tidak nyata karena odema, hiperemi dan perdarahan. Setelah
beberapa hari sampai beberapa minggu bagian yang terkena akan
mengalami fibrosis mulai dari tepi kepusat nekrosis sehingga
infark dig anti oleh jaringan perut yang pucat. Bagian pucat
kadang-kadang dapat mencair karena proses lisis yang bila luas
maka akan membentuk kista dan akhirnya cairan diresopsi
diganti oleh jaringan padat.
Akibat Infark
1) Rasa nyeri karena iritasi pada syaraf atau karena
radang pada permukaan serosa
2) Kadang-kadang demam dan lekositosis karena nekrosis
3) Pada infark paru terjadi hemogtisis
4) Pada infark ginjal terjadi hematuri
5) Pada infark miocard dapat terjadi ruptur atau pun
shock cardial
6) Bila terjadi pada jaringan otak dapat terjadi
aphasia, kelumpuhan, buta, kesadaran menurun dan
sebagainya
Gejala yang Ditimbulkan dari Infark Miokardial (Serangan
Jantung)
1. Nyeri dada semakin sering muncul bahkan setelah melakukan
aktivitas fisik yang ringan. Unstable angina seperti ini
bisa berakhir menjadi suatu serangan jantung.
2. Nyeri di pertengahan dada menjalar ke punggung, rahang
atau lengan kiri, atau yang lebih jarang menjalar ke
lengan kanan.
3. Nyeri pada serangan jantung mirip dengan nyeri pada
angina tapi lebih hebat dan lebih lama, tidak berkurang
dengan istirahat. Kadang-kadang nyeri dirasakan di perut
dan disalah artikan sebagai salah makan, terutama karena
setelah penderita bersendawa. Nyeri agak berkurang atau
hilang untuk sementara waktu.
M.DEHIDRASI
Definisi
Dehidrasi adalah berkurangnya cairan tubuh total, dapat
berupa hilangnya air lebih banyak dari natrium (dehidrasi
hipertonik), atau hilangnya air dan natrium dalam jumlah yang
sama (dehidrasi isotonik), atau hilangnya natrium yang lebih
banyak dari pada air (dehidrasi hipotonik).
Jenis - Jenis Dehidrasi
a. Dehidrasi hipertonik (berat) : ditandai dengan tingginya
kadar natrium serum (lebih dari 145 mmol/liter) dan
peningkatan osmolalitas efektif serum (lebih dari 285
mosmol/liter).
b. Dehidrasi isotonic (sedang) : ditandai dengan normalnya
kadar natrium serum (135-145 mmol/liter) dan osmolalitas
efektif serum (270-285 mosmol/liter).
c. Dehidrasi hipotonik (ringan): ditandai dengan rendahnya
kadar natrium serum (kurang dari 135 mmol/liter) dan
osmolalitas efektif serum (kurang dari 270 mosmol/liter).
Diagnosis
Gejala klasik dehidrasi seperti rasa haus, lidah kering,
penurunan turgordan mata cekung sering tidak jelas
Gejala klinis paling spesifik yang dapat dievaluasi
adalah penurunan berat badan akut lebih dari 3%.
Terapi
Lakukan pengukuran keseimbangan (balans) cairan yang
masuk dan keluar secara berkala sesuai kebutuhan.
Pada dehidrasi ringan, terapi cairan dapat diberikan
secara oral sebanyak 1500-2500 ml/24 jam (30ml/kg berat
badan/24 jam) untuk kebutuhan dasar, ditambah dengan
penggantian defisit cairan sehari, termasuk jumlah
insensible water loss sangat perlu dilakukan setiap hari.
Perhatikan tanda – tanda kelebihan cairan seperti
ortopnea, sesak napas, perubahan pola tidur, atau
confusion. Cairan yang diberikan secara oral tergantung
jenis dehidrasi.
Dehidrasi hipertonik: cairan yang dianjurkan adalah air
atau minuman dengan kandungan sodium rendah, jus buah
seperti apel, jeruk, dan anggur
Dehidrasi isotonik: cairan yang dianjurkan selain air dan
suplemen yang mengandung sodium (jus tomat), juga dapat
diberikan larut isotonik
Dehidrasi hipotonik cairan yang dianjurkan seperti di
atas tetapi dibutuhkan kadar sodium yang lebih tinggi
Pada dehidrasi sedang sampai berat dan pasien tidak dapat
minum per oral, selain pemberian cairan enternal, dapat
diberikan rehidrasi parental. Jika cairan tubuh yang
hilang terutama adalah air, maka jumlah cairan rehidrasi
yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus.
Rumus
Defisit cairan (liter) = cairan badan total (CBT) yang
diinginkan – CBT saat ini
CBT yang diinginkan = kadar na(natrium) serum X CBT saat
ini
140
CBT saat ini (pria) = 50% X berat badan (kg)
CBT saat ini (perempuan) = 45% berat badan (kg)
N.SHOCK
Shock adalah kolapsnya tekanan darah arteri sistemik pada
penurunannya tekanan darah yang berat, aliran darah tidak
dapat secara adekuat memenuhi kebutuhan energy jaringan dan
organ. Tubuh berespons dengan mengalihkan darah menjauhi
sebagian besar organ-organ vital yaitu jantung, otak, dan
paru-paru menerima cukup darah.
Respons Baroreseptor Terhadap Shock
Pada permulaan shock, reflex baroreseptor diaktifkan dan
tubuh akan mengkompensasi penurunan darah yang drastic. Bila
penyebab skock terus berlangsung, maka kompensasi menjadi
tidak adekuat dan kemunduran kondisi berbagai organ akan terus
berlanjut termasuk jantung , paru-paru dan otak.
Penyebab Shock
Kondisi gangguan hemodinamik dan metabolic karena tidak
adekuat airan darah dan suplai oksigen pada kapier dan
jaringan tubuh. Manifastasi shock berupa gejala hipotensi,
takhikardia, oliguria, kulit lembab, gelisah, dan penurunan
tingkat kesadaran. Penyebab yang khas adalah penurunan curah
jantung, penurunan perfusi jaringan.
Macam - Macam Shock :
1. Shock Hipovelemik
Yaitu kehilangan volume intravaskuiler ( volume
darah/cairan sirkulasi) contoh pada pendarahan, luka bakar
dandehidrasi.
Penyebab shock hipovelemik :
1. Pendarahan.
2. Dehidrasi.
3. Luka Bakar, khususnya luka bakar derajat III.
2. Shock kardiogenik
Yaitu akibat penurunan curah jantung secara langsung dan
dapat dihubungkan dengan gungguan atau penurunan curah
jantung. Misal :
Kegagalan jantung dmana jantung tidak dapat
berkontraksi secara efektif disebut gagal jantung
atau decompensatio cordi.
Penurunan aliran baik vena dimana volume darah yang
kembali ke jantung berkurang akibat penurunan curah
jantung sehingga tekanan darah menurun disertai
kerusakan jarigan dan perfusi organ.
3. Shock vasogenik
Yaitu kehilangan cairan redistribusi. Isilah ini
digunakan karena cairan darah sentral didistribusikan kembali
vaskularisasi perferi, khususnya vena-vena. Yang termasuk
shock distributive antara lain :
Shock Neurogenik akibat kehilangan tonus vasomotor
sehingga terjadi dilatasi vean dan arteriol umum.
Shock septic disebabka karena toksin dari kuman
gram+/- ataupun virus pada keadaan ini terjadi
kolaps vaskuler prefer.
Shock anafilatik pada kondisi ini juga terjadi
kolaps perifer yang diakibatkan oleh reaksi antigen-
antibody.
Pembagian Shock
1) Shock Primer
Terjadi karena ruang vaskuler membersar yang berasal dari
neurogen, contoh :
Kecelakaan keras, rasa nyeri sangan
Radang akut pancreas
Hernia incarserata
Perasaan takut mendadak
2) Shock Sekunder
Terjadi gangguan keseimbangan cairan yang mennyebabkan
defisiensi sirkulasi perifer disertai jumlah darah yang
menurun. Sirkulasi yang berkurang tidak terjadi segera setelah
terjadi kerusakaan, tetapi setelah beberapa waktu sesudahnya.
Oleh karena itu disebut shok sekunder atau delayed shock.