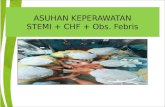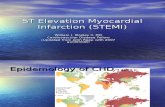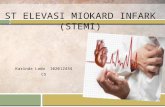Stemi
-
Upload
may-maghdalena -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
description
Transcript of Stemi

Laporan Kasus
Infark Miokard Akut dengan ST Elevasi
(STEMI)
OLEH :
Meidy Shadana
NIM. 1008114272
PEMBIMBING:
dr. Irwan, SpJP-FIHA
KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN KARDIOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN VASKULER
RSUD ARIFIN ACHMAD FAKULTAS KEDOKTERAN UNRI
PEKANBARU
2014

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Infark miokard akut (IMA) dengan ST elevasi merupakan bagian dari
spektrum sindrom koroner akut (SKA) yang terdiri dari angina pektoris tidak
stabil, NSTEMI dan STEMI.1 Infark miokard akut merupakan salah satu diagnosis
rawat inap tersering di negara maju. Laju mortalitas awal (30 hari) pada IMA
adalah 30% dengan lebih dari separuh kematian terjadi sebelum pasien mencapai
Rumah Sakit.1 Infark miokard akut merupakan salah satu penyebab tingginya
angka kesakitan dan kematian di Amerika Serikat dan banyak dijumpai pada
kelompok umur 35-65 tahun (kelompok umur produktif).2,3
Penyebab terbanyak IMA adalah rupturnya plak aterosklerosis dan adanya
trombus. Diagnosis infark miokard dapat ditegakkan bila memenuhi 2 dari 3
kriteria, yaitu: nyeri dada khas infark, peningkatan serum enzim lebih dari 1½ kali
nilai normal dan terdapat evolusi EKG khas infark.4
Untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit ini, maka kesadaran
masyarakat mengenali gejala-gejala infark miokard akut dan segera membawa
penderita ke fasilitas kesehatan terdekat perlu ditingkatkan.5

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi
Infark miokard akut (IMA) dengan ST elevasi merupakan bagian dari
spektrum sindrom koroner akut (SKA) yang terdiri dari angina pektoris tidak
stabil, NSTEMI dan STEMI. Infark miokard akut dengan ST Elevasi (STEMI)
umumnya terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak setelah
oklusi trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya.1
2.2 Epidemiologi
Infark miokard akut merupakan salah satu penyebab tingginya angka
kesakitan dan kematian di Amerika Serikat. Dilaporkan 600 kasus per 100.000
orang dan 500.000-700.000 meninggal karena IMA dan banyak dijumpai pada
kelompok umur 35-65 tahun (kelompok umur produktif).2,3
Secara umum, IMA dapat terjadi pada semua umur, tetapi peningkatan
angka kejadian IMA seiring dengan umur penderita. IMA banyak terjadi pada pria
berumur 40-70 tahun.2
2.3 Etiologi
Penyebab terbanyak IMA adalah rupturnya plak aterosklerosis dan adanya
trombus.
Penyebab lain yang dapat menyertainya adalah:6
1. Vasospasme arteri koronaria
2. Hipertrofi ventrikel (LVH, kelainan katup jantung)
3. Hipoksia
4. Emboli arteri koronaria
5. Penggunaan kokain, amfetamin dan efedrin
6. Artritis

7. Anomali koronaria, termasuk aneurisma arteri koronaria
8. Peningkatan afterload atau efek inotropik, dimana terjadi peningkatan
beban miokardium.
Faktor resiko terjadinya plak aterosklerosis, yaitu:6
1. Umur
2. Pria
3. Merokok
4. Hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida
5. Diabetes Mellitus
6. Hipertensi yang tidak terkontrol
7. Riwayat keluarga
8. Obesitas
9. Gaya hidup
10. Ketidakaktifan fisik
2.4 Patofisiologi
STEMI umumnya terjadi jika aliran darah koroner menurun secara
mendadak setelah oklusi thrombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada
sebelumnya. STEMI juga terjadi jika thrombus arteri koroner terjadi secara cepat
pada lokasi injuri vaskular, di mana injuri ini dicetuskan oleh faktor-faktor seperti
merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid.
Infark terjadi jika plak aterosklerosis mengalami fisur, ruptur atau ulserasi
dan jika kondisi lokal atau sistemik memicu trombogenesis, sehingga terjadi
thrombus mural pada lokasi ruptur yang mengakibatkan oklusi arteri koroner.
Plak koroner cenderung mengalami ruptur jika mempunyai fibrous cap yang tipis
dan inti kaya lipid (lipid rich core). Pada STEMI gambaran patologis klasik terdiri
dari fibrin rich red thrombus, yang dipercaya menjadi dasar sehingga STEMI
memberikan respons terhadap terapi trombolitik.
Arteri koroner yang terlibat (culprit) mengalami oklusi oleh trombus yang
terdiri dari agregat trombosit dan fibrin. Pada kondisi yang jarang, STEMI dapat
juga disebabkan oleh oklusi arteri koroner yang disebabkan oleh emboli koroner,
abnormalitas kongenital, spasme koroner dan berbagai penyakit inflamsi sistemik.

Aterosklerosis pembuluh koroner merupakan penyebab penyakit arteri
koronaria yang paling sering ditemukan. Lesi biasanya diklasifikasikan
sebagai endapan lemak, plak fibrosa dan lesi komplikata.1
Aterosklerosis menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam
arteri koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah.
Bila lumen menyempit maka resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan
membahayakan aliran darah miokardium. Bila penyakit ini semakin lanjut, maka
penyempitan lumen akan diikuti perubahan pembuluh darah yang mengurangi
kemampuan pembuluh untuk melebar. Dengan demikian keseimbangan antara
penyediaan dan kebutuhan oksigen menjadi tidak stabil sehingga membahayakan
miokardium yang terletak di sebelah distal dari daerah lesi.
Manifestasi klinis penyakit belum tampak sampai proses aterogenik
mencapai tingkat lanjut. Fase praklinis dapat berlagsung 20-40 tahun. Lesi
bermakna secara klinis yang mengakibatkan iskemia dan disfungsi miokardium
biasanya menyumbat lebih dari 75% lumen pembuluh darah.7
Langkah terakhir proses patologis yang menimbulkan gangguan klinis
dapat terjadi melalui:
1. Penyempitan lumen progresif akibat pembesaran plak
2. Perdarahan pada plak ateroma
3. Pembentukan trombus yang diawali agregasi trombosit
4. Embolisasi trombus atau fragmen plak.
5. Spasme arteri koronaria.
2.5 Diagnosis
Diagnosis IMA dengan elevasi ST ditegakkan berdasarkan anamnesis
nyeri dada yang khas dan gambaran EKG adanya elevasi ST ≥ 2 mm, minimal
pada 2 sandapan prekordial yang berdampingan atau ≥ 1 mm pada 2 sandapan
ekstremitas. Pemeriksaan enzim jantung, terutama troponin T yang meningkat,
memperkuat diagnosis.1
1. Anamnesis
Pada pasien dengan keluhan nyeri dada perlu dianamnesis apakah nyeri
dadanya berasal dari jantung atau dari luar jantung. Perlu dianamnesis pula

apakah ada riwayat infark miokard sebelumnya serta faktor-faktor resiko antara
lain hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, stress serta riwayat sakit
jantung koroner pada keluarga.
Gejala-gejala umum iskemia dan infark miokardium adalah nyeri dada
retrosternal. Yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keluhan nyeri dada iskemik
SKA adalah:1
1. Lokasi nyeri di daerah retrosternal, substernal dan prekordial. Pasien sulit
melokalisir rasa nyeri.
2. Deskripsi nyeri rasa berat seperti dihimpit, ditekan atau diremas, rasa tersebut
lebih dominan dibandingkan rasa nyeri. Perlu diwaspadai juga bila pasien
mengeluh nyeri epigastrik, sinkope atau sesak nafas (angina ekuivalen).
3. Penjalaran nyeri ke lengan kiri, bahu, punggung, leher rasa tercekik atau
rahang bawah (rasa ngilu) kadang penjalaran ke lengan kanan atau kedua
lengan.
4. Nyeri membaik atau hilang dengan istirahat, atau obat nitrat.
5. Faktor pencetus berupa latihan fisik, stress emosi, udara dingin, dan sesudah
makan.
6. Lama nyeri pada SKA lebih dari 20 menit
7. Gejala sistemik disertai keluhan seperti mual, muntah atau keringat dingin,
cemas dan lemas.3
Hal-hal dapat menyerupai nyeri dada iskemia:
- Diseksi aorta
- Emboli paru akut
- Efusi pericardial akut dengan temponade jantung
- Tension pneumothoraks
- Perikarditis
- GERD (Gastro esophageal Reflux disease)
2. Pemeriksaan fisik
Sebagian besar pasien cemas dan tidak bisa istirahat (gelisah). Seringkali
ekstremitas pucat disertai keringat dingin. Sekitar seperempat pasien infark
anterior mempunyai manifestasi hiperaktivitas saraf simpatis (takikardia dan atau
hipertensi) dan hampir setengah pasien infark inferor menunjukkan hiperaktivitas

parasimpatis (bradikardia dan atau hipotensi). Peningkatan suhu sampai 380 C
dapat dijumpai dalam minggu pertama pasien STEMI.
3. Pemeriksaan penunjang
a. Elektrokardiogram
Berdasarkan gambaran EKG pasien SKA dapat diklasifikasikan dalam 3
kelompok:
1. Elevasi segmen ST minimal di dua lead yang berhubungan.
2. Depresi segmen ST atau inverse gelombang T yang dinamis pada saat pasien
mengeluh nyeri dada.
3. EKG non diagnostic baik normal ataupun hanya ada perubahan minimal.7
Pemeriksaan EGK 12 sandapan harus dilakukan pada pasien dengan
keluhan nyeri dada atau keluhan yang dicurigai STEMI. Pemeriksaan ini
dilakukan segera dalam 10 menit sejak kedatangan di IGD. Gambaran elevasi
segmen ST dapat mengidentifikasi pasien yang bermanfaat untuk dilakukan terapi
perfusi. Jika pemeriksaan EKG awal tidak diagnostic untuk STEMI tetapi pasien
tetap simtomatik dan terdapat kecurigaan kuat STEMI, EKG serial dengan
interval 5-10 menit atau pemantauan EKG 12 sandapan secara kontinyu harus
dilakukan untuk mendeteksi perkembangan elevasi segmen ST. pada pasien
dengan STEMI inferior, EKG sisi kanan harus diambil untuk mendeteksi
kemungkinan infark pada ventrikel kanan. Sebagian besar pasien dengan
presentasi awal elevasi segmen ST mengalami evolusi menjadi gelombang Q pada
EKG yang akhirnya didiagnosis infark miokard gelombang Q. sebagian kecil
menetap menjadi infark miokard gelombang non Q. Jika obstruksi trombus tidak
total, obstruksi bersifat sementara atau ditemukan banyak kolateral, biasanya tidak
ditemukan elevasi segmen ST, pasien tersebut mengalami angina pektoris tidak
stabil atau non STEMI. Pada sebagian pasien tanpa elevasi segmen ST
berkembang tanpa menunjukkan gelombang Q disebut infark non Q.
Untuk menentukan lokasi iskemia atau infark miokard serta predileksi
pembuluh koroner mana yang terlibat, diperlukan dua atau lebih sadapan yang
berhubungan yang menujukkan gambaran anatomi daerah jantung yang sama.

Lokasi infark miokard dapat dibagi menjadi beberapa regio, dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:10
Regio infark
miokard
Arteri yang tersumbat Lead EKG yang
mengalami perubahan
Anterior Arteri koronaria
desendens anterior sinistra
V2-V5: “lead dada
anteroseptal”, biasanya juga
pada lead I dan aVL
Inferior Kanan (biasanya) II, III, aVR “lead inferior”
Posterior Kanan atau sirkumfleksa Sulit dilihat : infark dinding
posterior menyebabkan
timbulnya gelombang R
(bukan gelombang q) pada
V1 disertai depresi ST.
Sering bersama-sama
dengan infark miokard
inferior
Lateral Arteri koronaria
desendens anterior sinistra
cabang sirkumfleksa atau
diagonal
I, aVL, V5,6 “lead lateral”
b. Laboratorium

Peningkatan nilai enzim di atas 2 kali nilai batas atas normal menunjukkan
ada nekrosis jantung (infark miokard).
- CKMB : meningkat setelah 3 jam bila ada infark miokard dan mencapai
puncak dalam 10-24 jam dan kembali normal dalam 2-4 hari. Operasi
jantung, miokarditis dan kardioversi elektrik dapat meningkatkan CKMB
- cTn : ada 2 jenis yaitu cTn T dan cTn I. Enzim ini meningkat setelah 2 jam
bila ada infark miorkard dan mencapai puncak dalam 10-24 jam dan cTn T
masih dapat dideteksi setelah 5-14 hari, sedangkan cTn I setelah 5-10 hari.
Pemeriksaan enzim jantung yang lain dapat dilakukan yaitu:
- Mioglobin : dapat dideteksi satu jam setelah infark dan mencapai puncak
dalam 4-8 jam.
- Creatinine Cinase (CK) : meningkat setelah 3-8 jam bila ada infark
miokard dan mencapai puncak dalam 10-36 jam dan kembali normal
dalam 3-4 hari.
- Lactic dehydrogenase (LDH), meningkat setelah 24-48 jam bila ada infark
miokard, mencapai 3-6 hari dan kembali normal dalam 8-14 hari.
2.6 Komplikasi
Komplikasi yang dapat terjadi pada IMA, yaitu:8
1. Gangguan irama dan konduksi
2. Renjatan kardiogenik
3. Gagal jantung kiri
4. Gagal ventrikel kanan
5. Emboli paru dan infark paru
6. Emboli arteri sistemik
7. Sumbatan pembuluh darah otak
8. Ruptur jantung
9. Disfungsi dan ruptur muskulus papilaris
2.7 Penatalaksanaan
1. Terapi inisial pada SKA

Terapi inisial pada pasien sindrom koroner akut (SKA) adalah sebagai
berikut:
a. Oksigen
Suplemen oksigen harus diberikan pada pasien dengan saturasi oksigen
arteri < 90%. Pada semua pasien STEMI tanpa komplikasi dapat diberikan
oksigen selama 6 jam pertama.
b. Nitrogliserin (NTG)
Nitrogliserin sublingual dapat diberikan dengan aman dosis 0,3 mg dan
dapat diberikan sampai 3 dosis dengan interval 5 menit. Selain mengurangi
nyeri dada, NTG juga dapat menurunkan suplai oksigen miokard dengan
menurunkan preload dan meningkatkan suplai oksigen miokard dengan cara
dilatasi pembuluh koroner yang terkena infark atau pembuluh kolateral.
Nitrogliserin Dosis
Tablet sublingual 0,2-0,6 mg/5 menit
Spray 0,4 mg/5 menit
Transdermal atau pasta 0,2-0,8 mg/jam
Intravena 5-200 mcg/menit
c. Aspirin
Aspirin merupakan tatalaksana dasar pada pasien yang dicurigai STEMI dan
efektif pada spektrum sindrom koroner akut. Inhibisi cepat siklooksigenase
trombosit yang dilanjutkan reduksi kadar tromboksan A2 dicapai dengan
absorpsi aspirin bukkal dengan dosis 160-325 mg di ruang emergensi.
Selanjutnya aspirin diberikan oral dengan dosis 75-162 mg.
d. Morfin
Morfin sangat efektif mengurangi nyeri dada dan merupakan analgesik
pilihan dalam tatalaksana nyeri dada. Morfin diberikan dengan dosis 2-4 mg
dan dapat diulang dengan interval 5-15 menit sampai dosis total 20 mg.
2. Terapi reperfusi pada pasien STEMI
a. Obat fibrinolitik
Tujuan utama fibrinolisis adalah restorasi cepat patensi arteri koroner.
Pengobatan fibrinolisis lebih awal < 30 menit dapat membatasi luasnya

infark, fungsi ventrikel normal, dan mengurangi angka kematian. Beberapa
macam obat fibrinolitik antara lain streptokinase, tissue plasminogen
activator (tPA, alteplase), Reteplase (rPA), tenekteplase (TNK). Semua obat
ini bekerja dengan cara memicu konversi plasminogen menjadi plasmin,
yang selanjutnya melisiskan trombus fibrin. Streptokinase dengan dosis 1,5
juta unit IV dalam 60 menit, alteplase dengan dosis bolus 15 mg, dilanjutkan
dengan 0,75 mg/kgBB (max 50 mg)/ 30 mnt, dilanjutkan 0,5 mg/kgBB (max
35 mg) / 1 jam.
Kontra indikasi absolute terapi fibrinolitik adalah :
- Stroke hemoragik
- Stroke iskemik kurang dari 3 bulan dan lebih dari 3 jam
- Tumor intrakranial
- Adanya kelainan stuktur vaskuler serebral
- Adanya cedera kepala tertutup atau cedera wajah dalam 3 bulan terkahir
- Diketahui adanya perdarahan internal aktif atau gangguan sistem
pembekuan darah
- Diseksi aorta
Kontraindikasi relative terapi fibrinolitik adalah:
- Transient ischaemic attack dalam waktu 6 bulan terakhir
- Terapi antikoagulan oral
- Kehamilan atau 1 minggu post partum
- Hipertensi refrakter (TD sistolik > 180 mmHg)
- Penyakit hati stadium lanjut
- Endokarditis infektif
- Ulkus peptikum aktif
b. Antikoagulan
Heparin diberikan bila ada infark luas, tanda-tanda gagal jantung atau bila
diperkirakan bahwa penderita akan dirawat lama. Pada infark miokard akut
yang ST elevasi > 12 jam diberikan Heparin bolus iv 5.000 unit dilanjutkan
drip 10.000 IU/12 jam atau kurang lebih 1000 unit per jam dengan infus

selama rata-rata 5 hari dengan menyesuaikan aPTT 1,5 – 2 x nilai kontrol.
Antikoagulan oral diberikan 3 bulan.6
c. PCI (percutaneous coronary intervention)
Terapi PCI ini memiliki tingkat pengembalian aliran darah sampai 90 %
kasus dan menurunkan risiko perdarahan intrakranial dan syok. Kasus
STEMI pada pasien usia lebih dari 75 tahun dan pasien yang memiliki
kontraindikasi fibrinolitik sebaiknya dilakukan PCI.9,10

BAB III
ILUSTRASI KASUS
Identitas Pasien
Nama : Tn. G
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Masuk RS : 9 November 2014
Tgl periksa : 14 November 2014
ANAMNESIS ( Autoanamnesis)
Keluhan utama
Nyeri dada kiri sejak 1 jam SMRS
Riwayat Penyakit Sekarang
1 jam SMRS pasien mengeluhkan nyeri dada kiri. Nyeri dirasakan muncul
dengan tiba-tiba ketika pasien sedang beristirahat. Nyeri terasa seperti
diremas-remas dan menjalar sampai ke punggung kiri. Serangan nyeri
berlangsung lebih dari 30 menit. Pasien juga mengeluhkan badan terasa
lemas dan berkeringat. Pasien juga merasa nafas menjadi sesak ketika
nyeri. Demam tidak ada, BAB dan BAK tidak ada keluhan. Lalu pasien di
bawa ke IGD RSUD Arifin Achmad.
Riwayat Penyakit Dahulu
Pasien pernah dirawat sebelumnya karena sakit jantung pada tahun 2008
Riwayat hipertensi baru diketahui pasien pada tahun 2008. Pasien tidak
rutin kontrol dan berobat.
Riwayat DM (-)
Riwayat Penyakit Keluarga
Ayah pasien pernah mengalami sakit jantung
Kedua orang tua pasien mempunyai riwayat hipertensi
Riwayat DM (-)
Riwayat Pekerjaan, Kebiasaan, dan Sosial Ekonomi
Pasien bekerja sebagai buruh bangunan.

Pasien memiliki kebiasaan merokok sejak kelas 3 SMP sampai sekarang
Pasien suka makan makanan yang berlemak
PEMERIKSAAN UMUM
Keadaan umum : Tampak Sakit Sedang
Kesadaran : Komposmentis
Tanda – tanda Vital : Tekanan darah :150/90 mmHg
Nadi : 82 x/menit
Nafas : 18 x/menit
Suhu : 36,8 °C
TB : 165 cm
BB : 70 kg
IMT : 25,7
PEMERIKSAAN FISIK :
KEPALA & LEHER :
konjungtiva tidak anemis
sklera tidak ikterik
pembesaran KGB (-)
JPV tidak meningkat
THORAX :
Paru :
Inspeksi : Gerakan dinding dada simetris kanan dan kiri
Palpasi : Vokal fremitus simetris kanan dan kiri
Perkusi : Sonor pada kedua lapangan paru
Auskultasi : Vesikuler pada kedua lapangan paru, ronkhi (-/-),
wheezing (-/-)
Jantung :
Inspeksi : Ictus kordis tidak terlihat.
Palpasi : Ictus kordis teraba pada SIK 6 Linea Aksilaris Anterior
Sinistra

Perkusi : Batas jantung kiri SIK 6 Linea Aksilaris Anterior Sinistra
Batas jantung kanan SIK 5 Linea Parasternal Dekstra
Auskultasi : Bunyi jantung S1 dan S2 dalam batas normal, murmur(-),
gallop(-)
Abdomen :
Inspeksi : Perut tampak datar, venektasi (-), distensi (-)
Auskultasi : Bising usus (+) 10x/menit
Perkusi : Timpani.
Palpasi : Perut supel, hepar dan lien tidak teraba, nyeri tekan (-)
Ekstremitas :
Akral hangat
CRT < 2 detik
Udem ekstremitas (-)
PEMERIKSAAN PENUNJANG :
Pemeriksaan Darah
Leukosit 11,8x103 /uL
Eritrosit 5,15x106 /uL
Hb 15,9 g/dl
Ht 45,9 %
PLT 223x103 /Ul
Pemeriksaan Kimia darah
Glu 96 mg/dl
Chor 163 mg/dl
HDL 28,3 mg/dl
LDL 55,8 mg/dl
TG 353 mg/dl
Ure 25 mg/dl
Cre 0,74 mg/dl
AST 266 u/L
ALT 71 u/L
ALB 3,72 mg/dl

Rontgen Toraks
CTR > 50%
Kesan: Kardiomegali
EKG
Irama : SinusHR : 75 kali / menitRegularitas : RegularInterval PR : 0,16 detikAksis : normalMorfologi : ST elevasi Lead II, III, aVF, V5, V6Kesan : Infark miokard akut inferolateral

RESUME
Tn. G umur 50 tahun masuk Rumah Sakit dengan keluhan nyeri dada kiri
sejak 1 jam SMRS. Nyeri dirasakan muncul dengan tiba-tiba ketika pasien sedang
beristirahat. Nyeri terasa seperti diremas-remas dan menjalar sampai ke punggung
kiri. Serangan nyeri berlangsung lebih dari 30 menit. Pasien juga mengeluhkan
badan terasa lemas dan berkeringat. Pasien juga merasa nafas menjadi sesak
ketika nyeri.
Pasien pernah dirawat sebelumnya karena sakit jantung pada tahun 2008.
Riwayat hipertensi baru diketahui pasien pada tahun 2008 dan pasien tidak rutin
untuk kontrol dan berobat. Pasien memiliki kebiasaan merokok sejak kelas 3 SMP
sampai sekarang. Pasien suka makan makanan yang berlemak.
Dari pemeriksaan fisik didapatkan TD 150/90 mmHg, batas jantung kanan
SIK 5 Linea Parasternal Dekstra, batas jantung kiri SIK 6 Linea Aksilaris Anterior
Sinistra. Pada pemeriksaan kimia darah HDL 28,3 mg/dl, TG 353 mg/dl. Dari
rontgen toraks didapatkan kesan kardiomegali. Pada pemeriksaan EKG
didapatkan ST Elevasi pada lead II, III, aVF, V5, V6.
DIAGNOSIS KERJA :
Infark miokard akut inferolateral dengan ST Elevasi
Hipertensi Heart Disease
Dislipidemia
RENCANA PENATALAKSANAAN
Non Farmakologi:
Bed rest
Hindari aktivitas yang berlebihan
Diet rendah garam
O2 3L nasal kanul
Farmakologi
ISDN 3x5 mg
Aspilet 1x80 mg

Clopidogrel 1x75 mg
Captopril 2x12,5 mg
Simvastatin 1x20 mg
IVFD RL bolus Heparin 5000 unit, kemudian lanjutkan drip 20.000
unit/24 jam selama 5 hari.
Inj Ranitidine 2x1 ampul

PEMBAHASAN
Pasien Tn. G 50 tahun masuk dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 1 jam
sebelum masuk rumah sakit (SMRS). Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik
dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada pasien
ini mengalami infark miokard akut inferolateral dengan ST elevasi.
Berdasarkan anamnesis didapatkan pasien mengeluhkan nyeri dada khas
infark yaitu nyeri seperti ditekan dan terasa tumpul, menjalar punggung kiri,
berlangsung sekitar ± 30 menit. Pasien juga memiliki faktor risiko seperti
hipertensi, merokok, dan makan makanan yang berlemak. Dari pemeriksaan fisik
jantung dan rontgen thoraks didapatkan adanya pembesaran jantung. Dari
pemeriksaan EKG didapatkan infark miokard akut inferolateral (ST elevasi pada
II, III, aVF, V5, V6), sehingga infark miokard pada pasien ini digolongkan ke
dalam STEMI.
Keluhan nyeri dada dan sesak nafas pada pasien terjadi karena oklusi
lumen arteri koroner yang mendadak sehingga mengganggu aliran darah ke distal
dan menyebabkan nekrosis miokard. Sesak nafas merupakan suatu kompensasi
agar kebutuhan oksigen terpenuhi.
Hipertensi, merokok, dan dislipidemia pada pasien ini merupakan faktor
risiko terbentuknya aterosklerosis. Tekanan darah pasien yang tinggi dan menetap
akan menimbulkan trauma pada dinding pembuluh darah arteri koronaria,
sehingga memudahkan terjadinya aterosklerosis. Pada pasien ini STEMI terjadi
karena aliran darah koroner menurun secara mendadak setelah oklusi thrombus
total pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya.
Kardiomegali pada pasien ini dapat disebabkan oleh riwayat hipertensi
yang lama. Hipertensi merupakan beban berat untuk jantung sehingga terjadi
hipertrofi ventrikel kiri dan gangguan fungsi diastolik (asimptomatik/subklinik)
yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan sistolik ventrikel kiri.
Hipertrofi ventrikel kiri merupakan respon terhadap kenaikan wall stress ventrikel
kiri akibat hipertensi dan suatu upaya untuk mengembalikan wall stress ventrikel
kiri kepada nilai normal, mempertahankan fungsi sistolik ventrikel kiri dan

mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan perfusi miokard. Hipertrofi
ventrikel kiri juga dapat menyebabkan penyempitan pada arteri koronaria.
Terapi pasien ini yaitu pemberian oksigen, ISDN, aspilet, captopril,
clopidogrel, dan heparin.. Pemberian obat vasodilator pada pasien ini berupa
pemberian ISDN, berguna dalam mengurangi preload jantung dengan
meningkatkan kapasitas vena sehingga dapat menurunkan kebutuhan oksigen
miokard dan meningkatkan suplai oksigen miokard dengan cara dilatasi
pembuluh koroner yang terkena infark atau pembuluh kolateral. Aspilet dan
clopidogrel merupakan antitrombotik yang bekerja menghambat pembentukan
trombus. Captopril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang bekerja
menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga dapat
menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Heparin merupakan antikoagulan
yang digunakan untuk menghambat proses pembekuan darah.

DAFTAR PUSTAKA
1. Alwi I. Infark Miokard Akut dengan ST Elevasi. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid II. Edisi V. Jakarta: Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2010: 1741-54.
2. Bajzer Christopher T. Acute Myocardial Infarction. 2008. http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/acutemi/acutemi.htm. [diakses 1 juli 2013]
3. Tumer HE. Infark Miokard Akut. Dalam: Davey P, editors. At a Glance Medicine. Jakarta: Erlangga. 2006: 144-5.
4. Irmalita. Infark Miokard. Dalam: Rilantono LI, Baraas F, Karo SK, Roebiono PS, editors. Buku Ajar Kardiologi. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002: 173-81
5. Kalim, H., dkk. 2004. Pedoman Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia: Tatalaksana Sindroma Koroner Akut Dengan ST-Elevasi. Jakarta: PERKI.
6. Fenton DE. Myocardial Infarction. http://www.emedicine.com/emerg/TOPIC327.HTM
7. Brown CT. Penyakit Aterosklerotik Koroner. Dalam: Price SA, Wilson LM, editors. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Jakarta: EGC, 2006; 31: 579-80.
8. Tumer HE. Infark Miokard Akut. Dalam: Davey P, editors. At a Glance Medicine. Jakarta: Erlangga. 2006: 144-5.
9. Karo-karo, S. Rahajoe, A. U. Kursus bantuan hidup jantung lanjut. Jakarta: perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular indonesia. 2011: 75-8
10. Kusmana, D. Setianto, B. Standar pelayanan medik Rumah Sakit jantung dan pembuluh darah Harapan kita. Jakarta: 2003: 12-8.