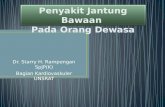PJB ISI
-
Upload
denisafriansyah -
Category
Documents
-
view
53 -
download
12
Transcript of PJB ISI

PENDAHULUAN
Jantung adalah organ muskular berongga yang terletak di rongga dada, di bawah
perlindungan tulang iga, sedikit ke sebelah kiri sternum. Secara fungsional jantung dibagi 2 sisi,
jantung kanan dan jantung kiri. Jantung terdiri dari 4 rongga : atrium kanan, atrium kiri, ventrikel
kanan, ventrikel kiri. Antara atrium kanan dan atrium kiri terdapat septum atrium. Antara
ventrikel kanan dan ventrikel kiri terdapat septum ventrikel. Antara atrium dan ventrikel terdapat
katup atrioventrikuler. Katup trikuspid adalah Katup AV di kanan jantung, katup mitral adalah
katup AV di kiri jantung. Antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis terdapat katup
semilunaris pulmonalis, dan antara ventrikel kiri dan aorta terdapat katup semilunaris aorta.1
Gambar 1. Anatomis Jantung2
1

Gambar 2. Peredaran darah manusia2
Sirkulasi Fetus: Tiga fitur utama dari sirkulasi fetus adalah :
1. Sirkulasi maternal (ibu) melalui placenta membawa oksigen dan nutrisi ke fetus dan
mengeluarkan karbon dioksida dari sirkulasi fetus.
2. Foramen ovale adalah sebuh lubang yang terletak di septum (dinding) antara kedua
ruangan atas jantung (atria kanan dan kiri). Foramen mengizinkan darah mengalir melalui
jalur samping (shunt) dari atrium kanan ke atrium kiri.
3. Jalur samping yang lain, ductus arteriosus, mengizinkan darah yang miskin oksigen
mengalir dari arteri pulmonary kedalam aorta dan melalui itu ke tubuh.
2

Sirkulasi sesudah kelahiran: Placenta sudah dikeluarkan dan paru-paru harus mengambil alih
fungsi oksigenisasi darah. Perubahan-perubahan utama sirkulasi terjadi setelah kelahiran.
Perubahan-perubahan ini termasuk :
Sirkulasi maternal tidak dapat lagi membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida
dari sirkulasi bayi.
Foramen ovale menutup dan tidak bertindak lagi sebagai jalur samping antara kedua atria
jantung.
Ductus arteriosus menutup dan tidak lagi menyediakan komunikasi antara arteri
pulmonary dan aorta
Sekali ini terjadi, maka sirkulasi fetus menjadi suatu barang dari masa lalu dan seluruh pengaruh
dari berbagai kerusakan jantung genital dirasakan. Kerusakan-kerusakan ini menjadi nyata,
menyebabkan tanda-tanda dan gejala-gejala yang dapat didiagnosis. Perubahan-perubahan lebih
jauh terjadi di sistim kardiovaskular selama waktu bayi dan waktu anak-anak dan juga di
hubungan tekanan antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Perubahan-perubahan ini membawa
lebih banyak kasus-kasus PJB ke permukaan.
Gambar 3. Skema Sirkulasi darah pada neonatus
3

Gambar 4. Sirkulasi darah pada neonatus
4

Sirkulasi darah pada janin dan bayi terdapat perbedaan, antara lain :
1. Pada janin terdapat pirau intrakardiak (foramen ovale) dan pirau ekstrakardiak(duktus
arteriosus Botalli, duktus venosus Arantii) yang efektif. Arah pirau adalah dari kanan
ke kiri, yakni dari atrium kanan ke kiri melalui foramen ovale dan dari a.pulmonalis
menuju ke aorta melalui duktus arteriosus. Pada sirkulasi pascalahir pirau intra-
maupun ekstra kardiak tersebut tidak ada.
2. Pada janin ventrikel kiri dan kanan bekerja serentak, sedang pada keadaan pasca lahir
ventrikel kiri berkontraksi sedikit lebih awal dari ventrikel kanan.
3. Pada janin ventrikel kanan memompa darah ke tempat dengan tahanan yang lebih
tinggi, yakni tahanan sistemik, sedang ventrikel kiri melawan tahanan yang rendah
yakni plasenta. Pada keadaan pasca lahir ventrikel kanan akan melawan tahanan paru,
yang lebih rendah daripada tahanan sistemik yang dilawan ventrikel kiri.
4. Pada janin darah yang dipompa oleh ventrikel kanan sebagian besar menuju ke aorta
melalui duktus arteriosus, dan hanya sebagian kecil yang menuju ke paru. Pada
keadaan pasca lahir darah dari ventrikel kanan seluruhnya ke paru.
5. Pada janin paru memperoleh oksigen dari darah yang mengambilnya dari plasenta;
pasca lahir paru memberi oksigen kepada darah.
6. Pada janin plasenta merupakan tempat yang utama untuk pertukaran gas, makanan,
dan ekskresi. Pada keadaan pascalahir organ-organ lain mengambil alih berbagai
fungsi tersebut.
7. Pada janin terjamin berjalannya sirkuit bertahanan rendah oleh karena terdapatnya
plasenta. Pada keadaan pasca lahir hal ini tidak ada.3,4
5

Latar Belakang
Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini angka kejadian beberapa penyakit non-infeksi makin
menonjol, baik di negara maju maupun negara berkembang. Perbaikan tingkat sosial ekonomi
telah membawa perubahan pola penyakit. Penyakit infeksi serta defisiensi gizi makin lama
makin menyurut, sedangkan pelbagai penyakit non-infeksi, termasuk penyakit kongenital makin
meningkat. Peristiwa tersebut juga terjadi dalam bidang kardiologi. Di Indonesia, walaupun
belum ada data PJB yang akurat, namun masalah PJB jelas telah memerlukan perhatian yang
sungguh-sungguh baik dari dokter umum maupun spesialis. Data Poliklinik Jantung Anak di
Bagian Anak FKUI—RSCM melaporkan peningkatan jumlah pengunjung dari 241 menjadi 512
pada tahun 1970 dan 1973. Jumlah PJB (72%) lebih tinggi dari Penyakit Jantung Didapat (28%),
dan jumlah konsultasi berasal dari Dokter umum (47%) tidak jauh berbeda dari dokter spesialis
(53%).5
Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyakit jantung bawaan sangat diperlukan bagi
mahasiswa kedokteran dalam menunjang standart kompetensi pendidikan dokter. Dalam laporan
ini, penulis tidak membahas semua PJB. Namun, penulis hanya membahas PJB yang
berhubungan dengan kasus dan yang menjadi standart kompetensi dokter umum.
6

PENYAKIT JANTUNG BAWAAN
(CONGENITAL HEART DESEASE)
Congenital heart disease (CHD) atau penyakit jantung kongenital adalah kelainan jantung
yang sudah ada sejak bayi lahir, jadi kelainan tersebut terjadi sebelum bayi lahir. Tetapi kelainan
jantung bawaan ini tidak selalu memberi gejala segera setelah bayi lahir, tidak jarang kelainan
tersebut baru ditemukan setelah pasien berumur beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun.
Insidensi terjadinya adalah 6-10 (rata-rata 8) per 1000 kelahiran hidup, insidens ini tidak
banyak berbeda dengan rumah sakit di luar negeri seluruh dunia, baik di Negara maju maupun di
Negara yang sedang berkembang. Dari seluruh penyakit jantung bawaan, kira-kira sepertiga
masuk ke dalam golongan penyakit jantung bawaan sianotik, dan sisanya non-sianotik. Frekuensi
relatif masing-masing jenis penyakit jantung bawaan dapat di lihat pada table dibawah.
Jenis kelainan Frekuensi relatif
Defek Septum ventrikel 20
Defek septum atrium 10
Duktus arteriosus persisten 10
Stenosis pulmonal 10
Tetralogi Fallot 8
Defek septum atrioventrikular 5
Stenosis aorta 5
Koartasio aorta 5
Transposisi arteri besar 5
Trunkus arteriosus 2
Atresia pulmonal 2
Anomaly total drainase vena pulmonalis 1
Atresia trikuspid 1
Anomaly ebstein 1
Ventrikel kanan jalan keluar ganda 1
Interupsi arkus aorta 1
7

Sindrom hipoplasia jantung kiri 1
Kombinasi kelainan dan lain-lain Sisanya
Tabel 1. Frekuensi relatif penyakit jantung bawaan5
Embriogenesis jantung
Embriogenesis jantung merupakan serangkaian proses yang kompleks. Untuk keperluan
pemahaman , proses yang rumit tersebut dapat disederhanakan menjadi empat tahapan, yaitu :6
1. Tubing, yaitu tahapan ketika bakal jantung masih merupakan tabung sederhana
2. Looping, yakni suatu peristiwa kompleks berupa perputaran bagian-bagian bakal jantung
dan arteri besar (aorta dan a. Pulmonalis)
3. Septasi, yakni proses pemisahan bagian-bagian jantung serta arteri besar dengan
pembentukan berbagai ruang jantung
4. Migrasi, yakni pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya.
Perlu diingat bahwa keempat proses tersebut benar-benar merupakan proses yang terpisah,
namun merupakan rangkaian proses yang saling tumpang tindih.6
Etiologi
Penyebab penyakit jantung congenital berkaitan dengan kelainan perkembangan
embrionik, pada usia lima sampai delapan minggu, jantung dan pembuluh darah besar dibentuk.
Gangguan perkembangan mungkin disebabkan oleh factor-faktor prenatal seperti infeksi ibu
selama trimester pertama. Agen penyebab lain adalah rubella, influenza atau chicken fox. Factor-
faktor prenatal seperti ibu yang menderita diabetes mellitus dengan ketergantungan pada insulin
serta factor-faktor genetic juga berpengaruh untuk terjadinya penyakit jantung congenital. Selain
factor orang tua, insiden kelainan jantung juga meningkat pada individu. Faktor-faktor
lingkungan seperti radiasi, gizi ibu yang jelek, kecanduan obat-obatan dan alcohol juga
mempengaruhi perkembangan embrio.7,4
8

Tanda dan Gejala
1. INFANTS:8
Dyspnea
Difficulty breathing
Pulse rate over 200 beats/mnt
Recurrent respiratory infections
Failure to gain weight
Heart murmur
Cyanosis
Cerebrovasculer accident
Stridor and choking spells
2. CHILDREN8
Dyspnea
Poor physical development
Decrease exercise tolerance
Recurrent respiratory infections
Heart murmur and thrill
Cyanosis
Squatting
Clubbing of fingers and toes
Elevated blood pressure
Gambar 5. Clubbing Fingers
9

Klasifikasi
Terdapat berbagai cara penggolongan penyakit jantung kongenital. Penggolongan yang
sangat sederhana adalah penggolongan yang didasarkan pada adanya sianosis serta vaskularisasi
paru.4,5,9
1. Penyakit Jantung bawaan (PJB) non sianotik dengan vaskularisasi paru bertambah,
misalnya defek septum ventrikel (DSV), defek septum atrium (DSA), dan duktus
arteriousus persisten (DAP)
2. PJB non sianotik dengan vaskularisasi paru normal. Pada penggolongan ini termasuk
stenosis aorta (SA), stenosis pulmonal (SP) dan koarktasio aorta
3. PJB sianotik dengan vaskularisasi paru berkurang. Pada penggolongan ini yang paling
banyak adalah tetralogi fallot (TF)
4. PJB sianotik dengan vaskularisasi paru bertambah, misalnya transposisi arteri besar
(TAB)
PENDEKATAN KLINIS UNTUK PENYAKIT JANTUNG BAWAAN SIANOSIS YANG
DISERTAI PENURUNAN ALIRAN DARAH KE PARU (CARDIAC CYANOSIS) PADA
NEONATUS
Sianosis adalah manifestasi klinis tersering dari PJB simptomatik pada neonatus. Sianosis
tanpa disertai gejala distres nafas yang jelas hampir selalu akibat PJB, sebab pada kelainan
parenkhim paru yang sudah sangat berat saja yang baru bisa memberikan gejala sianosis dengan
demikian selalu disertai gejala distres nafas yang berat.
Pada neonatus normal, pelepasan oksigen ke jaringan harus sesuai dengan kebutuhan
metabolismenya. Jumlah oksigen yang dilepaskan ke jaringan bergantung kepada aliran darah
sistemik, kadar hemoglobin dan saturasi oksigen arteri sistemik. Pada saat lahir, kebutuhan
oksigen meningkat sampai 3 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme agar
menghasilkan enersi untuk bernafas dan termoregulasi. Untuk ini diperlukan peningkatan aliran
darah sistemik 2 kali lipat dan saturasi oksigen 25% sehingga pelepasan dan pengikatan oksigen
di jaringan juga meningkat sesuai kebutuhan. sianosis perifer (acrocyanosis) sering dijumpai
pada neonatus, hal ini akibat tonus vasomotor perifer yang belum stabil. Tampak warna kebiruan
10

pada ujung jari tangan dan kaki serta daerah sekitar mulut, disertai suhu yang dibawah normal
dan hiperoksia tes menunjukkan hasil yang negatif.
Pada neonatus dengan PJB sianosis, tidak mampu meningkatkan saturasi oksigen arteri
sistemik, justru sangat menurun drastis saat lahir, sehingga pelepasan dan pengikatan oksigen di
jaringan menurun. Kondisi ini bila tidak segera diatasi mengakibatkan metabolisme anaerobik
dengan akibat selanjutnya berupa asidosis metabolik, hipoglikemi, hipotermia dan kematian.
Sianosis sentral akibat penyakit jantung bawaan (Cardiac cyanosis) yang disertai
penurunan aliran darah ke paru oleh karena ada hambatan pada jantung kanan, yaitu katup
trikuspid atau arteri pulmonalis. Kondisi ini mengakibatkan kegagalan proses oksigenasi darah di
paru sehingga darah dengan kadar oksigen yang rendah (unoxygenated) akan beredar ke sirkulasi
arteri sistemik melalui foramen ovale atau VSD (pada tetralogy Fallot). Seluruh jaringan tubuh
akan mengalami hipoksia dan menimbulkan gejala klinis berupa sianosis sentral tanpa gejala
gangguan pernafasan. Kesulitan akan timbul, bila sianosis disertai tanda-tanda distres
pernafasan. Terdapatnya anemia berat mengakibatkan jumlah Hb yang tereduksi tidak cukup
menimbulkan gejala sianosis. Adanya pigmen yang gelap sering mengganggu sianosis sentral
yang berderajat ringan akibat PJB. Sianosis perifer bila disertai bising inoccent dapat
menyesatkan dugaan adanya PJB sianotik.
Beberapa kondisi klinis yang memberikan dugaan cardiac cynosis pada neonatus dan sudah
merupakan alasan yang cukup untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, didasari
beberapa alasan tambahan sebagai berikut :
1. Hipoksemia sistemik menimbulkan gejala sianosis sentral
2. Sianosis sentral akibat PJB tidak timbul segera setelah lahir
3. Sianosis sentral tidak tampak selama saturasi oksigen arteri masih diatas 85
4. Sianosis sentral dengan frekuensi pernafasan yang cepat (hiperventilasi) tanpa disertai
pernafasan cuping hidung dan retraksi ruang iga serta kadar CO2 yang rendah.
5. Sianosis sentral dengan tes hiperoksia positif.
11

6. Harus dicari apakah aliran darah sistemik berasal dari ventrikel kanan atau kiri, adanya
duktus yang masih terbuka mengakibatkan aliran darah aorta asenden dan disenden
berasal dari ventrikel yang tidak sama. Pada kondisi ini diperlukan pemasangan pulse
oxymetri pada tangan kanan dan kaki.
PENDEKATAN KLINIS UNTUK PENYAKIT JANTUNG BAWAAN YANG DISERTAI
PENINGKATAN ALIRAN DARAH KE PARU (NON SIANOSIS) PADA NEONATUS
Pada neonatus - neonatus normal, saat lahir masih disertai tahanan arteri pulmonalis yang
tinggi. Setelah 4-12 minggu terjadi penurunan tahanan arteri pulmonalis sampai menuju nilai
normal. Pada neonatus dengan PJB non sianotik, selama tahanan arteri pulmonalis masih tinggi,
defek jantung yang ada belum menimbulkan perubahan aliran darah dari sistemik ke paru.
Setelah 4-12 minggu postnatal, pada saat terjadi penurunan tahanan arteri pulmonalis sampai
menuju nilai normal, defek jantung yang dan akan menimbulkan perubahan aliran darah yaitu
yang seharusnya ke sistemik berubah menuju ke paru. Pada saat inilah baru terjadi pirau kiri ke
kanan disertai gejala klinis berupa mulai terdengarnya bising sampai gagal jantung dengan gejala
utama takipnea.
Harus dibedakan takipnea akibat PJB dan akibat kelainan parenkhim paru. Takipnea
akibat PJB non sianosis pada neonatus baru timbul bila peningkatan aliran darah ke paru sampai
lebih dari 2,5 kali aliran normal. Takipnea akibat penyakit paru pada neonatus sudah timbul
walaupun peningkatan aliran darah ke paru masih ringan-ringan saja. Adanya penyakit pada paru
akan memperjelas gejala takipnea pada PJB usia neonatus.
Peningkatan aliran darah ke paru mengakibatkan peningkatan tekanan prekapiler di paru
dan aliran limfatik sehingga terjadi peningkatan cairan intersisial di parenkhim paru dan terutama
di peribronkhial. Hal ini mengakibatkan penurunan fungsi bronkhioli dan terjadi penurunan
aliran udara serta peningkatan tekanan udara, kondisi ini meningkatkan work of breathing dan
terdengarnya wheezing expiratoir.
12

PENDEKATAN KLINIS UNTUK PENYAKIT JANTUNG BAWAAN YANG DISERTAI
PENURUNAN ALIRAN DARAH KE SISTEMIK PADA NEONATUS
Penurunan aliran darah ke sistemik akibat PJB pada neonatus berupa
hambatan aliran darah dari paru atau atrium kiri ke ventrikel kiri
ventrikel kiri tidak adekuat memompa darah ke aorta. Kedua kondisi ini mengakibatkan
peningkatan tekanan vena paru dan edema paru serta penurunan perfusi organ-organ
vital.
Gejala klinis tampak segera setelah lahir dan berat, berupa penurunan suhu kulit dan
perubahan warna kulit yang pucat, penurunan tekanan darah sampai tidak terukur, sulit atau tidak
terabanya denyut nadi perifer, hiperaktif RV, dan penurunan capillary refile, metabolik asidosis
berat serta distres nafas sedang sampai berat.
Denyut nadi dan tekanan darah harus diukur pada ektremitas atas dan bawah, normal tekanan
darah ekstremitas bawah lebih tinggi. Bila ada perbedaan denyut nadi tanpa disertai perbedaan
tekanan darah, harus diraba pulsasi arteri karotis. Perbedaan pulsasi arteri karotis dengan pulsasi
ekstremitas bawah dan ekstremitas bawah menunjukkan kemungkinan koartasio aorta,
interrupted aorta atau arteri subklavia berasal dari aorta. Ada keadaan pada neonatus yang baru
lahir dengan penurunan perfusi perifer disertai gejala distres nafas derajat sedang sampai berat
yang disertai retraksi ruang iga, subkosta, nafas cuping hidung dan grunting, yaitu persistent
pulmonary hypertension dan total anomalous pulmonary venous return. Kedua kondisi ini sulit
dibedakan!, pada persistent pulmonary hypertension sering disertai riwayat prenatal berupa
ketuban pecah dini, sindroma aspirasi mekonium atau asfiksia berat.
13

VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (VSD)
VSD merupakan kelainan jantung bawaan yang tersering dijumpai, yaitu 33% dari
seluruh kelainan jantung bawaan.8 Tergantung pada umur anak yang diperiksa dan jenis
pemeriksaan, angka berkisar 1 sampai 7 per 1000 kelahiran hidup diketahui sebagai insidens
defek sekat ventrikel. Perlu direncanakan pelayanan diagnostik dan terapeutik pada bayi atau
anak dengan kelainan tersebut.10
VSD terjadi bila sekat ventrikel tidak terbentuk dengan sempurna. Istilah defek septum
ventrikel menggambarkan suatu lubang pada sekat ventrikel. Defek tersebut dapat terletak di
manapun pada sekat ventrikel, dapat tunggal atau banyak, dan ukuran serta bentuknya dapat
bervariasi. Akibatnya darah dari bilik kiri mengalir ke bilik kanan pada saat systole.10
Embriologi Terjadinya VSD
Antara minggu ke empat hingga ke delapan kehamilan, rongga ventrikel yang semula
tunggal terbagi menjadi dua. Hal tersebut terlaksana akibat fusi pars membranasea septum,
bantalan endokardium, dan bulbus kordis. Pars muskularis septum tumbuh kearah cranial
bersama dengan pembesaran ruang ventrikel, sampai akhirnya bertemu dengan rigi (ridge)
bulbus kordis kanan dan kiri. Rigi sebelah kanan bersatu dengan katup tricuspid dan bantalan
endokardium, sehingga akan memisahkan katup pulmonal dari katup tricuspid. Rigi yang
disebelah kiri bersatu dengan rigi pada septum ventrikel, sehingga akhirnya cincin aorta
merupakan suatu kontinuitas dengan cincin mitral. Bantalan endokardium secara bersamaan
tumbuh dan kemudian bersatu dengan rigi bulbus dan pars muskularis septum. Penutupan akhir
dan separasi kedua ventrikel terjadi dengan jaringan fibrosa pada pars membranasea septum.5
14

Defek septum ventrikel disebabkan oleh keterlambatan penutupan sekat interventrikuler
sesudah kehidupan interauterin 7 minggu pertama, alasan penutupan terlambat atau tidak
sempurna belum diketahui. Kemungkinan faktor keturunan berperan dalam hal ini. Defek septum
ventrikel adalah jelas lebih sering pada bayi prematur dan pada mereka yang berat badan lahir
rendah, dengan laporan insidensi setinggi 7,06 per 1000 kelahiran prematur hidup.7,10
Gambar 6. Jantung normal dan jantung dengan VSD1
15

Gambar 7. VSD2
Klasifikasi
Berdasarkan lokasi lubang, dibagi 3: 11,12
1. Perimembranous (tipe paling sering, 60%) bila lubang terletak di daerah pars membranaceae
septum interventricularis
2. Subarterial doubly commited, bila lubang terletak di daerah septum infundibuler dan sebagian dari
batas defek dibentuk oleh terusan jaringan ikat katup aorta dan katup pulmonal
3. Muskuler, bila lubang terletak di daerah septum muskularis interventrikularis
16

Patofisiologi
Adanya lubang pada septum interventrikularis memungkinkan terjadinya aliran darah dari
ventrikel kiri ke ventrikel kanan oleh karena gradien tekanan sehingga aliran darah ke paru bertambah.
Gambaran klinis tergantung dari besarnya defek dan aliran darah (shunt) serta besarnya tahanan
pembuluh darah paru. 3
Apabila defek kecil atau restriktif tidak tampak adanya gejala (asimptomatik). Pada defek kecil
gradien tekanan ventrikel kiri dan kanan sebesar > 64 mmHg, tekanan sistolik ventrikel kanan dan
resistensi pulmonal normal. Pada defek moderat dengan restriksi gradien tekanan ventrikel kiri dan kanan
berkisar 36 mmHg, resistensi pulmonal dan tekanan sistolik ventrikel kanan meningkat namun tidak
melebihi tekanan sistemik. Pada keadaan ini, ukuran ventrikel kiri dan atrium kiri dapat membesar akibat
bertambahnya beban volume.6
Pada defek septum ventrikel sedang dan besar tanpa penyakit vaskular paru terjadi pirau
kiri ke kanan yang bermakna, sehingga terjadilah perubahan yang tercermin pada foto dada.
Adanya pembesaran ventrikel kiri dan atrium kiri, konus pulmonalis menonjol, dangan aorta
normal. Ventrikel kanan dan atrium kanan normal. Pada elektrokardiogram akan tampak
hipertrofi ventrikel kiri dan kadang disertai dengan pembesaran atrium kiri.5
Bila sudah terjadi penyakit vaskular paru atau hipertensi pulmonal/ sindrom eisenmenger,
maka akan terjadi pirau terbalik (kanan ke kiri) sehingga pada foto dada akan tampak atrium
kanan dan ventrikel kanan membesar, konus pulmonalis sangat menonjol, serta terdapat
gambaran ’pruning’ yakni vaskularisasi paru di hilus amat meningkat, sedangkan vaskularisasi di
perifer berkurang. Jantung kanan normal. Pada elektro kardiogram tampak hipertrofi ventrikel
kanan, dan pembesaran atrium kanan.14 Pada keadaan ini memberikan keluhan seperti sesak napas dan
cepat capek serta sering mengalami batuk dan infeksi saluran napas berulang. Hal ini mengakibatkan
gangguan pertumbuhan.3
Dalam perjalanannya, beberapa VSD dapat menutup secara spontan (tipe perimembranous dan
muskuler), terjadi hipertensi pulmonal, hipertrofi infundibuler, atau prolaps katup aorta yang dapat
disertai regurgitasi (tipe subarterial dan perimembranous). 4,8
17

Gambar 8. Patofisologi VSD2
18

A B
19

C
Gambar 9. VSD ringan – VSD sedang – VSD berat
Gambar 10. VSD besar dg tahanan vaskular paru tinggi
20

Gambaran Klinis
Defek kecil asimtomatik, defek sedang hingga besar menimbulkan keluhan seperti
kesulitan waktu minum atau makan karena cepat lelah atau sesak dan sering mengalami batuk
serta infeksi saluran napas berulang. Ini menyebabkan pertumbuhan yang lambat.8
Pada pemeriksaan selain didapat pertumbuhan terhambat, anak terlihat pucat, banyak
keringat bercucuran, ujung-ujung jari hiperemik. Diameter dada bertambah, sering terlihat
pembonjolan dada kiri. Tanda yang menojol adalah nafas pendek dan retraksi pada jugulum, seia
intrakostal dan region epigastrium. Pada anak yang kurus terlihat impuls jantung yang
hiperdinamik.5,9
Pada pemeriksaan fisik biasanya terlihat takipneu, aktivitas ventrikel kiri meningkat,
dapat teraba thrill sistolik, bunyi jantung II mengeras bila telah terjadi hipertensi pulmonal,
terdengar bising pansistolik di SIC 3-4 parasternal kiri yang menyebar sepanjang parasternal dan
apeks. Pada pirau yang besar dapat terdengar bising middiastolik di apeks akibat aliran
berlebihan, dapat ditemukan gagal jantung kongestif. Bila telah terjadi penyakit vaskuler paru
dan sindrom eisenmenger, penderita tampak sianosis dengan jari tabuh, bahkan mungkin disertai
tanda gagal jantung kanan. 8,12
Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan bising holosistolik (pansistolik) yang terdengar selama
fase sistolik, keras, kasar di atas tricuspid di sela iga 3-4 parasternal kiri menyebar sepanjang parasternal
dan apex cordis. Bising ini sudah dapat terdengar selama defek VSD kecil. Bising mid-diastolik dapat
didengar di apex cordis akibat aliran berlebihan. Pada VSD sering bersifat non-sianotik kecuali apabila
terjadi eisenmengerisasi (terjadi aliran shunt kanan ke kiri). pada penderita VSD dengan aliran shunt yang
besar biasany terlihat takipneu, aktivitas ventrikel kiri meningkat dan dapat teraba thrill sistolik. Apabila
terjadi aliran shunt dari kanan ke kiri dengan defek besar akan tampak stenosis dengan jari-jari tabuh
(clubbing of finger). Pada defek cukup besar dapat terjadi komplikasi berupa stenosis infundibuler,
prolaps katup aorta, insufiensi aorta, hipertensi pulmonal dan gagal jantung. 8
21

Pemeriksaan
1. Foto thorax : dapat ditemukan kardiomegali dengan LVH, vaskularisasi paru
meningkat, bila terjadi penyakit vaskuler tampak pruned tree disertai penonjolan a.
pulmonal.
2. Elektrokardiografi : LVH, LAH. Deviasi sumbu QRS ke kiri dengan hipertrofi
biventrikular. Interval P-R biasanya memanjang. Bila terdapat hipertrofi kedua ventrikel dan
deviasi sumbu QRS ke kanan maka perlu dipikirkan adanya hipertensi pulmonal atau hipertrofi
infundibulum ventrikel kanan
3. Ekokardiografi : dengan M-mode dapat diukur dimensi atrium kiri dan ventrikel
kiri, dengan ekokardiografi 2 dimensi dapat dideteksi dengan tepat ukuran dan lokasi
defek septum ventrikel, dengan defek doppler dan warna dapat dipastikan arah dan
besarnya aliran yang melewati defek tersebut.
4. Kateterisasi jantung : dilakukan pada penderita dengan hipertensi pulmonal, dapat
mengukur rasio aliran ke paru dan sistemik serta mengukur tahanan paru; angigrafi
ventrikel kiri dilakukan untuk melihat jumlah dan lokasi VSD. 1,7,13
Gambar 11. Rontgent VSD : kardiomegali
22

Gambar 12. Ekokardiografi VSD
Penatalaksanaan
Pasien dengan VSD besar perlu ditolong dengan obat-obatan untuk mengatasi gagal
jantung. Biasanya diberikan digoksin dan diuretic, misalnya lasix. Bila obat dapat memperbaiki
keadaan, yang dilihat dengan membaiknya pernafasan dan bertambahnya berat badan, rnaka
operasi dapat ditunda sampai usia 2-3 tahun. Tindakan bedah sangat menolong karena tanpa
tindakan tersebut harapan hidup berkurang.7,13
Pada usia 2 tahun, minimal sebanyak 50% VSD yang berukuran kecil atau sedang akan
menutup secara spontan baik sebagian atau seluruhnya sehingga tidak diperlukan tatalaksana
23

bedah. Operasi penutupan sekat pada bayi usia 12-18 bulan direkomendasikan apabila terdapat
VSD dengan gagal jantung kongestif atau penyakit pembuluh darah pulmonal. Gangguan atau
lubang yang berukuran sedang namun tanpa disertai dengan peningkatan tekanan pembuluh
darah pulmonal, penanganannya dapat ditunda. Terapi pengobatan untuk profilaksis atau
pencegahan endokarditis (peradangan pada endokardium atau selaput jantung bagian dalam)
diberikan untuk semua pasien dengan VSD.9,12
Operasi merupakan tindakan definitif berdasarkan rasio aliran ke paru terhadapa sistemik
dan rasio tahanannya. Indikasi bila ratio > 2 (highflow). Kontraindikasi bila ratio < 1
(lowflow).9,13
Medikamentosa
Penatalaksanaan CHF dengan digitalis dan diuretik.
Tidak diperlukan pembatasan aktivitas kecuali bila telah terjadi hipertensi pulmonal.
Perlu diperhatikan higiene gigi dan profilaksis terhadap SBE.
24

DAFTAR PUSTAKA
1. Rakhman, Otte. 2003. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik pada Penyakit Jantung. Dalam : Buku Ajar Kardiologi. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
2. Afandi, Maemunah. 1983. Penyakit Jantung Bawaan : Apa yang harus dilakukan. www.kalbe.co.id.
3. Kusumawidjaja. Patologi. Jakarta: FKUI 1996. pp: 110 – 16.
4. Masud, Ibnu. 1992. Dasar-Dsar Fisiologi Kardiovaskuler. Jakarta : EGC.
5. S. Silbernagl, F. Lang. 2007. Patofisiologi. Jakarta : EGC. pp: 176-249
6. Ikatan Dokter Anak Indonesia. 1994. Buku Ajar Kardiologi Anak. Jakarta : Binarupa Aksara. pp: 1- 404.
7. Joto, Santa. 2001. Diagnosis Penyakit Jantung. Jakarta : Penerbit Widya Medika.
8. Rilantono LI. 2003. “Defek Septum Ventrikel” in Rilantono LI (ed) et al. 2003. Buku Ajar Kardiologi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
9. Sastroasmoro, sudigdo. 1998. Dasar Diagnosis dan Tata Laksana Penyakit Jantung Bawaan. FKUI
10. Fyler, Donald. 1996. Kardiologi Anak Nadas. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
11. Chandrasoma dan Taylor. 2006. Ringkasan Patologi Anatomi. Ed: ke-2. Jakarta : EGC.
12. Purwaningtyas, Niniek. 2008. Klasifikasi Klinis Penyakit Jantung Anak Kongenital. Dalam : Cardiology After Mid. Surakarta : Filamen 05.
13. Kertohoesodo, Soeharto. 1987. Pengantar Kardiologi. Jakarta : Penerbit UI.
25