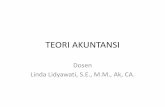teori dramaturgi erving goffman
-
Upload
maulinamutiaranate -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of teori dramaturgi erving goffman
teori dramaturgi erving goffmandiposting oleh sufyan-ahamad-fisip11 pada 21 October 2012di Tokoh Sosiologi - 1 komentar
Pernyataan paling terkenal Goffman tentang teori dramaturgis berupa buku Presentation of Self in Everyday Life, diterbitkan tahun 1959. Secara ringkas dramaturgis merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Istilah Dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi diatas panggung dimana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan.
Dalam Dramaturgi terdiri dari Front stage (panggung depan) dan Back Stage (panggung belakang). Front Stage yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Front stage dibagi menjadi 2 bagian, Setting yaitu pemandangan fisik yang harus ada jika sang actor memainkan perannya. Dan Front Personal yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasa perasaan dari sang actor. Front personal masih terbagi menjadi dua bagian, yaitu Penampilan yang terdiri dari berbagai jenis barang yang mengenalkan status social actor. Dan Gaya yang berarti mengenalkan peran macam apa yang dimainkan actor dalam situasi tertentu. Back stage (panggung belakang) yaitu ruang dimana disitulah berjalan scenario pertunjukan oleh “tim” (masyarakat rahasia yang mengatur pementasan masing-masing actor)
Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Beliau menggalisegala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kitasendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi. Pertunjukan yang terjadi di masyarakat
untuk memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dari presentasi dari Diri – Goffman ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Bila seorang aktor berhasil, maka penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut. Aktor akan semakin mudah untuk membawa penonton untuk mencapai tujuan dari pertunjukan tersebut. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari komunikasi. Karena komunikasi sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Bila dalam komunikasi konvensional manusia berbicara tentang bagaimana memaksimalkan indera verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan akhir komunikasi, agar orang lain mengikuti kemauan kita. Maka dalam dramaturgis, yang diperhitungkan adalah konsep menyeluruh bagaimana kita menghayati peran sehingga dapat memberikan feedback sesuai yang kita mau. Perlu diingat, dramatugis mempelajari konteks dari perilaku manusia dalam mencapai tujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilakunya tersebut. Dramaturgi memahami bahwa dalam interaksi antar manusiaada “kesepakatan” perilaku yang disetujui yang dapat mengantarkankepada tujuan akhir dari maksud interaksi sosial tersebut. Bermain peran merupakan salah satu alat yang dapat mengacu kepadatercapainya kesepakatan tersebut.
Dalam teori Dramatugis menjelaskan bahwa identitas manusia adalahtidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”. Dalam mencapaitujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut.Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, penggunakan kata (dialog) dan tindakan non verbal lain, hal ini tentunya bertujuanuntuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan diatas
disebut dalam istilah “impression management”. Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung (“front stage”) dan di belakang panggung (“back stage”) drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita. Perilaku kita dibatasi oleh oleh konsep-konsep drama yang bertujuan untuk membuat drama yang berhasil (lihat unsur-unsur tersebut pada impression management diatas). Sedangkan back stageadalah keadaan dimana kita berada di belakang panggung, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga kita dapat berperilakubebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan. Contohnya, seorang teller senantiasa berpakaian rapi menyambut nasabah dengan ramah, santun, bersikap formil dan perkataan yang diatur. Tetapi, saat istirahat siang, sang teller bisa bersikap lebih santai, bersenda gurau dengan bahasa gaul dengan temannya atau bersikap tidak formil lainnya (ngerumpi, dsb). Saat teller menyambut nasabah, merupakan saat front stage baginya (saat pertunjukan). Tanggung jawabnya adalah menyambut nasabah dan memberikan pelayanan kepada nasabah tersebut. Oleh karenanya, perilaku sang teller juga adalah perilaku yang sudah digariskan skenarionya oleh pihak manajemen. Saat istirahat makansiang, teller bebas untuk mempersiapkan dirinya menuju babak ke dua dari pertunjukan tersebut. Karenanya, skenario yang disiapkanoleh manajemen adalah bagaimana sang teller tersebut dapat refresh untuk menjalankan perannya di babak selanjutnya.
Sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang pasti akan mempersiapkan perannya dulu, atau kesan yang ingin ditangkap olehorang lain. Kondisi ini sama dengan apa yang dunia teater katakansebagai “breaking character”. Dengan konsep dramaturgis dan permainan peran yang dilakukan oleh manusia, terciptalah suasana-suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri. Terbentuklah kemudian masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana dan corak kehidupan. Masyarakat yang tinggal dalam komunitas heterogen perkotaan, menciptakan panggung-panggung sendiri yang
membuatnya bisa tampil sebagai komunitas yang bisa bertahan hidupdengan keheterogenannya. Begitu juga dengan masyarakat homogen pedesaan, menciptakan panggung-panggung sendiri melalui interaksinya, yang terkadang justru membentuk proteksi sendiri dengan komunitas lainnya. Apa yang dilakukan masyarakat melalui konsep permainan peran adalah realitas yang terjadi secara alamiah dan berkembang sesuai perubahan yang berlangsung dalam diri mereka. Permainan peran ini akan berubah-rubah sesuai kondisi dan waktu berlangsungnya. Banyak pula faktor yang berpengaruh dalam permainan peran ini, terutama aspek sosial psikologis yang melingkupinya.
Dramarturgi hanya dapat berlaku di institusi total,Institusi total maksudnya adalah institusi yang memiliki karakter dihambakan oleh sebagian kehidupan atau keseluruhan kehidupan dari individual yang terkait dengan institusi tersebut, dimana individu ini berlaku sebagai sub-ordinat yang mana sangat tergantung kepada organisasi dan orang yang berwenang atasnya. Ciri-ciri institusi total antara lain dikendalikan oleh kekuasan (hegemoni) dan memiliki hierarki yang jelas. Contohnya, sekolah asrama yang masih menganut paham pengajaran kuno (disiplin tinggi), kamp konsentrasi (barak militer), institusi pendidikan, penjara, pusat rehabilitasi (termasuk didalamnya rumah sakit jiwa, biara, institusi pemerintah, dan lainnya. Dramaturgi dianggap dapat berperan baik pada instansi-instansi yang menuntutpengabdian tinggi dan tidak menghendaki adanya “pemberontakan”. Karena di dalam institusi-institusi ini peran-peran sosial akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Orang akan lebih memahami skenario semacam apa yang ingin dimainkan. Bahkan beberapa ahli percaya bahwa teori ini harus dibuktikan dahulu sebelum diaplikasikan.
Teori ini juga dianggap tidak mendukung pemahaman bahwa dalam tujuan sosiologi ada satu kata yang seharusnya diperhitungkan, yakni kekuatan “kemasyarakatan”. Bahwa tuntutan peran individual menimbulkan clash bila berhadapan dengan peran kemasyarakatan. Ini yang sebaiknya dapat disinkronkan.
Dramaturgi dianggap terlalu condong kepada positifisme. Penganut
paham ini menyatakan adanya kesamaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, yakni aturan. Aturan adalah pakem yang mengatur dunia sehingga tindakan nyeleneh atau tidak dapat dijelaskan secara logis merupakan hal yang tidak patu
Teori Interaksi Simbolik
Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa
dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead (1863-1931).
Mead membuat pemikiran orisinal yaitu “The Theoretical
Perspective” yang merupakan cikal bakal “Teori Interaksi
Simbolik”. Dikarenakan Mead tinggal di Chicago selama lebih
kurang 37 tahun, maka perspektifnya seringkali disebut sebagai
Mahzab Chicago.
Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat
non verbal dan pesan verbal yang dimaknai berdasarkan
kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu
interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti
yang sangat penting.
Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang
diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku orang
tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita
dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya
dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain.
Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead, definisi singkat dari
tiga ide dasar dari interaksi simbolik adalah :
a. Mind (pikiran) - kemampuan untuk menggunakan simbol yang
mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus
mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu
lain.
b. Self (diri pribadi) - kemampuan untuk merefleksikan diri tiap
individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain,
dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam
teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self)
dan dunia luarnya.
c. Society (masyarakat) - hubungan sosial yang diciptakan, dibangun,
dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan
tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih
secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan
manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.
Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari
interaksi simbolik antara lain:
1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
Tema ini berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi
perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik
tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya
makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di
konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses
interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati
secara bersama dimana asumsi-asumsi itu adalah sebagai
berikut : Manusia, bertindak, terhadap, manusia, lainnya
berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka,
Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, Makna
dimodifikasi melalui proses interpretif .
2. Pentingnya konsep mengenai diri (self concept)
Tema ini berfokus pada pengembangan konsep diri
melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada
interaksi sosial dengan orang lainnya dengan cara antara
lain : Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui
nteraksi dengan orang lain, Konsep diri membentuk motif yang
penting untuk perilaku Mead seringkali menyatakan hal ini
sebagai : ”The particular kind of role thinking – imagining
how we look to another person” or ”ability to see ourselves
in the reflection of another glass”.
3. Hubungan antara individu dengan masyarakat.
Tema ini berfokus pada dengan hubungan antara
kebebasan individu dan masyarakat, dimana norma-norma sosial
membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya tiap
individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial
kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini adalah untuk
menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses
sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini
adalah : Orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh
proses budaya dan sosial, Struktur sosial dihasilkan melalui
interaksi sosial
Generasi setelah Mead merupakan awal perkembangan
interaksi simbolik, dimana pada saat itu dasar pemikiran Mead
terpecah menjadi dua Mahzab, dimana kedua mahzab tersebut
berbeda dalam hal metodologi, yaitu :
1. Mahzab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer : Blummer
memberikan pengembangan dalam pikiran-pikiran mead menjadi tujuh
buah asumsi yang mempelopori pergerakan mazhab Chicago baru.
Tujuh asumsi tersebut adalah :
Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang
diberikan orang lain pada mereka, Makna diciptakan dalam
interaksi antar manusia, Makna dimodifikasi melalui sebuah proses
interpretif, Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui
interaksi dengan orang lain, Konsep diri memberikan sebuah motif
penting untuk berperilaku, Orang dan kelompok-kelompok
dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, Struktur sosial
dihasilkan melalui interaksi sosial.
2.Mahzab Iowa yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young
Mahzab Iowa dipelopori oleh Manford kuhn dan
mahasiswanya, dengan melakukan pendekatan kuantitatif,
dimana kalangan ini banyak menganut tradisi epistemologi dan
metodologi post- positivis yang mengambil dua langkah cara
pandang baru yang tidak terdapat pada teori sebelumnya,
yaitu memperjelas konsep diri menjadi bentuk yang lebih
kongkrit.
Tokoh teori interaksi simbolik antara lain : George
Herbert Mend, Herbert Blumer, Wiliam James, Charles Horton Cooley. Teori
interaksi simbolik menyatakan bahwa interaksi sosial adalah
interaksi symbol. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan
cara menyampaikan simbol yang lain memberi makna atas simbol
tersebut. Asumsi-asumsi: a. Masyarakat terdiri dari manusia
yang berinteraksi melalui tindakan bersama dan membentuk
organisasi. b. Interaksi simbolik mencangkup pernafsiran
tindakan. Interaksi non simbolik hanyalah mencangkup stimulus
respon yang sederhana.
Pelapisan Sosial /Stratifikasi Sosial
Pelapisan sosial adalah perbedaan tinggi rendah kedudukan
seseorang/sekelompok orang dibandingkan dengan sseseorang atau
sekelompok orang lain dalam masyarakat. Pelapisan sosial dapat terjadi
karena pengaruh berbagai kriteria, antara lain ekonomi, politik,
sosial.
1. Sistem Pelapisan Sosial
Menurut status kependudukan asli atau pendatang misalnya di
daerah Jawa dengan adanya cikal bakal yaitu orang yang merintis
tinggal didaerah tersebut dan mempunyi keturunan di daerah tersebut,
womg baku yaitu orang yang mempunyai saudara, tanah, dan lahir di
daerah tersebut, pendatang yaitu orang yang membeli tanah dan
membangun didaerah tersebut. Sedangkan di Sumatra Utara ada yang
disebut dengan Sipunta huta/bangsa taneh yaitu keturunan nenek
moyang dan penduduk pendatang.
2. Diferensiasi Sosial
Diferensiasi sosial ialah perbedaan sosial dalam masyarakat
secara horisontal. Bentuk diferensiasi sosial yaitu diferensiasi
jenis kelamin, diferensiasi agama, diferensiasi profesi dsb.
Interaksi Simbolik : Teori ini menyatakan bahwa Interaksi sosial pada
hakekatnya adalah Interaksi simbolik. Manusia berinteraksi dengan yang
lain dengan cara menyampaikan simbol, yang lain memberi makna atas
simbol tersebut.
Stratifikasi Sosial/Pelapisan Sosial : Adalah pembedaan tinggi rendah
kedudukan sekelompok orang atau seseorang di bandingkan dengan
seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Pelapisan Sosial
dapat terjadi karena pengaruh berbagai kriteria, antara lain:
1. Ekonomi (kekayaan)
2. Politik (Kekuasaan)
3. Sosial (Martabat)
Pengertian Berfikir : Adalah proses memahami natalitas dalam rangka
mengambil kesimpulan dan menghasilkan masalah baru. Cara orang
berfikir yaitu dengan menggunakan Austik (melamun, fantasi, berkaca dll)
dan dengan realiustik (nalar, sesuai dengan dunia nyata).
Persepsi : Adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga
memperoleh engetahuan sesuai dengan yang di inginkan atau dengan kata
lain adalah proses memberi makna pada stimuli inderawi.
Adapun faktor personal yang mempengaruhi persepsi adalah :
1. Perhatian (Attention)
2. Faktor biologis
3. Faktor Psikologis
Pengertian Memori : Adalah sistem ingatan yang sanggup merekam fakta
dan dapat di gunakan untuk membimbing perilaku manusia.
Proses memori :
Perekaman (Encoding) adalah pencatatan informasi melalui reseptor
indera
Penyimpanan (Storage) menentukan berapa lama informasi tersebut
bersama kita
Pemanggilan (Retrieval) mengingat kembali informasi yang telah
tersimpan.
Mekanisme Memori :
Mekanisme memori hendak menjelaskan cara kerja memori, mengapa kita
ingatsesuatu dan melupakan yang lainnya.
Prespektif interaksi simbolik, perilaku manusia harus di
pahami dari sudut pandang subyek. Dimana teoritis interaksi
simbolik ini memandang bahwa kehidupan sosial pada dasarnya
adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol,
(D.Mulyana, 2001: 70). Inti pada penelitian ini adalah mengungkap
bagaimana cara manusia menggunakan simbol-simbol yang
merepresentasikan apa yang akan mereka sampaikan dalam proses
komunikasi dengan sesama.
Penggunaan simbol yang dapat menunjukkan sebuah makna
tertentu, bukanlah sebuah proses yang interpretasi yang diadakan
melalui sebuah persetujuan resmi, melainkan hasil dari proses
interaksi sosial.
Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada
objek, melainkan dinegosiasikan dalam penggunaan bahasa. Negosiasi itu
dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek
fisik, tindakan atau peristiwa ( bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau
peristiwa itu).(Arnold M Rose 1974:143 dalam D.Mulyana 2001:72).
Terbentuknya makna dari sebuah simbol tak lepas karena
peranan individu yang melakukan respon terhadap simbol tersebut.
Individu dalam kehidupan sosial selalu merespon lingkungan
termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia)
yang kemudian memunculkan sebuah pemaknaan . Respon yang mereka
hasilkan bukan berasal dari faktor eksternal ataupun didapat dari
proses mekanis, namun lebih bergantung dari bagaimana individu
tersebut mendefinisikan apa yang mereka alami atau lihat. Jadi
peranan individu sendirilah yang dapat memberikan pemaknaan dan
melakukan respon dalam kehidupan sosialnya.
Namun, makna yang merupakan hasil interpretasi individu
dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan dari
faktor-faktor yang berkaitan dengan bentuk fisik (benda) ataupun
tujuan (perilaku manusia) memungkinkan adanya perubahan terhadap
hasil intrepetasi barunya. Dan hal tersebut didukung pula dengan
faktor bahwa individu mampu melakukan proses mental, yakni
berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Proses mental tersebut
dapat berwujud proses membayangkan atau merencanakan apa yang
akan mereka lakukan. Individu dapat melakukan antisipasi terhadap
reaksi orang lain, mencari dan memikirkan alternatif kata yang
akan ia ucapkan.
Menurut pandangan Mead, perilaku manusia sebagai sosial
dan berbeda dengan perilaku hewan yang pada umumnya ditandai
dengan stimulus dan respon. Perilaku merupakan produk dari
penafsiran individu atas objek di sekitarnya.makna yang mereka
berikan kepada objek berasal dari interaksi sosial dan dapat
berubah selama interaksi itu berlangsung.
Hal tersebut di atas senada dengan apa yang bisa kita
lihat dari penampilan fisik atau budaya material kaum Punk.
Dimana pola pemaknaan yang terjadi dalam masyarakat terhadap kaum
Punk adalah berkonotasi negatif. Penampilan dengan gaya pakaian
yang terkesan kumal, penuh dengan aksesoris sangar seperti Peniti
yang dijadikan hiasan di wajah yang pada akhirnya membentuk
respon masyarakat kepadanya.
Konsep tentang “self ” atau diri merupakan inti dari teori
interaksi simbolik. Mead menganggap konsep diri adalah suatu
proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang
lain ( D. Mulyana, 2001:73 ).
Dalam Mind, Self and Society (1934) Mead pun menanyakan “bagaimana
seorang individu bisa keluar dari dirinya sendiri untuk menjadi objek lagi bagi dirinya
sendiri?”, lanjut Mead, “…melalui proses tingkah laku atau aktivitas sosial dimana
individu yang ada di simpulkan ……….individu mengalami dirinya sendiri semacam
itutidak secara langsung, dari perlakuan individu lain dari kelompok sosial yang sama
…..dia menjadi objek untuk dirinya sendiri seperti orang lain menjadi objek bagi
dirinya.”( R. Soeprapto, 2002:205).
Diri sendiri “ the self ”, dalam pandangan ahli
interaksionalisme simbolik merupakan obyek sosial dalam hubungan
dengan orang lain disebuah proses interaksi. Dengan demikian,
individu melihat dirinya sendiri ketika ia berinteraksi dengan
orang lain.
Bagi Mead, kesadaran akan “diri” berarti menjadi suatu
“diri” dalam pengalaman seseorang sejauh “suatu sikap yang
dimilikinya sendiri membangkitkan sikap serupa dalam upaya social
. kesadaran akan konsep “diri” akan muncul ketika individu
memasuki pengalaman dirinya sendiri sebagai suatu obyek.
Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang
baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19
yang lalu. Sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus
berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung SI
merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional
(Ardianto. 2007: 40).
Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, dimana
merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi,
yang barangkali paling bersifat ”humanis” (Ardianto. 2007: 40).
Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keangungan dan maha
karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai yang ada selama
ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya
memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial
masyarakatnya, dan menghasilkan makna ”buah pikiran” yang
disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan
bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap
individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah
salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran
interaksionisme simbolik.
Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara
simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini
adalah individu (Soeprapto. 2007). Banyak ahli di belakang
perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang
paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka mengatakan bahwa
individu adalah objek yang bisa secara langsung ditelaah dan
dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.
Menurut Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes (1993)dalam
West- Turner (2008: 96), interaksi simbolik pada intinya
menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana
manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik
dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia.
Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk
makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri
(Self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuan
bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di
tengah masyarakat (Society) dimana individu tersebut menetap.
Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970)dalam Ardianto (2007:
136), Makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain
untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan
individu lain melalui interaksi.
Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi
simbolik, antara lain: (1) Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk
menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana
tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui
interaksi dengan individu lain, (2) Diri (Self) adalah kemampuan
untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut
pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme
simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang
mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya,
dan (3) Masyarakat (Society) adalah jejaring hubungan sosial yang
diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu
ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam
perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada
akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di
tengah masyarakatnya.
”Mind, Self and Society” merupakan karya George Harbert
Mead yang paling terkenal (Mead. 1934dalam West-Turner. 2008:
96), dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep
dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori
interaksi simbolik.
Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang
mendasari interaksi simbolik antara lain:
a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
b. Pentingnya konsep mengenai diri,
c. Hubungan antara individu dengan masyarakat
Tema pertama pada interaksi simbok berfokus pada pentingnya
membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori
interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi,
karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya
di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses
interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara
bersama. Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya
Herbert Blumer (1969)dalam West-Turner (2008: 99) dimana asumsi-
asumsi itu adalah sebagai berikut: Manusia bertindak terhadap
manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain
kepada mereka, Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia,
Makna dimodifikasi melalui proses interpretif.
Tema kedua pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya
”Konsep diri” atau ”Self-Concept”. Dimana, pada tema interaksi
simbolik ini menekankan pada pengembangan konsep diri melalui
individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi sosial
dengan orang lainnya. Tema ini memiliki dua asumsi tambahan,
menurut LaRossan & Reitzes (1993) dalam West-Turner (2008: 101),
antara lain: Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui
interaksi dengan orang lain, Konsep diri membentuk motif yang
penting untuk perilaku.
Tema terakhir pada interaksi simbolik berkaitan dengan
hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, dimana asumsi
ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku tiap
individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan
pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema
ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan
dalam proses sosial. Asumsi- asumsi yang berkaitan dengan tema
ini adalah:
1. Orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan
sosial,
2. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.
Rangkuman dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya
mengenai tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang
berkaitan dengan interaksi simbolik, dan tujuh asumsi-asumsi
karya Herbert Blumer (1969) adalah sebagai berikut:
Tiga tema konsep pemikiran Mead
• Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
• Pentingnya konsep diri,
• Hubungan antara individu dengan masyarakat.
Tujuh asumsi karya Herbert Blumer
a. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang
diberikan orang lain pada mereka,
b. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia
c. Makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretif,
d. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi
dengan orang lain,
e. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku,
f. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan
sosial,
g. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.
D. IMPLIKASI DALAM ILMU/TEORI DAN METODOLOGI
Implikasi dari teori interaksi simbolik dapat dijelaskan dari beberapa
teori atau ilmu dan metodologi berikut ini, antara lain: Teori
sosiologikal modern (Modern Sociological Theory) menurut Francis
Abraham (1982)dalam Soeprapto (2007), dimana teori ini menjabarkan
interaksi simbolik sebagai perspektif yang bersifat sosial-
psikologis. Teori sosiologikal modern menekankan pada struktur sosial,
bentuk konkret dari perilaku individu, bersifat dugaan, pembentukan
sifat- sifat batin, dan menekankan pada interaksi simbolik yang
memfokuskan diri pada hakekat interaksi. Teori sosiologikal modern
juga mengamati pola-pola yang dinamis dari suatu tindakan yang
dilakukan oleh hubungan sosial, dan menjadikan interaksi itu sebagai
unit utama analisis, serta meletakkan sikap-sikap dari individu yang
diamati sebagai latar belakang analisis.
Perspektif interaksional (Interactionist perspective)
merupakan salah satu implikasi lain dari interaksi simbolik,
dimana dalam mempelajari interaksi sosial yang ada perlu
digunakan pendekatan tertentu, yang lebih kita kenal sebagai
perspektif interaksional (Hendariningrum. 2009). Perspektif ini
menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari
interaksi sosial masyarakat, dan mengacu dari penggunaan simbol-
simbol yang pada akhirnya akan dimaknai secara kesepakan bersama
oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka.
Konsep definisi situasi (the definition of the situation)
merupakan implikasi dari konsep interaksi simbolik mengenai
interaksi sosial yang dikemukakan oleh William Isac Thomas
(1968)dala m Hendariningrum (2009). Konsep definisi situasi
merupakan perbaikan dari pandangan yang mengatakan bahwa
interaksi manusia merupakan pemberian tanggapan (response)
terhadap rangsangan (stimulus) secara langsung. Konsep definisi
situasi mengganggap bahwa setiap individu dalam memberikan suatu
reaksi terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku dari individu
tersebut didahului dari suatu tahap pertimbangan-pertimbangan
tertentu, dimana rangsangan dari luar tidak ”langsung ditelan
mentah-mentah”, tetapi perlu dilakukan proses selektif atau
proses penafsiran situasi yang pada akhirnya individu tersebut
akan memberi makna terhadap rangsangan yang diterimanya.
Konstruksi sosial (Social construction) merupakan implikasi
berikutnya dari interaksi simbolik yang merupakan buah karya
Alfred Schutz, Peter Berger, dan Thomas Luckmann, dimana
konstruksi sosial melihat individu yang melakukan proses
komunikasi untuk menafsirkan peristiwa dan membagi penafsiran-
penafsiran tersebut dengan orang lain, dan realitas dibangun
secara sosial melalui komunikasi (LittleJohn. 2005: 308).
Teori peran (Role Theory) merupakan implikasi selanjutnya
dari interaksi simbolik menurut pandangan Mead (West-Turner 2008:
105). dimana, salah satu aktivitas paling penting yang dilakukan
manusia setelah proses pemikiran (thought) adalah pengambilan
peran (role taking). Teori peran menekankan pada kemampuan
individu secara simbolik dalam menempatkan diri diantara individu
lainnya ditengah interaksi sosial masyarakat.
Teori diri (Self theory) dalam sudut pandang konsep diri,
merupakan bentuk kepedulian dari Ron Harrě, dimana diri
dikonstruksikan oleh sebuah teori pribadi (diri). Artinya,
individu dalam belajar untuk memahami diri dengan menggunakan
sebuah teori yang mendefinisikannya, sehingga pemikiran seseorang
tentang diri sebagaiperson merupakan sebuah konsep yang
diturunkan dari gagasan-gagasan tentangpersonhood yang
diungkapkan melalui proses komunikasi (LittleJohn. 2005: 311).
Teori dramatisme (Dramatism theory) merupakan implikasi
yang terakhir yang akan dipaparkan oleh penulis, dimana teori
dramatisme ini merupakan teori komunikasi yang dipengaruhi oleh
interaksi simbolik, dan tokoh yang menggemukakan teori ini adalah
Kenneth Burke (1968). Teor ini memfokuskan pada diri dalam suatu
peristiwa yang ada dengan menggunakan simbol komunikasi.
Dramatisme memandang manusia sebagai tokoh yang sedang memainkan
peran mereka, dan proses komunikasi atau penggunaan pesan
dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita
tertentu (Ardianto. 2007: 148).
FENOMENOLOGI
Adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupannya didunia. Studi ini melihat objek dan peristiwa dari perspektif orang yang mengalami. Relaitas dalam fenomenologi selalu merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang.Pendekatan ini merupakan suatu langkah maju terhadap aliran yang menganggap bahwa suatu realitas terlepas dari kesadaran atau persepsi manusia.
Maurice Merleu-Ponty, seorang fenomenologis terkenal, mengungkapkan pandangannya;Seluruh pengetahuan saya tentang dunia, bahkan pengetahuan ilmiahsaya, diperoleh dari sudut pandang saya sendiri, atau dari beberapa pengalaman yang tampa menggunakan sudut pandang saya sendiri akan menyebabkan simbol-simbol ilmiah menjadi tidak berarti. Untuk kembali kepada hal-hal tersebut adalah kembali kepada dunia yang mendahului pengetahuan, dimana pengetahuan selalu bicara.
Fenomenologi menempatkan pengalaman nyata sebagai data dasar daripengetahuan. Fenomenologi juga menghindari penerapan ketentuan kategori teoritis,”fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatumengungkapkan dirinya sendiri, tanpa memaksakan kategori kita kepada mereka”.
Tiga prinsip dasar fenomenologi dikemukakan oleh Stanley Deetz;1. Pengetahuan haruslah sadarPengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman, tetapi diekspresikan dalam pengalaman sadar itu sendiri.2. Makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang
Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu ojek akan menentukanmakna tersebut.3. Bahasa merupakan perantara bagi munculnya maknaKita mengalami banyak hal melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengunkapkan hal-hal tersebut.
Fenomenologi terbagi menjadi dua kubu;Edmund Husserl, mengajarkan bahwa fenomenologi dapat menjadi suatu disiplin ilmu, dengan menggunakan kesadaran jernih, orang dapat mengungkap kebenaran.Martin Heidegger, mengajarkan bahwa pengetahuan yang pasti adalahtidak mungkin dan bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri mereka dari pengalaman subjektif