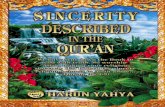SUHUF: Jurnal Kajian Al-Qur'an No. 01 Vol. 07 2014 PDF Full
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of SUHUF: Jurnal Kajian Al-Qur'an No. 01 Vol. 07 2014 PDF Full
iii
ISSN 1979-6544 e-ISSN 2356-1610
J u r n a l K a j i a n A l – Q u r ’ a n Vol. 7, No.1, 2014
Daftar Isi
Zaenal Arifin Madzkur Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia
dalam Perspektif Ilmu ¬ab¯ 1—22
Abdul Hakim
Pola Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan sebelum Tahun 1959
23—38
Lenni Lestari Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an:
Telaah Metodologi atas Buku Judaism and Islam 39—58
Muhammad Yusuf
Studi Kasus tentang ‘Iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulawesi Selatan
59—80
Ahmad Jaeni Tinjauan Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama
di Jawa Timur 81—100
iv
Ali Akbar
Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat: Kajian Beberapa Aspek Kodikologi
101—123
Agus Iswanto Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformasi atas Kritik
Al-Qur’an terhadap Agama Lain 125—139
Pustaka
141—149
ملخص149-2—149-6
Pedoman Pengiriman Tulisan
149-8—149-11
v Pengantar Redaksi v
Pengantar Redaksi Jurnal SUHUF Volume 7, No. 1 Tahun 2014 menampilkan sejum-lah artikel, hasil penelitian, tinjauan buku, dan pustaka. Semua tulisan yang dimuat adalah tentang kajian Al-Qur’an. Tulisan pertama berjudul “Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu ¬ab¯” ditulis oleh Zainal Arifin Madzkur. Tulisan ini menguraikan ulang pembahasan bentuk harakat dan tanda baca dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang telah menjadi standar baku peredaran dan penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia sejak tahun 1984. Kajian ini penting, selain sebagai pengantar naskah akademik studi «abt dalam Mushaf Al-Qur'an Standar juga sebagai upaya mendudukkan kembali sejarah perkembangan harakat dan tanda baca dalam diskursus penulisan Al-Qur'an (rasm mushaf) yang jarang diulas dalam diskusi penulis-an Al-Qur'an di Indonesia. Kedangkalan memahami ilmu «ab¯ acapkali juga menjadi pemicu perselisihan sebagaimana pem-bahasan tentang rasm Usmani dalam penulisan Al-Qur'an.
Artikel kedua ditulis oleh Abdul Hakim dengan judul “Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan sebelum Tahun 1959”. Tulisan hasil kajian ini menje-laskan tentang pola-pola tashih Al-Qur’an di Indonesia dengan mengambil contoh dari Al-Qur’an tulis tangan dan beberapa Al-Qur’an cetakan yang terbit sebelum 1959. Tahun tersebut merupa-kan tahun berdirinya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an yang berfungsi sebagai lembaga tashih tunggal atas semua Al-Qur’an yang beredar di Indonesia. Ada dua pola tashih mushaf tulis tangan, yaitu tashih saat penyalinan dan tashih pasca penyalinan. Adapun Al-Qur’an cetakan memiliki dua pola yaitu tashih kepada lembaga keagamaan lokal dan tashih kepada pentashih yang terdiri dari para ulama Al-Qur’an.
Artikel Lenni Lestari tentang kajian orientalisme berjudul “Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an, Telaah Metodologi atas Buku Judaism and Islam”. Artikel ini menjelaskan bahwa salah satu hasil penelitian orientalis yang cukup “menggelitik” keimanan para sarjana Muslim saat ini adalah Al-Qur’an yang dianggap seba-gai imitasi ajaran agama Yahudi. Ungkapan ini muncul dari salah seorang orientalis beragama Yahudi yaitu Abraham Geiger. Tulisan
vi vi ¢u¥uf, Vol. 6, No. 1, 2013
ini membahas tentang; Pertama, latar belakang pemikiran Abraham Geiger; Kedua, Pemikiran Geiger tentang hal-hal yang diadopsi Nabi Muhammad dari agama Yahudi, dan ketiga, tanggapan me-ngenai penelitian Geiger terhadap Al-Qur’an.
Tulisan berjudul “Studi Kasus tentang Idah dalam Tafsir Berba-hasa Bugis Karya MUI Sulawesi Selatan” oleh Muhammad Yusuf menjadi tulisan keempat pada SUHUF edisi sekarang. Tulisan ini mengulas pandangan ulama Bugis mengenai idah dalam Tafsere Akorang Mabbasa Ogi karya MUI Sulsel. Persoalan idah seringkali mendapat sorotan dari pemerhati jender. Rumusan idah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kini menghadapi gugatan atas nama kesamaan jender sehingga idah yang hanya berlaku untuk perem-puan kini digugat agar diberlakukan juga untuk laki-laki. Idah harus dilihat pada amanat teks, konteks historis, dan konteks budaya. Teks telah mengatur idah dengan jelas; idah pada masa Rasulullah hanya berlaku bagi wanita. Idah dan i¥d±d bertujuan memelihara nasab, di samping sebagai momentum instrospeksi diri dan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Nilai-nilai kearifan budaya Bugis la-yak menjadi pertimbangan mengenai penetapan masa idah.
Artikel kelima berjudul “Tinjauan Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama di Jawa Timur” merupakan hasil penelitian Ahmad Jaeni. Penelitian ini meninjau sistem distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama yang dinilai masih belum merata dan tepat sasaran, khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi mushaf Al-Qur’an yang selama ini dijalankan Kementerian Agama menganut sistem distribusi ganda (multi channel distribution system), yaitu sistem yang memungkin-kan setiap kanal distribusi memainkan dua fungsi sekaligus, sebagai perantara dan penyalur. Meskipun cukup efektif mempercepat target proses distribusi, namun sistem ini membuka kemungkinan terjadinya sasaran distribusi yang tumpang tindih. Akibatnya, distri-busi menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran. Membuat seg-mentasi sasaran distribusi pada setiap kanal distribusi menjadi sebuah tawaran solusi.
Artikel keenam merupakan hasil penelitian Ali Akbar berjudul “Manuskrip Al-Qur'an dari Sulawesi Barat, Kajian Beberapa Aspek Kodikologi”. Artikel ini mengkaji delapan mushaf Al-Qur’an kuno dari Sulawesi Barat, semuanya dari koleksi perorangan. Bagian pertama tulisan ini mendeskripsi masing-masing mushaf, dan selan-
vii Pengantar Redaksi vii
jutnya membahas sisi teks Al-Qur’an serta teks-teks tambahan lainnya, baik di bagian awal maupun akhir mushaf. Mushaf Al-Qur’an yang dikaji berasal dan merupakan tradisi mushaf Bugis, meskipun saat ini milik orang di Mandar, Sulawesi Barat. Rasm usmani dalam mushaf banyak digunakan di wilayah Sulawesi Sela-tan, termasuk Wajo dan Bone, pada abad ke-19. Hal itu juga dileng-kapi dengan bacaan qirā’āt sab‘ yang disertakan di bagian tepi mushaf. Dari delapan mushaf yang dikaji dalam tulisan ini hanya satu mushaf yang tidak memiliki catatan qira’at.
Tulisan ketujuh merupakan tinjauan atas buku ”Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an terhadap Agama Lain” karya Mun’im Sirry. Artikel ketujuh ini ditulis oleh Agus Iswanto, peneliti Balai Penelitian Agama Jakarta.
Rubrik yang secara tetap ditampilkan pada jurnal ini adalah pustaka. Rubrik ini berisi ulasan singkat buku-buku terbaru dalam bidang kajian Al-Qur’an dan bisa dijadikan rujukan dalam kajian di bidang ini. Pada edisi ini diulas secara singkat buku-buku terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
Kami informasikan bahwa Jurnal SUHUF telah mendapatkan akreditasi untuk tiga tahun dan telah memulai pula publikasi dalam bentuk e-Jurnal (lihat: lajnah.kemenag.go.id/esuhuf). Untuk itu, ka-mi sampaikan terima kasih kepada segenap unsur yang sudah ber-peran bagi tumbuh-kembangnya jurnal ini.
Selamat membaca!
Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu ◙ab•
Vowel and Punctuation Mark of the Qur’an of Indonesian Standard in the Perspective of ◙ab• Science Zaenal Arifin Madzkur Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur’an TMII, Jakarta Timur, 13560 [email protected] Naskah diterima: 13-3-2014; direvisi: 06-05-2014; disetujui: 29-05-2014. Abstrak Tulisan ini ingin menelisik ulang pembahasan bentuk harakat dan tanda baca dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang telah menjadi standar baku peredaran dan penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia sejak tahun 1984. Kajian ini penting, selain sebagai pengantar naskah akademik studi «ab¯ dalam Mushaf Al-Qur'an Standar juga sebagai upaya mendudukkan kembali sejarah perkembangan harakat dan tanda baca dalam penulisan Al-Qur'an (rasm al-mushaf) yang jarang diulas dalam diskusi penulisan Al-Qur'an di Indonesia. Ke-dangkalan memahami ilmu «ab¯ acapkali juga menjadi pemicu perselisihan sebagaimana pembahasan tentang rasm Usmani dalam penulisan Al-Qur'an.
Kata kunci: Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, harakat, dan tanda baca. Abstract This paper would like to re-analyze the discussion of the form of vowel and punctuation in the Qur’an of Indonesian Standard that has become the fixed standard for the distribution and publication of the Qur'an in Indonesia since 1984. This study is important, besides as an introduction to the academic text of the study of «ab¯ in the Standard Quran, also as an effort to reinstate the historical development of vowel and punctuation mark in the writing of the Qur’anic discourse (rasm al-mushaf) which are rarely addressed in discussions of the writing of the Qur'an in Indonesia. The shallowness to understand science of «ab¯ often becomes a trigger of the disputes as it is also happened in the discussion of the “Rasm Uthmani” in the writing of the Qur'an.
Keywords: Qur’an of Indonesian Standards, vowel and punctuation marks.
2 2 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
Pendahuluan Sejak tahun 1984 Indonesia secara resmi telah memiliki
Mushaf Al-Quran Standar sebagai acuan bagi pentashihan dan penerbitan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia. Mushaf Al-Qur’an ini terdiri dari tiga jenis berdasarkan segmen penggunanya: (1) Mushaf Standar Usmani untuk orang awas (bisa melihat), (2) Mushaf Standar Bahriyah untuk para penghafal Al-Qur’an, dan (3) Mushaf Standar Braille untuk para tunanetra. Praktis sejak saat itu sampai sekarang, semua jenis cetakan dan penulisan Al-Qur’an yang ber-edar di Indonesia secara legal harus mengacu pada salah satu dari tiga jenis Mushaf Al-Qur’an Standar tersebut.
Sejarah panjang penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indone-sia (selanjutnya disingkat MAQSI)1, merujuk pada dokumen resmi Kementerian Agama,2 adalah dipicu oleh dua hal penting yang terjadi pada tahun 1972: (1) Apa pegangan Lajnah Pentashih Al-Qur’an yang dapat dipergunakan untuk menetapkan penulisan yang dianggap benar?; (2) harakat, tanda baca, dan tanda waqaf manakah yang akan ditetapkan dan dapat diikuti oleh para penerbit Al-Qur’an untuk masa yang lama? Hal ini dianggap cukup krusial, mengingat sebelum ada MAQSI, Lajnah dalam tugasnya mentashih mempergunakan cara musyawarah tradisional dengan membuka kitab, sebab belum memiliki pedoman tertulis. Begitupun penerbit dengan bebasnya melakukan inovasi bentuk rasm, harakat, tanda baca dan tanda waqaf. Sehingga, yang muncul di masyarakat umum bukan lagi keragaman, melainkan kesimpangsiuran dan bercampur-nya berbagai macam jenis rasm, harakat, tanda baca, dan tanda waqaf dalam setiap terbitan Al-Qur’an.
Beberapa peneliti dan praktisi mushaf Al-Qur’an sering meng-kritik diksi kata “standar” dalam MAQSI yang mulai beredar pada 1984. Bagi sebagian orang, pilihan kata ini menegaskan bahwa
1Mushaf Standar Indonesia secara terminologi didefinisikan sebagai
‘Mushaf Al-Qur’an yang dibakukan cara penulisan, harakat, tanda baca, tanda waqaf-nya, sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur’an yang berlangsung 9 tahun, dari tahun 1974 s.d 1983 dan dijadikan pedoman bagi Al-Qur’an yang diterbitkan di Indonesia.’ Muhamad Shohib et al (editor), Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Keme-nag, 2013, hlm.11-12.
2Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Mengenal Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: Depertemen Agama, 1984-1985, hlm. 8.
3 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 3
mushaf Indonesia bukanlah mushaf Al-Qur’an yang berstandar internasional. Oleh karena itu, penting dikemukakan kata ‘Standar Indonesia’ bukan menegaskan bahwa yang lain bukanlah standar atau berarti mushaf-mushaf Al-Qur’an terbitan luar negeri bukanlah standar.3 Akan tetapi, merupakan kalimat definitif untuk menunjuk-kan pilihan baku umat Islam Indonesia terkait rasm, harakat, tanda baca dan tanda waqafnya dalam konteks penyeragaman produk cetak dan elektronik Al-Qur’an yang dicetak dan beredar di Indo-nesia. Hal ini penting, mengingat, ketika penerbit-penerbit Al-Qur’an tidak diberikan ketentuan yang mengikat tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan mencetak Al-Qur’an, khususnya dalam komponen-komponen pokok mushaf Al-Qur’an seperti rasm (tulis-an), harakat, tanda baca dan tanda waqaf, maka yang muncul adalah bercampuraduknya pola penulisan, harakat, tanda baca dan tanda waqaf yang sering membingungkan masyarakat.4
Dari sebab dan kronologi di atas, Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an yang pada waktu itu (1974) berada di bawah Lembaga Lektur yang dipimpin HB. Hamdani Aly, MA., M.Ed pada masa Menteri Agama H.A. Mukti Ali, me-mulai pelaksanaan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an—selanjut-nya di sebut Muker—yang baru dapat direalisasikan pada tahun 1974 di Ciawi Bogor Jawa Barat. Hasilnya, empat bagian penting cetakan mushaf Al-Qur’an, berupa aspek rasm (pola penulisan), harakat, tanda baca dan tanda-tanda waqaf berhasil distandarkan pada Muker IX/1983.5
Dalam artikel ini keempat aspek di atas tidak akan diuraikan secara mendetail, akan tetapi kajian ini hanya lebih memfokuskan dan membatasi pada aspek harakat dan tanda baca yang diber-
3Barangkali pengertian standar yang dapat dianggap sebagai standar inter-
nasional adalah rasm usmani, yang menjadi dasar pijakan Mushaf Al-Qur’an sejak masa kekhalifahan ‘U£mān bin ‘Affān, selebihnya hampir tidak ditemukan mushaf yang mendominasi secara internasional.
4Selengkapnya dapat dibaca dalam Muhammad Shohib et al (editor), Seja-rah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013.
5Muhamad Shohib et al (editor), Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Stan-dar Indonesia, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2013, hlm. 90.
4 4 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
lakukan dalam MAQSI berdasarkan kajian ilmu «ab¯.6 Kajian ini hemat penulis penting, mengingat pembahasan tentang harakat dan tanda baca dalam MAQSI diduga banyak tidak memiliki rujukan ilmiah dan dasar argumentasi yang memadai, serta tidak pernah dikaji dan dideskripsikan secara proporsional. ‘Ulumul-Qur’an tentang Harakat dan Tanda Baca
Kajian tentang harakat dan tanda baca, dalam ulumul-Qur’an (studi ilmu-ilmu Al-Qur’an) lazimnya masuk dalam pembahasan tentang ilmu «abt/asy-syakl. Kajian ilmu «ab¯ menurut Muhammad Salim Muhaisin mencakup lima aspek pembahasan: (1) harakat; (2) bentuk sukun; (3) syiddah; (4) tanda mad; dan (5) hamzah.7
Dari kelima aspek tersebut terdapat dua hal yang secara epistimologi keilmuan sering rancu dan berpotensi untuk disalah-pahami. Pertama, terkait syakl sukun yang kerap dimasukkan pada jenis harakat.8 Padahal, sejatinya ia merupakan salah satu jenis «abt/syakl bukan harakat. Kedua, adalah penulisan hamzah.9 Se-mentara secara keilmuan, hamzah masuk dalam dua klaster, yaitu dalam pembahasan rasm dan «ab¯.
Dalam sejarah penulisan Al-Qur’an pada masa-masa awal, model penulisan harakat dan tanda baca (a«-«ab¯/asy-syakl) masih berbentuk titik bulat (an-naq¯) dengan warna-warna tertentu, seperti
6Kajian dari aspek rasm usmani dapat dibaca dalam Zaenal Arifin, “Menge-
nal Mushaf Al-Qur’an Standar Usmani Indonesia: Studi Komparatif atas Mushaf Standar Usmani 1983 dan 2002”, Suhuf, Vol. 4, No. 1, 2011.
7Mu¥ammad Salīm Mu¥aisīn, Irsyād at-°ālibīn ilā ¬abt al-Kitāb al-Mubīn, al-Qāhirah: al-Maktabah al-Azhāriyyah li at-Turā£, 1989, hlm. 6. Ibrāhīm bin A¥mad al-Maragini, Dalīlul-¦airān Syar¥ Maurid al-Îam’ān, al-Qāhirah: Dār al-Qur'ān, 1974, hlm. 321.
8Karena sukun adalah tanda bahwa huruf tersebut mati, tidak bergerak, tidak berbunyi. Hal ini berbeda dengan fathah, kasrah dan «ammah, dimana huruf yang diberi tanda itu menunjukan adanya suara a-i dan u.
9Tentang hamzah dalam disiplin ilmu Rasm Usmani juga menjadi kaidah tersendiri, namun tidak semua hamzah masuk dalam diskursus ini. Ada beberapa pola penulisan hamzah yang tidak masuk pembahasan rasm-rasm akan tetapi masuk dalam kategori «ab¯. Selengkapnya baca: Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur’an tentang Penulisan dan Tanda Baca, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departeman Agama, 1976, h. 33-36, bandingkan dengan Muhammad Salīm Mu¥aisīn, Irsyād a¯-°ālibīn ilā ¬abt al-Kitāb al-Mubīn, hlm. 23-26.
5 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 5
hitam, hijau, kuning dan merah.10 Menurut al-Farmawi berdasarkan informasi ad-Dani (w. 444 H), sistem warna yang diterapkan pada masa awal (baik menyangkut pada substansi rasm maupun «ab¯) memiliki ragam pewarnaan yang berbeda-beda berdasarkan wila-yah tertentu. Mushaf Madinah menggunakan tiga sistem pewarna-an: hitam untuk huruf dan naqt al-i’jām, merah untuk harakat, su-kun, dan tasydīd, dan kuning hanya untuk hamzah. Mushaf Andalus (Spanyol) menggunakan empat sistem pewarnaan: hitam untuk huruf, merah untuk syakl, kuning untuk hamzah dan hijau untuk alif wa¡al. Mushaf Irak menggunakan dua sistem pewarnaan: merah untuk hamzah dan hitam untuk huruf. Beberapa mushaf tertentu mempergunakan tiga sistem pewarnaan: merah untuk «ammah, kasrah dan fathah, hijau untuk hamzah, dan kuning untuk hamzah bertasydid.11
Bentuk ini sangat berbeda dengan model harakat dan tanda baca yang kita kenal sekarang, seperti: «ammah yang dilambangkan dengan waw kecil di atas huruf, fathah berbentuk baris miring lurus melintang di atas huruf, dan kasrah berbentuk garis miring lurus di bawah huruf. Selanjutnya, bentuk titik bulat (an-naqt) ini kemudian terklasifikasi menjadi dua, [1] naqtul-i’rāb yang berarti titik untuk menandakan baris huruf, seperti baris fathah, kasrah dan «ammah, dan [2] naqtul-i’jām yang berarti titik yang menandakan jenis huruf, seperti titik pada huruf ba’, ta’ dan tsa’.12
Gambar 1. Mushaf Al-Qur’an Usman (Topkapi Turki) dengan titik-titik tanda baca. Hasil editing Dr. Tayyar Altikulac
10Abdul-Hayy al-Farmawi, Rasm al-Mus¥af wa-Naqtuh, Makkah: al-Makta-
bah al-Makkiyah, 2004 M/1425 H, cet. ke-1, hlm. 308-309. 11Abdul-Hayy al-Farmawi, Rasm al-Mus¥af wa-Naqtuh, hlm. 308-310. 12Gānim Qaddūri al-Hamd, “Muwazanah bain a«-¬abt fī Rasm al-Mus¥af
war-Rasm al-Qiyās”, Majalah al-Bu¥µ£ wa ad-Dirāsah al-Qur'āniyah, hlm. 22.
6 6 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
Terdapat banyak riwayat yang mencoba meluruskan, siapa peletak dasar disiplin dua cabang ilmu ini. Peletak dasar naqt al-i’rāb menurut salah satu sumber adalah al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi (w. 170 H ), menurut riwayat lain Nasr bin Ashim al-Laitsi (w. 90 H) dan Yahya bin Ya’mar al-‘Udwani (w. Sebelum 90 H), menurut sumber yang lain Abdullah bin Ishaq al-Hadrami. Namun, menurut sumber terpercaya, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Amr ad-Dani (w. 444 H), Abu Daud (w. 496 H), dan Abu Hatim (w. 322 H) peletak dasar ilmu ini adalah Abul Aswad ad-Duali (w. 62 H) atas perintah Ziyad bin Abi Ziyad, Gubernur Basrah (45-53 H) pada masa Khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun (41-60 H/661-680 M).13
Sebagaimana terjadi perbedaan dalam pencetus naqt al-i’rab. Dalam ilmu naqt al-i’jām juga terjadi banyak riwayat, namun berdasarkan penelitian yang lebih kuat menurut Salim Muhaisin peletak dasar disiplin ilmu ini adalah Nasr bin Ashim dan Yahya bin Ya’mar atas perintah al-Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi, Gubernur Irak (75-95 H ) di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan (65-86 H). Adapun kontribusi besar al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi dalam perkembangan disiplin ilmu ini adalah sebagai penyempurna teori naqt (titik bulat) yang dirintas oleh Abul-Aswad ad-Duali14 ke dalam bentuk huruf kecil atau yang belakangan dikenal sebagai harakat seperti yang berlaku hingga sekarang. Al-Khalil membe-rikan kreasi-kreasi baru dalam ilmu «ab¯/syakl yakni dengan me-rumuskan syiddah dengan kepala sin, sukun dengan kepala kha’
13Ibrāhīm bin A¥mad al-Maragini, Dalīl al-¦airān Syarh Maurīd ¬am‘ān,
hlm. 322; A¥mad Mu¥ammad Abū Zai¯ar, (Editor) Yasīr Ibrāhīm al-Mazru‘i, as-Sabīl Ilā ¬abt Kalimāt at-Tanzīl, Kuwait: Masyru Ra‘iayah Al-Qur'ān, cet. I, hlm. 12.
14Menurut teori naq¯ ad-Du’ali, fat¥a¥ adalah huruf dengan titik di depan-nya, kasrah dengan titik di bawah, tanwin atau ghunnah dengan dua titik. Penje-lasan lebih detail tentang hal ini dapat dilihat dalam Abū Bakr ‘Abdillāh bin Sulaimān bin al-As‘ab al-Sijistanī (Ibn Abī Dāwūd), Kitāb al-Ma¡āhif Editor: Arthur Jeffery: Mesir: Maktabah al-Rahmāniyyah, 1355 H/1936 M, crt. Ke-1. Bandingkan; Gānim Qaddūri al-¦amd, Rasm al-Mu¡¥af; Dirāsah Lughawiyah Tarīkhiyyah. Baghdād: Lajnah Wa¯aniyah li al-I¥tifāl bi Ma¯la‘ al-Qarn al-Khā-mis ‘Asyar al-Hijrī, 1402 H/1982.
7 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 7
(bukan bulat bundar), dan lain-lain.15 Meskipun al-Khalil berupaya menyempurnakan konsep ad-Duali dalam bentuk «ab¯/syakal yang di konversi dalam bentuk huruf kecil, fathah dengan alif kecil yang dimiringkan, «ammah dengan huruf waw kecil, dan kasrah dengan ya kecil tanpa titik. Namun terdapat beberapa ulama yang mencoba tetap memegang konsep ad-Duali tentang «ab¯, misalnya Abu Amr ad-Dani (w. 444 H) yang berupaya mempertahankan beberapa konsep ad-Duali dalam kitabnya al-Muhkam fī Naqt al-Ma¡ā¥if.16
Dari karya-karya di ataslah semua bentuk «abt/syakal pada cetakan Mushaf Al-Qur’an di dunia saat ini secara umum mengacu. Baik yang menerapkannya secara konsisten atas karya monumental al-Khalil bin Ahmad, mengacu pada konsep ad-Duali, atau kombi-nasi antara beberapa teori di atas yang dianggap lebih memudahkan pembacaan terhadap mushaf Al-Qur’an. Misalnya, Mushaf Medi-nah/Mesir17 (dalam hal rasm Usmani mengacu mazhab syaikhāni (ad-Dani dan Abu Dawud) dan men-tarjih-kan mazhab Abu Dawud (w. 496 H) pada banyak kasus ketika ada perbedaan dengan ad-Dani). Ternyata, dalam hal «abt sukun, tidak semuanya mengacu pada mazhab Abu Dawud yang menuliskannya dengan bulat bun-dar (¡ifr ¡agīr),18 akan tetapi memilih konsep al-Khalil, yakni de-ngan bentuk kepala huruf khā’.
15Mu¥ammad Salīm Mu¥aisin, Irsyād a¯-°ālibīn ilā ¬ab al-Kitāb al-Mubīn,
al-Qāhirah: al-Maktabah al-Azhāriyyah lit-Turā£, 1989, hlm. 7-42. 16Abū ‘Amr ‘Usmān bin Sa‘īd ad-Dānī, al-Mu¥kām fī Naqt al-Ma¡ā¥if.
diskusi lebih dalam dalam disiplin ilmu ini dapat dibuka dalam kaya-karya seje-nis, seperti: U¡ūl ad-¬abt karya Abū Dāwūd Sulaimān bin Naja¥, Na©m Maurīd a«-«am‘ān fī rasm Al-Qur'ān karya Abū ‘Abdullāh Mu¥ammad bin Ibrāhīm al-Amawī asy-Syuraisyī atau yang lebih terkenal dengan nama al-Kharrāz (w. 718 H), a¯-°irrāz ilā ¬abt al-Kharrāz karya Abū ‘Abdillāh Mu¥ammad bin ‘Abdillāh at-Tanasi (w. 899 H), dan terakhir buku kecil yang dihimpun dari karya al-Kharrāz di atas, yang berjudul Irsyād a¯-°ālibīn fī ¬abt al-Kitāb al-Mubīn yang ditulis oleh Mu¥ammad Salīm Mu¥aisin.
17Mushaf Madinah yang di maksud adalah Mushaf Al-Qur’an riwayat Hafs ‘an Ashim yang dicetak oleh Mujamma’ Malik Fahd, Saudi Arabia sejak tahun 1984. Adapun Mushaf Mesir yang dimaksud adalah mushaf Al-Qur’an edisi Mesir 1923 atau edisi Raja Fuad I yang menjadi embrio dominasi mushaf Al-Qur’an dengan rasm usmani mengacu pada mazhab as-Syaikhani bir-rasm de-ngan tarjih pandangan Abu Dawu Sulaiman bin Najah (w. 496 H) atas gurunya Abu Amr ad-Dani (w. 444 H) ketika terjadi perbedaan pendapat antara keduanya.
18Abū Dāwūd Sulaimān bin Naja¥, (editor) A¥mad bin A¥mad bin Mu'am-mar Syirsyal, U¡ūl a«-¬abt, Makkah: Maktabah Mālik Fahd, 1427, hlm.45.
8 8 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
Dalam konteks kajian pada MAQSI, peneliti untuk seterusnya tidak akan mempergunakan terminologi «abt/syakl, akan tetapi lebih memilih istilah ‘harakat dan tanda baca’ sebagai istilah ganti naq¯ al-‘irāb. Sementara kajian naq¯ al-i’jām tidak akan diulas, me-ngingat adanya kesamaan pola MAQSI dengan mayoritas mushaf-mushaf internasional, melainkan hanya ditampilkan sebatas penga-yaan informasi dan sejarah dalam perjalanan ilmu «abt.
Konsep Penetapan Bentuk Harakat dan Tanda Baca dalam MAQSI
Sebagaimana diskusi tentang rasm usmani mulai diperbin-cangkan sejak Muker Ulama Ahli Al-Qur’an pada tahun 1974. Diskusi tentang harakat dan tanda baca pun juga mengiringinya pada Muker Ulama ke-II/1976. Data menarik lain yang sering dilupakan oleh para pengkaji tanda baca Mushaf Al-Qur’an di Indonesia adalah keterkaitan antara MAQSI dengan Mushaf Al-Qur’an Kuno Nusantara. Muker II/1976 jelas mempertimbangkan dan mengkomparasikan beberapa bentuk penulisan al-ta’rif dan bentuk tanwin, tanda mad silah, dan tanda sifir.19 Misalnya, dalam model penulisan al-ta’rif dan penulisan tanwin yang dipresentasi-kan oleh H. Sawabi Ihsan, MA sebagai pemakalah Masalah Tanda Baca Al-Qur’an, melampirkan 8 model mushaf, mulai dari; Mesir, Bahriyah 1950, Bahriyah 1968, Pakistan, Menara Kudus, Al-Qur’an berusia 125 tahun, Firma Sumatera, dan Indonesia (umum).
Berdasarkan telaah beberapa dokumen Muker Ulama Al-Qur’an terkait penetapan harakat dan tanda baca, penting dikemu-kakan bahwa konsep penetapannya dalam rumusan MAQSI tidak berangkat dari literatur ilmu «abt, akan tetapi bertolak dari data komparasi harakat dan tanda baca berbagai mushaf Al-Qur’an dari dalam dan luar negeri serta beberapa mushaf Al-Qur’an yang telah beredar di Indonesia di kisaran tahun 1974-1980-an. Tidak ada keterangan resmi kenapa menempuh metode tersebut, akan tetapi dugaan penulis hal ini dipicu salah satunya kelangkaan sumber tulisan, karena literatur-literatur ilmu «abt di kurun waktu itu belum
19Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur’an tentang Penulisan dan Tanda
Baca, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departeman Agama, 1976, hlm. 60-63.
9 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 9
banyak tercetak secara masif dan masih berbentuk banyak manu-skrip yang masih tersimpan di beberapa perpustakaan.20
Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian H. Sawabi Ihsan, MA yang menjadi salah satu pemateri Muker Ulama Al-Qur’an yang dipresentasikan dalam Muker II/1976, saat itu Muker diha-dapkan pada tiga persoalan penting yang harus diputuskan:
1. Tanda baca yang telah di adopsi dari luar negeri; 2. Apakah tanda-tanda baca tersebut memiliki pengaruh besar
bagi anak-anak Indonesia, dengan catatan bila berpengaruh perlu ada pengkajian sehingga dapat dijadikan pedoman, khususnya untuk penyeragaman pentashihan;
3. Kalau memang ada tanda baca yang belum dimiliki, tetapi dapat diterima dan lebih memudahkan cara membaca Al-Qur’an, tentu dapat dipilih yang terbaik untuk dipergu-nakan di Indonesia.21
Dari tiga persoalan di atas, secara jelas terbaca bagaimana realitas mushaf-mushaf Al-Qur’an yang beredar di tahun 1976-an memiliki banyak keragaman. Sebagian penerbit telah melakukan konversi dan inovasi penggunaan tanda baca dari luar negeri untuk dicetak di dalam negeri dengan standar tanda baca yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya, Muker dihadapkan pada pertanyaan, apa-kah penerapan tanda-tanda baca tersebut memiliki impact terhadap pengguna mushaf Al-Qur’an dalam negeri, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut. Terakhir, pilihan keterbukaan Muker yang membuka ruang adopsi tanda baca yang tidak familiar bila memang dipandang perlu. Oleh karena itu, bila kita jeli memperbandingkan antara mushaf Al-Qur’an yang beredar sebelum dan setelah MAQSI, akan memiliki
20Sebut misalnya al-Muhkām fī Naqt al-Ma¡ā¥if karya ad-Dānī (w. 444 H)
berdasarkan studi ‘Izzah ¦asan awalnya beradasarkan manuskrip Mus¯afā Khan di Perpustakaan Fakultas Bahasa dan Sejarah di Universitas Ankara (Turki), baru berhasil dipublikasi pertama kali pada tahun 1960, cetakan kedua 1984 dan cetak ulang edisi ke-2 pada tahun 1997. Abū ‘Amr ‘Usmān bin Sa‘īd ad-Dānī, al-Mu¥kām fī Naqt al-Ma¡āhif, Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu‘±¡ir, 1997, dalam bab mukadimah, hlm. 22.
21Sawabi Ihsan, Masalah Tanda Baca Al-Qur’an, dalam Badan penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur’an tentang Penulisan dan Tanda Baca, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departeman Agama, 1976, hlm. 55.
10 10 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
titik perbedaan yang substantif dalam hal ini, seperti penggunaan sifir yang tidak lazim dalam mushaf 1960-an.
Terdapat kaidah umum dalam penempatan harakat dan tanda baca dalam MAQSI. Pola tersebut adalah mempergunakan harakat dan tanda baca secara lengkap sesuai dengan bacaanya,22 dengan spirit untuk memudahkan dalam membaca Al-Qur’an bagi masya-rakat umum. Selain berpijak dari mushaf yang sudah beredar dan dipergunakan secara turun-temurun (mushaf Bombay), dan seba-gian mushaf Al-Qur’an Kuno Nusantara, Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an sebagai forum tertinggi dalam penetapan MAQSI juga melakukan kajian hasil komparasi harakat dan tanda baca berdasar-kan masukan para ulama yang hadir.
Gambar 2. Model «ab¯ pada Mushaf ala Bombay.
Dari semangat di atas, pada pelaksanaan Muker II/1976 telah
berhasil mengidentifikasi 27 kategori bentuk penulisan harakat dan tanda baca dari 6 sampel mushaf cetakan Mushaf yang beredar waktu itu, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ke-27 item pembahasan yang dimasukkan dalam kategori bentuk harakat dan tanda baca tersebut secara berurutan adalah: ha-rakat, saknah, tanwin, mad ¯abi’i, huruf tidak berfungsi, tanda me-mudahkan bacaan, imālah, isymām, saktah, hamzah, tanwin wa¡al, bacaan masyhūr, huruf tertinggal, tanda sajdah, hizib, marka’, no-mor ayat, mad (tanda panjang), harakat lafal jalālah, i©hār, idgam, iqlāb, ikhfa’, idgam mi£lain, idgām mutāqaribain, idgām mutajāni-sain dan mad ¡ilah.23
22Mazmur Sya’roni, “Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur’an Standar
Indonesia”, Lektur, Vol. 5. No. 1, 2007. 23Badan Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Pedoman Pentas-
hihan Mashaf Al-Qur’an tentang Penulisan dan Tanda Baca, hlm. 68a-68c.
11 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 11
Dari semua daftar tersebut di atas, kemudian Muker membahas dan mengkaji efektivitas tanda-tanda yang ada untuk kemudian disepakati, dipilih serta dibakukan penggunaannya. Pada akhirnya, semua pilihan tersebut secara bertahap diterapkan dalam pola penulisan MAQSI dengan ketiga jenisnya (lihat halaman lampiran).
Dari hasil penelitian dan inventarisasi Muker II/1976, ternyata tidak semua kategori yang berhasil diidentifikasi masuk dalam disiplin ilmu «abt, akan tetapi lebih pada pembakuan hasil kreasi dan penyempurnaan dalam perkembangan cetakan Al-Qur’an wak-tu itu, tepatnya di kisaran waktu 1976-1980-an.
Dari hasil inventarisasi tersebut, berikut adalah penjelasan singkat, sedikit komentar dan perbandingan bentuknya dengan Mushaf Madinah, terkait penggunaan harakat dan tanda baca hasil komparasi pada Muker II/1976 dan diterapkan dalam MAQSI sam-pai sekarang. a. Harakat
MAQSI membakukan tanda harakat fathah, kasrah, dan dammah seperti konsep yang dikenalkan oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi.
Berikut adalah komparasi harakat dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Harakat MAQSI Mushaf Madinah
Fatihah # (Q.S.1/1)
Kasrah ) (Q.S.1/2)
¬ammah & (Q.S.1/2)
b. Saknah
MAQSI membakukan syakl sukun sebagaimana konsep al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, yakni berbentuk kepala huruf kha’, bukan bulat bundar menyerupai tanda sifir bulat bundar.
Berikut adalah komparasi tanda saknah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Saknah MAQSI Mushaf Madinah
Saknah i§hār U TV (Q.S.11/40)
Saknah idgām ? > (Q.S.2/8)
Saknah ikhfa’ ) (Q.S.2/6)
12 12 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
c. Tanwin MAQSI secara umum membakukan tanda tanwin sejajar, baik fathatain, kasratain dan «ammatain,24 tanpa mempertimbang-kan bacaan tajwid pada huruf sesudahnya. Hal ini berbeda dengan Mushaf Madinah yang membedakan penulisan tanwin pada bacaan idzhar dengan dua harakat yang sejajar dan bacaan idgam bigunnah atau ikhfa’ dengan tanwin yang tidak sejajar. Berikut adalah komparasi tanwin dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Dabt Tanwin MAQSI Mushaf Madinah
Bacaan izhar \ [ (Q.S.2/10)
Bacaan idgam A @ (Q.S.2/19)
Bacaan ikhfa’ V U (Q.S.2/10)
d. Mad ¯abi’i
MAQSI secara umum membakukan harakat lengkap dan syakl sukun dalam bacaan mad ¯abi’i. Kecuali pada mad ¯abi’i yang berupa alif, maka tidak ada dibubuhkan sukun. Berikut adalah komparasi penulisan mad ¯abi’i dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Mad ¯abi‘i MAQSI Mushaf Madinah
Huruf ya’ b (Q.S.2/11)
Huruf alif a(Q.S.2/11)
e. Huruf tidak berfungsi
MAQSI secara umum membakukan dua perangkat untuk menandakan huruf tidak berfungsi dengan dua cara; (1) dengan memberikan tanda sifir mustadir, (2) tidak memberikannya harakat/syakl.
Berikut adalah komparasi penanda huruf tidak berfungsi dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Huruf tanpa fungsi
MAQSI Mushaf Madinah
Sifir mustadīr (' (Q.S.12/87)
24Kecuali yang berhadapan dengan nun ¡ilah.
13 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 13
Sifir musta¯īl L (Q.S.18/38)
Tanpa harakat × Ù Ø (Q.S.49/11)
f. Tanda memudahkan bacaan
MAQSI membakukan dalam konteks tanda untuk memudahkan bacaan, tidak mempergunakan kode tertentu (seperti bulatan hitam/jajaran genjang segi empat) atau huruf tertentu. Akan tetapi menuliskannya sesuai dengan hukum bacaan tersebut. Se-perti: bacaan imālah dituliskan dengan redaksi imālah di bawah huruf yang dimaksud. Hal yang sama juga berlaku untuk bacaan isymām dan saktah.
Berikut adalah komparasi tanda memudahkan bacaan dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Bacaan MAQSI Mushaf Madinah
Imālah c (Q.S.11/41)
Isymām ¬ « (Q.S.12/11)
Tashīl ° (Q.S.41/44)
g. Tanda saktah
Sebagaimana lazimnya mushaf Al-Qur’an yang mengacu riwa-yat Hafs dari ‘Ashim, MAQSI memiliki empat saktah. Hanya saja model penandaannya dengan dituliskan kata saktah di atas kalimat yang dimaksud.
Berikut adalah komparasi tanda saktah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Bacaan MAQSI Mushaf Madinah
Q.S. 18/1 ¶¸ º ¹
Q.S. 36/52 ¿ ¾ÁÀ Â
h. Hamzah
MAQSI membakukan untuk tidak membedakan antara hamzah qatha dan hamzah wa¡al. Sebagaimana lazimnya beberapa mushaf luar negeri yang terkadang memberikan tanda kepala ¡ad di atas hamzah wa¡al, dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia pada umumnya tidak dipergunakan. Begitupun, kepa-la ‘ain pada hamzah qa¯a, kecuali pada beberapa hal.
14 14 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
Berikut adalah komparasi penulisan hamzah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Hamzah MAQSI Mushaf Madinah
Di awal ± (Q.S.2/14)
Di tengah Æ(Q.S.2/16)
Di akhir ¿ (Q.S.2/15)
i. Tanwin wa¡al
MAQSI dalam kasus nun ¡ilah membakukan ketentuan. Tanwin (fathatain, «ammatain dan kasratain) pada kata yang berha-dapan dengan hamzah wa¡l dan kalimat tersebut dibaca wa¡l, tanda tanwin-nya cukup ditulis dengan «ammah dan kasrah sedang kata yang mengandung hamzah wa¡l diberi huruf nun kecil (di bawah) hamzah-nya untuk memudahkan bacaan.
Berikut adalah komparasi tanwin washal dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Bentuk tanwin MAQSI Mushaf Madinah
Fathatain ¶ (Q.S.2/180)
Kasratain j i (Q.S.7/8)
Dammatain n m (Q.S.9/30)
j. Bacaan masyhur25
MAQSI membakukan menyangkut bacaan masyhur berupa tan-da sin kecil di atas huruf yang bersangkutan, bukan menuliskan-nya dalam bentuk kalimat.
Berikut adalah komparasi bacaan masyhur dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Bacaan masyhur MAQSI Mushaf Madinah
al-A’raf/7:69 ?@
25Bacaan masyhur yang dimaksud adalah riwayat bacaan tertentu yang lebih
banyak diikuti (populer) dari sekian riwayat bacaan yang diperselisihkan oleh para pakar qira’at.
15 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 15
k. Tanda sajdah26 MAQSI membakukan menandai tanda sajdah di akhir ayat tersebut dan menuliskan kata sajdah di luar bingkai/frame-nya.
Berikut adalah komparasi tanda sajdah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Tanda sajdah MAQSI Mushaf Madinah
Simbol WX (Q.S.17: 109)
l. Hizib
MAQSI membakukan dan memberlakukan tanda hizib dalam satu juz menjadi 4 hizib. 27
Berikut adalah komparasi hizib dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis hizib MAQSI Mushaf Madinah hizib 1 -- --
¼ hizib 1 I J (Q.S.2/26)
½ hizib 1 s t (Q.S.2/44)
¾ hizib 1 J L K (Q.S.2/60)
hizib 2 ³ (Q.S.2/75)
26Tanda sajdah diletakkan pada akhir ayat-ayat sajadah dengan tanda di
akhir ayat dan bingkai luar teks (iluminasi). Dalam literatur terkait, terjadi khila-fiah para ulama tentang penempatan ayat-ayat sajadah, namun Muker menyepa-kati dan membakukan 15 tempat secara definitif dalam MAQSI, sebagai berikut; al-A’rāf/7: 206, ar-Ra’d/13:15, an-Nahl/16: 16:50, al-Isrā’/17: 109, Maryam/19: 58, al-Hajj/22: 18, al-Furqān/25: 60, an-Naml/27: 26, as-Sajdah/32: 15, ¢ād/38: 24, Fu¡¡ilat/41: 38, an-Najm/53: 62, al-Insyiqāq/84: 21, dan al-‘Alaq/96: 19.
27Hizb adalah pembagian dalam satu juz menjadi bagian-bagian tertentu. Misalkan dalam juz satu, terdiri dari: hizib 1, ¼ , ½ , dan ¾, hizb 1, hizb 2, ¼, ½, dan ¾ hizib 2. Dalam ulumul-qur’an dikenal ada disiplin ilmu tentang tahzib/ taqsim Al-Qur’an menjadi beberapa bagian, di antaranya yang tersisa sampai sekarang dalam penerbitan dan percetakan Al-Qur’an adalah pembagiannya men-jadi 30 dan 60. Pembagian Al-Qur’an menjadi 30 familiar dikenal menjadi juz, sehingga dikenal menjadi 30 juz. Sementara pembagiannya menjadi 60 dalam literatur taqsim Al-Qur’an dikenal sebagai hizib. Kedua sistem ini tetap diakomo-dasi dalam penulisan MAQSI. Keterangan tentang tahzib selengkapanya dapat dibaca: ‘Abd al-Az³z bin ‘Al³ al-♦arb³, Ta¥z³b Al-Qur′±n, Makkah: D±r Ibnu Hazm, 2010 M/1431 H, cet. Ke-1, dan Abµ al-Faraj ‘Abdurrahman bin al-Jauz³, Funµn al-Afn±n f³ ‘Uyµni ′Ulµm Al-Qur′±n, Bairµt: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyah, 1987 M/1408 H, cet. I.
16 16 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
¼ hizib 2 { | (Q.S.2/92)
½ hizib 2 ! # " (Q.S.2/106)
¾ hizib 2 t v u (Q.S.2/124)
m. Marka’28
MAQSI membakukan dan memberlakukan tanda ruku’ dengan huruf ’ain di luar bingkai.
Berikut adalah komparasi marka’ dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Marka’ MAQSI Mushaf Madinah
Tanda huruf ‘ain --
n. Nomor ayat
MAQSI membakukan dan mengacu tanda ayat dengan lingkaran bulat dengan mengacu jumlah ayat Al-Qur’an menurut al-Kuffiyun, yakni 6236 ayat.
Nomor ayat MAQSI Mushaf Madinah
Lingkaran bulat s
o. Mad (tanda panjang)
MAQSI membakukan dan membedakan antara tanda panjang mad wajib dan mad jaiz. Tidak seperti lazimnya mushaf Timur Tengah yang pada umumnya menyamakan dua tanda tersebut. Berikut adalah komparasi tanda panjang dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Mad MAQSI Mushaf Madinah
Wajib mutta¡il £ (Q.S.2/22)
Jaiz munfa¡il Z Y (Q.S.2/20)
28Marka’ adalah tanda yang dituliskan dengan huruf ‘ain yang diletakkan di
akhir ayat-ayat tertentu (di dalam tubuh teks di samping bulatan nomor ayat dan di bingkai iluminasi ayat). Panulis belum menemukan keterangan detail tentang maksud tanda marka’. Menurut salah satu sumber, marka’ adalah tanda berakhirnya satu kesatuan tema dalam rangkaian ayat tertentu yang masih berada dalam satu surah. Makanya, dalam surah-surah pendek pada juz 30 pada umumnya menjadi satu marka’.
17 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 17
p. Harakat lafal jalālah MAQSI membakukan tanda harakat berdiri pada lam setiap lafal jalalah. Berikut adalah komparasi harakat jalalah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis Harakat MAQSI Mushaf Madinah
Harakat tegak .
q. I§hār
MAQSI membakukan untuk tidak menambahkan tanda nun i§hār pada bacaan i§hār sebagaimana mushaf yang lazim pada tahun 1960-an. Berikut adalah komparasi bentuk i§hār dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Bentuk izhar MAQSI Mushaf Madinah
Sukun izhar % $ (Q.S.2/6)
r. Idgām
MAQSI membakukan setiap bacaan idgham, baik karena nun mati atau tanwin dengan menambahkan tanda syiddah dalam huruf idgam tersebut. Ketentuan yang sama juga berlaku pada idgām mi£lain, idgām mutaqāribain,dan idgām mutajānisain. Berikut adalah komparasi harakat idgam dalam kedua mushaf.
Jenis Idgam MAQSI Mushaf Madinah
mitslain a (Q.S.24/33)
mutaqaribain D (Q.S.12/80)
mutajanisain $ # (Q.S.10/89)
s. Iqlab
MAQSI membakukan tanda iqlab setelah nun mati atau tanwin dengan menambahkan mim kecil sebagai tanda bacaan iqlab. Berikut adalah komparasi harakat iqlab dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Iqlab MAQSI Mushaf Madinah
Tanda mim kecil { z (Q.S.2/27)
18 18 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
t. Ikhfa’ MAQSI membakukan untuk tidak memberikan tanda apa pun untuk bacaan ikhfa melainkan berdasarkan fungsi harakat seca-ra penuh dan syakl pada 15 huruf ikhfa. Berikut adalah kompa-rasi harakat ikhfa’ dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Ikhfa’ MAQSI Mushaf Madinah
Sukun ikhfa’ ) ( (Q.S.2/6)
u. Mad ¡ilah
MAQSI membakukan tanda harakat kasrah berdiri dan «am-mah terbalik untuk menandakannya.29 Berikut adalah kompa-rasi ¡ilah dalam MAQSI dan Mushaf Madinah.
Jenis silah MAQSI Mushaf Madinah
Silah kasrah = < (Q.S.2/25)
Silah dammah Ê ÉÌ (Q.S.2/255)
Simpulan
Dari pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan. Per-tama, konsep penetapan bentuk harakat dan tanda baca dalam MAQSI adalah mengacu berdasarkan hasil komparasi tanda baca dan harakat terhadap cetakan mushaf-mushaf Al-Qur’an dari enam sampel: tiga mushaf dari dalam negeri dan tiga mushaf dari luar negeri, beberapa manuskrip Al-Qur’an kuno dan tanda baca mushaf ‘Bombay’ yang familiar dipergunakan di masyarakat pada tahun 1970-an. Semuanya, menghasilkan 27 kategori dan bentuk harakat dan tanda baca.
Kedua, dari 27 kategori harakat dan tanda baca yang dise-pakati dan dibakukan penggunaannya dalam MAQSI dilihat dari perspektif ilmu «abt, ternyata tidak semuanya memiliki keterkaitan. Dari semua pembahasan harakat dan tanda baca yang memiliki benang merah dengan disiplin ilmu «abt hanya mencakup 4 kate-gori, yakni harakat, sukun, syiddah, dan tanda mad. Selebihnya merupakan pembakuan hasil penelitian Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an/Puslitbang Lektur Agama, suatu inovasi berdasarkan
29 Untuk memperjelas pembahasan di atas, dapat dilihat dalam tabel kom-
parasi di halaman lampiran.
19 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 19
komparasi berbagai mushaf dan hasil kesepakatan Muker Ulama Al-Qur’an dari tahun 1974-1983.[] Wallahu a‘lam. Daftar Pustaka
Abū Zai¯h±r, A¥mad Mu¥ammad, as-Sabīl Ilā ¬abt Kalīmah at-Tanzīl, Kuwait:
Masyrū‘ Rai’ayah Al-Qur'ān, cet. Ke-1.
Badan Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departeman Agama, 1976.
__________, Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, Jakarta: Depar-temen Agama, 1984-1985.
ad-Dānī, Abū ‘Amr U£mān bin Sa‘īd, al-Mu¥kām fī Naqtil-Ma¡āhif, Libanon: Dārul-Fikr al-Mu‘a¡ir, 1997.
al-Farmāw³, ‘Abdul-Hayy Rasmul-Mu¡haf wa-Naqtuh, Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 2004 M/1425 H, cet. ke-1.
al-¦arb³, ‘Abd al-Az³z bin ‘Al³, Ta¥z³b Al-Qur′±n, Makkah: D±r Ibnu Hazm, 2010 M/1431 H, cet. Ke-1.
al-Hamd, Ghānim Qaddūri, Abhā£ fī ‘Ulūm Al-Qur'ān, Irak: Dār ‘Ammar, 1426 H/2006 M, cet. Ke-1.
__________, Muwazanah baina ad-¬abt fī Rasm al-Mu¡haf war-Rasm al-Qiyāsi, dalam Majalah al-Buhu£ wad-Dirāsah al-Qur'āniyyah.
________, Rasm al-Mu¡¥af; Dirāsah Lughawiyah Tarikhiyyah. Baghdād: Lajnah Wa¯aniyah lil-i¥tifāl bi Ma¯la‘ al-Qarn al-Khāmis ‘Asyar al-Hijrī, 1402 H/1982.
al-Jauz³, Abµ al-Faraj ‘Abdurrahman bin, Funµn al-Afn±n f³ ‘Uyµni ′Ulµm Al-Qur′±n, Bairµt: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyah, 1987 M.1408 H, cet. Ke-1.
al-Maraghini, Ibrāhīm bin A¥mad, Dalīl al-¦airān Syar¥ Maurīd ¬am‘ān, al-Qāhirah: Dār Al-Qur'ān, 1974.
Mu¥ammad Sālim Mu¥aisīn, Irsyād a¯-°ālibīn ilā ¬abt al-Kitāb al-Mubīn, al-Qāhirah: al-Maktabah al-Azhāriyyah lit-Turā£, 1989.
Muhammad Shohib (editor), Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
Naja¥, Abū Dāwūd Sulaimān bin, U¡ūlu«-«abt, Makkah: Maktabah Mālik Fahd, 1427.
20 20 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 1-22
Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Proyek
Penelitian Keagamaan RI, “Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar,” Menge-nal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, (Jakarta:1973 s/d. 1984), lam-piran IX.
as-Sijistanī, Abū Bakr ‘Abdillāh bin Sulaimān bin al-As‘āb (Ibnu Abī Dāwūd), Kitāb al-Ma¡āhif, Mesir: Maktabah ar-Ra¥māniyyah, 1355 H/1936 M, cet. Ke-1.
Sya’roni, Mazmur, Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia, Jurnal Lektur, Vol. 5. No. 1, 2007.
Syirsyal, A¥mad bin A¥mad, at-Taujīh as-Sadīd fi Rasm wa ¬abt Balagah Al-Qur'ān al-Majīd, Kuwait: Kulliyah asy-Syarī‘ah wa Dirāsah al-Islāmiyyah, 2002.
at-Tanasi, Abū ‘Abdillāh Mu¥ammad bin ‘Abdillāh, a¯-°irrāz ilā ¬abt al-Kharrāz, t.t.
Zaenal Arifin, Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia; Studi Komparatif atas Mushaf Standar Usmani 1983 dan 2002, Suhuf, Vol. 4, No. 1, 2011.
21 Harakat dan Tanda Baca Al-Qur’an Indonesia — Zaenal Arifin 21
Lampiran Tanda baca Al-Qur’an dari berbagai negara. Sumber: Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur’an tentang Penulisan dan Tanda Baca, diterbitkan oleh Puslit-bang Lektur Agama, Badan Litbang Agama tahun 1976, hlm. 68-69.
Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia Benang Merah Institusi Pentashihan sebelum Tahun 1959
The Pattern of the Correction of the Qur’an Relations of the Institution of the Correction of the Qur’an in Indonesia before 1959
Abdul Hakim Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Gedung Bayt Al-Qur’an TMII, Jakarta 13560 [email protected] Naskah diterima: 09-03-2014; direvisi: 07-05-2014; disetujui: 16-05-2014. Abstrak Tulisan ini menjelaskan tentang pola-pola tashih Al-Qur’an di Indonesia dengan mengambil sampel dari Al-Qur’an tulis tangan dan beberapa Al-Qur’an cetakan yang terbit sebelum 1959. Tahun tersebut merupakan tahun berdirinya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an yang berfungsi sebagai lembaga tashih tunggal atas semua Al-Qur’an yang beredar di Indonesia. Ada dua pola tashih mushaf tulis tangan, yaitu tashih pada saat penyalinan dan tashih pasca-penyalinan. Adapun Al-Qur’an cetakan memiliki dua pola: tashih kepada lembaga keaga-maan lokal dan tashih kepada pentashih yang terdiri dari para ulama Al-Qur’an.
Kata kunci: tashih, Al-Qur’an cetakan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, mushaf kuno. Abstract This paper describes the patterns of the correction of the Quran in Indonesia by taking samples from the Quranic handwriting and some printed Qur'an which were published before 1959. The year was the year of the establishment of the Institution of the Correction of the Quran which serves as the sole for all the Quran circulated in Indonesia. There are two pattens of the correction of the Quranic handwriting namely the correction at the time of rewriting and that of after rewriting. As for the printed Quran, there are two patterns: correction to the local religious institution and correction to the correctors which consist of the Quranic scholars.
Keywords: tashih (correction of the Qur’an), printed Qur’an, Standing Committe of the Correction of the Quran, ancient manuscript.
24 24 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
Pendahuluan Sebagai kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh umat
Islam, Al-Qur’an sejak awal diturunkan hingga kini selalu melalui tashih untuk menjaga kemurniannya. Pada zaman Rasulullah, Al-Qur’an sudah banyak ditulis oleh para sahabat. Di antara para saha-bat penulis wahyu zaman Nabi antara lain Usman bin Affan, Ali bin Abi °alib, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin ¤abit dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Ada tiga unsur yang saling terkait dalam memelihara kesahihan Al-Qur’an pada masa Nabi yaitu hafalan dari mereka yang hafal Al-Qur’an; naskah yang ditulis untuk Nabi; naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis untuk mereka masing-masing.1
Pada masa khalifah Abu Bakar, atas prakarsa Umar bin Khatab yang prihatin terhadap banyaknya huffaz yang gugur, dibentuk panitia penyusunan mushaf Al-Qur’an diketuai oleh Zaid bin ¤abit. Prosesnya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an dari pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta dan kambing dan dari hafalan sahabat. Setelah terjilid benda tersebut dinamakan “Mushaf”. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga ia meninggal, kemudian diamanatkan kepada khalifah sesudahnya, Umar bin Khattab, dan tetap di tangan Umar selama masa pemerintahannya. Sesudah ia wafat, mushaf dibawa ke rumah Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Qur’an di masa Khalifah Usman. Pada masa Khalifah Usman, Al-Qur’an ditulis oleh satu panitia yang terdiri dari empat orang yang diketuai oleh Zaid bin ¤abit. Mushaf yang ditulis mengalami pentashihan sangat ketat oleh panitia empat yaitu melalui mushaf Abu Bakar; mushaf yang ada pada para sahabat; dan menanyakan kepada mereka tentang bagaimana dahulu Nabi Muhammad mem-bacakan ayat-ayat tersebut. Mushaf yang ditulis pada masa Usman kemudian menjadi standar kesahihan penyalinan Al-Qur’an di seluruh dunia Islam.2
Di Indonesia, jejak tashih mushaf Al-Qur’an mulai jelas tere-kam ketika Menteri Agama Muda K.H. Moh. Iljas mengeluarkan
1M.M. Azami, The History of the The Qur’an Text, From Revelation to
Compilation, (Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu sampai Kompilasi) terjemah-an (Sohirin Solihin, dkk), Jakarta: 2005, hlm. 83-85. Lihat juga Manna Khalil Al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
2Ibid.
25 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 25
Peraturan Menteri Agama (PMA No. 01 tahun 1957) yang mewa-jibkan penerbit mushaf di Indonesia memuat surat keterangan bahwa naskah Al-Qur’an telah ditashih oleh ulama-ulama yang nama dan tanda tangan mereka dibubuhkan dalam sebuah surat keterangan. Lembar tashih ditempelkan pada setiap akhir mushaf.3
Dua tahun berselang, KH. Wahib Wahab selaku Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Muda Agama Nomor 11 tahun 1959. Peraturan ini mengukuhkan keberadaan Lajnah Pentas-hihan Mushaf Al-Qur’an yang bertugas mempelajari, menyelidiki dan mengetahui mushaf yang beredar di Indonesia. PMA ini juga memperjelas bahwa penerbit mushaf Al-Qur’an harus mentashih-kan mushaf kepada Lajnah, tidak lagi kepada ulama perseorangan.
Tulisan ini mencoba meneliti pola-pola tashih mushaf Al-Qur’an di Indonesia sebelum berdirinya institusi Lajnah tahun 1959. Pola tersebut meliputi institusi pentashihannya ataupun tek-nik pentashihannya. Kajian sejarah pentashihan masih sedikit. Enang Sudrajat menulis ‘Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indone-sia’. Tulisan tersebut menguraikan pentashihan pada era Nabi Muhammad, dilanjutkan langsung ke era berdirinya Lajnah Pentas-hihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia4. Artikel ini berfokus pada pentashihan di Indonesia sebelum berdirinya LPMA tahun 2007.
Bahan primer tulisan ini yaitu beberapa mushaf kuno yang memiliki keterangan tashih; mushaf cetakan Afif Cirebon, 1933 dan 1951; Al-Qur’an Bukittinggi, 1933; Al-Qur’an cetakan Firma Salim Nabhan 1951; Al-Qur’an cetakan Tintamas 1954; dan Al-Qur’an cetakan Firma Bir & Co tahun 1956. Semuanya merupakan Al-Qur’an yang beredar sebelum 1959, tahun ketika Lajnah Pentas-hihan Mushaf Al-Qur’an resmi berdiri. Manfaat dari tulisan ini untuk memberikan gambaran peta pentahihan mushaf sebelum berdirinya lembaga pentashihan. Pola Tashih pada Mushaf Kuno
Tidak mudah menelusuri porses tashih pada mushaf kuno. Dari segi fisik mushaf Al-Qur’an, selain rentang waktu panjang, juga
3Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Himpunan Peraturan dan
Keputusan Menteri Agama RI tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta: LPMA, 2011, hlm. 7.
4Enang Sudrajat, ‘Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia, dalam Jurnal SUHUF, Vol. 6, No. 1, 2013: 53-81.
26 26 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
biasanya, kalaupun ada, lembaran “pentashihan”-nya terletak di bagian belakang yang mudah lepas dan hancur. Faktor lainnya karena pada masa lalu, tidak ada otoritas tunggal yang bertugas mengawasi produksi dan penyebaran mushaf. Masing-masing wi-layah memiliki kebijakan sendiri dalam mengontrol produk-produk keagamaan, sehingga lain daerah lain polanya.
Tashih mushaf kuno terbagi dalam dua pola besar, yaitu pola tashih saat penyalinan dan pola pasca-penyalinan. Masing-masing pola besar tersebut memiliki variasi.
[1] Pola tashih mushaf saat penyalinan. Caranya dengan meng-gunakan penyalin seorang hafiz (hafal Qur’an). Beberapa Al-Qur’an dari Keraton Sambas secara jelas memberikan gambaran bahwa mushaf ditulis oleh para hafiz (ahli kaligrafi sekaligus hafal Al-Qur’an). Sebuah mushaf ditulis oleh Haji Muhammad Anwar Al-Hafiz as-Sambasi tahun 1083 H. Mushaf lainnya ditulis oleh Haji Muhammad Asy’ari al-Hafiz tahun 1071 H (?).5 Teknik terse-but digunakan untuk meminimalisasi tingkat kesalahan pada mus-haf. Penyalin yang hafiz setidaknya lebih bisa melakukan pengo-reksian langsung atas tulisannya dibandingkan dengan yang bukan hafiz.
Cara lainnya untuk menjaga kesahihan Al-Qur’an yang dila-kukan saat penyalinan adalah dengan mencontoh pada mushaf induk. Metode ini ditemukan pada penyalinan beberapa mushaf di Keraton Ternate. Sebuah mushaf Al-Qur’an berangka tahun 1005 H ditulis oleh Afifuddin Abdul Bakri bin Abdullah bin Adhmi. Al-Qur’an tersebut menjadi pedoman bagi 8 Al-Qur’an yang disalin sesudahnya dan disebarkan ke seluruh wilayah kesultanan yang terhimpun di dalam Moluku Kie Raha.6 Mereka menyalin Al-
5Lihat juga laporan penelitian Zarkasi dan Ahmad Jaeni, “Khazanah Al-
Qur’an di Kalimantan Barat”. Jakarta: LPMA, Badan Litbang dan Diklat, 2012. Tidak terbit. Analisis berbeda dikemukakan oleh Ali Akbar, bahwa kolofon pada mushaf Sambas terutama angka tahunnya meragukan. Bisa jadi tulisan itu ditulis oleh orang lain. Lihat tulisan Ali Akbar, http://quran-nusantara.blogspot.com/ 2013/08/jangan langsung percaya-1.html. diakses senin 05 Mei 2014.
6Mushaf tersebut oleh Sultan Khairun dan Sultan Babullah dijadikan sebagai simbol supremasi kekuasaan kesultanan Moluku Kie Raha di seluruh Maluku dan Papua. Hlm. 268. Analisis berbeda tentang kolofon mushaf ini dilakukan Ali Akbar. Ia menemukan bahwa Al-Qur’an Ternate tersebut disalin oleh Haji Abdul Alim bin Abdul Hamid pada 9 Zulhijjah 1185 (14 Maret 1772 M). Lihat Ali
27 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 27
Qur’an dengan berpedoman pada sebuah mushaf yang sudah ditashih di Mekah.7
[2] Pola tashih pasca-penyalinan. Pola ini dilakukan setelah sebuah Al-Qur’an selesai disalin. Terdapat dua model tashih pasca-penyalinan, pertama adalah dengan mentashih mushaf yang sudah jadi kepada institusi keagamaan yang dianggap lebih otoritatif. Dari sekian banyak penelitian tentang Al-Qur’an kuno yang sudah dila-kukan, jarang ditemukan informasi mushaf yang ditashihkan. Tidak adanya kewajiban tashih serta mencantumkan lembar pengesahan mushaf, menjadi faktor jarang ditemukannya mushaf bertanda tashih. Namun begitu, keberadaan pola ini bukan berarti tidak ada sama sekali di Indonesia.
Sebuah mushaf kuno di Majene, ditulis pada Jumat 27 Rajab 1248 H (20 Desember 1832) oleh H Ahmad bin Syeikh al-Katib Umar, pada bagian awalnya terdapat catatan bahwa Qur’an ini sudah ditashih di Mekah.8 Adanya prakarsa untuk mentashihkan mushaf ke Mekah menunjukkan semangat kaum muslim di Indonesia dalam menjaga kesahihan Al-Qur’an. Berikut transkripsi kolofon mushaf Majene (Gambar 1):
Gambar 1. Lembar tashih mushaf Majene yang dilakukan di Makkah. (Foto: Ali Akbar)
Akbar, “Mushaf Sultan Ternate Tertua di Nusantara: Menelaah Ulang Kolofon” dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 08, No. 2, Desember 2010, 283-296.
7Fadhal AR Bafadhal, Khazanah Al-Qur’an Kuno Nusantara, Jakarta: Puslit-
bang Lektur Kehidupan Agama, 2003, hlm. 270. 8 Ali Akbar, “Laporan Penelitian Mushaf Kuno Sulawesi Barat”, Jakarta:
LPMA Badan Litbang dan Diklat, 2012.
28 28 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
Wa kāna al-farāg min ta¥¡īli ta¡¥ī¥ī ¥urūf hā©ā al-Mu¡¥af al-mubārak yawma a£-£ulu£ ba‘da ¡alāti a§-§uhri bi makkata al-musyarrafati. Yā ikhwānī ra¥imakumullahu qad ¡a¥a¥tu ¥urūf hā©ā al-mu¡haf ‘alā qadri mā yassaranī Allāh tā’ālā al-la§ī ra`aituhu gala¯an ¡a¥a¥tuhu, wa al-la«ī mā ra’aituhu min al-galati, in wajadtum syai’an min al-¥urūf ka«ālika falā…. ‘alayya. Anna al-gaiba lā ya‘lamuhu illa Allāh. Wa Allah ‘alam bi a¡-¡awāb wa ilayhi al-marji‘. Amīn Amin. Ya ikhwānī in wajadtum fi ha©ā al-Mu¡haf gala¯an min al-¥urūf wa kalimatin fasāmihūni ra¥imakumullāh rabbanā sub¥anahu wa ta‘āla wa in qara’tum wa wajadtum ¡a¥īhan fasykurullāha ta‘āla, wal ¥amdulillāhi rabbi al-ālamīn.9
Berdasarkan tashih yang penulis lakukan terhadap sampel beberapa juz dari Qur’an Majene, tidak ditemukan kesalahan jali. Bahkan kesalahan khafi juga sangat minim, seperti salah penem-patan tanda ayat. Koreksi kesalahan dilakukan dengan memberi warna putih kemudian ditimpakan di atasnya ayat yang benar, se-perti terlihat pada surah al-Baqarah ayat 62.
Keberadaan mushaf Majene yang diujisahihkan ke Makkah, memunculkan dugaan bahwa di tempat lain di Indonesia terdapat pula mushaf yang melalui tashih serupa. Hanya saja, keterangan tashihnya tidak dituangkan secara tersurat. Mushaf lainya yaitu sebuah Mushaf di Keraton Ternate. Makkah menjadi tujuan utama untuk tashih. Hal ini dimungkinkan karena belum adanya otoritas keagamaan yang menyatukan kesultanan-kesultanan di Nusantara.
Model kedua pola tashih pasca-penyalinan yaitu tashih sepan-jang hayat. Pola ini untuk mushaf yang diturunkan secara turun-temurun dan generasi ke generasi. Biasanya terjadi pada mushaf yang disalin oleh masyarakat umum. Prosesnya, setiap kali mene-
9Artinya: “Dan telah selesai ujisahih terhadap huruf-huruf yang ada pada
mushaf Al-Qur’an yang mulia ini pada hari Selasa bakda salat Zuhur di Mekah al-Musyarrafah. Wahai saudaraku kami telah menguji sahih mushaf ini atas anugerah Allah swt. Jika saya melihat kesalahan, saya langsung perbaiki. Adapun yang luput dari pandangan mata saya, jika saudara menemukan kesalahan, maka jangan timpakan kepadaku. Sesunguhnya perkara gaib hanya Allah semata Yang Tahu. Hanya Allah yang Mahatahu tentang kebenaran. Dan kepadanya tempar kembali. Saudaraku, jika kalian menemukan kesalahan huruf atau kalimat dalam mushaf ini, maka mohon dimaafkan. Semoga Allah Tuhan Kami merahmati kalian semuanya. Jika kalian menemukan kebenaran maka ucapkanlah syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.”
29 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 29
mukan kesalahan pada naskah Qur’an, pemiliknya melakukan perbaikan sendiri dengan mencoretnya. Kemudian memberikan koreksian pada bagian atas dari ayat yang salah atau pada pinggir halaman jika koreksiannya terlalu panjang. Ketika mushaf tersebut diwariskan, generasi berikutnya juga melakukan hal yang sama ketika menemukan kesalahan. Selama masih ditemukan kesalahan, selama itu pula tashih masih berlangsung. Sampai mushaf Al-Qur’an tersebut sudah tidak layak baca (rusak berat) atau tidak ditemukan lagi kesalahan.
Gambar 2. Mushaf Haji Rawi Batang-batang Sumenep
Gambar 3. Mushaf Al-Qur’an koleksi Bapak H. Zaeni, Sumenep.
Gambar 4. Mushaf Koleksi H. Muhammad Faisol, Ambunten Sumenep.
Berikut beberapa contoh koreksian pada kata yang salah pada mushaf kuno yang berasal dari Madura. Pada gambar 2 kata ā§īm
30 30 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
kurang huruf ‘ain. Koreksian ditulis pada bagian bawah kata yang salah dengan tinta hitam. Pada gambar 3 koreksian terhadap kata yang hilang (al-bayyināt) ditulis pada bagian luar bidang teks dengan menggunakan tinta merah. Pada gambar 4 merupakan koreksian terhadap kata zakariya, yang seharusnya tidak menggu-nakan huruf hamzah. Pada model kedua tashih pasca-penyalinan tidak ada institusinya. Tashih hanya dilakukan pemilik naskah, guru ngaji, atau individu yang memiliki kecukupan ilmu agama. Pola Tashih Mushaf Cetakan sebelum Tahun 1959
Dibandingkan dengan mushaf tulisan tangan, pola tashih pada mushaf cetakan lebih mudah ditelusuri. Hal ini disebabkan jarak waktu yang masih relatif dekat, juga keberadaan mushaf yang banyak serta terbaca dengan jelas. Mushaf ‘Bombay’ adalah salah satu mushaf pelopor yang “bertanda tashih”. Jenis mushaf ini sudah mulai banyak beredar di Indonesia pada akhir abad ke-19 Masehi. Mushaf ini juga yang diduga kuat sebagai induk dari varian-varian mushaf cetakan yang beredar di Indonesia pada awal abad ke-20. Sebuah Al-Qur’an cetakan Bombay tahun 1885 milik Abdul Hakim Cirebon mencantumkan nama-nama para pentashih yaitu Sayyid Hasan Qodiri, Sayid Qamaruddin, Haji Muhammad Sammah, al-Hafiz Abdullah, Mawli Muhammad, Sayid Wadi Muhammad, dan Sayid Hasan al-Bagdadi.10
Dari sejumlah mushaf yang terbit di Indonesia sebelum tahun 1959, tashih mushaf cetakan dapat dikelompokkan dalam dua pola. Pertama, tashih kepada institusi keagamaan di wilayah setempat. Hal ini terjadi karena Indonesia saat itu belum memiliki lembaga induk tempat tashih Al-Qur’an seperti sekarang. Beberapa contoh di antaranya yaitu sebuah mushaf Al-Qur’an dicetak di Bukittinggi tahun 1933 ditashih oleh Mahkamah Syari’ah Sumatra Tengah yang, saat itu, dikepalai oleh Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli. Pada lembar ‘sahih’ yang termuat di halaman belakang diterangkan bah-wa mushaf tersebut ditashih dengan berpedoman mushaf Usmani (rasm Usmani?).11
10Abdul Hakim, “Al-Qur’an cetak di Indonesia, Tinjauan Kronologis
Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20”, Suhuf, Vol. 5 No. 2, 2012, 231-254
11Ulasan tentang mushaf Al-Qur’an cetakan di Indonesia bisa dilihat di Abdul Hakim, “Al-Qur’an cetak di Indonesia, Tinjauan Kronologis Pertengahan
31 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 31
Mushaf Al-Qur’an lainnya yang ditashih melalui lembaga ke-agamaan adalah Al-Qur’an terbitan Bir & Co tahun 1956. Lembaga tersebut adalah Jam’iyyah Qurra’ wal Huffadz (JQH). Menjabat sebagai ketua JQH saat itu Ahmad Nahrowi dan Muhammad Manshur bin Hasani selaku sekretarisnya. Lembar legalitas meng-gunakan bahasa Arab.
Ba‘da mā qara’a wa fa¥a£a al-‘ulama al-mu¡¥¥i¥īn li jam‘iyatul qurro wa al-¦uffa§ al-qur’ān alla©ī tastawriduhu syirkatu Bir & Co fanajidu al-gil§ata al-fa§ī‘ah al-wa¥īdah allatī ta‘ummu al-ummah al-islāmiyyah al-Indunisiyyah ma‘rifatuhā wa hiya inqilabu al-wa«‘i fī surah al-kahfi khāliyan inda ©ālika al-mu¡¥af inda ¯ab‘i a£-£āniyyati. Wa amma ba‘«u al-gil§āt al-khafifah fi ¯ab‘i kamā tūjadu ‘ādatun fī al-ma¡ahifi al-ukhro, al¥aqnā £awābahā fī nihāyati al-mu¡¥af. i©ā kāna tilka al-gil§āt tu¡a¥¥a¥u qabla al-qirā’ati falā māni’a lanā fī ta¡rīhi al-i©in li bay‘i tilka al-ma¡āhif ‘ala ¯ab’ī al-Jadīdah hā©ihī li tahlī¡i al-maqādīr allatī udkhila ilā Indunisiyya. Tahrīran fī Jākarta 18/04/1956 Markaz Jam‘iyyahal-Qurra’ wa al-¦uffa§ Ar-ra‘īs: A¥mad Na¥rawi As-sikrītīr: Mu¥ammad Man¡ūr bin ¦usaini.12
Transkripsi tashih di atas menggambarkan kepada kita bahwa Penerbit Firma Bir & Company bertindak sebagai importir Al-Qur’an. Surat tashih tersebut sekaligus bermakna ganda, yaitu seba-gai legalitas kesahihan Al-Qur’an yang mau masuk sekaligus izin untuk mengedarkan mushaf Al-Qur’an di Indonesia.
Pola kedua adalah tashih kepada individu-individu yang meru-pakan tokoh dalam bidang Al-Qur’an (hafiz). Salah satu mushaf Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20” dalam Suhuf, Vol. 5 No. 2, 2012, 231—254.
12Artinya: “Setelah para ulama pentashih di Jamiyatul Qurra dan Hufaz
membaca dan mengoreksi Al-Qur’an yang dimintakan oleh Penerbit Bir & Co, maka kami menemukan kesalahan (jali) satu-satunya yaitu kesalahan sususan surah al-Kahfi. Adapun kesalahan kecil yang terdapat dalam mushaf kami lampirkan ralatnya pada bagian akhir mushaf. Jika kesalahan (jali) tersebut terkoreksi sebelum dibaca, maka kami tidak berhak memberikan izin penjualan mushaf Al-Qur’an tersebut pada cetakan baru. Hal ini dilakukan untuk mengu-rangi kesalahan pada mushaf yang masuk ke Indonesia Disahkan di Jakarta 18/04/1956 Markaz Jamiyatul Qurro dan Hufaz Ketua: Ahmad Nahrawi Sekretaris: Muhammad Mansur bin Husaini”
32 32 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
Al-Qur’an yang menggunakan pola ini adalah mushaf terbitan Maktabah Afif, Cirebon, tahun 1933. Mushaf ini mencantumkan pernyataan dari Kyai Badawi dan Kyai Muhammad Usman, bahwa mereka telah menelaah mushaf tersebut. Keduanya adalah ulama Al-Qur’an pimpinan Pesantren Kaliwungu pada masanya. Kyai Badawi juga teman sekaligus murid dari Kyai Munawwir Krapyak. Lembar tashih menggunakan aksara pegon.13
Pada Al-Qur’an terbitan Maktabah Afif, Cirebon tahun 1951, ada empat nama pentashih tambahan yang pada Al-Qur’an tahun 1933 tidak ada. Semua nama keenam pentashih mushaf Afif Cirebon yaitu K.H. Muhammad Usman, K.H. Ahmad Badawi, K.H. Reden Asnawi, K.H. Ridwan, K.H. Abdullah, dan K.H. Mahmud Rais.
Mushaf Al-Qur’an lainnya yaitu terbitan Salim Nabhan, Sura-baya tahun 1951 ditashih oleh sebuah tim yang terdiri dari enam ulama Al-Qur’an (lihat gambar pada lampiran). Berikut transkrip-sinya:
Bismilla¥irahmanira¥īm Wa ba‘du faqod tamma bi ‘awnillahi ta‘āla ¯ab‘u ha©ā al-mus¥af asy-syarif, bi sūrabayā indunīsī. Muwāfiqan fī al-Kha¯¯ rasmi mu¡¥af amirul mu’minīn ©īnnūraini khulafā’ūrrāsyidīn: sayyidunā ‘ū£mān bin ‘Affān ra«iyallahu ‘anhu ‘ala mā ©akarahū al-imām Abū ‘Amr ad-dānī fi Muqni’īhi wa ©ālika ba‘da «ubi¯a wa ta¡¥ī¥i afā«ul Qurrā’ wa hum: al-ustā©© ¦asan A¥mad Bangil, Kyai al-¦āj Muhammad A¥san Jamfas Kediri, Kyai al-¦āj Mu¥ammad ‘Adlān Cukir Jombang, Kyai al-¦āj ‘Abdullah bin Yāsīn Fasuruan, al-Ustā© Sālim bin ‘Aqīl Surabaya wa al-ustā© Abdullah Jalal al-Makki surabaya. Wa ‘ala ta¡¥ī¥i hā’ulā’ al-afa«il wāfaqa ‘alaihi wazīru syu’ūni ad-dīniyyati, ¡ā¥ibul ma’ali al-ustā© Abdul Wahid Hasyim ‘Asy’ari. ¥asbi kitābihil karīm mu¥arrar 22 September sanah 1951 Raqm A/7/13125.14
13Ulasan tentang Al-Qur’an terbitan Afif Cirebon lihat Abdu Hakim “Al-
Qur’an cetak di Indonesia…” Suhuf, Vol. 5 No. 2, 2012, 231—254. 14
Artinya: “Bismillāhirrahmanirra¥īm Wa ba‘du, telah selesai berkat rahmat Allah pencetakan Al-Qur’an ini di Surabaya Indonesia. Sesuai dengan khat rasm mushaf amirul mu’minin zinnurain salah seorang khulafah rasyidin: Sayyidina Usman bin Affan ra, seperti yang tertuang dalam kitab Al-Muqni’karya Imam Abu Amr ad-Dāni. Hal tersebut setelah dicocokkan dan ditashih oleh ulama qurro’ yaitu: Ustad Ahmad Bangil, KH Muhammad Ihsan Jampes Kediri, KH Muhammad Adlan Cukir Jombang, KH Abdullah bin Yasin Pasuruan, Ustadz Salim bin Aqil Surabaya dan ustadz Abdullah Jalal al-Makki, Surabaya.
33 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 33
Berdasarkan lembar tashihnya dapat diketahui para pentashih Al-Qur’an terbitan Salim Nabhan, Surabaya tersebut yaitu Ustadz Ahmad Hasan Bangil, K.H. Muhammad Ihsan Jampes Kediri, K.H. Muhammad ‘Adlan Cukir Jombang, K.H. Abdullah bin Yasin Pasu-ruan, Ustadz Salim bin ‘Aqil Surabaya dan Ustadz Abdullah Jalal.
Tiga tahun setelah 1951, penerbit Tintamas mencetak Al-Qur’an dengan tashih oleh Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) dan Muhammad Zain Jambek. Dalam lembar tashih ada keterangan tambahan tentang beberapa kalimat yang musykil. Berikut alih aksara lembar tashih Al-Qur’an terbitan Tintamas tahun 1954, menggunakan aksara Jawi:
Kalimatu mu¡a¥i¥ Bismiallahirrahmānirrahīm Al¥amdulillah wa a¡-¡alātu wa as-salām ‘alā rasūlillāhi wa ‘alā Alihi wa ¡a¥bihi wa man wālāhu. Amma ba’du. Maka telah selesai pekerjaan mentashihkan mushaf ini di Jakarta Raya pada malam jum’ah tanggal 17 Romadhon 1373 dengan menggunakan sebagai bahan pembanding mushaf-mushaf cetakan dalam dan luar negeri. Beberapa tanda, seperti alif rasm yang mungkin mengganggu bacaan seperti alif pada لن ندعوا atau yang tidak perlu seperti رسول یتلوا yang terdapat pada umumnya mushaf sengaja kami hilangkan. Dan pada bagian yang terdapat perlainan bacaan diantara mushaf-mushaf itu seperti antara ضعف dan ضعف pada surah ar-Rūm ayat 54 kami berpegang pada keterangan dalam tafsir-tafsir yang kenamaan (mu’tabaroh) Dalam usaha yang membawa kesempurnaan mengenai penerbitan mushaf ini kami ucapkan syukur dan puji kepada Allah. Dan dimana terdapat kekurangan karena kekhilafan kami mohonkan ampun kepadanya dengan menanti teguran dan peringatan yang langsung kepada Kami dari para ahli dan semua orang yang berniat baik dan berhati ikhlas yang akan kami sambut dengan ucapan banyak terima kasih. Wa as-salām. Al-¦ajj Abdul Malik Karim Amrullah Muhammad Zein Jambek
Pada lembar tashih Tintamas 1954 juga diterangkan tentang bacaan musykil yang perlu disederhanakan atau dihilangkan. Ter-utama bacaan لن ندعوا dan رسول یتلوا dengan menghilangkan huruf alif. Adapun perbedaan bacaan diselesaikan dengan memberi kete-
Berdasarkan tashihan para ulama tersebut di atas, kemudian disetujui oleh Menteri Agama Abdul Wahid Hasyim Asy’ari. Tertanggal 22 September tahun 1951 Nomor A/7/13125
34 34 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
rangan yang merujuk pada kitab-kitab tafsir kenamaan (mu’taba-rah). Contohnya kalimat ضعف . Simpulan
Seperti diuraikan pada pembahasan, tashih Al-Qur’an merupa-kan salah satu filter untuk tetap menjaga kemurnian Al-Qur’an. Tugas ini sangat historis, ada sejak zaman awal Al-Qur’an diwah-yukan, masa Al-Qur’an tulis tangan dan cetak modern. Di Indonesia hanya terdapat dua era yaitu Al-Qur’an tulis tangan dan Al-Qur’an cetak. Data-data yang ada menunjukkan bahwa Al-Qur’an tulis tangan yang tersebar di Indonesia juga melalui tashih. Terdapat dua pola tashih yaitu pola saat penyalinan dan pola tashih pascapenyalinan. Adapun tashih mushaf Al-Qur’an cetakan dilaku-kan melalui tim yang terdiri dari para ulama Al-Qur’an. Biasanya terdiri atas enam orang. Cara kedua, yaitu dengan menggandeng lembaga-lembaga keagamaan lokal yang ada saat itu. Studi ini menemukan dua lembaga, yaitu Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah dan Jamiyyah Qurra’ wal Huffaz, Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena saat itu belum ada lembaga pemerintah resmi yang menangani tashih Al-Qur’an di Indonesia.
Dalam perkembangan terkini, khususnya setelah berdirinya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMA), legalitas kesahih-an yang diuraikan di atas tidak lagi diakui. Sebuah Al-Qur’an boleh beredar, jika sudah ditashih di LPMA sebagai otoritas tashih tingkat nasional. Selain itu, tidak adanya ‘tashih sepanjang hayat’ mela-hirkan aturan yang tidak tertulis. Aturan ini salah satunya ‘jika menemukan kesalahan pada mushaf, dianjurkan untuk melaporkan kepada penerbit, toko, atau institusi berwewang. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, yaitu membakar mushaf yang sudah dicetak jika ditemukan banyak kesalahan.[] Wallāhu a’lam bi¡-¡awāb.
35 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 35
Daftar Bacaan Al-Qur’an
Manuskrip Al-Qur’an Kuno milik keluarga Bapak H. Sufyan Mubarok Majene Sul-Bar
Manuskrip Al-Qur’an Kuno milik keluarga Bapak H Zaeni, Sumenep
Manuskrip Al-Qur’an Kuno milik keluarga Bapak H Rawi Sumenep
Manuskrip Al-Qur’an Kuno milik keluarga Bapak H Muhammad Faisol, Sumenep
Mushaf Al-Qur’an cetakan Maktabah Afif Cirebon, 1933 dan 1951;
Mushaf Al-Qur’an cetakan Bukittinggi, 1933;
Mushaf Al-Qur’an cetakan Firma Salim Nabhan Surabaya, 1951;
Mushaf Al-Qur’an cetakan Firma Bir & Co Jakarta, 1956;
Mushaf Al-Qur’an cetakan Tintamas Jakarta, 1954.
Buku
Abdurohim, Acep Iim., Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, Bandung: Diponegoro, 2012.
Akbar, Ali, Delapan Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat: Beberapa Ciri Khas, Hasil Penelitian pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2012. Belum dipublikasikan.
Akbar, Ali, “Mushaf Sultan Ternate Tertua di Nusantara: Menelaah Ulang Kolofon” dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 08, No. 2, Desember 2010, 283-296.
Al-Qattah, Manna Khalil, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
Bafadhal, Fadhal AR, dan Rosehan Anwar, Khazanah Al-Qur’an Kuno Nusan-tara, Jakarta: Puslitbang Lektur Kehidupan Agama, 2005.
Azami, MM., The History of the The Qur’an Text, From Revelation to Compilation, (Sejarah Teks Al-Qur’an dari Wahyu sampai Kompilasi) terjemahan (Sohirin Solihin, dkk), Jakarta: 2005.
Ensiklopedi Islam Jld. III lema “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an”, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, hlm. 90-91.
Fathurahman, Oman, Filologi dan Islam Indonesia, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010.
36 36 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
Hakim, Abdul, Al-Qur’an Cetak di Indonesia: Tinjauan Kronologis Petengahan
Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20 dalam Jurnal Suhuf, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 231-254.
Hakim, Abdul, Laporan Penelitian Mushaf Kuno Sumenep Jawa Timur, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an tahun 2012.
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Himpunan Peraturan dan Keputusan Menteri Agama RI tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta: LPMA, 2011.
Sudrajat, Enang, ‘Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia’ dalam Jurnal Suhuf, Vol. 6. No. 1, 2013: 59-81.
Watsoen, Inggrid, Ulumul Qur’an Zaman Kita, Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur’an, Jakarta:Serambi, 2013.
Zarkasy & Jaeni, Laporan Penelitian Mushaf Kuno Kalimantan Barat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an tahun 2012.
37 Pola Tashih Mushaf Al-Qur’an di Indonesia — Abdul Hakim 37
Lampiran
Gambar 5. Tanda sahih mushaf terbitan Tintamas Jakarta, tahun 1954. Penanggung Jawab yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA dan Muhammad Zain Jambek.
Gambar 6. Lembar tashih mushaf Al-Qur’an terbitan Bir & Co, Jakarta tahun 1956. Ditashih oleh tim dari Jam’iyatul Qurra’ wal Huffad.
38 38 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
Gambar 7. Tanda Tashih Mushaf terbitan Firma Salim Nabhan Surabaya, 1951.
Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an Telaah Metodologi atas Buku Judaism and Islam
Abraham Geiger and the Study of the Qur'an Analyzing the Methodology of the ‘Judaism and Islam’ Lenni Lestari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta [email protected] Naskah diterima: 12-12-2013; direvisi: 12-04-2014; disetujui: 15-05-14. Abstrak Salah satu hasil penelitian orientalis yang cukup “menggelitik” keimanan para sarjana Muslim saat ini adalah Al-Qur’an yang dianggap sebagai imitasi ajaran agama Yahudi. Statemen ini muncul dari salah seorang orientalis beragama Yahudi, yaitu Abraham Geiger. Tulisan ini akan membahas, pertama, latar bela-kang pemikiran Abraham Geiger, dan kedua, pemikiran Geiger tentang hal-hal yang diadopsi Nabi Muhammad dari agama Yahudi, dan ketiga, tanggapan mengenai penelitian Geiger terhadap Al-Qur’an.
Kata kunci: Abraham Geiger, historis-kritis, Muhammad, Al-Qur’an, Yahu-di.
Abstract One of the result of orientalist research that influences Muslim scholars’s faith today is Al-Qur’an as imitation of Judaism. This statement appears from Abraham Geiger, a Judaism orientalist. This writing tries to explain the histo-rical background of Abraham Geiger. Then, the writer explores about the adop-ted things by Prophet Muhammad from Judaism in Geiger’s view and tries to catch the response and reaction of Islamic scholars about Geiger’s research.
Keywords: Abraham Geiger, historical-critical, Muhammad, Al-Qur’an, Judaism.
40 40 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
Pendahuluan Secara umum, ketertarikan para sarjana orientalis, khususnya
terhadap studi Al-Qur’an, sudah dimulai sejak abad ke-12 dan terus berlangsung hingga sekarang. Kajian yang intens dalam durasi yang panjang tersebut akhirnya memunculkan banyak karya, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Dalam hal ini, Fazlur Rahman dalam karyanya The Major Themes of the Quran menyebutkan ada tiga tipe karya-karya orientalis terhadap Al-Qur’an.
Pertama, karya-karya orientalis yang ingin membuktikan keterpengaruhan Al-Qur’an oleh tradisi Yahudi dan Kristen. Kedua, karya-karya orientalis yang menekankan pada pembahasan sejarah dan kronologi Al-Qur’an. Ketiga, karya-karya orientalis yang mem-bahas tema-tema tertentu dalam Al-Qur’an.1
Dari ketiga tipe tersebut, maka Abraham Geiger termasuk pada tipe pertama, yaitu orientalis yang ingin membuktikan pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen terhadap Al-Qur’an. Dengan kata lain, Geiger ingin mengatakan bahwa Al-Qur’an bukanlah suatu yang transenden, karena “terbukti” di dalamnya terdapat kombinasi ber-bagai tradisi, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun Jahiliyah. Menu-rutnya, Al-Qur’an hanyalah refleksi Muhammad tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu (simplikasi Bible) dan kare-nanya bersifat kultural dan tidak transenden.2 Pendekatan yang dilakukan Abraham Geiger ini disebut pendekatan historis-kritis.3
1Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur’an, terj, Anas Mahyudin, Ban-
dung: Pustaka, 1996, hlm. xi. 2Ahmad Farhan, Orientalis Al-Qur’an, Studi Pemikiran Abraham Geiger,
dalam buku Orientalisme Al-Qur’an dan Hadis, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007, hlm. 64.
3 Historis atau historisme muncul pada abad ke-19. Tokoh utamanya adalah Leopold von Ranke, seorang sejarawan dari Jerman. Historisme memandang suatu entitas, baik itu institusi, nilai-nilai maupun agama berasal dari lingkungan fisik, sosiokultural dan sosio-religius tempat entitas itu muncul. Penjelasan mengenai suatu entitas sudah cukup melalui penemuan asal-usulnya dan hakikat seluruhnya dipahami dari perkembangannya. James K, Feibleman, “Historism,” dalam Dagobert D, Runes (ed) Dictionary of Philosophy, Totawa: Littlefield, 1976, hlm. 127, Sebagaimana dikutip oleh Yudhi R, Haryono, dkk, Al-Qur’an, Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan, Bekasi: Gugus Press, 2002, hlm. 85. Munculnya historisme menurut Fuck-Frankfurt mendorong kecenderungan dalam studi Al-Qur’an di Barat yang mengasalkan Al-Qur’an dan Islam dari kitab suci dan tradisi Yahudi dan Kristen. Von Johann Fuck-Frankfurt,
41 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 41
Menurut Sahiron Syamsuddin, ada tiga pendekatan yang dite-rapkan orientalis dalam studi Al-Quran, yaitu pendekatan historis-kritis, interpretatif penafsiran,4 dan deskriptif-sosioantropologis (fenomenologis).5 Menurut Marshall, yang dimaksud dengan pen-dekatan historis-kritis adalah kajian terhadap kandungan sebuah narasi (cerita), dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi sehing-ga hal tersebut disinggung dalam sebuah tulisan. Kritik historis meliputi tiga hal, yaitu bentuk, redaksi, dan sumber.6
Berdasarkan pembagian ini, maka Abraham Geiger termasuk kelompok yang pertama, yang mengkaji situasi dan kondisi ma-syarakat Arab yang dianggap menjadi sumber isi Al-Qur’an. Pende-katan ini menjadi masalah ketika diterapkan ke dalam teks Al-Qur’an. Bagi mereka yang tidak sepakat, mengatakan bahwa tidak mudah menerapkan metode ini ke dalam kajian kitab suci. Bagi mereka yang sepakat, mengatakan bahwa ada banyak problem krusial yang harus dicari jawabannya melalui metode ini.7
Tulisan ini akan membahas tentang latar belakang kehidupan Abraham Geiger, sehingga ia meyakini bahwa Al-Qur’an adalah imitasi dari Yahudi, selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai pemikiran Geiger tentang hal-hal yang diadopsi Nabi Muhammad dari agama Yahudi. Di akhir pembahasan, penulis akan memotret bagaimana tanggapan para sarjana terhadap penelitian Geiger tersebut. Mengenal Abraham Geiger
Sebelum berbicara tentang Abraham Geiger, penulis kemu-kakan terlebih dahulu tentang agama Yahudi, sebagai agama yang dianut Abraham Geiger. Agama Yahudi yang sering diartikan de-
“Die Originalitat des Arabischen Propheten,”, hlm. 510, Yudhi R, Haryono, dkk, Al-Qur’an, Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan, hlm. 86.
4Pendekatan interpretatif adalah melakukan penafsiran atau analisis terhadap teks melalui metode tertentu, Ada 3 metodenya, yaitu; filologi, sastra, dan linguistik.
5Pendekatan fenomenologi adalah mendeskripsikan resepsi Al-Qur’an yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
6Marshall, Historical Criticism, hlm. 126, Sebagaimana dikutip oleh Sahiron Syamsuddin dalam artikel, “Contemporary Western Approaches to the Quran”, yang disampaikan dalam seminar Internasional di UIN Sunan Kalijaga, 24 Februari 2013.
7Ibid.
42 42 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
ngan istilah Judaism, dalam Jewish Encyclopedia diartikan sebagai “Suatu bentuk kehidupan yang berdasarkan kepada kebapakan Tuhan serta wahyu-Nya”. Istilah Judaism mengandung pengertian tentang eksistensi seperangkat kepercayaan dan kebiasaan yang membentuk Judaism dan menciptakan ketaatan yang membuat seseorang menjadi Yahudi.8 Sementara itu, bagi orang Islam, Yahu-di cenderung diartikan sebagai agama yang diturunkan Tuhan kepa-da Nabi Musa sebagai Nabi dengan Taurat sebagai kitab sucinya.9 Ada beberapa kitab yang dianggap suci oleh agama Yahudi seperti Torah, Talmud, Septuaginta,10 dan Pentateuch. Dari kitab-kitab ini, yang menjadi kitab inti adalah Taurat atau The Old Testament.11
Salah satu orientalis yang mengatakan bahwa Al-Qur’an dipe-ngaruhi agama Yahudi adalah Abraham Geiger (1810-1874). Ia adalah seorang intelektual, Rabbi, dan tokoh sekaligus pendiri Yahudi Liberal di Jerman. Ia terlahir dalam keluarga dan ling-kungan hidup ortodoks yang keras.12 Ia memulai karirnya sebagai seorang Rabbi (guru yang menguasai keseluruhan 613 mitzvot (hukum agama Yahudi) pada tahun 1833. Ia mengabdi di kota Wiesbaden, Breslau, Frankfurt dan Berlin secara simultan.13
Geiger mengikuti kompetisi masuk ke Universitas Bonn tahun 1832 dengan menulis sebuah esai dalam bahasa Latin. Essainya diseleksi Prof. B. F. Freutag dari fakultas Oriental Studies, Universitas Bonn. Hasilnya, Geiger menang dan mendapat hadiah
8Ismail Razy al-Faruqi, Trilogi Tiga Agama Besar, Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997, hlm. 43, Yudhi R, Haryono, dkk, Al-Qur’an, Buku yang Menye-satkan dan Buku yang Mencerahkan, hlm. 59.
9Burhanuddin Daya, Agama Yahudi, Yogyakarta: PT Bagus Arafah, 1982, hlm. 2.
10Septuaginta adalah terjemahan kitab-kitab Perjanjian Lama atau Tanakh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang artinya adalah 70 dan sering ditulis sebagai "LXX" karena konon disusun 70 orang Yahudi. Apa itu Tetragramaton dan Septuaginta?. Written by Lukas. http://www.alfa-omega.or.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=93. Akses 20 Mei 2014.
11Mujahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55, Yudhi R, Haryono, dkk, Al-Qur’an, Buku yang Menye-satkan dan Buku yang Mencerahkan, hlm. 59.
12Abraham Geiger, Judaism and Islam, New York: Publishing House, 1989, hlm. vii-ix.
13Ibid, hlm. ix.
43 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 43
dari hasil tulisannya. Padahal saat itu usianya baru 22 tahun.14 Pada tahun 1833, essai tersebut dipublikasikan dalam bahasa
Jerman dengan judul “Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?”, Apa yang telah Muhammad Pinjam dari Yahudi?. Dalam tulisan tersebut, Geiger menyimpulkan kosa kata Ibrani cukup berpengaruh terhadap Al-Qur’an. Di antara kata-kata terse-but yaitu, tābūt, taurāt, jannatu ‘adn, jahannam, a¥bār, darasa, rabbānī, sabt, tāgūt, furqān, mā’ūn, ma£ānī, dan malakūt.15
Essai ini merupakan bagian dari bukunya yang berjudul Judaism and Islam. Buku ini terdiri dari 2 bagian pembahasan. Bagian awal buku ini menjelaskan tentang latar belakang pemikir-annya tentang Al-Qur’an dan Islam. Sedangkan 2/3 sisanya, men-jelaskan tentang hal-hal yang menurut Geiger diadopsi nabi Muhammad dari agama Yahudi, sebagaimana tertuang dalam essainya yang berjudul “Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?”.
Geiger menekuni Bibel, Talmud, dan sejarah abad Pertengah-an. Selain itu, ia juga mendalami adat dan pengetahuan orang Yahudi, filologi, sejarah, kesusastraan, dan filsafat.16 Ia sering di-undang dalam berbagai aktivitas akademik dan komunal. Ia juga pernah menerbitkan sebuah jurnal yang dikelola secara pribadi, menulis berbagai karya, dan mengajar di masa-masa akhir hidupnya hingga ajal menjemputnya pada tahun 1874 di Berlin. Dalam komunitas Yahudi, ia dikenang sebagai tokoh penggerak beberapa konferensi ajaran Yahudi dan juga diskusi-diskusi tentang problem kontemporer agama Yahudi.17
Pemikiran Abraham Geiger Terhadap Al-Qur’an Dalam tulisannya, Geiger menyebutkan ada 3 masalah utama
yang diadopsi Nabi Muhammad dari tradisi Yahudi, yaitu;
a. Beberapa Kosakata Al-Qur’an yang Berasal dari Tradisi Yahudi Menurut Geiger, ada 14 kosa kata Al-Qur’an18 yang diadopsi
14Ibid, hlm. viii. 15Ibid, hlm. 41. 16Ibid, hlm. viii. 17Ibid, hlm. ix. 18Dari 14 kosa kata yang dikaji oleh Geiger, 6 di antaranya juga pernah
dikaji oleh as-Suyū¯ī dalam kitab al-Muhazzab fī Mā Waqa‘a fī Al-Qur’ān min al-Mu’arrab. as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Quran, hlm. 193.
44 44 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
dari bahasa Ibrani, di antaranya; sakīnah, tāgūt,19 furqān, mā’ūn, ma£ānī, malakūt,20 darasa,21 tābūt, Jannatu ‘adn,22 taurāt, jahan-nam,23 rabbānī,24 sabt, dan a¥bār.
Tābūt Geiger mengatakan bahwa akhiran “ut” dalam kata ini meru-
pakan bukti bahwa itu bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Ibrani asli yang berkenaan dengan ajaran Yahudi. Kata tābūt dalam ajaran Yahudi ada pada dua tempat. Salah satunya pada kisah Nabi Musa yang diletakkan ibunya ke dalam perahu.
Jannatu ‘Adn Kata ’adn dalam bahasa Arab bermakna kesenangan atau ke-
bahagiaan (nama surga). Menurut Geiger, pada dasarnya kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama Yahudi, “’adn” adalah nama dari suatu daerah yang telah dihuni oleh orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Bagian daerah yang mereka tempati itu berupa kebun pohon yang biasa disebut dalam Injil dengan “Taman Eden”. Dalam perkembangannya, arti kata ini tidak lagi mewakili nama suatu tempat, tetapi digunakan untuk menunjuk arti surga, meskipun dalam tataran praksisnya bangsa Yahudi masih meng-gunakan Taman Eden sebagai sebuah tempat juga.
Jahannam Kata ini juga diklaim berasal dari Yahudi. Kata “Jahannam”
19Menurut as-Suyū¯ī, kata ini berasal dari bahasa Habasyah, yang artinya
dukun, Lihat as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm. 198. 20Abu Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Wasithi berkata di
dalam al-Irsyad, “Maknanya adalah malaikat-malaikat menurut bahasa Nabathea.” as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm. 199.
21Maknanya adalah kamu saling membacakan, menurut umat Yahudi as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm. 197.
22Dalam penafsiran Juwaibir bahwa kata itu berasal dari bahasa Romawi. as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm.198.
23Ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa asing. Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Persia dan bahasa Ibrani. Kata asalnya adalah .as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm. 197 .كھنام
24Al-Jawaliqi berkata bahwa Abu Ubadah berkata, “Bangsa Arab tidak mengenal kata “al-Rabbaniyyun”, tetapi yang mengetahui kata ini adalah para fuqaha dan ahli ilmu. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani.” Al-Qāsim menegaskan bahwa kata ini berasal dari bahasa Suryaniyah. as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, hlm. 197.
45 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 45
mengacu pada lembah Hinnom, yaitu suatu lembah yang penuh dengan penderitaan. Karena simbol dari penderitaan, kemudian mendorong penggunaan hinnom menjadi gehinnom dalam kitab Talmud untuk menandakan neraka.
Rabbānī Kata ini dianggap berasal dari Yahudi karena akhiran “an”
pada kata “rabb”, yang berarti Tuhan kita atau guru. Menurut Geiger, akhiran “an” seperti itu adalah hal yang biasa dalam bahasa Yahudi yang bermakna pendeta (rahib), seperti pada kata; rabban dan ruhban.
Sabt Kata ini digunakan untuk menunjukkan hari sabtu (hari akhir
pekan) oleh Islam, Yahudi dan Kristen. Dalam kitab Eksodus XVI : I, Ben Ezra memberikan pandangannya bahwa dalam bahasa Arab ada 5 hari yang diberi nama sesuai urutan angka, yaitu hari pertama (a¥ad), hari kedua (i£nain), hari ketiga (£ula£ā’u), hari keempat (arbi’ā’u), dan hari kelima (khamīs). Tetapi di hari keenam tidak demikian. Justru Islam menggunakan kata “sabt”, dan dianggap hari yang suci dalam seminggu. Oleh karena itu, menurutnya, kata “sabbat” dalam bahasa Arab Shin yang dilafalkan seperti Samech dalam bahasa Ibrani dipertukarkan ke dalam bahasa mereka.
Taurāt25 Maknanya hukum. Kata ini hanya digunakan untuk tradisi
pewahyuan dalam agama Yahudi. Nabi Muhammad dengan tradisi oralnya tidak bisa membedakan perbedaan makna kata ini secara pasti. Bahkan Nabi Muhammad memasukkan makna “Pentateukh” dalam kata ini.26
b. Konsep Agama Islam Keimanan dan Doktrin Keagamaan
Abraham Geiger menganggap ada beberapa aspek keimanan dan doktrin keagamaan yang diadopsi Nabi Muhammad dari ajaran
25Kitab Taurat (Ibrani: תורה, Torah, "Instruksi") adalah lima kitab pertama
Tanakh/Alkitab Ibrani atau bagian Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateukh ("lima wadah" atau "lima gulungan"). Taurat adalah bagian terpenting dari kanon/kitab suci orang Yahudi. Ditulis oleh Fandi Firmansyah. Taurat. http://fandifirmansyah.blogspot. com/2013/05/taurat.html. Akses 20 Mei 2014.
26Abraham Geiger, Judaism and Islam, hlm. 32.
46 46 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
sebelum Islam, seperti: Pertama, tentang penciptaan langit dan bumi beserta segala
isinya dalam enam hari. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini pemi-kiran Nabi Muhammad sejalan dengan ajaran Bibel. Namun, di ayat lain, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa bumi diciptakan selama dua hari, gunung dan tumbuhan diciptakan selama empat hari, dan langit dengan segala isinya selama dua hari. Ayat ini menurut Abraham, kontradiktif dengan ayat pertama. Maka dari itu, ia menganggap Nabi Muhammad sangat sedikit pengetahuannya tentang Bibel, sehingga akhirnya tak sejalan lagi.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa meskipun Nabi Muhammad mengakui adanya hari ke-tujuh, yaitu sabt, tapi Nabi Muhammad tidak mau mengakui kesakralan (kesucian) hari tersebut. Menurut-nya, Nabi Muhammad telah menyinggung perasaan umat Yahudi dan menolak kepercayaan mereka tentang Tuhan yang beristirahat pada hari ke-tujuh tersebut.27
Kedua, tujuh tingkatan surga. Dalam kitab suci disebutkan bahwa ada tujuh tingkatan surga dan semuanya telah diberi nama. Hal ini tertera dalam Chagiga 9; 2. Begitu juga dalam Al-Qur’an, Nabi Muhammad juga menyebutkan hal yang sama, seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29, ( …فسواھن سبع سموات…).28
Ketiga, kepercayaan tentang pembalasan di hari akhir. Orang Yahudi percaya tentang hal ini, begitu juga tentang balasan surga dan neraka. Geiger mengatakan bahwa ternyata hal ini juga muncul dalam agama Islam. Dalam Isaiah, v. 14 disebutkan, penguasa neraka setiap hari bertanya, “Beri kami makanan agar kami merasa puas”. Dalam Al-Qur’an juga terdapat pernyataan yang sama, meski dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu Q.S. Qāf/ 50: 30,29
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam, “Apakah kamu sudah penuh?” Dia menjawab, “Masih ada tambahan?”
27Abraham Geiger, What did Muhammad Borrow from Judaism, dalam
buku The Origins of The Koran, ed, Ibnu Warraq, New York: Prometheus Books, 1998, hlm. 174.
28 Ibid, hlm. 174. 29 Ibid, hlm. 50.
47 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 47
Selain itu, kepercayaan tentang Ya’juj dan Ma’juj, Malaikat dalam kubur, perumpamaan orang saleh, dan lain sebagainya.30
Aturan Hukum dan Moral Yahudi kaya akan ajaran tunggal dan Nabi Muhammad
dianggap telah meminjam ajaran ini, di antaranya: a. Salat.
Ada beberapa aspek dalam ibadah salat yang dianggap Geiger sama dengan ajaran Yahudi, yaitu: [1] Konsep salat khauf. Menurutnya, Nabi Muhammad itu seperti rabbi yang menentukan posisi berdiri bagi ibadah salat. Seperti dikutip Geiger dari perkataan Nabi Muhammad, “Berdirilah ketika menghadap Tuhanmu, tetapi jika kamu takut, lakukanlah (shalat) sambil berjalan atau berkendaraan”.31 Tiga posisi ini juga terdapat dalam surat X. 13. Dengan kata lain, konsep salat dalam kondisi berbahaya atau peperangan (salat khauf) terdapat dalam agama Yahudi dan juga Islam. Kesamaan inilah yang dianggap Geiger sebagai “peminjaman” tradisi. [2] Larangan salat bagi yang mabuk. Terkait kondisi genting yang disebutkan pada poin pertama, konsentrasi dalam menjalankan salat menjadi hal yang urgen bagi seorang Muslim. Maka dari itu, menurut Geiger, Nabi Muhammad melarang umatnya untuk tidak menjalankan ibadah shalat ketika dalam keadaan mabuk. Larangan ini jugat terdapat dalam ajaran Talmud. [3] Legitimasi tayammum. Dalam ajaran Talmud, air adalah salah satu sarana untuk bersuci. Bila tidak ada air, maka pasir bisa menjadi alternatif utama. Begitu juga halnya dalam agama Islam, yang memperbolehkan tayammum sebagai sarana bersuci.32
Selain tiga poin di atas, ada juga konsep ajaran Islam lainnya yang dianggap Geiger diadopsi dari agama Yahudi, seperti batalnya wudu ketika menyentuh perempuan, etika salat berjamaah, dan aturan dalam ibadah puasa, serta aAturan agama terkait perempuan, seperti durasi masa ‘iddah selama tiga bulan dan durasi menyusui bayi selama dua tahun.
30 Ibid, hlm. 177-180. 31Q.S. Al-Baqarah/2: 239, وقوموا للھ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. 32 Abraham Geiger, Judaism and Islam, hlm. 68.
48 48 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
Pandangan Hidup Menurut Geiger, ada beberapa hal yang sama antara Islam dan
Yahudi dari aspek pandangan hidup, seperti; a. Harapan menjadi ¥usnul khātimah (meninggal dalam keadaan
yang baik). Dalam Al-Qur’an disebutkan, (وتوفنا مع الأبرار).33 Begitu juga dalam Balaam, “Let me die the death of the righteous”.34
b. Etika saat membuat janji. Dalam Islam, seseorang dianjurkan mengucapkan “Insya Allah” ketika berjanji untuk melakukan sesuatu.35 Begitu juga dalam ajaran Yahudi.
c. Yahudi mengenal adanya balasan kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Baba Kamma. 92. Hal ini juga senada dengan Q.S. an-Nisā/4: 85 (من یشفع شفاعة حسنة یكن لھ نصیب منھا).
d. Amal jariah. Dalam ajaran Yahudi, orang yang meninggal akan meninggalkan semuanya, kecuali amal ibadahnya. Begitu juga dengan hadis Nabi pernah mengatakan hal yang sama bahwa tiga hal yang akan mengiringi seseorang saat kematian, dua hal akan kembali dan satu hal yang akan menemaninya. Tiga ter-sebut yaitu keluarga, kesuksesan dan amal kebajikan. Keluarga dan kesuksesan (duniawi) akan kembali pulang, tetapi amal kebajikan tetap akan menemaninya (di dalam kubur).36
c. Kisah-kisah Al-Qur’an dari Tradisi Yahudi Ada empat kategori kisah dalam Al-Qur’an yang dianggap
Geiger berasal dari Yahudi, yaitu; Pertama, kisah tentang kepemim-pinan laki-laki (patriarchs), yaitu nabi-nabi yang diutus Allah untuk umatnya, meliputi; Kisah nabi Adam hingga nabi Nuh; Kisah nabi Nuh hingga nabi Ibrahim; dan Kisah nabi Ibrahim hingga nabi Musa. Kedua, kisah nabi Musa. Ketiga, Tiga raja yang kekuasa-annya tak terbatas, yaitu raja Thalut, nabi Daud, dan nabi Sulaiman. Keempat, orang-orang suci yang diutus setelah masa Sulaiman.37
33 Q.S. Ali Imran/3: 191. 34XXII, 10, Sebagaimana dikutip oleh Abraham Geiger, Judaism and Islam,
hlm. 70. 35Q.S. Al-Kahfi/18: 23-24, (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء اللھ) 36Abraham Geiger, Judaism and Islam, hlm. 72. 37Abraham Geiger, What did Muhammad Borrow from Judaism, hlm. 185-
223.
49 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 49
Kajian Bahasa Serapan dalam Al-Qur’an: Perspektif Muslim Jika dilihat dari aspek linguistik (akulturasi bahasa), kajian
yang dilakukan Geiger sebenarnya juga pernah dilakukan oleh sar-jana Ulumul Qur’an Islam lainnya, seperti Badr ad-Dīn Muhammad bin ‘Abdillāh az-Zarkasyī dalam karyanya al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Jalāluddīn as-Suyū¯ī dalam al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Mu¥ammad ‘Abdul ‘A§im az-Zarqānī dalam Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, dan lain sebagainya.
Dari pembacaan penulis terhadap mereka, terlihat bahwa keti-ganya memang mengakui peran bahasa lain dalam ayat Al-Qur’an. Imam as-Suyū¯ī menyebutkan ada 120 kosakata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Ia mengatakan bahwa adanya berbagai kosakata yang seperti ini di dalam Al-Qur’an adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur’an itu mencakup ilmu-ilmu para pendahulu maupun mereka yang akan datang kemudian.38
Untuk menguatkan argumennya, as-Suyū¯ī mengutip pendapat Ibnu Naqīb yang menjelaskan hal ini dengan tegas. Ibnu Naqīb berkata, “Di antara kekhususan Al-Qur’an dibandingkan dengan kitab-kitab Allah yang lain adalah Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa sebuah kaum yang diturunkan kepada mereka dan tidak ada sesuatu pun yang turun selain bahasa mereka.39 Hal ini juga sesuai dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad kepada segenap umat. Allah telah berfirman dalam Q.S. Ibrāhīm/14: 4,
n m l k j i h g fo s r q p
v u tw { z y x
Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (Q.S. Ibrāhīm/14:4)
38as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Beirut: Dar al-Fikri, 2008, hlm.
194. 39Ibid, hlm. 206.
50 50 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
Respons terhadap Karya Abraham Geiger
Warisan Ajaran Hanif Masa Lalu
Bukan hanya Geiger yang melakukan pendekatan historis-kritis terhadap Al-Qur’an, tetapi juga Kraemer,40 Gibb,41 John Wans-brough,42 dan lain-lain. Kreamer mengatakan bahwa sebagian dari isi Al-Qur’an diperoleh dari Kitab Perjanjian Lama, sedangkan hari kiamat yang pada dasarnya tidak diketahui oleh orang-orang Arab, asalnya adalah dari agama Masehi.43 Selain itu ada juga Gibb dalam bukunya Bunyah al-Fikr al-Dīni44 mengatakan bahwa pemikiran Islam dibangun atas berbagai macam kepercayaan yang dianut masyarakat Arab. Salah satu sumber rujukannya adalah Syaikh Syah Waliyullāh ad-Dahlāwi dalam karyanya ¦ujjatullāh al-Bāli-gah. Ternyata ia salah menafsirkan perkataan ad-Dahlawi. Hal ini diketahui karena salah satu pembaca bukunya adalah ad-Dahlawi sendiri. Padahal yang dimaksud oleh ad-Dahlawi sangat berbeda
40Dr. Hendrik Kraemer (lahir 17 Mei 1888 di Amsterdam, meninggal 11
November 1965 di Driebergen) adalah seorang misiolog, ahli bahasa teolog awam, dan tokoh ekumenis Hervormd Belanda. Kraemer menikah pada tahun 1919. Kraemer terkenal karena ia mencetuskan ide tentang cara pendekatan pekabaran Injil bagi agama lain. Dalam dunia teologi, Kraemer termasuk kaum awam, karena ia tidak pernah belajar teologi secara formal sampai akhir hidupnya. Sebagai seorang pekabar Injil, Kraemer pernah melayani di Indonesia dari tahun (1922-1937). Tanpa penulis. Hendrik Kraemer. http://id.wikipedia.org/ wiki/Hendrik_Kraemer. Akses 20 Mei 2014.
41Hamilton Alexander Rossken Gibb adalah seorang tokoh orientalis terke-muka, ia merupakan kelahiran mesir daerah alexanderia. Ia menyatakan bahwa Islam adalah sekte kristen yang sesat dengan menyatakan bahwa Islam adalah mohammadanisme. Pemikiran Gibb sendiri lebih menfokuskan kepada tradisi Islam dari nabi Muhammad atau sunnah nabi yang di anut oleh kaum ortodoks. Abid. Hamilton Alexander Rossken Gibb. http://abid3011.blogspot.com/2011/ 12/hamilton-alexander-rossken-gibb.html. Akses 20 Mei 2014.
42John Wansbrough mempersoalkan keautentikan Al-Qur’an, berpandangan bahwa Al-Qur’an adalah kompilasi dari sejumlah hadith dan karenanya Al-Qur’an “dibuat” pada masa pasca wafatnya Nabi (post-prophetic). Prof. Thoha Hamim, Ph.D. Menimbang Kejujuran Akademik Kaum Orientalis dalam Kajian Keislaman. pdf, hlm. 13-14. Akses 20 Mei 2014.
43Athaillah, Sejarah Al-Qur’an, Verifikasi tentang Otetisitas Al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 87.
44 Penulis tidak menemukan karya asli dari buku terjemahan ini.
51 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 51
dengan apa yang disampaikan oleh Gibb.45 Ad-Dahlawi mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus
sebagai rasul dengan membawa ajaran hanif yang berakar dari ajaran Ismail. Selanjutnya Nabi Muhammad meluruskannya, meng-hilangkan bagian-bagian yang rusak, dan menyulut kembali api ajarannya. Jadi, bukan meminjam atau imitasi ajaran agama sebe-lumnya. Itulah yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur’an sebagai ‘agama (millah) ayah kalian Ibrahim’.46 Karena itu, fondasi ajaran tersebut haruslah dapat diterima. Mereka masih memegang ajaran ini hingga kemunculan Amr bin Luhayy. Dialah orang pertama yang memasukkan ajaran berhala ke tanah jazirah Arab.47
Geiger mengatakan Nabi mengadopsi dari ajaran Yahudi karena beberapa alasan, di antaranya; 1) Ketika Nabi Muhammad menjalankan misinya di Madinah, Nabi
berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sudah sejak lama memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat setempat.48 Hal ini juga diamini oleh Moshe Pearlman dalam sambutannya terhadap karya Geiger, ia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang hidup di Jazirah Arab pada masa pra-Islam, sudah memiliki basis ekonomi, politik, intelektual, pertanian, dan juga kerajinan ta-ngan yang unggul. Menurutnya, Nabi Muhammad sengaja me-manfaatkan kesempatan ini untuk menarik simpati dan kesetiaan mereka agar mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. 49
2) Nabi Muhammad memiliki hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi di sekitarnya, seperti Abdullah bin Salam dan Waraqah.
45Said Ramadhan al-Buthi, Fikih Sirah, Hikmah Tersirat dalam Lintas
Sejarah Hidup Rasulullah saw, Terj, Fuad Syaifudin Nur, Bandung: Mizan, 2010, hlm. 40-42.
46 Q.S. Yūsuf: 38
& % $ # " !' / . - , + * ) (0 6 5 4 3 2 1
= < ; : 9 8 7
Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya).
47Syaikh Syah Waliyullāh ad-Dahlawi, ¦ujjatullāh al-Bāligah, sebagaimana dikutip oleh Said Ramadhan al-Buthi, Fikih Sirah, hlm. 42.
48Abraham Geiger, Judaism and Islam, hlm. 4-5. 49Ibid, hlm. xv-xvi.
52 52 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
Awalnya, mereka adalah mantan Yahudi terpelajar dan sudah mengenal kitab suci dan bahasa Hebrew (Ibrani). Begitu juga dengan Habib bin Malik, ia seorang raja Arab yang sangat kuat dan juga beragama Yahudi. Namun, akhirnya mereka semua menjadi pengikut Nabi Muhammad. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad memiliki kesempatan yang luas untuk ber-interaksi dengan orang Yahudi.50 Maka, Geiger menyimpulkan bahwa orang Islam mempelajarai ajaran Yahudi hanya melalui obrolan semata (conversation only), bukan melalui kitab suci. Sehingga wajar jika Nabi Muhammad banyak menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yahudi yang sebenar-nya.51 Bukti terjadinya interaksi antara Islam dan Yahudi, Geiger mengutip Q.S. al-Baqarah/2: 76 sebagai dasar alasannya,
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÞ á à ß
Lalu mereka berkata, “Apakah kamu menceritakan kepada me-reka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?”
3) Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kitab Suci Yahudi. Walaupun demikian, bukan berarti Nabi Muhammad kehilangan sumber. Ia bisa saja mempelajari Yahudi dari informasi orang-orang sekitarnya yang sudah sangat mengerti tentang kekayaan tradisi orang-orang Yahudi.
Menanggapi pernyataan Geiger di atas, ada beberapa penola-kan yang dikemukakan sarjana muslim, di antaranya;
Pertama, Nabi Muhammad memang pernah berpergian ke Syam,52 namun hanya dua kali. Pertama, ketika beliau masih berusia sekitar 9 atau 12 tahun, bersama paman beliau, Abu Thalib dan orang-orang Quraisy. Menurut riwayat yang dinukilkan Ibnu Hisyām dari Ibnu Is¥āq, pertemuan antara Muhammad dengan pendeta Buhaira tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang
50 Ibid, hlm. 17-18. 51 Ibid, hlm. 17. 52 Muhammad Ri«ā. Muhammad Rasūlillāh saw. Dār I¥yā’ al-Kutub al-
‘Arabiyah. 1380 H, hlm. 75. Sebagaimana dikutip oleh Athaillah, Sejarah Al-Qur’an, hlm. 97.
53 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 53
sangat singkat.53 Setelah itu, nabi Muhammad tidak pernah bertemu lagi dengan pendeta tersebut. Alasan ini menyimpulkan, tidak mungkin Nabi Muhammad menerima sekian banyak ajaran pendeta tersebut hanya dalam satu kali pertemuan yang singkat. Kedua, ketika beliau sudah dewasa, bersama Maisarah dan orang-orang Quraisy untuk menjual barang dagangan Khadijah.54 Dalam perja-lanan kali ini, Nabi Muhammad juga tidak bertemu lagi dengan pendeta Buhaira. Selain itu, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dan rombongan telah berbincang-bincang dengan pendeta Nasrani tentang agama dan kitab suci agama mereka.55
Kedua, selain pernah bertemu dengan pendeta Buhaira, Nabi juga sering bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Di Mekah beliau telah bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan Zibr ar-Rumi. Pertemuan nabi dengan Waraqah telah terjadi sebelum beliau menerima wahyu Al-Qur’an yang pertama. Dalam pertemuan yang singkat, Waraqah hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebagai tanggapan terhadap cerita tentang pengalaman nabi di gua Hira’. Adapun pertemuan beliau dengan Zibr hanya karena beliau ingin melihat cara pembuatan senjata bukan untuk berguru. Terkait hal ini, Al-Qur’an sendiri telah membantah tuduhan-tuduhan mereka melalui Q.S. an-Na¥l/16: 103.56
Ketiga, Meskipun ada banyak kesamaan antara ajaran Yahudi dan Islam, namun banyak pula informasi dalam Al-Qur’an yang bertolakbelakang dengan ajaran Yahudi, seperti 1) Dalam Perjan-jian Lama, Keluaran 2: 5-6, disebutkan bahwa orang yang memu-
53 Lihat Ibnu Ishaq-Ibnu Hisyam. Sirah Nabawiyah; Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah saw. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media, 2013, hlm. 111-113.
54 Ibnu Ishaq-Ibnu Hisyam. Sirah Nabawiyah, hlm. 115-116. 55 Saat Abu Thalib, Nabi Muhammad dan rombongan dagang Quraisy
menuju Syam, mereka memang singgah di kediaman Buhaira. Tetapi Ibnu Is¥āq meriwayatkan bahwa tidak ada perbincangan mengenai kitab suci, baik Taurat maupun Injil. Buhaira hanya menanyakan kondisi nabi Muhammad tidur, posisinya, postur tubuh, dan tanda kenabian ada di antara dua pundak. Setelah itu, Nabi Muhammad dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Syam. Lebih lengkap lihat dalam Ibnu Ishaq-Ibnu Hisyam. Sirah Nabawiyah, hlm. 111-117.
56Athaillah, Sejarah Al-Qur’an, hlm. 101-102. Sebagaimana dikutip dari Badr Al-‘Ainī. ‘Umdat al-Qārī Syar¥ ¢a¥ī¥ al-Bukhārī. Jilid I, Damaskus: Al-Munīriyyah, t.th, hlm. 46.
54 54 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
ngut Nabi Musa adalah anak perempuan Firaun, sedangkan dalam Al-Qur’an istri Firaun sendiri. 2) Dalam Perjanjiian Lama, yang membuat patung anak sapi adalah Nabi Harun, sedangkan dalam Al-Qur’an bernama Sāmirī.
Keempat, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana Nabi Muhammad tahu tentang isinya. Hal ini ditegaskan Al-Qur’an dalam Q.S. al-‘Ankabūt/29: 48,
] \ [ Z Y X W V U T^ b a _
“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).
Jika memang benar Nabi Muhammad pernah berguru kepada Buhaira, mengapa orang-orang Quraisy yang pernah menyaksikan pertemuan antara Nabi Muhammad dan pendeta Buhaira, tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, padahal mereka adalah musuh-musuh yang gigih menentang perjuangan nabi Muhammad.
Kelima, Al-Qur’an bukan berasal dari Nabi melainkan dari Allah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa argumen, yaitu [1] Nabi Muhammad pada awalnya selalu terburu-buru dalam menghafal ayat Al-Qur’an yang sedang dibacakan Jibril. Beliau baru berhenti terburu-buru, ketika Allah menjamin bahwa hafalan beliau akan tetap melekat dalam ingatan beliau. [2] Dalam Al-Qur’an banyak dijumpai ayat yang berisi teguran atau kritikan terhadap beberapa sikap Nabi Muhammad. [3] Di dalam Al-Qur’an juga terdapat ayat-ayat yang pada mulanya tidak diketahui oleh Nabi. Beliau baru memahaminya setelah turun ayat lain yang menjelaskannya. 57 Evaluasi Historis-Kritis dalam Kajian Al-Qur’an
Sarjana Barat yang menggunakan metode historis-kritis memandang agama Yahudi dan Kristen sebagai lingkungan sosio-religius Nabi Muhammad, darinya Nabi Muhammad mendapatkan informasi tentang kitab suci kedua agama itu.
57 Athaillah, Sejarah Al-Qur’an, hlm. 99-100.
55 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 55
Sejarah mengakui berkembangnya kedua agama tersebut (Kristen dan Yahudi) di Jazirah Arab, agama Kristen di Syiria dan beberapa kabilah Yahudi di Madinah. Di Mekah dan sekitarnya, kedua agama itu hanya dianut oleh kalangan tertentu, tidak dalam bentuk kabilah dan jumlahnya amat sedikit. Agama Yahudi dibawa oleh orang Yahudi yang hijrah ke negeri Arab akibat tekanan perang pada abad pertama Masehi, dan agama Kristen dibawa oleh orang Nabatean pada abad ke-3 Masehi. Menurut Philip K. Hitti, meskipun kedua agama itu masuk ke jazirah Arab, tetapi tidak memberi kesan dalam pikiran orang Hijaz (Mekah dan sekitarnya) kecuali orang-orang tertentu.58
Fuck-Frunfurt menolak sama sekali agama Yahudi dan Kristen menjadi basis Al-Qur’an. Sebab, agama Yahudi sangat menolak keberadaan Yesus dan Maryam. Sementara Al-Qur’an mengagung-kan Nabi Isa dalam taraf yang tinggi serta kelahirannya dari seorang wanita. Sementara, agama Kristen mempertuhankan Nabi Isa dan percaya pada penyaliban, suatu doktrin yang amat ditolak dalam Al-Qur’an.59
A.T. Welch berpendapat bahwa Nabi Muhammad berusaha mempelajari Bibel yang asli yang disembunyikan oleh orang Yahudi. Alasannya Q.S. al-An’ām/6: 91 di bawah ini.
: 9 8 76 5 4 3 2 1 0; ? > = <
@A H G F E D C BI K JL R Q P O N M
“....Katakanlah: "Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui(nya)?" Katakanlah: "Allah-lah (yang menurunkannya)", kemudian (sesudah kamu
58Philip K, Hitti, History of The Arabs, London: Macmillan & Co, 1958,
hlm. 107, Sebagaimana dikutip oleh Yudhi R, Haryono, dkk, Al-Qur’an: Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan, Bekasi: Gugus Pres 2002, hlm. 96.
59 Ibid.
56 56 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
menyampaikan Al Quran kepada mereka), biarkanlah mereka ber-main-main dalam kesesatannya.”
Sebenarnya, maksud ayat ini adalah orang Yahudi yang menyembunyikan ayat Bibel yang menjelaskan kebenaran Islam dan Nabi Muhammad. Tetapi Welch memahaminya bahwa Nabi Muhammad mencari naskah Bibel yang disembunyikan orang Yahudi untuk ditiru.60
Menurut Canon Sell, tidak mungkin Nabi Muhammad mencari dan meniru naskah Bibel karena Bibel (Perjanjian Lama) baru dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab tahun 900 M dan Perjanjian Baru diterjemahkan tahun 1171 M serta tidak ada bukti sejarah Nabi Muhammad pandai bahasa Ibrani.61 Karena itu, tidak ada bukti sejarah yang kuat, yang menggambarkan Nabi Muhammad menja-dikan Bibel sebagai landasan Al-Qur’an.62 Evaluasi Metodologis
Pendekatan historisisme dalam studi Al-Qur’an tidak akan menghasilkan konklusi yang positif dalam pandangan Islam. Karena historisisme melakukan eksplanasi terhadap objek penyeli-dikannya. Eksplanasi dilakukan sebagai pihak outsider. Akibat negatifnya menurut Hall, “The Danger of being ‘outsider’ is that the data of being studied can easily reduced to fit methodological categories”, bahaya yang muncul dari pihak luar adalah (ketika) data yang sedang dipelajari itu bisa dengan mudah direduksi, agar sesuai dengan kategori metodologi. Karena itu, pendekatan kritik-historis dalam Al-Qur’an bersifat reduksionis.
Menurut Royster, bila historisisme ingin mencari akar sebuah institusi, maka ia akan menolak hal-hal yang fundamental dan berusaha memperluas dasar teoritisnya, tetapi akibatnya menampil-kan hasil yang kurang ilmiah.63 Menurut Maryam Jamilah, kesa-lahan yang paling besar di masa modern adalah reduksionisme, dimana hal yang besar dijelaskan dalam taraf yang sangat kecil.
60Alford T, Welch, “Al-Kur’an”, dalam Encyclopedia of Islam, Vol V,
1986, hlm. 403, Ibid, hlm. 96. 61Canon Sell, Studies in Islam, London: CMSSS, 1928, hlm. 27, Ibid, hlm.
97. 62Ibid, hlm. 97. 63T. William, “Methodological Reflection”, dalam Introduction to the Study
of Religion, Harper dan Row Publisher, 1979, hlm. 253, Ibid, hlm. 97.
57 Abraham Geiger dan Kajian Al-Qur’an — Lenni Lestari 57
Wahyu yang bersifat supranatural dijelaskan sebagai fenomena natural.64
Kesamaan-kesamaan al-Quran dengan kitab suci sebelumnya bukan pengambil-alihan, melainkan bukti dari kesamaan asal-usul kitab-kitab suci tersebut, yaitu dari Tuhan yang satu, Allah swt. Dan kondisi historis tersebarnya ajaran agama sebelumnya kepada masa nabi atau rasul yang datang belakangan adalah efek dari tradisi isnad yang telah membudaya di kalangan umat manusia dalam mentransmisikan ajaran agama dan bukan sebagai bukti adanya saling mempengaruhi antara satu agama dengan agama yang lain.65
Angelika Neuwirth mengatakan bahwa hubungan antara Al-Qur’an dan sejarah sangatlah kompleks. Sehingga pendekatan yang memungkinkan untuk mengkaji Al-Qur’an adalah pendekatan sastra, sebagai mikrostruktural dari Al-Qur’an itu sendiri. Hal ini karena sejarah Al-Qur’an tidaklah dimulai dari proses kanonisasi, akan tetapi inheren (melekat) dalam teks Al-Qur’an itu sendiri. Dimana Al-Qur’an tidak hanya ditinjau dari aspek kandungannya saja tetapi juga bentuk dan struktur yang menjadi jejak sejarah dari proses kanonisasi, yang menggabungkan dua dimensi penting yaitu, kehadiran Al-Qur’an sebagai kitab suci dan kehadiran sebuah komunitas masyarakat.66
Simpulan Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa
hal. [1] Kajian Geiger terhadap Al-Qur’an erat kaitannya dengan profesinya sebagai seorang rahbi dalam agama Yahudi, sehingga ia tidak setuju jika Al-Qur’an dianggap kitab suci paling otentik ka-rena banyak ajaran agamanya yang diadopsi Islam. [2] Geiger me-nyebutkan ada tiga masalah utama yang diadopsi Nabi Muhammad dari tradisi Yahudi, yaitu: beberapa kosakata Al-Qur’an yang ber-
64James E, Royster, “The Study of Muhammad: A Survey of Approaches
from the Perspective of the History and Phenomenology of Religion,” dalam the Muslim World, No, 62 1972, hlm. 56, Ibid, hlm. 97.
65Ummu Iffah. Gugatan Terhadap Keotentikan Al-Quran (Studi Kritis Terhadap Kajian S.D Goitein, dalam buku Nuansa Studi Islam; Sebuah Pergulatan Pemikiran. Yogyakarta: Teras, 2010, hlm. 52.
66Angelika Neuwirth, “Quran and History. A Disputed Relationship; Some Reflections on Quranic History and History in the Quran”, Journal of Quranic Studies, V. I. 2003, hlm. 16.
58 58 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 39-58
asal dari tradisi Yahudi; konsep agama Islam; dan kisah-kisah Al-Qur’an dari tradisi Yahudi. [3] Penelitian Geiger dianggap tidak ilmiah karena tidak didukung data-data yang valid, terutama dari aspek historis.[] Wallāhu a’lam bi a¡-¡āwāb.
Daftar Pustaka
Al-Bµ¯i, Sa’īd Ramad±n. 'Fikih Sirah, Hikmah Tersirat dalam Lintas Sejarah Hidup Rasulullah saw. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Bandung: Mizan. 2010.
Athaillah. Sejarah Al-Qur’an, Verifikasi tentang Otetisitas Al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Farhan, Ahmad, Orientalis Al-Qur’an, Studi Pemikiran Abraham Geiger, dalam buku Orientalisme Al-Qur’an dan Hadis. Yogyakarta: Nawesea Press. 2007.
Geiger, Abraham. Judaism and Islam. New York: Publishing House. 1989.
_________, What did Muhammad Borrow from Judaism, dalam buku The Origins of The Koran, ed. Ibnu Warraq. New York. Prometheus Books. 1998.
Haryono, Yudhi R., dkk. Al-Qur’an: Buku yang Menyesatkan dan Buku yang Mencerahkan. Bekasi: Gugus Press. 2002.
Ilyas, Hamim. Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bigetisme Yahudi dan Kristen. Jurnal Al-Jami’ah. 1998.
Neuwirth, Angelika, dkk. The Quran in Context, Historical and Literary Investigations into the Quranic Milieu. Leiden: Brill. 2010.
_________, Quran and History. A Disputed Relationship; Some Reflections on Quranic History and History in the Quran. Journal of Quranic Studies, V. I. 2003.
Rahman, Fazlur. Tema-tema Pokok Al-Qur’an. Terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka. 1996.
Rashid, Khulqi, Al-Qur’an Bukan Da Vinci’s Code. Jakarta: Hikmah. 2007.
as-Suyū¯ī, Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Beirut: Dar al-Fikri. 2008.
Watt, Montgomery. Pengantar Studi Al-Qur’an. Terj. Taufik Adnan Akmal. Jakarta: Rajawali. 1991.
Az-Zarkasyī, Badr ad-Dīn Mu¥ammad bin ‘Abdillāh, Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. T.tp. T.th.
http://menaraislam.com dan http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat
Studi Kasus tentang Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel
Case Study of the ‘Idda in the Quranic exegesis in Buginese language by MUI of South Sulawesi Muhammad Yusuf UIN Alauddin, diperbantukan pada STAI Al-Furqon Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Daya Makassar [email protected] Naskah diterima: 12-12-2013; direvisi: 12-05-2014; disetujui: 23-05-2014. Abstrak Artikel ini mengulas pandangan ulama Bugis mengenai idah dalam Tafsere Akorang Mabbasa Ogi karya MUI Sulawesi Selatan. Persoalan idah seringkali mendapat sorotan dari pemerhati jender. Rumusan idah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kini menghadapi gugatan atas nama kesamaan jender sehingga idah yang hanya berlaku untuk perempuan kini digugat agar diberlakukan juga untuk laki-laki. Idah harus dilihat pada amanat teks, konteks historis, dan konteks budaya. Teks telah mengatur idah dengan jelas, bahwa idah pada masa Rasulullah hanya berlaku bagi wanita. Idah dan i¥d±d bertujuan memelihara nasab, di sam-ping sebagai momentum instrospeksi diri dan mediasi agar tidak terjadi perce-raian. Nilai-nilai kearifan budaya Bugis layak menjadi pertimbangan mengenai penetapan masa idah.
Kata kunci: idah, i¥d±d, wanita, jender, budaya Bugis, introspeksi diri.
Abstract This article temps to investigate Bugis Muslims Scholars’ view about idah in ‘Tafesere Akorang Mabbasa Ogi’ by MUI of South Sulawesi. Idah sometimes be criticized by gender movement supporters. Form of idah in Compilation of Islamic Law (KHI) nowadays forward challange because of gender equality. Therefore, idah which formulated for women, nowadays criticed that it is not only for women, but also for men. Idah should be seen comprehensively, including texstual side, historical context, and cultural context. Texts formulated it clearly and in era of Prophet Muhammad it was for women only. Idah and i¥dād aim both to sterilize generation line and to be momentum for self introspection and mediation for preventing divorce. The wisdom values of Bugis culture can be an alternative consideration on role of idah.
Keywords: idah and i¥d±d, women, gender, Bugis culture, fairness, self in-trospection.
60 60 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
Pendahuluan Sekelompok pemikir kontemporer mencoba menawarkan suatu
gagasan baru dengan melihat perspektif jender, yaitu gagasan untuk memberlakukan idah bagi laki-laki atau suami yang ditinggal oleh istri, baik karena meninggal maupun talak. Bagi duda atau suami yang pernikahannya putus karena kematian istrinya berlaku 130 hari, sedangkan apabila putus karena perceraian maka masa tunggu-nya ditetapkan mengikuti masa tunggu mantan istrinya. Menurut mereka, konsep penetapan idah hanya pada pihak istri dinilai sangat bias jender. Penulis buku Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam mencoba menggugat keputus-an-keputusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang hukum perkawinan. Dalam KHI banyak keputusan hukum yang perlu diperbarui karena sudah tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan jender. Pada Bab XIII “Masa transisi idah, pasal 86 ayat 7, misalnya, penulis mengusulkan masa idah seorang duda sebagai berikut.
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, masa transisi ditetapkan 130 hari;
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya. Pasal 87: Selama dalam menjalani masa transisi, kedua belah pihak harus saling menghormati, menghargai, membantu, menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak kawin dengan orang lain.1
Gagasan tersebut dinilai resisten dan sulit diterima karena di samping tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur’an dan hadis, juga dari sisi psikologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang normal secara seksual dapat terangsang kapan saja sepanjang hidupnya, sementara perempuan berbeda, sebab ada batas masa produktifnya, yaitu pada saat menopause. Atas pertimbangan perbedaan psikologis, tabiat, kodrat, dan sosial-budaya, tentu gugat-an keadilan jender yang menilai konsep idah yang telah dirumuskan perlu dinilai secara arif dan komprehensif.
1Lihat: Muhammad Zein dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga
Humanis, Jakarta: Grahacipta, 2005, hlm. 262−264.
61 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 61
Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel2 Tafsir berbahasa Bugis karya MUI Sulsel merupakan ikhtiar
untuk mempersatukan umat Islam di Sulsel yang menghadapi hege-moni ketika itu, yang dimulai dari kalangan elitnya. Pembentukan tim untuk menulis tafsir ini bertujuan menghimpun potensi ulama Bugis untuk berkarya bersama dalam melayani umat. Itulah menga-pa tim penulis tafsir ini berasal dari latar belakang yang variatif. Para ulama yang terlibat dalam proses penulisan adalah: K.H.3 Abd. Muin Yusuf (ketua), K.H. Makmur Ali (Muhammadiyah), K.H. Hamzah Manguluang (As‘adiyah), K.H. Muhammad Djunaid Sulai-man (Bone sekaligus senior), H. Andi Syamsul Bahri (DDI-AD sekaligus junior), dan lain-lain.
Penulisan tafsir ini juga menjadi media komunikasi antara ula-ma dan umara (elit kultural dan elit struktural). Hal itu terlihat misalnya dari segi pendanaan. Penulisan tafsir ini didanai oleh BAZIS Provinsi Sulsel atas kebijakan Gubernur Prof. Ahmad Ami-ruddin. Penulisan tafsir ini juga merupakan ikhtiar untuk memeliha-ra dan melestarikan khazanah kebudayaan lokal, yaitu melestarikan aksara Lontarak Bugis. Itulah sebabnya tafsir ini ditulis dalam aksa-ra Lontarak Bugis.4 Aksara Lontarak Bugis adalah salah satu ke-kayaan budaya masyarakat Bugis khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di tengah ancaman globalisasi aksara Lontarak rawan mengalami kepunahan sehingga ulama dan umara bertanggungja-wab melesatarikannya; bukan karena aksara Lontaraknya semata, tetapi juga karena di dalamnya mengandung sejumlah nilai-nilai kearifan yang patut dipelihara dan dijadikan pedoman hidup.
Tafsir ini memuat penafsiran 30 juz Al-Qur’an dan diberi judul dalam bahasa Arab Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm dan dalam bahasa
2Di Sulsel teridentifikasi beberapa karya tafsir dan terjemah berbahasa Bu-
gis. Lihat: Muhammad Yusuf, “Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Sulawesi Se-latan (Studi Kritis terhadap Tafesere Akorang Mabbasa Ogi Karya MUI Sulsel)”, Disertasi, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2011, lampiran.
3K.H. merupakan akronim dari Kyai Haji. Dalam masyarakat Sulsel Kyai Haji disebut AG. H., akronim dari Anre Gurutta’ Haji. Anre Gurutta’ berarti ma-haguru atau guru besar secara kultural, bukan gelar akademik. Gelar ini diberikan kepada ulama senior di Sulawesi Selatan yang diakui keluhuran ilmu dan akhlak-nya. Adapun gelar bagi ulama yang dinilai masih satu tingkat di bawahnya adalah Gurutta (disingkat G.), alias ulama junior.
4Tim MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi, Jilid I (Ujung Pandang: MUI Sulsel, 1988), hlm. v.
62 62 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
Bugis tpEEser akor mbs aogi—Tafesere Akorang Mabbasa Ogi. Mulanya tafsir ini terdiri dari 10 jilid, namun kemudian dicetak ulang dan diperbanyak oleh MUI Sulsel menjadi 11 jilid. Pada awalnya setiap jilid memuat 3 juz, namun karena jilid 10 dinilai terlalu tebal maka juz ini dibagi menjadi dua.
Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan primer dalam penyu-sunan tafsir ini di antaranya: Tafsīr al-Marāgī karya Ahmad Mus-¯afā al-Marāgī, Tafsīr al-Qāsimī karya Jamāluddīn al-Qāsimī, Tafsīr al-Qur’ān al-‘A§īm karya Ismā‘īl bin ‘Umar bin Ka£īr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, dan Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm karya al-Bai«āwī. Adapun rujukan-rujukan sekundernya yaitu Tafsīr a¯-°abarī, Tafsīr al-Qur¯ubī, at-Tafsīr al-Wā«ī¥, ¢afwat at-Tafāsīr, ad-Durr al-Man£ūr, dan Tafsīr al-Muntahnāb. Pengertian Idah
Idah merupakan kata serapan dari bahasa Arab ‘iddah yang diderivasi dari kata ‘adad yang berarti bilangan atau hitungan.5
Disebut ‘iddah karena di dalamnya terdapat unsur bilangan, yaitu hari-hari haid dan masa-masa suci bagi seorang perempuan yang ditalak. Secara terminologis idah didefinisikan sebagai masa penan-tian bagi seorang wanita, yaitu satuan waktu (fase) yang di dalam-nya ia tidak boleh dipinang secara terang-terangan maupun mene-rima pinangan dari lelaki lain setelah suaminya wafat atau setelah ia diceraikan olehnya.6 Idah merupakan ketentuan hukum Islam me-ngenai masa tunggu seorang yang berstatus sebagai istri untuk dipi-nang dan/atau menerima pinangan secara terang-terangan setelah perceraian dengan suaminya, baik karena talak maupun karena ke-matian suami. Kondisi yang melingkupi perceraian itu harus men-
5Di antara ide-ide yang dilontarkan adalah Counter Legal Draft (CLD)
Kompolasi Hukum Islam (KHI), yang mendapat kritikan dari beberapa ulama Indonesia. Oleh mereka, KHI 1991, khususnya mengenai peraturan perkawinan, dinilai tidak lagi relevan untuk konteks kekinian. Lihat: Siti Musdah Mulia, “Pengantar” dalam Membangun Keluarga Humanis, Muhammad Zein dan Mukh-tar Alshodiq, Jakarta: Grahacipta, 2005, hlm. xxiii.
6Ibnu ‘Ābidīn, ¦asyiyah Radd al-Mukhtār ‘alā ad-Dur al-Mukhtār, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 502; Mu¥ammad ¦usain aż-Żahabī, Asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah bain Ahl as-Sunnah wa Mażhab al-Ja‘fa-riyyah, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968, hlm. 347.
63 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 63
jadi dasar pertimbangan untuk menentukan masa tunggu masing-masing. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Al-Qur’an. Ketentuan Idah dalam Al-Qur’an
Melanggengkan perkawinan dengan cara mengharamkan perce-raian tidak selalu memberi maslahat, bahkan kadang justru berten-tangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan memunculkan resistensi terhadap Islam. Islam mengabsahkan perceraian dengan segala keengganannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”7 Islam mene-tapkan seperangkat aturan dalam rangka menghindari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan.8 Islam datang dengan seperangkat aturan yang bertujuan mengangkat posisi perempuan menjadi lebih baik, yaitu membolehkan perceraian tetapi dengan aturan-aturan yang ditetapkan berupa idah. Dengan idah ini kedua pihak diberi kesempatan untuk berdamai atau putus sama sekali.
Batas masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan cara seorang perempuan ditinggal oleh suaminya. Al-Qur’an membeda-kan antara idah perempuan yang ditinggal mati suaminya (al-muta-waffā ‘anhā zaujuhā) dengan idah cerai perempuan yang bukan di-akibatkan oleh kematian suaminya (gair al-mutawaffā ‘anhā zauju-hā). Kondisi rahimnya ketika diceraikan ada kalanya sedang ter-buahi dan ada kalanya dalam keadaan kosong. Ada pula perempuan
7Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Riyadh: Bayt al-Afkar
ad-Dauliyah, t.th. dalam Kitāb a¯-°alāq, Bāb fī Karāhiyah a¯-°alāq, no. 2178. 8Perlakuan terburuk yang dialami perempuan dalam perceraian ditemukan
dalam masyarakat jahiliah. Dalam tradisi mereka perceraian dapat dilakukan de-ngan cara, alasan, dan tujuan yang beragam atau tanpa sebab apa pun. Seorang suami dapat menceraikan istrinya hanya dengan alasan istri tidak cantik lagi atau tidak lagi tampak menarik atau menggairahkan secara seksual. Perempuan juga sering diceraikan lalu dirujuk kembali secara berulang-ulang sampai batas yang tidak ditentukan. Laki-laki dapat menceraikan istrinya sesering yang ia inginkan. Laki-laki juga sering menceraikan istrinya dengan catatan istri tersebut tidak boleh menikah tanpa izinnya. Laki-laki bisa menikahkan mantan istrinya dengan laki-laki mana pun yang diinginkan meski mantan istrinya tidak suka. Mengenai jaminan sosial, mereka yang diceraikan tidak mendapatkan apa-apa. Pemberian suami selama perkawinan berlangsung dapat atau bahkan lazimnya diambil kem-bali. Lihat: Fatimah Umar Nasif, Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam, Terj. Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001, hlm. 71.
64 64 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
yang diceraikan pada saat memasuki masa menopause, ada pula yang sudah digauli dan ada juga yang belum digauli.
Persoalan idah diuraikan di dalam Al-Qur’an dengan gamblang, demikian pula dituangkan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Namun demikian, akibat perkembangan pemikiran umat Islam pada dasawarsa ini, sebagian intelektual Islam mencoba mereview aturan-aturan idah itu.9 Menurut mereka, demi keadilan jender, idah mestinya tidak hanya diberlakukan bagi pihak istri, melainkan juga bagi pihak suami.
Di Indonesia pembaruan hukum Islam telah disuarakan oleh beberapa tokoh intelektual muslim, sebut saja di antaranya Harun Nasution, Nurcholis Majid, Munawir Syazali, serta beberapa tokoh-tokoh intelektual muda yang tidak jarang mendapat kritik pedas dari beberapa kelompok Islam lainnya, misalnya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dipimpin oleh Ulil Absar-Abdalla. Di antara ide-ide yang dilontarkan adalah Counter Legal Draft (CLD) Kompolasi Hukum Islam, yang pernah mendapatkan kritik dari beberapa ulama Indonesia. Dikatakan bahwa Kompolasi Hukum Islam 1991, khu-susnya yang terkait dengan peraturan perkawinan, tidak lagi repre-sentatif untuk konteks kekinian karena KHI sangat dipengaruhi oleh nuansa fikih klasik yang bercorak Arab.10 Pendapat mereka ini jus-tru melahirkan persoalan baru yang menggelisahkan umat Islam sebab secara tekstual tidak dukung oleh dalil, baik dari Al-Qur’an maupun hadis. Lebih lagi, jika tujuan idah adalah menjaga kesucian rahim maka tentu hal itu tidak bisa diberlakukan bagi laki-laki.
Masa idah diklasifikasikan oleh Al-Qur’an sebagai berikut. 1. Perempuan yang bercerai karena ditinggal mati suaminya harus
menjalani masa idah selama 4 bulan 10 hari seperti disebutkan dalam Surah al-Baqarah/2: 234.
2. Perempuan yang bercerai bukan karena ditinggal mati suaminya menjalani masa idah selama 3 kali masa suci berdasarkan Surah al-Baqarah/2: 228.
3. Perempuan yang sedang hamil idahnya berlaku hingga ia mela-hirkan sesuai Surah a¯-°alāq/65: 4.
9Wahbah az-Zu¥ailī, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-
Fikr, t.th., jilid VII, hlm. 624; Zakariyā al-An¡ārī, Fat¥ al-Wahhāb Syar¥ Manhaj a¯-°ullāb, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 103.
10Lihat: Siti Musdah Mulia, “Pengantar” dalam Membangun Keluarga Hu-manis, Muhammad Zein dan Mukhtar Alshodiq, hlm. xxiii.
65 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 65
4. Perempuan yang sudah menopause menjalani masa idah selama 3 bulan sesuai Surah a¯-°alāq/65: 4. Demikian juga bagi pe-rempuan yang belum pernah haid.
5. Tidak ada idah bagi perempuan yang cerai ketika belum digauli oleh suaminya, seperti disebutkan dalam Surah al-A¥zāb/33: 49.
Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228 dinyatakan,
“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurµ'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”
Yang dimaksud “wanita-wanita yang diceraikan” pada ayat ini adalah mereka yang sudah pernah haid, belum menopouse, telah bercampur dengan suaminya, dan tidak dalam keadaan hamil.11
Dipahami demikian karena pada ayat lain dijelaskan bahwa masa idah bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan (a¯-°alāq/65: 4), masa idah bagi wanita menopause dan yang belum haid adalah tiga bulan (a¯-°alāq/65: 4), dan tidak ada masa idah bagi wanita yang cerai sebelum bercampur dengan suaminya (al-A¥zāb/33: 49). Atas dasar itu, perempuan yang ditalak diwajibkan menunggu untuk tidak menerima pinangan secara terang-terangan dan tidak pula kawin selama interval tersebut.12
Frasa “menahan diri mereka (menunggu)” mengisyaratkan bahwa wanita-wanita itu tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukan atas kesadaran dan bukan karena paksaan atau tekanan dari luar, karena mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid mereka. Dalam keadaan demikian, dibutuhkan kejujuran dari wanita tersebut. Masa tunggu diperlukan di antaranya untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Dalam kasus wanita yang dicerai, pada ayat ini, di samping tujuan tersebut, idah juga bertujuan untuk memberi suami kesempatan guna mempertimbangkan keputusan-nya—bercerai atau rujuk—sekaligus memberi waktu bagi keduanya
11MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330. 12MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330.
66 66 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
untuk merenung dan mengintrospeksi diri.13 Itulah salah satu bukti bahwa hukum Islam dibangun di atas prinsip maslahat; akibat per-ceraian tidak sebatas persoalan status (janda, duda), tetapi juga ber-dampak pada kesejahteraan (ekonomi, sosial) dan psikologi anak-anak mereka.
Talak merupakan suatu tindakan merugikan yang sangat dian-jurkan untuk tidak dilakukan kecuali ketika semua upaya penyele-saian menemui jalan buntu. Dalam beberapa ayat disebutkan usaha-usaha yang perlu dilakukan sebelum talak. Diterangkan bahwa talak harus dijatuhkan pada masa suci yang belum terjadi hubungan biologis di dalamnya. Hal ini akan mengendorkan kemauan untuk menjatuhkan talak karena suami harus menunggu hingga datangnya masa suci bagi istri, barulah ia dapat dijatuhkan talak.14
Al-Qur’an menyatakan dengan tegas bahwa masa idah wanita yang berada dalam masa-masa haid adalah tiga qurū‘. Kata qurū‘ memiliki dua makna, yaitu ¯uhr (suci) dan haid. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan satu dari kedua makna ini karena kata ini merupakan kata musytarak (multiinterpretasi). Ulama seperti Dāwūd, Abu ¤aur, dan ulama-ulama bermazhab Maliki dan Syafi’i memilih memaknai tiga qurū‘ sebagai tiga kali suci, yaitu masa antara dua haid. Dengan demikian, masa idah bagi wanita yang dicerai usai seiring dengan datangnya haid yang ketiga. Sementara itu, ulama-ulama bermazhab Hanafi dan Hanbali memahami tiga qurū‘ sebagai tiga kali haid. Berdasarkan pendapat ini, masa idah wanita yang dicerai suaminya usai bertepatan dengan usainya haid yang ketiga.15
Tafsir karya MUI Sulsel hanya mengungkapkan adanya perbe-daan pandangan para ulama dalam memaknai kata tersebut tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Mari kita perhatikan penafsiran atas Surah al-Baqarah/2: 228.
13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. I,
hlm. 455. 14Sayyid Qu¯b, Fī ¨ilāl al-Qur'ān, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1992, juz I-IV,
hlm. 246. 15Ibnu Ka£īr, Tafsīr al-Qur'ān al-'A§īm, Beirut: Dar al-Makabah al-Asriyah,
2000 M/1420 H., jilid I, hlm. 236-237; M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, hlm. 456.
67 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 67
Aksara Bugis Lontarak: “Mjepu mkurwiea mredkea nerko riteleai rilkwin—riweteai dr—npurmuai msibw lkain wjiai mtje eatk “telu pci” pdtoh ptron aer gurut aim cpiai aereeg aim mliki ayerg “telu dr aule-pule” pdtoh pphn aer gurut abu hnip sibw ahemde” Transliterasi: “Majeppu makkunrai maradekae narekko ritellei rilakkkainna (newettei dara) napuramui massibawa lakkainna wajii mattajeng ettana “tellu pac-cing” padatoha pattarona anregurutta Imam Syafi’i, enrennge Imam Maliki, iyarega “tellu dara uleng-puleng” padatoha pappahanna anregu-rutta Abu Hanifah sibawa Ahmad”16 (Bugis) Artinya: “Sesungguhnya perempuan yang merdeka apabila ditalak dan sudah digauli maka wajib menunggu selama tiga kali suci, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik, atau tiga kali haid sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.”
Penafsiran di atas mirip dengan buku-buku tafsir rujukannya.
Bedanya, tim MUI Sulsel mengartikan kata al-mu¯allaqāt dengan “perempuan yang merdeka”. Mereka mengutip Tafsīr Ibni Ka£īr yang menjelaskan bahwa sudah menjadi kesepakatan empat ulama mazhab bila wanita hamba sahaya bila ditalak maka idahnya dua kali qurū’—separuh dari idah wanita merdeka. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, “Talak bagi seorang hamba adalah dua kali talak dan idahnya dua kali haid.”17
Tim MUI Sulsel dalam tafsirnya juga tidak menguraikan secara detail persoalan hamba sahaya yang ditalak; mereka hanya menaf-sirkan kata al-mu¯allaqāt secara global. Di sini terlihat bahwa me-tode yang digunakan bersifat ijmālī.18
Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan makna suatu kata musytarak—kata quru‘ adalah salah satunya. Imam Syafi’i menerima semua makna yang mungkin dikandung oleh kata musy-tarak, baik dalam kalimat afirmatif maupun negatif, selama tidak tidak ada dalil yang menguatkan salah satu makna dan makna-makna itu tidak saling kontradiksi. Sementara itu, sebagian kecil ulama Hanafiyah hanya menerapkan makna kata musytarak pada
16MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330. 17Ibnu Ka£īr, Tafsīr al-Qur'ān al-'A§īm, jilid I, hlm. 236. 18Metode ini justru bisa menimbulkan permasalahan lain bagi pembacanya
karena masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
68 68 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
kalimat negasi, bukan dalam kalimat afirmasi. Ketika tim MUI Sulsel tidak cenderung pada salah satu pendapat di atas, maka hal itu mengisyaratkan bahwa mereka menerima pemberlakuan semua makna tersebut, yaitu “suci” dan “haid”,19 apalagi dimungkinkan kedua pendapat ini sama-sama benar. Seseorang bisa memilih salah satunya, tergantung pada keyakinannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa mazhab tafsirnya tidak berafiliasi kepada mazhab. Mereka berusaha mengakomodasi semua pendapat selama itu tidak berten-tangan dengan arus utama pemikiran Islam, yakni empat mazhab fikih yang dianut oleh Ahlussunnah. Hal ini terjadi karena latar belakang pemikiran fikih pada tafsir ini bersumber pada perban-dingan mazhab sehingga memberi kebebasan kepada masyarakat Bugis untuk memilih sesuai dengan afiliasi mazhab mereka. Ini bisa dimaklumi karena MUI Sulsel sebagai pemimpin umat Islam harus mampu berdiri di atas dan mengayomi semua kelompok, golongan, dan mazhab.
Allah berpesan bahwa, “tidak boleh bagi mereka menyembu-nyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,” baik berupa kehamilan (janin) maupun haid.20 Ungkapan Al-Qur’an ini “menyentuh” hati mereka dengan mengingatkan mereka kepada Allah yang menciptakan apa yang ada dalam rahim mereka, dan dibangkitkan pula rasa keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir dengan kalimat “jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.” Keimanan mensyaratkan agar mereka tidak menyembunyi-kan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka. Penggalan ayat ini juga menunjukkan bahwa terkait persoalan haid atau keha-milan, wanita itu sendiri yang paling tahu, dan mereka diancam jika tidak menginformasikan hal yang sebenarnya.21 Meski demikian, tidak secara otomatis ucapan mereka harus diterima. Bila diragukan maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan.22 Menurut tim MUI Sulsel, pihak perempuan yang ditalak dituntut untuk bersikap jujur (malempu’) dalam mengakui keadaan yang dialaminya ketika sudah ditalak,23 apakah dia hamil atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan kondisi demikian, sang suami masih berhak merujuk istri-
19MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330. 20MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330. 21Ibnu Ka£īr, Tafsīr al-Qur'ān al-'A§īm, jilid I, hlm. 237. 22M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. I, hlm. 455. 23MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330.
69 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 69
nya bila ia masih menginginkan memperbaiki hubungannya. Itulah mengapa idah dinilai sebagai sarana untuk saling mengintrospeksi diri.24 Dengan demikian, pengadilan seyogianya tidak menerima argumen-argumen untuk mengambil keputusan perceraian—bagi laki-laki yang mengajukan cerai atau wanita yang mengajukan gugat cerai—sebelum adanya mediasi maksimal. Mediasi bertujuan meminimalkan kemungkinan jatuhnya talak mengingat dampak psikologis dan sosial yang akan ditimbulkannya.
Mengatakan bahwa masa idah ditetapkan untuk mengetahui bersihnya rahim (barā’at ar-ra¥im) masih disangsikan karena keha-milan seorang wanita bisa diketahui tanpa membutuhkan waktu selama itu. Perkembangan iptek dapat menjawab hal tersebut. Ka-rena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa ‘illat penetapan wak-tu tiga qurū‘ tidak diketahui secara pasti dan ketentuan tersebut tidak termasuk persoalan ta‘aqqulī.25 Sementara, tim MUI Sulsel memahami ayat ini secara kontekstual, yaitu dengan melihat bahwa penentuan masa idah bersifat ta‘aqqulī. Penentuan itu bukan sekadar untuk mengetahui barā’at ar- ra¥im, melainkan juga seba-gai sarana introspeksi agar kedua pihak ada upaya berdamai dalam masa idah itu dan rujuk kembali.26 Pemikiran semacam ini mem-pertimbangkan tidak hanya dampak psikologis, tetapi juga dampak sosial yang timbul jika sekiranya terjadi permasalahan akibat tidak jelasnya nasab anak yang dilahirkan. Pemikiran semacam ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yaitu memelihara nasab.
Jika tujuan idah sekadar untuk mengetahui kondisi rahim maka teknologi kedokteran saat ini sudah mampu mendeteksi terjadinya pembuahan dalam rahim meski hal itu baru terjadi dalam hitungan menit. Jika demikian maka akan melahirkan kesimpulan bahwa ayat ini tidak perlu diberlakukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa se-canggih apa pun teknologi, ia masih dikendalikan oleh manusia. Artinya, masih ada kemungkinan manipulasi yang dapat mengotori keturunan yang diantisipasi oleh syariat. Seorang wanita, karena tujuan tertentu, misalnya untuk menikah secepatnya, bisa saja ber-sepakat dengan dokter untuk menyatakan hasil deteksi kehamilan
24MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 330. 25MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 331. 26Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed.), Problematika Hukum
Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994, hlm. 194.
70 70 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
negatif meski nyatanya positif. Dengan demikian, penetapan tiga qurū‘ oleh Al-Qur’an sangat tepat. Di samping itu, serapat apa pun seorang perempuan menjaga rahasia kehamilannya kepada suami-nya yang baru, sekiranya ia menikah sebelum masa idah berakhir, pasti akan ketahuan juga. Kelahiran seorang bayi ketika usia perka-winan baru mencapai enam bulan membuktikan bahwa bayi itu bukan benih suami yang kedua.
Tim MUI Sulsel memberi perhatian besar terhadap hak-hak perempuan (istri). Hal itu dapat dilihat dari komentar atas Surah al-Baqarah/2: 228 bahwa idah merupakan salah satu sarana introspeksi diri bagi pasangan tersebut untuk memperbaiki hubungan mereka. Suami tidak boleh bermain-main dengan cerai/talak karena mem-permainkan istri bertentangan dengan ajaran agama.27 Itulah sebab-nya, pada ayat ini disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak atas suaminya, demikian pula sebaliknya. Hak istri itu tidak boleh diinjak-injak oleh suami karena perbuatan tersebut membuatnya mendurhakai Allah.28 Kelebihan atau kemuliaan yang telah Allah berikan kepada seorang lelaki berupa pemberian nafkah dan menja-di pemimpin atas keluarganya bergantung pada sejauh mana ia memperlakukan istrinya dengan baik (mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf).29
Adapun ketentuan idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 234,
“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Sebagian mufasir menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk tidak
saja menetapkan idah bagi seorang istri ditinggal wafat oleh suami-nya, tetapi juga masa berkabung. Selama masa itu istri tidak diper-kenankan keluar rumah dalam keadaan berdandan atau hal-hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki.
Menurut tim MUI Sulsel, persoalan ini sudah jelas dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Mereka hanya menfokuskan pada dua hal,
27MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 331. 28MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 331. 29MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 331.
71 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 71
yaitu penjelasan tentang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi hamil dan masa berkabungnya. Mengenai istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam kondisi hamil, tim MUI Sulsel mengemukakan dua pendapat. Pertama, mengutip pendapat Ibnu Abbas, masa idahnya wanita tersebut adalah masa terpanjang dari dua masa berikut: 1) apabila ia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari maka masa idahnya adalah empat bulan sepuluh hari; 2) jika masa empat bulan sepuluh hari sudah terlampaui dan ia be-lum juga melahirkan maka idahnya berakhir ketika ia melahirkan.
Kedua, mengutip salah satu hadis terkait Subai’ah al-Aslami-yah yang hamil ketika suaminya meninggal. Dikisahkan bahwa berselang beberapa hari kemudian ia melahirkan. Usai membersih-kan diri dari darah nifas ia mulai berdandan. Mengetahui hal ini, Abu as-Sanābil menegurnya, “Mengapa engkau berdandan? Apakah engkau sudah punya keinginan untuk menikah lagi? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari.”30 Mendengar teguran itu, Subai’ah lantas mengumpulkan pakaiannya dan menemui Rasulullah untuk menanyakan solusi atas persoalan yang dialaminya. Rasulullah lalu menegaskan bahwa halal baginya menikah setelah melahirkan.31
Di sini tim MUI Sulsel tidak menetapkan pendapat mana yang dipilih, padahal jelas sekali disebutkan dalam Surah a¯-°alāq/65: 4 bahwa,
“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” Pada ayat di atas jelas dinyatakan bahwa idah bagi wanita ha-
mil adalah hingga ia melahirkan. Dengan demikian, pendapat ke-dualah yang tepat. Bagi seorang istri yang hamil ketika ditinggal wafat oleh suaminya tidak ada ketentuan idah terpanjang karena fungsi idah adalah memastikan kandungannya kosong. Terlebih lagi nasab anak yang dikandungnya juga sudah jelas, sehingga tidak menjadi soal bila wanita itu menikah lagi usai melahirkan. Keempat
30MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 350. Bandingkan dengan: Ibnu Ka-
£īr, Tafsīr al-Qur'ān al-'A§īm, jilid I, hlm. 250. 31MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 350. Hadis ini diriwayatkan oleh
Muslim, ¢a¥ī¥ Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1991, dalam Ki-tāb a¯-°alāq, Bāb Inqi«ā‘ ‘Iddah al-Mutawaffā ‘Anhā Zaujuhā, no. 1484.
72 72 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
imam mazhab juga menegaskan bahwa bila seorang istri hamil ke-tika suaminya wafat maka idahnya adalah sampai melahirkan, tidak peduli apakah ia melahirkan tidak lama setelah itu.32
Pendapat berlainan dikemukakan oleh mufasir kontemporer Mesir, Syekh Mutawalli asy-Sya’rāwi. Menurutnya, idah bagi wani-ta hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah masa terlama dari dua masa idah. Jika masa terlama itu adalah empat bulan sepu-luh hari maka itulah masa idahnya. Jika masa kehamilan lebih lama daripada itu maka idahnya adalah hingga ia melahirkan.33
Seperti disinggung sebelumnya, mayoritas ulama memahami dari Surah al-Baqarah/2: 234 adanya dua hal yang harus dijalani seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu idah dan i¥dād. I¥dād berarti mencegah (imtinā‘), membatasi diri untuk tidak bersolek atau semisalnya sebagai tanda berkabung atas kematian suaminya atau keluarganya.34 Bila yang wafat bukan suaminya ma-ka i¥dād baginya hanya diwajibkan selama tiga hari. Dalam fikih disebutkan bahwa tujuan i¥dād adalah menyempurnakan penghor-matan seorang wanita atas suami dan memelihara haknya.35
Dalam hal ini tim MUI Sulsel mengikuti pemahaman ulama fikih klasik. Menurut mereka, seorang istri yang suaminya wafat tidak hanya dilarang untuk menikah selama masa idah, tetapi juga dilarang bersolek dan keluar rumah tanpa alasan yang diperboleh-kan oleh agama—misalnya adanya darurat—selama masa idah itu.36
Pertimbangan darurat itu juga tidak boleh bertentangan dengan maslahat.
Integrasi Nilai-nilai Budaya Bugis
Orang Bugis dikenal dengan prinsip siri’ (malu), lempu’ (keju-juran), dan paccing (kesucian). Pandangan ulama Bugis dalam ma-salah idah didasarkan pada hadis Nabi mengingatkan seorang istri
32‘Abdurra¥man bin Mu¥ammad ‘Au« al-Jazīrī, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Ma-
żāhib al-Arba‘ah, t.tp.: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1996, juz IV, hlm. 446. 33Mu¥ammad Mutawalli asy-Sya’rāwī, al-Mukhtār min Tafsīr al-Qur’ān al-
‘A§īm, Kairo: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th., jilid II, hlm. 1008. 34Ibnu Qudāmah, al-Mugnī fi Fiqh Imām as-Sunnah A¥mad bin ¦anbal asy-
Syaibānī, Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980, juz III, hlm. 289. 35‘Abdul-Barr an-Namīrī, al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī, Beirut:
Dar al-Kutub, 1992, hlm. 294. 36MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 351.
73 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 73
yang ditinggal wafat oleh suaminya agar tidak keluar rumah mem-pertontonkan dirinya di tengah orang banyak karena dikhawatirkan dapat mengundang perhatian kaum pria.37 Idah dan i¥dād menuntut kejujuran (lempu’) seorang wanita tentang apa yang ada dalam ra-himnya (haid dan janin), serta menjaga kesucian diri dan keturunan-nya. Prinsip kesucian diri dan keturunan itu sejalan dengan nilai paccing dalam budaya Bugis.
Pandangan di atas juga sejalan dengan budaya siri’38 dan pesse (solidaritas). Prinsip ini bagi masyarakat Bugis adalah sebagai nor-ma yang sangat dihormati karena merupakan bukti bahwa seorang istri dapat menjaga kesucian diri dan kehormatannya. Dalam kaitan ini, syair Bugis menyebutkan: “duw kual spo; auGn pnsea, eblon knukuea” - Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue- Artinya: “Dua (hal) yang kujadikan pagar (pelindung diri dan ke-hormatan), bunga nangka dan hiasan kuku.”39
Kata panasa pada unganna panasae bersinonim dengan kata lempu.40 Bila diberi tekanan glottal stop (‘) pada suku kata ter-akhir—menjadi lempu’—maka kata itu berubah maknanya menjadi kejujuran. Demikian pula kata belona kanukue, digunakan untuk hiasan kuku (belo kanuku) yang disebut pacci. Kata pacci bila
37MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 351. 38MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 351. Hadis tentang i¥dād dapat
ditemukan misalnya dalam riwayat al-Bukhārī, ¢a¥ī¥ al-Bukhārī, Damaskus: Dar Ibni Kasir, cet. 1, 2002, dalam Kitāb al-Janā’iz, Bāb I¥dād al-Mar’ah ‘alā Gair Zaujihā, no. 1281.
39Dalam tradisi Bugis ada dua norma yang sangat dihormati selain norma-norma agama, yaitu siri’ dan passe’. Siri’ adalah harga diri, yaitu suatu unsur yang sangat prinsipil dalam diri bagi orang Bugis. Bagi mereka, siri’ adalah jiwa, harga diri, dan martabat mereka. Lihat: Hamid Abdullah, Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar, Jakarta: Inti Dayu, 1985, hlm. 37. Adapaun pesse’ ada-lah rasa solidaritas sesama orang Bugis, yaitu suatu nilai dimana ikut merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap sesama. Lihat: Christian Pelras, Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abud dkk., The Bugis (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), hlm. 254. Bandingkan dengan: Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur’an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kaji-an terhadap Pemikiran-Pemikirannya,” Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidaya-tullah, 2008, hlm. 231-232.
40Mattulada, “Latoa; Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis,” Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1975, hlm. 13. Lihat pula: Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis…”, hlm. 232.
74 74 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
mendapat tambahan bunyi “ng” pada akhirnya—menjadi paccing—maka kata itu berubah arti menjadi tidak ternoda, bersih, atau suci. Dengan demikian, dapat diartikan “hanya dua yang bisa dijadikan pagar, yaitu kesucian dan kejujuran.” Konteks ini, sebagaimana ungkapan di atas, memberi pemahaman bahwa wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, demi terjaganya kesucian, tidak di-perkenankan keluar rumah selama masa idah tanpa alasan yang membolehkannya.
Ada dua pendapat dalam penetapan idah. Ada yang memahami dengan sangat ketat sehingga melarang seorang istri untuk melaku-kan hal-hal kecil sekalipun, seperti memakai sabun mandi, wangi-wangian, berbicara—termasuk menerima telepon dari lelaki yang bukan mahramnya, bahkan memakai jam tangan karena dinilai sebagai perhiasan. Dalam tafsir berbahasa Bugis yang ditulis oleh tim MUI Sulsel hal-hal seperti ini tidak diungkapkan. Dalam buku hanya dikatakan, mengutip pendapat Ibnu Ka£īr, bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menahan diri untuk tidak berdandan dan tetap berada di rumah selama masa idah.41 Larangan-larangan yang sangat detail seperti di atas bertentangan dengan se-mangat Islam, yaitu memberi kemudahan dan kelonggaran.
Kelompok kedua mamahami aturan idah dengan lebih toleran sehingga dalam waktu beberapa hari saja istri yang ditinggal wafat suaminya sudah boleh keluar rumah, menghadiri acara dengan ber-dandan seolah mengundang pria lain untuk segera menikahinya dan telah melupakan kedukaannya atas meninggalnya sang suami. Da-lam budaya Bugis, hal itu dinilai berpotensi mencederai perasaan keluarga suami. Dalam budaya Bugis dikenal prinsip asitinajang (kepatutan). Artinya, menikah tidak lama setelah meninggalnya sang suami dinilai tidak pantas dalam budaya Bugis karena bisa me-nyinggung perasaan keluarga suami yang wafat. Berbeda halnya ji-ka pernikahan dilakukan usai masa idah maka hal itu tidak dilarang.
Seperti disebutkan sebelumnya, penafsiran tim MUI Sulsel atas ayat idah di atas sejalan dengan pendapat para mufasir yang tidak hanya menetapkan idah, tetapi juga i¥dād. Dengan penafsiran se-perti itu maka buku ini seakan ingin berkata kepada masyarakat bahwa para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan
41Mukhlis (ed), Dinamika Bugis-Makassar, t.tp.: Pusat Latihan Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial dan YIIS, 1986, hlm.51.
75 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 75
ber-i¥dād karena secara moral dan kultural hal tersebut dapat men-jaga diri mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, wajar bila agama menetapkan agar perempuan yang suaminya meninggal dan masih dalam keadaan masa berkabung tetap berada di rumah. Ini tidak bisa dipahami bahwa agama ingin memasung aktivitas perempuan dan membatasi geraknya, melain-kan justru memberi petunjuk kepada pihak perempuan untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya,42 apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat Bugis yang memegang teguh ade’ (adat, atur-an). Ade’ yang dimaksud bukan hanya yang berhubungan dengan diri dan orang lain, tetapi juga hubungan dengan Allah. Ade’ mem-punyai nilai-nilai luhur yang menjadikan manusia mulia.
Menurut pemahaman masyarakat Bugis, ade’ adalah esensi ma-nusia. Ade’ itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia. Seorang yang tidak mengetahui, menghayati, dan memerankan diri dengan ade’ tidak dapat disebut manusia. Dari ade’ itulah manusia berpangkal. Tanpa ade’ yang menjadi pangkal kemanusiaan, apa yang disebut lempu’ (kejujuran), takwa kepada Allah dan memper-tinggi siri’ (harga diri, malu) sebagai nilai dan martabat kemanu-siaan, tidak mungkin terwujud. Siri’ harus ditegakkan oleh semua pihak. Ia tidak mungkin dipandang kewajiban satu pihak saja. Lon-tarak Bugis menyatakan:
Aksara Bugis Lontarak: “Naiy riaseeg albniige aiyp nsoku sipitgreeg nsiaolo ealo nsipkaige rigau ptujuea nsiaksirise risinin gau mk riposiriea” Transliterasi: “Naiyya riasengnge allaibinengeng iyyapa nasokku’ sipatangerengnge nasiolong elo nasipakainge rigau patujue nasiakkasiriseng risininna gau maka riposirie” 43
Artinya: “Kehidupan suami-istri (keluarga), hanya bisa sempurna apabila kedua belah pihak saling memberi pertimbangan, lalu sejalan kehendak, dan saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling melindungi dari semua hal-hal yang dapat merusak harga diri (memalukan)”.
42MUI Sulsel, Tafesere Akorang…, hlm. 351. 43Ade’ (adat) bagi orang Bugis adalah nilai dan harga diri mereka. Orang
yang memegang nilai ade’ (makkiade’) adalah dia yang mempunyai nilai dan harga diri.
76 76 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 187, “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” Pada ayat ini suami-istri dianalogikan sebagai pa-kaian yang di antara fungsinya adalah menutup anggota tubuh yang lazim ditutup—disebut aurat—agar tidak tampak karena ketampak-annya adalah hal yang memalukan. Ada kesamaan fungsi antara pakaian dengan fungsi suami-istri. Suami-istri diharapkan dapat saling melindungi dan menjaga aib pasangannya. Jadi, siri’ (harga diri) suami harus dijaga oleh istri, begitupun sebaliknya. Satu sama lain harus saling memelihara dan menghormati untuk mencegah timbulnya perbuatan atau tindakan yang memalukan (mappaka-siri’), perasaan malu (masiri’), dipermalukan (ripaksiri’),44 bukan hanya bagi pasangan suami-istri itu sendiri, tetapi juga bagi pihak keluarga keduanya.
Jika agama memberi tuntunan kepada seorang istri yang sua-minya wafat untuk tidak langsung beraktivitas di luar rumah maka hal itu sesungguhnya sejalan dengan tradisi masyarakat Bugis di atas. Jika demikian, idah merupakan ajaran agama yang sangat ma-nusiawi. Di samping sebagai ketentuan agama, idah juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga suami atau didasari oleh moral agama. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan keluarga suami bila istri yang ditinggalkannya dalam beberapa hari saja menikah dengan pria lain. Jadi, penetapan hukum Islam senantiasa mempertimbangkan aspek eksternal (budaya). Dalam nilai-nilai bu-daya Bugis ini disebut asitinajang (asas kepatutan).45 Jadi, orang Bugis yang masih tetap menjunjung tinggi nilai ini tidak terlalu mempersoalkan apakah tiga quru’ itu dipahami tiga haid atau tiga suci.
Dalam Al-Qur’an Allah mengingatkan agar suami-istri saling mengingat kebaikan dan jasa pasangannya. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 237 yang artinya, “…Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu.”46 Demikian sebaliknya, meski aga-ma tidak menetapkan idah bagi laki-laki jika istrinya meninggal, namun secara moral-budaya bukan berarti ia bisa buru-buru
44Benjamin Frederik Matthes, “Boegineesche Chrestomathie”, dalam Bica-
ranna Latoa, Amsterdam: Het Nederlan Bijbelgnootschap, 1874, hlm. 43. 45A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Yogyakarta:
Penerbit Ombak, 2011, hlm. xix-xx. 46A. Rahman Rahim, Nilai-nilai Utama…., hlm. xix - xx.
77 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 77
menikah beberapa hari kemudian. Dengan pertimbangan moral agama dan ade’ sipakatau, (etika saling menghormati) suami diha-rapkan untuk sebisa mungkin menangguhkan keinginannya untuk cepat menikah selama hal itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam konteks nilai budaya Bugis, ajaran tentang idah dan i¥dād juga sesuai dengan asas asitinajang (asas kepatutan).
Gagasan pemberlakuan idah bagi mantan suami memang me-ngagetkan, bukan saja karena ide itu dinilai kontroversial, tetapi juga karena tidak adanya dalil primer yang mendukungnya. Pertim-bangan psikologis antara perempuan dan laki-laki meniscayakan adanya pemberlakuan hukum Islam yang berbeda atas keduanya. Jangankan cerai—baik karena talak maupun karena meninggalnya istri—poligaini saja masih ditoleransi oleh Islam sepanjang tidak melanggar dalil-dalil yang lebih eksplisit, apalagi jika memang telah bercerai. Yang lebih dekat untuk dijadikan pertimbangan da-lam hal ini adalah nilai-nilai keaifan budaya (al-‘urf).
Nilai budaya asitinajang (kepatutan) merupakan suatu nilai yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menahan sejenak laki-laki untuk menikah demi menghargai keluarga pihak istri yang ma-sih dalam kondisi berkabung. Tentu saja, segera menikah setelah kematian istri bisa menambah duka cita bagi keluarga mantan istri. Karena itu, meski teks agama tidak melarang suami untuk segera menikah, namun demi kemaslahatan hubungan dan kesan positif maka lebih etis jika ia menunda pernikahan berikutnya hingga waktu yang patut (sitinaja). Bahkan, lebih etis lagi (sipakatau) jika ia meminta restu keluarga mantan istri apabila ingin menikah. Hal ini diharapkan lebih membawa maslahat hubungan dengan keluarga mantan istri.
Penutup
Diberlakukannnya masa idah bagi seorang perempuan bertu-juan menegakkan hak-hak istri sehingga ia tidak merasa tercampak-kan. Di samping itu, disyariatkannya idah dan i¥dād juga sejalan dengan pertimbangan etis-moral. I¥dād dalam konteks ini tidak berarti mewajibkan istri untuk menjalani larangan-larangan yang tidak manusiawi, seperti yang pernah berlaku pada masa jahiliah dimana seorang perempuan yang sedang menjalani masa idah dila-rang untuk sekadar menyisir rambut, memotong kuku, dan hal-hal
78 78 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
remeh semisalnya. I¥dād diberlakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan moral (kearifan lokal).
Kemajuan iptek dengan segala permasalahan yang menyertai-nya memang seringkali mempengaruhi pengambilan kesimpulan hukum Islam, tetapi roh maslahat yang sejatinya menjadi tujuannya tidak dapat dinafikan. Masalahat harus mencakup pencapaian keba-ikan dan proteksi terhadap mudarat harus tercapai secara simultan. Kemajuan iptek tidak dapat dijadikan alasan satu-satunya untuk menggugat aturan tentang idah, karena idah selain bertujuan me-mastikan kosongnya rahim demi menjaga keturunan, ia juga me-rupakan momentum untuk introspeksi diri dan menciptakan per-damaian (rujuk), karena perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Karena itu, interpretasi ayat-ayat tentang idah harus mampu menangkap roh maslahat dan mempertimbang-kan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat selama hal itu sejalan dengan prinsip maslahat. Maslahat yang berbasis pada kearifan lokal ini dikenal dalam Islam dengan istilah ‘al-‘urf’. Maslahat da-pat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak berten-tangan dengan dalil yang tegas dari Al-Qur’an dan sunah.
Masyarakat Bugis mempunyai budaya yang sarat dengan nilai kearifan, khususnya budaya siri’ (prinsip malu), lempu’ (kejujuran), paccing (kesucian), asitinajang (asas kepatutan), dan pesse (solida-ritas). Nilai-nilai ini menghiasi hidup dan perilakunya mereka, ke-cuali bagi mereka yang telah melupakan nilai-nilai budayanya sendiri. Masyarakat Bugis mempunyai dua landasan untuk hidup terhormat, yaitu agama dan budaya. Mereka dapat menjaga ketu-runan dan kehormatannya dengan prinsip budayanya dan konsisten-sinya terhadap pengamalan ajaran Islam. Islam dapat bersinergi dan terintegrasi dengan beberapa nilai budaya masyarakat Bugis. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam, yaitu tradisi yang baik dapat dijadikan asas hukum (al-‘ādah mu¥akkamah).[]
79 Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis — Muhammad Yusuf 79
Daftar Pustaka
Abdullah, Hamid, Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar. Jakarta: Inti Dayu, 1985.
Ahmad, Kadir, “Tranformasi Kelekturan di Pesantren al-Urwat al-Wutsqa”, da-lam Abd. Azis Bone, Transformasi Kelekturan di Pesantren Sulsel, Ujung-pandang: Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1993.
Al-An¡ārī, Zakariyā, Fat¥ al-Wahhāb Syar¥ Manhaj a¯-°ullāb, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
Al-Bukhārī, ¢a¥ī¥ al-Bukhārī, Damaskus: Dar Ibni Kasir, cet. 1, 2002
Ibnu ‘Abidīn, ¦āsyiyah Radd al-Mukhtār ‘ala ad-Dur al-Mukhtār, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Ibnu Ka£īr, Tafsīr al-Qur'ān al-'A§īm, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, cet. II, 2000.
Ibnu Qudāmah, al-Mugnī fī Fiqh Imām as-Sunnah A¥mad ibn ¦anbal asy-Syaibānī, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1980.
al-Jazīrī, ‘Au« bin Mu¥ammad, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Ma©āhib al-Arba‘ah, t.tp.: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, cet. I, 1996.
Matthes, Benjamin Frederik, “Boegineesche Chrestomathie”, dalam Bicaranna Latoa, Amsterdam: Het Nederlan Bijbelgnootschap, 1874.
Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
MUI Sulsel, Tafesere Akorang Mabbasa Ogi, Ujung Pandang: MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 1988.
Mukhlis (ed), Dinamika Bugis-Makassar, t.tp.: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan YIIS, cet. I, 1986.
Mursalim, “Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur’an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan; Kajian terhadap Pemikiran-Pemikiran-nya” Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
Muslim, ¢a¥ī¥ Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1991.
An-Namīrī, ‘Abd al-Barr, al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
Nasif, Fatimah Umar, Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam, Terj. Burhan Wirasubrat dan Kundan D. Nuryakien, Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001.
Pelras, Christian, Manusia Bugis, Terj. Abdul Rahman Abud dkk., Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris (EFEO), 2005.
80 80 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 59-80
Qu¯b, Sayyid, Fī ¨ilāl al-Qur'ān, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1992.
Rahim, A. Rahman, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Asy-Sya’rāwī, Mu¥ammad Mutawallī, al-Mukhtār min Tafsīr al-Qur’ān al-‘A§īm, Kairo: Maktabah at-Turas al-Islami, t.th.
Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary AZ (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1994.
Yusuf, Muhammad, “Perkembangan Tafsir Alquran di Sulawesi Selatan: Studi Kritis terhadap Tafesere Akorang Mabbasa Ogi Karya MUI Sulsel”, Diser-tasi, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010.
a©-ªahabī, Mu¥ammad ¦usain, asy-Syarī‘ah al-Islāmiyah: Dirāsah Muqāranah bayn Ahl as-Sunnah wa Ma©hab al-Ja‘fariyah, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1968.
Zein, Muhammad, dan Mukhtar al-Shodiq, Membangun Keluarga Humanis, Jakarta: Grahacipta, 2005.
Az-Zu¥ailī, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.
Tinjauan Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama di Jawa Timur
Reviewing the Distribution System of Qur’an in East Java
Ahmad Jaeni Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 [email protected] Naskah diterima: 24-02-2014; direvisi: 09-05-2014; disetujui: 23-05-2014. Abstrak Tulisan ini meninjau sistem distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama yang dinilai masih belum merata dan tepat sasaran, khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, distribusi mushaf Al-Qur’an yang selama ini dijalankan Kementerian Agama menganut sistem distribusi ganda (multi channel distribution system), yaitu sistem yang memungkinkan setiap kanal distribusi memainkan dua fungsi sekaligus, sebagai perantara dan penyalur. Meskipun cukup efektif mempercepat target proses distribusi, namun sistem ini membuka kemungkinan terjadinya sasaran distribusi yang tumpang tindih. Akibatnya, dis-tribusi menjadi tidak merata dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, membuat segmentasi sasaran distribusi pada setiap kanal distribusi menjadi sebuah tawaran solusi.
Kata kunci: sistem distribusi, mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Abstract This article reviews the distribution system of Qur’an carried out by Ministry of Religious Affairs in East Java. Based on the research results, the distribution of Qur’an adopts multi-channel distribution system, a system that enables every channel of the distribution plays two functions, as intermediary and retailer. Although quite effectively accelerate the distribution process, but this system opens the possibility of overlapping target distribution. As a result, the distribution is uneven and not well targeted. Thus, segmenting the target of the distribution in any distribution channel into an offer solutions.
Keywords: distribution system, Qur’an, Ministry of Religious Affairs
82 82 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
Pendahuluan Al-Qur’an adalah bacaan utama umat Islam, mayoritas pendu-
duk Indonesia. Keberadaannya yang begitu penting bagi umat Islam karena menjadi sumber pengetahuan, spiritual dan moral.1 Karena itu, ketersedian mushaf Al-Qur’an bagi setiap muslim Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kaitan ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan pengadaan Al-Qur’an dalam setiap tahunnya.
Upaya Kementerian Agama untuk melakukan pengadaan Al-Qur’an terus menunjukkan peningkatan. Ini bisa dilihat dari alokasi anggaraan yang disiapkan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2011 anggaran yang disiapkan untuk peng-adaan Al-Qur’an mencapai 22 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 55 miliar rupiah.2 Kecenderungan pening-katan alokasi anggaran tersebut tentu menggembirakan dan patut diapresiasi. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kebijakan pengadaan Al-Qur’an yang selama ini berlang-sung telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Islam, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an pada tahun 2011 dan 2012 tentang penggunaan mushaf Al-Qur’an menunjukkan kenyataan yang menarik. Ternyata dalam realitasnya, mushaf Al-Qur’an yang dimiliki dan digunakan masyarakat Islam hampir semuanya berasal dari cetakan penerbit swasta, bukan mushaf terbitan Kementerian Agama. Mushaf Ke-menterian Agama baru dijumpai di beberapa orang atau pihak yang mempunyai kaitan atau akses dengan Kementerian Agama setem-pat, seperti pimpinan organisasi atau pegawai di lingkungan Ke-menterian Agama sendiri.3 Ketiadaan Mushaf Kementerian Agama juga terjadi di sejumlah Mesjid Raya maupun Mesjid Agung.4 Bah-kan, sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di sejumlah daerah
1Abdullah bin Umar Baydawi, Anwār at-Tanzīl, Kairo: Ahmad Najib, 1887.
hlm. 45. Lihat. Mu¥ammad ¦useyn a¯-°aba'tab'iy, al-Mīzan fīi Tafsir al Qur’ān, Beirut: Mu'assasah al-‘²lamiy, 1975, Jilid II, hlm. 128-9.
2Tempo, 3 juli 2013. 3LPMA, Laporan Penelitian Penggunaan Al-Qur’an di Masyarakat, Jakar-
ta: LPMA, 2012. 4LPMA, Laporan Penelitian Penggunaan Al-Qur’an di Masyarakat, Jakar-
ta: LPMA, 2011.
83 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 83
mengaku belum mendapatkan mushaf Al-Qur’an terbitan Kemen-terian Agama ini.5
Beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan Al-Qur’an memang belum sepenuhnya dirasakan manfa-atnya secara merata oleh masyarakat Islam. Hal tersebut dalam pandangan Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, akibat proses distribusi yang belum berjalan baik. Menurutnya, seharusnya bukan masalah produksi yang dipermasalahkan, melainkan proses distri-businya. Kementerian Agama harus bisa menjamin proses distribusi berjalan baik.6
Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan un-tuk melihat sistem distribusi mushaf Al-Qur’an yang selama ini telah diterapkan oleh Kementerian Agama dan kenyataan distribusi mushaf Al-Qur’an yang masih belum merata dan tepat sasaran dengan mengambil studi kasus di Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem distribusi yang lebih baik. Batasan Konseptual Sistem Distribusi
Pengertian ‘distribusi’ pada dasarnya merujuk pada sebuah kegiatan atau aktivitas membagi atau penyaluran (pembagian, pe-ngiriman) kepada beberapa orang atau tempat.7 Dalam konteks penelitian ini distribusi yang dimaksud lebih merujuk pada penger-tian distribusi fisik (physical distribution), yaitu pemindahan barang yang telah jadi (finished goods products) dari jalur akhir produksi ke konsumen atau pengguna (the end user).8 Produsen di sini adalah Kementerian Agama Pusat, sedangkan konsumennya adalah masya-rakat muslim Indonesia.
5Untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang Ramadan, sejumlah KUA berinisiatif menghimpun mushaf Al-Qur’an dari setiap pengantin baru. Ahmad Jaeni dan Ahmad Badrudin, Laporan Monitoring Peredaran Al-Qur’an di Cilegon Banten. Jakarta: LPMA, 2011.
6Tempo, 4 Juli 2012. 7Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendi-
dikan Nasional, 2008, hlm. 359. 8Pengertian ini merujuk pada definisi yang dibuat oleh The National Coun-
cil of Physical Distribution Management (NCPDM). Lihat. Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic of Distribution Management: A Logistics Approach, India: Asoke K. Ghosh, 2005, hlm. 2.
84 84 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
Dalam sistem distribusi dikenl 3 istilah teknis yang menggam-barkan jalannya sebuah distribusi, yaitu saluran distribusi, pola distribusi dan mekanisme distribusi. Saluran distribusi berhubungan dengan struktur unit organisasi dalam perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen.9 Pola distri-busi terkait pilihan-pilihan saluran distribusi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.10 Sedangkan mekanisme distribusi berkenaan dengan pengaturan peran-peran masing-masing saluran untuk me-wujudkan distribusi yang efektif dan efisien.11Menurut Julian Dent12, pilihan terhadap beberapa pola distribusi biasanya diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan segmentasi peng-guna sebagai sasaran distribusi paling akhir (the end user). Hal ini dilakukan agar tujuan distribusi bisa diwujudkan secara efisien dan efektif. Terkadang pula untuk memenuhi target tertentu, kombinasi beberapa pola distribusi (a mix distribution models) juga dilaku-kan.13 Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama
Mushaf Al-Qur’an yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah mushaf yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kemen-terian Agama melalui anggaran APBN-P 2011 dan didistribusikan secara serentak di semester awal tahun 2012 ke seluruh Kantor Wilayah Provinsi dan sejumlah Kankemenag Kabupaten/Kota di Indonesia. Selain itu, mushaf yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam merupakan Mushaf Standar Usmani, salah satu dari tiga jenis Mushaf Standar Indonesia.14
9Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 28. 10Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 9. 11Vinod V. Sople, Logistic Management, India: Dorling Kindehrsley, 2007,
hlm. 134 12Julian Dent, Distribution Channels: Understanding and Managing Chan-
nels to Market, USA: Kogan Page, 2011, hlm. 13 13Julian Dent, Distribution Channels…, hlm. 15.
14Mushaf Standar Indonesia merupakan mushaf Al-Qur’an yang sistem penulisan, tanda baca dan tanda waqafnya disusun melalui Muker Ulama Ahli Al-Qur’an selama 9 kali (1963-1973) dan telah dikukuhkan berdasarkan Kete-tapan Menteri Agama (KMA) Nomor 25 tahun 1984. Melalui Intruksi Menteri Agama Nomor 07 tahun 1984, Mushaf Standar Indonesia ditetapkan sebagai referensi/pedoman penulisan dan penerbitan mushaf Al-Qur’an di Indonesia.
85 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 85
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (policy-oriented
research) yang didisain untuk memahami satu aspek atau lebih dari proses kebijakan publik15, khususnya terkait dengan distribusi mus-haf Al-Qur’an Kementerian Agama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga bersifat preskriptif (bersifat menentukan, memberi petunjuk) dalam rangka memberi-kan kontribusi pembuatan kebijakan.16 Penelitian dilakukan di Jawa Timur dengan mengambil dua tempat pengumpulan data lapangan, yaitu Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Timur dan Kankemenag Kabupaten Banyuwangi. Dua tempat ini diambil sebagai sampel karena secara geografis letaknya berjauhan sehingga dimungkinkan memiliki kompleksitas yang lebih dibanding lokasi lainnya yang relatif berdekatan.
Penelitiaan ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan un-tuk mencatat data distribusi mushaf Al-Qur’an, baik yang terkait dengan kebijakan, sistem, ataupun data tentang aliran distribusinya. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali perspektif dan persepsi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan masya-rakat17, seperti Kasi Bimas di Kanwil maupun Kankemenag Kota/ Kabupaten, serta Kepala KUA di sejumlah Kecamatan, termasuk tokoh dan masyarakat penerima. Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.
Dasar Kebijakan Distribusi Mushaf Al-Qur’an
Salah satu misi Kementerian Agama adalah mewujudkan kua-litas kehidupan beragama sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 62 Tahun 2005 Pasal 53.18 Selain bantuan yang bersifat fisik, berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, Kementerian Agama
Lihat. LPMA, Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: LPMA, 2013, hlm. 10.
15Saul Becker,Alan Bryman, Harry Ferguson (ed.), Understanding Research for Social Policy and Social Work: Themes, Methods and approaches, Amerika: The Policy Press, 2012, hlm. 7.
16Ibid. hlm. 14. 17Christine, Metode-metode Riset Kualitatif, Yogayakarta: Bentang, 2008,
hlm. 258. 18Diakses dari Kemenag.go.id tanggal 14 September 2013.
86 86 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
juga berupaya dalam hal penyediaan kitab suci bagi umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia.
Pengadaan mushaf Al-Qur’an di Kementerian Agama dilaksa-nakan oleh Ditjen Bimas Islam. Selain dalam hal pengadaan, Ditjen Bimas Islam juga bertanggung jawab dalam pendistribusiannya. Distribusi mushaf Al-Qur’an oleh Ditjen Bimas Islam telah dila-kukan dengan memanfaatkan struktur internal Kementerian Agama di daerah, baik Kanwil Provinsi maupun Kankemenag Kabupaten/ Kota, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.
Dasar kebijakan terkait distribusi mushaf Al-Qur’an memang belum diketahui secara jelas, namun merujuk sebuah surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam bersamaan diki-rimnya mushaf Al-Quran di setiap provinsi, dasar kebijakan peng-adaan dan distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama terse-but, khususnya yang bersumber dari APBN-P tahun 2011 sedikit agak tergambarkan.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan mushaf Al-Qur’an bagi masyarakat
kurang mampu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ditjen Bimas Islam dalam tahun 2011 mendapat dana tambahan untuk
pengadaan mushaf Al-Qur’an memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam rangka pemberantasan buta baca tulis Al-Qur’an dan program gerakan maghrib mengaji.
2. Dalam rangka memudahkan kontrol pengiriman mushaf, maka pendis-tribusian Al-Qur’an tersebut melalui kantor wilayah Kementrian Aga-
ma provinsi sesuai alokasi yang telah ditetapkan, agar disalurkan kepa-da mesjid/mushola/yayasan dan lembaga lainnya dengan cara menga-jukan permohonan ke kantor wilayah yang diketahui oleh Kantor
Urusan Agama kecamatan setempat. 3. Untuk keperluan tertib administrasi diminta Saudara setelah menerima
mushaf Al-Qur’an tersebut segera mengembalikan tanda terima ter-lampir kepada Ditjen Bimas Islam di sekretariat Ditjen Bimas Islam
dan kepada perusahaan pengiriman.19
Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bimas Islam di atas secara eksplisit telah menjelaskan dasar kebijakan, mekanis-me dan sasaran distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama,
19Surat nomor DJ.II.I/4/BA.00/445/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 ten-
tang Pengiriman Mushaf Al-Qur’an.
87 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 87
khususnya yang bersumber dari APBN-P tahun 2011. Dasar kebi-jakan pengadaan mushaf Al-Qur’an dengan demikian cukup jelas sebagai upaya Kementerian Agama untuk memenuhi kebutuhan mushaf Al-Qur’an, khususnya bagi kalangan masyarakat Islam yang tidak mampu. Dengan ketersedian mushaf Al-Qur’an ini diha-rapkan persoalan buta baca tulis di kalangan umat Islam bisa di-selesaikan. Seiring dengan itu, Gerakan Magrib Mengaji yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama dapat berjalan efektif.
Sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran bahwa sasar-an utama distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama adalah masyarakat Islam yang tidak mampu. Namun demikian, mekanisme distribusinya tetap melalui mesjid, mushola, yayasan atau lembaga lainnya dengan cara pengajukan permohonan (proposal) ke kantor wilayah terdekat yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama di ting-kat kecamatan. Mekanisme prosedural ini ditempuh dalam rangka mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap proses distribusi yang telah dilakukan. Peta Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Peta Distribusi Kemenag Pusat (Ditjen Bimas Islam)
Berdasarkan data dari Ditjen Bimas Islam, distribusi mushaf Al-Qur’an APBN-P tahun 2011 disalurkan ke sejumlah lembaga, tidak saja di lingkungan Kementerian Agama tetapi juga ke sejum-lah lembaga lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan.
Tabel. 1 Peta Distribusi Mushaf Kemenag APBN-P Tahun 2011
No Lembaga Penerima Jumlah (exp.) Persentase (%) 1 Ditjen Bimas Islam 240.672 36 2 33 Kanwil Kemenag Provinsi 335.690 51,4 3 50 Kankemenag Kab/Kota 49.000 7,5 4 LPMA 1.120 0,1 5 Dirjen Anggaran Kemenku 1.540 0,23 6 Komisi Anggaran DPR 24.978 38
Jumlah 653.000 100
Sebagaimana tergambar dalam tabel 1, persentase jumlah mus-
haf Al-Qur’an yang disalurkan ke daerah, baik melalui Kanwil maupun ke Kankemenag Kabupaten/Kota sebesar 59%. Jumlah ini tentunya masih harus dibagi ke 33 propinsi. Sisanya didistribusikan
88 88 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
ke lembaga-lembaga yang berkedudukan di Jakarta. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa jumlah persentasi distribusi mushaf Al-Qur’an yang terkosentrasi di Jakarta cukup besar, mencapai 41%, hampir separuh dari jumlah total mushaf yang dicetak/dipro-duksi.
Peta Distribusi Kemenag Pusat (Ditjen Bimas Islam) ke Sejumlah Wilayah
Sementara itu, jumlah mushaf yang didistribusikan ke setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.
Tabel. 2 Peta Distribusi Mushaf Kemenag APBN-P Tahun 2011
ke Beberapa Wilayah Indonesia
No Wilayah Kepulauan
Jumlah (Exp.) Porsi Terkecil (Kanwil)
Porsi Terbesar (Kanwil)
1 Sumatera 7.980 - 14.000 Bangka Belitung Lampung 2 Jawa 24.000 - 35.980 DIY Jateng, Jatim 3 Kalimantan 1.988 - 4.984 Kalbar, Kalteng Kalsel 4 Sulawesi 1.988 - 4.984 Sultra Sulsel 5 NTB, NTT, Bali 1.988 - 2.996 Bali, NTT NTB 6 Maluku, Papua 1.988 Maluku, Papua
Seperti ditunjukkan dalam tabel 2, jumlah terbesar distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama diterima oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah antara 24.000- 35.980 exp. Porsi terbanyak diterima oleh Kanwil Jawa Tengah dan Kanwil Jawa Timur, sedangkan porsi terkecil diterima Kanwil DIY. Yog-yakarta. Jumlah dengan urutan kedua diterima oleh provinsi-pro-vinsi di Pulau Sumatera, kemudian disusul Kanwil di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Papua.
Perbedaan porsi jumlah mushaf Al-Qur’an yang disalurkan ke setiap provinsi tentu didasarkan pada sebuah pertimbangan. Meski-pun belum diketahui secara pasti, namun nampaknya perbedaan jumlah porsi tersebut didasarkan pada jumlah populasi umat Islam yang ada. Ini bisa dilihat dari jumlah porsi terbesar diberikan ke-pada wilayah di Jawa yang mempunyai populasi umat Islam yang lebih banyak dibanding wilayah di luar Jawa. Selain itu, penentuan jumlah porsi merupakan ketetapan Ditjen Bimas Islam, bukan usul-
89 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 89
an masing-masing Kanwil Kemenag berdasarkan asumsi kebutuhan di daerahnya masing-masing. Kenyataan tersebut sebagaimana di-akui oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur20 dan Kankemenag Banyu-wangi21 yang tidak mengetahui dasar jumlah porsi yang diterima, melainkan hanya menerima saja dan selanjutnya mendistribusikan-nya.
Selain itu, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabu-paten/Kota tidak mendapatkan informasi yang cukup ketika proses distribusi mushaf Al-Qur’an akan dilakukan. Sebagaiamana diakui oleh pihak Kanwil, proses pengiriman mushaf Al-Qur’an dalam jumlah yang begitu besar dari Kementerian Agama Pusat tanpa memberi konfirmasi terlebih dahulu. Akibatnya, pihak Kanwil sempat terkejut dan tidak mempunyai kesiapan yang cukup untuk menerima barang dalam jumlah besar tersebut. Tentu ini sangat dimaklumi, karena Kanwil tidak mempunyai tempat yang represen-tatif sebagai gudang penyimpanan sementara (temporary ware-house). Sedangkan penyimpanan mushaf Al-Qur’an harus di dalam ruangan yang kering, tidak lembab dan tertutup.
Distribusi Mushaf Al-Qur’an di Jawa Timur Peta Distribusi
Berdasarkan data dari Urais Bimas Islam Kemenag Pusat dan data di Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur, distribusi mushaf Al-Qur’an dari Kemenag Pusat untuk wilayah Jawa Timur dila-kukan pada bulan Maret dan diterima oleh Kanwil Prov. Jatim pada bulan yang sama.
Tabel. 3
Daftar Distribusi Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI dari APBN-P Tahun 2011 untuk wilayah Jawa Timur. 22
20 Wawancara dengan Kasi Bimas Kanwil Provinsi Jawa Timur, 1 Juli
2013. 21 Wawancara dengan Kasi Bimas Kankemenag Banyuwangi, 4 Juli 2013. 22Laporan Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur’an
Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2012.
No Penerima Jumlah 1 Kanwil Kemenag Prov. Jatim 1285 dus X@ 28 = 35.980 exp. 2 Kankemenag Kota Pasuruan 35 dus X @ 28 = 980 exp. 3 Kankemenag Kota Batu 35 dus X @ 28 = 980 exp. 4 Kankemenag Kab. Pasuruan 35 dus X @ 28 = 980 exp.
90 90 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi mushaf Al-Qur’an dari APBN-P Tahun 2011 belum diterima secara merata oleh Kan-kemenag Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Timur, karena dari 38 kankemenag yang ada, hanya 9 Kankemenag yang mene-rima langsung distribusi mushaf Al-Qur’an dari Kemenag Pusat, yaitu 2 Kankemenag Kota (Pasuruan dan Batu) dan 7 Kankemenag Kabupaten (Pasuruan, Jombang, Tuban, Bangkalan, Sampang, Jember dan Banyuwangi). Selain itu, jumlah yang diterima kanwil lebih besar dibanding yang diterima kankemenag. Perbedaan jum-lah ini tentu dapat dimaklumi, karena dengan demikian, kanwil mempunyai keleluasaan untuk mendistribusikan kepada setiap Kan-kemenag yang belum menerima kiriman mushaf Al-Qur’an sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pola Distribusi
Kementerian Agama mempunyai struktur organisasi yang cu-kup lengkap dari pusat hingga daerah. Keberadaan struktur organi-sasi ini tentu sangat menguntungkan ketika distribusi akan dilaku-kan. Setiap struktur akan menjadi saluran distribusi (channel of dis-tribution) yang secara efektif bisa langsung dijalankan.
Mencermati gambaran peta distribusi mushaf Al-Qur’an—sebagaimana dijelaskan sebelumnya—Kementerian Agama Pusat tampaknya mempunyai pilihan yang beragam dalam menentukan saluran distribusi di suatu daerah/wilayah. Setidaknya terkait distri-busi mushaf Al-Qur’an APBN-P tahun 2011 ke sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ada dua pola distribusi yang ditempuh oleh Kementerian Agama Pusat. Pertama, aliran distri-busi melalui Kanwil. Dari Kanwil, baru diteruskan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. Kedua, aliran distribusi langsung ke Kankemenag Kabupaten/Kota tanpa melalui kanal Kanwil. Kedua pola tersebut dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut.
5 Kankemenag Kab. Bangkalan 35 dus X @ 28 = 980 exp. 6 Kankemenag Kab. Sampang 35 dus X @ 28 = 980 exp. 7 Kankemenag Kab. Jombang 35 dus X @ 28 = 980 exp. 8 Kankemenag Kab. Tuban 35 dus X @ 28 = 980 exp. 9 Kankemenag Kab. Jember 35 dus X @ 28 = 980 exp. 10 Kankemenag Kab. Banyuwangi 35 dus X @ 28 = 980 exp. Jumlah 1600 dus x @28 = 44.800 exp.
91 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 91
Bagan 1. Pola Distribusi Mushaf Kemenag di Jatim
Pola 1 Pola 2
KP = Kemenag Pusat = Arah Distribusi K1 = Kanwil Kemenag Prov. = Dikirim K2 = Kankemenag Kab./Kota = Diambil Dalam bagan pola saluran distribusi di atas Kemenag Pusat
(KP) menjadi produsen sekaligus distributor pertama yang menen-tukan pola distribusi yang akan diterapkan. Jika meminjam konsep Julian Dent23 pola pertama disebut distribusi tingkat 2 (two-tier distribution), yaitu distribusi dengan melibatkan saluran distribusi lainnya. Sedangkan pola kedua disebut distribusi dengan banyak tingkatan (multiple tired distribution system), yaitu distribusi de-ngan melibatkan beberapa saluran distribusi. Merujuk data dari Bimas Islam, pola pertama juga diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara pola kedua hanya diterapkan beberapa pro-vinsi saja, yaitu Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat.
Pada tingkat distribusi dari Kemenag Pusat ke Kanwil Kemenag Provinsi (pola 1) maupun ke Kankemenag Kabupaten/Kota (pola 2) tidak ada masalah berarti. Semua bisa terlaksana secara baik. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena proses distribusi dari KP ke K1 ataupun K2 menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu sebuah jasa pengiriman barang. Sudah barang tentu, penggunaan jasa pe-ngiriman barang tersebut karena tersedianya anggaran yang dimiliki Kementerian Agama Pusat.
Sementara dalam proses distribusi dari Kanwil Kemenag Pro-vinsi ke Kankemenag Kabupaten/Kota (pola 1) ditemukan kasus beragam. Meskipun dapat memberikan keleluasaan kepada Kanwil Kemenag provinsi Jawa Timur untuk mendistribusikan sesuai de-ngan kebutuhan di wilayahnya, namun pola ini membuat Kanwil
23Julian Dent, Distribution Channels …, hlm. 13.
K P K 1 K 2
K P K 2
92 92 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
harus menghadapi beberapa persoalan. Selain belum adanya keter-sediaan gudang penyimpanan sementara (temporary warehouse), Kanwil juga menghadapi kendala terkait ketiadaan dana/anggaran pegiriman ke sejumlah Kankemenag. Kondisi ini menyebabkan proses distribusi tidak segera bisa dilakukan. Sebagai alternatifnya, Kanwil meminta masing-masing Kankemenag untuk mengambil sendiri. Namun, kondisi serupa juga dihadapi oleh kankemenag. Karena ketiadaan anggaran, jatah mushaf Al-Qur’an dari Kanwil tidak dapat segera diambil. Terlebih dengan letak geografis yang berjauhan, sejumlah Kankemenag harus berfikir keras untuk dapat mengambil jatah tersebut.
Berdasarkan kenyataan tersebut, Kankemenag Banyuwangi me-nilai sistem distribusi dengan pola pertama lebih efisien, karena tidak membutuhkan biaya transportasi untuk pengambilan di Kan-wil Kemenag Jawa Timur. Begitu pula bagi Kanwil, distribusi de-ngan mengambil pola pertama dapat mengurangi beban Kanwil dalam mendistribusikan mushaf ke sejumlah kankemenag di ba-wahnya.
Sistem Distribusi Ganda
Orientasi distribusi produk komersial memang berbeda dengan produk non-komersial. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap sistem distribusi yang akan diterapkan. Dalam distribusi produk komersial, setiap saluran distribusi biasanya memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda-beda. Karena jika tidak, akan terjadi kon-flik kepentingan antar saluran dalam merebutkan profit. Inilah yang dalam istilah pemasaran disebut sebagai sistem pemasaran vertikal (vertical marketing system) atau sistem distribusi vertikal (vertical distribution system). Dalam sistem ini, hanya saluran distribusi pa-ling akhir/bawah (pengecer, pedagang) yang berhak memasarkan langsung kepada konsumen atau pengguna terakhir (the end user).24
Tentu ini berbeda dengan fungsi saluran di dalam distribusi produk non-komersial. Setiap saluran distribusi di setiap level bisa mempunyai fungsi sama, meskipun masing-masing saluran mempu-nyai wilayah kerja yang berbeda. Dalam dunia marketing model seperti ini sering diistilahkan sebagai sistem saluran pemasaran
24Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketing 15th Global
Edition, USA: Pearson Education, 2012, hlm. 370.
93 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 93
ganda (multichannel marketing system) atau saluran distribusi ganda (multichannel distribution system).25 Sistem yang terakhir ini tampaknya cukup menggambarkan distribusi mushaf Al-Qur’an di lingkungan Kementerian Agama yang selama ini berjalan.
Bagan 2
Sistem Distribusi Ganda (Multi Channel Distribution System)
= perantara antar saluran (intermedier)
= penyalur langsung (retailer) pada masyarakat pengguna
Penerapan sistem saluran distribusi ganda (multichannel distri-
bution system) seperti gambaran bagan di atas diakui membantu target distribusi dapat dilakukan lebih cepat, karena semua saluran distribusi di semua tingkatan bersama-sama berperan sebagai peng-ecer atau penyalur langsung (retailer, direct distributor) kepada pengguna. Kemenag Pusat dan Kanwil tidak hanya berperan seba-gai perantara (intermedier) terhadap saluran di bawahnya, namun juga bisa berperan sebagai pengecer. Namun, sistem model ini tidak lepas dari kelemahan. Belum adanya aturan terkait segmentasi sasaran distribusi di setiap saluran distribusi membuka kemung-kinan terjadinya sasaran distribusi yang tumpang tindih. Misalnya, sejumlah sasaran distribusi seperti mesjid atau lembaga lain yang berada di wilayah kabupaten/kota tidak hanya dapat mengajukan permohonan kepada Kankemenag, tetapi secara bersamaan juga dapat mengajukan kepada Kanwil, dan bahkan ke Kemenag Pusat.
25Satish K. Kapoor dan Purva Kansal, Basic …, hlm. 36.
DITJEN BIMAS ISLAM
KANWIL KEMENAG ROVINSI
KANKEMENAG KAB./KOTA
ORMAS, MASJID, MUSALA, MAJELIS TAKLIM, DLL
94 94 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
Sehingga sangat dimaklumi, jika beberapa sasaran distribusi terse-but dapat memperoleh mushaf Al-Qur’an dari Kankemenag, Kanwil dan Kemenag Pusat.
Sementara itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai struktur terbawah Kementerian Agama dan yang paling dekat dengan ma-syarakat, sejauh ini belum terlibat langsung dalam struktur sistem distribusi mushaf Al-Qur’an. Peran KUA masih sebatas membantu dalam hal sosialisasi, belum berperan sebagai distributor (retailer) secara langsung.26 Pusat distribusi yang paling bawah, dengan demi-kian, masih berada di tingkat Kankemenag. Jangkauan Kankemenag dengan sasaran distribusi di wilayah kecamatan maupun desa/kelu-rahan dinilai masih terlalu jauh, sehingga menjadikan peta penye-baran distribusi mushaf Kementerian Agama belum sepenuhnya merata karena sangat dipengaruhi oleh akses informasi dan keterse-diaan transportasi.
Sasaran dan Mekanisme Distribusi Seperti disebutkan dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam
terkait distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, yang menjadi sasaran distribusi (the end user) mushaf Al-Qur’an adalah masyarakat Islam yang kurang mampu. Meskipun demikian, meka-nismenya tetap dilakukan secara prosedural dengan cara pengajuan proposal. Sedangkan pengajuan proposal harus dilakukan melalui lembaga atau organisasi, seperti mesjid, musala, pesantren, TPA, atau yang lainnya, bukan individu. Dalam penelitian ini, ditemukan keragaman latar belakang pengaju proposal, sebagaimana ditemu-kan di Kankemenag Banyuwangi seperti tergambar dalam tabel berikut.
Tabel 4
Distribusi Mushaf Al-Qur’an di Kankemenag Banyuwangi
No Penerima Jumlah Lembaga Jumlah mushaf 1 TPQ 30 598 exp. 2 Musala 12 262 exp. 3 Mesjid 9 150 exp. 4 Pesantren 6 105 exp. 5 Majis Taklim 3 50 exp. 6 Sekolah 13 214 exp.
26Wawancara dengan Kepala KUA Srono dan Kepala KUA Srono Banyu-
wangi, 5 Jui 2013.
95 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 95
7 Panti Asuhan 1 20 exp. 8 Nahdatul Ulama 1 15 exp. 9 HMI 1 20 exp. 10 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 1 15 exp. Jumlah 77 1.399 exp.
Tabel 4 di atas memperlihatkan peta aliran distribusi mushaf Al-Qur’an ke sejumlah sasaran distribusi di Banyuwangi. Distribusi dengan jumlah terbesar diterima Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Jumlah ini tentu dipengaruhi jumlah proposal yang masuk, bukan karena kebijakan yang diambil Kankemenag setempat. Selain itu, di TPQ kebutuhan terhadap mushaf Al-Qur’an memang sangat realistis, karena kenaikan santri pada level Al-Qur’an bisa terjadi setiap saat. Di samping faktor tersebut, hampir setiap penyuluh di KUA membina TPQ di tempatnya masing-masing.
Mekanisme distribusi ditempuh melalui prosedur pengajuan proposal memang bertujuan agar proses distribusi mudah dimonitor dan dikontrol. Namun di sisi lain, kelemahan dari sistem ini juga tidak bisa dihindarkan. Peta aliran distribusi mushaf Al-Qur’an ke sasaran distribusi, baik di tingkat Kanwil maupun Kankemenag menunjukkan penyebaran yang tidak merata. Beberapa sasaran dis-tribusi, seperti masjid, musala atau organisasi lainnya, selalu men-dapatkan mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama dalam setiap ta-hunnya, namun sejumlah sasaran distribusi lainnya tidak pernah mendapatkan.27 Kenyataan ini disebabkan oleh informasi yang tidak merata diterima oleh setiap pengurus musala atau mesjid. Sehingga kecenderungannya, musala atau mesjid yang mendapatkan aliran distribusi mushaf adalah musala atau mesjid yang mempunyai akses dengan Kementerian Agama.28
Beberapa Faktor Pemerataan Distribusi
Distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama yang belum merata merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Sejumlah persoalan yang menjadi sebab telah diuraikan sebelumnya, dan berikut ini beberapa hal yang perlu
27Wawancara dengan ustaz Bunyamin, salah satu pengurus Musala di daerah
Waru, Surabaya, 3 Juli 2013. 28Wawancara dengan Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, 3 Juli
2013.
96 96 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
dipertimbangkan untuk mewujudkan distribusi mushaf Al-Qur’an menjadi lebih merata dan tepat sasaran, yaitu antara lain:
a. Akses informasi yang terbuka dan merata Mekanisme prosedural yang harus ditempuh untuk mendapat-
kan mushaf Al-Qur’an meniscahyakan adanya informasi yang terbuka dan merata bagi seluruh masyarakat atau titik-titik yang menjadi sasaran distribusi. Dengan demikian, semua sasaran distri-busi mempunyai kesempatan sama untuk mengajukan dan menda-patkan mushaf yang diberikan secara gratis itu. Namun memang harus diakui, meskipun akses informasi terkait adanya distribusi mushaf Al-Qur’an sudah terbuka, tetapi memang belum merata menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Seperti ditemukan dalam penelitian ini, beberapa sampel penerima mushaf Al-Qur’an pada umumnya mempunyai akses dengan Kementerian Agama setempat. Di sisi lain, kenyataan ini tentu harus dimaklumi, karena jika akses informasi benar-benar terbuka dan merata, sedangkan ketersediaan jumlah mushaf terbatas, maka tentu Kementerian Agama tidak mungkin dapat memenuhi permintaan (demand) yang datang. Memang sangat problematis. Jika demikian keadaannya, menentukan skala prioritas terhadap sasaran distribusi adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan. Apalagi pengadaan mushaf Al-Qur’an akan dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah.
b. Menguatkan Peran KUA Pusat distribusi mushaf Al-Qur’an yang masih terpusat di
Kankemenag dan Kanwil membuat letak geografis menjadi salah satu faktor pemerataan distribusi. Daerah yang jauh dari saluran/ pusat distribusi akan menghadapi tantangan tersendiri untuk men-dapatkan distribusi mushaf. Sekalipun akses informasi tersedia, namun jika letaknya begitu jauh dari pusat distribusi dan membu-tuhkan cost yang tinggi, tentu keinginan untuk mendapatkan mushaf Al-Qur’an sangat berat dilakukan. Oleh karena itu, menjadikan KUA sebagai salah satu saluran dan pusat distribusi menjadi alter-natif yang perlu dilakukan. Dengan demikian, jarak antara pusat distribusi dengan sasaran distribusi akan lebih dekat, sehingga proses distribusi lebih mudah dilakukan. Keuntungan lainnya, akses informasi bisa lebih merata dan biaya transportasi bisa ditekan. Selain itu, sebagai struktur Kementerian Agama yang paling bawah
97 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 97
di tingkat kecamatan, KUA mempunyai data-data tentang kondisi masyarakat yang lebih aktual, sehingga kesalahan dalam menentu-kan sasaran distribusi dapat dihindari. Dengan peran KUA yang lebih optimal dalam sistem distribusi di Kementerian Agama, ha-rapan terwujudnya distribusi mushaf Al-Qur’an yang lebih merata dan tepat sasaran dapat diupayakan.
c. Penggunaan data-data keagamaan Proses distribusi mushaf Al-Qur’an tampaknya belum meman-
fatkan data-data keagamaan secara lebih maksimal. Mekanisme prosedural cenderung membuat proses distribusi lebih bersifat pasif. Pusat-pusat distribusi di semua tingkatan saluran/kanal distribusi belum bergerak aktif dengan memanfaatkan data-data keagamaan sebagai basis dalam menentukan sasaran distribusi. Memang di be-berapa tempat, proses distribusi telah dilakukan lebih aktif dengan mendatangi langsung sasaran distribusi, namun persentase ini sangat sedikit dan biasanya hanya bersifat aksidental. Safari Rama-dan, kunjungan kerja, dan bentuk kegiatan sejenisnya, biasanya menjadi cara efektif untuk menyalurkan mushaf Al-Qur’an secara langsung. Oleh sebab itu, penggunaan data-data keagamaan, baik di Kemenag Pusat, Kanwil, Kankemenag maupun di KUA menjadi sebuah keharusan. Manfaat utama data-data keagamaan adalah sebagai bahan untuk melakukan pemetaan kebutuhan di masing-masing daerah dan menentukan skala prioritas terhadap sasaran distribusi. Selain itu, data-data tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi terpusatnya distribusi pada sasaran distribusi ter-tentu. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya distribusi yang tidak tepat sasaran bisa dihindari dan pemerataan distribusi bisa diwujudkan.
d. Membuat segmentasi sasaran distribusi Segmentasi sasaran distribusi menjadi penting dibuat untuk
mengantisipasi ekses dari penerapan sistem distribusi ganda. Sistem yang diterapkan untuk mendistribusikan mushaf Al-Qur’an ini memang dapat mempercepat target distribusi, karena semua saluran distribusi ikut menjadi penyalur, namun potensi terjadinya penum-pukan distribusi pada sasaran distribusi tertentu sangat mungkin terjadi. Segmentasi dapat disusun berdasarkan tingkatan saluran distribusi. Sasaran distribusi pada tingkat Kemenag pusat harus dibedakan dengan sasaran distribusi di tingkat Kanwil, Kankeme-
98 98 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
nag maupun KUA. Dengan adanya segmentasi sasaran distribusi di setiap tingkatan saluran distribusi, tidak saja target distribusi yang dapat dicapai, namun pemerataan distribusi juga bisa diwujudkan.
Beberapa hal di atas merupakan bahan untuk menyempurnakan sistem distribusi yang telah ada agar pemerataan distribusi bisa terwujud dan kesalahan sasaran distribusi dapat dihindari. Adapun terkait pelaksanaan distribusi sendiri, tentu ada sejumlah masalah teknis lainnya yang juga harus mendapat perhatian, seperti keter-sediaan anggaran, gudang penyimpanan, dan faktor pendukung lainnya.
Penutup Simpulan
Distribusi mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama dilakukan dengan memanfatkan semua struktur Kementerian Agama di daerah sebagai saluran distribusinya. Distribusi ke daerah dilakukan de-ngan dua pola, distribusi ke Kanwil Kemenag Provinsi dan distri-busi langsung ke Kankemenag Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemen-terian Agama menganut sistem saluran distribusi ganda (multi channel distribution system) yang memungkinkan setiap saluran distribusi dapat melakukan dua tugas sekaligus, baik penyalur (retailer) maupun perantara (middlemen). Keuntungan sistem ini dapat mempercepat distribusi mushaf Al-Qur’an sampai pada sasaran distribusi. Namun di sisi lain, sistem ini berpotensi mem-buat sasaran distribusi menjadi tumpang tindih, sehingga distribusi mushaf Al-Qur’an tidak merata dan tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi ekses penerapan sistem tersebut sejumlah faktor bisa ditawarkan, seperti penyediaan akses informasi yang merata, pe-nguatan peran KUA, penggunaan data-data keagamaan dan penyu-sunan segmentasi sasaran distribusi.
Rekomendasi
Kemenag pusat diharapkan dapat membuat petunjuk teknis (juknis) distribusi mushaf Al-Qur’an secara menyeluruh, baik ter-kait pola distribusi, saluran distribusi dan segmentasi sasaran distri-busi. Dalam hal tersebut, Kemenag pusat, Kanwil, dan Kankemenag diharapkan dapat memanfaatkan data-data keagamaan untuk me-metakan sasaran distribusi.
99 Tinjauan Sistem Distribusi Al-Qur’an di Jawa Timur — Ahmad Jaeni 99
Di pihak lain, Kanwil dan Kankemenag diharapkan dapat menyiapkan alokasi anggaran untuk menunjang distribusi mushaf Al-Qur’an ke sejumlah sasaran distribusi. Daftar Pustaka
Arifin M, Zaenal, ‘Mengenal Mushaf Standar Usmani Indonesia’, dalam Jurnal
Suhuf, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
Baydawi, ‘Abdullāh bin ‘Umar, Anw±r at-Tanzīl, Kairo: A¥mad Najīb, 1887.
Daymon, Christine, Metode-metode Riset Kualitatif, Yogyakarta: Bentang, 2008.
Dent, Julian, Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market, USA: Kogan Page, 2011.
K. Kapoor, Satish dan Purva Kansal, Basic of Distribution Management: A Logistics Approach, India: Asoke K. Ghosh, 2005.
Kotler, Philip, Gary Armstrong, Principles of Marketing 15th Global Edition, USA: Pearson Education, 2012.
Harry Ferguson, Saul Becker, Alan Bryman, (ed.), Understanding Research for Social Policy and Social Work: Themes, Methods and approaches, Amerika, The Policy Press, 2012.
Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasio-nal, 2008.
Laporan Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur’an Dirjen Bimas Tahun 2012.
LPMA, Laporan Penelitian Mushaf Al-Qur’an dalam Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2011.
LPMA, Laporan Penelitian Mushaf Al-Qur’an dalam Masyarakat, Jakarta: LPMA, 2012.
LPMA, Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: LPMA, 2013.
Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan-nya. Jakarta: Grasindo.
Ramachandran, Sai, Distribution and Sales Management, New Delhi: Sunil Sachdev, 2005.
a¯-°aba'tab'iy, Mu¥ammad ¦usain, al-Mīzan fī Tafsīr al-Qur’ān, Beirut: Mu'as-sasah al-‘²lamiy, 1975.
V. Sople, Vinod, Logistic Management, India: Dorling Kindehrsley, 2007.
100 100 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014: 81-100
W. McCalley, Russell, Marketing Channel Development and Management,
(USA: Quorum Books, 1992).
Tempo, 4 Juli 2012.
Laporan Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur’an Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2012.
Surat nomor DJ.II.I/4/BA.00/445/2012 tertanggal 16 Pebruarai 2012 tentang Pengiriman Mushaf Al-Qur’an.
Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, 1 Juli 2013.
Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Banyuwangi, 4 Juli 2013.
Wawancara dengan Kepala KUA Rogojampi Banyuwangi, 5 Juli 2013.
Wawancara dengan Kepala KUA Srono Banyuwangi, 5 Juli 2013.
Wawancara dengan Staf KUA Purwoharjo Banyuwangi, 5 Juli 203.
Wawancara dengan Imam Masjid Raya Surabaya, 4 Juli 2013.
Manuskrip Al-Qur'an dari Sulawesi Barat Kajian Beberapa Aspek Kodikologi
Qur'an Manuscripts from West Sulawesi Study of some aspects of codicology Ali Akbar Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 [email protected] Naskah diterima: 15-04-2014; direvisi: 07-05-2014; disetujui: 16-05-2014. Bayt al-Qur’an & Museum Istiqlal, Abstrak Artikel ini mengkaji delapan mushaf Al-Qur’a kuno dari Sulawesi Barat, semuanya dari koleksi perorangan. Bagian pertama tulisan ini mendeskripsi masing-masing mushaf, dan selanjutnya membahas sisi teks Al-Qur’an serta teks-teks tambahan lainnya, baik di bagian awal maupun akhir mushaf. Mushaf Al-Qur’an yang dikaji berasal dan merupakan tradisi mushaf Bugis, meskipun saat ini milik orang di Mandar, Sulawesi Barat. Rasm usmani dalam mushaf banyak digunakan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Wajo dan Bone, pada abad ke-19. Hal itu juga dilengkapi dengan bacaan qirā’āt sab‘ yang disertakan di bagian tepi mushaf. Dari delapan mushaf yang dikaji dalam tulisan ini hanya satu mushaf yang tidak memiliki catatan qira’at.
Kata kunci: mushaf kuno, Sulawesi Barat, iluminasi, Bugis, Al-Qur’an. Abstract This article examines eight ancient Qur’ans of West Sulawesi. All of those manuscripts are from individual collections. The first part of this paper describes each of the manuscripts, and then discusses the text of the Qur'an as well as other additional texts, either at the beginning or at the end of manuscripts. The Qur’an which is studied in this article comes from the Bugis and becomes its tradition, although currently it is belonged to someone in Mandar, West Sulawesi. Rasm uthmani in the manuscript had been widely used in South Sulawesi, including Wajo and Bone, in the 19th century. The manuscript was also equipped with the reading of qira'at sab’ (seven styles of reciting the Qur’an) which is attached at the edge of the Qur’an. Of the eight Qur’ans reviewed in this paper, it was only one which has not a record of the qira'at note.
Keywords: ancient Qur’an, West Sulawesi, illumination, Bugis.
102 102 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
Pendahuluan Sejak sekitar satu dasawarsa terakhir telah terbit sejumlah
kajian tentang mushaf Nusantara dalam bentuk artikel di jurnal atau buku kumpulan tulisan, yang terbit di Indonesia atau di luar negeri. Meskipun demikian, berbagai aspek mushaf kuno Nusantara masih perlu penelitian lebih lanjut. Aspek-aspek mushaf, baik menyang-kut sejarah penulisannya, rasm, qiraat, terjemahan bahasa Melayu atau bahasa daerah lainnya, maupun sisi visualnya, yaitu iluminasi dan kaligrafi, masih banyak yang belum terungkap secara jelas. Be-berapa buku dan katalog pameran Al-Qur’an atau seni Islam hanya sedikit menyinggung mushaf-mushaf dari Nusantara.
Selama beberapa tahun terakhir telah muncul sejumlah pene-litian tentang mushaf kuno di Sulawesi yang ditulis oleh beberapa peneliti, yaitu 1) “Mushaf kuno di Sulawesi” ditulis oleh Bunyamin Surur dimuat dalam buku Mushaf-mushaf kuno di Indonesia (Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005); 2) “Mushaf kuno di Provinsi Sulawesi Tenggara” oleh Munawiroh (Lektur, Vol. 5, No.1, 2007); 3) “The Bone Qur’an from South Sulawesi” dalam Treasures of the Aga Khan Museum: Arts of the Book and Calligra-phy oleh Annabel Teh Gallop dalam Margaret S. Grases and Benoit Junod (eds.), Istanbul: Aga Khan Trust for Culture and Sakıp Sabancı University & Museum, 2010, pp.162-173; dan 4) “Migra-ting manuscript art: Sulawesi diaspora styles of illumination”, sebuah kertas kerja yang disampaikan Annabel Teh Gallop di Universitas Sydney pada 21 Juni 2007.
Empat tulisan di atas tidak membicarakan mushaf Al-Qur’an di Sulawesi Barat, namun dapat memberikan gambaran mengenai tra-disi mushaf di Sulawesi Selatan secara umum, dan menjadi bahan bandingan bagi kajian ini. Penelitian lain yang lebih terkait lang-sung dengan penelitian ini adalah “Tinggalan-tinggalan Islam di Majene Sulawesi Barat” yang dilakukan oleh Idham pada 2010. Penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Lektur Keaga-maan itu mencatat adanya tiga mushaf di Majene. Penelitian terakhir ini merupakan penelitian penjajakan, sehingga data dan pembahasannya terbatas. Ketiga mushaf tersebut dalam tulisan ini dibahas kembali, dan dilengkapi dengan mushaf-mushaf lainnya sehingga terkumpul delapan mushaf yang menjadi bahan kajian ini.
Bagian pertama tulisan mendeskripsi masing-masing mushaf, dan bagian selanjutnya membahas mushaf dari segi teks Al-Qur’an
103 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 103
serta teks-teks tambahan lainnya, baik di bagian awal maupun akhir mushaf. Deskripsi Mushaf
Mushaf A Mushaf ini adalah milik Hj. Nuryena Atjo, Majene, Sulawesi
Barat. Ukuran mushaf 31,5 x 23 cm, tebal 6 cm. Ukuran teks 23 x 13 cm. Cap kertas moonface dengan cap tandingan huruf “VG” (Valentino Galvani). Menurut Russell Jones,1 kertas berciri seperti itu berasal dari Italia, sekitar tahun 1833-1840. Pemilik mushaf mewarisinya dari KH. Abdur Rasyid, kakek buyutnya dari jalur ibu, seorang kadi (hakim agama). Abdur Rasyid dahulu tinggal di Wajo selama puluhan tahun.
Mushaf yang mempunyai catatan qiraat lengkap ini berilumi-nasi gaya floral yang sangat istimewa, terdapat di awal, tengah, dan akhir mushaf. Iluminasi mushaf sangat detail, bergaya “Pantai Timur” Semenanjung Malaysia2, dikerjakan dengan keterampilan artistik yang dapat dikatakan luar biasa. Amat disayangkan, mushaf telah mengalami penjilidan ulang beberapa tahun lalu yang menye-babkan sebagian tulisan dan hiasan di tepi naskah terpotong. Sang penjilid tampaknya kurang berhati-hati, karena lembar yang berisi statistik jumlah huruf Al-Qur’an tidak masuk dalam jilidan.
Iluminasi awal Surah al-Baqarah, yang berpasangan dengan Surah al-Fatihah, sangat disayangkan, telah hilang. Untuk sekadar melengkapi teks mushaf, bagian itu oleh pemiliknya diganti dengan lembaran mushaf cetakan bergaya Bombay. Selebihnya, mushaf ini masih lengkap. Pada bagian akhir, mushaf ini dilengkapi, secara berurutan, dengan penjelasan kode imam qiraat, daftar imam qiraat, doa khatam al-Qur’an, serta statistik jumlah huruf Al-Qur’an.
Pada bagian bawah ilustrasi statisktik jumlah huruf Al-Qur’an pada mushaf ini (lihat Gambar 12) terdapat petunjuk angka tahun penyalinan mushaf, tertulis, “Hijrat an-Nabiy sallallahu ‘alaihi wa sallam alf mi’atani sittun wa sab’un” (1276 H) bertepatan dengan
1Email 11 Agustus 2012. Semua pendapat Russell Jones dalam artikel ini
merujuk kepada email tersebut. 2Lihat kajian Annabel Teh Gallop (2005), “The spirit of Langkasuka? Illu-
minated manuscripts from the East Coast of the Malay peninsula”, Indonesia and the Malay World, 33: 96, 113-182.
104 104 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
tahun Masehi 1859-1860. Angka tahun tersebut tidak disertai de-ngan penyebutan bulan dan tanggal. Nama juz dan surah dicantum-kan di tepi atas halaman sebelah kiri.
Gambar 1. Mushaf A. Mushaf B
Mushaf ini adalah milik Muhammad Gaus, beralamat di Sala-bose, Pangaliali, Banggae, Majene, Sulawesi Barat. Ia mewarisinya secara turun-temurun dari keluarga imam di masjid lama setempat. Tidak seperti biasanya, ukuran mushaf agak kecil, yaitu 15,5 x 10 cm, tebal 4 cm. Mushaf ini memiliki kotak khusus, terbuat dari kayu, berukuran 19 x 15 cm, tebal 6 cm. Sehari-hari, mushaf terse-but berada di dalam kotak itu. Kertas mushaf tipis, dan menurut Russell Jones, lebih tua dibandingkan naskah-naskah mushaf Sulawesi Barat lainnya yang umumnya berasal dari abad ke-19. Cap kertas tidak bisa diidentifikasi dengan utuh, karena naskah ber-ukuran kecil, sehingga gambarnya terpotong. Iluminasi hanya ter-dapat di bagian awal mushaf.
Meskipun terbilang tua dibanding naskah lainnya, mushaf ini masih lengkap 30 juz. Kondisi mushaf masih cukup baik, dan sekali-kali masih dibaca oleh pemiliknya, terutama di bulan Rama-dan. Iluminasi hanya terdapat di awal mushaf, dan Surah an-Nas di
105 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 105
penghujung Al-Qur’an ditulis dalam bentuk segitiga dengan hiasan garis-garis sederhana.
Teks tambahan di akhir mushaf yaitu catatan tentang qiraat, kode tajwid yang digunakan (lihat Gambar 10), serta doa khatam Al-Qur’an. Di dalam catatan itu dinyatakan bahwa mushaf ini menggunakan tiga riwayat, yaitu riwayat Qalun dari Nafi’, ad-Duri dari Abu Amr, dan Hafs dari ‘Asim. Tidak seperti umumnya mus-haf Nusantara yang menggunaan riwayat Hafs, teks utama mushaf ini ditulis dengan riwayat Qalun, menggunakan tinta hitam. Adapun catatan di tepi halaman yang menggunakan tinta merah adalah riwayat ad-Duri, dan tinta hijau untuk riwayat Hafs. Penyalinan mushaf dengan riwayat Qalun terbilang sangat jarang dalam mus-haf Nusantara. Mushaf lainnya, di antaranya, adalah sebuah koleksi Keraton Kacirebonan di Cirebon.
Gambar 2. Mushaf B. Mushaf C
Mushaf ini adalah milik Drs. Sufyan Mubarak, Majene, Sula-wesi Barat. Ukuran mushaf agak besar, 43,5 x 28 cm, tebal 7 cm. Bidang teks berukuran 30 x 17,5 cm. Menurut catatan kolofon yang berada di akhir naskah, mushaf ini selesai ditulis pada Jumat 27
106 106 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
Rajab 1248 H (20 Desember 1832) oleh Haji Ahmad bin Syekh al-Katib Umar al-masyhūr fī jamī’i bilād al-Būqīs wa gairihā min ba‘d bilād al-Muslimīn – yang masyhur di seluruh negeri Bugis dan sebagian negeri muslim lainnya. Berbeda dengan naskah lainnya, mushaf ini tidak beriluminasi, dan menyisakan bagian kosong yang biasanya dihias, yaitu di awal, tengah, dan akhir mushaf. Sisa bagi-an kosong pada ketiga halaman tersebut menunjukkan bahwa mus-haf ini sedianya akan dihias, namun tidak terlaksana. Menurut ca-tatan di awal naskah, mushaf ini ditashih di Mekah.
Gambar 3. Mushaf C.
Selain catatan tashih, teks tambahan di bagian depan mushaf adalah daftar kode imam qiraat, doa, dan lafaz niat membaca Al-Qur’an. Mushaf ini memiliki catatan qiraat lengkap. Nama juz dicantumkan di tepi atas halaman sebelah kiri. Salah satu keunikan mushaf ini, sebagian nama juz ditulis dalam bentuk gambar perahu, menggunakan tinta merah. Itu tampak jelas, misalnya pada juz ke-15 pada awal Surah al-Isra’. Halaman yang memuat kata ‘wal-yatala¯¯af’ yang menandai tengah mushaf dibuat dengan bidang
107 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 107
teks lebih kecil, namun bagian tepi halaman kosong, menandakan bahwa pada halaman tersebut sedianya akan dihias. Mushaf D
Mushaf ini milik Hasan HM (Haji Maila), seorang sando kappung (dukun kampung), di Dusun Pallarangan, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mushaf ini berukuran 20,5 x 14,5 cm, tebal 4,5 cm, dan bidang teks ber-ukuran 14,5 x 9 cm.
Gambar 4. Mushaf D. Hingga kini, mushaf ini masih digunakan untuk ‘mengobati’
berbagai penyakit seperti terkena guna-guna, dengan meletakkan mushaf ini di atas segelas air, dan membaca doa-doa. Berdasarkan cap kertasnya, Russell Jones memperkirakan bahwa mushaf ini ber-asal dari abad ke-18. Iluminasi terdapat di awal dan akhir mushaf. Kondisi naskah sudah tidak utuh lagi, sebagian sobek, dan sebagian halaman tidak berurutan.
Tidak seperti mushaf lainnya, mushaf ini tidak memiliki catat-an qiraat. Teks mushaf ditulis secara berterusan, dan permulaan juz
108 108 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
ditandai dengan tinta merah dan hiasan setengah lingkaran di tepi halaman. Mushaf E
Mushaf ini milik Drs. Abdul Muis Mandra (alm.), Mosso, Sendana, Majene, Sulawesi Barat. Mushaf ini berukuran 33 x 23,5 cm, tebal 6,5 cm, dan ukuran bidang teks 23 x 13 cm. Cap kertas bergambar moonface berasal dari Italia, abad ke-19.
Gambar 5. Mushaf E. Mushaf ini memiliki catatan qiraat lengkap, dan setiap permu-
laan surah disertai dengan hadis-hadis keutamaan surah. Nama juz dan surah dicantumkan di tepi atas halaman sebelah kiri. Di akhir mushaf terdapat doa khatam Al-Qur’an yang pada permulaannya dihias cukup indah. Iluminasi floral yang cukup indah terdapat di bagian awal, tengah, dan akhir mushaf. Mushaf F
Mushaf ini milik H. Madeali Tahir, Cempalagian, Polewali-Mandar, Sulawesi Barat. Ukuran mushaf 36,5 x 25,5 cm, tebal 7 cm, dan ukuran bidang teks 26 x 14,5 cm. Kondisi mushaf baik dan
109 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 109
lengkap. Menurut pengakuan pemilik, mushaf ini ia dapatkan se-cara tiba-tiba di pagar rumahnya. Cap kertas tidak dapat teriden-tifikasi dengan baik, namun diperkirakan dari abad ke-19. Iluminasi floral yang indah terdapat di awal, tengah, dan akhir mushaf.
Gambar 6. Mushaf F. Kondisi mushaf ini masih sangat baik, dengan jilidan kulit ber-
warna merah berhias emas. Pada awal mushaf terdapat teks tam-bahan sebanyak lima halaman, berisi doa sebelum membaca Al-Qur’an dalam berbahasa Arab, serta keterangannya dalam bahasa Bugis. Mushaf ini memiliki catatan qiraat lengkap. Setiap permu-laan surah disertai dengan hadis keutamaan surah. Nama juz dan surah dicantumkan di tepi atas halaman sebelah kiri. Pada akhir mushaf terdapat doa khatam Al-Qur’an yang diambil dari kitab I¥yā’ ‘ulūm ad-dīn, serta teks lain dalam bahasa Bugis, berisi pen-jelasan jumlah huruf Al-Qur’an dalam bentuk teks biasa.
Mushaf G
Mushaf ini milik Hj. Mul Azam, Pambusuang, Polewali-Mandar, Sulawesi Barat, yang ia warisi dari ayahnya, H. Abdul Gani. Ukuran mushaf 33 x 23 cm, tebal 8 cm, dan ukuran bidang
110 110 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
teks 23 x 13,5 cm. Kondisi naskah baik, lengkap 30 juz. Cap kertas bergambar moonface dengan cap tandingan Andrea Galvani – Pordenone asal Italia, dari tahun 1870-1884. Cap kertas ini sama dengan yang digunakan Mushaf E dari Sendana. Iluminasi floral yang indah terdapat di awal, tengah, dan akhir mushaf. Teks tambahan di bagian akhir mushaf ini mirip dengan Mushaf F, berisi doa khatam Al-Qur’an, dengan keterangan dalam bahasa Bugis berhuruf serang (Arab-Bugis). Mushaf ini dilengkapi dengan catat-an qiraat, dan setiap permulaan surah disertai dengan hadis keuta-maan surah. Nama juz dan surah dicantumkan di tepi atas halaman sebelah kiri.
Gambar 7. Mushaf G.
Bagian awal mushaf, sebelum teks utama, memuat ilustrasi statistik jumlah huruf Al-Qur’an (lihat Gambar 13, dan bandingkan dengan Gambar 12), serta kode dan daftar imam qira’at. Di bagian bawah ilustrasi statisktik jumlah huruf Al-Qur’an terdapat petunjuk angka tahun penyalinan naskah, namun tampaknya kurang jelas, dan belum dapat dipastikan angka tahunnya. Teksnya terbaca “Hij-rat an-Nabiy ¡allallāhu ‘alaihi wa sallam arba‘ah sittah (?) wa £alā£ah mi’ah ba‘da alf”. Pernyataan ini membingungkan. Jika
111 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 111
yang dimaksudkan adalah tahun 1364 H (1944) tampaknya tidak mungkin, karena terlalu muda. Tetapi yang paling bisa dipercaya, dan hampir tidak mungkin salah, adalah penyebutan dua angka pertama, yaitu 1300 H (1882-1883). Angka ini kurang lebih berse-suaian dengan kertas asal Italia yang digunakan, Andrea Galvani – Pordenone yang menurut Russell Jones beredar sekitar tahun 1870-1884. Jadi dapat disimpulkan bahwa mushaf ini berasal dari akhir abad ke-19.
Sangat mungkin bahwa mushaf ini berasal dari tradisi yang sama dengan Mushaf A (lihat Gambar 1 dan 12). Meskipun dari masa yang berbeda, terpaut paling kurang 20 tahun, namun bebera-pa ciri menunjukkan kemiripan, yaitu ilustrasi statistik jumlah huruf Al-Qur’an, pencantuman nama surah dan nama juz di tepi atas halaman, penyalinan kode dan daftar imam qiraat, serta gaya tulisan floral yang digunakan.
Gambar 8. Mushaf H. Mushaf H
Mushaf ini terdiri atas 10 jilid. Jilid pertama disimpan oleh Hj. Mul Azam, Pambusuang, sedangkan 9 jilid lainnya disimpan oleh adiknya, Drs. H. Syauqaddin Gani, ketua MUI Kabupaten Majene. Ukuran mushaf 20,5 x 16 cm, tebal 1,5 cm, dan ukuran bidang
112 112 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
kertas 14 x 8,5 cm. Cap kertas Concordia bergambar singa memba-wa pedang, dari abad ke-19. Kondisi jilid pertama telah rusak pa-rah, tidak terawat, sedangkan 9 jilid lainnya masih baik.
Mushaf ini memiliki catatan qiraat, meskipun tidak selengkap naskah lainnya. Setiap permulaan juz ditulis di halaman baru, de-ngan satu baris bertinta merah, dan diakhiri dengan kalimat ¡adaqa Allāh al-‘a§īm (Mahabenar Allah yang Mahaagung) serta selawat. Nama juz dicantumkan di tepi atas halaman sebelah kiri. Rasm
Dari delapan mushaf yang dikaji dalam penelitian ini, lima di antaranya menggunakan rasm usmani, sedangkan tiga lainnya menggunakan rasm imla’i3. Sebuah mushaf lainnya, dengan ciri iluminasi floral yang hampir sama, koleksi Museum La Galigo, Makassar, juga dengan rasm usmani. Adapun tiga mushaf lainnya menggunakan rasm imla’i – dua di antaranya memang dengan tra-disi yang berbeda, dan berdasarkan kertasnya, diduga berusia lebih tua, yaitu abad ke-18, atau bahkan sebelumnya. Hal ini memper-lihatkan bahwa dari mushaf yang sezaman, yaitu abad ke-19 (Mus-haf A, C, E, F, G) menggunakan rasm yang sama, yaitu usmani. Model tatamuka (layout) ayat yang digunakan juga sama, “ayat pojok”, kecuali Mushaf C yang ditashih di Mekah.
Rasm usmani rupanya banyak digunakan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Wajo dan Bone, pada abad ke-19. Hal itu juga disertai dengan bacaan qira’at sab’ yang disertakan di bagian tepi mushaf. Sebuah mushaf dari istana Bone bertahun 1804 yang kini dalam koleksi Museum Aga Khan di Swiss, juga dengan rasm usmani, namun bukan ayat pojok. Berarti, penggunaan ayat pojok, di kawasan ini – sebagaimana juga tampak di kawasan lain Nusan-tara – mulai pada masa belakangan, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19.
3Yang dimaksud dengan rasm imlā’ī dalam artikel ini adalah penulisan Al-
Qur’an dengan ejaan biasa, kecuali kata as-salāt, az-zakāt, al-hayāt yang meng-gunakan huruf waw, bukan alif.
113 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 113
Gambar 9. Mushaf asal Kesultanan Bone, 1804, koleksi Aga Khan Museum, Swiss. (Foto: Annabel Teh Gallop)
Penggunaan rasm usmani dalam mushaf Nusantara, berdasar-
kan temuan mushaf yang ada hingga saat ini, dapat dikatakan tidak-lah terlalu banyak. Mushaf-mushaf dari Aceh, Sumatra, Jawa, Bali (Singaraja), Banten, Sumbawa, Kalimantan, hingga Ternate, keba-nyakan menggunakan rasm imla’i, dan hanya sedikit sekali yang menggunakan usmani. Oleh karena itu, penggunaan rasm usmani untuk mushaf yang selain dari Sulawesi Selatan, selanjutnya peng-amatan perlu dilakukan terhadap tahun mushaf. Barangkali, dapat diduga, bahwa rasm usmani dalam mushaf selain dari Sulawesi Selatan, terdapat pada mushaf-mushaf yang lebih tua, yaitu abad ke-18. Mushaf Sultan Ternate bertahun 1772 dan sebuah mushaf dari Kerajaan Sumbawa bertahun 1785 menggunakan rasm usmani. Namun, mushaf dari Ternate dan Sumbawa dari masa kemudian, yaitu abad ke-19, menggunakan rasm imla’i.
114 114 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
Riwayat dan ragam qiraat Salah satu mushaf yang ditemukan di Sulawesi Barat, yaitu
Mushaf B, menggunakan riwayat Qalun dari Nafi’. Penggunaan jenis riwayat ini dapat dikatakan jarang terjadi dalam mushaf Nu-santara. Ada satu mushaf lain di Keraton Kacirebonan mengguna-kan riwayat ini juga.
Gambar 10. Keterangan pada halaman akhir Mushaf B yang berisi tentang penggunaan riwayat Qalun, warna tinta pembeda antarqiraat, dan penggunaan
lambang tajwid. Berdasarkan cap kertasnya, Russell Jones memperkirakan bah-
wa mushaf ini jauh lebih tua daripada mushaf-mushaf lainnya. Namun, karena ukuran mushaf ini kecil, pengamatan terhadap cap
115 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 115
kertas kurang sempurna, sehingga belum dapat ditemukan angka tahun yang lebih pasti. Permukaan kertas mushaf ini halus dan tipis, tidak seperti umumnya kertas Eropa. Dari segi iluminasi, mushaf ini juga berbeda, yaitu hanya terdapat di permulaan mushaf.
Tujuh dari delapan mushaf yang ditemukan di Sulawesi Barat menggunakan catatan qirā’āt sab’ lengkap. Ini tampaknya meru-pakan hal tidak biasa, sebab kebanyakan mushaf Nusantara tidak menggunakan catatan qiraat. Berdasarkan inventarisasi, catatan qiraat lengkap terdapat pula pada mushaf-mushaf asal Banten koleksi Perpustakaan Nasional. Empat dari enam mushaf Banten mencantumkan qiraat lengkap. Selain itu, empat mushaf di Keraton Ternate juga mencantumkan ragam qiraat. Sebuah mushaf dari Keraton Bone, tahun 1804 yang kini dalam koleksi Aga Khan Mu-seum di Swiss juga menggunakan ragam qiraat lengkap.
Sementara itu, mushaf-mushaf lainnya dari Aceh, Pantai Timur Semenanjung Malaysia (Terengganu, Kelantan, Patani), Sumatra, dan Jawa (kecuali Banten), kecuali sejumlah kecil mushaf, keba-nyakan tidak mencantumkan ragam bacaan qiraat.Berdasarkan buk-ti yang ada, tampak bahwa mushaf-mushaf yang mencantumkan ragam qiraat terdapat pada mushaf yang berasal dari lingkungan keraton. Namun, ketujuh mushaf di Sulawesi Barat ini diduga berasal dari lingkungan pendidikan agama pertengahan abad ke-19, dan bukan dari keraton. Tanda tajwid
Tanda waqaf yang digunakan, yaitu huruf ط untuk waqaf mut-laq; ڪ untuk waqaf kafi; dan ت untuk waqaf tamm. Untuk bacaan tawid, huruf ظ untuk bacaan izhar; خ untuk ikhfa; kepala غ untuk gunnah, dan lain-lain.
Untuk bacaan mad wajib muttasil ditandai dengan garis susun tiga, dengan dua garis di atas warna merah, namun dalam mushaf lainnya hanya menggunakan satu garis hitam, atau merah. Mad ja’iz munfasil ditandai dengan sebuah garis merah; dan mad tabi’i ditandai dengan garis tegak warna merah.
Teks Tambahan
Tidak semua mushaf dari Sulawesi Barat memiliki teks tam-bahan di awal atau akhir mushaf. Dari delapan mushaf, tiga di antaranya memiliki teks tambahan di bagian depan, sebelum teks
116 116 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
Al-Qur’an, yaitu pada Mushaf C, F, dan G. Sedangkan teks tambahan di akhir mushaf terdapat pada Mushaf A, B, C, E, dan F.
Teks tambahan di awal Mushaf C berupa catatan tashih, rumus lambang huruf riwayat yang berlaku, doa sebelum membaca Al-Qur’an, dan lafaz niat membaca Al-Qur’an.
Gambar 11. Rumus lambang huruf riwayat, doa, dan niat membaca Al-Qur’an, di halaman awal Mushaf C.
Pada awal Mushaf F terdapat cataan tambahan sebanyak lima
halaman dalam bahasa Bugis dan Arab. Bahasa Bugis beraksara serang (Arab-Bugis) digunakan sebagai pengantar, sedangkan lafaz doa menggunakan bahasa Arab. Salah satunya berbunyi:
Nigi-nigi bacai doanngè ri yolo nabacana koranngè, ri wèrènngi ri Allataala eppa uangenna. Sèuwani mèncèngi appalanna, maduanna ri sarèyanngi ri Allataala lanpè umuru, matellunna, ri akkamasèyangngi ri padanna ri pancaji ri Allataala, maeppana, matèi sibawa teppena ri Allataala. Iyanaè doanngè.
Artinya: Barangsiapa membaca doa ini sebelum membaca Al Qur’an, Allah swt akan memberikan empat hal. Pertama, pahalanya bertambah; kedua, Allah swt memanjangkan umurnya; ketiga, disayangi oleh sesama makhluk Allah swt; keempat, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah swt. Inilah doanya.
117 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 117
Sedangkan pada Mushaf G di awal mushaf terdapat gambar statistik jumlah huruf Al-Qur’an (lihat Gambar 13), serta daftar lambang huruf periwayat qiraat Al-Qur’an. Biasanya, dalam mushaf-mushaf lain, statistik jumlah huruf Al-Qur’an terletak di bagian akhir mushaf.
Adapun teks tambahan di bagian akhir mushaf terdapat pada Mushaf A, B, C, E, dan F. Pada Mushaf A terdapat rumus qiraat, doa, dan statistik jumlah huruf Al-Qur’an. Statistik jumlah huruf seperti ini terdapat di beberapa mushaf lain dalam “keluarga mushaf Bugis”. Di antaranya, selain Mushaf G dari Sulawesi Barat, juga terdapat pada mushaf asal Kesultanan Bone koleksi Aga Khan Museum di Swiss (tahun 1804) (Gallop 2010:170), Mushaf Sultan Ternate (1772), dan “mushaf Bugis” asal Kedah di Pulau Penyengat (1753). Bentuk gambar agak berbeda-beda, bergantung pada kreativitas senimannya. Statistik ini berjudul Bayān al-a‘dād allatī ta‘allaqat bi-al-Qur’ān al-Majīd yang ditulis oleh Imām Mu¥am-mad bin Ma¥mūd as-Samarqandī (sekitar tahun 1203-4 M) (Gallop 2010:170).
Gambar 12 dan 13. Statistik jumlah huruf dalam Al-Qur’an pada Mushaf A (kiri), dan Mushaf G (kanan).
118 118 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
Teks tambahan lainnya di bagian akhir mushaf, yaitu pada Mushaf B, berupa keterangan riwayat Qalun, penggunaan warna tinta, lambang tajwid, serta doa penutup membaca Al-Qur’an. Ca-tatan akhir mushaf juga terdapat pada Mushaf C, berupa kolofon selesai penulisan mushaf. Mushaf ini selesai ditulis pada Jumat 27 Rajab 1248 H (20 Desember 1832) oleh H. Ahmad bin Syekh al-Katib Umar, yang terkenal di seluruh negeri Bugis (al-masyhūr fī jamī’i bilād al-Būqis …).
Gambar 14. Doa khatam Al-Qur’an serta penjelasan jumlah huruf Al-Qur’an pada akhir Mushaf F.
Pada bagian akhir Mushaf E terdapat doa khatam Al-Qur’an,
demikian pula pada Mushaf F. Pada mushaf yang terakhir ini di-lengkapi dengan sebuah doa lainnya yang dipetik dari kitab Ihyā’ Ulūm ad-Dīn, serta teks dalam bahasa Bugis. Pada Mushaf G ter-dapat doa yang sama seperti halnya pada Mushaf F. Kesamaan teks ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dua mushaf tersebut. Hal itu juga didukung oleh gaya tulisan yang mirip, dan ada kemungkinan dua mushaf tersebut ditulis oleh orang yang sama
119 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 119
– atau paling tidak, ditulis pada skriptorium yang sama. Teks pada akhir Mushaf F ditulis dalam aksara serang, artinya:
Inilah bilangan huruf dalam Al-Qur’an, 32.504.445 (tiga puluh dua juta lima ratus empat ribu empat ratus empat puluh lima isinya.)
Adapun bilangan huruf dalam Al-Qur’an 30 katinna 2 kati 5000, 4445 isinya.
Adapun jumlah isim Jalalah dalam Al-Qur’an berulang 2664 kali. Barangsiapa mengingat bilangan ini Allah menjadikan dia lebih rajin daripada yang dia niatkan, apa saja yang dicari ia akan mendapatkannya dengan izin Allah Ta’ala.
Adapun jumlah lafal Jalalah dalam 30 juz Al-Qur’an ada 2664.
Teks tambahan lainnya pada sebagian mushaf dari Sulawesi Barat ini, yang cukup penting dicatat, adalah kutipan hadis-hadis keistimeaan surah Al-Qur’an. Ini terdapat pada Mushaf A, E, F, dan G. Kutipan hadis itu terdapat pada hampir setiap awal surah, ditulis dalam posisi miring, di luar garis teks. Kutipan hadis seperti itu terdapat pula pada “keluarga mushaf Bugis” lainnya, yaitu Mushaf Sultan Ternate, mushaf Bugis asal Kedah di Pulau Penyengat, serta mushaf asal Bone koleksi Aga Khan Museum di Swiss.
Terakhir, yang tidak kalah penting untuk dicatat pada bagian ini adalah adanya “inovasi”, yaitu pencantuman nama juz dan nama surah di bagian atas-kiri setiap halaman. Dikatakan “inovasi”, karena pencantuman seperti itu jarang (atau tidak) ditemukan dalam mushaf dari tempat lain. Dilihat dari gaya tulisan dan jenis tinta yang digunakan, diduga kuat bahwa nama juz dan surah tersebut ditulis pada masa yang sama dengan penulisan mushafnya, dan bu-kan ditambahkan kemudian pada masa belakangan.
Nama juz dan nama surah seperti itu terdapat pada Mushaf A, F, dan G, sedangkan Mushaf C, E, dan H hanya mencantumkan nama juz. Nama-nama itu melengkapi kata alihan (catchword) yang terdapat di bagian bawah-tengah setiap halaman. Meskipun demi-kian, semua mushaf ini belum mencantumkan nomor halaman.
Kelengkapan running head (judul lari) dalam mushaf Al-Qur’an seperti itu menjadi kelaziman kira-kira sejak akhir abad ke-19, ketika mushaf dicetak dalam jumlah besar melalui mesin percetakan.
Kedelapan mushaf yang berasal dari Sulawesi Barat ini, ber-dasarkan sejumlah cirinya, sebenarnya merupakan bagian dari tra-
120 120 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
disi mushaf yang lebih luas, yaitu Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat sendiri merupakan wilayah hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Barat, diresmikan pada 5 Oktober 2004. Sula-wesi Barat memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Mandar.
Dari kedelapan mushaf yang ditemukan di Sulawesi Barat, sesungguhnya tidak ada satu pun yang bisa dipastikan sebagai mushaf asli tempatan. Ini masalah penting yang belum bisa dijawab dengan pasti. Sebaliknya, empat mushaf, yaitu Mushaf A, C, F, dan G jelas berasal dari tradisi Bugis. Mushaf A diwarisi dari orang yang selama puluhan tahun tinggal di Wajo sebagai hakim agama, sementara Mushaf C ditulis oleh orang Bugis, serta Mushaf F dan G sebagian teksnya menggunakan bahasa Bugis yang sekaligus bisa dianggap sebagai asal tradisinya. Secara geografis dan budaya, antara Bugis dan Mandar memang tidaklah terpisah jauh, sehingga, dalam hal ini, perpindahan mushaf dari satu tempat ke tempat lainnya dalam wilayah itu sangat mudah terjadi. Sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 perkembangan Islam di Sulawesi Selatan dalam berbagai hal cukup pesat. Antara iluminasi geometris dan floral
Hal menarik lainnya adalah terkait ciri iluminasi mushaf. Annabel Teh Gallop dalam ceramahnya (2007) tentang gaya ilumi-nasi naskah Sulawesi Selatan telah menyebut adanya dua gaya, yaitu geometris (contoh polanya lihat Gambar 9) dan floral, meski-pun dalam uraiannya ia hanya menyinggung gaya floral sedikit saja. Dari kedelapan mushaf yang dibahas dalam tulisan ini, empat di antaranya, yaitu Mushaf A, E, F, dan G memperlihatkan dengan jelas gaya iluminasi floral yang dimaksudkan itu – bahkan ba-rangkali merupakan contoh yang terbaik dalam kelompok ini. Di antara keempatnya, iluminasi dalam Mushaf A merupakan yang terbaik. Detail iluminasi dikerjakan dengan sangat teliti dan menga-gumkan.
Mengenai hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut, sebenar-nya kelompok sosial manakah yang memproduksi mushaf dengan gaya geometris dan floral itu. Namun, tampaknya ada kemung-kinan, bahwa yang mengembangkan gaya geometris adalah para penyalin di lingkungan kerajaan, sedangkan gaya floral dikem-bangkan oleh para penyalin di luar itu, dari kalangan ahli agama. Mushaf Bone (Gallop 2010) dan mushaf Kedah di Pulau Penyengat
121 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 121
merupakan contoh yang jelas dalam hal ini. Kedua mushaf bergaya iluminasi geometris ini, seperti terbaca di dalam kolofonnya, disalin di lingkungan keraton, seraya menyebut nama sultan dengan penuh pujian keagungan. Sementara, Mushaf Sultan Ternate yang berilu-minasi geometris, meskipun penyalinnya seorang imam, namun mushaf tersebut merupakan ‘mushaf istana’ (Akbar 2010).
Di pihak lain, patut disayangkan, bahwa dalam mushaf berilu-minasi floral, hanya sedikit sekali yang mencantumkan kolofon secara lengkap. Salah satu mushaf dari kelompok ini, yang mencan-tumkan kolofon cukup panjang adalah sebuah koleksi Museum La Galigo di Makassar, yang disalin oleh ‘Haji Sufyān a£-¤aur imām Bone bin Abdullah al-Qā«ī Bone’. Di dalam kolofon ini tidak disinggung nama penguasa, tetapi yang disebutkan adalah jabatan keagamaan sebagai imam.
Hal lain yang menarik untuk dibandingkan lebih lanjut adalah perbedaan masa penyalinan. Mushaf-mushaf bergaya geometris disalin pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, sedangkan mushaf bergaya floral lebih muda daripada itu, yaitu pertengahan dan akhir abad ke-19.
Memang masih memerlukan penelitian lain tentang hal ini, namun yang pasti, bahwa kedua gaya iluminasi, geometris dan floral, dikembangkan oleh orang Bugis dengan citarasa artistik dan ketelitian yang tinggi. Simpulan
Rasm usmani dalam mushaf banyak digunakan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Wajo dan Bone, pada abad ke-19. Hal itu juga disertai dengan bacaan qirā’āt sab’ yang disertakan di bagian tepi mushaf.Dari delapan mushaf yang dikaji dalam tulisan ini hanya satu mushaf yang tidak memiliki catatan qira’at. Ini menunjukkan bahwa ilmu Al-Qur’an yang dipelajari masyarakat muslim pada masa itu sudah cukup tinggi.
Mushaf-mushaf Al-Qur’an yang dikaji dalam tulisan ini, khu-susnya Mushaf A, C, E, F, G, dilihat dari uraian di atas, merupakan tradisi Bugis. Meskipun saat ini merupakan milik beberapa orang di Mandar, Sulawesi Barat, namun mushaf-mushaf tersebut berasal dan dari tradisi mushaf Bugis. Dalam hal tatamuka (lay out) penya-linan mushaf, berdasarkan mushaf-mushaf yang ada, patut diduga
122 122 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, 2014: 101-123
bahwa “ayat pojok” dalam mushaf Nusantara mulai digunakan sejak pertengahan abad ke-19.
Terkait gaya iluminasi, Mushaf A, E, F, dan G meneguhkan dengan kuat adanya gaya “iluminasi floral” dalam tradisi mushaf di Sulawesi Selatan. Gaya iluminasi ini melengkapi gaya “iluminasi geometris” yang telah dikenal sebelumnya.[]
Ucapan terima kasih Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Idham Khalid Bodi, peneliti Balai Litbang Agama Makassar yang menemani penulis selama penelusuran dan pemotretan naskah di Sulawesi Barat. Berkat bantuannya, proses pekerjaan di lapangan menjadi begitu lancar dan mudah. Sebagai bahan tambahan dan bandingan, pengalaman penelitian atas biaya SEASREP Foundation sangat berarti, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih ke-pada lembaga ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Rahman yang berbaik hati membaca aksara Serang dan menerjemahkannya untuk tulisan ini. Terima kasih juga saya sam-paikan kepada Dr. Russell Jones yang membantu mengidentifikasi cap kertas, juga kepada Dr. Annabel Teh Gallop, serta beberapa kawan lain di kantor, yang membaca draf artikel ini dan memberi-kan sejumlah kritik yang sangat penting. Meskipun demikian, tang-gung jawab artikel tetap pada penulis. Semua foto dibuat oleh penu-lis kecuali disebutkan sumbernya. Daftar Pustaka Akbar, Ali, “Mushaf Sultan Ternate tertua di Nusantara? Menelaah kembali
kolofon” Lektur, Vol.8, No.2, 2010, hlm. 283-296
Gallop,Annabel Teh, “The spirit of Langkasuka? Illuminated manuscripts from the East Coast of the Malay peninsula”, Indonesia and the Malay World, Vol. 33, No. 96, 2005
Gallop, Annabel Teh, “Migrating manuscript art: Sulawesi diaspora styles of illumination”, kertas kerja pada ceramahdi Universitas Sydney pada 21 Juni 2007 (tidak terbit).
Gallop, Annabel Teh, “The Bone Qur’an from South Sulawesi” dalam Margaret S. Grases and Benoit Junod (eds.), Treasures of the Aga Khan Museum:
123 Manuskrip Al-Qur’an dari Sulawesi Barat — Ali Akbar 123
Arts of the Book and Calligraphy, (Istanbul: Aga Khan Trust for Culture and Sakip Sabanci University & Museum, 2010, hlm.162-173.
Munawiroh, “Mushaf kuno di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Lektur, Vol. 5, No.1, 2007, hlm. 19-38.
Surur, Bunyamin Yusuf, “Mushaf kuno di Sulawesi” dalam Mushaf-mushaf kuno di Indonesia,Jakarta, Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005, hlm. 237-259.
Tinjauan Buku
Judul : Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an terhadap Agama Lain Penulis : Mun’im Sirry Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Cetakan : 2013 Halaman : 1xxxiv + 453 halaman Agus Iswanto Balai Litbang Agama, Jakarta Jl. Rawa Kuning, No. 60 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950 [email protected] Pengantar
Dua di antara dari beberapa sasaran strategis pembangunan bidang agama, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama tahun 2010-2014 (yang kemungkin-an masih akan tetap bertahan pasca-tahun 2014), adalah: (1) Me-ningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; dan (2) Ber-kembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan mul-tikultural. Sudah barang tentu beberapa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal itu adalah dengan pengembangan dan pengarus-utamaan (mainstreaming) wawasan keagamaan sebagaimana yang diharapkan di atas.
Upaya-upaya semacam itu dapat dilakukan dengan penyebaran gagasan-gagasan keagamaan moderat dan toleran, melalui penerbit-an buku-buku keagamaan yang mewacanakan perlunya pandangan dan sikap keagamaan moderat dan toleran. Dalam konteks inilah terbitnya buku-buku seperti itu perlu mendapatkan apresiasi, seba-gai bagian dari pelaksanaan misi pembangunan agama oleh Kemen-terian Agama. Tulisan ini mencoba memaparkan dan mendisku-sikan satu buku dengan tema hubungan antaragama berdasarkan perspektif studi kitab tafsir Al-Qur’an, satu tema yang signifikan
126 126 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
dalam konteks membangun kerukunan nasional di Indonesia, berda-sarkan perspektif tafsir Al-Qur’an di kalangan muslim. Tentang Polemik Kitab Suci
Buku ini berawal dari sebuah disertasi doktoral yang diajukan penulisnya, Mun’im Sirry, di Divinity School (Sekolah Teologi) Universitas Chicago dan berhasil dipertahankan pada Mei 2012. Judul disertasi tersebut adalah “Reformist Muslim Approach to the Polemics of the Qur’an againts Other Religions.” Pilihan untuk menulis disertasi dalam tema ini—studi tafsir di sisi lain dan studi hubungan antar agama di sisi lain—adalah, sebagaimana diakuinya sendiri, karena minat personal dan intelektualnya. Personal karena mungkin sebagai bagian dari muslim Indonesia, Mun’im mengha-dapi secara praktis persoalan-persoalan rumit yang sering kali mengganggu keharmonisan sosial antar agama di Indonesia, dan intelektual karena sudah sejak awal ia sudah seperti disiapkan seba-gai sarjana terlatih (well-trained scholar) di bidang studi Islam, yang dimulai dengan menjadi santri di Pesantren TMI Al-Amien, Prenduan, Madura.
Mungkin hasil didikan pesantren tersebut yang kemudian menjadikannya akrab dengan khazanah dan tradisi keilmuan Islam dalam bahasa Arab, terlebih ia juga pernah belajar (S1 dan S2) di bidang hukum Islam pada International Islamic University, Isla-mabad, Pakistan, sebuah negeri yang kini lebih dikenal dengan aksi bomnya. Kita dapat memeriksa betapa akrabnya Mun’im dengan beberapa literatur keilmuan Islam klasik itu dalam bibliografi. Namun, di sisi lain ia tetap berdialog dan mendebat beberapa sar-jana Barat, yang menjadi “teman diskusi” dalam penulisan buku-nya.
Sebagaimana tampak dalam judulnya, buku ini berusaha menampilkan pandangan-pandangan “muslim reformis” terhadap ayat-ayat polemik dalam al-Qur’an mengenai agama lain, khusus-nya Kristen dan Yahudi. Pandangan-pandangan tersebut tertuang di dalam berbagai kitab tafsir para muslim reformis tersebut. Mereka yang disebut dengan muslim reformis kemudian direduksi dalam enam tokoh dengan enam kitab tafsirnya, yakni: Jamal al-Din al-Qasimi (w. 1914) dari Suriah dengan kitab tafsirnya Ma¥asin al-Ta’wīl, Rasyid Rida (w. 1935) dari Mesir dengan kitab tafsirnya Tafsīr al-Man±r, Maulana Abul Kalam Azad (w. 1958) dari India
127 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 127
dengan kitab tafsirnya Tarjumān al-Qur’ān, Muhammad Jawad Mughniyah (w. 1979) dari Lebanon dengan kitab tafsirnya Al-Tafsīr al-Kāsif, Muhammad Husain Tabataba’i (w. 1981) dari Iran dengan kitab tafsirnya Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan Hamka (w. 1981) dengan kitab tafsirnya Tafsir Al-Azhar. Menurut Mun’im, inilah beberapa mufasir (para penafsir), yang secara formal menulis kitab tafsir dari kelompok yang disebut dengan muslim reformis. Tokoh ini adalah, dianggap oleh Mun’im, yang kitab tafsirnya menjadi karya magnum opus dalam perjalanan intelektual mereka.
Meskipun beberapa ahli terkadang menyebut tokoh-tokoh tersebut dengan “muslim modernis,” Mun’im lebih memilih meng-gunakan istilah “reformis” ketimbang “modernis” dengan dua ala-san: pertama, perhatian utama reformisme adalah untuk memelihara Islam dengan cara meremajakan unsur-unsur yang dinamis dalam tradisi Islam, sementara modernisme membangun asumsi utamanya bukan dari tradisi Islam, tapi dari pemikiran Barat.1 Kedua, seka-lipun jika reformisme bisa disebut dengan modernisme Islam, reformisme hanya melakukan modernisasi dalam pengertian khusus dan terbatas, yakni sebuah gerakan dari kelompok cendikia muda yang menyadari bahwa Islam harus dijauhkan dari kejumudan dan harus diperbarui.2 Kecuali dua argumen tersebut, bagi Mun’im, pada kenyataannya penggunaan istilah “reformis” setidaknya sesuai
1Hal ini tampak berbeda dengan Deliar Noer, yang sepertinya menyamakan
antara “reformisme” dengan “modernisme.” Noer menyebutkan bahwa: gerakan modern adalah sebuah gerakan perubahan-perubahan baik menggali mutiara-mutiara Islam dari masa lalu (tradisi Islam, tambahan penulis)...atau dengan menggunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia oleh ke-kuasaan kolonial serta pihak missi kristen. Lihat Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 71.Mungkin yang dimaksud dengan reformisme dalam buku Mun’im ini adalah sama dengan yang disebut oleh Fazlur Rahman, yakni “neo-modernisme,” yakni sebuah gerakan dan pemikiran yang mendasarkan pada kritisisme terhadap tradisi Islam dan Barat. Lihat ulasan Esposito terhadap pembagian pemikiran dan gerakan Islam dalam John L. Esposito, Islam Straigh Path: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus, Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat, 2010, hlm. 156-208.
2Hal ini ada kesamaan dengan pandangan Albert Hourani, yang mengajukan Rasyid Rida sebagai salah satu intelektual “liberal” dalam pembahasan bukunya. Mungkin ada kesamaan dengan maksud “reformisme” sebagaimana yang di-ajukan Mun’im. Lihat Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Bandung: Mizan, 2004.
128 128 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
dengan penyebutan di kalangan mereka sendiri. Menurut Mun’im, gerakan intelektual yang dimotori oleh Abduh, termasuk di dalam-nya Rasyid Rida sering menyebut sendiri dengan “reformis” (mu¡-li¥ūn).3 Namun, sepertinya ada informasi yang hilang atau terserak di sini, yakni Mun’im tidak secara jelas mengurai bukti-bukti apa-kah tokoh-tokoh lain yang dikaji, seperti Azad dan Hamka mendaku juga sebagai reformis?
Apakah yang dimaksud dengan ayat-ayat polemis dalam al-Qur’an pada buku ini? Polemik (yang secara bahasa berarti “perde-batan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka)4 digunakan dalam buku ini sebagai istilah umum untuk serangkaian diskursus yang lebih luas, mulai dari klaim keselamatan eksklusif yang dianggap sebagai khusus untuk kaum muslim, kritik al-Qur’an terhadap agama lain, terutama Yahudi dan Kristen, serta hubungan dengan mereka. Jadi ayat-ayat dengan ketiga hal polemis itulah yang dibahas dalam buku ini. Untuk itu, buku ini disusun dalam lima bab ditambah dengan pendahuluan. Setelah bab pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan bab satu, yakni mendiskusikan ka-rakteristik polemik Al-Qur’an terhadap agama lain. Bab ini sebetul-nya mengkaji secara kritis, apa yang disebut oleh Mun’im sebagai “teori peminjaman,” yakni sebuah pandangan bahwa Al-Qur’an memuat atau menyinggung banyak ajaran Yahudi dan Kristen, yang membuat para sarjana modern berargumen bahwa Nabi Muhammad telah merumuskan agama barunya secara eklektik melalui kontak-nya dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Dengan pandangan tersebut, bab ini mencermati bagaimana Al-Qur’an menyapa agama lain dalam gayanya yang ekumenikal (kerjasama dan saling mema-hami) dan polemis. Siapa saja yang menjadi sasaran dari teks pole-mik tersebut? Jika polemik kitab suci ini pada mulanya digunakan untuk membangun identitas agama baru, dapatkah ditafsirkan dalam konteks yang berbeda pula?
Bab kedua langsung pada pembahasan utama buku ini, yakni mendiskusikan penafsiran muslim reformis atas ayat-ayat yang bia-sanya dipahami sebagai bukti tekstual (dalil) tentang superioritas keselamatan Islam atas agama lain. Setidaknya ada dua ayat di sini
3Mun’im Sirry, Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an
terhadap Agama Lain, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. xxxvi. 4Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1198.
129 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 129
yang dibahas, yakni Q.S. 3: 19 dan Q.S. 5:3. Ayat-ayat ini pada umumnya dikutip untuk mendukung teologi keselamatan eksklusif. Dalam bab ini juga, Mun’im membahas apakah konteks ayat-ayat tersebut mendukung argumen sebagian kaum muslim yang menjadi-kannya sebagai bukti tekstual bahwa Islam merupakan satu-satunya jalan keselamatan.
Bab ketiga mengkaji tentang polemik ta¥rīf, sebuah istilah untuk menjukkan pemalsuan (perubahan atau pengrusakan)kitab-kitab terdahulu. Memang Al-Qur’an mengakui bahwa kitab Yahudi dan Kristen bersumber dari Tuhan. Namun juga, ayat-ayat dalam al-Qur’an menyebutkan sejumlah perubahan dalam kitab suci yang dilakukan oleh sekelompok ahli kitab. Ada empat ayat dalam Al-Qur’an yang menggunakan kata turunan dari ta¥rīf, yakni Q.S. 5: 13, Q.S. 2: 27, Q.S. 4: 46, dan Q.S. 5: 41. Al-Qur’an juga berbicara tentang tindakan ta¥rīf orang-orang Yahudi dan Kristen terhadap kitab suci mereka, baik dengan tangan (Q.S. 2: 79) maupun lisan (Q.S. 3: 78). Persoalan polemis ini dibahas oleh Mun’im dengan alasan bahwa persoalan ini menjadi terus digunakan berabad-abad oleh orang Islam dalam berpolemik dengan orang Yahudi dan Kristen tentang ajaran mereka. Oleh karena itu, dalam bab ini juga Mun’im berupaya menemukan hambatan bagi upaya untuk melam-pui perdebatan yang sudah berlangsung sekian lama itu.
Bab keempat mendiskusikan penolakan Al-Qur’an terhadap konsep anak Tuhan, sifat kemanusiaan Tuhan dan doktrin Trinitas. Mengenai persoalan “anak Tuhan,” Mun’im mendiskusikan ayat al-Qur’an (Q.S. 9: 30) yang menyangkal ‘Uzair dan Isa (Yesus) sebagai anak Tuhan, berserta ayat lain (Q.S. 5: 18) yang menolak klaim Yahudi dan Kristen bahwa mereka (‘Uzair dan Isa) adalah anak-anak Tuhan. Bab ini juga membahas kritik Al-Qur’an terhadap orang-orang Kristen yang meyakini Tuhan adalah Isa Almasih (Yesus), yakni dalam QS 5: 17 dan 72. Tidak ketinggalan, bab ini membahas tentang bagaimana Al-Qur’an berbiacara tentang tiga tuhan (Trinitas) yang dikemudian ditafsirkan oleh ahli tafsir yang menjadi kajiannya.
Bab kelima mendiskusikan tentang pembatasan al-Qur’an untuk berinteraksi dengan agama lain, serta bagaimana tafsir para tokoh yang menjadi kajiannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur’an tampaknya ada membatasi ruang per-gaulan kaum Muslim dengan penganut agama lain, seperti soal
130 130 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
memberikan kepercayaan kepada orang Yahudi, Kristen atau orang yang beragama lain, ataupun menjalin pertemanan dengan mereka. Ayat-ayat yang paling banyak dikutip adalah Q.S. 2:120, Q.S. 3:51, 57, 81. Al-Qur’an juga terkadang menggunakan istilah kaum kafir, bukan Yahudi dan Kristen (Q.S. 4:89, 139 dan 144). Kontribusi dalam Studi Tafsir Al-Qur’an
Secara teoritis, buku Mun’im sesungguhnya ingin menyanggah pandangan dalam kajian tafsir Al-Qur’an sebagaimana yang dike-mukakan oleh beberapa sarjana yang menjadi “lawan debatnya.” Beberapa sarjana al-Qur’an orientalis—yang di antaranya adalah Harris Birkeland, Rotraud Wielandt dan J.J.G Jansen—berpendapat bahwa mufasir belakangan hanya menyalin atau mengulang sumber-sumber tafsir terdahulu, seperti kitab-kitab tafsir karya a¯-°abari, Zamakhsyari, al-Razi, ataupun Ibn Ka£īr. Berbeda dengan mereka, Mun’im berpandangan—dengan memperkuat pendapat Karen A. Bauer—bahwa para mufasir reformis (atau modern) mes-kipun tetap merujuk pada tafsir terdahulu, mereka sering mengem-bangkan penafsiran sendiri untuk menjadikan al-Qur’an relevan dengan tempat dan masa kini. Jadi, citra tafsir modern yang dipandang tidak menghasilkan sesuatu yang baru, menurut Mun’im sama sekali tidaklah benar.5
Pandangan ini sepertinya menemukan pembenarannya—seti-daknya untuk konteks Indonesia—ketika memperhatikan hasil penelitian Islah Gusmian tentang khazanah tafsir Indonesia.6 Islah menyimpulkan bahwa, dari segi tema yang diangkat, terlihat bahwa karya tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an sangat terkait dengan wacana dan problem-problem pemikiran yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu yang relevan dengan buku karya Mun’im adalah tentang hubungan antarumat beragama.7 Hal terse-but akan jelas jika membaca Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Ketika membahas Q.S. 5: 51 yang terkait dengan hubungan dengan agama lain, alih-alih mengutip mufasir-mufasir klasik, Shihab lebih mengutip dan bersetuju dengan mufasir modern asal Mesir, yakni Muhamamd Sayyid Thantawi. Thantawi, menurut
5Mun’im Sirry, hlm. xxvii. 6Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga
Ideologi, Yogyakarta: LKiS, 2013. 7Islah Gusmian, hlm. 366-376.
131 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 131
Shihab, non-muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok: pertama, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslim dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan me-lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang menunjukkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik ke-pada mereka. Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslim dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh didekati. Mereka adalah yang dimaksud dengan Q.S. 5: 51. Ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslim, tetapi ditemukan sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersim-pati kepada kaum muslim, sebaliknya mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka, Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.8
Mengenai kreatifitas mufasir reformis, sebagaimana yang di-tunjukkan oleh Rasyid Rida—salah satu mufasir yang dikaji Mun’im—dengan bertitik tolak dari pandangan kritisnya terhadap beberapa mufasir klasik, telah ditunjukkan dalam kajian Shihab tentang kitab tafsir Al-Manar. Shihab menunjukkan pandangan-pandangan kritis Rida terhadap beberapa mufasir klasik, yakni Ibn Jarīr a¯-°abari, Fakhr al-Dīn al-R±zī, dan al-Zamakhsyari, al-Bay«±wi, al-Alµsi dan al-Suyū¯i. Rida, misalnya, mengkritik a¯-°abari ketika meriwayatkan hal-hal yang disebutnya sebagai suatu kebodohan (sebuah pandangan yang pedas). Rida juga sangat kritis terhadap al-Razi yang dipandangnya kurang pengetahuannya terha-dap hadis-hadis Nabi dan terlalu menjunjung akal. Ketika meng-kritik al-Zamakhsyari, Rida mengatakan bahwa ia (al-Zamakhsyari) telah melanggar etika kesopanan terhadap Rasulullah. Seharusnya, kata Rida sebagaimana dikutip oleh Shihab, al-Zamakhsyari dan pengikut-pengikutnya harus belajar dari ayat ini tata cara sopan santun yang setinggi-tingginya terhadap Rasulullah.9
Bukti kreativitas dan kritisnya mufasir modern juga ditunjuk-kan oleh Mun’im ketika ia membahas karakteristik pendekatan
8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-
Qur’an, Vol. 3, Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2009, hlm. 153-154. 9Muhammad Quraish Shihab, Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis atas
Tafsir Al-Manar, Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2007, hlm. 153-172.
132 132 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
tafsir Hamka dalam bukunya ini. Menurut Hamka: “Dalam banyak kasus al-Qur’an, begitu memukau dalam hal keluasannya sebagai sumber petunjuk bagi manusia, telah dipersempit oleh para mufasir demi mendukung sudut pandangnya sendiri.” Hal itu ditunjukkan oleh mufasir al-Razi dan al-Zamakhsyari yang telah menafsirkan Al-Qur’an untuk memperkuat pandangan teologis tertentu. Meski-pun demikian, Hamka juga menyebutkan ia tetap mengikuti bebe-rapa pendapat terdahulu yang masih relevan, dengan tetap memper-timbangkan keterbatasan-keterbatasannya.10
Untuk memperkuat argumennya tersebut, Mun’im menujukkan juga bahwa kebanyakan mufasir reformis modern tidak terlalu menyandarkan pendapatnya pada tafsir-tafsir terdahulu semata, ba-nyak sumber-sumber lain digunakan selain karya-karya tafsir, se-perti sirāh Nabi, teologi, fikih, dan berbagai tulisan-tulisan modern, baik yang ditulis oleh kalangan muslim maupun non-muslim. Misalnya, Mun’im memberikan bukti, Rida, ketika menafsirkan Q.S. 5: 3 tentang persoalan kesempurnaan agama, banyak merujuk pada karya Syatibi Muwafāqāt, sebuah kitab terkenal di bidang fil-safat hukum Islam dalam mazhab Maliki.11 Ia juga banyak meng-gunakan sumber-sumber Barat untuk mendukung pendapatnya, terutama ketika manfsirkan Q.S. 5: 17 dan 72 tentang ketuhanan Yesus atau Isa.12 Hal yang sama juga dilakukan oleh Hamka, yang mengutip sumber Barat, seperti ia mengutip John Peterson-Smyth dalam A People’s Life of Christ, yang menyatakan bahwa selama masa hidup Yesus/Isa, persoalan tentang ketuhanannya tidak pernah terpikirkan oleh para muridnya. Ia selalu dilihat oleh para muridnya sebagai manusia, tetapi baru setelah Kebangkitannya, Isa/Yesus mulai dianggap sebagai Tuhan. Hamka merujuk pendapat Peterson-Smith, seorang zending Kristen, untuk berpendapat bahwa ketuhan-
10Mun’im Sirry, hlm. 1xxvi-1xxvii. 11Mun’im Sirry, hlm. 145-147. Rida memberikan tafsir QS. 5:3 lebih
sebagai “keserbamencakupan”ajaran Islam daripada superioritas Islam atas agama lainsebagaimana tafsir kebanyakan mufasir terdahulu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hamka, yang tidak memandang ayat ini sebagai klaim superi-oritas Islam atas agama lain. Lihat juga Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI, Jakarta: Yayasan Nurul Ilmi, 1976, hlm. 112-113.
12Mun’im Sirry, hlm. 281.
133 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 133
an Yesus dikembangkan belakangan terutama oleh Yohanes (salah satu dari 12 rasul Yesus).13
Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mun’im berpandangan bah-wa asumsi tafsir Al-Qur’an modern tidak beranjak dari pola dan pendekatan tafsir klasik harus dikaji ulang. Lewat buku ini, Mun’im menunjukkan bahwa bagaimana mufasir reformis modern secara kritis merujuk pada tafsir klasik, tetapi juga memilah dan memilih sumber-sumber otoritatif lainnya, dan mereka juga, pada saat yang sama, sangat terlibat dengan tantangan masanya. Memang, bebe-rapa unsur keberlanjutan ditemukan, tetapi banyak juga komentar cerdas dan kritis dari mufasir reformis modern, yang dibentuk oleh perhatian mereka dalam konteks lokal dan global mereka sendiri.14 Mencari Solusi Polemik
Seperti yang telah dikemukakan sendiri oleh Mun’im, bahwa penelitiannya atas unsur-unsur polemis dalam Al-Qur’an adalah untuk memahami keyakinan kita (mungkin maksudnya adalah kaum Muslim) akan agama lain, menjawab tuntutan modern, dan akhirnya memberikan sumbangsih bagi kemajuan masyarakat.15 Kemajuan masyarakat di sini maksudnya mungkin adalah kemajuan kesaling-pahaman dan keharmonisan hubungan kaum muslim dengan non-muslim di tengah dunia yang semakin global dan majemuk. Oleh karena sebenarnya, di samping untuk memenuhi minat pengetahu-annya tentang khazanah tafsir atas ayat-ayat polemik, Mun’im ingin
13Mun’im Sirry, hlm. 284. Lihat juga Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI, hlm.
170. 14Mun’im Sirry, hlm. 422. Keterlibatan konteks lokal ini ditunjukkan oleh
Mun’im dalam tafsir Hamka. Dalam pembahasan mengenai kesempurnaan ajaran Islam dalam QS. 5:3, Hamka menyinggung soal perdebatan penggunaan tirai untuk memisahkan laki-laki dan perempuan di tempat-tempat pertemuan. Hamka berpendapat bahwa tidak ada landasan teks apa pun mengenai hal ini, karena konteks QS. 33:53 secara khusus berbicara soal istri-istri Nabi, sedangkan prinsip etika umum dalam pertemuan publik sebagaimana disebutkan dalam QS. 24:30-31 adalah diharuskan menundukkan pandangan mereka dan menjaga kesopanan. Pemberian contoh ini dilakukan oleh Hamka untuk menjelaskan bahwa agama yang sempurna, sebagaimana disebutkan dalam QS. 5:3, adalah agama yang mengakui sifat alami perkembangan manusia dan tidak menghalanginya. Hal yang membuat pikiran manusia menjadi jumud adalah ketika hasil pikiran manusia tidak lagi dipikir ulang dan diuji secara kritis. Lihat Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI, hlm. 115-116
15Mun’im Sirry, hlm. xxiv.
134 134 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
memberikan sebuah “jalan alternatif” bagi deadlock yang ditemu-kan dalam tafsir-tafsir yang dikajinya, sehingga masyarakat dunia akan tetap terkungkung dalam lingkaran kesalahpahaman, kecuriga-an, kebencian dan kekerasan yang akut.16
Hal tersebut berangkat dari keprihatinannya atas wacana hubungan antar agama yang ada. Menurutnya, perhatian para peng-kaji dan pegiat hubungan antar agama lebih banyak pada unsur-unsur Al-Qur’an yang memang sudah bersifat inklusif dengan mengabaikan unsur-unsurnya yang eksklusif.17 Menurut Mun’im juga, banyak sarjana memilih sejumlah ayat Al-Qur’an yang dapat dipahami sebagai memberikan landasan keagamaan bagi kehidupan beragama yang harmonis, tetapi ketika mereka dihadapkan bagai-mana ayat-ayat polemik ini dipahami oleh ulama, mereka cende-rung merujuk pada tafsir Al-Qur’an masa klasik. Dari sini tampak, bahwa Mun’im melalui kajiannya ini sedang melihat sejauh mana mufasir reformis modern menafsirkan ayat-ayat polemik tersebut yang “sudah memuaskan” dari sudut pandang Mun’im, dan hal-hal yang mungkin disikapi melalui solusi dari tafsir-tafsir reformis tersebut yang dipandang “belum memuaskan.”
Ketika membahas tentang teologi keselamatan eksklusif, Mun’im menyimpulkan bahwa semua mufasir reformis bersepkat bahwa keselamatan dan kesempurnaan Islam bukanlah monopoli umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengem-bangkan pemahaman baru dan penafsiran ulang terhadap makna Islam dalam Al-Qur’an yang cocok dengan kebutuhan masyarakat pluralis di dunia modern.18
Pemberian jalan alternatif sebagai sebuah solusi dari penafsiran ayat polemik ini tampak dalam setiap bab pembahasan. Misalnya, pada pembahasan soal pemalsuan kitab suci Yahudi dan Kristen, Mun’im menyimpulkan dengan memberikan jalan solusi berdasar-kan analisisnya terhadap mufasir reformis, bahwa karakteristik pewahyuan dalam ketiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) berbe-
16Mun’im Sirry, hlm. xxiv. 17Di antara buku tersebut adalah misalnyaAbdul Moqsith Ghazali, Argumen
Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an, Depok: KataKita, 2009; Budhy Munawar-Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: Sri Gunting, 2004; Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme: Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, Jakarta: Serambi, 2006.
18Mun’im Sirry, hlm. 159-161.
135 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 135
da, dan para mufasir reformis tidak memahami bahwa menurut Yahudi dan Kristen, unsur manusia dalam kepengarangan Al-Kitab dan kanosisasi tersebut tidak otomatis berarti penyimpangan. Al-Kitab, menurutnya, jelaslah bukannya sebuah kitab yang dicatat langsung oleh Tuhan dari surga, tetapi merupakan inspirasi dari Tuhan yang ditulis oleh manusia. Jadi, saran Mun’im, jika orang Islam ingin menghargai kitab suci orang lain, mereka harus mulai memahami secara serius cara orang lain memahami kitab suci mere-ka. Selama orang Islam memaksakan teori pewahyuan mereka terhadap kitab suci agama lain (Yahudi dan Kristen), tuduhan pemalsuan kitab suci pra-Al-Qur’an akan tetap kuat.19
Perspektif yang berbeda juga diberikan oleh Mun’im saat me-nyimpulkan berbagai tafsir tentang anak Tuhan, ketuhanan Yesus/ Isa dan doktrin trinitas oleh para mufasir reformis ini. Nyatanya, memang para mufasir reformis sulit menerima tiga klaim teologis utama kaum Kristiani, yaitu status Yesus sebagai anak Tuhan, sifat ketuhanannya dan doktrin trinitas, karena ketiga hal tersebut berten-tangan dengan konsep tauhid. Namun, di akhir bab pembahasan ini, Mun’im berpendapat—dengan kesadaran perbedaan teologis adalah yang paling sulit dipertemukan—bahwa perbedaan antara agama Kristen dan Islam tentang doktrin Trinitas bukanlah persoalan ten-tang keesaan Tuhan, tetapi persoalaannya adalah tentang karakte-ristik dari keesaan Tuhan itu. Bagi Mun’im, harus diakui bahwa kedua tradisi keimanan tersebut membenarkan akan keberadaan dan keesaan Tuhan, serta menolak penyembahan berhala dan polite-isme, tetapi sementara orang Islam menekankan keesaan Tuhan dalam pengertian yang ketat, orang Kristen percaya bahwa keesaan Tuhan memungkinkan pembedaan tanpa pemisahan. Dengan kata lain, baik orang Islam maupun orang Kristen berbicara tentang keesaan Tuhan, tetapi keduanya berbeda dalam cara mengungkap-kannya.20 Meninjau Ulang Tipologi Eksklusif, Inklusif, dan Pluralis
Sebelum menutup tinjauan buku ini, ada satu hal lagi yang penting dikemukakan, yakni soal gugatan atas pembagian pandang-an seseorang atas agama lain menjadi: eksklusif, inklusif, dan
19Mun’im Sirry, hlm. 241-242. 20Mun’im Sirry, hlm. 320-324.
136 136 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
pluralis.21 Studinya terhadap tafsir ayat-ayat polemik dalam kitab-kitab tafsir dari mufasir reformis menunjukkan bahwa penerapan tiga kategori tersebut terhadap pandangan-pandangan mereka tidak memadai,22 misalnya ia menunjukkan bahwa meskipun Azad—se-bagai salah satu mufasir yang dikajinya—dapat dipandang sebagai yang paling pluralis di antara mufasir reformis yang dikajinya dalam buku ini, ia enggan menerima ketuhanan Yesus dan doktrin trinitas sebagai ekspresi lain dari keyakinan monoteisme.23
Jadi, menilai inklusif atau ekslusif, menurut Mun’im, sebaiknya melihat pada apa yang mereka katakan (pandangan), bukan pada siapa yang mengatakannya. Sebab mengaburkan dua hal ini akan jatuh pada generalisasi yang gegabah. Sesungguhnya sampai di sini, menurut penulis, Mun’im hendak menunjukkan bahwa jangan ter-lalu terburu-buru menilai seseorang dengan cap atau kategori ter-tentu hanya karena satu pandangannya, dan mengabaikan pandang-annya yang lain. Inilah yang mungkin dapat disebut sebagai pan-dangan yang moderat. Kelemahan Buku
Mun’im tampaknya belum memberikan jalan alternatif yang jelas dalam soal pembatasan dan pergaulan antar agama, ia hanya memberikan petunjuknya. Mun’im menemukan bahwa para mufasir
21Secara sederhana dapat diterangkan di sini: eksklusif adalah pandangan
bahwa agama tertentu saja yang memiliki kebenaran tunggal dan agama lain salah. Pandangan inklusif adalahpandangan yang menyatakan bahwa bahwa kebenaran mutlak tunggal pada agama tertentu tetapi memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberikan keselamatan terhadap agama lain. Sedangkan pandangan pluralis berpandangan bahwa tidak ada tradisi agama yang bisa mendaku sebagai pemilik kebenaran satu-satunya.
22Tipologi ini, terutama dua tipologi pertama, eksklusif dan inklusif pernah digunakan oleh Fatimah Husein untuk mengkaji pandangan-pandangan muslim di kedua kelompok tersebut tentang hubungan muslim-kristiani di masa Orde Baru. Memang tampak kecanggungannya dalam mengaplikasikan dua tipologi ini, yang terlihat dalam mengelompokkan siapa yang masuk ke dalam kelompok eksklusif dan siapa yang masuk kelompok inklusif. Fatimah Husein menyebut nama-nama tertentu untuk mengelompokkan kalangan inklusif, tetapi ia hanya menyebut beberapa organisasi yang dapat dikelompokkan sebagai eksklusif. Lihat Fatimah Husein, Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims’ Perspective, Bandung: Mizan, 2005, hlm. 143-220.
23Mun’im Sirry, hlm. 421.
137 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 137
reformis menghadapi kesulitan dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat soal pembatasan dan pergaulan antar agama, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang telah dilakukan untuk memberlakukan secara umum makna ayat-ayat tersebut dan memberlakukan secara khusus ayat-ayat tersebut juga, yakni dalam lingkungan yang tidak bersa-habat. Berangkat dari kesulitan ini, Mun’im memberikan “kunci” dengan berargumen bahwa untuk mengurai kebebalan tersebut, yak-ni membuka kemungkinan tafsir baru yang sesuai dengan semangat dan kepentingan masa. Ini dilandasi dengan pemikiran bahwa tafsir merupakan produk masa dan tempatnya sendiri, sedangkan teks-teks menyediakan berbagai kemungkinan makna.24
Sampai di sini, mungkin Mun’im belum sampai pada tafsir Shihab atas soal ini yang sudah memberikan tafsir alternatif atas ayat-ayat tersebut sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan tuntut-an problem keragaman agama masa kini.25 Penutup
Buku ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur’an, yang berpandangan bahwa para mufasir reformis modern tidak selalu mengikuti tafsir-tafsir terdahulu tanpa pan-dangan yang kreatif dan kritis. Hal ini didasari bahwa tafsir adalah sebuah kegiatan intelektual yang selalu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kontekstual, baik ruang dan waktu. Kasus yang dilihat adalah mengenai ayat-ayat polemis tentang agama lain, dalam hal ini Kristen danYahudi.
Buku ini juga memberikan kontribusi bagi dialog dan kehar-monisan antar agama di Indonesia, yang dapat mewujudkan suasana yang harmonis.26 Benar bahwa persoalan teologis menjadi hal yang sangat pelik dan sulit untuk didialogkan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk upaya memahami—dengan batas-batas iman tertentu—demi mewujudkankesalingpahaman antara agama yang berbeda, khususnya di sini Islam, Kristen dan Yahudi. Meskipun buru-buru perlu ditambahkan bahwa, upaya memahami ini bukan
24Mun’im Sirry, hlm. 403. 25Lihat catatan kaki nomor 8. 26Buku lainnya yang juga penting bagi kontribusi hubungan harmonis antar
agama di Indonesia baru-baru ini juga telah terbit, terutama dari sisi sejarahnya. Hugh Goddard, Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia. Jakarta: Serambi, 2013.
138 138 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 125-139
berarti untuk menanggalkan iman seseorang, tetapi untuk keharmo-nisan dan kasih sayang sesama manusia. Bukankah itu yang dimak-sud dengan kaidah u¡ūl fiqh: dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-ma¡āli¥ (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meng-ambil kebaikan). Karenanya, buku ini layak dibaca bagi siapa yang berkepentingan bagi isu dialog dan hubungan antar agama di Indonesia, baik peniliti, pendidik, tokoh agama, aktivis dialog antar agama, pemangku kebijakan di bidang agama, maupun masyarakat secara umum yang meminati. Terakhir, meskipun bahasa yang digunakan buku ini relatif mudah dipahami, namun buku ini akan terasa lengkap dan informatif jika ditambahkan indeks, tetapi sayang kita tidak dapat menemukannya.
Daftar Pustaka
Esposito, John L., Islam Straigh Path: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus, Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat, 2010.
Ghazali, Abdul Moqsith, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an, Depok: KataKita, 2009.
Goddard, Hugh, Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia. Jakarta: Serambi, 2013.
Gusmian, Islah, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi, Yogyakarta: LKiS, 2013.
Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI, Jakarta: Yayasan Nurul Ilmi, 1976.
Hourani, Albert, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Bandung: Mizan, 2004.
Husein, Fatimah, Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia: The Exclusivist and Inclusivist Muslims’ Perspective, Bandung: Mizan, 2005.
Munawar-Rachman, Budhy, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: Sri Gunting, 2004.
Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1996.
Rakhmat, Jalaluddin, Islam dan Pluralisme: Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, Jakarta: Serambi, 2006.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 3, Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2009.
139 Tinjauan Buku: Polemik Kitab Suci— Agus Iswanto 139
________, Rasionalitas Al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar, Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2007.
Sirry, Mun’im, Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an terhadap Agama Lain, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Pustaka
Tim Tafsir Ilmi Lajnah dan LIPI, Waktu dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sains, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013, xxx + 135
halaman.
Masalah-masalah pokok terkait penafsiran ‘waktu’ dalam Al-Qur’an adalah menjawab pertanyaan apakah pemahaman manusia tentang waktu yang dipergunakan sehari-hari sama seperti yang di-maksud dalam Al-Qur’an atau ada pengertian lain? Mencari makna atas nama-nama waktu dan peristiwa dalam Al-Qur’an merupakan suatu yang menarik dalam prespektif sains dan spiritualitas.
Dalam Al-Qur’an, Allah menyebutkan banyak nama waktu di dalam sejumlah ayat-Nya, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ayat 36 Surah al-Baqarah menunjukkan waktu da-lam konteks kekuasaan Allah, pembatasan waktu dari sebuah peris-tiwa di planet bumi maupun di alam semesta tidak dapat dicampuri manusia. Ada siklus peristiwa yang dapat dipahami manusia namun ada pula fenomena yang siklusnya tidak diketahui dengan pasti, karena terlalu panjang dan terlalu singkat.
Surah A¡-¡āffāt ayat 137-138 menunjukkan waktu dalam kon-teks fenomena “pagi” yang dipahami manusia sebagai gubahan ke-adaan pada waktu matahari terbit hingga tengah siang. Sedangkan di waktu malam dipahami fenomena matahari berada di bawah ufuk maupun kulminasi bawah matahari.
Surah a«-¬u¥ā ayat 1-2 menunjukkan waktu dalam konteks fenomena pagi yang dipahami sebagai keadaan pada waktu mata-hari telah terbit dan menuju tengah hari. Sedangkan waktu malam dipahami sebagai fenomena lingkungan yang sunyi ketika matahari berada di bawah ufuk.
Bagi yang berdiam di Ekuador dan sekitarnya, fenomena peru-bahan suasana dari terbit hingga terbenam matahari merupakan fenomena-fenomena perubahan suasana dari terbit hingga terbenam matahari merupakan fenomena sehari-hari yang mudah dikenali. Namun bagi mereka yang diam di kutub akan menghadapi suasana ekstrem lain, matahari bisa terus menerus di atas horizon, dan juga
142 142 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 141-149
sebaliknya. Dalam setahun mereka menikmati kondisi tersebut da-lam beberapa hari, lebih sedikit bila dibandingkan dengan kawasan dekat ekuator.
Dalam bahasa Indonesia, istilah waktu diantaranya kemarin, besok, lusa, tahun depan, nanti, dan sebagainya. Al-Qur’an menye-but lebih banyak nama waktu. Beberapa diantaranya: sā‘ah, ¥īn, ajalin musammā, ummatim ma‘dūdah, ajal, al-waqt al-ma‘lūm, mau’īd, qadarim ma‘lum dan ajal al-qarīb.
Selain itu ada istilah-istilah al-lail, idbār, an-nahār, li dulu-qisysyams, gasaqi al-lail, a«-«u¥ā, ibkār, gadāh, bukrah, isyrāq, al-‘asyisyyi, al-’ā¡āl, ¯arafayin-nahār, zulafam-minal-lail, mu¡bi-¥īn, ¯u¡bi¥ūn, ¡ub¥, zuhur, fajr, an-nujūm, syahr, yaum, sanah, dan as-sinīn.
Beberapa isyarat waktu dalam Al-Qur’an memiliki pengertian satuan atau unit yang kecil sehingga terkesan tak bisa diukur, seperti sā‘ah (sekejap atau sesaat). Ada waktu yang diungkapkan dengan unit yang lebih besar: yaum (hari), syahr (bulan), atau sanah (tahun).
Isyarat waktu dalam Al-Qur’an dapat dikelompokkan sebagai berikut: pertama, waktu dalam pengertian tanpa batas yakni seperti sa‘ah (Q.S. al-An’ām/6:31 dan at-Taubah/9: 117). Kedua, waktu dalam pengertian di dalam bilangan jumlah tertentu/siklus semacam ‘āim, sinīn, dan sanah atau tahun. Ketiga, waktu yang merupakan bagian dari fenomena malam atau siang hari seperti disebutkan da-lam istilah-istilah ibkār, gadāh, bukrah, dan isyrāq. Keempat, waktu yang merupakan bagian dari sebutan-sebutan yang menun-jukkan lebih kecil dari penggalan waktu yang masuk kategori ketiga, misalnya ¯arafayin-nahār, zulafam-min-al-lail. Kelima, bagian-bagian waktu yang dikaitkan dengan nama salat, semacam «u¥ā atau sepenggalan naik, al-‘asr dan ¡ub¥. Keenam, waktu relatif, di antaranya dalam Surah al-¦ajj/22:47 dan Fa¯ir/35: 5 mengungkapkan “seribu tahun di bumi sebanding dengan sehari di hadapan Allah”.
Sekelumit bahasan singkat di atas merupakan bahasan yang ada pada buku Waktu dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sains. Tema besar yang dibahas dalam buku ini antara lain hubungan malam dan siang hari dengan Allah; jumlah bilangan bulan dalam Al-Qur’an; waktu dalam bilangan tahun; waktu untuk saat dan bilangan ter-tentu; waktu dalam kisah Al-Qur’an. []
143 Pustaka 143
***
Tim Tafsir Ilmi Lajnah, Makanan dan Minuman dalam Prespektif
Al-Qur’an dan Sains, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, 2013, xxx + 170 halaman.
Lebih dari enam miliar manusia penduduk bumi, dikaruniai
persediaan makanan dari bumi yang tiada habis-habisnya. Sumber makanan terutama dari berasal dari tanah berupa tanaman-tanaman didukung oleh keberadaan air dan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Dari tumbuhan Allah menciptakan biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sebagai makanan manusia seperti firman Allah dalam Q.S. ‘Abasa/80:24-32 dan Q.S. an-Na¥l/16: 11.
Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan sumber makanan yang dikenal sebagai sumber nabati. Ajaibnya, tanah atau sawah yang ditanami sejak zaman dahulu sampai sekarang praktis tidak pernah habis atau kehilangan unsur haranya. Proses daur ulang air beserta unsur hara seperti nitrogen, oksigen, dan fosfor di alam adalah proses teramat unik yang diciptakan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup tanam-tanaman. Surah ‘Abasa tersebut menjelaskan bahwa tanam-tanaman termasuk rerumputan juga diperuntukkan bagi binatang ternak guna makanan yang lezat dan menyehatkan.
Salah satu bab buku ini menjelaskan tentang halal dan haram menurut Al-Qur’an dan Hadis. Pada dasarnya semua makanan yag disediakan Allah, sebelum datang ketentuan Allah, dasar hukumnya adalah halal. Manusia sendiri yang kemudian tersesat dan berini-siatif menetapkan sebagai halal dan haram seperti tertuang dalam Q.S. Yūnus/10: 59 dan surah Ali ‘Imrān/3: 93. Yakub adalah Nabi pertama yamng mengharamkan beberapa makanan untuk dirinya sendiri. Pengharaman ini disebabkan oleh penyakit yang diderita dan mengharuskan beliau untuk menghindarinya. Apabila ia me-maksakan diri untuk memakannya maka ia yakin penyakitnya akan semakin parah. Di antara makanan yang dipantang Nabi Yakub adalah daging unta.
Ada empat makanan yang secara jelas diharamkan Al-Qur’an yaitu [1] hewan mati (bangkai), yaitu hewan yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat, misalnya hewan mati karena sakit,
144 144 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 141-149
tercekik, terpukul, terjatuh dan sebagainya; [2] darah mengalir atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih atau karena luka dan sebagainya; [3] daging babi dan semua bagian tubuhnya; [4] bina-tang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, seperti disembelih dengan menyebut nama berhala atau yang dipersembah-kan kepada selain Allah.
Dari ayat-ayat tentang makanan dan minuman dalam Al-Qur’an ditambah pandangan dari aspek ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman memiliki manfaat dan pengaruh penting bagi manusia di antaranya: pertama, sumber energi. Makanan akan dicerna dalam usus dan dibakar oleh oksigen yang diserap oleh paru-paru menghasilkan panas untuk gerak dan kegiatan. Kedua, makanan amat penting bagi anak-anak dan bayi atau janin dalam kandungan yang masih dalam proses pertum-buhan. Bagi orang dewasa, makanan penting untuk mengganti sel-sel yang mati atau rusak. Ketiga, kesehatan. Artinya, makanan yang halal dan sehat akan menjadikan jiwa tenang dan mudah bersyukur. Adapun makanan yang haram, baik zat maupun cara pengolahan-nya, akan berakibat buruk bagi jiwa maupun kehidupan spiritual seseorang. Keempat, keturunan. Baik buruknya makanan dapat pula berpengaruh pada keturunan. Ini karena makanan berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur orang tua. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil juga amat berpengaruh bagi perkembangan dan kesehatan janin di kandungannya. Status gizi ibu hamil adalah pele-tak dasar kesehatan keturunan. Dalam pendidikan pranatal, diajar-kan bahwa tali pusar tidak hanya mengalirkan dari ibu kepada janinnya sari makanan, tetapi juga mengalirkan kehidupan meta-fisik.
Uraian singkat di atas secara lengkap tertuang dalam buku Makanan dan Minuman dalam Presfektif Al-Qur’an dan Sains. Buku ini secara umum terdiri dari enam bab. Dimulai Pendahuluan, menyusul tema-tema lain tentang makanan dan minuman, antara lain Sumber Makanan dan Nilai Gizi; Metabolisme Makanan dalam Tubuh; Keamanan Pangan; Makanan Halal dan Haram. Pada bagian akhir buku ini diuraikan secara singkat latar belakang kebijakan sertifikasi halal.[]
***
145 Pustaka 145
Tim Tafsir Ilmi Lajnah, Samudra dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sains, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013, xxx + 140 halaman.
Al-Qur’an berulang kali menyebutkan dan mengenalkan laut, samudra, pantai, muara, dan berbagai hal yang terkait dengan laut. Hal tersebut menakjubkan, karena kitab suci ini diturunkan di wila-yah padang pasir, bahkan tidak ada satu pun riwayat yang menyata-kan adanya ayat yang diturunkan di tengah samudra. Walau demi-kian, Al-Qur’an begitu jelas menerangkan keterkaitan antara kehi-dupan manusia dengan eksistensi laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Bukan sekadar menun-jukkan kekuasan Allah, tetapi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, mulai dari fungsi prasarana transportasi, penyediaan sumber protein, sumber energi, hingga aneka komoditas yang bisa diperoleh dari laut.
Dalam Al-Qur’an terdapat dua istilah, yaitu al-yamm dan al-ba¥r. Kata yamm berasal dari bahasa Suryani yang diarabkan untuk mengungkapkan wilayah air asin atau sungai yang sangat besar. Dari ketujuh ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang al-yamm, semuanya berkaitan dengan kisah Musa dan Firaun. Kata tersebut lebih tepat diartikan sebagai sungai besar. Hal ini didasarkan pada kisah ibu Musa yang menghanyutkan bayinya sebagai upaya penye-lamatan dari usaha pembunuhan oleh Firaun, sebagaimana terekam dalam Surah al-Qa¡a¡/28: 7 dan °āhā/20: 38-39.
Adapun istilah al-ba¥r dijumpai dalam 38 ayat. Kata ini pada umumnya diungkapkan untuk menunjukkan sejumlah besar kum-pulan air asin atau sedikit tawar. Disebut demikian karena luas dan dalamnya air yang terdapat di dalamnya, dan kadang-kadang ting-kat keasinannya menurun sehingga mendekati tawar atau payau.
Perbincangan Al-Qur’an tentang samudra itu sendiri, dalam artian tidak sekadar menyadarkan manusia tentang fungsi dan kegu-naannya, tetapi sampai pada pelibatan perasaan yang dalam tentang kekuasaan Allah yang telah menciptakan semua itu. Manusia disa-darkan bagaimana samudra luas terbentang, menyimpan aneka biota laut dengan volume air yang tidak mungkin diketahui secara pasti, dan ditundukkan agar mudah dilayari untuk mengantar ma-nusia dari satu tempat ke tempat lain. Fenomena samudra sering dijadikan Al-Qur’an untuk menyadarkan manusia akan keterbatas-
146 146 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 141-149
annya sebagai hamba, dan karenanya ia mau mengagungkan Allah Sang Pencipta. Perumpamaan akan tak terbatasnya firman Allah digambarkan dengan melebur volume air tujuh samudra untuk dija-dikan tinta, dan pepohonan dijadikan pena, semuanya tidak akan mampu menuliskan firman-Nya, Q.S. al-Kahf/18: 109 dan Q.S. Luqmān/31: 28.
Luas lautan melebihi luas daratan, air laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-rata laut sekitar 3.800 m, jauh berbeda dengan dari ketinggian rata-rata daratan yang hanya 840m. ruang kehidupan yang tersedia di lautan 300 kali lebih ba-nyak dibandingkan dengan daratan dan udara.
Terdapat tiga teori yang paling banyak penganutnya tentang asal mula air. Pertama, air terpisah dari bebatuan sebagai fase gas yang terpisah dari fase padat pada proses pembekuan. Kedua, mate-rial pembentuk bumi dari awan angkasa luar yang tergabung dalam gumpalan inti. Ketiga, air datang belakangan bersama benda angka-sa lain setelah bumi terbentuk. Adapun tahapan pembentukan laut ada empat yaitu tahap pembentukan air pertama, tahap rumah kaca; tahap kondensasi, dan tahap perkembangan makhluk hidup. Secara geologi, samudra bukan sekadar wilayah yang digenangi air. Dasar semudra ternyata memiliki karakteristik sendiri yang berbeda de-ngan permukaan daratan, baik dalam hal morfologi maupun kimia-wi dan mineralogi penyusun batuan.
Terdapat banyak pelajaran yang dapat ditarik dari pembahasan tentang samudra, antara lain: Pertama, samudra yang dijelaskan dalam Al-Qur’an merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang harus direnungkan untuk memperdalam dan mempertajam keyakin-an kita akan kemahakuasaan Allah. Kedua, air laut yang sangat melimpah dapat digunakan untuk bersuci yang disyaratkan dalam berbagai ibadah, seperti untuk istinja’, wudu dan mandi. Air laut termasuk dalam kategori air mutlak. Ia mendaur air-air yang sudah dipakai melalui aliran sungai yang ke samudra. Ketiga, samudra diciptakan untuk menstabilkan alam ini; ada daratan dan ada pula lautan, semuanya saling mempengaruhi. Semua benda alam memi-liki manfaat bagi yang lain. Samudra menampung air yang meng-alir dari pegunungan dan lembah. Kemudian melalui proses alami-ah air laut menjadi air hujan yang menumbuhkan muka bumi. Keempat, samudra diciptakan oleh Allah untuk memberi kemu-dahan dan penghidupan bagi umat manusia. Dalam beberapa ayat
147 Pustaka 147
Al-Qur’an Allah menjelaskan kemudahan melakukan mobilisasi di laut. Laut juga memberi manfaat sebagai sumber mata pencaharian. Kelima, samudra luas menyimpan kekuatan dahsyat. Ia dapat melu-luhlantakkan berbagai benda yang dilaluinya. Kita mengenal badai besar di tengah samudra, topan laut, tsunami, dan berbagai jenis gelombang lainnya. Keenam, Al-Qur’an memberi pesan moral ke-pada manusia untuk senantiasa memelihara dan memanfaatkan ka-runia Allah sebaik-baiknya tanpa merusaknya. Alam dianugerahkan Allah untuk seluruh makhluk, termasuk generasi yang lahir setelah generasi kita saat ini.
Paparan di atas merupakan bahasan yang ada pada buku Sa-mudra dalam Prespektif Al-Qur’an dan Sains. Buku ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Agama (LPMA) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Buku ini membahas beberapa subtema tentang samudra antara lain: Penciptaan Samudra; Peranan Laut untuk Kehidupan Bumi; Laut Sebagai Tanda Kemahakuasaan Allah; Samudra sebagai Rahmat Allah; dan Potensi Bencana Ke-lautan. [] Abdul Hakim
***
Zainal Arifin Madzkur (dkk.), Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia, Jakarta: Lajnah Balitbang Kemenag,
2013, xviii + 180 halaman.
Bebeberapa tahun belakangan ini kesadaran keagamaan ma-syarakat Islam Indonesia menunjukan grafik yang terus meningkat. Indikasi mengenai hal ini setidaknya bisa dilihat dari semakin se-marak dan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang diseleng-garakan. Bersamaan dengan meningkatnya kesadaran ini, tidak sedikit dari mereka yang kemudian melakukan upaya kritik ter-hadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, baik berupa tradisi, perilaku, hingga produk-produk keagamaan tertentu yang sebelumnya sudah terbangun mapan, established. Salah satu yang mendapat kritik adalah Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia. Sikap kritis sebagian orang terhadap Mushaf Standar Indonesia sedikitnya terekspresikan dalam dua kategori, yakni me-reka yang sekadar mempertanyakan, dan yang kedua mereka yang menggugat keabsahannya.
148 148 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 141-149
Untuk pertama, yang sekadar mempertanyakan, mereka umum-nya bersikap demikian karena didasarkan pada ketidaktahuan tentang eksistensi Mushaf Standar Indonesia, ditinjau dari penama-an maupun isinya; misalnya apa yang membedakan Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Saudi, mana dasar penulisan mushaf ini, dan sejumlah pertanyaan lain yang terkait. Sedangkan yang kedua sudah pada tahap menggugat. Yang kedua ini biasanya memperta-nyakan landasan penetapan Mushaf Standar Indonesia ditinjau dari sisi rasm, waqaf dan lain sebagainya. Kalangan terakhir ini sering menilai dan berargumen bahwa mushaf standar Indonesia tidak Usmani. Benarkah demikian?
Buku Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia memuat jawabannya. Buku yang ditulis Zainal Arifin Madzkur dkk ini membahas tentang asal mula perumusan dan penetapan Mushaf Standar Indonesia. Buku yang diterbitkan Lajnah ini mencoba mengurai dan mendudukkan persoalan yang berkaitan dengan Mus-haf Standar Indonesia ke tengah masyarakat sebagaimana yang sering dipertanyakan. Karya ini diharapkan menjadi ‘buku putih’ yang menjelaskan secara komprehensif tentang apa dan bagaimana Mushaf Standar Indonesia yang selama ini dipertanyakan masya-rakat.
Mushaf Standar Indonesia yang menjadi rujukan resmi dalam penerbitan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia ini tidak lahir dari ruang yang kosong. Ada banyak diskusi dan perdebatan cukup ketat yang menyertai lahirnya Mushaf ini. Sedikitnya ada sembilan rangkaian Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur’an yang mengiringi lahirnya Mushaf Standar Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang dinamika yang muncul pada Muker tersebut, di bagian awal, pe-nyusun menjelaskan terlebih dahulu pengertian Mushaf Standar Indonesia. Pada definisi ini dijelaskan, bahwa Mushaf Standar adalah “Mushaf Al-Qur’an yang dibakukan cara penulisan, harakat, tanda baca, dan tanda waqafnya, sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur’an yang berlangsung 9 kali, yakni dari tahun 1974–1983 dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Qur’an yang diterbitkan di Indonesia”. Mushaf yang menjadi rujukan ini terdiri dari tiga, yakni Mushaf Standar Usmani untuk orang awas, Bahriyah untuk para penghafal Al-Qur’an, dan Braille bagi tunanetra. Tiga jenis mushaf ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA).
149 Pustaka 149
No. 25 Tahun 1984, sedangkan penggunaannya sebagai pedoman dalam pentashihan ditetapkan melalui Instruksi Menteri Agama (IMA) No. 7 Tahun 1984.
Bab selanjutnya memuat gambaran pelaksanaan Muker Ulama Al-Qur’an dari tahun 1974–1983 berikut dinamika yang ada di dalamnya. Beberapa hal yang diungkap pada bagian ini, di antara-nya adalah sejarah munculnya Musyawarah Kerja Ulama, diskusi yang terjadi di setiap Muker, dan keputusan yang dihasilkan. Salah satu perdebatan yang muncul pada pada Muker 1, di Ciawai, Bogor, adalah pembahasan Mushaf Standar mengenai boleh dan tidaknya mushaf ini ditulis dengan rasm imla’i. Menyikapi hal ini, para ulama menolak usulan tersebut. Di antara ulama yang menolak adalah KH. Arwani, Kudus dan KH Abdul Hamid, Pasuruan yang mewakilkan pandangannya pada KH Ali Maksum Krapyak. Penda-pat serupa juga dikemukakan KH. Abdullah Pabbajah, Sulawesi Selatan dan KH. Nur Ali, Bekasi. Terkait persoalan ini, peserta Muker mensepakati beberapa hal, di antaranya bahwa Mushaf Al-Qur’an tidak boleh ditulis selain dengan rasm usmani kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian, naskah Pedoman Penulisan dan Pen-tashihan Mushaf Al-Qur’an yang disusun oleh Lembaga Lektur Ke-agamaan Departemen Agama disetujui sebagai pedoman dalam penulisan dan pentashihan Al-Qur’an di Indonesia.
Pembahasan tentang identitas mushaf standar terus disem-purnakan pada setiap Muker, seperti penetapan harakat, penulisan lafal Allah, memberi tanda tasydid untuk hukum tajwid seperti idgam, memberi tanda khusus pada mad wajib dan mad jaiz, saktah, dan imalah, hingga tanda waqaf. Dengan demikian, penetapan rasm, harakat, dan lain sebagainya yang menjadi ciri khas Mushaf Standar Indonesia ditetapkan dan diputuskan melalui rangkain muker ulama yang memiliki otoritas khusus berkaitan dengan mushaf standar. Buku ini pada gilirannya ingin menegaskan, bahwa Mushaf Standar Indonesia yang selama ini dijadikan rujukan dalam menerbitkan Al-Qur’an secara pasti menggunakan rasm usmani, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi menjadikan Al-Qur’an terbitan Indonesia sebagai Al-Qur’an yang menggunakan rasm usmani.[] Mustopa.
149 - 2
عالمات�الضبط����امل��ف�املعياري�اإلندون�����من�منظور�
علم�الضبط ز�ن�العارف�ن�مذ�ور
،�جاكرتااإلدارة�املركز�ة�لشؤون�القرآن�الكر�م
�املعياري��ركز ت �امل��ف ��� �الضبط �عالمات ��� �البحث �إعادة �ع�� �الورقة �ذه
)� �اعتماMushaf Al-Qur’an Standar Indonesiaاإلندون���� �تم �والذي (���� ده
.��تقع�أ�مية��ذا�١٩٨٤عملية�طبع�املصاحف�وتداول�ا����أنحاء�إندون�سيا�منذ�عام�
���� �الضبط �دراسات �مجال ��� �اإل�اديمية �للبحوث �مقدمة �بمثابة �أنھ ��� البحث
���� �املعمول���ا �الضبط �تطور�عالمات �لرصد�تار�خ �أنھ�محاولة �جانب امل��ف،�إ��
�يتطر �لم �والذي �بإندون�سيا �امل��ف �والدراسات�رسم �البحوث ��� �الكث�� �إليھ ق
�ب�ن� �يث���خالفا �كث��ا�ما �الضبط �القص���لعلم �الف�م �وأن ��ذا، القرآنية�بإندون�سيا.
الباحث�ن�كما��و�ا��اصل����رسم�امل��ف�وكتابتھ.
Mushaf Al-Qur’an Standar:��امل��ف�املعياري�اإلندون�����(ال�لمات�الرئ�سة
Indonesia.عالمات�الضبط�،(
عالقات�املؤسسية�ملراجعة�:�الامل��ف�مراجعة� أنماط
امل��ف�بإندون�سيا عبد�ا��كيم
ب�ت�القرآن،�جاكرتا
يقوم�الباحث�����ذا�البحث��شرح�األنماط�املتبعة����مراجعة�املصاحف�بإندون�سيا�
� �عام �قبل �فيما �املطبوعة �وعدد�من�املصاحف �املخطوطة �أخذ�املصاحف �١٩٥٩مع
�القرآن�نموذجا،�وذلك�الع �إ�شاء�اإلدارة�املركز�ة�لشؤون �فيھ �تم �الذي ��و�العام ام
152 149-3 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 149-2 – 149-6
�املؤسسة� �و�� �الدي�ية، �الشؤون �بوزارة �سابقا) �املصاحف �مراجعة �(��نة الكر�م
���� �نمطان ��ناك �بإندون�سيا. �تداول�ا �قبل �املصاحف �بمراجعة �تقوم �ال�� الوحيدة
��مراجعة�املصاحف�املخطوطة،�و�ما� ���امل��ف�واملراجعة�املراجعة�األولية�أثناء
األخ��ة��عد�االن��اء�من�ال���.�أما�بال�سبة�للمصاحف�املطبوعة�ف�ناك�أيضا�نمطان�
�واملراجعة�من� �املؤسسة�الدي�ية�املحلية�أوال، �قبل �و�ما�املراجعة�من من�املراجعة،
�اإلندون�سي�ن� �القرآن �علماء �من �امل�ونة �الكر�م �لشؤون�القرآن �املركز�ة �اإلدارة قبل
ا.ثاني
�الرئ�سة �القرآن�ال�لمات �لشؤون �املركز�ة �اإلدارة �املطبوعة، �املصاحف �املراجعة، :
الكر�م
أبرا�ام�جيجر�والدراسات�القرآنية
(دراسة�من��ية�لكتاب�"ال��ودية�واإلسالم") لي���لستاري
جامعة�سونان��ا���جاغا�اإلسالمية�ا���ومية،�يوغياكرتا
� �املمن ���ا �قام �ال�� �البحوث �لدى�نتائج �إيمانيا �تث���قلقا �ما �كث��ا �وال�� س�شرقون،
� �تقليد �إال �ل�س �الكر�م �القرآن �أن �األخ����و �اآلونة ��� �املسلم�ن �العلماء �–�عض
� �–بزعم�م �أحد�� �جيج��، �أبرا�ام �قالھ �الزعم �و�ذا �ال��ودية. �الديانة لتعاليم
الفكر�ة�ألبرا�ام��املس�شرق�ن�ال��ود.�تحاول��ذه�الورقة�دراسة�ما�ي��:�أوال:��ا��لفية
�الديانة� �من �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �محمد �أخذه �ما �غيغر�حول �آراء �ثانيا: جيجر.
ال��ودية.�وثالثا:�الرد�ع���دراسات�جيجر�حول�القر�آن�الكر�م.
نقدي،�محمد،�القرآن،�ال��ود.- :�أبرا�ام�جيجر،�تار���ال�لمات�الرئ�سة
149-4
وغ�س�تأليف����التفس���املكتوب�بلغة�بدراسة�حالة�العدة
مجلس�العلماء�اإلندون�����بمحافظة�سوالو�����ا��نو�ية محمـد�يوسف
جامعة�عالء�الدين�اإلسالمية�ا���ومية،�ما�اسار
�املرأة� �عدة �موضوع �حول �املسلم�ن �بوغ�س �علماء �آراء �دراسة �البحث ��ذا يحاول
،�و�و�تفس���للقرآن�Tafsere akorang Mabbasa Ogiاملطلقة�من�خالل�كتاب�
�ا��نو�ية.�ا �سوالو���� �ملحافظة �اإلندون�سي�ن �العلماء �مجلس �تأليف �من � �لكر�م
وموضوع�العدة�من�املوضوعات�ال���تحظى�ا�تماما�بالغا�خاصة�من�قبل�الناشط�ن�
�الشرعية� �األح�ام �مجموعة ��� �العدة �مف�وم �واجھ �فقد �ا���سية. �املساواة ��
)Kompilasi Hukum Islamأن�� �فبدال�من �ا���سية، �باسم�املساواة �طعنا �اآلن (
يتم�تطبيق�العدة�ع���املرأة،�قالوا�إنھ�يجب�تطبيق�العدة�ع���الرجل�أيضا.�وفسروا�
�السياق� �ومن �النص، �مف�وم �من �النظر�إليھ �يجب �العدة �موضوع �بأن �ذلك قول�م
حفظ�ال�سب��التار����لھ،�إ���جانب�السياق�الثقا��.�فالعدة�واإلحداد�الغرض�م��ما
إ���جانب�أ��ما�فرصة�لكال�ا��انب�ن�من�الرجل�واملرأة�ملراجعة�الذاتومحاولة�التوسط�
�املمكن� �من �بوغ�س �ملجتمع �املحلية �الثقافية �القيم �أن �الباحث �يرى �للطالق. تجنبا
اعتباره�لتطبيق�العدة.
ا��فظ،��ال�لمات�الرئ�سة:�العدة،�اإلحداد،�املرأة،�ا���س،�ثقافة�بوغ�س،�املالءمة،
مراجعة�الذات.
مراجعة�نظام�توز�ع�املصاحف�لوزارة�الشؤون�الدي�ية�بمحافظة�
جاوا�الشرقية أحمد�ز���
،�جاكرتااإلدارة�املركز�ة�لشؤون�القرآن�الكر�م
154 149-5 ¢u¥uf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 149-2 – 149-6
مراجعة�نظام�توز�ع�املصاحف�بوزارة�الشؤون�الدي�ية�حيث�يبدو��يحاول��ذا�البحث
�توز�ع�ا��ش�ل�م� �يتم �لم �خاصة�وكأن�املصاحف �األقاليم، �جميع �االن�شار��� ساوي
�ع���امل���امليدا�ي،�فإن�الوزارة�تقوم�بتطبيق� أقاليم�محافظة�جاوا�الشرقية.�فبناء
)� �القنوات �متعدد �التوز�ع �و�و�النظام�multichannel distribution systemنظام ،(
ما�أ��ا��الذي�يمكن�من�خاللھ�أن�تلعب�قناة�ما�من��ذه�القنوات�بدور�ن�مختلف�ن��
�عملية�التوز�عمن�أن��ذا�النظام�يتم����ع���الرغم�وسيطة�وموزعة����نفس�الوقت.�
�السر�عة ،� �أنھ �إال �ليفتح �مجاال �تداخل �ان�شار��املس��دفةالفئات �عليھ �ي��تب مما
�غ��� �فئات �إ�� �ووصول�ا �جانب، �من �األقاليم �جميع �غ���م�ساو��� ��ش�ل املصاحف
�وع����ذا، �من�جانب�آخر. �����ل�قناة�من����يحة �الفئات�املس��دفة �تجزئة فإن
�ذه�القنوات�حل�من�ا��لول�املمكنة.
:�نظام�توز�ع�املصاحف،�وزارة�الشؤون�الدي�يةل�لمات�الرئ�سةا
مخطوطات�املصاحف�من�محافظة�سوالو�����الغر�ية�(بإندون�سيا)
دراسة�جوانب�علم�الرموز
ع���أك��
تاب�ت�القرآن�ومتحف�االستقالل،�جاكر
�محافظة� �من �الشر�ف �امل��ف �من �قديمة ���� �ثما�ي �بدراسة ��ذه�الورقة تقوم
�ا��زء� ��� �الباحث �يقوم �فردية. �مكت��ات �من �و�ل�ا �بإندون�سيا، �الغر�ية سوالو����
�يقوم� � �التا��، �ا��زء ��� �ثم، �ومن �الثما�ي، �ال��� �من ��ل ��عرض �ورقتھ �من األول
�ودراسة�النص �الزائدةأو�امل��قة���ا،�بدراسة�ا��انب�الن����ل�ل����ة �األخرى وص
�تمت�دراس��ا�مأخوذة�من� �ال�� �واملصاحف �أول�امل��ف�أو����آخره. ��انت��� سواء
�أحد� �ممتل�ات �من �اآلن �أ��ا �من �الرغم �ع�� �التقليدية �"بوغ�س" �مجتمع مصاحف
األفراد����إقليم�"ماندار"�بمحافظة�سوالو�����الغر�ية.�ومن�املالحظ�أن�نظام�الرسم�
149-6
ا�ي�يك���استعمالھ����املصاحف�املتداولة�بمحافظة�سوالو�����ا��نو�ية�بما����العثم
�املصاحف� �أن �كما �عشر. �التاسع �القرن ��� �وذلك �"بو�ي"، �و �"واجو" �إقليما ذلك
املدروسة�تم�أ��اق�القراءات�السبع�ع����وامش�ا،�ما�عدا����ة�واحدة�،�مما��ش���
�علوم�القرآن�ال���ت �ذلك�إ���املستوى�الرفيع�من �املح����� وصل�إل��ا�املجتمع�املسلم
�سوالو����� �مصاحف �من �عددا �فإن �الزخرفية، �باإلضاءة �يتعلق �فيما �أما الوقت.
�ا��نو�ية� �من�مصاحف�سوالو���� �وعددا �النباتية، �الزخرفة �نوع الغر�ية��عتمد�ع��
ع���نوع�الزخرفة�ال�ندسية.
�الغر�ية �سوالو���� �القديمة، �املصاحف �الرئ�سة: �الزخرفية،�ال�لمات �اإلضاءة ،
بوغ����،�القرآن�الكر�م.
Ketentuan Pengiriman Tulisan Ketentuan Umum Redaksi Jurnal Suhuf menerima artikel ilmiah dari para peneliti dan pengkaji Al-Qur’an, baik tentang mushaf, terjemahan, tafsir, rasm, qira'at, dan ulumul Qur’an. Artikel belum pernah dipublikasikan di media atau jurnal lain. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Redaksi berhak menyunting artikel tanpa mengurangi maksudnya. Isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengem-balikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan. Pengiriman artikel harus disertai dengan surat resmi dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirim ke:
Redaksi JURNAL SUHUF Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal, Jl. Raya TMII Pintu I Jakarta, 13560
Penulis mengirim satu eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta
file (softcopy) dalam compact disk (CD) atau melalui surat elektronik ke: [email protected]
Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi nama lengkap (tanpa gelar apa pun), tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal dan alamat lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, dan e-mail untuk kepentingan korespondensi.
Ketentuan Khusus
Seluruh bagian dari tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik satu setengah (1½) spasi, minimal 20 halaman dan maksimal 25 halaman, kertas ukuran A4. Pengetikan menggunakan font “Times New Roman-Arab” untuk bodytext, ukuran 12. Untuk tulisan Arab di dalam bodytext menggunakan font “Times New Roman” ukuran 12. Untuk teks Arab yang pisah dari bodytext menggunakan font “Traditional Arabic” ukuran 16. Margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah 3 cm.
Ketentuan Penulisan
Sistematisasi tulisan adalah sebagai berikut: 1. Judul. Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang
singkat, padat, dan jelas. Dalam judul sudah sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. Nama penulis. Nama penulis ditulis lengkap, tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari satu orang ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan
149-9
lambang “&”). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (satu spasi di bawah nama penulis).
3. Abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keselurahan naskah. Ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak maksimal terdiri atas 200 kata. Kata kunci ditulis di bawah abstrak, antara tiga hingga enam kata/frase.
4. Pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, serta hipotesis (jika ada).
5. Metode penelitian. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, jika artikel merupakan hasil peneliti-an.
6. Temuan dan pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari hasil pene-litian, meliputi: deskkripsi data dan analisis hasil penelitian, serta inter-pretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggu-naan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
7. Cara penyajian tabel. Tabel ditampilkan tanpa menggunakan garis vertikal. Judul ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis dengan font “Times New Roman” 12. Tulisan “Tabel” dan “nomor” ditulis (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal. Gunakan angka arab (1, 2, 3, dst…) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditam-pilkan rata kiri halaman (bukan center). Jenis dan ukuran font untuk isi tabel menggunakan “Times New Roman Arabic” ukuran 8-11 dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan “Times New Roman Arabic” ukuran 10.
8. Cara penyajian gambar, grafik, foto, dan diagram. Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman (center). Keterangan gam-bar, grafik, foto, dan diagramditulis di bawah ilustrasi. Tulisan “gam-bar”, “grafik”, “foto”, dan “diagram” serta “nomor” ditulis tebal (bold), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst…) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantum-an sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri menggunakan “Times New Roman Arabic” ukuran 10. Ilustrasi gambar, grafik, foto, dan diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
9. Penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang meliputi kesimpulan dan saran (jika ada).
Adapun rujukan/referensi ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki)
menggunakan font “Times New Roman-Arab”, ukuran 10, dengan format (nama penulis, judul buku (italic), tempat terbit: penerbit, tahun, nomor halaman). Contoh (M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Mizan,1996, hlm. 280). Untuk referensi surat kabar/majalah ditulis: “judul artikel” (nama surat
149-10 kabar/majalah, tanggal, bulan, tahun, dan halaman). Contoh: “Khazanah Mushaf Al-Qur’an Kalimantan Barat”, Hidayatullah, Edisi Juni 2013, hlm. 37.
Sedangkan penulisan Daftar Pustaka mengacu format sebagai berikut. 1. Buku. Pengarang (nama belakang, nama depan), judul buku, tempat
terbit: Penerbit, tahun. Contoh: Tjandrasasmita, Uka, Arkeologi Islam Nusantara, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
2. Bab dalam buku. Pengarang (nama belakang, nama depan), “Judul Artikel/Tulisan”. Dalam Judul Buku Utama, editor, tempat terbit: pe-nerbit, tahun.
3. Jurnal. Pengarang (nama belakang, nama depan), “judul artikel/ tulisan.” nama jurnal, edisi, tahun.
4. Surat kabar/majalah. Pengarang (nama belakang, nama depan), “judul artikel,” nama surat kabar, tanggal, tahun. untuk artikel berita, hanya ditulis: nama surat kabar/majalah, tanggal, bulan, tahun.
5. Internet. Pengarang (nama belakang, nama depan), “judul tulisan,” nama website, tanggal diakses, tahun.
6. Skripsi/tesis/disertasi. Pengarang (nama belakang, nama depan), “judul skripsi/tesis/disertasi”, pada lembaga perguruan tinggi, tahun.
7. Makalah seminar/tidak diterbitkan. Pengarang (nama belakang, nama depan), tahun, “makalah”, makalah disampaikan pada seminar, penyelenggara, tempat, tanggal, tahun.
Penulisan transliterasi mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987 tentang Translitereasi Arab-Latin. 1. Konsonan
No Arab Latin No Arab Latin
Tidak ا 1dilambangkan 16 ط ¯
§ ظ b 17 ب 2
‘ ع t 18 ت 3
g غ 19 £ ث 4
f ف j 20 ج 5
q ق 21 ¥ ح 6
k ك kh 22 خ 7
l ل d 23 د 8
m م 24 © ذ 9
n ن r 25 ر 10
w و z 26 ز 11
149-11
h ه s 27 س 12
‘ ء sy 28 ش 13
y ي 29 ¡ ص 14
» ض 15
2. Vokal Pendek
تب
a kataba : _ ك
i su’ila : _ سئل
�ب
u ya©habu : _ يذ
3. Vokal Panjang
ال ـ ــــ:��ق
ā qāla ـاـ
ī qīla يـــ ــــ:��قيل
:�ـ�يقول ū yaqūlu و ـ
4. Kalimat panjang
�ار د ع ال
مو ل Dār al-‘Ulūm
ع ني الد �م و ل ‘Ulūm ad-Dīn
5. Diftong
ي ai = ا
ي ك
ف kaifa
و ل و ح au = ا ¥aula