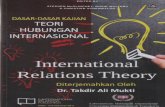14 II. KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Perkembangan ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 14 II. KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Perkembangan ...
14
II. KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Perkembangan Agama dan Moral
a. Teori Perkembangan Agama dan Moral
Makna agama dan keyakinan beragama berubah sepanjang jalan
perkembangan, sebagian besar teori agama memiliki landasan teori perkembangan
kognitif Piaget (Bridges & A.Moree, 2002). Fokus dari teori-teori ini adalah pada
struktur pemikiran keagamaan karena berubah dari waktu ke waktu, bukan pada isi
keyakinan agama, yang paling terkenal di antara teori-teori ini adalah teori Elkind,
Goldman, Fowler, dan Oser. Teori-teori ini memiliki kesamaan bahwa pemikiran
keagamaan, dalam hubungannya dengan bidang pemikiran lainnya, bergerak dari
sesuatu yang konkret dan keyakinan literal di masa kanak-kanak ke pemikiran
keagamaan yang lebih abstrak di masa remaja.
Teori-teori perkembangan keagamaan yang dielaborasi oleh Elkind, Fowler,
dan Oser, serta perspektif teoritis keterikatan Kirkpatrick tentang perkembangan
perbedaan individu dalam agama. Berikut akan dijelaskan beberapa teori tentang
perkembangan agama dan moral yaitu:
1) Studi Elkind tentang perkembangan agama
Pada masa remaja dan dewasa, individu-individu memahami bahwa setiap
agama yang berbeda memiliki keyakinan dasar yang berbeda, termasuk keyakinan
yang berbeda tentang sifat Allah (atau para dewa) dan manusia, dan hubungan antara
keduanya yang diungkapkan melalui ibadah, doa, dan kegiatan kehidupan sehari-hari.
Ketika remaja dan dewasa mereka lebih sadar dalam beragama dan beribadah, patuh
15
terhadap perintah-perintah di dalam agama mereka dan menganggap agama penting
dalam kehidupan mereka. Elkind pada tahun (1964; 1970) dalam artikelnya
menemukan bahwa pemahaman seperti itu tentang kepercayaan dan praktik
keagamaan tidak hadir pada anak-anak, tetapi lebih berkembang di masa kanak-kanak.
Elkind menyatakan bahwa ada tiga tahap perkembangan agama di masa kanak-kanak
dan remaja yang sejajar dengan tahap pra-operasional, operasional konkret, dan
operasional formal perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget.
2) Teori pengembangan Iman Fowler
Fowler mengembangkan teori pengembangan iman seperti teori Elkind,
mencakup serangkaian tahapan yang sebagian besar mengikuti teori tahap
perkembangan kognitif Piaget. Teori ini juga sangat dipengaruhi oleh teori psikososial
Eric Erikson tentang pengembangan identitas ego. Sebagaimana didefinisikan oleh
Fowler, Iman adalah proses dinamis dari komitmen yang memusatkan kepercayaan
dan kesetiaan kita, ketergantungan dan kepercayaan diri pada realitas kehidupan.
Fowler menyarankan bahwa iman berkembang dalam konteks hubungan antar pribadi,
dan kapasitas dan kebutuhan akan iman adalah sifat bawaan manusia. Iman mencakup
iman religius, tetapi iman juga dapat mencakup kepercayaan dan kesetiaan pada pusat
nilai termasuk keluarga, negara, dan lainnya.
3) Teori Oser
Teori Oser berfokus pada pengembangan penilaian agama. Oser
mendefinisikan penilaian agama sebagai alasan yang menghubungkan realitas sebagai
pengalaman dengan sesuatu di luar realitas yang berfungsi untuk memberikan makna
dan arah tujuan hidup (Bridges & A.Moree, 2002). Oser sangat tertarik pada perubahan
16
perkembangan dalam penjelasan yang dimiliki anak-anak dan orang dewasa untuk
pengalaman, baik pribadi maupun yang diamati, yang tampaknya bertentangan dengan
kepercayaan agama. Oleh karena itu penilaian agama melibatkan jawaban yang
ditemukan oleh individu untuk mereka sendiri yang mendamaikan iman agama dan
kenyataan yang tampaknya bertentangan dengan iman itu.
Oser menggambarkan lima tahap dalam pengembangan penilaian agama, tiga
diantaranya merupakan tahap-tahap penalaran yang dicapai pada masa kanak-kanak
dan remaja, dan yang keempat berkembang dalam minoritas individu di masa remaja.
Tahap 1, pandangan anak-anak tentang Tuhan sangat konkret dan literal. Tuhan dilihat
sebagai terlibat langsung dalam peristiwa sehari-hari di dunia, sebagai penyebab
semua peristiwa dan sebagai menciptakan semua hal. Tuhan harus dipatuhi karena
ketidaktaatan membawa hukuman langsung, seperti kecelakaan atau sakit. Pada saat
yang sama, individu dipandang memiliki pengaruh minimal terhadap Tuhan. Bentuk
penilaian religius ini sejajar dengan tahap paling awal dari penalaran moral pra-
konvensional seperti yang dijelaskan oleh Colby dan Kohlberg (1987), di mana hukum
dan peraturan harus dipatuhi terutama untuk menghindari hukuman.
Pada tahap 2 dan 3, anak-anak dan remaja yang lebih tua memandang Tuhan
dengan cara yang kurang menghukum. Tuhan dapat dipengaruhi oleh perilaku baik
seorang individu, dengan doa, dan kepatuhan pada ritual dan praktik keagamaan.
Terlihat sebagai bukti dalam kehidupan yang sehat dan bahagia, murka Tuhan atas
kegagalannya untuk campur tangan di saat terjadi perselisihan. Pada saat yang sama,
Tuhan juga dipandang lebih kecil kemungkinannya untuk campur tangan secara
konkret dan langsung dalam urusan manusia.
17
Pada tahap 4 dan 5, individu yang mempertahankan iman dapat kembali kepada
Tuhan sebagai pencipta akhir yang merupakan sumber kebebasan dan kehidupan, dan
yang keberadaannya membuat hidup bermakna. Teori Oser tidak menyarankan bahwa
semua penilaian agama yang diperlihatkan oleh seorang individu akan selalu berada
pada tahap yang sama, atau bahwa semua individu pada usia yang sama akan
menunjukkan tingkat penilaian agama yang sama.
4) Teori Kirkpatrick
Kirkpatrick mengusulkan bahwa kepercayaan dan praktik keagamaan individu
dipengaruhi oleh orang tua mereka, dan kualitas hubungan ikatan orangtua-anak.
Menurut Kirkpatrick (Bridges & A.Moree, 2002) anak-anak yang hubungan dengan
orang tuanya aman cenderung untuk mengadopsi kepercayaan agama orang tua
mereka. Lebih lanjut, berdasarkan pada teori kelekatan, Kirkpatrick menyarankan
bahwa hubungan individu dengan Tuhan dapat dianggap sebagai hubungan kelekatan.
Seperti halnya hubungan kelekatan yang dibangun antara pengasuh dengan bayi,
diharapkan akan sangat mempengaruhi karakteristik kualitas hubungan dengan Tuhan.
Hubungan yang baik dengan orang tua yang beragama, dapat ditiru oleh anak
bagaimana orang tua mereka beragama dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan
kepercayaan pada Tuhan. Begitu sebaliknya hubungan yang tidak aman dengan orang
tua, akan membuat anak atheis dan meragukan kepercayaan mereka pada Tuhan. Pada
masa remaja atau dewasa, seseorang dapat beralih ke hubungan pribadi dengan Tuhan
dalam upaya untuk mendapatkan keamanan yang tidak tersedia bagi mereka dari
hubungan keterikatan awal mereka.
18
5) Penilaian moral oleh Piaget
Didalam karya klasik Piaget (Crain, 2014:193), The Moral Judgment of Child
(1932), Piaget memberi perhatian khusus kepada cara anak memahami aturan
permainan marbel. Piaget mengamati bagaimana cara anak-anak memainkan
permainan itu sesungguhnya, dan dia menemukan bahwa antara usia empat sampai
tujuh tahun, anak-anak bermain dengan cara egosentris. Mereka tidak mengerti
menang dan kalah, bahkan mereka akan berkata satu sama lain “aku menang dan kamu
menang juga.” Namun setelah usia tujuh tahun, anak-anak mulai berusaha mengikuti
aturan umum permainan dan berusaha menang menurut aturan-aturan tersebut.
Piaget meneliti pemikiran anak-anak tentang aturan. Dititik ini Piaget
menemukan bahwa anak-anak selama beberapa tahun sampai usia 10 tahun percaya
bahwa aturan sudah baku dan tidak bisa diubah. Jika aturan diubah maka
permainannya harus berubah juga. Setelah usia 10 tahun lebih, anak-anak jadi lebih
relatif terhadap aturan. Aturan dilihat sebagai cara-cara yang sama disetujui untuk
memainkan permainan. Mereka tidak lagi melihat aturan sebagai hal yang baku, dan
mereka menyatakan bahwa aturan bisa dirubah selama setiap orang di dalam
permainan setuju.
Konsepsi yang berbeda-beda tentang aturan ini mengisyaratkan dua sikap
moral mendasar yaitu heteronomi moral dan otonomi moral (Crain, 2014:194).
Heteronomi moral adalah sebuah kepatuhan yang kaku terhadap aturan-aturan yang
dipaksakan orang dewasa, anak berasumsi bahwa terdapat sebuah hukuman yang mesti
mereka ikuti. Moralitas kedua, yaitu berasal dari anak yang lebih tua usianya yang
disebut otonomi moral. Moralitas ini menganggap aturan-aturan yang dibuat untuk
19
kesetaraan demi kerja sama yang baik yang memungkinkan individu bersikap dan
berprilaku sesuai control dirinya.
Piaget percaya kalau heteronomi moral terikat pada egosentrisme, anak-anak
memandang aturan dari perspektif tunggal, yaitu perspektif orang dewasa yang
berkuasa atas dirinya. Sebagai suatu bentuk egosentrisme, heteronomi moral baru bisa
ditaklukkan sekitar usia 10 tahun atau lebih. Piaget mengingatkan bahwa heteronomi
adalah suatu bentuk pikiran egosentris dari anak. Anak-anak perlu terlibat di dalam
hubungan yang baik dengan bermain bersama teman-teman sebayanya.
Berdasarkan beberapa teori tentang perkembangan agama dan moral seperti
teori Elkind, Fowler, Oser, Kirkpatrick, dan Piaget semuanya merujuk sesuai pada
tahap perkembangan anak usia dini. Teori perkembangan agama dan moral juga sama
dengan teori yang lainnya yang juga merujuk pada teori Piaget.
b. Hakikat Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia Dini
Golck dan Stark (Dewi, 2017) mendefinisikan agama sebagai simbol,
keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terpusat pada persoalan-persoalan
hidup. Tipologi Glock dan Stark dengan ajaran Islam, dan menurut mereka tipologi
tersebut mampu menjelaskan konsep beribadah secara menyeluruh dalam ajaran Islam,
yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dalam beribadah kepada Allah. Dimensi
religiusitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dimensi ideologis/ keyakinan (akidah), sejauh mana seorang muslim mempercayai
ajaran-ajaran yang sifatnya fundamental dan dogmatis dalam Islam, seperti; rukun
iman.
20
2. Dimensi intelektual/ pengetahuan (ilmu), sejauh mana pengetahuan yang dipahami
oleh setiap muslim berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan, ritual, kitabsuci, dan
tradisi-tradisi yang dilakukan.
3. Dimensi ritual/ praktik agama (syariah), berkaitan dalam menjalankan ibadah,
misal; sholat lima waktu, membaca Al-Quran, puasa, dan lainnya.
4. Dimensi penghayatan/ eksperiensial, berkaitan dengan pengalaman-pengalaman
keagamaan, seperti; persepsi, perasaan, dan sensasi ketika melakukan komunikasi
dalam suatu esensi ketuhanan.
5. Dimensi konsekuensial/pengalaman (akhlak), bagaimana seorang muslim
berperilaku di dunia dengan motivasi oleh nilai religius internal. Diibaratkan bahwa
dimensi ini merupakan hasil dari proses identifikasi terhadap keyakinan
keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang yang diekspresikan
dalam tindakan perilakunya sehari-hari.
Mendefinisikan agama ada dua pendekatan, yaitu pendekatan substantif dan
pendekatan fungsional (Syamsudin, 2016). Pendekatan substantif lebih menekankan
apa itu agama, sedangkan pendekatan fungsional lebih menekankan apa guna agama
bagi pemeluknya. Pendekatan substantif menyebut agama identik dengan Tuhan yang
maha suci, sedangkan pendekatan fungsional menyebut agama sebagai ruang bagi
ekspresi manusia untuk menyatukan diri atau memecah belah umat manusia. Pola
definisi agama ada empat yaitu; personal fungsional, personal substansial, sosial
fungsional, dan sosial substansial (Syamsudin, 2017). Definisi agama memakai pola
personal fungsional menjadi agama sebagai pemenuhan tujuan spiritual individu, pola
personal substansial menjadi agama sebagai kesadaran personal tentang yang sakral.
21
Pola definisi agama yang tepat untuk anak usia dini adalah personal fungsional,
yaitu anak memenuhi rasa ingin tahunya tentang yang gaib melalui apa yang
bermanfaat atau berbahaya bagi dirinya melalui pengalaman langsung. Berdasarkan
pengalaman langsung itulah anak-anak akan mengenal dan menghayati perilaku positif
yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. (Syamsudin, 2016). Makna agama
yang dipahami anak-anak tidak sama dengan makna agama yang dipahami oleh orang
dewasa, terlebih lagi perbedaan rasa beragama diantara keduanya. Rasa beragama
berbeda dengan pengetahuan tentang agama, baik orang dewasa maupun anak-anak.
Perbedaannya adalah, pengetahuan agama adalah informasi tentang agama yang
bersumber dari kitab suci, sedangkan rasa beragama adalah buah dari pengetahuan
terhadap agama tersebut. Menurut Dzakiyah Darajat (Suyadi, 2010:125) anak-anak
sudah mempunyai rasa beragama melalui perkembangan bahasa yang diucapkan
orangtua atau orang dewasa sekelilingnya.
Munculnya agama dalam diri anak berawal dari mengenal Tuhan melalui kata-
kata. Pada awalnya anak bersikap acuh tak acuh terhadap kata Tuhan tersebut. Namun
seiring dengan perkembangan otaknya, kemudian didukung oleh fungsi mata yang
mulai mampu menatap ekspresi kepatuhan orang dewasa kepada Tuhan, anak mulai
gelisah dan ragu-ragu. Kegelisahan tersebut disebabkan karena anak-anak belum
mempunyai pengalaman empiris mengenai Tuhan sama sekali, sedangkan ia sendiri
menyaksikan ekspresi kepatuhan orang-orang dewasa kepada Tuhan. (Suyadi,
2010:128).
Saat anak-anak menaruh perhatian pada kata Tuhan, sejak itulah ia sedikit demi
sedikit mempunyai pengalaman empiris mengenai agama. Biasanya, pada awal-awal
22
perhatiannya pada kata Tuhan, pengalaman tersebut bersifat tidak menyenangkan.
Contoh: ketika anak melihat orang dewasa beribadah dengan penuh ketaatan, anak
mempersepsikan bahwa Tuhan adalah menakutkan yang harus ditaati; ketika anak
mendengar bahwa orang yang bersalah atau berdosa akan dihukum di neraka, dan anak
mempersepsikan Tuhan sebagai hakim yang kejam. Begitu seterusnya, sehingga anak-
anak gelisah hatinya. Saat hatinya gelisah anak-anak berusaha untuk menolak
kehadiran Tuhan dalam dirinya. Namun, perasaan tersebut semakin ditolak justru
semakin kuat mempengaruhi dirinya.
Freud (Suyadi, 2010:128) mengatakan “Mengingkari kenyataan yang
menyakitkan hati adalah satu fase pertengahan antara menekan dan menerima.” Freud
memberi argumen bahwa mengingkari pengalaman pahit membuahkan ketenangan
dalam hati. Artinya, semakin kuat seseorang menolak sesuatu, semakin kuat ia
memikirkannya, walaupun hanya untuk ditolak. Oleh karena itu, semakin kuat anak-
anak menolak kata Tuhan justru semakin kuat mereka untuk menerimanya. Ketika
persepsi anak sampai pada sifat-sifat positif Tuhan (Maha Pengampun, Maha
Pemurah, Maha Penyayang, dan lain-lain), maka hatinya menjadi tenang. Selanjutnya,
ia akan menerima kehadiran Tuhan dalam dirinya. Sejak itulah Tuhan muncul dari
dalam diri anak. Dengan demikian, munculnya Tuhan dalam diri anak bermula dari
faktor luar (bahasa) yang mempengaruhinya dan kemudian diterima oleh anak melalui
pengalamannya (Suyadi, 2010:129).
Perkembangan moral sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan
santun, dan kemauan dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang sebagai pribadi, masyarakat maupun
23
warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah suatu proses pendekatan yang
digunakan secara komprehensif untuk menjadikan anak bermoral (Suryana, 2016:50).
Dengan adanya nilai-nilai moral yang tertanam dari keluarga, diajarkan di sekolah oleh
guru dan masyarakat diharapkan setiap anak dapat memparaktikkan nilai moral dalam
totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai moral yang sudah ada
pada anak memudahkan anak untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam
mewujudkan masyarakat yang ideal.
Hubungan akhlak dengan moral tidak dapat dipisahkan, moral adalah keadaan
batin yang menentukan perilaku manusia dalam bersikap, bertingkah laku dan
perbuatannya. Dalam agama Islam, moral dikenal dengan akhlaq al karimah, yaitu
kesopanan yang tinggi dan keyakinan terhadap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas
yang tergambar dalam perbuatan lahir manusia (Inawati, 2017). Sikap dan perbuatan
manusia diharapkan sesuai dengan nilai agama dan norma masyarakat. Nilai agama
dan akhlak (moral) sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa hakikat perkembangan agama
dan moral anak usia dini dimulai dari munculnya Tuhan dalam diri anak dan diikuti
dengan sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan ajaran agamanya. Anak memiliki
rasa beragama melalui perkembangan bahasa dari orang disekelilingnya. Agama dan
moral erat kaitannya dengan budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun dan
kemauan dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan
dalam penelitian ini adalah rasa beragama anak dimulai dari lingkungan, oleh karena
itu stimulasi lingkungan sangat dibutuhkan anak untuk menumbuhkan rasa beragama
mereka dari usia dini.
24
c. Tahapan Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia Dini
Menurut Harms (Akbar, 2019:55) membagi tahapan perkembangan agama
pada anak menjadi tiga, yaitu:
1. Tahap fairytale (tingkat dongeng)
Tahap ini dialami anak usia 3-6 tahun. Pada tahapan ini anak membangun konsep
ketuhanan berdasarkan khayalannya, misalnya mengenl Tuhan sebagai raksasa,
hantu, malaikat bersayap, dan sebagainya.
2. Tahap realistis (tingkat kenyataan)
Tahap ini dialami anak usia 7-12 tahun. Pada tahapan ini anak lebih cendrung
mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok
penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar bagi
kehidupan di bumi. Konsep ini dapat timbul dari pengajaran agama, pengalaman
dan dari orang dewasa lainnya.
3. Tahap individualistik (tingkat individu)
Pada tahap ini, anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama
tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13-18 tahun yang terbagi atas dua
golongan. (a) konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif yang didapat
anak dari lingkungan sekitar, sehingga dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. (b)
konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang
bersifat personal (perorangan) yang didapat dari pemikiran pribadi berdasarkan
pengalaman yang didapat anak.
25
David Elkind mengembangkan teori Piaget ke dalam pola perkembangan
keagamaan pada anak. Elkind (Akbar, 2019:55) empat kebutuhan mental yang
muncul ketika anak tumbuh dewasa, yaitu:
1. Pencarian untuk konservasi, anak menganggap bahwa hidup ini adalah abadi.
2. Tahap pencarian representasi, tahap ini dimulai saat anak prasekolah. Hal
terpenting dalam tahap ini adalah gambaran perkembangan mental dan bahasa.
3. Pencarian relasi, pada tahap ini anak telah memiliki kematangan mental
sehingga ia dapat merasakan hubungan dengan Tuhan.
4. Pencarian tentang pemahaman, pada tahap ini anak menyerap jalinan
persahabatan dan kemampuan berteori telah berkembang.
Menurut Piaget dalam teori perkembangan moral menyimpulkan bahwa
anak melewati dua tahap yang berbeda dalam cara mereka berfikir tentang moralitas
(Akbar, 2019:60; Santrock, 2007:117) yaitu:
1. Moralitas Heteronom (dari usia 2 – 7 tahun)
Pada tahap ini anak belum dapat menalar atau menilai suatu aturan yang
berlaku di sekitar anak, sehingga anak masih memandang kaku pada aturan
tersebut. Anak memandang perilaku benar dan salah bukan berdasarkan
motivasi dari dalam dirinya, melainkan dari konsekuensi yang didapatnya.
2. Moralitas Otonom (setelah usia 7 tahun)
Pada tahap ini anak mulai mengalami tahap moralitas otonomi.
Memandang suatu aturan tidak kaku lagi dan berkembang secara bertahap
seiring dengan perkembangan kognitifnya, yaitu berpikir abstrak, memahami
dan memecahkan masalah berdasarkan asumsi, dalil, atau teori tertentu.
26
Misalnya, jika pada tahap sebelumnya anak menganggap berbohong adalah
salah dalam segala situasi, maka pada tahap ini anak memandang berbohong
tidak selamanya salah. Perbuatan ini dianggap benar jika terdapat alasan yang
dapat diterima.
Menurut Kohlberg (Akbar, 2019:61; Crain, 2014:231; Santrock, 2007:120),
mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Piaget menjadi tiga tahapan
perkembangan moral pada anak yaitu:
1. Tahap moralitas pra-konvensional
Tahap ini dialami oleh anak usia 4-9 tahun. Ciri khas yang terdapat pada tahap ini
adalah anak tunduk pada aturan yang berlaku di lingkungan. Perilaku pada diri anak
dikendalikan oleh akibat yang muncul pada perilaku tersebut, yaitu hadiah dan
hukuman. Contoh: anak tidak mau memukul adiknya karena takut dimarahi orang
tuanya, serta anak berperilaku baik agar mendapat hadiah atau pujian dari orang
tua.
2. Tahap konvensional
Tahap ini dialami oleh anak usia 9-13 tahun. Pada tahap ini perilaku anak timbul
dari kesepakatan yang dibuat bersama lingkungan anak sebagai bentuk penyesuaian
diri. Contoh: anak melakukan perbuatan tertentu karena ingin diterima atau bermain
bersama teman sebayanya.
3. Tahap pascakonvensional
Tahap ini dialami oleh anak di atas usia 13 tahun yang telah mampu mengendalikan
perilakunya dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegangnya. Anak
memutuskan suatu tindakan moral alternatif dan menjajaki pilihan-pilihan. Pada
27
tahap ini, anak diharapkan mampu membentuk keyakinannya sendiri dan bisa
menerima jika ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda yang tidak
mudah untuk diubah atau dipengaruhi oleh orang lain.
Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap
tahapan perkembangan agama dan moral pada anak usia dini memiliki tahapan yang
disesuaikan dengan usia dan karakteristik perkembangan anak usia dini.
Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat memiliki pengaruh yang besar
terhadap setiap tahapan yang dialami oleh anak.
d. Karakteristik Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia Dini
Keberagamaan pada anak usia dini berkembang melalui pengalaman dari
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pengalaman anak yang bersifat
keagaaman akan membawa pada sikap, perilaku dan tindakan yang sesuai dengan
ajaran agamanya. Sifat dan bentuk pemahaman keagamaan pada anak usia dini,
Mansur (Akbar, 2019:56) adalah sebagai berikut:
1. Tidak mendalam (Unreflective), ajaran agama yang diterima dari lingkungan akan
dipahami anak sekedarnya. Artinya anak akan merasa puas dengan keterangan yang
diberikan meskipun kurang masuk akal.
2. Egosentris, seiring dengan pertumbuhan yang dialami, egosentris pada anak akan
semakin meningkat sejalan dengan pengalaman yang diperolehnya. Sehingga,
konsep keagamaan dipahami anak berdasarkan kesenangan pribadinya dan
menonjolkan kepentingan dirinya.
3. Antrophomorphis, artinya anak memahami konsep ketuhanan seperti manusia. Bagi
anak, Tuhan adalah sosok yang memiliki wajah, hidung, tangan dan sebagainya.
28
4. Verbal dan ritualis, perkembangan keberagamaan anak muncul seiring dengan
pembiasaaan yang diberikan kepadanya. Kehidupan beragama pada anak muncul
dengan cara menghapal kalimat-kalimat keagamaan serta tuntutan perilaku dari
lingkungan.
5. Imitatif, anak melakukan kegiatan keagamaan berdasarkan hal-hal yang dilihatnya
di lingkungan kemudian ditiru oleh anak. Contoh ketika orangtua melakukan ibadah
anak menirukan gerakan ibadah tersebut sesuai dengan yang dilihatnya. Sifat peniru
pada anak menjadi pengaruh yang besar dalam pendidikan keagamaan pada anak
usia dini.
6. Rasa heran, sifat keagamaan pada anak adalah rasa heran. Artinya anak merasa
kagum pada keindahan sesuatu. Rasa kagum pada anak adalah rasa kagum pada
keindahan yang bersifat lahiriah. Sehingga untuk mengembangkan nilai keagamaan
pada anak, dapat disalurkan melalui berbagai cara yang menimbulkan rasa kagum
pada diri anak, seperti bercerita.
Selain itu, rasa keberagamaan pada anak dapat timbul melalui dua hal (Akbar,
2019:57), yaitu:
1. Rasa ketergantungan, manusia memiliki empat keinginan sejak dilahirkan, yaitu
keinginan perlindungan, pengalaman baru, mendapatkan tanggapan dan dikenal.
Melalui keinginan inilah manusia hidup dalam ketergantungan. Melalui
pengalaman yang diperoleh dari kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan
tersebut, akan terbentuk rasa keagamaan pada diri anak.
29
2. Insting keagamaan, bayi yang baru lahir telah memiliki insting keagamaan. Namun
insting tersebut belum berfungsi dengan matang karena beberapa fungsi kejiwaan
yang menopang insting tersebut belum sempurna.
Robert W.Crapps (Akbar, 2019:58) menjelaskan proses pendidikan agama
pada anak usia dini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Pembinaan pribadi anak
Orangtua merupakan pembina pribadi pertama dalam hidup anak. Melalui
proses pendidikan orangtua maupun guru dapat melakukan pembinaan pada
anak baik melalui pendidikan formal maupun informal. Setiap pengalaman yang
diperoleh anak melalui penglihatan, pendengaran, maupun perilaku yang
diperoleh anak, akan membentuk pembinaan pribadi pada anak.
2. Perkembangan agama pada anak
Pengalaman keagaaman pada anak akan membentuk sikap dan perilaku
yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendidikan agama bagi anak usia
dini sebaiknya ditanamkan bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya, bahkan
sejak anak berada dalam kandungan.
3. Pembiasaaan pendidikan pada anak
Dalam menanamkan sikap terpuji pada anak, tidak cukup bila hanya
penjelasan saja, melainkan perlu adanya proses pembiasaan. Pembiasaan dan
latihan akan membawa anak pada perilaku yang baik. Agama akan lebih
memiliki arti pada anak apabila dijelaskan dengan cara yang lebih dekat pada
anak dalam kehidupan sehari-hari dan lebih konkret.
30
e. Capaian Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia 5-6 Tahun
Sesuai Peraturan Menteri dan Kebudayaan No.146 Tahun 2014, bahwa
perkembangan agama dan moral adalah salah satu aspek perkembangan yang perlu
distimulasi sejak usia dini. Pengembangan nilai agama dan moral mencakup
perwujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari
nilai agama dan moral, serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat. Capaian
perkembangan nilai agama dan moral anak usia 5 – 6 tahun dalam Peraturan Menteri
dan Kebudayaan No.146 Tahun 2014 (KD 3.1dan 3.2) yaitu mengenal kegiatan
beribadah sehari – hari dan mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia.
KD 3.1 dan 3.2 merujuk pada Kompetensi Inti (KI-3) kompetensi inti pengetahuan.
Diawali dari pengetahuan anak tentang agama dan moral, yang memutuskan untuk
anak bertindak dan berperilaku baik atau buruk berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan moral dan agama yang
memiliki tiga komponen yaitu: komponen kognitif (knowing), afektif (sikap moral),
dan tindakan moral (action) (Wiyani, 2013).
2. Teori Belajar Behaviorisme
Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pada peran
lingkungan yang dapat diramalkan dalam memunculkan perilaku yang teramati
(Papalia, Olds, & Feldman, 2009:48). Pandangan behaviorist memandang bahwa
lingkungan sangat berpengaruh. Mereka percaya bahwa manusia di semua umur
belajar mengenai dunia dengan cara sama, dengan bereaksi terhadap kondisi atau
aspek dari lingkungan mereka yang dianggap menyenangkan, menyakitkan atau
31
mengancam. Penelitian perilaku berfokus pada belajar mengasosiasikan (associative
learning), dimana hubungan mental dibentuk antara dua rangsangan atau peristiwa
sensoris. Dua bentuk belajar mengasosiasikan adalah classical conditioning dan
operant conditioning.
Classical conditioning, Psikolog Rusia bernama Ivan Pavlov (Papalia & Ruth
Duskin Feldman, 2015:33) membuat berbagai eksprerimen perihal anjing belajar
mengeluarkan air liurnya saat mendengar suara bel berbunyi sebagai tanda waktu
makan. Eksperimen ini menjadi dasar untuk pengkondisian klasikal (classical
conditioning). Pengkondisian klasikal yakni respon (dalam kasus ini, air liur) terhadap
stimulus (suara bel) membangkitkan (setelah dilakukan berulang kali) asosiasi dengan
stimulus yang normalnya memperoleh respon (makanan)
Behaviorist dari Amerika, John B.Watson (1878-1959), melakukan sejenis
teori respons stimulasi kepada anak, menyatakan bahwa dia dapat mencetak semua
bayi dengan cara yang dia pilih. Dia menulis pengaruh generasi dari orangtua untuk
melaksanakan prinsip teori belajar dalam pengasuhan anak. Di satu demonstrasi awal
dan yang paling terkenal dari pengkondisian klasikal pada manusia, yaitu dia melatih
bayi 11 bulan yang dikenal sebagai “Albert kecil” untuk takut pada objek putih yang
berbulu. Albert terpapar suara keras ketika mulai mengguncang seekor tikus, suara
ramai menakutkan dan membuat Albert menangis. Setelah berulang memasangkan
tikus dengan suara ramai yang keras, Albert merengek dengan ketakutan ketika
melihat seekor tikus. Albert juga mulai menunjukkan respons takut pada kelinci putih
dan kucing. Pengkondisian klasikal terjadi sepanjang kehidupan, suka dan tidak suka
terhadap makanan tertentu mungkin sebagai hasil dari belajar pengkondisian. Respon
32
takut terhadap objek seperti mobil atau anjing mungkin merupakan hasil dari suatu
kecelakaan atau pengalaman buruk (Papalia & Ruth Duskin Feldman, 2015:33).
Operant conditioning, belajar berdasarkan asosiasi perilaku dengan
konsekuensinya. Seorang psikolog dari Amerika Serikat bermana B.F Skinner,
merumuskan prinsip-prinsip operant conditioning, lebih banyak melakukan penelitian
dengan menggunakan tikus dan merpati. Skinner mengatakan bahwa prinsip yang
sama berlaku bagi manusia. Ia menemukan bahwa suatu organisme akan cendrung
mengulang sebuah respons yang telah diperkuat (reinforced) dengan akibat-akibat
yang menarik dan akan menekan sebuah respons yang telah dihukum. Penguatan
(reinforcement) adalah proses ketika perilaku diperkuat, meningkatkan kecendrungan
bahwa perilaku akan diulang. Penguatan bisa positif atau negatif, penguatan positif
terdiri atas pemberian ganjaran seperti makanan, bonus, atau pujian. Penguatan negatif
terkadang hampir sama dengan hukuman. Hukuman (punishment) dalam operant
conditioning, suatu proses melemahkan dan menurunkan pengulangan suatu perilaku
(Papalia & Ruth Duskin Feldman, 2015:34).
Penguatan paling efektif ketika dengan segera mengiringi suatu perilaku, jika
tidak lagi mendapatkan penguatan, pada akhirnya suatu respon anak memudar, yaitu
kembali ke tingkat semula. Modifikasi perilaku atau terapi perilaku merupakan suatu
bentuk operant conditioning yang digunakan untuk menghilangkan perilaku yang
tidak diinginkan atau mengajari perilaku positif secara bertahap. Hal tersebut terutama
efektif diantara orang-orang kebutuhan khusus, gangguan mental, atau emosional.
Skinner memiliki penerapan yang terbatas, karena fokusnya pada prinsip-prinsip
33
perkembangan yang luas, dan tidak memadai untuk menangani perbedaan dalam
perilaku (Papalia et al., 2009:50).
Berdasarkan penjelasan di atas, teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme berpusat pada
lingkungan, peran lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku yang muncul
pada anak. Pemberian stimulus-respon yang sering dilakukan atau berulang-ulang
pada lingkungan sekitar anak membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Pemberian stimulus berupa media buku cerita bergambar yang memiliki ukuran besar,
warna-warna menarik, ilustrasi gambar cerita, dan memiliki bahasa Minang, membuat
anak merasa tertarik dan merespon dengan baik. Penerimaan respon yang baik
terhadap buku cerita bergambar membuat anak antusias mengikuti alur cerita sampai
selesai, dan menyimpan informasi penting atau pesan moral dalam cerita dapat
tersampaikan dengan baik dan melekat pada pengetahuan anak.
3. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” dan merupakan bentuk jamak
dari kata “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media
merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran,
perasaan, dan kemauan anak sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada
diri anak tersebut. Media merupakan bagian yang melekat atau tidak terpisahkan dari
proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara garis besar media
adalah alat bantu sebagai penyalur pesan atau penyampaian informasi seperti manusia,
34
materi, buku teks, lingkungan sekolah atau kejadian yang membangun kondisi
membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna
mencapai tujuan pembelajaran (Aqib, 2013;50 Arsyad, 2013:3; Djamarah, 2010:121).
Dengan adanya media, pembelajaran akan lebih menarik, interaktif, dan
menyenangkan sehingga secara tidak langsung kualitas pembelajaran pun dapat
ditingkatkan ke arah yang lebih baik (Fadlillah, 2014:205).
Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar diartikan
sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan
menyusun kembali informasi visual atau verbal. Batasan lain telah dikemukakan pula
oleh para ahli dan lembaga, diantaranya adalah berikut: (a) AECT (Association of
Education and Communication Technology) memberikan batasan tentang media
sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau
informasi. (b) Henich dan kawan-kawan dalam mengemukakan istilah medium
sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Televisi,
film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan,
dan sejenisnya adalah media. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi
yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud pembelajaran maka media itu
disebut media pembelajaran.
Media pembelajaran (Kustandi, Cecep dan Bambang, 2011:9) adalah alat yang
dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna
pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran lebih baik dan
sempurna. Media pembelajaran merupakan suatu bagian yang integral dari suatu
proses pendidikan di sekolah. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik
35
digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, sebagai sumber belajar yang
mengandung materi instruksional di lingkungan anak yang memotivasi anak untuk
belajar.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, berfungsi untuk
memperjelas makna pesan yang disampaikan, dan bertujuan untuk mengefektifkan dan
mengefisien proses pembelajaran itu sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan
pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.
b. Jenis Media Pembelajaran
Menurut (Djamarah, 2010:124-126) membagi jenis-jenis media dilihat dari
jenisnya: (a) Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara
saja, seperti: radio, casette recoder. (b) Media visual adalah media yang hanya
mengandalkan indra penglihatan, menampilkan gambar seperti foto, gambar, lukisan
dan cetakan. (c) Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan
unsur gambar.
Menurut (Wati, 2016:5) jenis media pembelajaran dibagi menjadi, (1) Media
visual, yaitu memiliki beberapa unsur berupa garis, bentuk, warna, dapat ditampilkan
dalam dua bentuk, menampilkan gambar diam atau symbol bergerak. (2) Media audio
visual, media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada
saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. (3) Komputer, sebuah perangkat yang
memiliki aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran,
menggunakan software atau perangkat lunak sebagai media untuk berinteraksi dalam
proses pembelajaran (4) Microsoft power point, (5) Internet, (6) Multimedia.
36
Media dilihat dari daya liputnya, dibagi menjadi: (a) Media dengan daya liput
luas dan serentak, tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah
anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh: radio dan televisi. (b) Media
dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, membutuhkan ruang dan
tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan
tempat yang tertutup dan gelap. (c) Media untuk pengajaran indidual, penggunaannya
untuk seorang diri. Contoh: modul berprogram dan pengajaran melalui computer.
Media dilihat dari bahan pembuatannya, dibagi menjadi: (a) Media sederhana,
bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah dan mudah digunakan. (b) Media
kompleks, bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit
membuatnya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Jenis-
jenis media pendidikan (Eliyawati, 2005:113-117) membagi ke dalam 3 bagian yaitu:
(1) media visual, adalah media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini paling
sering digunakan guru pada lembaga pendidikan anak usia dini untuk membantu
menyampaikan isi dari tema pendidikan. (2) media audio, adalah media yang
mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak untuk mempelajari isi
tema, melatih yang berhubungan dengan aspek keterampilan mendengarkan. (3) media
audio-visual, adalah kombinasi dari media audia dan visual. Dengan menggunakan
media ini maka penyajian pesan sesuai dengan tema kegiatan pada anak akan semakin
lengkap dan optimal.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
media pendidikan terbagi 3 yaitu, media visual (dilihat), media audio (didengar), dan
37
media audiovisual (dilihat dan didengar). Penggunaan masing-masing media
tergantung pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran
agar mendapatkan hasil yang optimal.
c. Fungsi Media Pembelajaran
Media mempunyai fungsi (Djamarah, 2010:122) sebagai alat bantu dalam
proses belajar mengajar, untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan
pengajaran. Hal ini dilandasi bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media
mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tengggang waktu yang cukup lama.
Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan
proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada tanpa bantuan media.
Fungsi media pembelajaran Levie dan Lentz (Kustandi, Cecep dan Bambang, 2011:21)
khususnya media visual dibagi menjadi: (1) Fungsi atensi yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian anak untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan
dengan makna visual. (2) Fungsi afektif dilihat dari tingkat kenikmatan anak ketika
belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat
menggugah emosi dan sikap siswa. (3) Fungsi kognitif media visual terlihat dari
temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar
memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau
pesan yang terkandung dalam gambar. (4) Fungsi kompensatoris, yaitu untuk
mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran
yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.
Menurut Kemp dan Dayton (Kustandi, Cecep dan Bambang, 2011:23) media
pembelajaran memiliki tiga fungsi utama apabila media itu digunakan perorangan,
38
kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal: (1) Memotivasi
minat atau tindakan, dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. (2)
Menyajikan informasi, (3) Memberikan instruksi, berfungsi sebagai pengantar,
ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat berbentuk
hiburan, drama atau teknik motivasi. Sejalan dengan (Rahmawati & Rukiyati, 2018)
bahwa stimulasi melalui media yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
anak dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak.
Secara perkembangan bahwa anak-anak mengalami kesulitan dalam
memusatkan perhatian mereka pada konten yang menonjol secara perseptual, dengan
media dapat menghubungkan pengetahuan mereka dengan konten yang ada di dalam
media (Piotrowski & Valkenburg, 2015)
d. Prinsip Media Pembelajaran
Prinsip penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan
pertimbangan guru diantaranya: a) pemilihan media pembelajaran, b) objektifitas
media pembelajaran, c) memahami kelebihan setiap media pembelajaran, d)
memahami karakteristik setiap media pembelajaran, e) faktor yang mempengaruhi
penggunaan media pembelajaran. Menurut Sudirman (Djamarah, 2010:126)
mengemukakan beberapa prinsip dalam pemilihan media pengajaran yaitu: (a) tujuan
pemilihan, memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan
yang jelas, (b) karakteristik media pengajaran, setiap media mempunyai karakteristik
tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara
penggunaannya, (c) alternatif pilihan, guru bisa menentukan pilihan media mana yang
akan digunakan apabila terdapat media yang dapat diperbandingkan.
39
Walker dan Hess (Arsyad, 2013:219) memberikan beberapa kriteria dalam
penentuan media pembelajaran berdasarkan kualitas, yaitu:
1. Kualitas isi dan tujuan, yaitu antara media pembelajaran yang dibuat atau dipakai
dapat memenuhi isi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berisikan
ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat/perhatian, kesesuaian
dengan situasi anak.
2. Kualitas instruksional, yaitu cara penyajian atau materi yang ada dalam media
pembelajaran berisikan tentang memberikan kesempatan belajar, memberikan
bantuan untuk belajar, memberikan motivasi, fleksibilitas instruksionalnya,
mempunyai hubungan dengan program pembelajaran lainnya, memberikan dampak
bagi anak, serta membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya.
3. Kualitas teknis/ kelayakan tampilan, yaitu terkait dengan tampilan fisik dan
ketahanan media pembelajaran yang akan digunakan. Berisikan tentang
keterbacaan teks, mudah digunakan, kualitas tampilan, dan sebagainya.
4. Buku Cerita Bergambar
a. Pengertian Buku Cerita Bergambar
Buku merupakan media yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan,
yakni meningkatkan peserta didik dalam berbagai aspek yang positif. Sebagaimana
pepatah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Hal tersebut dapat diartikan
bahwa buku merupakan salah satu jalan untuk menentukan kemajuan dunia. Buku
yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tingkat pendidikan (Fatimah,
2017).
40
Cerita merupakan wahana yang ampuh untuk mewujudkan pertemuan antara
emosi, pemahaman dan mental. Keasyikan dalam menyelami substansi cerita, apalagi
pencerita dapat menyelami materinya sehingga memasuki dunia minat anak tersebut,
dan menghasilkan penghayatan pengalaman yang paling mendalam. Terjadi
pertemuan tersebut merupakan peluang untuk menginkorporasikan segi-segi
pedagogis dalam ceritera tersebut, sehingga tanpa disadari cerita tersebut
mempengaruhi perkembangan pribadinya, membentuk sipak-sikap moral dan
keteladanan (Semiawan, 2008:34).
Horatius (Musfiroh, 2008:31) cerita adalah dulce et utile yang artinya
menyenangkan dan bermanfaat, anak senang menjadi penikmat cerita, karena
memberikan sisi kehidupan manusia, pengalaman hidup manusia dan bahan lainnya.
Cerita adalah karangan yang mengisahkan sesuatu benar-benar terjadi ataupun hayalan
bertujuan menghibur serta memberikan informasi kepada penikmatnya dalam
bentuknya bisa prosa atau puisi (Eliza, 2017). Cerita bergambar merupakan suatu
bahan ajar pembelajaran yang dapat menggambarkan atau mengintegrasikan
kehidupan sehari-hari anak. Dan dapat menjadi bahan ajar yang menyenangkan bagi
guru dan orang tua (Marlina: 2017).
Buku bergambar adalah buku bacaan cerita anak yang di dalamnya terdapat
gambar-gambarnya. Buku bergambar Huck (Nurgiyantoro, 2016:153) menunjuk pada
buku yang menyampaikan pesan lewat dua cara, yaitu lewat ilustrasi dan tulisan.
Ilustrasi (gambar) dan tulisan yang sama-sama dimaksudkan untuk menyampaikan
pesan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama dan saling mendukung
untuk mengungkapkan pesan. Jadi keduanya diikat oleh tuntutan untuk menyampaikan
41
pesan secara lebih baik dan kuat lewat dua cara yang berbeda, tetapi saling
menguatkan.
Sejalan dengan pendapat di atas, Mitchell (Nurgiyantoro, 2016:153) buku
cerita bergambar adalah buku yang menampilkan gambar dan teks, keduanya saling
berhubungan. Baik gambar maupun teks secara sendiri belum cukup untuk
mengungkapkan cerita secara lebih mengesankan, dan keduanya saling membutuhkan
untuk saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian pembacaan buku cerita
bergambar akan terasa lebih lengkap dan kongkret jika dilakukan dengan melihat
gambar dan membaca teks narasi lewat huruf-huruf, dan hubungan antara gambar dan
tulisan harus ada kesesuaian antara gambar-gambar cerita dengan alur teks dan tokoh
yang dikisahkan.
Lukens (Nurgiyantoro, 2016:154) menguatkan bahwa ilustrasi gambar dan
tulisan merupakan dua media yang berbeda, tetapi dalam buku cerita bergambar
keduanya secara bersama membentuk perpaduan. Gambar-gambar akan membuat
tulisan verbal menjadi lebih kelihatan, kongkret, dan sekaligus memperkaya makna
teks. Dalam buku cerita bergambar, gambar yang ditampilkan harus mencerminkan
alur dan karakter tokoh dan setiap ilustrasi tokoh dan alur cerita yang ditunjukkan
mengandung aspek-aspek latar yang mendukungnya Huck (Nurgiyantoro, 2016:154).
Sejalan dengan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa buku cerita
bergambar adalah buku yang didalamnya terdapat gambar dan tulisan yang saling
mewakilkan isi dalam cerita buku bergambar tersebut. Gambar cerita tersebut harus
menarik dan komunikatif. Kaitan dalam penelitian ini juga membuat ilustrasi gambar
yang memiliki tulisan di bawah gambar.
42
b. Jenis-jenis Buku Bergambar
Buku bergambar (picture book) dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis,
Rothlei dan Meinbach, 1991 dalam (Santoso, 2008) yaitu:
1. Buku abjad (alphabet book), dalam buku alphabet setiap huruf alphabet dikaitkan
dengan ilustrasi objek yang diawali dengan huruf. Ilustrasi harus jelas berkaitan
dengan huruf-huruf kunci dan gambar objek serta. Buku alfabet berfungsi untuk
membantu anak, menstimulasi, dan membantu pengembangan kosakata.
2. Buku mainan (toys book), menggunakan cara penyajian isi yang tidak biasa. Buku
mainan terdiri dari buku kartu papan, buku pakaian, dan buku pipet tangan. Buku
mainan ini mengarahkan anak-anak untuk memahami teks, dapat mengeksplorasi
konsep nomor, kata bersajak dan alur cerita.
3. Buku konsep (concept books), adalah buku yang menyajikan konsep dengan
menggunakan satu atau lebih contoh untuk membantu pemahaman konsep yang
sedang dikembangkan. Konsep-konsep ditekankan pengajarannya melalui alur
cerita atau dijelaskan secara repetisi dan perbandingan.
4. Buku bergambar tanpa kata (wordless picture books), buku untuk menyajikan cerita
melalui ilustrasi gambar saja. Buku bergambar tanpa kata terdiri dari berbagai
bentuk, seperti buku humor, buku informasi, atau buku fiksi. Mempunyai beberapa
keunggulan misalnya untuk mengembangkan bahasa dan tulisan lisan secara
produktif yang mengikuti gambar.
5. Buku cerita bergambar, memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Kedua
elemen ini merupakan elemen penting yang memuat berbagai tema
43
Kesimpulannya adalah dari beberapa jenis buku bergambar masing-masingnya
memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung kepada tujuan yang ingin
dicapai. Pada penelitian ini jenis buku bergambar yang akan digunakan adalah buku
cerita bergambar yang memiliki ilustrasi gambar dan tulisan, tulisan yang memakai
dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Buku cerita bergambar yang
memiliki tulisan, gambar, dan warna yang menarik akan membuat anak menjadi lebih
antusias dalam mendengarkan cerita yang ada dalam buku tersebut.
c. Karakteristik Buku Cerita Bergambar
Buku cerita bergambar untuk anak memiliki khas tersendiri, memiliki bahasa
dan ilustrasi yang terintegrasi dengan baik. Diharapkan anak mampu untuk
mengartikan atau menginterpretasikan gambar dengan teks yang dibacakan oleh orang
dewasa. Lukens (Ambarwati, 2016) menjelaskan tulisan dan gambar dalam buku cerita
bergambar memiliki hubungan yang sangat erat menjelaskan secara verbal tentang apa
yang mereka lihat dan memperluas makna yang membuat anak mampu untuk
berimajinasi dengan suguhan gambar yang diberikan.
Menurut Lukens (Ambarwati, 2016) delapan elemen sastra buku bergambar
yang perlu diperhatikan adalah karakter, plot, tema, latar, sudut pandang, gaya, ritme
dan tone. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teks pada buku cerita
bergambar adalah pemilihan gambar yang dapat mengaitkan kata dalam teks.
Karakteristik buku cerita yang sesuai bagi anak (Rahayu, 2017:89) diantaranya: (1)
bacaannya disukai, (2) topik menarik perhatian anak, (3) disesuaikan dengan tingkat
perkembangan anak, (4) menghubungkan pengalaman dan ketertarikan anak, (5)
penulisan cerita sangat bersahabat dan menjadi kesukaan anak, (6) ilustrasi cerita
44
sangat relevan pada latar belakang keluarga dan budaya anak, yakni ilustarsi cerita
memperkenalkan pada anak tentang latar belakang kebudayaan dan keluarga serta
pengalaman baru, (7) isi cerita merupakan kesukaan anak yang selalu ingin didengar,
(8) bahasa dan gambar mampu memberikan informasi serta ide baru bagi anak.
Menurut (Nurgiyantoro, 2016:156-157) ada beberapa kriteria dalam buku
cerita bergambar diantaranya:
1. Posisi dan format gambar
Letak gambar pada halaman-halaman dalam buku pada umumnya bervariasi,
misalnya ada di atas teks, di bawah teks, di sela-sela teks atau diapit oleh teks.
Penataan gambar-gambar itu memperhitungkan aspek keindahan tampilan, menarik
perhatian, enak dipandang, dan secara mudah mata anak beralih dari teks ke gambar
dan dari gambar ke teks. Pada buku cerita bergambar untuk anak, penampilan
gambar biasanya lebih mencolok, lebih besar, lebih realistik, dan menempati
separuh halaman atas.
2. Bahasa buku bergambar
Kata – kata dan teks dalam buku cerita bergambar sama pentingnya dengan
gambar ilustrasi. Membantu anak mengembangkan sensitivitas awal ke imajinasi
dalam penggunaan bahasa. Bahasa untuk bacaan anak harus sederhana. Hal inilah
letak pentingnya gambar ilustrasi untuk menutupi kekurangan anak dalam hal
bahasa.
3. Isi buku bergambar
Tema dan persoalan yang dikisahkan dalam buku cerita bergambar dapat berupa
persoalan kehidupan manusia. Berbagai persoalan kehidupan yang diangkat
45
menjadi cerita anak harus berangkat dari kacamata anak sehingga isi cerita tersebut
komunikatif bagi pembaca atau pendengar anak-anak.
Ada beberapa karakteristik buku cerita bergambar untuk anak usia dini,
karakteristik tersebut menjadi pembeda antara buku cerita orang dewasa dan buku
cerita anak-anak. Karakteristik seperti posisi dan format gambar, bahasa buku cerita
bergambar dan isi buku cerita bergambar menjadi daya tarik bagi anak untuk mau
melihat dan menjadi titik fokus anak ketika buku cerita tersebut dibacakan.
d. Elemen-elemen Sastra dalam Buku Cerita Bergambar untuk Anak
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bacaan buku cerita
bergambar untuk anak diantaranya (Ambarwati, 2016; Musfiroh, 2008:33-43;
Nurgiyantoro, 2016:68-92) yaitu :
1. Tema, dapat dipahami sebagai sebuah makna yang mengikat keseluruhan unsur
cerita. Tema juga dipahami sebagai gagasan atau ide utama dari sebuah tulisan.
Pengungkapan tema untuk cerita anak usia dini dapat diungkapkan secara langsung
dan cerita yang disuguhkan sebaiknya memiliki tema tunggal.
2. Amanat, ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam
cerita. Amanat untuk cerita anak-anak sebaiknya ditampilkan secara eksplisit baik
dinyatakan melalui para tokoh, maupun oleh penceritanya.
3. Alur, adalah peristiwa naratif yang disusun dalam serangkaian waktu. Alur
merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan menarik
tidaknya cerita dan memiliki kekuatan untuk mengajak anak secara total untuk
mengikuti cerita. Alur berkaitan dengan isi cerita. dan urutan penyajian cerita. Alur
46
untuk anak usia dini lebih baik menggunakan alur maju yang menggambarkan
cerita secara urut dan runtun.
4. Tokoh, adalah pelaku cerita lewat berbagai aksi yang dilakukan. Penokohan dapat
menunjuk pada tokoh dan perwatakan tokoh. Dalam bacaan cerita anak tokoh dapat
berupa manusia, binatang atau makhluk dan objek lain seperti makhluk halus (peri,
hantu) dan tetumbuhan. Tokoh-tokoh selain manusia biasanya dapat bertingkahlaku
dan berpikir sebagaimana halnya manusia. Mereka adalah personifikasi karakter
manusia. Tokoh cerita yang hadir dapat diidentifikasikan tentang aksi, tingkahlaku,
kata-kata, filosofi, bentuk
5. Sudut pandang, merupakan salah satu sarana cerita. Sudut pandang berbicara
tentang siapa yang menceritakan atau dari kaca mata siapa cerita dikisahkan. Secara
garis besar sudut pandang dikategorikan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang
pertama dan sudut pandang orang ketiga. Penggunaan sudut pandang orang ke tiga
memudahkan anak untuk mengidentifikasi, dan memahami cerita, karena mereka
terbantu oleh pencerita yang memberitahu hal-hal yang menyangkut tokoh,
peristiwa dan hal-hal yang melatarbelakanginya.
6. Latar, adalah tempat dimana dan kapan kejadian di dalam cerita berlangsung.
Setting waktu yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan bahasaa anak seperti
besok dan sekarang. Rincian waktu sebaiknya dihindari agar anak tidak terbebani
mengingat detil waktu sehingga melupkan amanat cerita.
7. Sarana Kebahasaan, berisi kata-kata yang sederhana, tepat, mudah diingat anak,
tidak bermakna ganda dan tidak bermakna konotatif. Struktur kalimat terdiri 5-7
47
kata dalam satu kalimat. Kalimat yang panjang biasanya dipecah menjadi beberapa
anak kalimat.
8. Ilustrasi, adalah gambar-gambar yang menyertai cerita dalam buku sastra anak.
Antara tulisan dan ilustrasi gambar saling mengisi dan melengkapi untuk
mendukung makna secara keseluruhan. Ilustrasi buku cerita anak harus menarik
dengan gambar-gambar yang jelas, berwarna-warni, komunikatif, dan ditampilkan
secara variatif pada hampir tiap halaman. Penggunaan warna yang berbeda akan
menciptakan emosional yang baik untuk anak dalam membangkitkan suasana hati
dan membantu penyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam buku cerita
bergambar.
9. Warna, untuk buku cerita bergambar anak-anak lebih menyukai warna-warna cerah
dari pada hitam seperti (kuning, biru, hijau, dan orange) (Treiman & Nicole
Rosales, 2016). Percampuran dari warna-warna yang menarik dan terang membuat
anak menjadi lebih bersemangat dan bisa menjadi titik fokus anak untuk mau
melihat buku cerita bergambar tersebut.
10. Ukuran dan bentuk huruf, dalam studi (Neumann, Summerfield, & David L, 2014)
menunjukkan bahwa pembaca pemula atau anak-anak lebih cendrung dan suka
melihat huruf dan buku yang lebih besar dibanding buku dan ukuran huruf yang
lebih kecil. Penggunaan tulisan untuk disetiap halaman pada buku cerita bergambar
untuk anak, sebaiknya disusun secara horizontal. Hal ini didukung oleh penelitian
(Treiman, Mulqueeny, & Kessler, 2015) menemukan bahwa 92% buku cerita
bergambar untuk anak pra sekolah di Amerika Serikat memiliki tulisan yang
disusun secara horizontal.
48
11. Format bacaan memegang peran penting untuk memotivasi anak membaca sebuah
buku cerita, walau format bukan bagian dari cerita. Bagian format buku adalah
bentuk, ukuran, desain sampul, desain halaman, kualitas kertas, dan model
penjilidan. Ketepatan sebuah format tidak hanya ditentukan oleh salah satu atau
beberapa aspek saja, melainkan perpaduan dari keseluruhan aspek format dan
bahkan juga isi bacaan cerita. Desain sampul yang terdiri dari gambar dan tulisan
harus terlihat menarik, berkaitan dengan adegan tertentu dalam isi cerita. Ukuran
huruf juga penting untuk buku bacaan anak, ditulis dengan huruf-huruf yang relatif
besar. Panjang pendek cerita atau jumlah halaman juga penting untuk
dipertimbangkan dalam pemilihan bacaan anak (Beeck, 2015; Colwell, 2013).
Berdasarkan uraian di atas kaitannya dengan pengembangan produk buku
cerita bergambar yang dikembangkan, yaitu; menggunakan tema surau, dengan
tokoh utama seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun, menggunakan sudut
pandang orang ketiga dengan sebutan untuk tokoh utama Ridwan, menggunakan
alur maju mulai dari si tokoh utama belum mengenal budaya mengaji ke surau
sampai dengan si tokoh utama belajar mengaji di surau, dan menggunakan latar
tempat di Ranah Minang dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia
dan bahasa Minang. Ukuran buku yang dipilih yaitu A3 dengan landasan bahwa
anak-anak menyukai buku yang berukuran besar dan memiliki warna yang menarik.
49
e. Fungsi Buku Cerita Bergambar
Beberapa fungsi dari buku cerita bergambar, Mitchell (Nurgiyantoro, 2016:159)
bagi anak sebagai berikut:
1. Buku cerita bergambar dapat membantu anak terhadap pengembangan dan
perkembangan emosi. Anak akan merasa terfasilitasi dan menerima dirinya sendiri
dan orang lain, serta untuk mengekpresikan berbagai emosinya, seperti rasa takut,
senang, sedih, bahagia. Berbagai sikap dan reaksi emosi anak perlu mendapat
rangsangan untuk penyaluran agar perkembangan emosi berjalan secara wajar dan
terkontrol. Pemahaman dan penerimaan terhadap keadaan diri sendiri dan orang
lain perlu dikembangkan lewat pembelajaran, dan salah satunya adalah lewat buku
cerita bergambar.
2. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia,
meyadarkan anak tentang keberadaan dunia di tengah masyarakat dan alam. Lewat
buku cerita bergambar anak dapat belajar tentang kehidupan masyarakat, baik
dalam perspektif sejarah masa lalu maupun masa kini, belajar tentang keadaan
geografi dan kehidupan alam, flora, dan fauna. Hal ini dapat menyadarkan anak
tentang kehidupan yang lebih luas dan menambah pengalaman hidup yang penting
dalam perkembangan dirinya.
3. Buku cerita bergambar dapat membantu anak belajar tentang oranglain, lewat buku
cerita bergambar yang menampilkan kehidupan keluarga, para tetangga, kawan
sebaya, pergaulan di sekolah, dan lain-lain yang mengisahkan relasi kehidupan
antar manusia dapat membelajarkan anak untuk bersikap dan bertingkahlaku,
verbal dan nonverbal, yang benar sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial-budaya
50
masyarakat. Demikian pula halnya dengan perasaan anak yang juga dapat
terbangun lewat hubungan antar sesama. Jadi pada hakikatnya lewat buku cerita
bergambar anak belajar tentang kehidupan yang disajikan secara lebih konkret
lewat kata-kata dan gambar ilustrasi.
4. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk memperoleh kesenangan. Ini
merupakan salah satu hal terpenting dalam pemberian buku bacaan jenis ini, yaitu
memberikan kesenangan dan kenikmatan batiniah. Kenikmatan batiniah
merupakan salah satu hal yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Tidak
hanya kebutuhan fisik saja, perkembangan kejiwaan dapat berlangsung secara
seimbang dan harmonis. Hal ini dapat diperoleh lewat cerita dan gambar-gambar
yang menarik, bagus dan cendrung realistic, dan hal-hal lucu yang merangsang anak
untuk tertawa senang.
5. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk mengapresiasi keindahan. Baik
cerita secara verbal maupun gambar-gambar ilustrasi. Keindahan cerita verbal
dapat diperoleh antara lain lewat kemenarikan plot dan karakter tokoh, sedangkan
gambar-gambar ilustrasi lewat ketepatan pelukisan objek, komposisi warna, dan
berbagai aksi yang menarik. Objek yang menawarkan keindahan perlu di apresiasi,
gihargai, dinikmati, dan kegiatan tersebut diperoleh lewat pembelajaran. Dalam diri
anak sudah terdapat bakat keindahan, namun ia tidak akan berkembang secara
maksimal jika tidak secara sengaja dirangsang dan dipacu untuk berkembang. Sikap
menghargai keindahan itu sendiri akan dapat menunjang pengembangan sikap dan
perilaku halus pada diri anak.
51
6. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasi. Lewat
cerita verbal imajinasi sudah terkembangkan, tetapi dengan ditambah gambar-
gambar ilustrasi yang mendukung cerita akan semakin dikonkretkan dan diperkuat.
Hal ini tidak saja memperkuat pemahaman terhadap cerita, tetapi juga daya
imajinasi.
f. Kelebihan Buku Cerita Bergambar
Kelebihan cerita bergambar terletak pada adanya gambar yang menyertai cerita,
dimana gambar merupakan sesuatu yang menarik bagi anak-anak dan dapat membantu
anak-anak yang belum lancar membaca tulisan untuk memahami isi cerita. Gambar
dapat memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan
kata-kata yang sifatnya abstrak seperti suasana atau konsep. Tulisan tanpa gambar
dapat mengahasilkan imajinasi dengan interpretasi-interpretasi visual yang berbeda
tergantung dari intelegensi dan latar belakang yang berbeda, namun dengan adanya
gambar yang melengkapi tulisan, perbedaan interpretasi tersebut dapat dibatasi
sehingga informasi mengenai suatu objek dapat tersampaikan jauh lebih jelas (Istanto,
2000).
Pada penelitian ini kelebihan buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan
yaitu dengan ukuran yang besar (A3) dan alur cerita yang dekat dengan anak, dengan
memasukkan unsur budaya Minangkabau yang memberikan kesan tersendiri, berbeda
dengan buku cerita bergambar yang lainnya. Desain gambar da nisi cerita yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan indikator-indikator
pembelajaran yang akan dicapai.
52
5. Budaya Minangkabau
a. Sejarah Perkembangan Surau di Minangkabau
Istilah Melayu-Indonesia “surau” adalah kata yang luas penggunaannya di
Asia Tenggara. Istilah ini sudah lama digunakan di Minangkabau, Sumatera Selatan,
Semenanjung Malaysia, Sumatera Tengan dan Patani (Thailand Selatan). Secara
bahasa “surau” berarti tempat atau ”tempat penyembahan”. Menurut pengertian
asalnya surau adalah bangunan kecil yang dibangun untuk penyembahan arwah nenek
moyang. Karena alasan inilah surau paling awal biasanya dibangun di puncak bukit
atau tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya (Zein, 2011).
Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau, bahkan sebelum
Islam masuk ke Minang surau sudah ada. Datangnya Islam, surau juga mengalami
proses Islamisasi, tanpa harus mengalami perubahan nama. Selanjutnya surau makin
berkembang di Minangkabau. Disamping fungsinya sebagai tempat beribadah
(sholat), tempat mengajarkan Al-Quran dan Hadits serta ilmu lainnya, juga sebagai
tempat musyawarah, mengajarkan adat, sopan santun, ilmu bela diri (silat Minang) dan
juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki-laki tua yang
sudah bercerai (Zein, 2011).
Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan islam, hanya saja fungsi
keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh
Burhanuddin Ulakan Pariaman. Surau ada yang berbentuk masjid, tetapi tidak sama
dengan masjid. Surau di Minangkabau tidak dilakukan sholat jumat, sementara masjid
tempat dilaksanakannya sholat jumat (Zein, 2011).
53
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan
surau di mulai dari sebelum Islam masuk. Surau yang memilki arti “tempat
penyembahan” arwah nenek moyang. Setelah islam masuk di Minangkabau istilah
surau mengalami proses islamisasi, dan tetap menggunakan surau yang berarti tempat
melakukan ibadah (sholat), belajar Al-quran dan hadits, belajar adat, ilmu bela diri
(silek Minang) dan belajar agama islam.
b. Peranan Surau di Minangkabau
Struktur surau di Minangkabau setelah kedatangan islam secara umum dibagi
ke dalam dua kategori, yaitu surau gadang (besar) dan surau ketek (kecil). Surau
gadang adalah surau yang dapat menampung 80 sampai 100 murid atau lebih. Surau
gadang tidak hanya berfungsi sebagai rumah ibadah dan mengaji seperi yang berlaku
pada surau ketek, tetapi yang lebih penting adalah surau ini dijadikan sebagai pusat
aktivitas pendidikan agama. Sedangkan surau ketek (kecil) adalah surau yang hanya
menampung 20 orang murid. Surau ketek ini dapat disamakan dengan langgar atau
musholla (Natsir, 2012).
Peranan surau di Minangkabau diantaranya sebagai lembaga pendidikan
agama, adat dan budaya, serta sebagai sentral aktivitas masyarakat. Surau merupakan
aset lokal yang menjadi milik bersama bagi masyarakat. Surau difungsikan dalam
segala aktivitas kemasyarakatan yang tidak hanya menyangkut persoalan agama,
namun juga penyelenggaraan aktivitas adat dan budaya. Namun seiring dengan
perkembangan masyarakat, fungsi surau sebagai sentral aktivitas menjadi berkurang.
Masyarakat lebih memandang surau hanya sebagai lembaga pendidikan agama dari
54
pada lembaga pendidikan adat, budaya dan sentral lembaga aktivitas masyarakat
(Natsir, 2012).
c. Karakterisik Sistem Pendidikan Surau
Karakteristik sistem pendidikan surau dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu
(Zein, 2011):
1. Klasifikasi surau berdasarkan jumlah murid
Berdasarkan jumlah murid surau terbagi ke dalam tiga kategori yaitu, surau
kecil, surau sedang dan surau besar. Surau kecil dapat menampung 20 murid,
dikenal dengan istilah surau mengaji (surau tempat belajar membaca Al-Quran dan
melakukan sholat). Surau kategori ini lebih kurang sama dengan “langgar” atau
mushalla. Surau sedang sengaja didirikan untuk tempat pendidikan agama dalam
pengertian yang lebih luas. Dengan kata lain surau sedang bukan hanya sekedar
tempat ibadah yang dilakukan sebagai surau mengaji, namun sebagai pusat
pendidikan agama yang lebih luas dalam berbagai aspek yang diajarkan ke murid-
muridnya. Surau besar yang dapat menampung antara 100 sampai 1000 murid, yang
sebagai lembaga pendidikan lengkap yang merupakan komplek bangunan yang
terdiri dari Mesjid, bangunan untuk tempat belajar dan surau-surau kecil yang
sekaligus menjadi pemondokan murid-murdi yang belajar di surau. Contohnya
seperti Surau Ulakan yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin.
2. Klasifikasi surau dari segi fungsinya
Surau dapat dibedakan menjadi surau nagari, surau suku, dan surau paham
keagamaan. Surau nagari merupakan institusi agama di samping masjid yang
menjadi persyaratan sebuah nagari. Surau suku adalah tempat penghulu/ ninik
55
mamak suku dalam pembinaan sopan santun anak kemenakan, maka surau suku
merupakan simbol budi. Suaru paham keagamaan, berbentuk pusat pengajaran dan
ibadat suatu paham tarekat, misal Surau Pasia Lubuk Nyiur, Surau Tanjung Limau
Sundai, dengan ulamanya adalah surau tarekat yang amat berpengaruh.
3. Kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau
Tuanku Syekh adalah personifikasi yang digunakan dari suatu surau itu
sendiri. Karena itu, prestise surau banyak bergantung pada pengetahuan, kesalehan,
dan karisma Tuanku Syekh. Tuanku Syekh tidak hanya berperan sebagai guru,
tetapi juga sekaligus pemimpin spiritual mereka yang ingin belajar memperdalam
ibadahnya.
4. Murid dalam sistem pendidikan surau
Orang yang belajar di surau disebut murid. Ini mencerminkan sifat alamiah
surau awal, karena istilah murid adalah terminologi sufi yang merujuk pada
pengikut baru yang bermaksud mengamalkan tarekat. Murid menerima pengajaran
dari Syekh, dan Syekh memahami murid-muridnya dalam mengajari mereka sesuai
dengan tingkat kemampuan intelektual masing-masing.
5. Isi/materi. metode dan literatur keagamaan sistem pendidikan surau
Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem
pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar
belajar huruf hijayyah, dan membaca Al-Quran, disamping ilmu-ilmu keislaman
lainnya, seperti keimanan, akhlak dan ibadah. Keterkaitan antara isi ecrita dengan
budaya Minangkabau terletak pada tema cerita tentang surau. Surau merupakan
56
lembaga pendidikan Islam Minangkabau yang telah menjadi simbol masyarakat
Minangkabau yang religius.
6. Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Budaya Minangkabau
untuk Meningkatkan Pengetahuan Agama dan Moral Anak Usia 5-6 Tahun
Buku cerita bergambar yang dikembangkan menjadi dua seri ini (Seri 1
“Ayo ke Surau, dan Seri 2 “Ini Surauku”) disesuaikan dengan kebutuhan di
lapangan. Di desain dengan jalan cerita dengan mempertimbangkan indikator-
indikator yang akan dicapai. Pembuatan buku cerita bergambar ini didasari oleh
Teori Behaviorime, yang berpandangan bahwa stimulasi dari lingkungan sangat
berperan penting dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak.
Perkembangan nilai agama dan moral anak melalui tiga tahapan yaitu: kognitif
(knowing), afektif (sikap moral), dan tindakan moral (action), (Akbar, 2019:133;
Wiyani, 2013:87). Tahapan pertama adalah kognitif (knowing), berhubungan
dengan pengetahuan anak dalam perilaku baik dan buruk berdasarkan ajaran agama
Islam.
Pentingnya komponen kognitif (knowing) didasari bahwa yang perlu anak
ketahui sebelum anak memiliki sikap afektif dan tindakan moral adalah anak harus
memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang pengetahun agama dan moral. Anak
akan bisa mengkonfirmasi pada pengalaman-pengalamannya untuk dapat
membedakan perbuatan baik dan buruk berdasarkan pengetahuan yang didapat
sebelumnya (Santrock, 2007:277). Peran dari faktor kognitif menggambarkan
bagaimana kognisi menjembatani pengetahuan, pengalaman dan lingkungan dalam
57
memunculkan perilaku moral. Berdasarkan hal ini maka buku cerita bergambar
tepat diberikan untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan anak tentang
agama dan moral. Buku cerita bergambar yang memiliki tulisan dan ilustrasi
gambar yang menarik akan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan
dan membantu anak dalam proses memahami dan memperkaya pengalaman dari
rangkaian cerita (Nihwan, 2018).
Buku cerita bergambar yang didesain dengan memasukkan unsur budaya
Minangkabau memilki beberapa tujuan diantaranya, yaitu: 1) untuk mengenalkan
budaya Minangkabau (budaya mengaji di surau) kepada anak-anak, 2) untuk
memberikan pengetahuan tentang sholat wajib melalui cerita mengaji di surau, 3)
memasukkan bahasa Minang dan bahasa Indonesia dalam cerita buku bergambar,
4) belum adanya buku cerita bergambar yang memasukkan bahasa Minang ke
dalam cerita anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan agama dan moral anak.
Pemilihan buku cerita bergambar yang berukuran besar (A3) didukung oleh
(Neumann et al., 2014) yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih cendrung dan
lebih suka melihat buku yang lebih besar dibanding buku yang kecil.
B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN
1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusnilawati; Fauziddin, 2018) yang berjudul
“Meningkatkan Aspek Perkembangan Nilai Agama dan Moral Ank Usia Dini
dengan Penerapan Metode Bercerita Islami”. Penelitian ini menunjukkan bahwa
melalui metode bercerita tema islami dapat meningkatkan perkembangan agama
dan moral anak usia 5-6 tahun. Metode bercerita adalah suatu cara penanaman nilai-
58
nilai kepada anak dengan menggunakan kepribadian tokoh-tokoh melalui
penuturan hikayat, legenda, dongeng dan sejarah lokal. Sejalan dengan penelitian
ini memilki persamaan dalam mengembangkan perkembangan agama dan moral
anak melalui bercerita, namun perbedaannya yaitu menggunakan buku cerita
bergambar berbasis budaya Minangkabau.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahimah & Izzaty, 2018) yang berjudul
“Developing Picture Story Book Media for Building the Self-Awareness of Early
Childhood Children”. Penelitian ini menunjukkan bahwa media buku cerita
bergambar yang dikembangkan layak digunakan dalam pembentukan kesadaran
diri anak usia dini. Pada hasil temuan catatan lapangan terdapat dinamika
pembelajaran yang kompleks dengan menggunakan buku cerita bergambar. Hasil
perhitungan posttest menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Persamaan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan media buku cerita bergambar, namun perbedaannya terdapat pada
aspek perkembangan, dalam penelitian relevan ini meningkatkan kesadaran diri
anak, sedangkan dalam penelitian ini mengembangkan pengetahuan agama dan
moral anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Eliza, 2017) yang berjudul “Pengembangan Model
Pembelajaran Karakter Berbasis Cerita Tradisional Minagkabau untuk Anak Usia
Dini”. Penelitian ini membahas pengembangan model pembelajaran karakter
berbasis nilai-nilai kearifan lokal budaya Minangkabau. Berdasarkan data yang
telah terkumpul banyak cerita, legenda, dongeng yang dikumpulkan yang
mengandung nilai-nilai kearifan Minangkabau yang dapat membentuk karakter
59
anak. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama
mengangkat cerita yang terintegrasi dengan kearifan lokal yaitu budaya
Minangkabau. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan menggunakan model
pembelajaran karakter, sedangkan pada penelitian ini menggunakan media buku
cerita bergambar.
C. KERANGKA PIKIR
Budaya tidak terlepas dari ajaran nilai agama dan moral, yang memiliki banyak
nilai-nilai keteladanan dan mengatur nilai-nilai kehidupan. Sesuai dengan falsafah adat
Minangkabau “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah”. Makna dari
ungkapan tersebut adalah bahwa budaya Minangkabau menjadikan ajaran Islam
sebagai sendi utama dalam mengamalkan adat, dan kebiasaan masyarakat Minang.
Salah satunya yaitu budaya mengaji di surau, yang merupakan lembaga pendidikan
Islam tradisional Minangkabau yang memiliki peran sebagai lembaga pendidikan
agama, pendidikan adat dan sebagai pusat aktivitas masyarakat (Zein, 2011). Nilai-
nilai budaya yang sudah dianggap baik dapat dijadikan materi atau sumber pendidikan
(Rukiyati & Purwastuti, 2016). Pentingnya mengenalkan kesadaran budaya bagi anak-
anak adalah untuk mereka mempelajari nilai-nilai kehidupan, dan nilai moral yang
dapat dijadikan sebagai basis pendidikan di sekolah (Morrisson, 2015:800).
Tahapan perkembangan agama dan moral memiliki tiga komponen, yaitu:
komponen kognitif (knowing), afektif (sikap moral), dan tindakan moral (action)
(Akbar, 2019:133; Wiyani, 2013:87). Komponen kognitif berhubungan dengan
kemampuan dalam mengetahui perilaku baik dan buruk yang sesuai dengan ajaran
60
agama yang diterima oleh anak. Aspek afektif berhubungan dengan kemampuan anak
dalam merasakan dan mencintai berbagai perilaku yang baik berdasarkan ajaran agama
yang diterima oleh anak. Aspek tindakan moral berhubungan dengan kemampuan anak
dalam memilih melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk
berdasarkan aturan yang didasari oleh ajaran agama (Nurjanah, 2018).
Pentingnya komponen kognitif (knowing) didasari bahwa yang perlu anak
ketahui sebelum anak memiliki sikap afektif dan tindakan moral adalah anak harus
memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang pengetahun agama dan moral. Anak
akan bisa mengkonfirmasi pada pengalaman-pengalamannya untuk dapat
membedakan perbuatan baik dan buruk berdasarkan pengetahuan yang didapat
sebelumnya (Santrock, 2007:277). Peran dari faktor kognitif menggambarkan
bagaimana kognisi menjembatani pengetahuan, pengalaman dan lingkungan dalam
memunculkan perilaku moral. Sejalan dengan (Heiphetz, Strohminger, Gelman, &
Young, 2018) bahwa untuk mencapai karakteristik moral yang menjadi identitas
seseorang, akan berubah seiring waktu secara substansial yang dimainkan oleh kognisi
moral.
Permasalahan mengenai pengetahuan agama dan moral anak yang dipengaruhi
oleh lingkungan tempat tinggal, seperti: anak berbicara dengan suara keras, berdoa
dengan berteriak, dan tidak mau melakukan aktivitas keagamaan (sholat dan mengaji).
Anak akan mencontoh dan meniru apa yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya.
Peran orangtua dan orang dewasa lainnya diperlukan untuk bisa memberikan contoh
dan perilaku yang baik, serta memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama
dan moral yang baik bagi anak.
61
Melihat hal tersebut bahwa pengetahuan anak-anak mengenai agama dan moral
sangat penting, berawal dari pengetahuan lah yang akan membuat anak mampu untuk
memilih perbuatan yang benar dan salah. Salah satu cara yang dapat meningkatkan
pengetahuan anak tentang agama dan moral adalah lewat bercerita. Sesuai dengan
tahapan perkembangan agama dan moral anak menurut Harms (Akbar, 2019:55) pada
usia 3-6 tahun anak mengalami tahap fairytale (dongeng), dimana pada tahap ini anak
akan senang jika mereka dibacakan cerita. Rothlein (Santoso, 2008) bercerita
menggunakan media buku cerita bergambar akan membantu anak-anak dalam proses
memahami dan memperkaya pengalaman dari cerita yang diberikan. Penyajian
ilustrasi gambar yang besar dan sesuai dengan karakteristik anak akan menambah
antusias dan semangat anak-anak untuk mendengarkan cerita. Gambar sebagai visual
dengan desain dan warna yang menarik akan mendukung proses pembelajaran yang
menyenangkan (Nihwan, 2008). Buku cerita bergambar untuk anak harus
menggunakan kalimat yang sederhana, memiliki teks, dan menggunakan kalimat aktif
(Nurgiyantoro; 2016-156).
Pengembangan buku cerita bergambar berbasis budaya Minangkabau
merupakan salah satu solusi bagi pendidik dalam meningkatkan pengetahuan agama
dan moral anak lewat budaya lokal (budaya mengaji di surau). Buku cerita yang
didesain sesuai kebutuhan anak dengan ukuran besar (A3), dan isi cerita yang
disesuaikan dengan kurikulum 2013, indikator 3.1 (mengenal kegiatan beribadah
sehari-hari) dan indikator 3.2 (mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia).
Buku cerita yang akan dikembangkan memiliki dua seri cerita dengan tema yang sama
yaitu budaya mengaji di surau, yang saling berkaitan antara seri 1 dan seri 2.
62
D. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan kerangka pikir yang didukung dengan kajian teori maka dapat
dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:
1. Apa saja materi yang terdapat pada buku cerita bergambar berbasis budaya
Minangkabau?
a. Apa nilai budaya yang terdapat dalam buku cerita bergambar?
b. Apa indikator yang terdapat dalam buku cerita bergambar?
c. Menggunakan bahasa yang seperti apa untuk anak usia 5-6 tahun?
d. Ilutrasi gambar yang seperti apa membuat anak dapat tertarik?
e. Apakah cerita antara seri 1 dan 2 saling terkait?
2. Bagaimana kelayakan pengembangan media buku cerita bergambar berbasis
budaya Minangkabau?
a. Bagaimana kelayakan media buku cerita bergambar berbasis budaya
Minangkabau ditinjau dari aspek materi?
b. Bagaimana kelayakan media buku cerita bergambar berbasis budaya
Minangkabau ditinjau dari aspek media?
3. Bagaimana keefektivan media buku cerita bergambar berbasis budaya
Minangkabau untuk meningkatkan pengetahuan agama dan moral anak usia 5-6
tahun?
a. Bagaimana hasil pre-test pengetahuan agama dan moral anak sebelum
menggunakan buku cerita bergambar berbasis budaya Minangkabau?
b. Bagaimana hasil post-test pengetahuan agama dan moral anak sesudah
menggunakan buku cerita bergambar berbasis budaya Minangkabau?