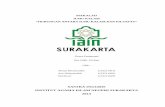Review: Studi Ilmu Al-Qur'an
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Review: Studi Ilmu Al-Qur'an
BAB I
Al-Qur’an dan Wahyu
Al-Qur’an dalam pengertian secara bahasa dapat
diartikan sebagai masdar (infinitif) dari kata qara’a,
qira’atan, qura’anan. Sedangkan dalam pengertian secara
istilah yaitu kalam atau firman Allah Ta’ala yang
diturunkan kepada hati nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam yang tidak lain beliau adalah nabi terakhir di
dunia dan dinilai sebagai ibadah bagi siapa pun yang
membacanya. Dinamakan al-Qur’an pula secara cermat karena
apa yang diturunkan Allah ke dalam hati Nabi Muhammad
sebagai “wahyu” yaitu, suatu lafaz yang mengandung
keseragaman makna wahyu yang diturunkan kepada semua nabi
dan rasul, serta untuk memberikan pengertian dasar
menurut bahasa sehubungan dengan maknanya sebagai
pemberitahu yang bersifat rahasia dan sangat cepat. Lafaz
wahyu pula digunakan untuk menyebut firman Allah yang
berupa perintah kepada para malaikat supaya mereka
melaksanakan perintah tersebut dengan segera. Adapula
sebagian ulama yang menyatakan bahwa dinamakan al-Qur’an
karena dalam kitab ini telah mencakup pokok pembahasan
dari kitab-kitab-Nya yang sebelumnya dan juga mencakup
pokok pembahasan dari semua ilmu yang terlahir di dunia
ini.
Al-Qur’an dapat pula diartikan sebagai mukjizat dengan
lafaz dan maknanya, serta sebagai mukjizat karena di
1
dalamnnya mengandung tantangan kepada kaum kafir untuk
mendatangkan yang semisal dengannya. Dan dinilai ibadah
dengan membaca lafaz yang terkandung di dalam al-Qur’an,
sebab lafaz tersebut menukilkan kepada kita dengan cara
mutawatir. Maka hal tersebut merupakan keutamaan al-
Qur’an yang jika dipelajari oleh kaum muslim akan
mendapat pahala dari sisi Allah Ta’ala. Begitu pula
dengan orang-orang yang mengajarkannya, maka akan
mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta’ala.
A. Nama-nama Al-Qur’an
a. Al-Kitab ( اب� bahasa ال�كت����������� Aramia) dari kata kitabah
yaitu kitab bermakna gambaran huruf [al-Baqarah:
2]
b. Al-Qur’an ( ن� را� bahasaال�ق�������� Aramia) dari kata qira’ah
yaitu tilawah, bacaan.
c. Al-Furqan ( ان� bahasaال�ق�رق�������������� Armaia) yang berarti
memisahkan atau membedakan antara kebenaran dan
kebatilan [al-Furqan: 1]
d. Dzikrun ( ك�ر murniذ� bahasa Arab) yang berarti
kemuliaan [al-Anbiya: 10 dan 50]
e. Tanzil ( ل ي�� ن�ز� �murni bahasa Arab) yang berarti sesuatuت�yang diturunkan atau pun wahyu yang diturunkan
Allah ke dalam hati Rasul-Nya, Muhammad [asy-
Syu’ara: 129]
2
B. Sifat-sifat Al-Qur’an
1. Nur (ور yang berarti cahaya. [An-Nisa: 174] , (ن��2. Huda (ه�دى) , yang berarti petunjuk. [Yunus: 57]3. Syifa’ (اء ف� yang berarti obat. [Yunus: 57] , (ش�'4. Rahmah ( yang berarti rahmat. [Yunus: 57] , (رح�مة�5. Mau’idzah ( ة� yang berarti nasihat. [Yunus: 57] , (م�وع�ظ-6. Al-Majid (د ي2 yang berarti hormat. [al-Buruj: 21](ال�مج�7. Al-Aziz ( ي�8ز� yang berarti mulia. [Fushshilat: 41](ال�عر�8. Mubin ( ي2ن� ت� -yang berarti yang menerangkan. [Al(م������
Ma’idah: 15]
9. Busyra (ز yang (ب��ش' berarti kabar gembira. [Al-
Baqarah: 97]
10. Basyir ن�ز) .yang berarti pembawa kabar gembira(ب��ش����'[Fussilat: 3-4]
11. Naziir (ي�8ز Aد yang (ن������������ berarti pembawa peringatan.
[Fussilat: 3-4]
12. Mubarak(Cارك� (م�ت��������� yang berarti yang diberkati.
[Al-An’am: 92]
3
C. Perbedaan al-Qur’an dengan Hadits Qudsi dan Hadits
Nabawi
Perlu diketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud
dengan hadits qudsi yaitu hadits atau berita atau
kabar yang diriwayatkan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
atas kalam Allah Ta’ala dengan lafaz dari beliau
sendiri. Makna quds memiliki arti menyucikan Allah.
Jadi apabila seseorang meriwayatkan hadits qudsi,
maka dia meriwayatkan dengan mengatakan: “Rasulullah
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengatakan tentang apa yang
diriwayatkan dari Tuhannya...” atau dengan
mengatakan: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda: Allah Ta’ala telah berfirman...” atau dengan
mengatakan: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
bersabda: Allah Ta’ala berfirman...”
Adapun pengertian hadits nabawi, yaitu hadits
atau berita atau kabar yang disandarkan kepada Nabi
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam baik berupa
perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan,
sifat fisik dan sifat akhlak beliau.1 Hadits nabawi
memiliki dua sifat, yaitu tauqifi dan taufiqi. Yang
dimaksud dengan hadits nabawi bersifat tauqifi yaitu
yang kandungannya diterima oleh Rasulullah dari
wahyu, kemudian beliau menjelaskan dengan kata-kata
beliau sendiri kepada manusia. Sedangkan yang
dimaksud dengan hadits nabawi bersifat taufiqi yaitu
yang disimpulkan oleh Rasulullah dengan pertimbangan
ى 1 ُلق� ى و خ��ُ ْلق� و وص�ف� خ��َ Oي�8ز ا ق�ر و ت�� Oعل ا و ف�� Oول ا ة و س�لم م�ن� ق� ى� ص�لى ال�لة ع�لي� ب� لى ال�ن� cف� ا ي� ض�� Oم�ا ا4
dan ijtihad tentang pemahaman beliau terhadap al-
Qur’an.
Walaupun sama-sama memiliki nilai penting dalam
menentukan hukum syari’at yang datang dari Allah
Ta’ala, tetapi diantara al-Qur’an dengan hadits qudsi
terdapat perbedaan yang memang tidak dapat
dipungkiri lagi yang meliputi:
1. Al-Qur’an mengandung tantangan kepada kaum kafir
untuk mendatangkan yang semisal dengan al-Qur’an
tersebut, sedangkan hadits qudsi tidak mengandung
yang demikian.
2. Al-Qur’an dinisbahkan kepada Allah Ta’ala,
sedangkan hadits qudsi terkadang diriwayatkan
dengan disandarkan kepada Allah Ta’ala dari
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
3. Seluruh isi al-Qur’an dinukil secara mutawatir
dan kepastiannya pun mutlak, sedangkan hadits
qudsi mayoritasnya merupakan hadits ahad dan
kepastiannya pun masih dalam dugaan.
4. Al-Qur’an merupakan wahyu dari Allah dalam segi
lafaz dan maknanya, sedangkan hadits qudsi
merupakan wahyu dari Allah dalam segi makna dan
lafaznya dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
5. Membaca al-Qur’an dinilai sebagai ibadah dan
dibaca di dalam shalat. Disebutkan pula dalam
sebuah hadits jika membaca setiap huruf ayat al-
Qur’an mendapatkan pahala sebanyak sepuluh kali
5
BAB II
Sejarah Pemeliharaan Al-Qur’an
Al-Qur’an diturunkan dari sisi Allah Ta’ala yaitu Lauh
Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus,
kemudian diturunkan dari langit dunia ke bumi secara
berangsur-angsur merupakan salah satu kemukjizatan yang ada
padanya (al-Qur’an). Hal ini merupakan proses turunnya al-
Qur’an sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam sebagai utusan yang mulia.
Adapun hikmah dibalik rahasia diturunkannya al-Qur’an
secara sekaligus ke langit dunia ialah untuk memuliakan al-
Qur’an dan memuliakan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai
utusan yang menerima wahyu tersebut, yaitu dengan
memberitahukan kepada penghuni tujuh langit bahwa al-Qur’an
merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir
dan umat yang paling mulia.
Selain itu pula, al-Qur’an diturunkan secara berangsur-
angsur dari langit dunia ke bumi selama dua puluh tiga tahun
memiliki hikmah tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam yaitu untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau
karena setiap peristiwa yang terjadi selalu disusul dengan
turunnya ayat-ayat baru yang dirasa oleh beliau sebagai hal
yang dapat meringankan penderitaan yang beliau hadapi dan
sebagai hiburan serta motivasi beliau untuk terus mendakwahkan
Islam serta agar al-Qur’an mudah dihafal.
Adakalanya ayat al-Qur’an turun lima ayat sekaligus dan
ada pula yang sepuluh ayat sekali turun. Atau adapula kurang
7
atau lebih dari itu. Begitulah al-Qur’an turun berangsur-
angsur. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam membacanya perlahan-
lahan, sedang para sahabat membacanya sedikit demi sedikit.
Ayat-ayat al-Qur’an diturunkan sehubungan dengan peristiwa,
baik yang bersifat individu atau sosial yang terjadi selama
kurun waktu 23 tahun sampai akhir hidup Rasulullah. Kadangpula
wahyu turun untuk mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi
wa Sallam tentang orang kafir yang sesungguhnya hanya menolak
dan membangkang kebenaran.
Namun adapun Subhi as-Shalih dalam bukunya menyatakan
bahwa ia tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan
bahwa al-Qur’an diturunkan tiga kali. Mula-mula di Lauh
Mahfudz, selanjutnya ke Baitul ‘Izzah (Rumah Kemuliaan) di
langit dunia (langit lapisan pertama), dan terakhir diturunkan
secara terpisah dan berangsur-angsur sejalan dengan peristiwa
tertentu. Sebab, turunnya al-Qur’an secara demikian itu
termasuk sesuatu yang ghaib, yang hanya dapat diterima
berdasarkan keyakinan akan kebenaran Kitabullah dan Sunnah
Rasul-Nya (bukan lagi kenyataan turunnya wahyu itu sendiri).2
Bahkan ada yang mendengar dari kaum Yahudi bahwa kitab Taurat
diturunkan kepada Nabi Musa ‘Alaihissalaam secara sekaligus.
Karena itu tidak mengherankan jika mereka menanyakan tentang
alasan al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur. Dan
mereka pun ingin agar al-Qur’an diturunkan sekaligus. Hal ini
pula disebutkan di dalam al-Qur’an:
“Orang-orang kafir mempertanyakan, ‘mengapa al-Qur’an tidak diturunkan
kepadanya (Muhammad) sekaligus?’ Demikianlah, (al-Qur’an Kami turunkan secara2 Dr. Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an (Jakarta: PustakaFirdaus) hal 60
8
berangsur-angsur) untuk memperteguh hatimu (wahai Muhammad) dan Kami
membacakannya secara tartil (perlahan-lahan, jelas dan sebagian demi sebagian).
Tiap mereka datang kepadamu membawa suatu permasalahan, Kami selalu
datangkan kepadamu kebenaran dan penafsiran yang sebaik-baiknya.” [QS Al-
Furqan: 32-33]
A. Pemeliharaan al-Qur’an pada masa Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam
Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
pemeliharaan al-Qur’an dilakukan dengan cara dihafalkan
dan dipahami. Hal inilah yang dimaksud dalam firman Allah
Ta’ala kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam surat Al-
Qiyamah ayat 16-19.
“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca al-Qur’an karena
hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah
mengumpulkannya di dadamu dan (membuatmu pandai) membacanya.
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu.
Kemudian atas tanggungan Kamilah penjelasannya.”
Dengan cara dihafalkan yaitu dengan sebab pada masa
itu bangsa Arab memang memiliki daya hafal yang kuat. Hal
tersebut karena mayoritas diantara mereka adalah buta
huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syiair-
syair dan silsilah mereka lakukan dengan catatan di hati
mereka.
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
mendapatkan wahyu maka beliau mendengarkannya, kemudian
menghafalkannya di dalam hati dan dipahami dengan benar.
Setelah itu beliau melafazkan wahyu tersebut kepada para
9
sahabat, sehingga mereka pun menghafalkan ayat al-Qur’an
dari beliau.
Adapun dengan cara penyusunan secara tertulis,
beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengangkat para sahabat yang
terkemuka, seperti Ali, Mu’awiyah, ‘Ubay bin Ka’abdan
Zaid bin Tsabit untuk menuliskannya dalam sebuah riqa’,
yaitu jamak dari kata rug’ah yang berarti lembaran kulit,
lembaran daun atau lembaran kain. Beliau Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam tidak memandang perlu untuk menghimpun ayat-ayat
yang ada pada setiap surat dalam berbagai shahifah yang
jumlahnya tidak terhitung. Juga tidak perlu menghimpun
semua cara pencatatan al-Qur’an di dalam satu mushaf.
Sebab, para penghafal dan pembaca al-Qur’an banyak sekali
jumlahnya. Dan karena para sahabat menghafal al-Qur’an di
dalam dada sesuai petunjuk beliau. Beliau pun juga
mengatakan bahwa urutan ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan
kehendak serta petunjuk Allah Ta’ala.
B. Pemeliharaan al-Qur’an pada masa Abu Bakr as-Shiddiq
Radhiyallahu ‘anhu
Ketika banyak para penghafal al-Qur’an yang terbunuh
pada peperangan melawan kaum murtad pada tahun ke-12 H,
Umar bin Khattab mengusulkan agar mengumpulkan dan
membukukan al-Qur’an. Hal tersebut karena dikhawatirkan
al-Qur’an akan musnah seiring dengan banyaknya para
penghafal Qur’an yang mati syahid. Awalnya Abu Bakr
menolak usulan tersebut dengan alasan bahwa hal
tersebut tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu
10
‘Alaihi wa Sallam dan tidak pula dianjurkan oleh beliau.
Namun akhirnya Allah Ta’ala membukakan pintu hati Abu
Bakr untuk menerima usulan tersebut.
Kemudian Abu Bakr mengingat kedudukan Zaid bin
Tsabit dalam qira’at, penulisan, pemahaman dan
kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan yang
terakhir kali. Dan Abu Bakr pun mengutusnya untuk mulai
mencari ayat al-Qur’an yang terdapat di pelepah kurma,
keping-kepingan batu dan dari para penghafal al-Qur’an
yang jumlahnya tidak banyak. Hingga lembaran-lembaran
yang sudah terkumpul tersebut diserahkan kepada Abu
Bakr, kemudian dia simpan hingga wafatnya. Sesudah itu
berpindah ke tangan Umar bin Khattab, selaku khalifah
sesudah Abu Bakr. Namun setelah wafatnya Umar,
lembaran-lembaran tersebut berada di tangan Hafshah
binti Umar.
C. Pemeliharaan al-Qur’an pada masa Utsman bin ‘Affan
Radhiyallahu ‘anhu
Ketika terjadi perang Armenia dan Azarbaijan dengan
penduduk Irak, diantara orang ikut perang yaitu
Huzaifah bin al-Yaman. Ia melihat banyak perbedaan
dalam cara-cara membaca al-Qur’an. Ada sebagian dari
bacaan tersebut yang bercampur dengan kesalahan, tetapi
masing-masing mempertahankan pendapatnya dalam bacaan
tersebut. Bahkan sampai saling mengkafirkan satu sama
lain diantara mereka. Melihat kenyataan tersebut,
Huzaifah melaporkannya kepada Utsman bin ‘Affan.
11
Hingga Utsman pun mengambil keputusan untuk menyalin
lembaran-lembaran pertama yang dikumpulkan pada masa
Abu Bakr dan menyatukan umat Islam pada lembaran-
lembaran tersebut dengan bacaan yang tepat. Kemudian
Utsman mengirimkan seorang utusan untuk meminjamkan
lembaran-lembaran Qur’an yang berada di tangan Hafshah
binti Umar. Dan Hafshah pun menyerahkannya.
Selanjutnya Utsman memanggil Zaid bin Tsabit al-
Anshari, dan tiga orang dari suku Quraisy, yaitu
Abdullah bin Zubair, Sa’id bin ‘As, dan Abdullah bin
Haris bin Hisyam agar menyalin dan memperbanyak mushaf.
Jika ada perselisihan diantara mereka, maka hendaklah
Zaid bin Tsabit menulis dalam bahasa Quraisy. Karena
al-Qur’an diturunkan dalam logat mereka. Mushaf yang
disusun itulah yang menyatukan pula kaum muslimin, yang
kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani atau
Mushaf Imam.
Setelah penyalinan selesai, Utsman mengembalikan
lembaran-lembaran asli kepada Hafshah binti Umar.
Kemudian Utsman mengirimkan mushaf tersebut ke berbagai
wilayah dan memerintahkan agar mushaf lainnya dibakar.
Tak hanya sampai disini perkembangan al-Qur’an, tata cara
pengucapan yang tepat dan baku pun dilakukan dengan cara
memberikan ketentuan harakat pada al-Qur’an, seperti
menciptakan tanda-tanda tertentu seperti syakl (harakat) dan
nuqtoh (titik). Adapula beberapa tokoh yang berpartisipasi
dalam penyempurnaan mushaf ini yaitu, Abul Aswad ad-Duali,
12
‘Ubaidillah bin Ziyad, dan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
Hal ini pula yang dianggap sebagai permulaan ilmu I’rabil
Qur’an.
Namun setelah banyak orang yang menandai mushafnya dengan
berbagai tanda untuk memisahkan ayat yang satu dengan yang
lain, mereka berani untuk menamai tiap awal surat al-Qur’an,
sehingga sulit dicegah upaya orang untuk memperindah dan
memperelok bentuk susunan mushaf. Kemudian muncul khothat
(penulisan). Seluruh dunia Islam pun menyambut dan menerima
baik mushaf tersebut, hingga banyak dicetak setiap tahunnya
berjuta-juta eksemplar, dan merupakan satu-satunya mushaf yang
bereda di kalangan umat muslim, karena para ulama di berbagai
daerah sudah menyetujui dan mengakui kecermatan yang sempurna.
Sampai pada akhir abad ke-3 H para ulama masih berbeda
pendapat mengenai penggunaan tanda-tanda titik. Kemudian pada
zaman selanjutnya, banyak muslim yang menggunakan tanda baca
titik dan syakl pada penulisan mushaf. Mereka yang dahulu
mengkhawatirkan terjadinya perubahan nash al-Quran karena
ditulis dengan tanda-tanda syakl dan titik, sekarang malah
mengkhawatirkan terjadinya salah baca pada orang-orang awan
yang tidak mengerti, jika penulisan mushaf tanpa dibubuhi
tanda-tanda baca.
Para sahabat yang lain pun setelah itu terus melanjutkan
usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna al-Qur’an dan
penafsiran ayat-ayat yang berbeda-beda diantara mereka, sesuai
dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahaminya.
Hal ini disebabkan karena perbedaan waktu yang panjang dan
13
tidak bertemunya mereka bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam.
Diantara para ahli tafsir yang terkenal dari para sahabat
yaitu Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibn Abbas, Ubay bin
Ka’ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy’ari, dan Abdullah bin
Zubair.
Banyak riwayat mengenai tafsir yang diambil dari Abdullah
bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab. Tetapi hal
tersebut tidak berarti penafsiran yang mutlak tentang Al-
Qur’an yang sempurna, karena hal tersebut masih terbatas pada
makna beberapa ayat dengan penafsiran tentang apa yang masih
samar dan penjelasan yang masih global. Kemudian di kalangan
para tabi’in terdapat suatu kelompok yang terkenal karena
mengambil ilmu ini dari para sahabat. Di samping itu pula,
mereka pun bersungguh-sungguh dalam melakukan ijtihad dalam
menafsirkan ayat.
Diantara murid-murid Ibn Abbas di Mekkah yang terkenal
yaitu Sa’id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah (mantan budak Ibn
Abbas), Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atha’ bin Rabah.
Kemudian diantara murid-murid Ubay bin Ka’ab yang terkenal di
Madinah yaitu Zaid bin Aslam, Abul ‘Aliyah dan Muhammad bin
Ka’ab al-Qurazi. Selanjutnya, diantara murid-murid Abdullah
bin Mas’ud di Irak yang terkenal yaitu ‘Alqamah bin Qais,
Masruq, al-Aswad bin Yazid, ‘Amir asy-Sya’bi, Hasan al-Basri
dan Qatadah bin Di’amah as-Sadusi.
Dan yang diriwayatkan dari mereka meliputi ilmu tafsir,
ilmu Garibil Qur’an, ilmu Asbabun Nuzul, ilmu Makki dan
14
Madani, ilmu Nasikh dan Mansukh. Tetapi semua ini tetap
didasarkan pada riwayat dengan cara dikte.
Kemudian pada abad kedua Hijriyah, terjadi masa pembukuan
hadits dengan segala bab yang bermacam-macam. Diantara para
ahli hadits tersebut yaitu Yazid bin Harun as-Sulami (wafat
117 H), Syu’bah bin Hajjaj (wafat 160 H), Waki’ bin Jarrah
(wafat 197 H), Sufyan bin ‘Uyainah (wafat 198 H), dan
‘Abdurrazaq bin Hammam (wafat 112 H).
Langkah mereka pun diikuti oleh segolongan ulama. Mereka
menyusun tafsir al-Qur’an yang kebih sempurna berdasarkan
susunan ayat. Yang paling terkenal diantara mereka yaitu Ibn
Jarir at-Tabari (wafat 310 H).
D. ‘Tujuh Huruf’
Banyak para ulama dan sahabat yang berbeda pendapat
tentang ‘tujuh huruf’ yang dimaksud, namun adapula yang
menyatakan bahwa bilangan ‘tujuh’ bukanlah bilangan dalam
arti sebenarnya, maka dapat kita berpendapat bahwa
perbedaan itu hanya megenai dialek, kita hanya menemukan
adanya kelainan sifat dalam pengucapan satu lafaz.
Diantara pendapat-pendapat para ulama, yang menjadi
pendapat yang kuat yaitu yang menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan tujuh huruf adalah tujuh macam bahasa
dari bahasa-bahasa Arab dalam mengungkapkan satu makna
yang sama.
Walaupun demikian, lafaz al-Qur’an tetap satu,
sekalipun bermacam-macam pengucapan dan dan bacaannya dan
perbedaannya tidak keluar dari tujuh kenyataan berikut:
15
Pertama, perbedaan i’rab (berubah-ubahnya kedudukan
kata atau lafaz di dalam kalimat), baik yang merubah
makna ataupun tidak.
Kedua, perbedaan penulisan huruf, baik yang meerubah
makna tanpa perubahan bentuk huruf itu sendiri,
maupun yang mengakibatkan perubahan bentuk huruf
tetapi tidak mengubah makna.
Ketiga, perbedaan kata nama, baik kata tunggal, dua,
atau jamak, penggolongannya ke dalam jenis laki-laki
atau perempuan.
Keempat, perbedaan pergantian suatu kata dengan kata
lain pad aghalibnya terjdai pada kata-kata sinonim,
yang mengenai makna pada dialek masing-masing
kabilah.
Kelima, perbedaan lafaz, mana yang ditempatkan di
awal kalimat ataupun di akhir kalimat menurut
susunan dan keserasian bahasa arab secara khusus.
Keenam, perbedaan tentang penambahan atau
pengurangan kata penghubung.
Ketujuh, perbedaan dialek dalam mengucapkan huruf.
Hikmah diturunnya al-Qur’an dengan tujuh huruf:
1. Untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang
tidak bisa baca-tulis, dimana setiap kabilah
memiliki dialek masing-masing, namun belum terbiasa
menghafal syari’at, apalagi menjadikannya tradisi.
2. Sebagai bukti kemukjizatan al-Qur’an bagi naluri
atau watak dasar kebahasaan orang Arab, dimana yang
16
dengannya memiliki banyak pola susunan bunyi yang
sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa
yang telah menjadi naluri bahasa orang Arab.
3. Sebagai bukti kemukjizatan al-Qur’an dalam aspek
makna dan hukum-hukumnya, sebab setiap perubahan
bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata
memberikan peluang luas untuk menyimpulkan berbagai
hukum yang terkandung di dalamnya.
17
BAB III
Ilmu-Ilmu Al-Qur’an
Ilmu-ilmu al-Qur’an atau yang biasa disebut dengan ulumul
quran merupakan ilmu yang membahas tentang masalah-masalah
yang berkaitan dengan al-Qur’an dari aspek asbabun nuzul atau
yang disebut juga dengan sebab-sebab turunnya al-Qur’an;
pengumpulan dan penertiban al-Qur’an; pengetahuan tentang
surat-surat Makiyah dan Madaniyah; nasikh dan mansukh; muhkam dan
mutasyabih; dan lain-lainnya yang berhubungan dengannya (al-
Qur’an). Kadang ilmu ini pula dinamakan dengan usulut tafsir
(dasar-dasar tafsir) karena yang dibahas berkaitan dengan
beberapa masalah yang harus diketahui oleh para mufasir
sebagai sandaran dalam menafsirkan al-Qur’an.
Ilmu-ilmu ini pun muncul seiring dengan perkembangan
zaman dari masa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam hingga masa modern
sekarang ini.
A. Ilmu Asbabun Nuzul
Ilmu asbabun nuzul dapat diartikan sebagai ilmu
yang mempelajari sebab turunnya ayat al-Qur’an untuk
menerangkan status (hukum)nya pada saat terjadi
turunnya dalam bentuk peristiwa maupun pertanyaan.
Maka di dalam al-Qur’an, tidak semua ayat memiliki
asbabun nuzul. Karena tidak semua ayat al-Qur’an
yang diturunkan sebab timbul suatu peristiwa dan
kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Disebabkan
pula adanya beberapa ayat yang memiliki satu sebab
18
dan beberapa peristiwa yang terekam dalam satu ayat.
Tetapi ada pula yang diturunkan sebagai permulaan,
tanpa sebab, mengenai akidah iman, kewajiban Islam,
dan syari’at Allah dalam kehidupan pribadi dan
sosial.
Asbabun nuzul dapat menerangkan tentang siapa
ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak
diterapkan kepada orang lain karena dorongan
permusuhan dan perselisihan.
Ada kalanya kita harus mencari sumber dari
hadits-hadits shahih dan kitab ilmu tafsir yang
ditulis oleh para ahli tafsir untuk mengetahui
asbabun nuzul.
Adapun keutamaan-keutamaan dalam mengetahui
asbabun nuzul, yaitu:
a. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu
hukum dan perhatian syara’ terhadap
kepentingan umum dalam menghadapi segala
peristiwa, karena sayangnya kepada umat.
b. Mengkhususkan atau membatasi hukum yang
diturunkan dengan sebab yang terjadi, bila
hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum.
c. Apabila lafaz yang diturunkan itu lafaz
yang umum dan dapat dalil atas
pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai
asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu
hanya terhadap yang selain bentuk sebab.
19
d. Mengetahui sebab nuzul merupakan cara
terbaik untuk memahami makna al-Qur’an dan
menyingkap kesamaran yang tersembunyi
dalam ayat-ayat yang tidak dapat
ditafsirkan tanpa mengetahui sebab
nuzulnya.
B. Ilmu Makki dan Madani
Makki dan Madani ini merupakan identifikasi dari
nama-nama surat yang terkandung dalam al-Qur’an.
Adapun pengertian dari Makki yaitu surat atau ayat-
ayat yang diturunkan pada periode dakwah Nabi
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam di kota Mekkah dan sekitarnya
serta terjadi sebelum hijrah beliau, dan ayat-ayat
itu pun ditujukan kepada penduduk kota Mekkah.
Sedangkan Madani yaitu surat atau ayat-ayat yang
diturunkan pada periode dakwah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam di kota Madinah dan sekitarnya serta terjadi
sesudah hijrah beliau, dan ayat-ayat itu pun
ditujukan kepada penduduk kota Madinah.
Adapun perbedaan antara surat Makki dan Madani
serta ciri khas dalam tema, berikut penjelasannya.
Dari sisi turunnya; surat Makiyah diturunkan sebelum
hijrah, meskipun bukan di Mekkah. Sedangkan surat
Madaniyah diturunkan sesudah hijrah, meskipun bukan
di Madinah.
Dari sisi tempat turunnya; surat Makiyah diturunkan di
kota Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan
20
Hudaibiyah. Sedangkan surat Madaniyah diturunkan di
kota Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan
Sil’.
Dari sisi mukhathab (orang yang diajak bicara); surat
Makiyah menyeru kepada penduduk Mekah, sedangkan
surat Madaniyah menyeru kepada penduduk Madinah.
Segi/
AspekMakki Madani
Ciri
khas
tema
Ajakan kepada tauhid dan
beribadah hanya kepada
Allah, pembuktian mengenai
risalah, kebangkitan dan
hari pembalasan, hari kiamat
dan kengeriannya, neraka dan
siksanya, surga dan
nikmatnya, argumentasi
terhadap orang musyrik
dengan menggunakan bukti
rasional dan ayat kauniyah.
Menjelaskan ibadah,
muamalah, had,
kekeluargaan, warisan,
jihad, hubungan sosial,
baik di waktu damai
maupun perang, kaidah
hukum dan masalah
perundang-undangan.
Ciri
khas
tema
Peletakan dasar umum bagi
perundang-undangan dan
akhlak mulia yang menjadi
dasar terbentuknya suatu
masyarakat; dan menyingkapan
dosa orang musyrik dalam
pertumpahan darah, memakan
harta anak yatim secara
Seruan kepada para ahli
kitab kalangan Yahudi
dan Nasrani untuk masuk
Islam, penjelasan
mengenai penyimpangan
mereka terhadap kitab
Allah, permusuhan
mereka terhadap
21
zalim, penguburan hidup bayi
perempuan dan tradisi buruk
lainnya.
kebenaran setelah ilmu
datang kepada mereka.
Ciri
khas
tema
Menyebutkan kisah para nabi
dan umat terdahulu sebagai
pelajaran bagi mereka, dan
sebagai hiburan bagi Nabi
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
Menyingkap perilaku
orang munafik,
menganalisis
kejiwaannya, membuka
kedoknya dan ia
berbahaya bagi agama.
C. Ilmu Qiraat
Qiraat merupakan masdar (infinitif) dari kata
qara’a yang memiliki arti ‘bacaan’. Adapun menurut
istilah ilmiah, ilmu qiraat merupakan salah satu
mazhab (aliran) pengucapan al-Qur’an yang dipilih
oleh masing-masing imam qurra’ sebagai ciri khas
mereka dalam melantunkan ayat suci al-Qur’an agar
terdengar lebih indah dan mengajarkannya kepada
orang-orang muslim menurut cara mereka dengan
berpedoman kepada masa para sahabat.
Berikut diantara nama-nama imam yang
meriwayatkan ilmu qiraat:
a) Abdullah bin Katsir ad-Dari (wafat 210 H)
di Mekkah;
b) Nafi’ bin Abdurrahman bin Abu Na’im (wafat
120 H) di Madinah;
c) Abdullah bin al-Yahshabi atau yang dikenal
dengan nama Ibnu Amir (wafat 118 H);
22
d) Zayyan bin al-‘Ala bin ‘Amar atau yang
dikenal dengan nama Abu ‘Amr (wafat 154
H);
e) Ya’qub bin Ishaq al-Hadhrami (wafat 205
H);
f) Hamzah bin Ibnu Habib az-Zayyat Maula
‘Ikrimah bin Rabi’ at-Taimi (wafat 188 H);
dan
g) ‘Ashim bin Anin Nujud al-Asadi (wafat 127
H).
D. Ilmu Muhkamat dan Mutasyabih
Muhkam berarti (sesuatu) yang dikokohkan, yaitu
mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang
benar dengan berita yang salah, dan urusan yang
lurus dari urusan yang sesat. Dengan pengertian
inilah Allah Ta’ala mensifati al-Qur’an bahwa
seluruhnya adalah muhkam sebagaimana dalam surat Hud
ayat 1. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berarti
tidak dapat dibedakan dari dua hal yang serupa,
yaitu mutamatsil (sama) dalam perkataan dna keindahan.
Dengan pengertian ini pula lah Allah Ta’ala mensifati
al-Qur’an bahwa seluruhnya adalah mutasyabih
sebagaimana dalam surat az-Zumar ayat 23.
Mengenai hal ini terdapat banyak perbedaan
pendapat, tetapi yang terpenting adalah:
23
a. Muhkam merupakan ayat yang mudah diketahui
maksudnya, sedang mutasyabih hanya
diketahui maksud oleh Allah Ta’ala sendiri.
b. Muhkam merupakan ayat yang hanya
mengandung satu wajah, sedang mutasyabih
mengandung banyak wajah.
c. Muhkam merupakan ayat yang maksudnya dapat
diketahui secara langsung tanpa memerlukan
keterangan lain, sedangkan mutasyabih
memerlukan penjelasan dengan merujuk
kepada ayat-ayat yang lain.
E. Ilmu Nasikh dan Mansukh
Naskh menurut bahasa dipergunakan untuk arti
izalah (menghilangkan), sedangkan dalam istilahnya
yaitu mengangkat (menghapuskan) hukum syara’ dengan
dalil hukum (khitab) syara’ yang lain. Sedangkan yang
dimaksud dengan mansukh yaitu hukum syara’ yang
diganti oleh hukum syara’ yang lain. Naskh dalam al-
Qur’an memiliki tiga macam: naskh tilawah dan hukum;
naskh hukum dan tilawahnya tetap; dan naskh tilawah
dan hukumnya tetap.
Adapun hikmah naskh, yaitu:
a. Memelihara kepentingan hamba.
b. Perkembangan tasyri’ menuju tingkat
sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah
dan perkembangan kondisi umat manusia.
24
c. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk
mengikutinya atau tidak.
d. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi
umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal
yang lebih berat maka di dalamnya terdapat
tambahan pahala, dan jika beralih ke hal
yang lebih ringan maka ia mengandung
kemudahan dan keringanan.
25
BAB IV
TAFSIR DAN I’JAZ AL-QUR’AN
A. Tafsir Al-Qur’an
Tafsir dalam pengertian secara bahasa yaitu
menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan
makna yang abstrak. Sebagaimana dalam surat al-furqan
ayat 33, bahwa maksud dari kata ‘tafsiiran’ adalah
“paling baik penjelasan dan perinciannya”. Sedangkan
tafsir menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang
cara pengumpulan lafaz-lafaz al-Qur’an, tentang petunjuk-
petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri
maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan
baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang
melengkapinya. Pengertian inilah yang didefinisikan oleh
Abu Hayyan.
Adapun ta’wil, yaitu berasal dari kata ‘aul’ yang
berarti kembali ke asal. Namun dalam pengertian secara
istilah dan maknanya memiliki dua makna: ta’wil kalam
dengan pengertian suatu makna yang kepadanya mutakallim
(pembicara, orang pertama) mengembalikan perkataannya,
atau suatu makna yang kepadanya suatu kalam dikembalikan.
Dan ta’wil kalam dalam arti menafsirkan dan menjelaskan
maknanya.
Namun demikian terdapat perbedaan antara tafsir dan
ta’wil, yaitu:
a. Apabila kita berpendapat, ta’wil adalah
menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya,
26
maka ta’wil dan tafsir merupakan dua kata yang
berdekatan atau sama maknanya.
b. Apabila kita berpendapat, ta’wil adalah esensi
yang dimaksudkan dari suatu perkataan, maka
ta’wil dari talab (tuntutan) merupakan esensi
perbuatan yang dituntut itu sendiri dan ta’wil
khabar adlaah esensi sesuatu yang diberitakan.
c. Dikatakan tafsir adalah apa yang telah jelas di
dalam Kitabullah atau tertentu (pasti) dalam
sunnahyang shahih karena maknanya telah jelas
dan gamblang. Sedangkan ta’wil adalah apa yang
disimpulkan para ulama.
d. Dikatakan tafsir jika digunakan lebih banyak
dalam menerangkan lafaz dan mufradat (kosa
kata), sedangkan ta’wil lebih banyak dipakai
dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat.
Tafsir pun dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tafsir bil-
ma’tsur dan tafsir bir-ro’yi.
1. Tafsir bil-Ma’tsur
Tafsir bil-ma’tsur merupakan tafsir yang
berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih
menurut urutan yang telah disebutkan di muka
dalam syarat-syarat mufasir, yaitu menafsirkan
al-Qur’an dengan al-Qur’an, dan dengan sunnah
karena ia berfungsi untuk menjelaskan
Kitabullah. Adapun di dalam buku Studi Ilmu-
Ilmu Al-Qur’an karangan Manna Khalil al-Qattan
27
mengungkapkan bahwa fatsir al-Qur’an yang
didasari atas dalil-dalil sahih yang dinukilkan
dengan hadits-hadits shahih secara tertib mulai
tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an ataupun
dengan assunnah karena hal tersebut datang
untuk menjelaskan kitab Allah yang satu, yaitu
al-Qur’an, dengan apa yang diriwayatkan dari
para sahabat karena mereka lah orang yang
paling tahu tentang kitab Allah yang diturunkan
kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan mereka
melihat langsung kejadian tersebut dengan apa
yang dikatakan oleh orang-orang tabi’in karena
umumnya mereka adalah orang yang menerima hal
tersebut dari para sahabat. Selain itu disini
akan dikemukakan kitab-kitab yang termasuk
golongan tafsir bil-ma’tsur:
a. Jam’ul Bayan Fii Tafsir Qur’an oleh Ibnu
Jarir at-Thabari (310 H)
b. Al-Kasyfu wal Bayan’an Tafsiril Qur’an oleh
Imam Ahmad Ibnu Karim ats-Tsabit (427 H)
c. Ma’alimut Tanzil oleh Imam Husain ibnu
Mas’ud al-Baghawi (516 H)
2. Tafsir bir-ro’yi
Tafsir bil-ra’yi merupakan tafsir yang di
dalamnya menjelaskan maknanya mufasir hanya
berpegang pada pemahaman sendiri dan
penyimpulan (istinbat) yang didasarkan pada rayuan
28
semata. Tafsir ini pula didasarkan pada sumber
ijtihad dan pemikiran para mufasir terhadap
tuntuan kaidah bahasa Arab dan kesusastraannya.
Adapun di dalam buku Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an
karya Manna Khalil al-Qattan menyatakan bahwa
tafsir ini merupakan penafsiran yang dilakukan
oleh para mufasir dengan menerangkan makna
hanya dnegan berlandaskan kepada pemahaman yang
sesuai dengan jiwa syari’ah dan yang
berlandaskan nas-nasnya. Maka sebenarnya
menafsirkan al-Qur’an dengan ra’yu dan ijtihad
semata tanpa ada dasar yang shahih adalah
haram, tidak boleh dilakukan. Sebagaimana Allah
Ta’ala berfirman:
“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyai pengetahuan tentangnya.” [al-Isra’: 36]
Adapun kitab-kitab yang termasuk tafsir
bil-ro’yi yaitu:
a. Tafsir Mafatihul Ghaib oleh Faruddin ar-
Razi (606 H)
b. Anwam at-Tanzil wa Haqiqatul Takwil oleh
Imam Abul Barakat
c. Madarikut Tanzil Fii Ma’arit Tanzil oleh
Imam al-Khazin (741 H)
Adapun tafsir yang masih terpuji dan tercela yang
telah diterangkan dari kalangan ulama, yaitu isra’iliyat yang
merupakan berita-berita yang diceritakan oleh Ahli Kitab29
yang masuk Islam, dimana beberapa berita ini diterima
oleh para sahabat selama hal tersebut tidak berhubungan
dengan akidah dan tidak pula berkaitan dengan hukum.
Kemudian tafsir Sufi, yang serupa berusaha untuk membawa nas-
nas ayat kepada arti yang tidak sejalan dnegan arti
lahiriyah, dan tenggelam dalam ta’wil-ta’wil batil yang
jauh serta menyeret kepada kesesatan-kesesatan seperti
ilhad (atheism) dan penyimpangan. Kemudian ada juga tafsir
Isyari, yaitu jika memasuki isyarat-isyarat yang samar akan
menjadi suatu kesesatan, tetapi selama ia merupakan
istinbat yang baik dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan
oleh zahir bahasa Arab serta didukung oleh bukti
keshahihannya, tanpa pertentangan maka ia dapat diterima.
Kemudian pula ada Gara’ibut Tafsir yaitu tafsir yang janggal,
merupakan kata-kata yang janggal atau asing yang sering
dikemukakan oleh para ahli tafsir sekalipun hal tersebut
membuatnya menyimpang dari jalan lurus dan menempuh jalan
berbahaya. Mereka membebani diri sendiri dengan hal-hal
yang tidak mampu dikerjakan dan memeras pikiran mereka
untuk sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali melalui
tauqifi (penjelasan dari Nabi). Maka mereka tampil dengan
membawa kedunguan dan kesesatan yang dipandang hina oleh
akal mereka sendiri.
Adapun ilmu-ilmu yang harus diketahui, dipahami
dengan baik oleh para mufassir adalah usuulut tafsiir
(dasar-dasar tafsir) yang mana mencakup ilmu-ilmu al-
Qur’an seperti: ilmu asbabun nuzul, ilmu turunnya al-
Qur’an, ilmu pengumpulan dan penertiban al-Qur’an, ilmu
30
makki dan madani, ilmu muhkam dan mutasyabih, ilmu ‘aam
dan khash, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu mutlaq dan
muqoyyad, ilmu mantuq dan mafhum, ilmu qasam al-Qur’an,
ilmu tafsir dan ta’wil, kisah-kisah yang terdapat di
dalam al-Qur’an, ilmu amtsalul qur’an, ilmu qiraat.
B. I’jaz (Mikjizat Al-Qur’an)
Pembahasan selanjutnya yaitu i’jaz atau yang dikenal
pula dengan sebutan mukjizat, yang memiliki arti
menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum
merupakan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, dan
merupakan lawan dari kemampuan. Dalam hal ini yaitu
menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam
pengakuannya sebagai Rasul dengan menampakkan kelemahan-
kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang
abadi, yaitu al-Qur’an, dan kelemahan-kelemahan generasi
setelah mereka. Dan mukjizat adalah suatu hal yang luar
biasa yang disertai tantangan dan selamat dari
perlawanan.
Kadar kemukjizatan al-Qur’an pun akan disebutkan di
bawah ini:
a. Golongan Mu’tazilah berpendapat bawha
kemukjizatan al-Qur’an merupakan hal yang
berkaitan dengan keseluruhan al-Qur’an, bukan
dengan sebagiannya, atau dengan setiap suratnya
secara lengkap.
b. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian kecil
atau sebagian besar dari al-Qur’an baik itu
31
tidak penuh satu surat, maka hal tersebut pula
dapat dikatakan sebagai mukjizat al-Qur’an,
sebagaimana didasari dari surat at-Tur ayat 34:
“maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal
Qur’an..”
c. Ulama yang lain berpendapat bahwa kemukjizatan
al-Qur’an itu cukup dengan hanya satu surat
lengkap saja, sekalipun ia pendek, atau dengan
ukuran satu surat, baik satu ayat atau beberapa
ayat.
Bahkan kemukjizatan al-Qur’an pun mempengaruhi aspek
tata bahasa, aspek ilmiah dan aspek tasyri’ (penetapan
hukum). Para penyair suku Arab yang handal dan
profesional pun tidak dapat menandingi tata bahasa al-
qur’an yang lebih indah daripada kata-kata yang diuntai
oleh mereka sendiri. Subhanallah!
Sedangkan dalam aspek ilmiah yaitu bukan terletak
pada kecakupan akan teori-teori ilmiah yang selalu baru
dan berubah serta menrupakan hasil usaha manusia dalam
penelitian dan pengamatan. Tetapi ia terletak apda
dorongannya untuk berpikir menggunakan akal sehat yang
telah diciptakan Allah Ta’ala. Bahkan al-Qur’an
membangkitkan pada diri setiap muslim akan kesadaran
ilmiah untuk memikirkan, memahami, dan menggunakan akal
sehat, sebagimana yang telah tersebut dalam surat al-
Qur’an: “demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar
kamu berpikir” [al-Baqarah: 219]
32
Adapun kemukjizatan al-Qur’an dalam aspek tasyri’
atau penetapan hukum yang sangat erat kaitannya dengan
memulai dari personal individu, karena individu merupakan
batu-bata masyarakat, dan menegakkan pendidikan individu
di atas penyucian jiwa dan rasa pemikulan tanggung jawab.
Al-Qur’an menyucikan individu tersebut dengan akidah
tauhid yang menyelamatkannya dari belenggu perbudakan
hawa nafsu dan syahwat, menjadi hamba yang taat dan
ikhlas kepada Allah Ta’ala dan hanya menjadikan-Nya
sebagai Tuhan Yang Satu dengan menempuh jalan yang lurus.
Kemudian berpindah dari pendidikan individu ke
pendidikan keluarga, karena keluarga adalah menih
masyarakat, hingga datanglah pendidikan sistem
pemerintahan yang mengatur masyarakat dengan menetapkan
kaidah-kaidah dasar hukum Islam dari panduan al-Qur’an
dalam bentuk yang paling baik dan ideal dengan
pengontrolan agama, seperti sabar, jujur, adil, berbuat
baik, santun, maaf dan tawadhu’.
33