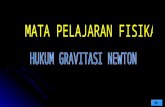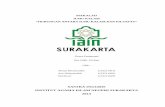Ilmu hukum
Transcript of Ilmu hukum
A. Pengertian Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum1. Pengertian Ilmu hukumMenurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yangberusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979 : v).Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.
2. Pengertian Pengantar ilmu hukumPengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.
B. Tujuan dan Kegunaan Pengantar Ilmu HukumTujuan Pengantar Imu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahamibagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.
C. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu HukumKedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran
lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagaimata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmuhukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatuyang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukumjuga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.
D. Ilmu Bantu Pengantar Ilmu Hukum• Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asalusul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatumasyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu• Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto)• Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).• Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu denganyang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain• Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).
E. Metode Pendekatan Mempelajari Hukum
1. Metode Idealis ; bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat
2. Metode Normatif Analitis ; metode yg melihat hukum sebagai aturan yg abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri
terlepas dari hal2 lain yang berkaitan dengan peraturan2. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.
3. Metode Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari pandanganbahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
4. Metode Historis ; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5. Metode sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
6. Metode Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.
Pengertian hukum menurut AristotelesSesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.
Pengertian hukum menurut Hugo de GrotiusPeraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (law is rule of moral action obligation to that which is right).
Pengertian hukum menurut Leon DuguitSemua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yangdlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukanpelanggaran itu.
Pengertian hukum menurut Immanuel KantKeseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan.
Pengertian hukum menurut Roscoe PoundSebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan hukum merupakan tingkah lakupara individu yang mempengaruhi individu lainnya. Adapun hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif Law as a tool of social engineering.
Pengertian hukum menurut John AustinSeperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga rakyatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi.
Pengertian hukum menurut Van VanenhovenSuatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain.
Pengertian hukum menurut Prof. Soedkno MertokusumoKeseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalamsuatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.
Pengertian hukum menurut Mochtar KusumaatmadjaKeseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusiadalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.
Pengertian hukum menurut Karl Von SavignyAturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat
Pengertian hukum menurut HolmesApa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan.
Pengertian hukum menurut Soerjono SoekamtoMempunyai berbagai arti:1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan3. Hukum dalam arti kadah atau norma4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis5. Hukum dalam arti keputusan pejabat6. Hukum dalam arti petugas7. Hukum dalam arti proses pemerintah8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilaiAsas ---> Asas secara umum adalah sesuatu yang meliputi semua aspek (dasar utama). Atau dapat juga dikatakan akar dari norma-norma dan aturan aturan (ini kata-kata saya, bukan kutipan jadi tidak dijamin benar, tapi gambarannya kurang lebih seperti itu). Berikut beberapa asas hukum umum yang saya copy melalui http://hendramardika.wordpress.com/2010/11/14/beberapa-istilah-dalam-asas-hukum
1. Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali (Azas Legalitas) : tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum didahului oleh suatu peraturan.
2. Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen : setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telahdilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
3. Lex Superior Derogat Legi Inferiori : hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, Undang-Undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, begitu seterusnya.
4. Lex Specialist Derogat Legi Generale : hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.
5. Lex Posteriori Derogat Legi Priori : peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undanglama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undanglama.
6. Lex Dura, Sed Temen Scripta : peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian.
7. Summum Ius Summa Iniuria : kepastian hukum yang tertinggi, adalah ketidakadilan yang tertinggi.
8. Ius Curia Novit : hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yangdiajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.
9. Presumption of Innosence (praduga tak bersalah) : seseorang tidak boleh disebut bersalah sebelum dibuktikan kesalahannyamelalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
10. Res Judicata Proveri Tate Habetur : setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
11. Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) : hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus,tidak dapat dinilai sebagai saksi.
12. Audit et Atteram Partem : hakim haruslah mendengarkan parapihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.
13. In Dubio Pro Reo : apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkanbagi terdakwa.
14. Fair Rial atau Self Incrimination : pemeriksaan yang tidak memihak, atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa.
15. Speedy Administration of Justice (peradilan yang cepat) : Artinya, seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.
16. The Rule of Law : semua manusia sama kedudukannya di depan hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hukum.
17. Nemo Judex Indoneus In Propria : Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.
18. The Binding Forse of Precedent atau Staro Decises et Quieta Nonmovere : pengadilan (hakim) terdahulu, mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut pada negera-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris).
19. Cogatitionis Poenam Nemo Patitur : tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada di hatinya.Artinya, pikiran atau niat yang ada di hati seseorang untuk melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan maka ia tidak boleh dihukum. Di sini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi.
20. Restitutio In Integrum : kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai “sarana penyelesaian konflik”.
Norma---> berasal dari bahasa latin norma yang berarti siku-siku.Siku-siku dipakai untuk membuat sudut 90 derajat dan menjadi tolak ukur sudut 90 derajat. Jadi norma dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi alat ukur atau tolak ukur untuk yang dipakaiuntuk menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk ( lagi-lagi ini kata-kata saya yang tidak dijamin kebenarannya, tetapi gambarannya kurang lebih seperti itulah)...Perbedaan asas, norma dan aturan hukum dapat dilihat sebagai berikut.Asas hukum melahirkan Norma hukum, dan norma hukum melahirkan aturan hukum.Contonya asas hukum pengakuan terhadap hak milik individu melahirkan norma dilarang mencuri, dilarang menggelapkan barang orang lain dsb. Dari norma tersebut dilahirkan aturan misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Hubungan kausalitas dalam hukum pidana biasanya banyak
dibahas dalam ajaran kausalitas (ajaran mengenai sebab dan
akibat). Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang
mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat
dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan atau hingga
berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu
akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang
telah melakukan tindaka tersebut dapat diminta
pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.1[1]
Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan
suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab Undang-Undang dan
Hukum Pidana sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara
penentuan sebab suatu akibat yang melahirkan delik. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa
untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat
tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.2[2] Apabila
dilihat dari cara merumuskannya, maka tindak pidana dapat
dibedakan antara (1) tindak pidana yang dirumuskan secara formil,
disebut dengan tindak formil (formeel delicten), dan (2) tindak
pidana yang dirumuskan secara materiil, disebut dengan tindak
pidana materiil (Materiel delicten).3[3]
Tindak pidana materiil mensyaratkan adanya akibat tertentu.
Sedangkan tindakan pidana materiil, ialah tindak pidana yang
1
2
3
dirumuskan dengan melarang menimbulkan akibat tertentu disebut
akibat terlarang. Titik beratnya larangan pada menimbulkan akibat
terlarang ( unsure akibat konstitutif). Contohnya mewujudkan
tingkah laku menghilangkan nyawa, misalnya dengan wujud
konkritnya: menusuk (dengan pisau) tidaklah dengan demikian
melahirkan tindak pidana pembunuhan, apabila dari perbuatan
menusuk itu tidak melahirkan akibat matinya korban.4[4] Dalam hal
terwujudnya tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3
syarat esensial, yaitu:
1. Terwujudnya tingkah laku
2. Terwujudnya akibat
3. Ada hubungan kausal antara wujud tingkah laku dengan akibat
konstitutif
Tindak pidana formil merupakan lawan dari tindak pidana
materiil.5[5] Mensyaratkan adanya perbuatan belaka, tidak
mensyaratkan adanya suatu akibat. Misalnya penghasutan (Pasal
150, KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), sumpah Palsu ()Pasal 242
KUHP) dan pemalsuan surat (pasal 263 KUHP).
Dalam hubungannya dengan penentuan pertanggung jawab pidana,
tidaklah mudah untuk menentukan factor yang manakah yang
menyebabkan akibat tindak pidana.dalam menghadapi persoalan
mencari dan menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud
perbuatan dengan akibatnya, ajaran kausalitas menjadi penting.
Ajaran kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari
4
5
jawaban dari masalah akibat tindak pidana.ajaran kausalitas dapat
membantu para praktisi hukum terutama hakim dalam mencari dan
menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud
perbuatan dengan akibat yang timbul.
2. Macam- macam ajaran kausalitas Banyaknya rangkaian sebab-sebab yang jumlahnya tak mungkin
untuk ditentukan karena selalu berubah menurut pandangan orang
yang akan menentukannya, maka teori-teori tersebut dibagi menjadi
3 bagian, yaitu:
a. Teori Ekivalensi (aquivalenz-theorie) atau Bedingungstheorie
atau Teori Condition Sine Qua Non dari Von Buri
Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan
teorinya conditio sine qua non yang secara literal berarti syarat
mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara
syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam
teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut
menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat
dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian
syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya
penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan
rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak
terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini
dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap
sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.6[6]
6
Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan
yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan
dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah
termasuk menjadi penyebabnya. Contoh: Seorang bapak mengendarai
motor hendak menyeberang- mengambil jalur yang lain dengang
berbelok ke kanan tanpa memperhatikan kendaraan dari arah
belakang, dan ketika itu ada sebuah mobil yang melaju dari arah
belakang. Pengendara mobil mengerem dengang kencang hingga
menimbulkan suara yang keras (akibat gaya gesek ban dengan jalan)
sehingga menyebabkan bapak tadi terkejut, walaupun mobil tidak
sampai menabrak bapak, akan tetapi bapak jatuh dari motor dan
pingsan. Dilarikan ke RS, setengah jam kemudian meninggal dunia.
Segala faktor yang menyebabkan terjadinya akibat terlarang
merupakan penyebab dalam teori ini. semua faktor dinilai sama
pengaruhnya atau andil atau peranannya terhadap timbulnya akibat
yang dilarang. Tanpa salah satu atau dihilangkannya salah satu
dari rangkaian faktor tersebut tidak akan terjadi akibat menurut
waktu, tempat, dan keadaan senyatanya dalam peristiwa itu.
Sehingga teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena
menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya
(equivalent).7[7]
Kelemahan ajaran ini ialah pada tidak membedakan antara
faktor syarat dengan faktor penyebab, yang dapat menimbulkan
ketidak adadilan. Pada contoh tadi, si pengemudi mobil
dipertanggung jawabkan atas kematian bapak tadi, dipandang tidak
7
adil, karena pada dirinya tidak ada kesalahan dalam hal
terjadinya peristiwa kematian bapak tadi, dan artinya
bertentangan dengang asas hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan
(geenstraf zonder schuld)
Walaupun teori ini memiliki kelemahan yang mendasar, tetapi
dalam praktik di negeri Belanda pernah juga dianut oleh Hoge Raad
dalam pertimbangan suatu putusan yang menyatakan bahwa “untuk
dianggap sebagai sebab daripada suatu akibat, perbuatan itu tidak
perlu bersifat umum atau normal” (Satochid: 451). Bersifat umum
atau normal maksudnya ialah bahwa faktor yang dinilai sebagai
penyebab itu tidaklah perlu berupa faktor yang menurut
perhitungan yang wajar dan kebiasaan yang berlaku dapat
menimbulkan akibat, asalkan ada kaitannya dalam rangkaian
peristiwa yang menimbulkan akibat- semuanya adalah faktor
penyebab.
b. Teori yang menggeneralisir
Teori yang menggeneralisir ialah teori yang dalam mencari
sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh/ berhubungan dengan
timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor
mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada
umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor
penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah
peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada
umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara
abstracto, tidak secara inconcreto.8[8]
Contoh: karena jengkel kepada bawahannya yang berbuat salah,
bawahannya itu ditempelengnya dengan tangan kosong yang secara
wajar menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya tidak akan
menyebabkan kematian, tetapi kemudian korban pingsan dan
meninggal.
Untuk menentukan bahwa suatu sebab itu pada umumnya secara
wajar dan menurut akal dapat menimbulkan suatu akibat maka timbul
2 pendirian:
1) Pendirian yang subjektif ( Teori Adequat Subjectif)
Teori Adequat Subjectif dipelopori oleh J. Von Kries, yang
menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut
kejadian yang normal adalah adequat (sebanding)/ layak dengan
akibat yang timbul, faktor yang diketahui dan disadari oleh si
pembuat yang akan menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori
ini faktor subjektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat
adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal,
sikap batin mana berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang
akan dilakukan itu adalah adequat untuk menimbulkan akibat yang
timbul, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman
manusia pada umumnya.
Contoh: meninggalnya bapak pengidap penyakit jantung tadi,
menurut teori ini, pengendara mobil tidak dipersalahkan atas
8
kematiaanya, karena faktor menginjak rem yang menimbulkan suara
keras tidak dapat dibayangkan pada umumnya sehingga menimbulkan
kematian bapak yang hendak menyeberang jalan
2) Pendirian objektif (Adequat Objectif)
Pada ajaran adequat objektif ini, tidak memperhatikan bagaimana
sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor-
faktor yang ada setelah (post factum) peristiwa senyatanya beserta
akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal (objektif)
faktor- faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana
alam pikiran/ sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah
penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa
terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal
dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.
Contoh: meninggalnya pasien yang diminumkan obat oleh perawat,
yang sebelumnya telah dicampuri racun oleh orang yang ingin
membunuh pasien, walaupun tidak diketahui oleh perawat, perbuatan
perawat meminumkan obat yang mengandung racun adalah adequat
terhadap matinya pasien, karena itu ada hubungan kausal dengan
akibat kematian pasien (Moeljanto, 1983:111)
c. Teori yang mengindividualisir
Teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya
mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya
melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan
dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta
akibatnya benar- benar terjadi secara konkrit (post factum). Teori
ini memilih secara post actum (inconcreto), artinya setelah
peristiwa kongkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan
pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa
tersebut; sedang faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat
belaka.9[9]
Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling
berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat
terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah
dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.10
[10] Pendukung teori yang mengindividualisir ini antara lain
Birkmeyer dan Karl Binding.
Contoh: meninggalnya orang yang awalnya ditempeleng oleh
atasannya, menurut teori ini, peristiwa tersebut harus dicari dan
dinilai diantara rangkaian faktor yang berkaitan dengan kematian
itu. Kiranya faktor “serangan jantung” yang paling dominan
peranannya terhadap kematian itu.11[11]
B. SIFAT MELAWAN HUKUM 1. Pengertian
Sifat melawan hukum yang dalam bahasa belanda disebut
wederrechtelijk oleh para ahli hukum diberikan arti yan berbeda –
beda. Van Hamel mengelompokkannya menjadi dua, yaitu :
a. Paham Positif
9
10
11
Paham positif mengartikan wederrechtelijk sebagai instridj met het
recht (bertentangan dengan hukum) atau sebagai met krenking van eens
anders recht (dengan melanggar hak orang lain). Pendapat pertama
dinyatakanakan oleh Simons dan yang kedua disebutkan oleh Noyon.
b. Paham Negatif
Wederrechtelijk diartikan pada paham negatif sebagai niet steunend
op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder bevoegdheid (tanpa
hak). Pendapat demikian dinyatakan oleh Hoge Raad. 12[12]
Melihat perdebatan yang terjadi mengenai pemberian arti
wederrechtelijk, Lamintang mencoba untuk mememberiikan arti kata
wederrechtelijk ke bahasa Indonesia tidak secara harfiah. Lamintang
mengartikan wederrechtelijk sebagai suatu perbuatan “secara tidak
sah”.
Menurut Lamintang, frasa “secara tidak sah” lebih tepat
digunakan karena mencakup keseluruhan arti yang diberikan oleh
para pakar. Instridj met het recht (bertentangan dengan hukum) atau met
krenking van eens anders recht (dengan melanggar hak orang lain) atau
niet steunend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder
bevoegdheid (tanpa hak) jelas merupakan perbuatan yang dilakukan
secara tidak sah.
2. Paham – Paham Wederrechtelijk a. Sifat melawan hukum dalam arti formal (formele wederrechtelijk).
Paham ini menyebutkan bahwa suatu perbuatan hanya bisa
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan telah
mencocoki larangan undang – undang, maka disitu ada kekeliruan.
12
Letak melawan hukumnya perbuatan sudah tercantum dalam sifat
melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika perbuatan tersebut
termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang.13
[13]
b. Sifat melawan hukum dalam arti material (materieele wederrechtelijk).
Paham ini menganggap bahwa belum tentu semua perbuatan yang
mencocoki undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka, yang
dinamakan hukum bukan hanya undang – undang yang tertulis saja,
karena ada pula hukum tidak tertulis berupa norma – norma dan
kenyataan – kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Unsur sifat melawan hukum di dalam rumusan perundang- undangan.
Sifat melawan hukum dinyatakan dalam rumusan tindak pidana
dengan pelbagai istilah, yaitu :
a. Secara tegas menyebut “melawan hukum”.
Adapun aturan perundang-undangan yang secara tegas
menyebutkan kata “melawan hukum” dapat dijumpai pada pasal 362,
368, 369, 372, dan 378 KUHP sebagai berikut :
Pasal 362
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.
13
Pasal 368
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau
orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan.
Pasal 369
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran
baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan
membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang
lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 372
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.
Pasal 378
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun
menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
b. Tanpa hak, tidak berhak, atau tanpa wenang (zonder daartoe
gerichtigd te zijn).
Adapun aturan perundang-undangan yang memberikan makna
“melawan hukum” dengan kata “tanpa hak, tidak berhak, atau tanpa
wenang (zonder daartoe gerichtigd te zijn)” dapat dijumpai pada pasal 548
dan 549 KUHP sebagai berikut :
Pasal 548
Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di
kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami,
diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh
lima rupiah.
Pasal 549
(1) Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di
kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang
rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau
ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah
kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah
diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan
pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
c. Tanpa izin (zonder verlof).
Adapun aturan perundang-undangan yang memberikan makna
“melawan hukum” dengan kata “tanpa izin (zonder verlof)” dapat
dijumpai pada pasal 496 dan 510 dalam KUHP sebagai berikut :
Pasal 496
Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk
untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri,
diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh
rupiah.
Pasal 510
(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh
puluh lima rupiah, barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu:
2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
d. Melampaui kekuasaannya (met overschrijding van zijn bevoegheid).
Adapun aturan perundang-undangan yang memberikan makna
“melawan hukum” dengan kata “melampaui kekuasaannya (met
overschrijding van zijn bevoegheid)” dapat dijumpai pada pasal 430 KUHP
sebagai berikut :
Pasal 430
(1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh
memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang
atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau
kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.
(2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui
kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain
yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi
keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan
denggan perantaraaan lembaga itu.
e. Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum
(zonder inachtneming van de bij algemeene verordeening bepaalde vormen).14[14]
Adapun aturan perundang-undangan yang memberikan makna
“melawan hukum” dengan kata “tanpa memperhatikan cara yang
ditentukan dalam peraturan umum (zonder inachtneming van de bij algemeene
verordeening bepaalde vormen)” dapat dijumpai pada pasal 429 KUHP
sebagai berikut :
Pasal 429
(1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa
mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum,
14
memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan
terututup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ
secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang
berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada
waktu menggeledah rumah, dengan melampaui ke kuasaannya atau
tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan
umum, memeriksa atau merampas surat surat, buku-buku atau kertas-
kertas lain.
BAB IIIPENUTUP
A. Simpulan 1. Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan
hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai
penyebab dari sesuatu keadaan atau hingga berapa jauh sesuatu
keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu
tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan
tindaka tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut
hukum pidana.
2. Ajaran kausalitas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
a. Teori Ekivalensi (aquivalenz-theorie) atau Bedingungstheorie
atau Teori Condition Sine Qua Non dari Von Buri
b. Teori yang menggeneralisir
c. Teori yang mengindividualisir
3. Sifat melawan hukum diartikan berbeda – beda oleh para pakar
yang pada intinya adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak
sah.
4. Ada dua paham mengenai sifat melawan hukum, yaitu :
a. Sifat melawan hukum dalam arti formal (formele
wederrechtelijk).
b. Sifat melawan hukum dalam arti material (materieele
wederrechtelijk).
B. Saran
Bagi lembaga yang berwenang untuk menetapkan undang – undang
hendaknya merumuskan suatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang
baru agar dapat menyelesaikan masalah secara kontekstual.
Bersamaan dengan itu juga memasukkan kejelasan sikap hukum pidana
di Indonesia mengenai paham apa yang digunakan dalam penentuan
sifat melawan hukum.