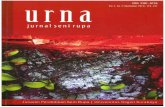REGULASI RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF HAM : KAJIAN YURIDIS-NORMATIF DAN SOSIO-EMPIRIS TERHADAP PBM...
-
Upload
unmermadiun -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of REGULASI RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF HAM : KAJIAN YURIDIS-NORMATIF DAN SOSIO-EMPIRIS TERHADAP PBM...
REGULASI RUMAH IBADAH DALAM HAK ASASI
Kajian Normatif dan Sosio-Empiris terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
Agung Hidayat Mazkuriy1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Paska amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945,
sistem pemerintahan mengalami transformasi kultur ketatanegaraan yang
fundamental, diantara perubahan konstitusi tersebut adalah dimasukanya Bab tentang
Hak asasi Manusia (Bab XA UU 1945) yang menegaskan cita negara dalam
pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Hasil
perubahan tersebut menambahkan banyak ketentuan jaminan perlindungan HAM
secara lebih spesifik.
Bahkan juga ditegaskan adanya hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun (non-derogable rights) yang meliputi; hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.2 Jika dalam UUD 1945 hanya
terdapat 7 butir ketentuan yang mengatur hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga negara, Perubahan UUD 1945 memuat 37 butir.3 Disamping itu, pembangunan
HAM ditegaskan lagi oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentantang HAM, UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Peradilan HAM.4 Namun kemajuan secara normatif tersebut tidak beriringan dengan
kemajuan pada tataran praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintahan paska reformasi yang telah berjalan satu setengah dekade belum
1 Ucapan terima kasih kepada Dr. Subadi, S.H., yang telah memberi saran dan kritik, dan Bayu Fajar
Nugraha dan Bakri Iskandar yang telah memberi support, baik materiil maupun immateriil. Makalah ini adalah makalah yang diajukan tim Debat Universitas Merdeka Madiun pada penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi 2015 di Universitas Surabaya pada tanggal 19-21 Mei 2015.
2 Muchammad Safa’at Ali, “HAM Di Era Reformasi”, Academia.edu, https://www.academia.edu/
6376473/HAM_Di_Era_Reformasi, diunduh pada tanggal 27 Maret 2015. 3 Ibid.
4 Bour Mana, 2005, Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hal. 700.
mampu membawa kemajuan yang signifikan,5 meskipun sudah dikeluarkannya
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009,6 sebagai kelanjutan program RANHAM
periode sebelumnya (1998-2004). Namun, ada kecenderungan bahwa dalam
menjalankan program RANHAM, pemerintah mengambil kebijakan politik
menghindar dari program-program yang mengundang resistensi dan konflik politik
dengan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti Kasus Trisakti, Semanggi I dan
II, Kasus Wamena-Wasior, Kasus Timor-Timur, serta penghilangan orang secara
paksa tidak mendapat perhatian dari pelaksanaan Rancangan Aksi Nasional HAM
(RANHAM). Dari hasil indeks skor, kinerja penegakan HAM pemerintahan2004–
2009 berada pada derajat minimum.7 Dari 103 program utama hanya 56 (54,6%)
program yang terlaksana dan 47 (45,4%) di antaranya tidak terlaksana. 56 program
yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal departemen.
Sebagian lain merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang
ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) meski dengan kualitas minimum.8 Artinya
dalam tataran aplikatif, perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar paska amandemen belum terlaksana dengan baik.
Sejarah kekerasan terhadap aspek yang bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia
yang berkaitan pendirian rumah ibadah telah terjadi sejak rezim Orde Baru hingga
sekarang. Seperti pengrusakan terhadap beberapa Gereja di Makassar, Sulawesi
Selatan, Pada 1 Oktober 1967, pengrusakan terhadap pembangunan sebuah gereja
methodis di daerah Meulaboh, Aceh Pada tahun 1967, penghancuran Gereja Protestan
disebuah daerah Pinggiran Jakarta pada awal tahun 1969. Salah satu konflik diseputar
rumah ibadah yang pernah menyita perhatian publik adalah Kasus Gereja HKBP
Ciketing ,Bekasi pada tanggal 12 September 2010 mengakibatkan 2 pemuka Gereja
5 Ibid.
6 Landasan hukum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut adalah Kepres No. 129 tanggal
15 Agustus 1998. Empat pilarprogram tersebut adalah; 1) Pengesahan perangkat Internasional, 2) Diseminasi dan penegakan HAM, 3) Pelaksanaan dan perlindungan ‘non-derogabel rights’, 4) Pelaksanaan isi dan ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
7 Ibid.
8 Ibid.
HKBP Ciketing harus dirawat intensif karena dianiaya oleh anggota Front Pembela
Islam (FPI).9
Berdasarkan sumber catatan yang dirilis Center for Religious and Cross-cultural
Studies Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM), setidaknya terjadi beberapa
peristiwa yang tercatat sepanjang 2008 berhubungan tempat ibadah.10 Berikut
beberapa data tentang kekerasan yang berkaitan dengan rumah ibadah:11 (i)
Penutupan Gereja GEKARI Bengkulu yang berdiri sejak 1990 oleh Masyarakat pada
tanggal 13 Januari 2008 di Bengkulu, (ii) pengrusakan Kompleks Pura Sengareng di
Kecamatan Narmada Lombok Barat pada tanggal 16 Januari 2008, (iii) Pembekuan
IMB GKI Bogor di Jawa Barat pada tanggal 14 Februari 2008, (iv) Pelarangan
Renovasi GpdI di Lampung Selatan di Dusun III, Kecamatan Sidomulyo, Lampung
Selatan pada tanggal 4 Maret 2008, (v) Pembubaran Misa Paskah di Gereja Santo
Johannes Baptista di Parung tanggal 22 Maret 2008, (vi) Ancaman Penutupan Gereja
HKBP Binjai di Sumatra Utara tanggal 1 Mei 2008, (vii) Penutupan Gereja GpdI
Pekanbaru tanggal 30 Mei 2008, (viii) Pembongkaran Gereja HKB Gekindo Bekasi
oleh Petugas Trantib Bekasi tanggal 14 Juni 2008; (ix) Pengrusakan Gereja Injili
Nabire oleh Jeemaat Gereja Solograsia di Nabire tanggal 30 Mei 2008; (x)
Pembongkaran Gereja Anglikan Indonesia Cibureum di Cimahi tanggal 20 Juni 2008;
(xi) Penolakan sebagian warga atas pembangunan Gereja Barnabas di Pamulang
tanggal 13 Agustus 2008; (xii) Penghentian pembangun Gereja HKBP Cinere di
Depok tanggal 11 September 2008; dan (xiii) Permintaan penghentian kegiatan
Ibadah di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Koja di Jakarta Utara tanggal 12 September
9 Ahmad Asroni, “Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”, Religi Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 1 (2012). Ahmad Asroni, “Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”, Religi Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 1 (2012), hal. 63-86, http://digilib.uin-suka.ac.id/ id/eprint/9852, diunduh pada 3 April 2015, diunduh pada 3 April 2015.
10 Zainal Abidin Bagir dkk., 2008, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008,
CRCS UGM, Yogyakarta, hal. 17. 11
Martin Luther Manao, “HAM di Indonesia; Sebuah Tinjauan Terhadap Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Martin Luther Manao Blog, https://martinmanao.wordpress.com/ilmu-hukum/, diakses pada tanggal 27 Maret 2015.
2008. Sedangkan menurut catatan CRCS UGM terdapat 18 kasus konflik seputar
rumah ibadah.12
Sementara tahun 2009 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2010 terdapat 39 kasus.13
Dari 39 kasus konflik diseputar rumah ibadah yang terjadi pada tahun 2010, masalah
perizinan menempati menempati posisi teratas dalam konflik pendiriran rumah
ibadah, yakni sebanyak 24 kasus (62%).14 Dalam aspek horisontal, terjadinya konflik
pendirian rumah ibadah mayoritas dilatar belakangi oleh penolakan kelompok
pemeluk agama tertentu dengan dalih meresahkan masyarakat. Sedangkan vertikal,
pemerintah berargumen bahwa bangunan atau tempat rencana pembangunan tidak
sesuai peruntukan atau menyalahi konsep tata ruang yang telah dibuat.15
Tren melonjaknya jumlah konflik mengenai rumah ibadah di NKRI paska
reformasi mengkonfirmasi bahwa terbitnya PBM Nomor 9/8 Tahun 2006, tetap saja
tidak cukup efektif dalam mereduksi konflik kepentingan antarumat beragama yang
telah terjadi, terutama mengenai hal pendirian rumah ibadah yang mana dalam
ketentuan pasal menyangkut pendirian rumah ibadah dianggap sebagai tindak
diskriminasi melalui cara legalisme hukum oleh kelompok mayoritas terhadap
kelompok minoritas dan aktivis HAM.
PEMBAHASAN
A. Hak Asasi Manusia dalam Teori
Jack Donelly mengatakan, HAM adalah hak tiap orang tanpa memandang
siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi
hak.Keberadaan HAM tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial dimana kita
berada.16 Artinya hak alamiah yang melekat pada diri manusia tidak mengenal
pembatasan sebagai individu dalam satu-kesatuan mayoritas atau sebagai minoritas.
Menurut Rousseau dan Isaiah Berlin, kunci adanya kebebasan (tegaknya HAM; pen)
12
Ibid. 13
Ibid. 14
Ibid, hal. 36 15
Akhol Firdaus, dkk., 2011, Negara Menyangkal: Kodisi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Pustaka Setara, Jakarta, hal. 61.
16 Hamid Awaludin, 2012, HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, Penerbit buku
Kompas, Jakarta, hal.
itu ada pada persamaan (equality). Menurut John Locke, secara alamiah manusia
dikaruniai kebebasan yang sempurna yang dimiliki oleh setiap orang untuk berbuat
sesuai kehendaknya.17 Disamaping itu, ada 2 hal pokok dalam diri HAM, yaitu;
pertama, soal rectitude yang menekankan aspek standar perilaku tentang bagaimana
manusia menggunakan hak-haknya, artinya membicarakan standard of conduct. Dan
kedua, ialah entitlement, selain diri kita yang memiliki hak, ada orang lain juga yang
memiliki hak, penekanannya memfokuskan perhatian pada pemilik hak lain.18
Jika melihat bagaimana mengklaim Hak Asasi tersebut, maka ada dua cara
dalam bentuk pengekspresiannya; pertama, Hak asasi yang bersifat murni, yaitu hak
yang murni bersifat individual, seperti hak hidup, hak berpikir dan hak meyakini
suatu kepercayaan agama; kedua, hak asasi individual yang dengan semestinya
diekspresikan secara kolektif, contoh hak penentuan nasib sendiri dan hak
menjalankan ritual keagamaan.19
B. Dasar Konstitusional Kebebasan Beragama di Indonesia: HAM Dalam Hukum
Munisipal
Pemajuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah
sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang
berlangsung. Indikasinya adalah Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998, MPR telah
mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM
dengan mengesahkan ketetapan mengenai HAM yang memuat Piagam HAM Universal
1948, diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal yang
secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM.
Pemajuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah
sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang
berlangsung. Indikasinya adalah ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998, MPR telah
mengambil sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM
dengan mengesahkan ketetapan mengenai HAM yang memuat Piagam HAM Universal
17
Ibid, hal. 105. 18
Ibid, hal. 134. 19
Malcom N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, hal. 270.
1948, diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal yang
secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM.
Saat ini, Indonesia telah meratifikasi 4 dari 6 instrumen pokok HAM
intemasional, yaitu (i) Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, (ii)
Konvensi Hak Anak, (iii) Konvensi Menentang Penyiksaan, (iv) Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Indonesia telah pula menandatangani Protokol
Tambahan Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan.20 Disamping itu, Indonesia saat ini sedang dalam
proses meratifikasi Kovenan Intemasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan
Intemasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.21 Artinya segala hal yang
menyangkut HAM dalam dokumen Internasional telah menjadi hukum munisipal.
Diharapkan, dengan pengesahan instrument-instrumen internasional HAM akan
memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hokum pada tingkat nasional
sebagai upaya untuk menjaminpemajuan dan perlindungan HAM secara lebih baik.
Kebijakan pengesahan instrument tersebut juga akan menunjang kebijakan pembangunan
hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara
internasional.22
Dalam Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang Tergolong Minoritas Nasional dan
Etnis, Agama dan Budaya (Declaration on The Right of Persons Belonging to National
or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities) pada Desember 1992, Pasal 1-nya
menyatakan “negara harus melindungi eksistensi dan identitas nasional atau etnis,
budaya, agama dan bahasa minoritas didalam wilayah masing-masing dan harus
mengambil langkah legislatif dan lainnya yang sesuai untuk mencapai tujuan ini”.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk kaum minoritas
mempunyai hak untuk menjalankan budaya mereka sendiri, mempraktikkan dan
memeluk agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri secara pribadi
dan ditempat umum tanpa hambatan.23 Lebih lanjut, Pasal 7 (1) UU HAM No. 39/1999,
menyatakan, “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan
20 Lya Russady, “Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hubungan
Internasional Dan Indonesia”, Academia, http://www.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content& view=article&id=104:pemajuan-danperlindungan-hak-asasi-manusia-ham-di-indonesia&catid=40:artikel-, diakses pada 30 April 2015.
21 Ibid.
22 Bour Mana, op.cit., hal. 701.
23 Malcolm N. Shaw QC, op .cit, hal. 278-279.
forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima
negara Republik Indonesia.” Pasal 7 (2)-nya menyatakan, “Ketentuan hukum
Internasional telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi
manusia menjadi hukum nasional”, sedang ketentuan Pasal 1 (3) UU HAM No. 39/1999
menyatakan:
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Bisa disimpulkan/ditafsirkan, dalam dalam pembangunan hirarki hukum nasional, semua
Undang-Undang (Formelgestz), Aturan Pelaksana (Verordnung) dan Peraturan Otonom
(Autonom Satzung) harus memuat norma yang sesuai dengan dokumen-dokumen Hak
Asasi Internasional tanpa perlu ratifikasi.
Pendekatan teori hukum doktrinal yang dianut dalam pembangunan HAM di
Indonesia adalah doktrin inkorporasi (penyatuan,pemasukan) dimana instrumen hukum
internasional mengenai HAM secara otomatis merupakan hukum nasional sebagaimana
rumusan Pasal 7 (2) UU HAM No. 39/1999.24
C. Memahami Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
Jika meruntut sejarah, konflik antar umat beragama di Indonesia saat ini, secara
kuantitas didominasi Islam vis-à-vis Kristen, setidaknya ketegangan tersebut bisa dilacak
mulai pertengahan tahun 1960-an. Negara mewajibkan kepada warganya untuk memilih
agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha) sebagai bukti loyalitas anti
komunis–yang sering disederhanakan sebagai atheis–yang diprogramkan oleh
pemerintah.25 Agama-agama lokal diharuskan untuk bergabung dengan agama-agama
yang mirip dengan agama atau kepercayaan lokal itu.26 Kebijakan pemeritah ini membuat
24
Ibid, hal. 132. 25
Suhadi, 2006, Kawin Lintas Agama; Perspektif Nalar Islam, LKiS, Yogyakarta, hal. 132. 26
Bambang Budiono, “Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Web Dosen Fisip Unair, http://bambudfisip-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64137-makalah%20umum Kebebasan%20 Beragama.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2015.
kalangan abangan yang pendukung PKI memilih konversi ke Kristen daripada memilih
Islam karena beberapa faktor: pertama, trauma terhadap pembantaian yang dilakukan
oleh kader-kader Ormas keagamaan Islam.27 Kedua, dalam lingkup dinamika politik saat
itu, PKI termasuk kelompok yang berafiliasi dengan kelompok Nasionalis bersaing
kelompok partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara.28
Menyikapi konversi keyakinan kaum abangan ke kristen yang massif,29 faksi
kelompok Islam pun mulai menempuh jalur politik pemerintahan untuk membendung
penetrasi Kristenisasi yang semakin kuat. Pada 1 dan 15 Agustus 1978, Menteri Agama,
Alamsyah Ratuperwiranegara, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 70 Tahun 1978
tentang pedoman Penyiaran Agama dan SK No. 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Lalu, kedua SK tersebut diperkuat
oleh SK Bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaaan di
Indonesia.30
PBM No. 9/2006 dan PBM No. 8/2006 merupakan revisi atas SKB Dua Mentreri
No.1/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama
oleh Pemeluk-Pemeluknya. Terbitnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 merupakan respon
pemerintah terhadap konflik antar agama di era pembangunan demokrasi.
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 memuat 10 Bab yang terdiri dari 31 Pasal,
Subtansi dalam PBM tersebut berusaha memberi payung hukum terhadap lalu lintas para
warga negara Indonesia yang memeluk suatu agama ketika berinteraksi dengan WNI
lainnya dan memeluk agama yang berbeda, yang memiliki cara beribadat tidak sama, dan
mengatur secara legal terhadap tata cara pelaksanaan pendirian rumah ibadat dalam
27
Suhadi, op.cit., hal. 132 28
Amos Sukamto, “Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Permusuhan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik”, Jurnal Teologi Indonesia Vol. 1 No. 1 (2013), hal. 25-47, https://academia.edu/4113423/Ketegangan_Antar_Kelompok_Agama_Pada_ Masa_Orde_Lama_Sampai_Awal_Orde_Baru_Dari_Konflik_Permusuhan_Ideologi_Negara_Sampai_Konflik_Fisik, diakses 28 Maret 2015
29 Andree Feillard mencatat bahwa jumlah orang yang yang melakukan konversi agama pada tahun
1960 hingga 1970-an sekitar 1,5 juta jiwa. Sedang di kota-kota tertentu di Jawa Tengah meningkat hingga 10% sesudah tahun itu. Baca: Andree Feillard, Kaum Kristen dan Muslim di Indonesia dalam Kilas Sejarah: Penjelasan tentang Terjadinya Kekerasan Baru Antar Agama.
30 Lukman Hakim, 1991, Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia: Kumpulan Tulisan
Media Dakwah, Media Dakwah, Jakarta, hal. 8.
masyarakat dan bernegara. PBM ini menjelaskan secara terperinci ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan 3 hal:
a. Kerukunan umat beragama.
b. Pemberdayaan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) oleh Pemerintah
dan penunjukan wewenang tanggung jawab atas pemeliharaan kerukunan umat
beragama.
c. Prosedur tata cara pendirian rumah ibadat.
Lokus yang menjadi perdebatan pro-kontra di masyarakat adalah Bab IV yang
mana berisi ketentuan tentang prasyarat pendirian rumah ibadah. Kehadiran PBM No. 9
dan 8 Tahun 2006 sejatinya menyulitkan agama minoritas untuk mendirikan rumah
ibadah. Betapa tidak, bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan rekomendasi dari
masyarakat sekitar berupa 60 KTP sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 14 Ayat 2B.
Apalagi menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)-Lazuardi Biru pada 2010,
mayoritas Muslim di Indonesia intoleran terkait pendirian rumah ibadah. Sebanyak
64,9%.31 Sementara menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny
JA pada tahun yang sama, sebanyak 42,8% responden menyatakan kurang bisa menerima
keberadaan pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungannya.32 Ketentuan
diskriminatif dalam PBM No. 9/8 Tahun 2006 terlihat dalam beberapa hal sebagai
berikut:33
a. Politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan mencabut IMB.
Secara kasuistik, contoh dari politisasi pemerintah adalah kejadian yang menimpa
HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat oleh
Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail. Ironisnya, argumentasi yang mendasari
pencabutan adalah keberadaan Gereja HKBP Jati Gandul dianggap meresahkan
Masyarakat.
b. Keanggotaan FKUB didasarkan pada representasi pemeluk agama suatu daerah
(Pasal 10 Ayat 2). Artinya, semakin besar banyak pemeluk suatu agama yang
mendiami suatu daerah,semakin besar pula jumlah anggotanya. Meski dalam PBM
No. 98 Tahun 2006 mensyaratkan pengambilan keputusan melalui jalur musyawarah
mufakat (Pasal 10 (4)), namun dalam realitasnya sering kali melalui voting.
31
Ahmad Asroni, op. cit. 32
Ibid. 33
Ibid.
Ketentuan Pasal 13 Ayat representatif menimbulkan masalah bagi kelompok pemeluk
agama minoritas untuk memenuhi kebutuhan rumah ibadah sebagai tempat
mengekpresikan HAM secara kolektif yang dijamin UUD.
c. Persyaratan mendapat dukungan 60 penduduk sekitar (Pasal 14 Ayat 2B) berpotensi
diskriminatif. Apalagi menurut survei LSI di atas pemeluk agama di Indonesia kurang
nyaman terhadap adanya pembangunan rumah ibadah lain dilingkungannya.
D. Peran Negara dalam Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama bagi Kaum
Minoritas
Secara umum, definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum
dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu
negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan
ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari
mayoritas penduduk.34 Minoritas sebagai kelompok yang dilihat dari jumlahnya lebih
kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam
posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis,
agama,maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan
setidaknyasecara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya,
tradisi,agama dan bahasa.35
Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang
Tergolong Minoritas Nasional dan Etnis, Agama dan Budaya (the Declaration on The
Right of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities)
pada Desember 1992, yang mana Pasal 1-nya menyatakan bahwa “Negara harus
melindungi eksistensi dan identitas nasional atau etnis, budaya, agama dan bahasa
minoritas didalam wilayah masing-masing dan harus mengambil langkah legislatif dan
lainnya yang sesuai untuk mencapai tujuan ini.”
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk kaum
minoritas mempunyai hak untuk menjalankan budaya mereka sendiri, mempraktikkan
dan memeluk agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri secara
34
Rhudy LA Political Acience, “Kelompok Sesial Mayoritas dan Minoritas”, Academia.edu, https://academia.edu/3769057/Kelompok_Sesial_Mayoritas_dan_Minoritas, diakses pada 1 April 2015.
35 Ibid.
pribadi dan di tempat umum tanpa hambatan.36 Disisi lain, PBM Nomor 9 dan 8
Tahun 2006 tidak memberi definisi dengan jelas tentang yang dimaksud kategori
rumah ibadah, karena seperti kita ketahui bersama, dalam budaya keagamaan muslim
nusantara ada istilah Masjid dan Surau/Musolla/Langgar. Karena hemat penulis, jika
hal ini tak diatur dengan detail, maka akan terjadi kekosongan hukum dan akan
berujung pada polemik juga.
Tabel 1: Data Statistik Umat Beragama di Indonesia Pada Tahun 2010
36
Shaw QC, op. cit, hal. 278-279
Jika melihat tabel di atas, peraturan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 sangat sulit
untuk dipenuhi oleh kaum minoritas. Ketentuan tersebut tentu akan sulit dipenuhi
pemeluk Katholik di kabupaten Pasuruan yang berjumlah 6.950 orang (lihat tabel 1)
dengan luas wilayah 1.474 km2.37 Artinya, kepadatan kurang lebih 5 orang penganut
Katholik per km2. Kemungkinan maksimal Gereja Katholik dibangun adalah 116
buah untuk kaum penganut Katholik dengan estimasi jarak antar-Gereja 12,7 km.
Sedangkan kondisi riil jumlah Gereja Katholik hanya 1 buah, artinya, secara kasat
mata umat Katholik di Kabupaten Pasuruan tentu akan sulit untuk menjalankan
aktifitas ibadah kebaktiannya.
Gambaran kondisi statistik diatas tentu akan berbeda dengan pemeluk Katholik
di Kota Madiun yang berjumlah 11.62138 orang (lihat tabel 2) dengan jumlah gereja
Katholik 20 buah (lihat tabel 3), dengan luas wilayah 23,05 km2.39 Artinya, kepadatan
rata-rata per km2 didiami oleh 505 orang pemeluk Katholik, estimasi jarak antar-
Gereja adalah 1,2 km. Sedang jumlah gereja yang maksimal bisa didirikan menurut
aturan PBM adalah 193 buah. Sedangkan pada 2013, kondisi riil di Kota Madiun ada
20 buah Gereja Katholik. Peraturan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentu menyulitkan
kaum minoritas dalam memenuhi hak-hak keagamaanya yang mana rumah ibadah
adalah tempat mengekpresikan “identitas agama” dan merupakan hak asasi asasi non-
derogable yang mana dalam mengklaimnya seyogyanya dengan cara kolektif.
PENUTUP
A. Simpulan
Pada akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa PBM No. 9 dan 8
Tahun 2006, yang berisi ketentuan tentang tata cara pendirian rumah ibadah
merupakan bentuk diskriminasi negara/pemerintah terhadap kaum minoritas di
Republik Indonesia, sebagimana kita tahu bersama bahwa rumah ibadat merupakan
tempat berkumpul/berserikat dan merupakan bangunan tempat mengekspresikan
ajaran agama yang mana kebebasan sebagai hak dasar dijamin oleh:
37
Katalog BPS; 1102001.35, Jawa Timur Dalam Angka, 2010, hal. 176. 38
Wikipedia, “KabupatenPasuruan”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan, daikses pada 16 April 2015.
39 Wikipedia, “Kota Madiun”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun, diakse pada 16 April 2015.
a. Kovenan Internasional 1966 tentang Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya;
b. Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang Tergolong Minoritas Nasional dan Etnis,
Agama dan Budaya;
c. Pasal 28C (1) dan (2), Pasal 28D (1), Pasal 28E (1) dan (2), Pasal 28H (1), Pasal
28I (1) dan (2), dan Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945;
d. Pasal 2, 3 (2) dan (3), Pasal 5 (3) UU Nomor 39 tentang HAM.
B. Saran
Regulasi tentang umat beragama yang plural mutlak diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum yang adil agar konflik-konflik menyangkut rumah ibadah
dapat dicegah, seagaimana amanat Pasal 1 Deklarasi tentang Hak-hak Orang yang
Tergolong Minoritas Nasional dan Etnis, Agama dan Budaya, ketentuan Pasal 28D
(1) UUD 45 dan cita negara hukum yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alenia keempat: “mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap tumpah darah Indonesia.”
Regulasi tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar memiliki
kekuatan mengikat yang lebih kuat. Menurut Rumadi Ahmad, hal yang paling
penting diperhatikan dalam setiap penyusunan regulasi adalah memberi arah yang
tercermin dalam asas-asas RUU itu. Imbuhnya, “kegaduhan” mengenai regulasi
pendirian rumah ibadah dalam PBM No.9/8 Tahun 2006 ini disebabkan adanya ruang
toleransi yang dipersempit sehingga menimbulkan banyak menimbulkan persoalan
dilapangan. Jadi kesan yang timbul adalah nuansa mengatur kompetisi perekrutan
pemeluk agama daripada memperluas arena toleransi tersebut.40
DAFTAR PUSTAKA
Perundang-undangan:
The Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious
and Linguistic Minorities Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945
TAP MPR No.XVII/MPR/1998.
40
Rhudy LA Political Acience, op.cit.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9/8 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
Buku-buku:
Akhol Firdaus, dkk., 2011, Negara Menyangkal: Kodisi Beragama/Berkeyakinan di
Indonesia, Pustaka Setara, Jakarta.
Hamid Awaludin, 2012, HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional,
Penerbit buku Kompas, Jakarta.
Katalog BPS; 1102001.35, Jawa Timur Dalam Angka, 2010.
Lukman Hakim, 1991, Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia:
Kumpulan Tulisan Media Dakwah, Media Dakwah, Jakarta.
Malcom N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung.
Suhadi, 2006, Kawin Lintas Agama; Perspektif Nalar Islam, LKiS, Yogyakarta.
Zainal Abidin Bagir dkk., 2008, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di
Indonesia Tahun 2008, CRCS UGM, Yogyakarta.
Jurnal:
Ahmad Asroni, “Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006
dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”, Religi Jurnal
Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 1 (2012). Ahmad Asroni, “Menyegel ‘Rumah
Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik
Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”, Religi Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8
No. 1 (2012), hal. 63-86.
Amos Sukamto, “Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama
Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Permusuhan Ideologi Negara Sampai
Konflik Fisik”, Jurnal Teologi Indonesia Vol. 1 No. 1 (2013), hal. 25-47.
Sumber Informasi Media Berita:
Bambang Budiono, “Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia”, Web Dosen Fisip Unair, http://bambudfisip-fisip.web.unair.ac.
id/artikel_detail-64137-makalah%20umumKebebasan%20Beragama.html, di-
akses pada 28 Maret 2015.
Lya Russady, “Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks
Hubungan Internasional Dan Indonesia”, Academia, http://www.ipdn.ac.id/index.
php?option=com_content&view=article&id=104:pemajuan-danperlindungan-hak-
asasi-manusia-ham-di-indonesia&catid=40:artikel-, diakses pada 30 April 2015.
Martin Luther Manao, “HAM di Indonesia; Sebuah Tinjauan Terhadap Perlindungan
Kebebasan Beragama di Indonesia”, Martin Luther Manao Blog,
https://martinmanao.wordpress.com/ilmu-hukum/, diakses pada tanggal 27 Maret
2015.
Muchammad Safa’at Ali, “HAM Di Era Reformasi”, Academia.edu, https://www.
academia.edu/6376473/HAM_Di_Era_Reformasi, diunduh pada tanggal 27 Maret
2015.
Rhudy LA Political Acience, “Kelompok Sesial Mayoritas dan Minoritas”,
Academia.edu, https://www.academia.edu/3769057/Kelompok_Sesial_Mayoritas
_dan_Minoritas, diakses pada 1 April 2015.
Wikipedia, “Kota Madiun”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun, diakse pada
16 April 2015.
Wikipedia, “KabupatenPasuruan”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan,
daikses pada 16 April 2015.