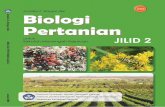Peta Sektor Pertanian
-
Upload
ubrawijaya -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Peta Sektor Pertanian
LAPORAN
PEMETAAN SEKTOR EKONOMI
(SEKTOR PERTANIAN)
Sebagai Bagian dari Pelaksanaan
Program Kerja Inisiatif 2005
PENINGKATAN PERAN BANK INDONESIA DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMETAAN SEKTOR
EKONOMI
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa patut kita panjatkan seiring dengan telah selesainya penyusunan Peta Sektor Ekonomi Pertanian Tahun 2005. Penyusunan Peta Sektor Ekonomi Pertanian merupakan salah satu upaya dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk dapat lebih memahami dengan baik kondisi, permasalahan dan prospek sektor pertanian pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Data dan informasi yang diperoleh dari laporan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya terutama yang terkait dengan upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan ini merupakan bagian dari program kerja Inisiatif Bank Indonesia yaitu melakukan pemetaan sektor ekonomi.
Penyusunan Peta Sektor Ekonomi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sbb:
1. Dewan Gubernur Bank Indonesia atas dukungannya dalam program kerja dimaksud.
2. Satuan kerja dan unit kerja internal Bank Indonesia sebagai anggota program kerja inisiatif yang salah satu kegiatannya adalah survei dimaksud.
3. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan peta sektor ekonomi.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan beberapa kelemahan dalam kualitas data dan informasi yang dihasilkan serta dalam interpretasinya. Oleh karena itu, untuk perbaikan kedepan kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca. Kegiatan penggalian data dan informasi sektor usaha semacam ini akan dilakukan secara kontinu oleh Bank Indonesia dalam berbagai bentuk kegiatan yang berbeda.
Akhirnya harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi Bank Indonesia, Pemerintah, Pelaku Usaha, Perbankan, Investor, Institusi Penelitian dan Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan peran sektor usaha riil dalam proses pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Jakarta, Desember 2006
Halim Alamsyah Direktur
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter – Bank Indonesia
DAFTAR ISI
Halaman
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
Output Sektor Pertanian
Sektor Pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
Sektor Pertanian di Beberapa Negara Lain
Komoditas Pertanian Food dan Non Food
Kegiatan Ekonomi menurut Struktur Rural – Urban
Komoditas Tradables dan Non-Tradables
Perkembangan Komoditas Tradables Pertanian
Ekspor Komoditas Pertanian Sebelum dan Sesudah Krisis
Perkembangan Ekspor Beberapa Komoditas Pertanian
Persaingan Ekspor Komoditas Pertanian
Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian
Produktivitas Pertanian
Luas Lahan dan Penggunaan Lahan Pertanian
Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi
Tenaga Kerja Menurut Gender
Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Pembiayaan Perbankan Terhadap Sektor Pertanian
Pembiayaan Formal Melalui Bank dan Non-Bank
Pembentukan Harga Output Sektor Pertanian
Output Pertanian Menurut Lokasi
Kebijakan Pemerintah Saat Ini
Komoditas Pertanian Unggulan
Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan
Profil Usaha Komoditas Pertanian
Profil Usaha Beberapa Komoditas Unggulan
1
1
6
8
10
11
14
14
17
20
21
23
23
24
25
27
29
29
32
34
36
38
38
41
43
DAFTAR TABEL
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
10.
Hasil Kajian Lanjutan Terhadap Komoditi Unggulan Sektor Pertanian
Gambaran Umum Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Peternakan
Komoditas Padi
Komoditas Jagung
Komoditas Jeruk dan Pisang
Komoditas Unggas (Ayam)
Komoditas Sapi
Komoditas Kambing-Domba
Permasalahan dalam Meningkatkan Kapasitas Produksi
Kebijakan Peningkatan Kapasitas Produksi
Gambaran Umum Subsektor Perkebunan
Peluang Peningkatan Kontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Daya
Saing di Pasar Internasional
Permasalahan dalam Peningkatan Produksi Subsektor Perkebunan
Komoditas Kelapa Sawit
Komoditas Karet
Komoditas Kakao
Komoditas Tebu
Gambaran Umum Subsektor Perikanan dan Komoditas Unggulannya
Komoditas Tuna
Komoditas Udang
Komoditas Rumput Laut
Penutup
Lampiran
Matriks Permasalahan Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Peternakan
Matriks Permasalahan Subsektor Perkebunan
Matriks Permasalahan Subsektor Perikanan
Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Tabama dan
Peternakan
Lima (5) Besar Daerah Produsen Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan
Sentra Produksi Subsektor Perikanan
45
45
45
48
49
52
52
53
54
56
58
60
62
63
66
69
71
73
75
77
79
81
Halaman
Tabel 1.
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.
Tabel 13.
Tabel 14.
Tabel 15.
Tabel 16.
Tabel 17.
Tabel 18.
Tabel 19.
Tabel 20.
Tabel 21.
Tabel 22.
Tabel 23.
Tabel 24.
Tabel 25.
Tabel 26.
Tabel 27.
Tabel 28.
Tabel 29.
Tabel 30.
Tabel 31.
Tabel 32.
Tabel 33.
Tabel 34.
Tabel 35.
PDB Menurut Sektor Ekonomi (Harga Berlaku)
Pangsa Sub Sektor Pertanian
PDB Menurut Sektor Ekonomi (Harga Konstan)
Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian
Pangsa Food dan Non Food
Pangsa PDB Menurut Daerah Rural dan Urban
Pangsa dan Peringkat Dunia Komoditas Pertanian Unggulan
Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian
Penggunaan Lahan Pertanian Antar Negara
Perkembangan Tenaga Kerja menurut Sektor Ekonomi
Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi
Perbandingan Produktivitas Sektor Pertanian Antar Negara
Kebutuhan Investasi Komoditas Pertanian Unggulan
Kebijakan Pemerintah 1970-2005
Komoditas Pertanian Tradables Ekspor Unggulan
Signifikansi Komoditas Pertanian Unggulan Terhadap Total Output Pertanian
Matriks Komoditas Pertanian Unggulan
Profil Usaha Beberapa Komoditas Pertanian Unggulan
Kondisi Jaringan Irigasi, 2006
Proyeksi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Proyeksi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung
Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Jeruk dan Pisang
Kinerja Komoditas Jeruk dan Pisang
Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Ayam Ras Pedaging
Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Daging Sapi
Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Daging Kambing/Domba
Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan, 1996–2005
Perkembangan Konsumsi CPO Indonesia Tahun 1996–2005
Luas Areal dan Produksi Karet 1999 – 2004
Produksi dan Konsumsi Karet Indonesia, 2000 – 2005
Perkembangan Produksi Perkebunan Kakao Indonesia
Luas Areal Tebu dan Produksi Gula Berdasarkan Propinsi
Proyeksi Produksi Tuna, Cakalang dan Tongkol, Tahun 2005-2009
Proyeksi Luas Areal dan Produksi Udang Budidaya dan Penangkapan
Proyeksi Produksi Rumput Laut, Tahun 2005-2009
1
2
3
4
8
11
20
21
24
25
27
28
30
36
38
40
41
44
46
47
49
50
51
52
53
54
64
65
67
68
70
73
77
78
80
DAFTAR GRAFIK
HalamanGrafik 1.
Grafik 2.
Grafik 3.
Grafik 4.
Grafik 5.
Grafik 6.
Grafik 7.
Grafik 8.
Grafik 9.
Grafik 10.
Grafik 11.
Grafik 12.
Grafik 13.
Grafik 14.
Grafik 15.
Grafik 16.
Grafik 17.
Grafik 18.
Grafik 19.
Grafik 20.
Grafik 21.
Grafik 22.
Grafik 23.
Grafik 24.
Grafik 25.
Grafik 26.
Grafik 27.
Grafik 28.
Grafik 29.
Grafik 30.
Grafik 31.
Grafik 32.
Grafik 33.
Grafik 34.
Grafik 35.
Grafik 36.
Grafik 37.
Pangsa Sektor Ekonomi dalam PDB
Pertumbuhan Rata-rata PDB
Kontribusi Pertumbuhan PDB
Kontribusi Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian
Pangsa PDB Sektoral di Beberapa Negara Asia
Peran PDB Sektoral di Beberapa Negara Non-Asia
Perkembangan Peran Sektor Pertanian di Beberapa Negara
Indeks Pertanian Beberapa Negara
Indeks Komoditas Food, Non-Food dan Tenaga Kerja
Perkembangan Food dan Non-Food di Beberapa Negara Asia
Struktur Demografi menurut Rural-Urban
Pangsa Tradables dan Non-tradables
Komoditas Non-Tradables menurut Sektor Ekonomi
Komoditas Tradables menurut Sub Sektor
Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 2000- 2005
Nilai Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 2000- 2005
Trade Balance Komoditas Food dan Non-Food
Pangsa dan Pertumbuhan Ekspor Komoditas Pertanian
Terhadap Total Ekspor Non-Migas
Negara Pengekspor Komoditas Pertanian Terbesar
Perkembangan Ekspor Komoditas Karet
Perkembangan Ekspor Komoditas CPO
Perkembangan Ekspor Komoditas Tekstil
Perkembangan Ekspor Komoditas Kayu dan Produk Kayu
Perkembangan Ekspor Komoditas Ikan Laut
Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian di Beberapa Negara Periode 1991-2003
Perkembangan Luas Lahan Pertanian
Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian menurut Gender
Perkembangan Indeks Tenaga Kerja Pertanian
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (1994-2003)
Perkembangan Kredit Perbankan Sektor Pertanian
Perkembangan Bobot Inflasi Komoditas Pertanian
Pangsa Komoditas Pertanian dan Inflasi
Pangsa Terbesar Sektor Pertanian menurut Propinsi
Location Quotient Sektor Pertanian
Sebaran Komoditas Pertanian Menurut Rasio Backward dan Forward Linkage
Proses Produksi Usaha Pertanian
Pembiayaan Modal Kerja Usaha Pertanian
2
3
5
5
6
7
7
8
9
10
10
12
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
20
22
23
25
26
27
29
32
33
34
34
39
42
43
PENDAHULUAN
ndonesia dengan total luas lahan 181 juta hektar (86 persen merupakan lahan pertanian)
dan luas lautan diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 sangat potensial untuk
mengembangkan sektor pertanian, bahkan menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar
pembangunan ekonomi di masa mendatang. Selain mengembangkan komoditas unggulan
untuk tujuan ekspor, output pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik
(domestic demand) dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa.
Berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) periode 2000-2005, sektor pertanian memiliki
pangsa sebesar 14,9 persen. Pangsa pertanian tersebut menyusut secara gradual dari waktu
ke waktu sejak periode 1961-1965 yang pangsanya mencapai 57,8 persen. Fenomena ini
tidak hanya terjadi di negara-negara Asean tetapi juga di negara-negara maju seperti USA
dan Jepang, dimana sektor-sektor lain dalam perekonomian tumbuh lebih tinggi terutama
sektor industri (proses industrialisasi).
Menurut klasifikasi yang digunakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), tidak
terjadi perubahan komposisi antara kelompok makanan (food) dan bukan makanan (non-
food) dari total output sektor pertanian dalam kurun waktu lebih dari empat dasawarsa.
Namun dalam kelompok food, terjadi penurunan output tanaman bahan makanan,
sementara peternakan dan perikanan semakin meningkat. Produktivitas pertanian juga
terlihat meningkat antara lain disebabkan adanya mekanisasi pertanian, sehingga
pertumbuhan produksi pertanian sejak 1985 lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut.
Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar (rata-
rata 44,2 persen), sebagaimana terjadi pula di negara-negara lain seperti Vietnam (67,9
persen), Thailand (57,6 persen) dan Philippina (40,5 persen). Hal inilah yang menyebabkan
produktivitas tenaga kerja pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya,
meskipun terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan beberapa negara lain,
produktivitas pertanian Indonesia juga termasuk rendah, jauh di bawah Philippina dan
Malaysia meski relatif sama dengan Thailand.
Secara demografis, terdapat indikasi adanya modernisasi wilayah ekonomi yang antara lain
ditunjukkan dengan peningkatan jumlah desa perkotaan (urban area), yang diikuti dengan
pergeseran tenaga kerja dari perdesaan (rural area) ke perkotaan. Output komoditas
pertanian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana Jawa Timur menempati urutan
tertinggi (21,0 persen), Jawa Barat pada urutan kedua (13,6 persen), disusul Jawa Tengah
I
(11,9 persen), sementara urutan keempat dan kelima masing-masing adalah Sumatera Utara
dan Riau.
Berdasarkan pengelompokan komoditas tradables dan non-tradables (yaitu komoditas yang
memilki komponen ekspor dan impor), diketahui 39,5 persen output perekonomian
merupakan komoditas tradables dan sisanya non-tradables. Untuk komoditas pertanian
(baik primer maupun olahan), sebesar 47,6 persen merupakan komoditas tradables,
sementara sisanya adalah non-tradables.
Dari sisi perdagangan, volume ekspor komoditas pertanian primer dan olahan mengalami
peningkatan yang diikuti dengan kenaikan volume impor yang lebih tinggi, sehingga
menyebabkan transaksi perdagangan menjadi negatif (deficit trade balance). Namun apabila
dilihat dari nilainya, transaksi perdagangan komoditas pertanian masih mengalami surplus.
Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-20 negara pengekspor terbesar komoditas
pertanian, namun masih di bawah Thailand dan Malaysia.
Volume ekspor karet terus mengalami pertumbuhan, meski sedikit turun pada saat krisis.
Indonesia merupakan negara terbesar ke-2 pengekspor komoditas karet. Demikian juga
untuk komoditas CPO, Indonesia juga menempati urutan ke-2 dalam pangsa ekspor dunia.
Meski tekstil merupakan salah satu komoditas unggulan, namun ekspornya masih terlalu
besar dan hanya berada pada urutan ke-45 pangsa ekspor dunia. Sementara itu, ekspor
kayu Indonesia yang saat ini menempati urutan ke-7 mengalami penurunan ekspor sejak
2001. Ikan laut (baik ikan segar maupun awetan) merupakan salah satu komoditas
unggulan yang sangat prospektif. Ekspor ikan Indonesia berada di urutan ke-10 pangsa
ekspor dunia, namun masih di bawah Thailand dan Vietnam.
Banyak faktor menjadi penyebab belum optimalnya pengembangan sektor pertanian (baik
primer maupun olahan) di Indonesia, salah satunya adalah faktor pembiayaan yang masih
lemah terutama pembiayaan formal melalui perbankan. Dari total kredit bank, hanya sekitar
6 persen yang disalurkan pada sektor pertanian. Untuk pengembangan pertanian ke depan,
diperlukan alternatif pembiayaan selain perbankan, misalnya pengembangan lembaga
pooling fund dengan melibatkan institusi swasta dan dukungan dari pemerintah.
Kebijakan pemerintah dalam kurun waktu lebih dari 3 dasawarsa (1970 s.d. 2005) dapat
dikelompokkan menjadi 3 aspek kebijakan, yaitu: kebijakan sumber daya lahan, kebijakan
infrastruktur, dan kebijakan insentif. Dalam periode tersebut, perkembangan pertanian
mengalami 3 fase pertumbuhan, yaitu: fase accelerating (1970an s.d. 1985), fase
decelerating (1985 s.d. 2000), dan fase rebounding (2001 s.d. 2005). Pada fase
accelerating, sektor pertanian memperoleh perhatian yang sangat besar dari pemerintah,
dimana pembangunan infrastruktur dan pembiayaan institusional melalui kredit-kredit
program menjadi suatu kebijakan yang menonjol pada masa itu (green revolution). Namun,
masa keemasan sektor pertanian tidak mampu bertahan lama, seiring dengan peran
pemerintah yang semakin menurun. Deregulasi perbankan pada periode 1980an tidak
mampu menyentuh sektor pertanian, sehingga pembiayaan dari perbankan tidak berpihak
kepada sektor tersebut.
Pada periode 2001 s.d. 2005, perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mulai terlihat
dengan dikeluarkannya kebijakan pokok pembangunan sistem usaha agribisnis dan
peningkatan ketahanan pangan. Meski demikian, banyak kendala yang dihadapi
pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian, terutama disebabkan oleh luas lahan
pertanian yang makin sempit, pendapatan tenaga kerja sektor pertanian rendah, dan
masalah ketersediaan bahan pangan.
Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam pengembangan komoditas unggulan, Bank
Indonesia telah melakukan studi awal mengenai hal tersebut, baik yang dilakukan melalui
pengolahan data sekunder, diskusi dengan intansi/institusi terkait, maupun dari hasil Survei
Pemetaan Sektor Ekonomi (SPSE). Penentukan komoditas unggulan sektor pertanian
dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu: 1) Pendekatan kontribusi ekspor dan linkages, 2)
Pendekatan output, konsumsi, produksi, dan/atau struktur input, serta 3) Pendekatan
kebijakan pemerintah. Dengan ketiga pendekatan diatas, komoditas pertanian
dikelompokkan sebagai komoditas unggulan apabila setidaknya memenuhi 2 pendekatan.
Dengan kriteria tersebut, diperoleh 12 komoditas pertanian yang merupakan komoditas
unggulan, yaitu padi/beras, jagung, karet, kelapa sawit, kelapa, pisang, jeruk, hasil kayu,
sapi, unggas, kambing/domba, dan ikan/udang. Ke-12 komoditas pertanian unggulan
merupakan penggerak utama sektor pertanian dengan sumbangan lebih dari 80 persen
terhadap output sektor pertanian primer dan merupakan komoditas input yang dominan
terhadap sektor pertanian olahan (agro-industri).
Dari hasil SPSE yang dilakukan tahun 2005, diperoleh gambaran awal mengenai profil usaha
komoditas pertanian yang mencakup struktur biaya produksi, sumber bahan baku, orientasi
penjualan, dan masalah pembiayaan. Ditinjau dari sifat proses produksinya, usaha
komoditas pertanian lebih banyak yang bersifat independen (69%) dibandingkan atas dasar
pesanan (31%). Sementara dari proses produksinya, 47 persen unit usaha pertanian
melakukan usahanya dengan mengolah bahan mentah sampai barang setengah jadi, dan 46
persen mengolah bahan mentah sampai barang jadi.
Dari sisi bahan baku, sebagian besar unit usaha pertanian melakukan proses produksi
dengan bahan baku domestik. Hal ini juga terlihat dalam struktur biaya produksinya dimana
65 persen dari total biaya adalah biaya bahan baku, sementara biaya tenaga kerja 11 persen,
biaya bahan penolong 9 persen, dan biaya bunga 4 persen.
Sumber dana untuk pembiayaan modal kerja secara umum berasal dari dana non-perbankan
yaitu 64 persen, sementara perbankan hanya memberikan kontribusi sebesar 36 persen
dalam pembiayaan modal kerja usaha pertanian. Secara lebih rinci, pembiayaan modal kerja
perusahaan terutama berasal dari dana iternal (termasuk dari retained earnings) mencapai
50,3 persen, dari bank domestik sebesar 31,4 persen, dan dari individu pemilik/partner usaha
sebesar 6,9 persen.
Berdasarkan hasil penentuan komoditas unggulan sektor pertanian, terdapat 12 komoditas
yang merupakan komoditas unggulan dalam sektor pertanian, baik pertanian primer
maupun agro-industri. Sementara berdasarkan hasil kongres ISEI 2006, telah ditetapkan 10
komoditas unggulan termasuk didalamnya 5 komoditas unggulan pertanian (kelapa sawit,
kopi, karet, kakao, serta ikan dan udang).
Kajian lanjutan dilakukan terhadap komoditas unggulan hasil kajian sebelumnya, termasuk
beberapa komoditas unggulan pertanian hasil kongres ISEI dan dengan komoditas pertanian
yang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penghitungan inflasi. Komoditas yang
dipilih untuk kajian lanjutan adalah padi, jagung, jeruk, pisang, unggas (ayam), sapi,
kambing-domba, kelapa sawit, karet, kakao, tebu, ikan tuna, udang, dan rumput laut.
Dari hasil kajian lanjutan terhadap komoditas unggulan pertanian diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa meskipun sektor pertanian memegang peranan yang penting dalam
bidang sosial-ekonomi, namun pembangunan sektor pertanian masih menghadapi beberapa
kendala / permasalahan. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian
adalah kurang tersedianya pembiayaan jangka panjang (investasi) dalam rangka penyediaan
dan perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, dan penguatan kegiatan penelitian dan
pengembangan di sektor pertanian. Namun demikian, apabila dilihat berdasarkan sub
sektor, perbedaan karakteristik subsektor pertanian / komoditi yang ada dalam sektor ini
menyebabkan permasalahan yang dihadapi masing-masing subsektor / komoditi berbeda-
beda. Sehingga permasalahan pada sektor pertanian lebih tepat dilihat pada masing-masing
subsektor / per komoditi.
Hasil kajian peta sektor pertanian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pemerintah, BI,
perbankan (kreditor) dan investor dalam mengambil keputusan untuk mengatasi
permasalahan di sektor pertanian.
PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI SEKTOR PERTANIAN
1. Output Sektor Pertanian
1.1. Sektor Pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB)
� Dalam kurun waktu hampir 4 (empat) dekade (Tabel 1 dan Grafik 1), sejak 1960
sampai dengan masa sebelum krisis ekonomi, pangsa sektor pertanian selalu
menempati urutan teratas dalam PDB namun dengan kecenderungan menurun.
Tabel 1. PDB Menurut Sektor Ekonomi (Harga Berlaku)
(Miliar Rp)
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
1 Pertanian 4,149.7 921.9 2,738.7 7,541.9 17,891.5 33,915.5 59,677.0 159,029.3 313,020.1Rata-rata pangsa (%) 55.8 50.9 37.6 29.9 25.9 27.3 20.0 17.2 14.9
2 Pertambangan dan Penggalian 254.9 83.4 1,265.0 5,810.2 14,397.3 18,774.6 33,301.8 99,919.2 198,360.4Rata-rata pangsa (%) 3.6 3.7 13.8 21.3 21.3 14.9 11.6 10.4 9.3
3 Industri Pengolahan 541.6 165.9 687.3 1,725.6 2,693.9 5,102.3 57,942.3 242,994.5 611,457.1Rata-rata pangsa (%) 8.0 8.6 9.1 7.5 3.7 4.1 15.7 26.2 29.0
4 Perdagangan, Hotel dan Restoran 151.3 295.0 1,324.1 4,025.4 11,799.5 24,880.9 54,896.3 146,749.3 343,341.7Rata-rata pangsa (%) 2.4 11.4 17.7 15.8 17.0 19.9 18.0 15.9 16.2
5 Lainnya 414.8 79.5 334.9 1,319.0 4,464.2 8,428.4 21,511.1 54,482.2 130,234.4Rata-rata pangsa (%) 6.0 5.1 4.3 5.1 6.4 6.8 7.0 6.0 6.1
Produk Domestik Bruto 7,171.5 1,863.7 7,689.8 25,698.1 69,103.1 124,815.4 313,372.7 921,103.5 2,117,351.4
Sektor Ekonomi
Sumber : BPS (Diolah)
� Pada periode 1996-2000, pangsa sektor pertanian turun menjadi urutan kedua
sementara pangsa terbesar dalam PDB adalah sektor industri pengolahan, sejalan
dengan proses industrialisasi. Dengan berkembangnya sektor industri tersebut, sektor
perdagangan, hotel dan restoran juga semakin tumbuh sehingga pangsa sektor
pertanian semakin turun menjadi urutan ketiga pada periode 2001-2005, sementara
pangsa terbesar kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Grafik 1. Pangsa Sektor Ekonomi dalam PDB
Sumber : BPS (Diolah)
� Pada periode 2001-2005, subsektor yang memiliki pangsa terbesar dalam sektor
pertanian adalah subsektor tanaman bahan makanan (51,1 persen), sementara
subsektor yang memiliki pangsa terkecil adalah subsektor kehutanan (6,2 persen).
Tabel 2. Pangsa Sub Sektor Pertanian
(Dalam %)
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
1 Tanaman bahan makanan 64.8 63.9 59.7 59.1 60.9 61.3 55.6 52.7 51.12 Tanaman perkebunan 17.4 17.1 16.9 17.7 15.9 16.5 16.4 16.6 15.13 Peternakan dan hasil-hasilnya 6.7 6.0 7.0 7.1 10.5 10.3 11.0 10.8 12.64 Kehutanan 3.1 3.4 10.7 10.2 5.8 4.2 7.9 8.0 6.25 Perikanan 8.0 9.5 5.6 5.9 7.0 7.7 9.2 11.9 15.1
Sektor Pertanian 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sub Sektor Pertanian
Sumber : BPS (Diolah)
Tabel 3. PDB Menurut Sektor Ekonomi (Harga Konstan)
(Miliar Rp, Pertumbuhan dalam %)
1 Pertanian 71,148.3 81,373.6 97,355.7 114,296.4 140,103.8 165,853.1 191,775.6 211,627.8 241,815.9Rata-rata pertumbuhan tahunan 1.4 3.8 3.1 4.0 4.1 3.0 2.9 1.4 3.3
2 Pertambangan dan Penggalian 30,019.5 45,048.9 88,885.4 121,456.5 115,723.9 116,039.0 140,114.2 163,408.4 165,980.1Rata-rata pertumbuhan tahunan 2.2 15.8 9.6 4.8 -2.1 2.6 4.6 1.9 -0.6
3 Industri Pengolahan 17,493.0 20,739.2 32,496.7 58,483.6 100,160.4 167,291.6 276,522.2 374,080.5 444,056.9Rata-rata pertumbuhan tahunan 1.9 7.7 10.1 15.1 9.4 10.7 10.5 3.1 5.0
4 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,270.4 16,651.8 48,096.3 68,474.9 97,592.6 135,701.1 196,003.1 230,977.8 259,911.0
Rata-rata pertumbuhan tahunan 0.8 95.3 9.8 7.5 5.6 8.4 7.4 0.3 5.6
5 Lainnya 37,738.5 45,983.1 71,865.0 124,011.2 185,499.3 246,865.7 364,810.0 420,390.0 475,994.9Rata-rata pertumbuhan tahunan 3.8 24.2 13.3 12.5 6.9 8.8 9.6 1.2 7.0
Produk Domestik Bruto 161,676.1 209,919.2 338,731.5 486,754.0 639,097.0 831,775.2 1,169,250.6 1,400,491.1 1,587,772.0Rata-rata pertumbuhan tahunan 1.9 10.0 7.9 7.7 4.4 6.5 7.3 0.9 4.7
Sumber : BPS (Diolah)
� Selama kurun waktu 40 tahun, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami
pertumbuhan positif, namun pertumbuhan sektor pertanian relatif lebih lambat
dibandingkan dengan sektor-sektor lain seperti sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa.
Grafik 2. Pertumbuhan Rata-rata PDB
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
%
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel dan Restoran Lainnya Produk Domestik Bruto
Sumber: BPS (diolah)
� Secara rata-rata, pertumbuhan sektor pertanian setelah krisis (2001-2005) yaitu
sebesar 3,3 persen cenderung lebih baik dibandingkan periode sebelum krisis (1990-
1997) yaitu 2,6 persen.
� Ditinjau dari kontribusi terhadap pertumbuhan PDB, sektor pertanian senantiasa
memberikan kontribusi positif kecuali pada tahun 1998 yang kontribusinya tercatat –
0,2 persen.
Tabel 4. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian
(Dalam %)
Sumber: BPS (Diolah)
� Berdasarkan perkembangan subsektor, hampir seluruh subsektor pertanian
mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada sub
sektor peternakan dan perikanan.
� Secara rata-rata, pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan setelah krisis
(2001-2005) sebesar 2,5 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelum
masa krisis (1990-1997) yaitu 1,1 persen. Sebaliknya, sub sektor kehutanan
mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam pada masa setelah krisis yaitu -0,2
persen dibandingkan dengan masa sebelum krisis sebesar 2,1 persen.
Grafik 3. Kontribusi Pertumbuhan PDB
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan
4 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5 Lainnya 5 Produk Domestik Bruto
Pertumbuhan PDB - Skala kanan
%%
Sumber: BPS (diolah)
� Berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB, sektor pertambangan dan
penggalian mengalami penurunan sementara sektor industri pengolahan cenderung
meningkat. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang relatif stabil terhadap
pertumbuhan PDB.
Grafik 4. Kontribusi Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
%
1 Tanaman bahan makanan 2 Tanaman perkebunan 3 Peternakan dan hasil-hasilnya 4 Kehutanan5 Perikanan 5 PDB Sektor Pertanian
Sumber : BPS (Diolah)
� Secara subsektor, kontribusi pertumbuhan sektor pertanian sampai dengan saat ini
disumbang oleh sub sektor tanaman bahan makanan, diikuti oleh sub sektor tanaman
perkebunan dan peternakan.
1.2. Sektor Pertanian di Beberapa Negara Lain
Grafik 5. Pangsa PDB Sektoral di Beberapa Negara Asia
0
20
40
60
80
100
91-93
94-96
97-99
00-03
Gov't & Banks
Fin, Insc, R-Estate & Business
Transport, Storage & Commun'c
Whole's & Retail, Rest's & Hotel
Construction
Electricity, Gas & Water
Manufacturing (Mfg)
Mining & Quarrying
Agriculture
% Malaysia
0
20
40
60
80
100
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-00
01-03
Service
Industry &Construction
Agriculture, Forestry& Fishery
% Vietnam
0
20
40
60
80
100
71-75
81-85
91-95
01-03
Others
Services
Public Adm & Defence
Sales Trade
Transport & Commn'c
Construction
Manufacturing
Mining and Quarrying
Agriculture
% Thailand
0
20
40
60
80
100
81-85
86-90
91-95
96-00
01-03
Finance & Other Services
Government Services
Trade
Transport, Storage & Commn'c
Electricity, Gas & Water
Construction
Manufacturing
Mining & Quarrying
Agri'c, Fishery, Forestry
% Philipina
Sumber : CEIC
� Penurunan pangsa sektor pertanian dalam perekonomian nasional terjadi pula di
beberapa negara lain meskipun dengan besaran yang berbeda-beda. Hal ini sejalan
dengan fenomena industrialisasi.
� Di negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam, terlihat bahwa
penurunan pangsa sektor pertanian diiringi dengan peningkatan pangsa sektor industri
pengolahan.
� Sementara untuk negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, pangsa sektor
pertanian yang menurun diimbangi dengan peningkatan pada sektor jasa perusahaan,
sementara di Meksiko sektor jasa publik meningkat secara pesat.
Grafik 6. Peran PDB Sektoral di Beberapa Negara Non-Asia
0
20
40
60
80
100
61-65
71-75
81-85
91-95
Government
Services
Finance, Ins'c & R-Estate
Retail Trade
Wholesale Trade
Transport & Public Utilities
Manufacturing
Construction
Mining
Agri, Forestry & Fishing
% Amerika S ik t
0
20
40
60
80
100
80-85
86-90
91-95
96-00
01-03
Taxes & Imp Bank Services
Public & Personal Service
Finance, Insc & R-Estate
Transport, Storage & Commn'c
Commerce, Rest's & Hotels
Construction
Manufacturing
Mining
Agri, Cattle, Forestry & Fishing
% Meksiko
0
20
40
60
80
100
81-85
86-90
91-95
96-00
01-02
Gov't & others
ServicesTransport & Commn'c
Real EstateFinance and Insurance
Whole's & Retail TradeElectricity, Gas & Water
ConstructionManufacturing
MiningAgri, Forestry and Fishing
% Japan Grafik 7. Perkembangan Peran Sektor Pertanian di beberapa Negara
0
10
20
30
40
50
80-85 86-90 91-95 96-00 01-03
Vietnam Indonesia Thailand MalaysiaMeksiko USA Japan
%
Sumber : CEIC
� Dengan demikian, kecenderungan penurunan pangsa sektor pertanian dalam PDB yang
terjadi di berbagai negara terutama disebabkan oleh akselerasi pertumbuhan sektor-
sektor non-pertanian yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Meskipun
ke-7 negara tersebut bervariasi dalam skala ekonomi, namun mengalami fenomena
pergeseran sektoral yang relatif sama.
Grafik 8. Indeks Pertanian Beberapa Negara
0
20
40
60
80
100
120
140
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Australia Indonesia JapanMalaysia Mexico PhilippinesThailand United States of America Viet Nam
Sumber: Agriculture Statistics, FAO
� Perkembangan Indeks Pertanian antar negara menggambarkan perkembangan produksi
pertanian di berbagai negara mengalami pertumbuhan positif, kecuali Jepang yang relatif
stabil selama 30 tahun terakhir.
1.3. Komoditas Pertanian Food dan Non-Food
Tabel 5. Pangsa Food dan Non Food
(Dalam %)
1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05
1 Food 79.5 79.5 72.4 72.1 78.4 79.3 75.8 75.4 78.8
2 Non Food 20.5 20.5 27.6 27.9 21.6 20.7 24.2 24.6 21.2
Sektor Pertanian 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sub Sektor Pertanian
Sumber: BPS(diolah berdasarkan konsep FAO)
� Pengelompokkan Food dan Non Food dilakukan sesuai dengan penggolongan yang
dilakukan oleh FAO. Kelompok Food terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan,
sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan sub sektor perikanan. Kelompok Non Food
terdiri dari sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan.
� Dengan mengelompokkan sektor pertanian kedalam 2 (dua) kelompok yaitu: Food dan
Non Food, terlihat bahwa pangsa Food cenderung tidak mengalami perubahan yang
berarti, yaitu rata-rata 77 persen.
� Hal yang menarik untuk dicermati dalam kelompok food dimana pangsa sub sektor
tanaman bahan makanan cenderung turun, sementara peranan sub sektor peternakan
dan hasil-hasilnya, dan sub sektor perikanan semakin meningkat. Kondisi ini
mencerminkan adanya pergeseran variasi makanan yang dikonsumsi masyarakat dimana
makanan hasil peternakan dan perikanan semakin banyak dikonsumsi.
Grafik 9. Indeks Komoditas Food, Non-Food dan Tenaga Kerja
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003
Indeks Food Indeks Non FoodIndeks Populasi Indeks TK-Pertanian
Sumber: BPS(diolah berdasarkan konsep FAO)
� Berbeda dengan kondisi pada periode 1960-1985, dalam 15 tahun terakhir komoditas
pertanian mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada jumlah orang yang bekerja
pada sektor tersebut. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas
tenaga kerja pada sektor tersebut yang antara lain disebabkan adanya mekanisasi
pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisasi pertanian berdampak pada
pertumbuhan komoditas Food yang lebih tinggi dibandingkan komoditas Non-Food.
Grafik 10. Perkembangan Food dan Non-Food di Beberapa Negara Asia
0
50
100
150
200
250
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003
Indeks Food Indeks Non FoodIndeks Populasi Indeks TK-Pertanian
Thailand%
0
50
100
150
200
250
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003
Indeks Food Indeks Non FoodIndeks Populasi Indeks TK-Pertanian
Malaysia%
Sumber: FAO, diolah
� Mekanisasi pertanian terjadi pula di Malaysia dan Thailand, bahkan dampaknya lebih
menonjol dibandingkan Indonesia. Serupa fenomena di Indonesia, komoditas Food di
Malaysia tumbuh lebih tinggi dibandingkan komoditas Non-Food, sementara di Thailand
terjadi sebaliknya dimana komoditas Non-Food tumbuh lebih tinggi.
1.4. Kegiatan Ekonomi menurut Struktur Rural-Urban
Grafik 11. Struktur Demografi menurut Rural-Urban
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1970 1980 1990 2000 2003
Desa Rural Desa Urban Penduduk Rural
Penduduk Urban TK Rural TK Urban
Sumber: BPS(diolah berdasarkan konsep FAO)
� Berdasarkan struktur demografi rural-urban, terlihat adanya modernisasi wilayah
ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah desa perkotaan (urban area),
yang diikuti dengan pergeseran aktivitas ekonomi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari
meningkatnya jumlah tenaga kerja di wilayah urban.
� Walaupun demikian, kawasan rural memegang peranan penting khususnya melalui
sektor pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan sumber devisa melalui
kegiatan ekspor.
Tabel 6. Pangsa PDB Menurut Daerah Rural dan Urban
(Dalam %)
Pertanian Industri Jasa Total Pertanian Industri Jasa Total
1984 1.53 17.94 35.57 55.03 18.56 10.5 14.22 43.281987 1.32 17.9 33.75 52.7 18.3 11.36 16.24 45.91990 1.29 18.55 30.36 50.2 17.37 11.56 20.19 49.121993 2.08 21.52 37.97 61.57 15.26 9.51 13.67 38.441996 1.79 21.87 37.39 61.05 13.77 10.3 14.89 38.961999 2.12 21.4 35.76 59.28 15.02 11.06 14.65 40.732002 2.75 25.53 40.08 68.36 13.34 6.91 11.38 31.63
Rata-rata 1.95 21.32 36.35 59.62 15.4 9.93 14.71 40.04
Urban RuralTahun
Sumber: SMERU Research Institute (diolah berdasarkan data BPS)
1.5. Komoditas Tradables dan Non-Tradables
� Pendekatan tradables dan non-tradables dilakukan dengan menggunakan Tabel I-O,
yaitu dengan mengelompokkan tradables sebagai output dan input perekonomian yang
memiliki komponen ekspor dan impor, sementara yang tidak memiliki komponen ekspor
dan impor dikelompokkan sebagai non-tradables. Komoditas pertanian mencakup hasil
produksi dari sektor pertanian dan hasil industri pengolahan yang berbasis pertanian
(agro-industri), yaitu industri makanan, tekstil, kayu, kertas, dan industri kimia.
Grafik 12. Pangsa Tradables dan Non-tradables
Pangsa Tradables dan Non-tradables Pangsa Tradables menurut Sektor
Tradables39,5%
Non-tradables60,5%
Agro-industri35,9%
Non-pertanian61,9%
Pertanian2,2%
Tradables
Sumber: BPS, Tabel Input-Output (diolah)
� Dari total ouput perekonomian, sebesar 39,5 persen merupakan output tradables dan
sisanya (60,5 persen) merupakan output non-tradables. Dari total output tradables,
sebesar 2,2 persen merupakan komoditas tradables dari sektor pertanian primer, 35,9
persen adalah komoditas tradables agro-industri, dan selebihnya (61,9 persen) adalah
komoditas tradables dari sektor lain.
Grafik 13. Komoditas Non-Tradables menurut Sektor Ekonomi
Agro-industri29,7%
Pertanian12,5%
Non Pertanian57,8%
Bangunan16,4%
Jasa-jasa14,8%
Perdagangan9,3%
Keuangan 5,2%
Lainnya12,1%
Sumber: BPS, Tabel Input-Output (diolah)
� Untuk komoditas non-tradables, sektor pertanian primer memegang peranan 12,5
persen dan agro-industri 29,7 persen, sementara sektor non-pertanian mencapai 57,8
persen. Dengan kata lain, sektor pertanian primer lebih banyak dikonsumsi di dalam
negeri (non-tradables) daripada sebagai komoditas tradables.
Grafik 14. Komoditas Tradables menurut Sub Sektor
11.1%
5.7%
12.0% 29.0%
20.3%21.9%
Pertanian primer Industri makanan, minuman & tembakau
Industri tekstil, barang kulit dan alas kaki Industri barang kayu & hasil hutan lainnyaIndustri kertas & barang cetakan Industri kimia & barang dari karet
Sumber: BPS, Tabel Input-Output (diolah)
� Ditinjau dari komoditas pertanian primer, pangsa sektor pertanian hanya sebesar 8,4
persen. Sementara itu, ditinjau secara lebih luas yaitu komoditas pertanian primer dan
olahan, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian
(40,6 persen).
� Secara sub sektor, industri tekstil menempati urutan pangsa terbesar komoditas
pertanian tradables yaitu 29,0 persen, diikuti oleh industri kimia dan karet (21,9 persen),
serta industri makanan (20,3 persen). Industri kayu dan industri kertas memiliki pangsa
komoditas tradables masing-masing sebesar 12,0 persen dan 11,1 persen. Sementara
itu, komoditas pertanian primer hanya memiliki pangsa 5,7 persen.
2. Perkembangan Komoditas Tradables Pertanian
2.1. Ekspor Komoditas Pertanian 2000 - 2005
� Pada tahun 2005 volume ekspor hampir mencapai 5 juta ton/tahun, meningkat
dibandingkan pada tahun 2000 sebesar 3,4 juta ton/tahun.
Grafik 15. Volume Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 2000 – 2005
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Ekspor (volume) Impor (volume) Neraca Perdagangan
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Juta ton
Sumber: BI (diolah)
� Peningkatan volume ekspor tersebut diikuti pula dengan kenaikan volume impor yang
tidak terlalu tinggi dari 7,1 juta ton/tahun pada tahun 2000, menjadi 7.6 juta ton/tahun
di tahun 2005.
� Meskipun dari sisi volume terjadi defisit, namun apabila dilihat dari sisi nilai, neraca
ekspor-impor (trade balance) komoditas pertanian masih mengalami surplus dari waktu
ke waktu. Pada tahun 2005 surplus perdagangan mencapai USD 2,3 milyar, atau
meningkat dari USD 282 juta pada tahun 2000.
Grafik 16. Nilai Ekspor-Impor Komoditas Pertanian 2000 – 2005
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Ekspor (nilai) Impor (nilai) Neraca Perdagangan
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Juta US$
Sumber: BI (diolah)
Grafik 17. Trade Balance Komoditas Food dan Non-Food
Food Non Food-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Juta USD
Export Import Trade Balance
Sumber: BPS (diolah)
� Secara lebih rinci, baik komoditas food maupun non-food mengalami surplus yang
cenderung meningkat dalam 6 tahun terakhir sejak krisis. Sementara itu, trade balance
Food mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan Non-Food.
Grafik 18. Pangsa dan Pertumbuhan Ekspor Komoditas Pertanian Terhadap Total Ekspor Non-Migas
Pangsa Ekspor Komoditas Pertanian Pertumbuhan Ekspor Komoditas Pertanian
0
5
10
15
20
25
1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Volume Nilai2000 2001 2002 2003 2004
-20
-10
0
10
20
30
Volume Nilai
Sumber: BPS, Tabel Input-Output (diolah)
� Dalam 6 tahun terakhir, pangsa ekspor komoditas pertanian terhadap total ekspor non-
migas meningkat secara gradual, sehingga pada 2004 pangsa volume ekspor pertanian
mencapai 11,6 persen, sedangkan pangsa nilai ekspor pertanian mencapai 22,4 persen.
Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor pertanian melambat sampai 2003, namun
meningkat lagi pada 2004, sehingga pertumbuhan nilai ekspor yang lebih tinggi daripada
pertumbuhan volume semata-mata disebabkan oleh faktor harga ekspor komoditas
pertanian pada periode tersebut.
� Dengan total ekspor komoditas pertanian sebesar 22,8 juta ton atau senilai USD 12,2
juta, Indonesia menduduki peringkat ke-20 negara eksportir terbesar komoditas
pertanian di bawah peringkat Thailand (ke-15) dan Malaysia (ke-16) yang luas lahan
pertaniannya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Sementara itu, peringkat 10 besar
negara eksportir komoditas pertanian adalah negara-negara maju, kecuali Brasil di
peringkat ke-7. Sedangkan, peringkat pertama sampai dengan ke-3 secara berturut-
turut diduduki oleh Amerika Serikat, Perancis dan Belanda.
Grafik 19. Negara Pengekspor Komoditas Pertanian Terbesar
Indonesia
Irlandia
New Zealand
Meksiko
Malaysia
Thailand
Brasil
Spanyol
Belgia
Jerman
Belanda
Perancis
USA
0 20 40 60 80
20
19
18
17
16
15
7
6
5
4
3
2
1
Rank
Nilai Ekspor ($ Miliar)
Sumber: BPS (diolah)
2.2. Perkembangan Ekspor Beberapa Komoditas Pertanian
� Total ekspor komoditas pertanian yaitu tekstil dan produk tekstil, minyak kelapa sawit
(CPO), kayu dan produk turunannya, ikan olahan dan awetan, dan karet dan produk
karet olahan mencapai 31,5 persen dari total ekspor non-migas. Untuk produk tekstil,
persentase yang diekspor dari output domestik adalah sebesar 70,1 persen, sedangkan
untuk komoditas kayu dan karet masing-masing sebesar 71,0 persen dan 60,3 persen.
Sementara itu, untuk komoditas kelapa sawit (CPO) dan ikan masing-masing adalah 32,2
persen dan 56,6 persen dari output domestik komoditas tersebut.
Grafik 20. Perkembangan Ekspor Komoditas Karet
Perkembangan Volume Ekspor Karet Perkembangan Nilai Ekspor Karet
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Ribu Mt)
Thailand Indonesia Malaysia
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Juta USD)
Thailand Indonesia Malaysia
Sumber: FAO (diolah)
� Volume Ekspor karet Indonesia terus mengalami pertumbuhan, meski agak turun pada
periode krisis (1998-1999) dan meningkat lagi sejak tahun 2000. Dalam pangsa pasar
dunia, ekspor karet Indonesia menduduki peringkat ke-2 setelah Thailand, namun masih
lebih tinggi dari Malaysia. Meski terjadi kenaikan volume ekspor, namun nilai ekspor
karet turun pada periode 1996-2001 sebagai akibat turunnya harga karet dunia.
Grafik 21. Perkembangan Ekspor Komoditas CPO
Perkembangan Volume Ekspor CPO Perkembangan Nilai Ekspor CPO
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Ribu Mt)
Malaysia Indonesia
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Juta USD)
Malaysia Indonesia
Sumber: FAO (diolah)
� Indonesia merupakan negara pengekspor CPO terbesar ke-2 setelah Malaysia. Volume
Ekspor CPO tumbuh dari sekitar 1,5 juta metric ton pada 1990-an menjadi 6,4 juta
metric ton pada 2003. Meski ekspor CPO Indonesia masih di bawah Malaysia, namun
pertumbuhannya lebih cepat yaitu sekitar 20 persen per tahun dibandingkan ekspor CPO
Malaysia yang hanya tumbuh sekitar 6 persen per tahun.
Grafik 22. Perkembangan Ekspor Komoditas Tekstil
Perkembangan Volume Ekspor Tekstil Perkembangan Nilai Ekspor Tekstil
010
2030
4050
6070
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Ribu Mt)
Indonesia Malaysia Thailand Viet Nam
05
10152025
3035
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Juta USD)
Indonesia Malaysia Thailand Viet Nam
Sumber: FAO (diolah)
� Komoditas tekstil mencakup produk serat sampai dengan produk olahan tekstil, seperti
pakaian jadi. Dari sisi volume, ekspor tekstil Indonesia hanya berada di peringkat ke-45
dunia, di bawah Vietnam dan Thailand, namun dari sisi nilai lebih tinggi dibandingkan
kedua negara tersebut.
Grafik 23. Perkembangan Ekspor Komoditas Kayu dan Produk Kayu
Perkembangan Volume Ekspor Kayu Perkembangan Nilai Ekspor Kayu
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Ribu Cum)
Indonesia Malaysia Thailand
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Juta USD)
Indonesia Malaysia Thailand
Sumber: FAO (diolah)
� Ekspor kayu Indonesia sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan, baik dari sisi
volume maupun nilai ekspor. Saat ini, ekspor kayu Indonesia menduduki peringkat ke-7
ekspor dunia dengan total ekspor mencapai 3,2 juta cum atau senilai USD 950 juta.
Grafik 24. Perkembangan Ekspor Komoditas Ikan Laut
Perkembangan Volume Ekspor Ikan Laut Perkembangan Nilai Ekspor Ikan Laut
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Ribu Mt)
Indonesia Thailand Viet Nam
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
(Juta USD)
Indonesia Thailand Viet Nam
Sumber: FAO (diolah)
� Ekspor ikan laut Indonesia cenderung turun sejak 1998, namun masih menduduki
peringkat ke-10 dengan volume ekspor mencapai 397 ribu Mt atau senilai USD 1,5 miliar
pada 2003. Hal tersebut berbeda dengan Vietnam dimana ekspor ikan terus meningkat
sehingga pangsa ekspornya melebihi Indonesia, sementara negara pesaing lain di Asean
adalah Thailand yang berada di urutan ke-2.
2.3. Persaingan Ekspor Komoditas Pertanian
Tabel 7. Pangsa dan Peringkat Dunia Komoditas Pertanian Unggulan
Terhadap Output
Terhadap Ekspor Dunia
Kelapa sawit dan minyak olahan 32.1% 27.5% 2 Malaysia (1) - 58.4%
Karet dan produk karet olahan 60.3% 27.5% 2 Thailand (1) - 41.8%
Ikan olahan 56.6% 2.74% 10 Thailand (2) - 7.24%
Tekstil dan produk tekstil 70.1% 0.23% 45 India (12) - 1.69%
Kayu dan produk dari kayu 71.0% 2.02% 10 Malaysia (7) - 3.74%
Pangsa Ekspor
Kelompok KomoditasPeringkat
DuniaNegara-negara pesaing Asia (peringkat) - pangsa dunia
Sumber: Tabel IO 2000 dan FAO (diolah)
� Empat dari lima komoditas pertanian unggulan Indonesia menduduki urutan 10 besar
peringkat pangsa ekspor dunia. Kelapa sawit dan karet beserta produk turunannya
masing-masing menduduki peringkat ke-2 dan menguasai hampir 30 persen pangsa
ekspor dunia. Negara Asean pesaing untuk komoditas kelapa sawit adalah Malaysia
yang menduduki peringkat pertama dan menguasai 58,4 persen pangsa dunia. Untuk
komoditas karet, Thailand merupakan negara pengekspor terbesar dengan pangsa dunia
sebesar 41,8 persen.
� Ekspor komoditas ikan dan kayu masing-masing menduduki peringkat ke-10 negara
pengekspor terbesar dunia, namun pangsa yang dikuasai tidak lebih dari 3 persen.
Negara pesaing di Asean untuk komoditas ikan adalah Thailand, sementara untuk
komoditas kayu adalah Malaysia. Untuk ekspor komoditas tekstil, meskipun Indonesia
hanya menempati di urutan ke-45, namun berada di atas negara-negara Asean lainnya.
China dan India masing menempati peringkat ke-3 dan ke-12 negara pengekspor tekstil
terbesar di dunia.
2.4. Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian
Tabel 8. Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian
TahunPertumb. Ekspor
Pertanian
Pertumb. PDB
Elastisitas PeriodeRata-rata
Elastisitas
1991 11.42 9.26 1.23
1992 8.92 10.30 0.87 1993 6.38 8.76 0.73 1994 33.88 8.15 4.16 1995 13.39 9.46 1.42 1996 7.51 9.10 0.83
1997 3.14 5.63 0.56 1998 (17.01) (10.56) 1.61 1999 1.61 1.68 0.96 2000 (3.78) 4.15 (0.91)
2001 (11.62) 3.83 (3.03) 2002 42.12 4.38 9.63 2003 12.64 4.88 2.59
Paska Krisis
2.07
Sblm Krisis
1.40
Masa Krisis
1.28
Sumber: BPS dan FAO (diolah)
� Elastisitas pertumbuhan ekspor komoditas pertanian terhadap pertumbuhan PDB
sebelum krisis tercatat sebesar 1,40, kemudian turun menjadi 1,28 pada masa krisis, dan
meningkat tajam menjadi 2,07 pada paska krisis. Angka elastisitas paska krisis
menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen akan mendorong
pertumbuhan ekspor komoditas pertanian sebesar 2,07 persen.
Grafik 25. Elastisitas Ekspor Komoditas Pertanian
di Beberapa Negara Periode 1991-2003
-
1.0
2.0
3.0
4.0
Elastisitas 2.84 1.75 1.69 1.59 1.10 0.41
Philippines Thailand USA Indonesia Vietnam China
E
Sumber: CEIC dan FAO (diolah)
� Elastisitas ekspor komoditas pertanian di beberapa negara Asean lainnya juga berkisar 1-
3. Dengan demikian, elastisitas pertumbuhan ekspor pertanian Indonesia (1,6) relatif
tidak jauh berbeda dengan negara-negara Asean yang cukup maju di bidang pertanian,
seperti Thailand (1,7). Negara Asean yang memiliki elastisitas tertinggi adalah Filipina
sebesar (2,84).
3. Produktivitas Sektor Pertanian .
3.1. Luas Lahan dan Penggunaan Lahan Pertanian
Grafik 26. Perkembangan Luas Lahan Pertanian
1981 2002
9.9%4.4%6.6%
14.7%64.4%
Lahan pertanian basah (arable land)Lahan perkebunan (permanent cropland)Ladang kering (permanent pasture)Hutan (forest and woodland)Penggunaan lahan lainnya
15.5%
7.2%11.3%
59.8%
6.2%
Lahan pertanian basah (arable land)Lahan perkebunan (permanent cropland)Ladang kering (permanent pasture)Hutan (forest and woodland)Penggunaan lahan lainnya
Sumber: FAO
� Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, terjadi peningkatan penggunaan lahan pertanian.
Dari total lahan (land area) seluas 181.157 ribu hektar digunakan sebagai lahan pertanian
basah (arable land) sebesar 9,9 persen (1980) dan meningkat menjadi 11,3 persen
(2002). Sedangkan penggunaan lahan untuk tanah perkebunan (permanent crops) juga
mengalami peningkatan, dari 4,4 persen (1980) menjadi 7,3 persen (2002). Pada periode
yang sama, luas area hutan (forest and woodland) menyusut dari 64,4 persen menjadi
59,8 persen.
� Peningkatan penggunaan lahan pertanian di Indonesia, merupakan salah satu faktor
yang mendukung peningkatan produksi sektor pertanian sebagaimana ditunjukkan oleh
peningkatan Indeks Pertanian pada pembahasan terdahulu. Dalam jangka pendek,
peningkatan produksi bisa dilakukan dengan memanfaatkan 1,08 juta hektar lahan tidur
yang tersebar di 13 propinsi. Secara keseluruhan ada 38,7 juta hektar potensi lahan
pertanian yang belum dimanfaatkan, terdiri dari 16,7 juta hektar lahan basah (sawah)
dan 22 juta hektar lahan kering.
� Sebagian besar lahan yang belum dimanfaatkan ini diluar Jawa. Potensi pertanian lahan
basah terbesar di Papua, Sumatera dan Kalimantan, sedangkan untuk pertanian lahan
kering di Sumatera dan Kalimantan. Khusus untuk perluasan lahan kering tanaman
tahunan (perkebunan), potensi terbesar di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
� Dalam periode 1981-1999 secara nasional terjadi konversi lahan pertanian ke non-
pertanian mencapai 1,63 juta hektar. Konversi ini sebagian besar terjadi di Jawa dimana
terjadi over utility lahan, dengan konversi lahan pertanian ke non-pertanian seluas 1 juta
hektar.
Tabel 9. Penggunaan Lahan Pertanian Antar Negara
Land Use
1981 2002 1981 2002 1981 2002 1981 2002
Indonesia 181,157 9.9 11.3 4.4 7.3 6.6 6.2 64.4 61.5
Malaysia 32,855 3.1 5.5 11.7 17.6 0.8 0.9 67.7 67.7
Philippines 29,817 17.5 19.1 14.8 16.8 3.5 5.0 41.1 45.6
Viet Nam 32,549 18.2 20.6 2.1 6.7 0.9 2.0 34.6 29.5
China 932,743 10.5 15.3 0.4 1.2 36.6 42.9 14.4 13.9
Mexico 190,869 12.1 13.0 0.8 1.3 39.0 41.9 24.8 25.4
Thailand 51,089 33.0 31.1 3.6 6.9 1.3 1.6 31.5 29.0
Japan 36,640 13.3 12.1 1.6 0.9 1.6 1.2 67.5 67.6
USA 915,896 20.6 19.2 0.2 0.2 25.9 25.5 32.0 32.2
India 297,319 54.8 54.4 1.8 2.8 4.1 3.7 22.7 22.8
Korea 9,873 20.8 17.1 1.4 2.0 0.6 0.6 66.5 65.5
Permanent Crops (%)
Permanent Pasture (%)
Forests and Woodland (%)
Land Area (1000Ha)
Arable Land (%)
Sumber: FAO (diolah)
� Kecenderungan peningkatan penggunaan lahan untuk arable area dan permanent crops
yang serupa terjadi pada beberapa negara seperti Malaysia, Philipina, Vietnam, China
dan Meksiko, sebaliknya di Thailand, USA dan Jepang justru menunjukkan penurunan
penggunaan lahan tersebut.
3.2. Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi
� Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Secara rata-rata, sektor pertanian mampu menyerap sebanyak 48,2 persen dari total
tenaga kerja yang bekerja di seluruh sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor
pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja di
Indonesia (labor intensive).
Tabel 10. Perkembangan Tenaga Kerja menurut Sektor Ekonomi
(Ribu orang)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Pertanian 37.092 54,7 39.787 54,7 38.470 49,5 35.932 42,9 39.490 44,5 41.140 44,8 40.608 43,3
Pertambangan dan Penggalian 339 0,5 501 0,7 627 0,8 789 0,9 617 0,7 772 0,8 1.035 1,1
Industri Pengolahan 5.611 8,3 7.431 10,2 9.061 11,7 10.720 12,8 11.030 12,4 11.897 13,0 11.070 11,8
Listrik, Gas dan Air 76 0,1 136 0,2 170 0,2 190 0,2 136 0,2 157 0,2 231 0,2
Bangunan 1.643 2,4 2.095 2,9 2.947 3,8 3.875 4,6 3.478 3,9 4.055 4,4 4.540 4,8
Perdagangan, Hotel dan Restoran 10.067 14,9 10.908 15,0 12.518 16,1 15.859 18,9 17.611 19,8 17.505 19,1 19.119 20,4
Pengangkutan dan Komunikasi 1.818 2,7 2.320 3,2 2.944 3,8 3.903 4,7 4.305 4,8 4.687 5,1 5.481 5,8
Keuangan, Persewaan dan Jasa 357 0,5 463 0,6 587 0,8 667 0,8 711 0,8 1.142 1,2 1.125 1,2
Jasa-jasa 10.784 15,9 9.161 12,6 10.443 13,4 11.825 14,1 11.398 12,8 10.400 11,3 10.513 11,2
Total 67.787 100 72.803 100 77.766 100 83.759 100 88.776 100 91.755 100 93.722 100
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004SEKTOR EKONOMI
1986-1988 1989-1991 1992-1994
Sumber : BPS
3.3. Tenaga Kerja Menurut Gender
Grafik 27. Perkembangan Tenaga Kerja Pertanian menurut Gender
Sebelum krisis Masa krisis Sesudah krisis
Pertumbuhan TK: 1,60% Pertumbuhan TK: 0,96% Pertumbuhan TK: 0,70%
P (39%)
L (61%)
P (42%)
L(58%)
L(57%)
P(43%)
Sumber: FAO
� Dalam kurun waktu 15 tahun tenaga kerja di sektor pertanian mengalami pertumbuhan
yang melambat. Pada periode sebelum krisis (1986-1997), secara rata-rata, tingkat
pertumbuhan tenaga kerja di sektor ini adalah sebesar 1,60 persen, sementara pada
periode krisis (1998-1999) menurun menjadi 0,96 persen dan pasca krisis (2000-2003)
sebesar 0,70 persen.
� Berdasarkan komposisi gender, tenaga kerja di sektor pertanian masih didominasi oleh
laki-laki, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan komposisi tenaga kerja wanita
di sektor tersebut.
Grafik 28. Perkembangan Indeks Tenaga Kerja Pertanian
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 200460
70
80
90
100
110
120
Indeks TK Pertanian Indeks Pertanian
%
Sumber: BPS (diolah)
� Dalam 15 tahun terakhir, sektor pertanian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata
2,75 persen, sementara jumlah tenaga kerja sektor pertanian tumbuh rata-rata 0,82
persen, sehingga sektor pertanian memiliki elastisitas terhadap pertumbuhan tenaga
kerja sebesar 3,37 persen. Setiap pertumbuhan 1 persen tenaga kerja di sektor pertanian
akan meningkatkan PDB sektor tersebut sebesar 3,37 persen. Dibandingkan dengan
sektor-sektor lain yang rata-rata memiliki elastisitas kurang dari 2 persen, peran tenaga
kerja sektor pertanian relatif lebih tinggi dalam pembentukan pertumbuhan PDB.
� Pada 1994 terjadi pergeseran dimana output sektor pertanian tumbuh menjadi lebih
tinggi dari pada pertumbuhan tenaga kerja sektor tersebut. Hal tersebut
mengindikasikan intensifikasi sektor petanian yang dapat terjadi karena peningkatan
produktifitas tenaga kerja ataupun karena penambahan investasi barang modal pada
sektor tersebut.
� Dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di beberapa negara
Asia, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia jauh
lebih tinggi dibandingkan Korea, Malaysia, dan Philipina namun masih lebih rendah
dibandingkan Vietnam dan Thailand.
Grafik 29. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (1994-2003)
2.2
4.5
4.7
11.1
19.9
22.3
40.5
44.2
57.6
67.9
0 20 40 60 80
Viet Nam
Thailand
Indonesia
Philippines
Mexico
Malaysia
Korea
Australia
Japan
USA
%
Sumber : BPS dan FAO (diolah)
3.4. Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Tabel 11. Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi
(Juta/orang)
Sektor Ekonomi Sebelum krisis Masa krisis Sesudah krisis
Pertanian 2.15 4.99 7.13
Pertambangan dan Penggalian 55.42 164.43 230.73
Industri Pengolahan 11.25 24.47 46.03
Listrik, Gas dan Air 30.66 73.51 99.75
Bangunan 9.67 18.65 25.46
Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.18 9.39 16.83
Pengangkutan dan Komunikasi 8.61 12.81 20.71
Keuangan, Persewaan dan Jasa 62.86 112.76 142.47
Jasa-jasa 3.72 7.60 17.16
Total 5.70 11.65 20.24
Sumber : BPS (diolah)
� Meskipun penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia cukup tinggi, namun
produktivitas tenaga kerja pada sektor tersebut sangat rendah. Berdasarkan
produktivitas tenaga kerja yang dihitung dari rasio antara PDB (harga berlaku) dengan
jumlah tenaga kerja per sektor, menunjukkan bahwa produktivitas sektor pertanian lebih
rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya maupun produktivitas PDB secara rata-rata.
Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian sebelum krisis tercatat sebesar Rp2,15
juta/orang, jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas sektor industri pengolahan
(Rp11,25 juta/orang) ataupun dibandingkan produktivitas rata-rata PDB (Rp5,70
juta/orang).
� Sebagaimana produktivitas pada sektor-sektor lain, produktivitas tenaga kerja sektor
pertanian tetap meningkat pada masa krisis menjadi Rp4,99 juta/orang dan meningkat
lagi menjadi Rp7,13 juta/orang.
Tabel 12. Perbandingan Produktivitas Sektor Pertanian Antar Negara
No. Countries
1979-81 2000-02 1979-81 2000-02 1979-81 2000-02 1979-81 2000-02 1979-81 2000-021. Indonesia 65,9 122,9 63,1 123,6 51,0 124,7 2.837,0 4.141,0 604,0 748,02. Malaysia 75,3 119,4 55,6 142,1 41,0 142,1 2.828,0 3.132,0 3.939,0 6.912,03. Thailand 79,1 124,3 79,7 123,5 64,5 135,3 1.911,0 2.654,0 616,0 863,04. Philipina 88,3 123,1 86,1 137,1 73,8 177,8 1.611,0 2.692,0 1.381,0 1.458,05. Vietnam 65,8 180,3 62,5 171,4 50,1 193,8 2.049,0 4.375,0 N.A 256,06. China 67,1 155,6 60,8 185,9 45,4 226,7 3.027,0 4.845,0 161,0 338,07. Japan 108,3 87,1 94,1 91,6 85,1 93,2 5.252,0 5.879,0 17.378,0 33.077,08. USA 98,6 118,3 94,5 122,5 89,0 123,6 4.151,0 5.830,0 20.672,0 53.907,09. Mexico 86,5 123,6 85,3 135,7 86,2 150,1 2.164,0 2.870,0 1.482,0 1.813,0
Note:*) Agriculture value added per worker (in USD)
kilogram/ha
Agricultural Productivity *)
Crop Production Index
Food Production Index
Livestock Production
Cereal Yield
Sumber : 2004 World Development Indicators – World Bank
� Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas sektor pertanian Indonesia masih jauh di
bawah negera-negara lainnya, kecuali Vietnam dan China. Dalam kurun waktu 1979-
1981, negara dengan produktivitas sektor pertanian yang tertinggi adalah USA dan
Jepang, dan yang terendah adalah China. Pada dua dekade berikutnya, Jepang,
Malaysia, USA dan China mengalami peningkatan produktivitas hampir dua kali lipat
sementara Indonesia hanya mengalami peningkatan sebesar 25 persen.
4. Pembiayaan Perbankan terhadap Sektor Pertanian
� Dilihat dari perkembangan kinerja sektor pertanian dalam PDB, struktur demografis,
penyerapan tenaga kerja, perdagangan ekspor dan impor, perkembangan pembiayaan
dari perbankan serta mempertimbangkan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan,
maka sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang masih memerlukan
perhatian dari banyak pihak termasuk pemerintah dan pihak perbankan.
4.1. Pembiayaan Formal Melalui Bank dan Non-Bank
� Ketersediaan modal dalam pembiayaan suatu usaha termasuk usaha di bidang pertanian
(baik usaha primer maupun olahan) memiliki peran yang sangat penting. Terdapat
indikasi bahwa sektor pertanian Indonesia saat ini masih banyak yang pembiayaannya
diperoleh dari sektor informal ataupun pembiayaan secara informal (self-financing).
Pembahasan pembiayaan dalam laporan ini akan difokuskan pada pembiaayaan formal
dari sektor keuangan, khususnya perbankan.
Grafik 30. Perkembangan Kredit Perbankan Sektor Pertanian
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
(Miliar Rp)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Total Kredit Bank Umum 188,871 234,611 292,921 378,134 487,426 225,133 269,000 307,594 365,410 437,942 553,548 689,671
Pertanian 13,860 15,525 17,630 26,002 39,308 23,777 19,504 20,864 22,332 24,307 32,376 36,678
Pangsa (dalam %) 7.3 6.6 6.0 6.9 8.1 10.6 7.3 6.8 6.1 5.6 5.8 5.3
Pertumbuhan (dalam %) 12.0 13.6 47.5 51.2 -39.5 -18.0 7.0 7.0 8.8 33.2 13.3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%
Sumber: LBU Bank Indonesia
� Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan
di atas 20 persen (kecuali masa krisis turun 53,8 persen). Pada tahun 1994, total kredit
perbankan mencapai Rp188,9 triliun meningkat menjadi Rp689,7 trilun pada 2005. Dari
jumlah tersebut, kredit yang disalurkan kepada sektor pertanian kurang dari 10 persen,
bahkan terdapat kecenderungan semakin menurun dalam periode tersebut, meskipun
secara nominal meningkat yaitu dari Rp13,9 trilun pada 1994 menjadi Rp36,7 triliun
pada 2005.
� Dilihat dari pertumbuhannya, secara rata-rata kredit perbankan tumbuh 16,1 persen per
tahun, sementara pertumbuhan kredit sektor pertanian tumbuh 12,3 persen per tahun,
dibawah pertumbuhan kredit sektor lain, seperti pada sektor pertambangan (36,3
persen), diikuti oleh sektor jasa (32,0 persen) dan sektor perdagangan (14,4 persen).
Tabel 13. Kebutuhan Investasi Komoditas Pertanian Unggulan
(Miliar Rp)
KOMODITAS PUBLIK PEMERINTAH SWASTA TOTAL
Total Tanaman Pangan 23.2 1,054.6 17,464.5 18,542.3 Padi - 616.6 14,147.6 14,764.2 Jagung 23.2 120.0 939.7 1,082.9 Kedelai - 318.0 2,377.2 2,695.2Total Hortikultura 2,751.2 154.2 4,894.8 7,800.2 Pisang 5.4 133.0 138.4 Jeruk 1,813.2 3.8 4,320.7 6,137.7 Bawang Merah 909.4 0.4 36.3 946.1 Anggrek 23.2 150.0 404.8 578.0Total Peternakan 23,250.0 5,600.0 22,450.0 51,300.0 Unggas 8,000.0 2,450.0 14,050.0 24,500.0 Sapi 13,500.0 2,500.0 8,000.0 24,000.0 Kado 1,750.0 650.0 400.0 2,800.0Total Perkebunan 26,841.4 6,654.5 34,604.3 68,100.2 Tanaman Obat 3,029.0 50.0 18,666.0 21,745.0 Cengkeh 767.5 85.5 182.2 1,035.2 Kelapa 221.0 647.8 916.8 1,785.6 Karet - 2,414.0 27.7 2,441.7 Kelapa sawit 18,226.4 1,699.2 7,556.6 27,482.2 Kakao 3,460.0 1,550.0 350.0 5,360.0 Tebu 1,137.5 208.0 6,905.0 8,250.5
JUMLAH 52,865.8 13,463.3 79,413.6 145,742.7
Sumber: Departemen Pertanian
� Berdasarkan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbang)
Departemen Pertanian, pengembangan 17 komoditas agribisinis yang menjadi prioritas
dalam pembangunan pertanian periode 2005-2010 dibutuhkan investasi sebesar 145,7
triliun yang sebagian besar berasal dari swasta (54,4%), sementara investasi publik dan
pemerintah masing-masing 36,3% dan 9,2%.
5. Pembentukan Harga Output Sektor Pertanian
� Dalam pembentukan inflasi, komoditas pertanian barang-barang yang diklasifikasikan ke
dalam sektor pertanian lebih fluktuatif dibandingkan inflasi pada barang-barang sektor
non pertanian. Besarnya bobot inflasi komoditas pertanian bersifat musiman, hal ini
terlihat dengan tingginya bobot pada masa-masa mendekati hari raya keagamaan,
kemudian pada awal tahun sekitar bulan Februari dan Maret bobot inflasinya menurun
secara drastis.
Grafik 31. Perkembangan Bobot Inflasi Komoditas Pertanian
%
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
FMAMJ J ASOND J F MAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J
2002 2003 2004 2005
Komoditas Pertanian Komoditas Non-Pertanian
Sumber: BPS, Inflasi Bulanan
� Sumbangan inflasi dari barang-barang yang diklasifikasikan ke dalam sektor non
pertanian terhadap inflasi umum lebih dominan dibandingkan sumbangan inflasi dari
barang-barang sektor pertanian. Sejalan dengan fenomena bobot inflasi komoditas
pertanian yang musiman, sumbangan inflasi dari barang-barang sektor pertanian
memuncak pada masa hari raya keagamaan (lebaran dan natal) yang dalam 4 tahun
terakhir ini jatuh di triwulan IV, sementara di awal tahun sumbangannya kecil bahkan
beberapa kali mencatat nilai negatif.
Grafik 32. Pangsa Komoditas Pertanian dan Inflasi
%
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
F MAMJ J ASOND J F MAMJ J ASOND J F MAMJ J ASOND J FMAMJ J
2002 2003 2004 2005
Komoditas Pertanian Komoditas Non-Pertanian
Sumber: BPS, Inflasi Bulanan
6. Output Pertanian menurut Lokasi
Grafik 33. Pangsa Terbesar Sektor Pertanian menurut Propinsi
0 5 10 15 20 25
JATIMJABAR
JATENGSUMUT
RIAUBANTEN
DKISULSELSUMSEL
LAMPUNG
%
Sumber: BPS (diolah)
� Menurut PDRB per Propinsi, terlihat bahwa output komoditas pertanian masih
terkonsentrasi di pulau Jawa, dimana Jawa Timur menempati urutan tertinggi (21,0
persen), Jawa Barat di urutan kedua (13,6 persen) dan Jawa Tengah (11,9 persen).
Sementara itu, urutan ke-4 dan ke-5 masing ditempati oleh Sumatera Utara dan Riau.
Grafik 34. Location Quotient Sektor Pertanian
Sumber: BPS, Tabel Input-Output (diolah)
� Sementara itu dengan menggunakan Location Quotient (LQ) atas dasar data PDRB 2004,
diketahui bahwa sektor pertanian di daerah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan
Kalimantan Tengah memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan daerah-
daerah lainnya. Jika dilihat secara subsektor, untuk subsektor tanaman bahan makanan,
daerah Nusa Tenggara Timur, Bengkulu dan Lampung unggul dibandingkan dengan
daerah-daerah lainnya. Sementara untuk perkebunan, 3 daerah yang memiliki LQ
terbesar adalah Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Untuk
peternakan, LQ terbesar dimiliki oleh daerah Nusa Tenggara Timur kemudian diikuti oleh
Lampung dan Sulawesi Tenggara. Untuk kehutanan Kalimantan Tengah, Riau dan
Sulawesi Tengah. Perikanan Maluku, Sulawesi Tenggara dan Bangka-Belitung.
7. Kebijakan Pemerintah Saat Ini
� Dalam kurun waktu lebih dari 3 dasawarsa (1970 – 2005), pokok-pokok kebijakan
pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek kebijakan, yaitu: kebijakan sumber
daya lahan, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan insentif. Dalam periode tersebut,
perkembangan pertanian mengalami 3 fase pertumbuhan, yaitu:
- Fase accelerating : periode 1970an s.d. 1985
- Fase decelerating : periode 1985 s.d. 2000
- Fase rebounding : periode 2001 s.d. 2005
Tabel 14. Kebijakan Pemerintah 1970-2005
1. Pemberdayaan lahanpertanian lebih diutamakanpada lahan sawah.
1. Pembangunan irigasi yangturut berperan dalamtercapainya swasembadaberas tahun 1984.
1. Intervensi pemerintah dalambentuk kebijakan harga, saranaproduksi dan kebijakanperdagangan.
2. Adanya konversi dari lahanpertanian ke lahan nonpertanian.
2. Pada masa reformasipembangunan irigasi menurun.
2. Pengembangan komoditasstrategis: beras, jagung, kedelai,ayam ras, susu, sapi, danberbagai komoditas perkebunan.
3. Kemampuan lahan sawahsebagai penggerakekonomi pedesaansemakin melemah.
3. Tahun 2003, pemerintahmenyediakan sekitar Rp 4,76trilyun untuk pembangunanirigasi.
3. Kebijakan tarif dan subsidi pupukkurang efektif, sehingga munculmasalah penyelundupan, sepertiberas dan gula.
INFRASTRUKTUR INSENTIFSUMBER DAYA LAHAN
Sumber: BI, BPS, Deptan (diolah)
� Pada periode 1970an s.d. 1985 dimana sektor pertanian mengalami fase accelerating
dapat dijadikan referensi kebijakan dimana pada saat itu sektor pertanian memperoleh
perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Adapun kebijakan yang paling menonjol
pada masa tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan pembiayaan institusional
melalui kredit-kredit program. Dengan pertumbuhan rata-rata lebih dari 4 persen per
tahun, periode tersebut sering disebut sebagai green revolution.
� Masa keemasan sektor pertanian nampaknya tidak mampu bertahan lama, sejalan
dengan semakin menurunnya peran pemerintah dalam menumbuhkembangkan sektor
pertanian. Deregulasi perbankan pada periode 1980an tidak mampu menyentuh sektor
pertanian, sehingga pembiayaan dari perbankan tidak banyak berpihak kepada sektor
tersebut. Kondisi ini diperparah dengan semakin memburuknya pembangunan
infrastruktur pertanian yang seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah.
� Pada periode 2001 – 2005, pemerintah mulai menunjukkan perhatiannya pada sektor
pertanian dengan kebijakan pokok pembangunan sistem usaha agribisnis dan
peningkatan ketahanan pangan. Adapun sasaran utama kebijakan tersebut adalah:
- Meningkatkan kapasitas produksi pertanian
- Mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian dan wilayah pedesaan
- Meningkatkan pendapatan rumah tangga tani
- Memantapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional
- Meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian
- Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap devisa negara
� Namun demikian, dalam periode tersebut pengembangan sektor pertanian menghadapi
banyak kendala, terutama dalam hal:
- Luas lahan pertanian semakin berkurang
- Pendapatan tenaga kerja sektor pertanian rendah
- Ketersediaan bahan pangan
8. Komoditas Pertanian Unggulan
8.1. Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan
� Dalam menentukan komoditas unggulan sektor pertanian, digunakan 3 pendekatan
yaitu: 1) Pendekatan Kontribusi Ekspor dan Linkage, 2) Pendekatan Konsumsi, Produksi,
dan/atau Struktur Input, serta 3) Pendekatan Kebijakan Pemerintah.
Tabel 15. Komoditas Pertanian Tradables Ekspor Unggulan
Kelompok Komoditas Komoditas% dari Total
Ekspor Backward Linkage
Forward Linkage
Pakaian jadi 1.25 0.53Barang-barang rajutan 1.34 0.56Tekstil 1.24 1.02Benang 1.19 1.49Permadani, tali dan tekstil lain 0.99 0.67Kayu lapis dan sejenisnya 1.06 0.71Industri kertas budaya 1.33 1.26Perabot RT dari kayu, rotan dan bambu 1.20 0.52Bahan bangunan dari kayu 1.14 0.55Bubur kertas 1.34 1.96Barang cetakan 1.14 0.73Karet olahan 1.05 0.87Damar sintetis, bahan plastik & serat 1.03 1.91Barang-barang dari karet 1.18 0.78
Kelapa Sawit Industri Minyak Nabati Dan Hewani 2.74 1.11 1.60Ikan (termasuk tuna) Ikan olahan & awetan 1.96 1.11 1.06
Karet dan produk karet olahan
Kayu dan produk dari kayu
Tekstil dan produk tekstil 12.25
11.25
3.29
Sumber: BPS, Tabel Input-Output 2000 (diolah)
� Dengan menggunakan pendekatan pertama, komoditas pertanian unggulan
dikelompokkan berdasarkan komoditas pertanian yang memberikan kontribusi ekspor
terbesar serta memiliki backward/forward linkage yang relatif kuat.
� Hampir seluruh komoditas pertanian primer memiliki derajat penyebaran (backward
linkage) dan daya kepekaan (forward linkage) yang relatif rendah (BL, FL <1), kecuali
komoditas ternak yang memiliki BL>1. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian
primer di Indonesia tidak memilki daya dorong yang cukup kuat terhadap pertumbuhan
sektor-sektor lain serta belum mampu menciptakan permintaan yang tinggi dari sektor-
sektor lain.
� Namun apabila dilihat dari komoditas pertanian olahan (agro-industri), industri kimia dan
karet, industri makanan dan industri kertas memilki backward dan forward linkage yang
cukup besar, sementara industri tekstil dan industri kayu memiliki backward linkage yang
cukup besar, namun forward linkage-nya tidak terlalu besar.
Grafik 35. Sebaran Komoditas Pertanian Menurut Rasio Backward dan Forward Linkage
tabama
karetkelapa
kebun lainnyaternak
kayu
hutan
ikan_lautikan_darat udang
tambang
migas in_makanan
minyaknabati
in_tekstil
in_kayu
in_kertas
in_kimiakaret
in-semen
in_logam
in_transport
in_dlllistrikair bangunan
perdagangan
angkutankeuangan
jasa
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8
Rasio Backward Linkage
Ras
io F
orw
ard
Lin
kag
e
Sumber: BPS, Tabel IO (diolah)
� Sebagai contoh, komoditas kelapa sawit dan produk olahannya memiliki rasio backward
linkage 1,1 yang berarti setiap pertumbuhan 1 persen produksi komoditas kelapa sawit
akan menarik tumbuhnya input dari komoditas lain sebesar 1,1 persen. Sedangkan rasio
forward linkage komoditas kelapa sawit sebesar 1,6 berarti bahwa setiap pertumbuhan 1
persen produksi kelapa sawit akan mendorong kenaikan produksi komoditas lain sebesar
1,6 persen.
� Dengan menggunakan pendekatan pertama tersebut, terdapat 5 kelompok komoditas
pertanian unggulan yaitu: 1) Tekstil dan produk tekstil, 2) Minyak nabati, termasuk
minyak kelapa sawit (CPO), 3) Kayu dan produk turunannya, 4) Ikan olahan dan awetan,
dan 5) Karet dan produk karet olahan.
� Dengan pendekatan kedua, komoditas pertanian dikatakan unggulan apabila output
besar, konsumsi domestiknya tinggi dan/atau menjadi input yang dominan bagi sektor
industri pengolahan yang berbasis pertanian. Dengan pendekatan tersebut, terdapat 14
komoditas pertanian yang memenuhi kriteria unggulan, yaitu: padi, jagung, umbi-
umbian, sayuran, buah-buahan, karet, kelapa, kelapa sawit, ternak, unggas, daging
potong, kayu, ikan dan hasil laut, dan udang.
Tabel 16. Signifikansi Komoditas Pertanian Unggulan Terhadap Total Output Pertanian
SUBSEKTOR KOMODITAS% THD
OUTPUT PERTANIAN
PENGGUNAAN
Tanaman Padi 18.5 Input beras (91,9%), bibit (4,4%)
bahan makanan Jagung 3.5 Konsumsi (37,8%), pakan ternak (21,8%), kopi giling (14,3%),
minyak nabati (8,2%), tepung (6,6%), bibit (4,5%)
Umbi-umbian 2.9 Konsumsi (70,0%), restoran (10,6%), pakan ternak (7,5%), bibit (2,4%)
Sayuran 4.5 Konsumsi (70,8%), restoran (11,9%), jasa kesehatan (4,0%), bibit (4,0%)
Buah-buahan 7.4 Konsumsi (70,8%), restoran (4,8%), jasa kesehatan (2,4%), bibit (1,8%)
Tanaman Karet 3.9 Industri karet remah/asap (57,3%), alas kaki (22,4%), bibit (16,3%)
perkebunan Kelapa 2.2 Konsumsi (39,7%), industri minyak (35,8%), kopra (12,3%)
Kelapa sawit 1.7 Industri minyak (78,0%), sabun (13,5%), kosmetik (3,1%)
Peternakan Ternak 3.2 Daging potong (72,6%), konsumsi (12,2%)
Unggas 11.6 Konsumsi (56,6%), Unggas potong (16,2%)
Daging potong 8.7 Konsumsi (63,4%), restoran (23,5%), industri kulit (5,6%)
Kehutanan Kayu 5.6 Kayu lapis (30,2%), bangunan (24,7%), kayu gergajian (19,4%),
industri kayu lain (9,8%), industri kertas (3,2%)
Perikanan Ikan & hasil laut 7.2 Konsumsi (49,8%), ikan olahan (28,6), ikan kering (6,9%), ekspor (7,2%)
restoran (5,6%)
Udang 3.6 Konsumsi (63,0%), bibit (11,0%), udang olahan (10,9%),
udang kering (6,9%)
Total 84.5
Sumber: BPS, Tabel IO (diolah)
� Pendekatan ketiga terkait dengan komoditas pertanian yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah sebagai komoditas unggulan. Sebagaimana tertuang dalam rencana
pelaksanaan pembangunan pertanian periode 2005 – 2010, Departemen Pertanian
secara khusus memprioritaskan pengembangan 17 komoditas agribisnis. Komoditas
tersebut meliputi padi, jagung, kedelai, pisang, jeruk, bawang merah, anggrek, kelapa
sawit, karet, cengkeh, kelapa, tanaman obat, kakao, tebu, unggas, kambing/domba, dan
sapi.
� Dari ketiga pendekatan diatas, komoditas pertanian dikelompokkan sebagai komoditas
unggulan apabila setidaknya memenuhi 2 pendekatan. Dengan kriteria tersebut,
terdapat 12 komoditas pertanian unggulan yang merupakan penggerak utama dalam
pertumbuhan sektor pertanian, baik pertanian primer maupun agro-industri.
Tabel 17. Matriks Komoditas Pertanian Unggulan
KOMODITAS PERTANIAN
PENDEKATAN TRADABLES & FORWARD-BACKWARD
LINKAGES
PENDEKATAN KONSUMSI,
PRODUKSI & INPUT
PRIORITAS PEMERINTAH
KOMODITAS UNGGULAN
Padi/beras - V V V
Jagung - V V V
Kedelai - - V -Tekstil (kapas) V - - -Karet V V V V
Kelapa sawit V V V VKelapa - V V VKakao - - V -
Tebu - - V -Cengkeh - - V -
Pisang - V V VJeruk - V V VKayu/produk kayu V V - V
Tanaman obat - - V -Bawang merah - - V -
Anggrek - - V -
Sapi - V V V
Unggas - V V V
Kambing/domba - V V V
Ikan & udang V V - V
Sumber: BI, BPS, Deptan (diolah)
8.2. Profil Usaha Komoditas Pertanian
(Berdasarkan hasil Survei Pemetaan Sektor Ekonomi – SPSE)
� Dari hasil SPSE yang dilaksanakan Bank Indonesia tahun 2005, khususnya terhadap
perusahaan yang menjalankan usaha komoditas pertanian, diperoleh gambaran awal
mengenai profil usaha, struktur biaya produksi, orientasi penjualan, dan masalah
pembiayaan.
� Ditinjau dari sifat proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan responden, pada saat
ini sedikit lebih banyak yang bersifat independen atau melakukan produksi atas dasar
perencanaan sendiri atau tidak ditentukan oleh pembeli/prinsipal atau sebagainya (69%)
dibandingkan atas dasar pesanan (30%). Sementara apabila ditinjau dari proses
produksinya, 47 persen unit usaha pertanian melakukan usahanya dengan mengolah
bahan mentah sampai barang setengah jadi, dan 46 persen unit usaha mengolah bahan
mentah sampai barang jadi.
Grafik 36. Proses Produksi Usaha Pertanian
Sifat Proses Produksi Proses Produksi
Lainnya
Produsen a/d pesanan
Produsen Independen
(69%)
(30%)
(1%)
Bhn mentah sampai brg
1/2 jadi
Bhn 1/2 jd sampai
barang jadi
Bhn mentah sampai
barang jadi
(46%)(47%)
(2%)
Sumber: Hasil SPSE Bank Indonesia
� Dari sisi bahan baku, diketahui bahwa sebagian besar unit usaha pertanian melakukan
proses produksi dengan bahan baku domestik. Hal ini juga terlihat dalam struktur biaya
produksinya dimana 65 persen dari total biaya adalah biaya bahan baku, sementara biaya
tenaga kerja 11 persen, biaya bahan penolong 9 persen, dan biaya bunga 4 persen.
� Ekspor komoditas pertanian sebagian besar dalam bentuk barang jadi, sementara untuk
impor didominasi oleh bahan baku. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan
produksi komoditas pertanian secara nasional memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.
� Dalam menjalankan usaha pertanian, sumber dana untuk membiayai modal kerja secara
umum berasal dari dana non-perbankan yaitu 64 persen, sementara perbankan hanya
memberikan kontribusi sebesar 36 persen dalam pembiayaan modal kerja usaha
pertanian. Secara lebih rinci, pembiayaan modal kerja perusahaan terutama berasal dari
dana internal (antara lain retained earnings) mencapai 50,3 persen, dari bank domestik
sebesar 31,4 persen, dan individu pemilik/partner usaha sebesar 6,9 persen.
Grafik 37. Pembiayaan Modal Kerja Usaha Pertanian
31.4
1.1 3.9 2.8 3.6 6.9
50.3
0
10
20
30
40
50
60
Bank Domestik Bank Milik AsingBank Diluar Negeri Penjualan SahamKeluarga Pemilik IndividuDana Internal
(%)
Sumber: Hasil SPSE Bank Indonesia
8.3. Profil Usaha Komoditas Pertanian
� Sebagaimana diuraikan diatas, terdapat 12 komoditas pertanian unggulan yang menjadi
penggerak utama sektor pertanian. Komoditas-komoditas tersebut memberikan
sumbangan lebih dari 80 persen terhadap output sektor pertanian primer dan
merupakan komoditas input yang dominan terhadap sektor agro-industri.
� Sementara itu, dari hasil SPSE 2005 dapat disajikan gambaran awal mengenai profil
usaha beberapa komoditas pertanian, yaitu: karet, kelapa sawit, kayu, sayuran dan buah-
buahan, serta ikan dan udang. Profil beberapa komoditas pertanian dari hasil SPSE
tersebut diharapkan dapat menjadi preliminary study yang dapat dimanfaatkan dalam
penelitian di lapangan dalam bentuk indepth study pada tahun 2006. Penelitian tersebut
akan dilakukan bekerjasama dengan instansi/institusi yang terkait dalam pengembangan
sektor pertanian di Indonesia.
Tabel 18. Profil Usaha Beberapa Komoditas Pertanian Unggulan
KOMODITAS
PROFIL
Domestik 100% 0.0 25.0 0.0 4.8 15.4
Ekspor >50% 91.3 33.3 50.0 95.2 53.9
Domestik 100% 100.0 91.3 70.0 61.9 76.9
Impor >50% 0.0 0.0 20.0 14.3 7.7
Bahan Baku 78.7 68.4 53.9 57.5 59.0
Bahan Penolong 4.4 7.7 17.2 11.4 10.0
Biaya Tenaga Kerja 9.0 10.1 12.0 11.3 12.2
Biaya Bunga 2.4 3.4 3.6 3.0 3.6
Lainnya 5.5 10.4 13.3 16.8 15.2
84.8 74.8 82.3 71.2 72.2
Dana Internal 43.6 70.2 67.5 38.6 35.1
Bank Domestik 41.4 24.2 8.4 27.4 38.1
Lainnya 15.0 5.5 24.1 34.0 26.8
Dana Internal 84.5 66.4 69.3 62.1 53.3
Bank Domestik 5.5 25.4 5.8 20.7 29.7
Lainnya 10.0 8.2 24.9 17.2 17.0
Manajemen 11.0 11.8 10.3 7.1 13.8
Tenaga Kerja Ahli 18.4 32.4 33.1 18.6 24.2
Tenaga Kerja Kurang Ahli 70.6 55.7 56.6 74.2 62.0
ASEANLebih Buruk
Lebih Buruk
Lebih Baik
Kurang Lebih Sama
Lebih Buruk
INTERNASIONALLebih Buruk
Kurang Lebih Sama
--Lebih Buruk
Kurang Lebih Sama
SAYURAN & BUAH
HASIL KARET
KELAPA SAWIT
HASIL KAYU
IKAN & UDANG
SUMBER PEMBIAYAAN
KOMPOSISI TENAGA KERJA
POSITIONING
MODAL KERJA
INVESTASI
ORIENTASI PENJUALAN
PRODUKSI
BAHAN BAKU
STRUKTUR BIAYA
KAPASITAS TERPAKAI (NORMAL)
Sumber: Hasil SPSE Bank Indonesia
PETA SEKTOR PERTANIAN
9. Hasil Kajian Lanjutan Terhadap Komoditi Unggulan Sektor Pertanian
� Berdasarkan hasil penentuan komoditas unggulan sektor pertanian, terdapat 12
komoditas yang merupakan komoditas unggulan dalam sektor pertanian, baik pertanian
primer maupun agro-industri. Sementara berdasarkan hasil kongres Ikatan Sarjana
Ekonomi Indonesia (ISEI) tahun 2006, telah ditetapkan 10 komoditas unggulan termasuk
didalamnya 5 komoditas unggulan pertanian (kelapa sawit, kopi, karet, kakao, serta ikan
dan udang).
� Kajian lanjutan dilakukan terhadap komoditas unggulan hasil kajian sebelumnya,
termasuk beberapa komoditas unggulan pertanian hasil kongres ISEI dan komoditas
pertanian yang memiliki peranan yang cukup signifikan dalam penghitungan inflasi.
Komoditas yang dipilih untuk kajian lanjutan adalah sebagai berikut: padi, jagung, jeruk,
pisang, unggas (ayam), sapi, kambing-domba, kelapa sawit, karet, kakao, tebu, ikan
tuna, udang, dan rumput laut.
� Untuk pembahasan selanjutnya, komoditas padi, jagung, jeruk, pisang, unggas (ayam),
sapi, kambing-domba akan dikategorikan dalam subsektor tanaman bahan makanan dan
peternakan. Sementara untuk komoditas kelapa sawit, karet, kakao dan tebu termasuk
dalam subsektor perkebunan dan komoditas ikan tuna, udang dan rumput laut termasuk
dalam subsektor perikanan.
9.1. Gambaran Umum Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Peternakan
� Hasil analisis model Input-Output menunjukkan bahwa komoditas padi dan industri
penggilingan padi, komoditas peternakan (sapi, domba, kambing dan peternakan
ruminansia besar dan kecil lainnya) dan industri pemotongan hewan, serta industri
unggas merupakan industri kunci nasional. Industri kunci nasional adalah industri yang
mampu membangkitkan dan mendorong industri lainnya yang pada akhirnya dapat
memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
9.1.1. Komoditas Padi
� Produksi padi mengalami perlambatan pertumbuhan sejak pertengahan tahun 1980-an,
dan sejak awal tahun 1980-an laju pertumbuhannya telah di bawah laju pertumbuhan
penduduk atau produksi beras per kapita terus menurun hingga saat ini. Laju
pertumbuhan produksi padi pada periode 1980-1989 sebesar 5,32% per tahun turun
menjadi 1,04% per tahun pada periode 2000-2005. Sementara pertumbuhan produksi
padi pada tahun 2005 tercatat sebesar 0,12%. Penurunan produksi beras ini
menyebabkan swasembada beras yang diraih tahun 1984 tidak dapat dipertahankan
secara berkelanjutan dan Indonesia harus melakukan impor beras.
� Hasil analisis menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan laju pertumbuhan produksi
padi adalah akibat dari kombinasi beberapa faktor yaitu : (a) penurunan luas baku lahan
sawah, khususnya di Jawa; (b) stagnasi atau bahkan penurunan produktivitas lahan.
Penurunan luas baku lahan sawah adalah akibat dari konversi lahan untuk peruntukan di
luar sektor pertanian. Cara yang paling mungkin untuk meningkatkan luas baku lahan
sawah adalah melalui pembukaan lahan sawah. Stagnasi atau bahkan penurunan
produktivitas padi adalah konsekuensi dari tidak berkembangnya inovasi baru dan
semakin memburuknya kesuburan lahan. Selain itu, peningkatan produksi padi juga
dihadapkan pada masalah kerusakan jaringan dan sumber air irigasi. Dari 6,7 juta hektar
jaringan irigasi yang dibangun, 1,5 juta hektar (22%) diantaranya rusak.
Tabel 19. Kondisi Jaringan Irigasi, 2006
KONDISI KEANDALAN AIR PRASARANA TERBANGUN
JUMLAH UNIT RUSAK BERAT
RUSAK RINGAN WADUK
NON WADUK
Jaringan irigasi 6.771.826 hektar 341.327 1.178.548 719.173 6.052.653
(0,05%) (17,4%) (10,62) (89,38)
Bendung 11.547 buah 49 - - -
(0,24%)
Waduk 273 buah 14 5 - -
(5,1%) (1,8)
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Usaha tani padi cukup menguntungkan secara finansial serta memiliki keunggulan
komparatif. Sistem pemasaran gabah – beras juga cukup efisien, namun dengan marjin
pemasaran cenderung meningkat. Hal ini terutama adalah akibat dari peningkatan biaya
transportasi dan refleksi dari struktur mata rantai pemasaran yang panjang. Isu kebijakan
utama dalam hal pemasaran ialah menjaga stabilitas harga musiman.
� Berdasarkan kecenderungan historis, dan bila program revitalisasi industri perberasan
nasional tidak efektif, diperkirakan produksi beras akan mengalami pertumbuhan negatif
pada periode 2006 – 2010. Produksi beras pada 2006 diperkirakan sebesar 30,6 juta ton
dan turun menjadi 27,5 juta ton pada 2010. Dalam kondisi demikian Indonesia akan
terpaksa mengimpor beras dalam jumlah yang semakin besar. Hal ini tentu akan
berdampak negatif terhadap ketahanan pangan nasional, dan dapat mengganggu
kestabilan harga (inflasi) mengingat peranan beras dalam penghitungan inflasi cukup
besar (sekitar 5,2%).
Tabel 20. Proyeksi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Luas panen (000 ha) 11.731 11.732 11.600 11.444 11.264 11.059
Produktivitas (kg/ha) 4.587 4.574 4.535 4.467 4.372 4.250
Produksi gabah (000 ton) 53.814 53.063 51.896 56.319 48.352 46.025
Produksi beras* (000 ton) 30.609 30.182 29.518 28.621 27.503 -
Total Konsumsi (000 ton) 31.130 31.528 31.935 32.254 32.479
Surplus (Defisit) (000 ton) (521) (1.346) (2.417) (3.633) (4.976)*) Konversi gabah – beras = 0.632 dan hilang 10%.
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Pada masa sebelum krisis, harga gabah tumbuh lebih cepat daripada harga beras.
Sementara pasca krisis, harga gabah tumbuh lebih lambat dari harga beras. Hal ini
menunjukkan ongkos pemasaran beras (termasuk laba pedagang) semakin tinggi. Harga
gabah dan beras cenderung stabil pada periode tahun 2000-2004, tidak hanya dibanding
masa krisis yang merupakan masa puncak instabilitas, tapi juga dibandingkan dengan
masa sebelum krisis. Harga gabah yang diterima petani jauh lebih tidak stabil daripada
harga beras yang dibayar konsumen. Peningkatan pangsa harga konsumen yang diterima
oleh petani padi (perbaikan efisiensi pemasaran) dan stabilisasi harga gabah yang
diterima petani tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan
produksi padi/beras dan meningkatkan pendapatan petani padi.
9.1.2. Komoditas Jagung
� Produksi jagung terus mengalami pertumbuhan tinggi dan akseleratif. Pada periode
2000-2005, komoditas jagung secara rata-rata tumbuh 5,13% pertahun, atau meningkat
dibandingkan 3,96% pada 1990-1999. Pertumbuhan produksi yang tinggi tersebut
terutama berasal dari pertumbuhan produktivitas sebagai refleksi dari pesatnya inovasi
teknologi. Berbeda dengan padi yang mengandalkan lembaga penelitian pemerintah,
teknologi jagung terutama ditopang oleh sistem inovasi swasta, tepatnya perusahaan
multi–nasional di bidang perbenihan dan agrokimia. Benih jagung hibrida dengan potensi
produktivitas yang amat tinggi dan terus meningkat merupakan kunci dan akselerasi
pertumbuhan produksi jagung.
� Selain di didorong oleh inovasi teknologi, pertumbuhan produksi jagung yang akseleratif
tersebut juga disebabkan oleh peningkatan permintaan jagung dalam negeri untuk
industri pakan ternak. Industri pakan ternak berkembang pesat karena ditarik oleh
pertumbuhan pesat usaha peternakan intensif, utamanya peternakan ayam ras.
Permintaan jagung untuk pakan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan
usaha peternakan intensif. Selain itu, usahatani jagung tidak saja layak secara finansial,
tetapi juga kompetitif sehingga jagung juga potensial untuk diekspor.
� Masalah pokok sisi penawaran jagung ialah ketidakstabilan produksi, yang terutama
berasal dari masalah luas panen. Luas panen tanaman jagung secara rata-rata tumbuh
0,8% pada 2000-2005, atau cenderung menurun dibandingkan 1,60% pada 1990-
1999, namun cenderung meningkat dibandingkan 0,63% pada 1970-1979. Akar
penyebab turunnya luas panen jagung adalah berfluktuasinya harga jagung yang
diterima petani sehingga pada saat harga jagung menurun, petani melakukan konversi
tanahnya untuk komoditas lain . Dengan demikian, stabilisasi harga jagung di tingkat
petani merupakan isu kebijakan pokok yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
� Hasil proyeksi menunjukkan bahwa untuk periode tahun 2006 – 2010, produksi jagung
akan terus tumbuh pesat dan akseleratif, melampaui laju peningkatan permintaan,
sehingga akan terjadi surplus produksi yang semakin tinggi.
Tabel 21. Proyeksi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
Luas panen (000 ha) 3.916 4.206 4.498 4.789 5.077
Produktivitas (kg/ha) 3.569 3.692 3.822 3.962 4.112
Produksi (000 ton) 13.978 15.527 17.194 18.978 20.875
Konsumsi (000 ton) 13.510 14.232 15.005 15.756 16.623
Surplus (defisit) (000 ton) 468 1.295 2.189 3.222 4.252
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Harga jagung di tingkat konsumen meningkat lebih cepat daripada harga jagung di
tingkat produsen. Pada tahun 1984-1989 harga gabah lebih tinggi 25% daripada harga
jagung, namun pada tahun 2000-2004 selisih harga gabah dengan jagung kurang dari
8%, ini berarti insentif harga untuk usahatani jagung terus meningkat. Inilah salah satu
alasan produksi jagung meningkat lebih cepat dalam tiga dekade terakhir. Sejak tahun
2000 harga jagung di tingkat produsen lebih stabil. Di sisi lain, harga jagung di tingkat
konsumen semakin tidak stabil. Kecenderungan ini jelas tidak menguntungkan bagi
konsumen jagung.
9.1.3. Komoditas Jeruk dan Pisang
� Setelah mengalami penurunan produksi pada 1990-an, produksi jeruk meningkat pesat
pada tahun 2000-an. Pada 1990-an, produksi jeruk rata-rata sebesar 502 ribu ton,
meningkat pesat menjadi 1,2 juta ton pada 2000-an. Walaupun mengalami peningkatan
produksi yang cukup signifikan, pengembangan komoditas jeruk masih menghadapi
permasalahan yang cukup serius antara lain instabilitas produksi terutama gagal panen
akibat serangan hama dan penyakit.
� Walaupun lebih rendah dari periode 1990-1999, laju pertumbuhan produktivitas jeruk
yang mencapai 9,48%, pada periode 2000-2004 sudah tergolong tinggi, yaitu dengan
produktivitas sebesar 22,28 ton per hektar.
� Masalah daya saing jeruk tidak terletak pada ongkos produksi tetapi pada mutu yang
masih rendah. Selain itu, usahatani jeruk juga membutuhkan modal investasi yang cukup
besar sementara pada umumnya petani tidak punya akses terhadap lembaga perbankan.
� Hasil proyeksi menunjukkan bahwa berdasarkan data historis peningkatan produksi jeruk
lebih cepat dari peningkatan permintaan domestik sehingga Indonesia akan surplus jeruk
dalam jumlah yang terus meningkat. Hal ini dapat pula dipandang sebagai peluang untuk
mengembangkan industri pengolahan jeruk dalam negeri dan memacu ekspor jeruk.
Tabel 22. Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Jeruk dan Pisang
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
1. Jeruk
Produksi (000 ton)
Konsumsi (000 ton)
Surplus (defisit)
3.275
2.446
829
4.242
2.622
1.620
5.617
2.825
2.792
7.609
3.056
4.553
10.511
3.306
7.205
2. Pisang
Produksi (000 ton)
Konsumsi (000 ton)
Surplus (defisit)
5.174
5.131
43
5.331
5.264
67
5.492
5.401
91
5.659
5.542
117
5.830
5.686
14
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Setelah terus menurun selama periode tahun 1984-1999, stabilitas harga jeruk di tingkat
produsen meningkat tajam pada periode tahun 2004-2005. Berbeda dengan di tingkat
konsumen, stabilitas harga jeruk di tingkat produsen adalah yang terburuk selama dua
dekade terakhir. Secara umum dapat dikatakan bahwa harga jeruk di tingkat produsen
cenderung makin stabil pada level riil yang rendah. Kecenderungan demikian tentu tidak
kondusif bagi upaya pemacuan produksi jeruk di dalam negeri.
� Marjin pemasaran jeruk secara riil meningkat secara tajam pada periode 2000-2004, hal
ini mengindikasikan semakin menurunnya pangsa harga konsumen yang diterima oleh
petani jeruk. Pada tahun 2000, pangsa harga konsumen yang diterima oleh petani jeruk
adalah sebesar 90% dan turun menjadi hanya sekitar 74% pada tahun 2004. Faktor lain
yang cukup signifikan meningkatkan marjin pemasaran jeruk adalah retribusi daerah,
pungutan tidak resmi dan pola perdagangan jeruk antar daerah yang meningkatkan
ongkos transportasi.
Tabel 23. Kinerja Komoditas Jeruk dan Pisang
URAIAN 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004
1. Jeruk
Luas Panen (ha) 35.156 64.494 45.512 49.781
Produktivitas (ton/ha) 5,21 7,06 12,34 22,28
Pertumbuhan (%/thn) 4,77 -3,10 12,50 9,48
2. Pisang
Luas Panen (ha) 253.253 162.873 78.309 81.267
Produktivitas (ton/ha) 7,16 12,83 44,09 53,07
Pertumbuhan (%/thn) 3,22 7,15 10,27 1,30
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Laju pertumbuhan produksi pisang terus meningkat secara konsisten. Masalah pokok
pada aspek produksi pisang ialah sifat produsennya yang dominan, usahatani keluarga
dan posisi usahatani pisang sebagai usahatani sampingan saja. Selain itu, tanaman pisang
juga amat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan sifat demikian, tanpa
ada upaya khusus, peningkatan produksi pisang diperkirakan akan tetap lambat dan
tidak secepat laju peningkatan permintaannya.
� Produktivitas komoditas pisang pada periode 2000-2004 mengalami peningkatan sebesar
1,3% per tahun, atau jauh menurun dari sebesar 10,27% per tahun pada 1990-1999.
� Harga riil pisang cenderung meningkat konsisten baik di tingkat konsumen maupun di
tingkat produsen. Harga pisang di tingkat konsumen meningkat lebih cepat daripada di
tingkat produsen yang mengindikasikan peningkatan marjin pemasaran. Kecenderungan
harga pisang ditingkat produsen yang semakin stabil dan meningkat secara riil
merupakan indikasi prospek pasar yang baik untuk usahatani pisang. Insentif harga
tersebut diperkirakan akan berperan signifikan dalam mendorong peningkatan produksi
pisang di masa mendatang. Namun demikian, peningkatan harga produsen yang lebih
lambat dan lebih stabil dari harga konsumen merupakan indikasi ketidaksempurnaan
pemasaran pisang.
9.1.4. Komoditas Unggas (Ayam)
� Usaha ternak ayam ras pedaging baru berkembang pada pertengahan 1970-an, tumbuh
amat cepat dan kini menjadi tulang punggung subsektor peternakan. Setelah
mengalami masa krisis pada periode 1998 – 1999, usaha ternak ayam ras pedaging kini
telah pulih total dan tumbuh amat pesat. Usaha ternak ayam ras terutama ditopang oleh
sektor swasta baik dari segi inovasi teknologi maupun dari segi modal dan pemasaran.
Usahatani dapat berkembang pesat atas kemampuan sendiri dengan fasilitasi terbatas
dari pemerintah.
Tabel 24. Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Ayam Ras Pedaging
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
Produksi (000 ton) 1.079 1.361 1.774 2.396 3.358
Konsumsi (000 ton) 1.150 1.535 2.094 2.918 4.107
Surplus (defisit) (71) (174) (320) (522) (649)
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Harga ayam di tingkat pedagang besar pada lima tahun terakhir cenderung tidak stabil.
Ketidakstabilan harga ayam di tingkat konsumen meningkat jauh lebih kecil dari harga di
tingkat pedagang besar. Ini mengindikasikan adanya ketidaksempurnaan pasar.
Instabilitas harga yang tinggi merupakan resiko pasar yang tidak kondusif bagi
perkembangan usaha ternak ayam.
9.1.5. Komoditas Sapi
� Produksi daging sapi potong meningkat relatif lebih lambat dibandingkan peningkatan
permintaan. Kondisi ini menyebabkan impor daging sapi mengalami peningkatan.
Masalah pokok untuk komoditas sapi potong adalah penurunan laju pertumbuhan
populasi yang berkelanjutan sejak dekade 1980-an. Bahkan pada periode tahun 2000-an,
populasi sapi potong menurun secara absolut.
� Usahaternak sapi potong didominasi oleh usahaternak tradisional dan pada umumnya
hanya sebagai usaha sampingan. Usahaternak sapi potong cukup menguntungkan secara
finansial, namun membutuhkan modal yang cukup besar, sementara peternak tidak
memiliki akses terhadap kredit perbankan. Semakin terbatasnya padang penggembalaan
juga merupakan kendala utama bagi usaha ternak sapi potong.
� Hasil proyeksi menunjukkan bahwa tanpa ada upaya yang dapat meningkatkan produksi
secara signifikan, Indonesia akan terus mengalami defisit daging sapi dalam jumlah yang
semakin besar dan ketergantungan impor yang semakin tinggi.
Tabel 25. Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Daging Sapi
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
Produksi (000 ton) 372 380 388 396 405
Konsumsi (000 ton) 513 547 587 633 684
Surplus (defisit) (141) (167) (199) (237) (279)
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Khusus untuk daging sapi, data yang digunakan adalah harga perdagangan besar di tiga
propinsi produsen utama, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Harga
perdagangan besar di daerah produsen utama dipandang berkorelasi kuat dan oleh
karenanya dapat mengindikasikan dinamika dari harga sapi di tingkat produsen
(peternak). Harga konsumen diwakili oleh data di Jakarta yang merupakan konsumen
utama daging sapi. Jakarta merupakan daerah pemasaran sapi dari berbagai propinsi di
Indonesia. Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa terdapat dinamika harga sapi
antar wilayah yang mengindikasikan telah terjadi perubahan mendasar dalam pola
perdagangan sapi antar pulau. Perubahan pola perdagangan sapi antar pulau tersebut
juga telah mendorong persaingan antara pedagang. Hal inilah yang menyebabkan harga
sapi di sentra produksi seperti Nusa Tenggara Barat meningkat lebih cepat daripada di
Jakarta yang merupakan wilayah pemasaran akhir utama. Perubahan pemasaran sapi
tersebut menguntungkan peternak di wilayah sentra produksi. Harga sapi yang stabil dan
meningkat secara riil di wilayah sentra produksi seharusnya menjadi insentif yang baik
bagi peternak.
9.1.6. Komoditas Kambing-Domba
� Permasalahan yang dihadapi oleh usahaternak kambing dan domba serupa dengan
permasalahan pada usaha ternak sapi potong. Usahaternak sapi dan domba dilakukan
oleh usaha keluarga dan hanya sebagai usaha sampingan. Usahaternak kambing dan
domba juga menghadapi permasalahan permodalan. Selain itu, semakin langkanya
padang pengembalaan juga menjadi kendala bagi usaha ternak kambing dan domba.
� Hingga lima tahun mendatang, produksi daging kambing dan domba masih tetap
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hasil proyeksi menunjukan,
produksi daging kambing dan domba masih di bawah permintaan domestik. Tanpa ada
program yang dapat meningkatkan produksi secara nyata sangat sulit bagi Indonesia
dapat menjadi negara pengekspor daging kambing dan domba.
Tabel 26. Produksi dan Konsumsi Domestik Komoditas Daging Kambing/Domba
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
Produksi (000 ton) 58 57 56 55 54
Konsumsi (000 ton) 59 60 61 62 64
Surplus (defisit) (000 ton) (1) (3) (5) (7) (10)
Sumber : Pusat Studi Sosial Ekonomi Departemen Pertanian.
� Harga kambing tergolong yang paling stabil diantara semua komoditas ternak. Ini adalah
refleksi dari pola pemasaran kambing yang tergolong bebas, berbeda dari komoditas
peternakan lainnya yang tersegmentasi dalam kawasan lokal/terbatas (tidak ada
perdagangan antar pulau). Selain itu, karena tidak ada impor kambing atau domba
sehingga harga domestik tidak dipengaruhi oleh harga dunia. Secara umum, harga yang
cenderung stabil dan meningkat secara riil dapat menjadi insentif yang kondusif bagi
perkembangan usaha ternak kambing dan domba.
9.1.7. Permasalahan dalam Meningkatkan Kapasitas Produksi
� Berdasarkan perkembangan kondisi komoditas sub sektor tabama dan peternakan di
atas, hal penting perlu dilakukan di bidang produksi adalah meningkatkan kapasitas
produksi.
� Untuk meningkatan kapasitas produksi di masa mendatang, terdapat beberapa resiko
yang perlu diperhatikan. Faktor resiko pertama adalah berkaitan dengan sumberdaya
lahan dan air. Dalam jangka pendek dan panjang Indonesia menghadapi empat ancaman
serius yang berkaitan dengan sumberdaya lahan dan air yaitu peningkatan laju konversi
baik di Jawa maupun Luar Jawa, rusaknya jaringan irigasi, rusaknya beberapa sistem
hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penguasaan lahan yang sempit. Oleh karena
itu, dalam jangka pendek dan panjang diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi
tekanan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan produktivitas lahan di Jawa melalui
pengembangan produksi komoditas yang bernilai tinggi dengan muatan teknologi yang
tinggi pula, meningkatkan alokasi fiskal untuk pembangunan jaringan irigasi dan
pencetakan sawah baru, perbaikan sistem hidrologi DAS yang rusak, sedangkan untuk
mencapai skala ekonomi minimum diperlukan upaya rekayasa kelembagaan kerjasama
antar petani.
� Faktor resiko kedua adalah kemampuan produksi industri pupuk nasional yang makin
menurun karena usia pabrik sudah tua dengan tingkat efisiensi yang rendah sekitar 70
persen. Selain itu, masalah lain adalah kelangkaan pasokan gas sebagai bahan baku
terbesar produksi pupuk urea juga menjadi faktor resiko yang menghadang keberhasilan
peningkatan produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peremajaan industri
pupuk nasional.
� Faktor resiko ketiga adalah sistem perbenihan nasional. Selain mutu benih nasional
belum memenuhi standar mutu yang baik, juga kuantitas benih belum seluruh komoditas
berkembang. Mungkin hanya padi dan jagung yang relatif berkembang dan itupun
belum memenuhi standar yang diharapkan. Akibat mutu benih nasional yang kurang
baik, petani melakukan penangkaran sendiri (contoh petani padi). Kondisi yang demikian
dinilai kurang baik dilihat dari aspek kemurnian dan mutu produksi, sehingga akan
menghambat peningkatan kapasitas produksi. Oleh karena itu, maka disarankan agar
pemerintah membangun sistem perbenihan nasional yang bermutu.
� Selain arah pengembangan peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi juga
diupayakan melalui ekstensifiksi dimana potensi lahan pengembangan tersebar di
propinsi Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Untuk padi, padi gogo dan jagung masing-
masing 12, 5 dan 7 juta hektar; jeruk dan pisang masing-masing 5 dan 13 juta hektar;
dan untuk padang pengembalaan 3 juta hektar.
� Berdasarkan hasil analisa terhadap subsektor tabama, pembiayaan investasi khususnya
untuk infrastruktur (perbaikan dan perluasan irigasi, pembukaan lahan, transportasi desa-
kota, riset dan teknologi) merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan
kapasitas produksi. Namun karena sifat pembiayaan investasi merupakan pembiayaan
jangka panjang, dan sektor pertanian memiliki resiko yang cukup tinggi, sebagian besar
investasi dilakukan oleh pemerintah dan hanya sedikit investor yang berminat untuk
menyediakan pembiayaan. Sementara itu, kemampuan permodalan juga merupakan
faktor penting lainnya untuk meningkatkan produksi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagian besar sumber pembiayaan usahatani berasal dari petani sendiri. Dengan
keterbatasan modal yang dimiliki petani, maka pembiayaan usahatani jelas tidak akan
memadai. Akses petani terhadap pembiayaan dari perbankan juga terbatas karena
usahatani yang dikelola petani walaupun memiliki kelayakan ekonomi yang cukup baik,
namun usahatani tersebut dinilai tidak layak dibiayai bank (bankable), sehingga
penyerapan kredit perbankan untuk sektor pertanian sangat kecil.
9.1.8. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Produksi
� Berdasarkan masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas
produksi dan prospek pasar domestik yang masih terbuka lebar serta lahan untuk
pengembangan lebih lanjut masih tersedia, maka disusun pokok-pokok kebijakan antara
lain sebagai berikut:
� Peningkatan kapasitas produksi industri perberasan nasional tidak cukup
dilakukan dengan memberikan dukungan harga gabah, subsidi pupuk, subsidi
benih dan subsidi kredit modal kerja. Kebijakan pemerintah harus diorientasikan
dari fokus kebijakan harga ke fokus peningkatan kapasitas produksi, yakni: (a)
rehabilitasi dan ekstensifikasi infrastruktur irigasi; (b) pembukaan lahan sawah
baru; (c) memacu inovasi teknologi, termasuk revitalisasi sistem penelitian dan
pengembangan pertanian serta sistem diseminasi inovasi pertanian dengan
deregulasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor swasta.
� Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan
produksi jagung ialah: (a) Stabilisasi harga di tingkat petani; (b) Menciptakan iklim
yang kondusif bagi peningkatan investasi swasta dalam industri perbenihan dan
agrokimia; dan (c) Menjamin praktek persaingan yang sehat dalam bisnis benih,
agrokimia dan pemasaran jagung.
� Kebijakan pokok yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempertahankan
pertumbuhan produksi jeruk: (a) Akselerasi peningkatan luas tanam jeruk melalui
pengembangan sistem perbenihan penyediaan modal investasi dan dukungan
infrastruktur usahatani; (b) Peningkatan efisiensi pemasaran jeruk melalui
pengembangan sistem pemasaran berbasis rantai pasok, perbaikan infrastruktur
pemasaran dan deregulasi pemasaran; (c) Pengembangan sistem pencegahan
serangan hama dan penyakit; (d) Perbaikan kualitas produk; dan (e)
Pengembangan industri pengolahan domestik dan memacu ekspor.
� Kebijakan yang perlu dilakukan untuk memacu laju pertumbuhan produksi pisang
ialah: (a) Membangun sistem pencegahan serangan hama dan penyakit; (b)
Pengembangan usahatani pisang komersial dan terspesialisasi; (c) Peningkatan
kualitas produk; dan (d) Pengembangan rantai pasok terkelola.
� Untuk pengembangan usahaternak ayam ras pedaging, kebijakan pemerintah
yang dapat ditempuh adalah: (a) Membangun sistem pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular (terutama penyakit flu burung); (b)
Pengembangan struktur industri perunggasan yang bersaing dan pencegahan
praktek persaingan yang tidak sehat; (c) Peningkatan peran usaha peternakan
rakyat.
� Kebijakan yang disarankan untuk meningkatkan produksi daging sapi potong
ialah: (a) Peningkatan populasi sapi potong melalui pengembangan usahaternak
intensif dan usaha pembibitan sapi; (b) Pengembangan sistem usaha integrasi sapi
dan tanaman; dan (c) Pemetaan sistem pemasaran sapi.
� Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk memacu produksi kambing dan
domba : (a) Pengembang usahaternak kambing dan domba skala komersial; (b)
Pengembangan sistem integrasi ternak kambing/domba dengan tanaman; (c)
Pengembangan sistem perbenihan ternak kambing dan domba.
� Berkaitan dengan permodalan, dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi
sub sektor tabama dan peternakan terutama dalam jangka panjang, kebutuhan
pendanaan tidak terbatas pada kebutuhan permodalan namun juga kebutuhan
investasi. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem perkreditan pertanian yang
dikelola oleh sistem perbankan pertanian yang kuat sehingga akses petani
terhadap pembiayaan perbankan dan permodalan meningkat sehingga dapat
meningkatkan produksi. Selain itu, perlu juga dipikirkan alternatif pendirian
lembaga pembiayaan khusus untuk sektor pertanian, termasuk pembiayaan
kepada sub sektor tabama dan peternakan.
9.2. Gambaran Umum Subsektor Perkebunan
� Produk-produk perkebunan termasuk minyak kelapa sawit (CPO), karet, kakao, dan gula
telah berperan penting dalam perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi,
penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, pengurangan kemiskinan,
perolehan devisa (kecuali gula), penyediaan bahan baku industri, dan ketahanan pangan
(khusus gula dan CPO).
� Dalam hal pertumbuhan ekonomi, PDB subsektor perkebunan tumbuh secara konsisten
yaitu 4,5% pada 2004, dan diperkirakan tumbuh sebesar 6,19% pada 2006. Dengan
komposisi yang sebagian besar (sekitar 85%) merupakan usaha perkebunan rakyat di
pedesaan, sektor perkebunan menampung lebih dari 17,5 juta tenaga kerja yang berarti
mempunyai kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan menjadi sumber
pendapatan di pedesaan. Devisa yang dihasilkan dari subsektor perkebunan adalah rata-
rata USD4,5 milyar per tahun, bahkan pada 2006 diperkirakan lebih dari USD6 milyar.
Minyak goreng dan gula merupakan kebutuhan pokok yang berkaitan dengan inflasi dan
ketahanan pangan.
� Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan
paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Secara keseluruhan, areal
perkebunan meningkat dengan laju 2,6% per tahun pada periode 1994–2004, dan
mencapai lebih dari 16 juta ha pada 2004. Dari beberapa komoditas perkebunan yang
penting di Indonesia (karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu), kelapa
sawit dan kakao tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya
dengan laju pertumbuhan diatas 5% per tahun. Pertumbuhan yang pesat dari kedua
komoditas tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusahaan
komoditas tersebut relatif lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong
perluasan areal komoditas tersebut.
� Sejalan dengan pertumbuhan areal, produksi perkebunan juga meningkat dengan
konsisten dengan laju 5,9% per tahun dalam 25 tahun terakhir atau 7,09% pada dekade
terakhir. Seperti juga areal, pertumbuhan produksi tercepat dicapai oleh tanaman kakao
dengan laju 9,2% per tahun dan kelapa sawit dengan laju peningkatan produksi sekitar
11,4% per tahun. Perkembangan produksi tanaman lainnya berkisar antara 0,5-5%,
kecuali tanaman tebu dan teh yang mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi
gula disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti penurunan
produktivitas dan bias kebijakan pemerintah, maupun pasar gula internasional yang
sangat distortif sehingga harga gula terus mengalami penurunan.
� Secara umum, laju pertumbuhan konsumsi dalam negeri relatif cepat untuk komoditi
CPO, karet, dan kakao dan relatif lambat untuk gula, kopi, dan teh. Karet dan CPO
bahkan tumbuh diatas 10% per tahun pada dekade terakhir. Lambatnya laju konsumsi
domestik untuk ketiga komoditi adalah indikasi bahwa industri hilir perkebunan belum
berkembang karena menyangkut masalah teknologi, hambatan pasar (entry barrier),
dukungan kebijakan yang belum optimal, serta jiwa kewirausahaan yang belum
berkembang.
� Produk tanaman perkebunan umumnya berorientasi ekspor dimana lebih dari 50%
produksi, kecuali gula, adalah diekspor. Sebagai contoh, proporsi produksi dari kopi dan
karet yang diekspor pada tahun 2004 masing-masing adalah 68,74% dan 96,13%.
Kinerja ekspor komoditas perkebunan Indonesia juga tumbuh dengan relatif stabil walau
dukungan kebijakan ekspor belum maksimal. Dari segi nilai, ekspor komoditas
perkebunan meningkat 6,52% per tahun yang menunjukkan bahwa nilai ekspor
berkembang lebih cepat dari volume ekspor. Namun dalam dekade terakhir, fenomena
ini berbalik dimana volume berkembang lebih cepat dibandingkan dengan nilai. Hal ini
memberi indikasi adanya kecenderungan melemahnya harga komoditas perkebunan
primer Indonesia di pasar internasional.
� Walaupun impor komoditas primer perkebunan Indonesia terus meningkat, volume dan
nilainya relatif masih kecil, kecuali impor gula. Sebagai contoh, impor CPO Indonesia
meningkat dengan laju 12,04% per tahun pada dekade terakhir, dengan volume impor
adalah sekitar 350 ribu ton pada tahun 1999 atau sekitar 6,15% dari produksi. Secara
umum, impor komoditas perkebunan Indonesia relatif masih kecil sehingga belum
merupakan pesaing yang signifikan untuk pasar domestik Indonesia.
� Seperti kebanyakan komoditas pertanian, harga produk perkebunan primer mengalami
fluktuasi yang cukup tajam di pasar internasional. Pada saat ini harga komoditas
perkebunan secara umum relatif tinggi seperti karet yang sampai melebihi USD2/kg,
demikian juga dengan gula dengan harga USD400/ton. Namun demikian, fluktuasi
harga tampaknya sudah menjadi karakter produk primer perkebunan, seperti tercermin
dari nilai koefisien keragaman harga tahunan yang cukup tinggi yaitu antara 18% untuk
karet sampai dengan 42% untuk teh. Fluktuasi harga ini berkaitan dengan fluktuasi
harga di pasar internasional berhubungan dengan faktor siklus biologis tanaman
khususnya untuk tanaman keras, iklim, dan kondisi ekonomi (harapan harga).
9.2.1. Peluang Peningkatan Kontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Daya
Saing di Pasar Internasional
� Subsektor perkebunan memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk melakukan perluasan lahan perkebunan
secara signifikan. Hal ini tidak dimiliki oleh negara pesaing, seperti Malaysia dan
Thailand. Selain itu, upah tenaga kerja yang relatif lebih murah akan membuat biaya
produksi menjadi relatif lebih rendah sehingga produk perkebunan Indonesia mempunyai
kecenderungan semakin kompetitif di masa mendatang.
� Produk perkebunan Indonesia pada masa mendatang diperkirakan memiliki prospek
pasar yang cerah di pasar internasional dengan daya saing yang semakin meningkat.
Paling tidak ada tiga faktor fundamental yang melandasi pemikiran tersebut. Faktor
pertama adalah keberhasilan Pertemuan World Trade Organization (WTO) Tingkat
Menteri di Hongkong pada bulan Desember 2005 yang menyepakati bahwa semua
bentuk subsidi ekspor pada sektor pertanian sudah harus dihapuskan paling lambat
tahun 2013. Penghapusan subsidi tersebut akan mengurangi kemampuan negara maju
untuk mengekspor produk pertanian seperti gula dan minyak nabati. Hal ini akan
memperbesar peluang pasar produk CPO Indonesia serta peningkatan produksi gula
Indonesia. Faktor kedua adalah negara pesaing, baik negara maju seperti Eropa Barat dan
Amerika, dan negara berkembang seperti Brazil yang secara konsisten menghadapi
tekanan untuk melakukan reformasi sektor pertanian dengan mengurangi dukungan
harga, subsidi, dan proteksinya secara substansial. Situasi ini akan meningkatkan daya
saing produk perkebunan Indonesia sekaligus mengurangi perlakuan yang tidak fair dari
negara maju, seperti untuk kasus kakao, kopi dan gula. Faktor fundamental ketiga
adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersumber dari fosil (BBM).
Kecenderungan kenaikan harga BBM merupakan kecenderungan jangka panjang yang
tidak dapat dihindarkan mengingat BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Jika ini benar, biofuel yang menggunakan bahan baku produk pertanian
seperti CPO dan tebu, akan terus berkembang. Di samping itu, karet sintetis yang
berbahan baku minyak bumi daya saingnya semakin lemah sehingga akan meningkatkan
peluang pasar karet alam Indonesia.
� Dengan perubahan fundamental tersebut serta dukungan kebijakan pemerintah yang
lebih kondusif, subsektor perkebunan diperkirakan akan berkembang secara lebih pesat.
Sebagai contoh, Indonesia berpeluang untuk melakukan perluasan areal kelapa sawit
sekitar 2 juta ha untuk jangka antara 5-10 tahun ke depan, atau tumbuh antara 7-9%
per tahun. Industri gula juga berpeluang tumbuh dengan laju sekitar 6-7% per tahun
sampai dengan tahun 2014. Untuk karet, peluang pasar akan semakin terbuka dengan
peluang perluasan sekitar 300-500 ribu ha untuk periode 2006-2010 atau sekitar 2-3%
per tahun. Untuk produk penyegar seperti kakao dan kopi, peluang peningkatan
produksi dan ekspor diperkirakan diatas 3% per tahun.
9.2.2. Permasalahan dalam Peningkatan Produksi Subsektor Perkebunan
� Upaya untuk merealisasikan peluang peningkatan produksi dan ekspor perkebunan
dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia, tampaknya masih
banyak menghadapi masalah, baik yang berkaitan dengan pengembangan industri hulu
maupun hilir. Beberapa masalah yang perlu mendapat penanganan yang antara lain
adalah (i) rendahnya produktivitas hasil dibandingkan produktivitas hasil negara lain; (ii)
mutu yang masih rendah/belum sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
pemerintah dan sering tidak konsisten; (iii) ekonomi biaya tinggi; (iv) kebijakan
pemerintah yang belum menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan (v) hambatan
perdagangan (tarif dan non-tarif) dan persaingan tidak sehat di pasar internasional.
� Berkaitan dengan rendahnya produktivitas pada industri hulu, terutama disebabkan oleh
komposisi tanaman yang masih didominasi tanaman asal biji/bibit tidak unggul/bibit palsu
dan sudah berumur tua, dan ketersediaan sarana produksi terutama bibit unggul
bermutu dan pupuk yang masih terbatas. Selanjutnya masalah mutu yang rendah dan
tidak konsisten disebabkan oleh (i) teknologi pengolahan yang ada belum memberi
insentif bagi pelaku usaha terutama petani untuk meningkatkan mutu; (ii) kebijakan
pemerintah tentang mutu (SNI) belum mencerminkan adanya sinergisme/koordinasi antar
lembaga di sektor pertanian dan industri.
� Ekonomi biaya tinggi merupakan masalah lain yang menghambat. Masalah ini berkaitan
dengan (i) mahalnya harga input (bibit, pupuk dan obat-obatan); (ii) tingginya beban
pelaku usaha termasuk petani dalam menanggung beban bunga pinjaman, pajak,
retribusi dan pungutan-pungutan, serta perijinan investasi; (iii) tingginya biaya transpor
dari kebun hingga pelabuhan atau ke lokasi industri pengolahan (primer dan hilir).
� Sejalan dengan hal diatas, iklim usaha perkebunan juga belum kondusif sebagai akibat
dari (i) pelaku usaha masih ragu tentang kepastian/perlindungan hukum dan jaminan
keamanan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, jaminan keamanan dari konflik
sosial dengan masyarakat lokal soal lahan; (ii) khusus untuk perusahaan perkebunan
kelapa sawit, adanya tekanan yang berkaitan dengan isu lingkungan (iii) ego sektoral dan
konflik kepentingan Pusat dan Daerah (iv) inkonsistensi penerapan payung
kebijakan/peraturan, seperti Revitalisasi Pertanian, UU No.18 Tahun 2004 Tentang
Perkebunan, dan UU/Perda Tentang Tata Ruang.
� Di pasar internasional, produk perkebunan Indonesia menghadapi berbagai hambatan
perdagangan (tarif dan non-tarif). Beberapa instrumen kebijakan yang menghambat
antara lain: (i) non-tariff/technical barriers yang diterapkan negara pengimpor minyak
sawit (Eropa, India dan negara pengimpor lainnya); (ii) automatic detention oleh Amerika
Serikat dan perlakuan diskriminasi (special and differential treatment) oleh negara-negara
Eropa Barat serta holding orders oleh Australia untuk kakao, tarif impor eskalasi di
negara-negara maju (iii) hegemoni/penguasaan perusahaan multinasional atau
transnasional di pasar internasional, terutama untuk karet, kakao, dan teh sehingga pasar
menjadi bersifat buyer’s market; (iv) proteksi dan/atau subsidi produksi oleh negara-
negara produsen utama, Eropa Barat, Amerika, Thailand, Brazil, Ghana dan Pantai
Gading.
� Dalam pengembangan industri hilir perkebunan, ada beberapa masalah mendasar seperti
(i) beban pajak pertambahan; (ii) dominasi perusahaan multinasional/transnasional yang
cenderung menerapkan multisourcing dalam penggunaan bahan baku melalui
mekanisme internal transaction; (iii) belum memadainya fasilitas/insentif bagi pelaku
usaha untuk menanamkan modalnya di industri hilir perkebunan (bunga, pajak, retribusi
dan pungutan-pungutan); (iv) lemahnya penelitian dan pengembangan bidang industri
hilir perkebunan; (v) mahalnya sebagian besar teknologi industri hilir perkebunan; dan (vi)
dominasi perusahaan multinasional/ transnasional penghasil produk jadi perkebunan
terhadap teknologi industri hilir perkebunan.
� Mengingat investasi di bidang usaha perkebunan merupakan investasi yang berjangka
panjang dan memerlukan jumlah yang besar, maka diperlukan alternatif pembiayaan
terutama untuk kredit investasi dengan mempertimbangkan masa grace period. Hal lain
yang harus dipertimbangkan adalah bukan hanya meningkatkan efisiensi dari investasi
yang sudah ada saat ini, tetapi juga investasi baru yang mengisi pasar komoditas
perkebunan yang baru, yang diperkirakan akan semakin terbuka pada masa yang akan
datang. Kebutuhan pembiayaan subsektor perkebunan juga diperlukan untuk membiayai
pengembangan industri hilir, peremajaan, promosi dan peningkatan kapasitas SDM serta
penelitian/pengembangan teknologi perkebunan. Sehingga kebutuhan akan alternatif
pembiayaan sektor perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja
sektor ini.
9.2.3. Komoditas Kelapa Sawit
� Areal terluas untuk kelapa sawit berada di Sumatera, yaitu mencapai 76,47% diikuti
Kalimantan dan Sulawesi, masing-masing 19,80% dan 2,31%. Pada tahun 2005, luas
areal perkebunan rakyat mencapai 3.873 ribu ha (31,11%), perkebunan negara seluas
2.049 ribu ha (16,46 %) dan perkebunan besar swasta seluas 6.528 ribu ha (52,43%).
Komposisi pengusahaan kelapa sawit juga mengalami perubahan, yaitu dari sebelumnya
hanya perkebunan besar, tetapi saat ini telah mencakup perkebunan rakyat dan
perkebunan swasta. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun 1996
hingga tahun 2005 tumbuh sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 10,66% per
tahun. Pertumbuhan areal terbesar dipegang oleh perkebunan swasta (11,99% per
tahun) diikuti pertumbuhan areal perkebunan rakyat (11,19%) dan perkebunan negara
(5,25%).
� Sejalan dengan perkembangan areal, produksi kelapa sawit juga mengalami
peningkatan, dari hanya 181 ribu ton CPO pada tahun 1968 menjadi 12.450 juta ton
CPO pada tahun 2005. Dalam 10 tahun terakhir, produksi CPO Perkebunan Besar Swasta
mendominasi komposisi produksi. Komposisi produksi CPO rata-rata secara berurutan
adalah Perkebunan Rakyat sebesar 2.480 ribu ton (29,93%), Perkebunan Besar Negara
sebesar 1.813 ribu ton (21,88%) dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 3.993 ribu ton
(48,19%).
Tabel 27. Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan, 1996–2005
PRODUKSI MINYAK SAWIT (RIBU TON)
TAHUN PERKEBUNAN RAKYAT (PR)
PERKEBUNAN MILIK NEGARA (PBN)
PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS)
JUMLAH
1996 1.133 1.707 2.058 4.898
1997 1.283 1.587 2.579 5.449
1998 1.345 1.501 3.084 5.930
1999 1.544 1.468 3.439 6.451
2000 1.906 1.461 3.644 7.011
2001 2.798 1.519 4.079 8.396
2002 3.426 1.608 4.588 9.622
2003 3.517 1.750 5.173 10.44
2004 3.745 1.981 6.079 11.80
2005*) 3.873 2.049 6.528 12.45
Pertumbuhan (%/th) 14,63 2,05 13,69 10,92
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan (2006)
Keterangan : *) Sementara
� Konsumsi domestik CPO yang merupakan komoditas primer masih belum berkembang.
Konsumsi CPO di dalam negeri sebagian besar untuk pangan (80%-85%) dan sisanya
industri oleokimia (15%-20%). Pertumbuhan konsumsi minyak sawit dalam negeri
adalah sekitar 11,07% per tahun. Laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia diproyeksikan
mencapai sekitar 5,0% per tahun hingga tahun 2010. Peningkatan yang signifikan
terutama akan terjadi pada negara yang sedang berkembang seperti di China, Pakistan,
dan juga Indonesia. Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan konsumsi
dengan laju sekitar 8% per tahun, sedangkan China, Eropa Barat, dan Pakistan
diproyeksikan akan tumbuh dengan laju masing-masing 7,4%, 6,7%, 7,7% per tahun.
Tabel 28. Perkembangan Konsumsi CPO Indonesia Tahun 1996–2005
TAHUN KONSUMSI (JUTA TON)
JUMLAH PENDUDUK (JUTA)
KONSUMSI/KAPITA (KG)
1996 2,53 198.320 12,76
1997 2,84 201.353 14,10
1998 2,83 204.393 13,85
1999 2,90 206.517 14,04
2000 2,93 205.843 14,23
2001 2,86 208.725 13,70
2002 2,93 212.003 13,82
2003 3,17 215.286 14,72
2004 3,36 217.854 15,42
2005 3,57*) 219.142 16,29
Pertumbuhan (%/tahun) 3,90 1,12 2,75
Sumber: ISTA Mielke GmbH (2005) dan Badan Pusat Statitistik (2006), diolah.
Keterangan : *) Sementara
� Perkembangan harga minyak sawit (CPO) di pasar domestik dan internasional (CIF
Rotterdam) sejak tahun 1996 sampai dengan 2005 menunjukkan kecenderungan yang
berfluktuasi. Secara umum pergerakan harga minyak sawit domestik searah dengan
perkembangan harga minyak sawit di pasar internasional. Walaupun terdapat pengaruh
musim, pembentukan harga CPO internasional yang dilakukan melalui mekanisme pasar
bebas dan berpusat di Rotterdam sangat ditentukan oleh penawaran dan permintaan
CPO internasional, disamping terkait dengan harga minyak nabati lain (minyak kedele)
dan pergerakan harga sebelumnya. Harga CPO di Rotterdam ini menjadi rujukan bagi
pembentukan harga di pasar domestik (Jakarta dan Medan), termasuk di bursa
komoditas.
� Dalam kaitan kebijakan, berbagai kebijakan areal dan produksi telah diterapkan oleh
pemerintah. Pola-pola lama yang sudah tidak dilanjutkan lagi diantaranya adalah
Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dan Perkebunan Besar Nasional (PBN). Pengembangan
perkebunan saat ini dilakukan melalui penerapan 5 pola, yaitu (1) pola koperasi usaha
perkebunan (Pola KUP), (2) pola patungan koperasi sebagai majoritas pemegang saham
dan investor sebagai minoritas pemegang saham (Pola Pat K-I), (3) pola patungan
investor sebagai mayoritas pemegang saham dan koperasi sebagai minoritas pemegang
saham (Pola Pat I-K), (4) pola built, operated, and transferred (Pola BOT), dan (5) pola
bank tabungan negara (Pola BTN). Pola pengembangan perkebunan ini lebih berdimensi
pada penerapan nilai keadilan dan sekaligus pula mengutamakan efisiensi, produktivitas,
dan peran serta masyarakat dalam satu paket kebijakan. Indonesia juga telah memiliki
Undang-undang khusus tentang perkebunan, yaitu UU No. 18 Tahun 2004 disamping
aturan perundang-undangan lainnya.
9.2.4. Komoditas Karet
� Areal karet Indonesia terluas di dunia, dengan luas areal mencapai sekitar 3,28 juta
hektar pada tahun 2005. Perkebunan karet di Indonesia sebagian besar diusahakan oleh
perkebunan karet rakyat (85%), dan sisanya merupakan perkebunan besar swasta dan
negara. Perkebunan karet rakyat tersebar di 12 propinsi di Indonesia, namun propinsi
utama karet rakyat Indonesia adalah Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan
Barat, dan Sumatera Utara.
� Dari sisi produksi, Indonesia merupakan negara penghasil karet alam terbesar kedua
setelah Thailand, dengan produksi sekitar 2,27 juta ton pada tahun 2005. Perkebunan
karet rakyat memberikan kontribusi produksi sekitar 81% (1,7 juta ton), sementara
produksi perkebunan besar negara dan swasta masing-masing mencapai sekitar 197 ribu
ton (9%), dan 208 ribu ton (10%).
� Pertumbuhan produksi karet alam Indonesia menunjukkan respon sejalan dengan
perkembangan harga karet alam dunia. Pada periode tahun 1982–2000 dimana harga
karet alam dunia masih relatif rendah, pertumbuhan produksi karet alam Indonesia rata-
rata adalah sekitar 3,8% per tahun. Sementara itu pada periode 2000-2005, dimana
harga karet alam dunia telah melonjak cukup tinggi, pertumbuhan produksi karet alam
Indonesia meningkat tajam sekitar 8,7% per tahun.
Tabel 29. Luas Areal dan Produksi Karet 1999 – 2004
TAHUN LUAS AREAL (000 HA)
PRODUKSI (000 TON)
PRODUKTIVITAS (KG/HA/TH)
2000 3.372 1.501 646
2001 3.345 1.607 686
2002 3.318 1.630 696
2003 3.290 1.792 764
2004 3.262 2.066 839
2005 3.279 2.271 842
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006.
� Sebagai negara produsen karet alam terbesar kedua di dunia, Indonesia berpotensi besar
untuk menjadi produsen utama dalam dekade mendatang. Hal ini sangat mungkin
dicapai karena Indonesia mempunyai potensi sumberdaya yang sangat memadai untuk
meningkatkan produksi, baik melalui pengembangan areal baru maupun peningkatan
produktivitas dengan meremajakan areal tanaman karet tua dengan menggunakan klon-
klon unggul terbaru.
� Konsumsi karet alam domestik relatif masih relatif rendah bila dibandingkan dengan
negara-negara produsen karet alam dunia lainnya. Pada tahun 2004 konsumsi domestik
baru mencapai sekitar 196 ribu ton (sekitar 9,5% dari total produksi), atau meningkat
sekitar 25% dari konsumsi tahun 2003. Konsumsi karet alam domestik pada tahun 2005
meningkat menjadi sekitar 217 ribu ton (9,7%), dan pada tahun 2006 diperkirakan
menjadi sekitar 242 ribu ton. Secara umum, tingkat pertumbuhan konsumsi karet alam
domestik selama enam tahun terakhir (2000–2005) adalah sekitar 9,72%.
Tabel 30. Produksi dan Konsumsi Karet Indonesia, 2000 – 2005
TAHUN PRODUKSI (000 TON) KONSUMSI (000 TON)
2000 1.501 139 (9,26)
2001 1.607 142 (8,84)
2002 1.630 145 (8,89)
2003 1.792 156 (8,70)
2004 2.066 196 (9,49)
2005 2.271 221 (9,73)
Pertumbuhan (%/thn) 8,63 9,72
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006.
� Harga karet alam di pasar internasional sangat berfluktuasi. Dalam satu dasawarsa
terakhir, harga karet alam pernah mencapai titik terendah pada bulan Nopember 2001,
yang mencapai sekitar USD0,46 cent/kg. Menurunnya harga karet alam dunia sejak
pertengahan tahun 1997 mendorong ketiga negara produsen utama karet alam dunia
yakni Thailand, Indonesia dan Malaysia untuk melakukan kerjasama tripartite dibidang
produksi dan pemasaran karet alam. Seiring dengan terbentuknya kerjasama tripartite
antara tiga negara produsen karet alam dunia tersebut, harga karet alam di pasaran
dunia memperlihatkan kecenderungan yang membaik.
� Agar diperoleh percepatan pembangunan agribisnis perkaretan nasional diperlukan
dukungan kebijakan sebagai berikut: 1) Penciptaan iklim investasi yang makin kondusif
antara lain melalui pemberian kemudahan dalam proses perijinan; pembebasan pajak (tax
holiday) selama tanaman atau pabrik belum berproduksi; pemberian rangsangan kepada
perajin industri hilir karet untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan
mempunyai prospek pasar yang cerah; penciptaan perangkat kepastian hukum dan
keamanan baik untuk usaha maupun lahan bagi perkebunan; penghapusan berbagai
pungutan dan pemberian keringan beban yang memberatkan pelaku agribisnis karet;
menghilangkan hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui pemerataan
pembangunan infrastruktur dan penciptaan regulasi yang kondusif bagi pembangunan
perkebunan, misalnya melalui penyederhanaan prosedur/birokrasi dan keringanan pajak;
2) Pengembangan sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, pelabuhan, alat
transportasi, komunikasi, dan sumber energi (tenaga listrik); 3) Penyediaan dana
pengembangan komoditas dengan menghidupkan kembali pungutan dari hasil
produksi/ekspor karet yang sangat diperlukan untuk membiayai pengembangan industri
hilir, peremajaan, promosi dan peningkatan kapasitas SDM karet serta penelitian dan
pengembangan teknologi di bidang perkaretan.
9.2.5. Komoditas Kakao
� Perkebunan kakao Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat selama 20 tahun
terakhir khususnya areal perkebunan kakao rakyat. Areal perkebunan kakao berkembang
cukup pesat dari 92.797 ha pada tahun 1985 menjadi 992.191 ha pada tahun 2004 atau
berkembang lebih dari 10 kali lipat dalam waktu 19 tahun.
� Sejalan dengan perkembangan areal, produksi kakao Indonesia meningkat pesat dari
33.798 ton tahun 1985 menjadi 650 ribu ton tahun 2004 atau meningkat lebih dari 19
kali lipat dalam waktu 19 tahun. Keberhasilan perluasan areal dan peningkatan produksi
kakao tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ke tiga
dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.
� Perkebunan kakao Indonesia sebagian besar (89,6%) dikelola oleh rakyat dan selebihnya
5,0% dikelola perkebunan besar negara serta 5,4% perkebunan besar swasta. Jenis
tanaman kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao lindak dengan sentra
produksi utama adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera
Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Irian Jaya dan Lampung.
Disamping itu juga diusahakan jenis kakao mulia oleh perkebunan besar negara
khususnya di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
� Konsumsi kakao/cokelat Indonesia relatif masih sangat rendah dan baru bangkit setelah
mengalami kemerosotan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997.
Pada tahun 1996/97 dan 1997/98, konsumsi cokelat Indonesia sebesar 12 ribu ton,
kemudian turun menjadi 9 ribu ton pada tahun 1998/99 dan 8,4 ribu ton pada tahun
1999/00. Selanjutnya konsumsi cokelat berangsur-angsur naik hingga mencapai 12 ribu
ton pada tahun 2003/04. Dengan total konsumsi sebesar 12 ribu ton tersebut berarti
konsumsi cokelat per kapita masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah yaitu 0,055
kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut sangat jauh dibawah tingkat konsumsi rata-
rata kakao dunia yang mencapai 0,565 kg/kapita/tahun.
Tabel 31. Perkembangan Produksi Perkebunan Kakao Indonesia
PRODUKSI (TON) TAHUN
PR PBN PBS JUMLAH
1970 487 1.061 190 1.738
1975 801 3.074 46 3.921
1980 1.058 8.410 816 10.284
1985 8.997 20.512 4.289 33.798
1990 97.418 27.016 17.913 142.347
1995 231.992 40.933 31.941 304.866
2000 363.628 34.790 22.724 421.142
2001 476.924 33.905 25.975 536.804
2002 511.379 34.083 25.693 571.155
2003 634.877 32.075 31.864 698.816
2004* 585.955 32.881 32.042 650.878
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006.
Keterangan: *) data sementara,
PR = Perkebunan Rakyat,
PBN= Perkebunan Besar Negara,
PBS = Perkebunan Besar Swasta.
� Di Indonesia, kakao merupakan salah satu komoditas yang tidak diatur tataniaganya oleh
pemerintah, sehingga harga kakao di tingkat petani ditentukan oleh mekanisme pasar
dan petani juga bebas menjual hasil panennya. Meskipun demikian, struktur pasar
komoditas kakao yang terbentuk cukup bervariasi dari yang bersifat monopsoni sampai
bersaing bebas.
� Pembentukan harga kakao dunia ditentukan oleh tingkat produksi, konsumsi biji kakao
dan posisi stok kakao dunia. Perkembangan harga kakao dunia sangat tergantung pada
perkiraan dari masing-masing variabel penentu harga kakao tersebut. Apabila perkiraan
produksi konsumsi menunjukkan adanya surplus, maka harga kakao dunia bergerak
turun dan sebaliknya harga kakao dunia bergerak naik jika produksi konsumsi
diperkirakan mengalami defisit.
� Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas kebun dapat
dilakukan melalui rehabilitasi dan intensifikasi serta perluasan areal dengan
menggunakan klon unggul. Rehabilitasi kebun dapat dilakukan dengan cara sambung
samping ataupun penyulaman kebun dengan bahan tanam klon unggul. Sementara,
intensifikasi dilakukan dengan penerapan sistem budidaya sesuai dengan anjuran
khususnya pemberian pupuk, pemangkasan bentuk dan pemberantasan hama dan
penyakit tanaman secara terpadu dan menyeluruh.
� Selanjutnya, permasalahan rendahnya mutu produksi kakao berkaitan dengan masalah
sosial ekonomi petani, insentif harga dan ketersediaan sarana pengolahan ditingkat
petani. Untuk mengatasi permasalahan ini, selain perlu adanya bantuan teknis dan
pendanaan, juga perlu dukungan kebijakan. Program perbaikan mutu produksi dilakukan
dengan penerapan SNI wajib fermentasi biji kakao. Program penerapan SNI wajib dapat
dilaksanakan setelah fasilitas pendukungnya terpenuhi. Disamping itu perlu adanya
program pendampingan dan mediasi agar pelaku bisinis khususnya pedagang kakao mau
memberikan insentif yang wajar bagi petani yang melakukan upaya perbaikan mutu
kakao. Upaya perbaikan mutu tersebut perlu diikuti dengan program atau penyusunan
rencana kerja untuk meniadakan potongan harga otomatis (automatic detention).
9.2.6. Komoditas Tebu
� Secara nasional total areal dan produksi tebu berkembang sangat dinamis mengikuti
dinamika berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Sejalan dengan kebijakan
pergulaan yang bersifat suportif dan stabilisasi (1970–1996), pemerintah berusaha
mendorong perkembangan areal dan produksi tebu/gula. Pada tahun 1985 areal tebu
sudah mencapai 340.229 ha dan terus meningkat mencapai puncaknya tahun 1996
mencapai 446.533 ha, atau meningkat dengan laju 5,2% per tahun. Produksi juga
meningkat secara konsisten dengan laju 2,8% per tahun. Namun produktivitas dalam
bentuk rendemen cenderung menurun dengan laju –1,4% per tahun. Produksi gula
nasional kembali mencapai puncaknya pada tahun 1994 dengan volume produksi 2,4
juta ton. Pada tahun 2005, produksi meningkat dengan laju 8,5% per tahun.
� Konsumsi gula di sisi lain terus meningkat, kecuali pada masa krisis ekonomi yang
mengalami penurunan. Secara umum, konsumsi gula meningkat dengan laju 3,4% per
tahun selama periode stabilisasi. Ketika krisis ekonomi terjadi, konsumsi menjadi stagnan,
bahkan menurun dengan laju –0,2% per tahun pada periode 1997-2002. Setelah
perekonomian nasional pulih kembali, konsumsi gula mulai meningkat dengan laju
1,98% per tahun pada periode 2002–2005. Pada tahun 2005 konsumsi mencapai 3,5
juta ton dan konsumsi per kapita pada kisaran 16,0 kg per kapita.
� Sebelum liberalisasi industri gula nasional yang dimulai tahun 1997, harga gula di tingkat
petani ditentukan oleh pemerintah melalui Bulog yang dikenal sebagai harga provenue.
Harga provenue ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan target harga eceran,
inflasi, biaya transpor, dan harga pupuk. Jika inflasi meningkat sebesar 1% maka harga
tingkat petani meningkat sekitar 0,84%, jika harga pupuk naik sebesar 1% maka harga
tingkat petani juga meningkat sekitar 0,60%. Pada tahun 1998–2002, pemerintah
melepas harga gula petani pada mekanisme pasar bebas yang mengacu pada harga gula
di pasar internasional. Selanjutnya pemerintah menerapkan kebijakan tataniaga impor
gula pada bulan September 2002 yang mengubah pembentukan harga di tingkat petani
seperti harga provenue, disebut harga patokan petani (HPP) yang merupakan harga gula
minimum di tingkat petani. HPP tersebut dijamin oleh perusahaan swasta yang bekerja
sama dengan kelembagaan petani dan PTPN.
� Mekanisme dan perkembangan harga gula eceran pada dasarnya identik dengan yang
terjadi pada harga tingkat petani. Sampai dengan tahun 1997 harga eceran tetap di
bawah kendali pemerintah sehingga harga eceran pada dasarnya sama dengan harga
provenue ditambah dengan biaya pemasaran. Dengan demikian, harga eceran menjadi
stabil terkendali dengan laju peningkatan sama dengan harga provenue sekitar 6,6%
per tahun. Setelah tahun 1997, pembentukan harga di tingkat eceran lebih banyak
ditentukan oleh harga gula impor, walaupun HPP yang ditentukan pemerintah juga
mempunyai pengaruh.
� Harga gula di pasar internasional cukup fluktuatif. Harga gula yang tinggi terjadi pada
awal tahun 1970-an dan tertinggi terjadi pada tahun 1974 yaitu sebesar USD 660/ton.
Pada dekade terakhir sebelum 2004, harga gula cenderung menurun dengan laju
penurunan sekitar 6,97% per tahun. Penurunan harga yang berkepanjangan ini
terutama disebabkan oleh peningkatan stok gula dunia sebagai dampak dari proteksi dan
subsidi yang dilakukan beberapa negara. Harga terendah pada dekade terakhir terjadi
pada tahun 1999 yaitu sebesar USD 114/ton.
� Semenjak tahun 2004, industri gula dunia mulai mengalami titik balik yang ditunjukkan
oleh peningkatan harga gula yang dipicu oleh defisit stok gula dunia antara 1–3 juta ton
dan harga minyak bumi yang melambung diatas USD 70/barrel. Melambungnya harga
minyak bumi tersebut telah mendorong penggunaan tebu sebagai bahan bakar alternatif
(etanol), terutama oleh negara Brazil. Pada tahun 2006, harga gula melambung tinggi di
atas USD400/ton.
Tabel 32. Luas Areal Tebu dan Produksi Gula Berdasarkan Propinsi
AREAL (HA) PRODUKSI (TON) PROPINSI
1980 2005
PANGSA 2005 (%)
1980 2005
PANGSA 2005 (%)
Jawa Timur 193.071 179.708 47,0 892.790 1.092.640 48,7
Jawa Tengah 62.309 32.613 8,5 358.529 152.236 6,8
Jawa Barat 21.008 22.726 5,9 68.240 123.110 5,5
DI Yogyakarta 5.550 9.339 2,4 26.028 30.423 1,4
Jawa 281.938 244.386 64,0 1.345.587 1.398.409 62,4
Lampung 12.237 102.848 26,9 38.693 694.192 31,0
Sumatera Selatan 0 12.297 3,2 0 55.637 2,5
Sumatera Utara 453 9.359 2,4 332 40.636 1,8
Sulawesi Selatan 5.244 5.472 1,4 26.314 26.162 1,2
Lainnya 16.045 7.721 2,0 32.674 27.275 1,2
Luar Jawa 33.979 137.697 36,0 98.013 843.902 37,6
Indonesia 315.917 382.083 100,0 1.443.600 2.242.311 100,0
Sumber : Ditjenbun (2005), diolah
� Beberapa kebijakan berkaitan dengan komoditas tebu yang dapat dilakukan antara lain
kebijakan perdagangan, kebijakan infrastruktur, kebijakan pendanaan dan investasi
dalam penyediaan sarana produksi.
9.3. Gambaran Umum Subsektor Perikanan dan Komoditas Unggulannya
� Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan yang sangat besar.
Sekitar 70% dari luas wilayah adalah lautan, dengan cakupan area mencapai sekitar 5,8
juta km2, yang membuat garis pantai sepanjang 81.000 km dan mengelilingi lebih dari
18.000 pulau. Didukung oleh iklim dan keadaan geografisnya, Indonesia memiliki
keanekaragaman dan produktivitas biota laut yang tinggi. Dari berbagai komoditas yang
potensinya yang telah berhasil diidentifikasi, diperkirakan perairan Indonesia mampu
memproduksi 6,4 juta ton ikan pertahun. Di antara komoditas-komoditas tersebut,
banyak di antaranya yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, misalnya tuna,
udang, dan rumput laut. Apabila dikelola dengan baik, komoditas-komoditas tersebut
mampu menopang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
� Selama kurun waktu lebih dari 20 tahun terakhir, penawaran maupun permintaan ketiga
komoditas tersebut (udang, tuna dan rumput laut) cenderung terus menunjukkan
peningkatan. Rata-rata pertumbuhan produksi ketiga komoditas tersebut masing-masing
sebesar 3,22%; 2,78%, dan 11,79%. Sementara itu, permintaan ketiga komoditas
tersebut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,10%, 3,02%, dan 10,07%.
� Hasil analisis Tabel I-O memperlihatkan bahwa peran ekonomi dari kegiatan usaha
komoditas udang, tuna dan rumput laut memiliki keterkaitan (linkages) yang tinggi
dengan sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian nasional baik secara keterkaitan ke
belakang (backward linkages) maupun keterkaitan ke depan (forward linkages). Besaran
nilai rata-rata koefisien keterkaitan ke belakang (backward linkages) untuk udang, tuna
dan rumput laut adalah masing-masing 1,46, 1,34, dan 1,44. Sementara rata-rata
koefisien keterkaitan ke depan (forward linkages) masing-masing mendekati nilai 1.
� Ketiga komoditas revitalisasi perikanan tersebut juga memiliki keunggulan komparatif
yang lebih besar dari rata-rata dunia. Analisis Revealed Comparative Advantage (RCA)
menunjukkan bahwa nilai indeks RCA untuk komoditas udang, tuna dan rumput laut
adalah berturut-turut sebesar 2,97; 8,43 dan 29,81). Angka-angka RCA yang
kesemuanya lebih besar dari satu menunjukkan bahwa berdasarkan pemetaan daya saing
ketiga komoditas unggulan tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sangat baik
dalam perdagangan internasional.
� Hasil-hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah untuk
merevitalisasi industri perikanan dengan menempatkan udang, tuna dan rumput laut
sebagai komoditas unggulan merupakan hal yang tepat. Hal ini membawa implikasi
perlunya dukungan upaya pengembangan investasi usaha budidaya dan penangkapan
ketiga komoditas unggulan tersebut termasuk usaha-usaha turunannya seperti usaha di
industri pengolahan hasil perikanan maupun perdagangan ekspor komoditas perikanan.
� Terlepas dari berbagai potensi di atas, sektor perikanan masih menghadapi beberapa
kendala seperti minimnya infrastruktur khusus perikanan seperti pelabuhan, stasiun
penyediaan bahan bakar solar, irigasi perikanan.
� Selain itu, petani/nelayan seringkali dihadapkan kepada kesulitan untuk menyediakan
agunan dalam jumlah tertentu sebagai jaminan kepada pihak perbankan pada saat
mengajukan kredit permodalan. Resiko produksi pada bisnis perikanan menyangkut
siklus produksi perikanan yang musiman, sehingga hasilnya seringkali tidak dapat
diperhitungkan dengan pasti. Hal inilah yang menyebabkan pihak perbankan enggan
menyediakan modal bagi perkembangan bisnis di sektor tersebut. Di samping resiko
produksi yang tergantung musim terutama hasil perikanan tangkap, juga mengandung
resiko harga yang tinggi. Tidak adanya kepastian harga dan sangat berfluktuatif
menyebabkan pendapatan nelayan dan petani ikan tidak dapat diperkirakan dengan
tepat. Karakteristik resiko pada bisnis perikanan yang demikian dan disertai dengan
status ekonomi petani ikan dan nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara
ekonomi, membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan. Untuk
mengatasi masalah permodalan tersebut perlu dipertimbangkan bentuk alternatif
pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan.
9.3.1. Komoditas Tuna
� Komoditas Tuna (termasuk cakalang) adalah salah satu komoditas unggulan di sektor
perikanan. Tingkat produksi Tuna masih sangat mungkin untuk ditingkatkan, terutama di
kawasan Timur Indonesia, meskipun pengembangan komoditas ini harus dilakukan
dengan selektif karena data menunjukkan bahwa usaha penangkapan sejumlah jenis
tuna, khususnya tuna besar telah menunjukkan penurunan.
� Potensi ikan pelagis besar (termasuk tuna) secara nasional mencapai 1.165,36 ribu ton.
Sumberdaya tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan dimasa mendatang bagi
kepentingan pembangunan perikanan nasional. Dari 9 Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) di Indonesia, semua WPP -selain WPP Selat Malaka dan WPP Laut Jawa- sebagian
besar masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Di WPP Selat
Malaka dan WPP Laut Jawa, tingkat pemanfatan sudah melebihi potensi yang ada
(overfishing). Potensi ikan pelagis besar di WPP Selat Malaka mencapai 27,67 ribu ton
sedangkan tingkat produksinya telah mencapai 36,27 ribu ton. Begitu pula halnya yang
terjadi di WPP Laut Jawa, produksi ikan pelagis besar mencapai 137,82 ribu ton
sedangkan potensinya hanya sekitar 55 ribu ton.
� Sejalan dengan meningkatnya produksi hasil tangkapan tuna, berkembang pula industri
pengolahan komoditas tersebut, terutama di lokasi-lokasi yang merupakan sentra
pendaratan tuna seperti Muara Baru-Jakarta, Pelabuhan Ratu–Jawa Barat, Cilacap-Jawa
Tengah, Benoa–Bali dan Bitung–Sulawesi Utara. Industri pengolahan dimaksud pada
umumnya mengolah tuna menjadi produk segar (dingin) dalam bentuk utuh disiangi
(fresh whole gilled and gutted); produk beku dalam bentuk utuh disiangi (frozen whole
gilled and gutted), loin (frozen loin) dan steak (frozen steak); dan produk dalam kaleng
(canned tuna).
� Konsumsi tuna pada tahun 2006 sebesar 629.782 ton, diproyeksikan meningkat menjadi
694.943 ton pada tahun 2009. Sedangkan ekspor tuna pada tahun 2006 sebesar
113.293 ton, pada tahun 2009 meningkat menjadi 134.673 ton. Dengan demikian,
permintaan total tuna pada tahun 2006 diproyeksikan sebesar 743.460 ton, dan pada
tahun 2009 meningkat menjadi 829.616 ton.
� Harga domestik tuna di Indonesia, disamping dipengaruhi oleh harga ekspor dan nilai
tukar rupiah terhadap USD juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak
yang berdampak mengurangi supply tuna. Hal yang sama juga terjadi pada saat nilai
tukar rupiah terhadap USD meningkat, dimana volume ekspor tuna meningkat, dan
supply domestik berkurang, untuk kemudian mendorong peningkatan harga domestik.
Tabel 33. Proyeksi Produksi Tuna, Cakalang dan Tongkol, Tahun 2005-2009
TAHUN PRODUKSI
TUNA (TON)
PRODUKSI CAKALANG
(TON)
PRODUKSI TONGKOL
(TON)
PRODUKSI TOTAL
SEBELUM REVITALISASI
(TON)
PRODUKSI TOTAL SETELAH
REVITALISASI (TON)
2005 185.654 258.180 281.733 725.567 -
2006 192.976 270.233 291.261 754.470 863.305
2007 200.298 274.445 297.197 771.940 885.111
2008 207.620 277.760 306.222 791.602 907.393
2009 214.942 283.979 313.255 812.176 930.916
Rata-rata 200.298 272.919 297.934 771.151 896.681
Pertumbuhan (%) 3.60 2.34 2.62 2.78 2.48
Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, data hasil olahan.
9.3.2. Komoditas Udang
� Udang dipilih menjadi komoditas unggulan untuk program revitalisasi karena posisi
Indonesia saat ini merupakan salah satu di antara sedikit negara yang memiliki potensi
produksi yang sangat besar.
� Rata-rata produksi udang Indonesia selama periode tahun 1999-2003 mencapai 400.551
ton. Tahun 2002, produksi udang mengalami penurunan mencapai 400.672 ton, hal ini
disebabkan oleh turunnya produksi udang hasil tangkapan. Produksi udang hasil
tangkapan paling besar dari Propinsi Riau sebesar 42.284 ton pada tahun 1999, dan dari
Propinsi Sumatera Utara sebesar 38.914 ton pada tahun 2003. Sementara itu, untuk
udang hasil budidaya rata-rata produksi selama 5 tahun (1999-2003) mencapai 157.213
ton. Produksi udang hasil budidaya paling besar dari Propinsi Jawa Timur sebesar 21.279
ton pada tahun 1999, dan dari Propinsi Jawa Barat sebesar 35.185 ton pada tahun 2003.
Berbeda halnya dengan produksi udang hasil tangkapan, ternyata dari hasil budidaya
mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode tersebut.
Tabel 34. Proyeksi Luas Areal dan Produksi Udang Budidaya dan Penangkapan
PRODUKSI UDANG (TON)
TAHUN AREAL
TAMBAK (HA)
BUDIDAYA PERAIRAN UMUM PENANGKAPAN TOTAL
TOTAL SETELAH
REVITALISASI
2005 468.993 192.189 33.305 266.751 492.245 -
2006 480.987 201.148 34.709 274.392 510.249 577.501
2007 492.981 209.557 36.113 281.902 527.572 586.415
2008 504.976 217.580 37.518 289.339 544.437 595.257
2009 516.970 225.330 38.922 296.738 560.990 604.060
Rata-rata 492.981 209.161 36.113 281.824 527.099 590.808
Pertumbuhan (%)
2,41 3,90 3,82 2,63 3,22 1,49
Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, data hasil olahan.
� Konsumsi udang diproyeksikan meningkat dari 338.288 ton pada tahun 2006 menjadi
366.273 ton pada tahun 2009. Sementara itu, ekspor udang pada tahun 2006
diproyeksikan sebesar 130.807 ton, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 143.129
ton. Permintaan total udang pada tahun 2006 sebesar 469.095 ton, pada tahun 2009
meningkat menjadi 509.402 ton. Total permintaan udang setiap tahunnya masih berada
dibawah tingkat produksinya; sebagai contoh, pada tahun 2009 diperkirakan terjadi
kelebihan produksi sebesar 51.588 ton. Kecenderungan tersebut mengindikasikan
adanya peluang untuk meningkatkan ekspor sebesar rata-rata 36% per tahun.
� Untuk komoditas udang, harga domestik ditentukan oleh harga ekspor dan jumlah
produksi udang, yaitu apabila harga ekspor meningkat maka peningkatan harga tersebut
akan ditransmisikan secara langsung ke harga domestik. Hal ini ditunjukkan oleh
kecenderungan yang memperlihatkan adanya hubungan antar peningkatan harga ekspor
dan volume ekspor udang Indonesia yang cenderung meningkat. Kecenderungan yang
ada juga menunjukkan bahwa peningkatan ekspor tersebut mengakibatkan supply di
dalam negeri menurun, dan mengakibatkan adanya kenaikan harga domestik. Hal yang
sama terjadi; apabila produksi udang meningkat maka harga domestik cenderung
menurun.
9.3.3. Komoditas Rumput Laut
� Rumput laut dipilih sebagai komoditas unggulan revitalisasi karena memiliki daya serap
tenaga kerja yang tinggi, teknologi budidaya yang mudah, masa tanam yang pendek
(hanya 45 hari) atau quick yield dan biaya per unit produksi sangat murah.
� Indonesia memiliki 5 propinsi utama penghasil rumput laut, yaitu Propinsi Bali, NTB, NTT,
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dalam periode 7 tahun (1997 – 2003), produksi
rata-rata tahunan tertinggi dicapai oleh Propinsi Bali (91.656 ton, basah), kemudian
Sulawesi Selatan (26.025 ton, basah) dan NTB (19,190 ton, basah). Selama kurun waktu
tersebut, produksi rumput laut di kelima propinsi utama cenderung meningkat dengan
kenaikan rata-rata 31 s.d 1,6%. Besarnya kisaran kenaikan rata-rata tersebut
menunjukkan bahwa produksi rumput laut di daerah tersebut cenderung tidak stabil.
Hampir semua propinsi utama penghasil rumput laut tersebut mengalami gejolak
produksi. Ketidakstabilan produksi rumput laut ini disebabkan oleh dominannya faktor
alam pada budidaya yang bersifat water-based aquaculture ini dimana seharusnya
menuntut campur tangan manusia yang relatif tinggi.
� Produksi rumput laut Indonesia pada Tahun 2001 mencapai 255.233 ton (basah), dan
cenderung meningkat selama 4 tahun sejak tahun 1998. Tahun 1998 produksi rumput
laut di kelima propinsi utama tersebut, dan propinsi lainnya, umumnya anjlok hingga ke
tingkat yang paling rendah. Pada tahun 2002 produksi rumput laut turun 223.080 ton
dan meningkat kembali pada tahun 2003 sebesar 233.156 ton.
� Konsumsi rumput laut pada tahun 2006 diproyeksikan sebesar 447.731 ton, dan pada
tahun 2009 menjadi 608.747 ton. Sementara itu, ekspor rumput laut pada tahun 2006
diproyeksikan sebesar 55.974 ton, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 71.539 ton.
Dengan demikian, permintaan total rumput laut pada tahun 2006 sebesar 503.705 ton,
dan pada tahun 2009 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 680.286 ton.
� Untuk komoditas rumput laut kondisi di lapangan menunjukkan bahwa harga rumput
laut di tingkat petani banyak ditentukan oleh standar mutu yang ditentukan oleh
kalangan industri (pabrikan). Kondisi lapangan juga menunjukkan bahwa harga rumput
laut di tingkat petani sangat rendah, terutama karena panjangnya mata rantai. Selain itu,
rendahnya harga pada komoditas rumput laut disebabkan adanya praktek yang
mengarah pada pasar oligopoli, sehingga harga tersebut banyak dipengaruhi oleh
pembeli dari kalangan industri dengan tingkat harga yang rendah.
Tabel 35. Proyeksi Produksi Rumput Laut, Tahun 2005-2009
Tahun Luas Areal
Rumput Laut (Ha)
Luas Areal Revitalisasi
Rumput Laut (Ha)
Produksi Rumput Laut
Sebelum Revitalisasi
(Ton)
Produksi Rumput Laut
Setelah Revitalisasi
(Ton)
2005 29.923 - 448.845 -
2006 33.580 4.800 503.706 727.706
2007 37.504 4.800 562.566 831.306
2008 41.428 7.200 621.426 943.826
2009 45.352 7.200 680.286 1.060.286
Rata-rata 37.557 6.000 563.366 890.781
Pertumbuhan (%) 9.87 11.11 9.87 11.79
Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan, data hasil olahan.
10. Penutup
� Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran penting sektor
pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal seperti penopang
pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional, penyedia kebutuhan
pangan masyarakat, penghasil devisa, dan pendorong tumbuhnya sektor industri.
� Meskipun memegang peranan yang penting, pembangunan sektor pertanian masih
menghadapi beberapa kendala / permasalahan. Secara umum permasalahan yang
dihadapi oleh sektor pertanian adalah kurang tersedianya pembiayaan jangka panjang
(investasi) dalam rangka penyediaan dan perbaikan infrastruktur, perluasan lahan, dan
penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian. Sehubungan
dengan hal tersebut, perlu dikembangkan alternatif pembiayaan jangka panjang sektor
pertanian, antara lain melalui pendirian lembaga pembiayaan khusus sektor pertanian.
� Namun, perbedaan karakteristik subsektor pertanian / komoditi yang ada dalam sektor ini
menyebabkan permasalahan yang dihadapi masing-masing subsektor / komoditi
berbeda-beda. Sehingga permasalahan pada sektor pertanian lebih tepat dilihat pada
masing-masing subsektor / per komoditi.
� Berdasarkan hasil kajian peta sektor pertanian yang dihasilkan oleh Bank Indonesia,
prioritas kebijakan sub sektor tabama dan peternakan sebaiknya diarahkan untuk
mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor, sementara untuk
sub sektor perkebunan dan perikanan prioritas kebijakan diarahkan pada peningkatan
ekspor.
� Hasil kajian peta sektor pertanian yang dihasilkan oleh Bank Indonesia ini diharapkan
dapat menjadi masukan bagi pemerintah, BI, perbankan (kreditor) dan investor dalam
mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian.
Lam
pir
an 1
Sekt
or
Pert
ania
n –
Mat
riks
Su
b S
ekto
r Ta
bam
a d
an P
eter
nak
an
AS
PEK
MA
SA
LA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTIN
DA
K L
AN
JU
T
Pengendalia
n k
onvers
i la
han
Penera
pan k
ete
ntu
an k
onvers
i
lahan irigasi
Pem
bukaan lahan s
aw
ah b
aru
Pem
bukaan lahan d
an P
em
buata
n
pera
tura
n r
encana t
ata
ruang d
an
tata
guna lahan
Inte
nsifikasi p
em
anfa
ata
n lahan
saw
ah
Perb
aik
an d
an p
erluasa
n s
ara
na
irig
asi
Revitalis
asi litbang:
mendoro
ng
pera
n s
wast
a d
ala
m b
isnis jasa
litbang d
an input
inovatif
Dere
gula
si litbang &
indust
ri
perb
enih
an
Pro
gra
m inovasi v
arieta
s unggul
baru
dip
erc
epat
Alo
kasi d
ana p
enelit
ian p
erb
aik
an
varieta
s padi dip
erb
esa
r
Perb
aik
an d
an p
erluasa
n s
ara
na
irig
asi
Perb
aik
an d
an p
em
bangunan
sara
na jala
n d
an a
ngkuta
n
pedesa
an
PRO
DUKSI
Penuru
nan p
ert
um
buhan p
roduks
i:
- p
enggunaan lahan p
ert
ania
n k
e
non p
ert
ania
n
- k
ete
rsedia
an b
ibit u
nggul
- s
ara
na p
roduks
i (p
upuk,
irigasi
,
dll)
Masa
lah infr
ast
rukt
ur
(sepert
i
sara
na irigasi
, ja
lan, pela
buhan,
dll)
.
AS
PEK
MA
SA
LA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTIN
DA
K L
AN
JU
T
Sis
tem
tra
nsport
asi dan
dis
trib
usi yang e
fisie
nPerb
aik
an d
an p
em
bangunan
sara
na jala
n d
an a
ngkutan
pedesaan
Kaji
ula
ng r
etribusi dan p
ungutan
terk
ait p
em
asa
ran h
asil pert
ania
n
Pengem
asa
n d
an p
erg
udangan
Belu
m a
da k
ebijakan p
em
erintah
yang k
husus
menangani m
asala
h
pengem
asa
n d
an p
erg
udangan
kom
oditi pert
ania
n
Kebijakan p
em
erinta
h t
erlalu
fokus
pada k
ebija
kan h
arg
a d
asa
r gabah
dan s
ubsidi pupuk (
khusus
untuk
subse
kto
r ta
bam
a)
Kebijakan r
evitalis
asi indust
ri
perb
era
san t
erp
adu
Perlu k
ajian u
lang k
ebija
kan s
ubsid
i
pupuk d
an H
DG
Info
rmal price m
aker
(te
rutam
a
untuk k
om
oditi su
bsekto
r tabam
a)
Penin
gkatan e
fisie
nsi pem
asara
n
dan s
tabilitasi harg
a g
abah
Perb
aik
an d
an p
em
bangunan
sara
na jala
n d
an a
ngkutan
pedesaan
Kaji
ula
ng r
etribusi dan p
ungutan
terk
ait p
em
asa
ran h
asil pert
ania
n
Bia
ya d
istr
ibusi yang b
esar
(teru
tam
a d
ari p
rodusen k
e
konsum
en)
DIS
TRIB
USI /
PEM
ASARAN
HARGA
Pangsa h
arg
a g
abah y
ang d
iterim
a
peta
ni m
inim
um
dan tid
ak s
tabil
AS
PEK
MA
SA
LA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTIN
DA
K L
AN
JUT
Invest
asi y
ang m
inim
(te
ruta
ma
untu
k p
engem
bangan infr
atr
uktu
r
dan p
engem
bangan indust
ri p
asc
a
panen)
Melib
atk
an s
ekto
r sw
ast
a d
ala
m
sekto
r pert
ania
n
Rendahnya p
enyera
pan m
odal kerja
(teru
tam
a p
ada s
ubse
kto
r ta
bam
a)
Kre
dit K
eta
hanan P
angan
Dere
gula
si p
rogra
m k
redit s
ekto
r
pert
ania
n
Berk
aitan d
engan p
erm
odala
n,
dala
m r
angka
menin
gka
tkan
kapasi
tas
pro
duks
i su
b s
ekt
or
tabam
a d
an p
ete
rnaka
n teru
tam
a
dala
m jangka
panja
ng, ke
butu
han
pendanaan tid
ak
terb
ata
s pada
kebutu
han p
erm
odala
n n
am
un
juga k
ebutu
han inve
stasi
.
Perlu d
ikem
bangka
n s
iste
m
perk
reditan p
ert
ania
n y
ang
dik
elo
la o
leh s
iste
m p
erb
anka
n
pert
ania
n y
ang k
uat se
hin
gga
aks
es
peta
ni te
rhadap
pem
bia
yaan p
erb
anka
n d
an
perm
odala
n m
enin
gka
t se
hin
gga
dapat m
enin
gka
tkan p
roduks
i.
Perlu juga d
ipik
irka
n a
ltern
atif
pendiria
n lem
baga p
em
bia
yaan
khusu
s untu
k se
ktor
pert
ania
n,
term
asu
k pem
bia
yaan k
epada
sub s
ekt
or
tabam
a d
an
pete
rnaka
n.
PEM
BIA
YAAN
AS
PE
KM
AS
ALA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MT
IN
DA
K L
AN
JU
T
TEKN
OLO
GI
Tin
gkat
adopsi
teknolo
gi yang r
endah d
i
tingkat
peta
ni
Mem
perk
uat
penelit
ian d
an
pengem
bangan (
R &
D)
Pro
gra
m p
enyulu
han d
an
pendam
pin
gan
Belu
m a
da a
rah/p
riorita
s kebijakan
sekto
r pert
ania
n y
ang jela
s
Perlu v
isi dan m
isi yang jela
s
mengenai pengem
bangan s
ekto
r
pert
ania
n
Tid
ak a
da k
ebijakan y
ang t
erp
adu a
nta
r
depart
em
en (
fragm
enta
si k
ebijakan)
Koord
inasi
kebijakan
KEBIJ
AKAN
PEM
ERIN
TAH
Sekt
or
Pert
ania
n –
Mat
riks
Su
b S
ekto
r Pe
rkeb
un
an
AS
PEK
MA
SA
LA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTIN
DA
K L
AN
JU
T
Adanya s
ert
ifik
asi bib
it u
nggul
Penyedia
an b
ibit u
nggul berm
utu
dengan h
arg
a y
ang t
erjangkau
Penguatan r
iset s
ektor
perk
ebunan
Penin
gkatan t
eknolo
gi pengola
han
Pers
ain
gan
Penin
gkatan a
kses d
an p
erluasan
pasar
ekspor
(antara
lain
mela
lui
mark
et intelligence d
an
penyebara
n info
rmasi pasar)
Pem
bentukan p
eru
sahaan
gabungan a
ntara
BU
MN
dan
sw
asta u
ntuk b
ers
ain
g
menghadapi peru
sahaan
multin
asio
nal
Perlu d
ikem
bangkan industr
i hilir
perk
ebunan
PRO
DUKSI
Rendahnya p
roduktivitas p
ada
industr
i hulu
, te
ruta
ma k
arena:
kom
posis
i ta
nam
an y
ang m
asih
did
om
inasi ta
nam
an a
sal biji/bib
it
tidak u
nggul/bib
it p
als
u d
an
beru
mur
tua, kete
rbata
san s
ara
n
pro
duksi dan p
upuk y
ang m
asih
terb
ata
s
Laju
pert
um
buhan p
roduksi yang
lebih
rendah d
ibandin
gkan d
engan
laju
pert
um
buhan k
onsum
si,
teru
tam
a u
ntu
k k
om
oditi CPO
,
kare
t dan k
akao
ham
bata
n p
erdagangan (
tarif d
an
non tarif)
, te
ruta
ma y
ang
ditera
pkan n
egara
pengim
por
min
yak s
aw
it.
DIS
TRIB
USI / P
EM
ASARAN
Pengem
bangan lem
baga
penunja
ng e
kspor
AS
PEK
MA
SA
LA
HK
EB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTIN
DA
K L
AN
JU
T
HARGA
Harg
a p
roduk p
rim
er
mengala
mi
fluktu
asi y
ang c
ukup t
aja
m d
i pasa
r
inte
rnasional
Masih
mengik
uti h
arg
a p
asar
inte
rnasio
nal
Kerj
asam
a d
engan n
egara
pro
dusen u
tam
a u
ntu
k m
enja
ga
kesta
bilan h
arg
a p
roduk.
Belu
m m
em
adain
ya f
asilit
as/
inse
ntif
bagi pela
ku u
saha u
ntu
k
menanam
kan m
odaln
ya d
i in
dust
ri
hilir
perk
ebunan
Pem
berian inse
ntif
invest
asi,
sepert
i keringanan b
unga d
an
paja
k
Mem
erlukan invest
asi jangka p
anja
ng
dala
m jum
lah y
ang b
esa
r dan
mem
pert
imbangkan g
race p
eriod.
Mengem
bangkan a
ltern
atif
pem
bia
yaan s
ekto
r perk
ebunan.
TEKNO
LO
GI
Teknolo
gi pengola
han b
elu
m
mem
berikan inse
ntif
bagi pela
ku
untu
k m
enin
gkatk
an m
utu
pro
duk.
Kebijakan m
utu
(SNI)
dari
pem
erinta
h.
Perlu a
danya k
oord
inasi a
nta
r
lem
baga d
i se
kto
r pert
ania
n d
an
indust
ri b
erk
aitan d
engan m
utu
pro
duk.
Konflik
kepentingan p
em
erinta
h
pusa
t dan d
aera
h
Kura
ngnya k
epast
ian h
ukum
dan
jam
inan k
eam
anan y
ang b
erk
aitan
dengan p
em
anfa
ata
n lahan,
jam
inan
keam
anan d
an k
onflik
sosial dengan
masy
ara
kat
lokal
Peneta
pan U
U N
o.
18 t
enta
ng
Perk
ebunan s
ebagai payung
uta
ma p
engam
bangan
perk
ebunan
Inkonsist
ensi p
enera
pan p
ayung
kebija
kan/p
era
tura
n
Pem
erinta
h p
erlu m
enerp
akan
kebijakan s
ecara
konsis
ten
KEBIJ
AKAN P
EM
ERIN
TAH
Revitalisasi Pert
ania
n, UU N
o. 18
tahun 2
004 tenta
ng
perk
ebunan,d
ll
PEM
BIA
YAAN
Sekt
or
Pert
ania
n –
Mat
riks
Su
b S
ekto
r Pe
rika
nan
ASP
EKM
ASA
LAH
KEB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTI
ND
AK
LA
NJU
T
Min
imny
a in
frast
rukt
ur :
- Pe
labu
han
- Iri
gasi
Per
ikan
an-
Stas
iun
pen
gisi
an
baha
n ba
kar
sola
r
Perlun
ya in
vest
asi un
tuk
mem
bia
yai p
emba
ngu
nan
infr
ast
rukt
ur.
Peng
emba
nga
n in
frast
rukt
ur t
erse
but
mem
erlu
kan
pend
anaa
n y
ang
cu
kup b
esar
sehi
ngg
a di
perlu
kan
adany
a du
kung
an le
mba
ga
keuan
gan,
yang
sec
ara
efe
ktif
dapat
mem
bantu
real
isas
i pe
mba
nguna
n in
fras
truk
tur
dim
aksu
d
Ove
rfis
hing
di b
ebe
rapa
dae
rah
pen
angka
pan,
teru
tam
a un
tuk
kom
oditi T
una
Penga
lihan
dae
rah
pen
angka
pan
yang
masi
h u
nder
fis
hin
g
Pen
urun
an p
rodu
ksi u
dang
ta
ngk
apan
Keb
ijaka
n pe
mer
inta
h ya
ng
men
duk
ung
usah
a pe
rtam
baka
n ud
ang
bai
k ol
eh
raky
at m
aupu
n sw
asta
.
Penin
gka
tan
prod
uksi
bud
iday
a ud
ang
.
Ket
idak
stabi
lan
prod
uks
i ter
uta
ma
unt
uk k
omodi
tas
rum
put
laut
kar
ena
dom
inann
ya f
akto
r al
am
dan
kur
angn
ya k
emam
puan
pet
ani
dal
am m
eng
elol
a k
egia
tan
pro
duks
i
Penyu
luhan
pet
ani m
engen
ai
penge
lola
an
kegi
atan
pro
duk
si
rum
put
laut
PRO
DU
KSI
ASP
EKM
ASA
LAH
KEB
IJA
KA
N /
PRO
GRA
MTI
ND
AK
LA
NJU
T
Lem
ahny
a sis
tem
dist
ribus
i pe
mas
aran
inte
rnas
iona
l
Perlu
jarin
gan
inte
rnas
iona
l yan
g m
empu
men
jem
bata
ni in
dust
ri pe
ngol
ahan
sub
sekt
or p
erik
anan
de
ngan
pas
ar d
unia
.
Sara
na d
an in
frast
rukt
ur
trans
port
asi m
asih
bur
uk s
ehin
gga
men
yeba
bkan
mah
alny
a bi
aya
trans
port
asi.
Perb
aika
n sa
rana
tran
spor
tasi.
Ham
bata
n ta
riff
dan
non
tarif
f m
enyu
litka
n pe
netra
si pa
sar
Indo
nesia
Perlu
dila
kuka
n up
aya
peni
ngka
tan
mut
u ha
sil s
ubse
ktor
pe
rikan
an s
ehin
gga
prod
uk
perik
anan
dap
at m
emili
ki m
utu
yang
bai
k da
n se
raga
m, t
erse
dia
seca
ra te
ratu
r dan
sin
ambu
ng
serta
dap
at d
isedi
akan
sec
ara
mas
al.
Pang
sa p
asar
Indo
nesia
mas
ih
rend
ah
DIS
TRIB
USI
/ PE
MA
SARA
N
ASP
EKM
ASA
LAH
KEB
IJA
KA
N /
PR
OG
RA
MTI
ND
AK
LA
NJU
T
HA
RGA
Mes
kipu
n In
done
sia
mer
upak
an
prod
usen
bes
ar,
mas
alah
dom
estik
m
enye
babk
an h
arga
dite
ntuk
an
oleh
mitr
a in
tern
asio
naln
ya
PEM
BIA
YA
AN
Fasi
litas
per
mod
alan
unt
uk s
ekto
r pe
rikan
an m
asih
min
im a
tau
mas
ih
kura
ng m
embu
ka a
kses
ter
hada
p us
aha-
usah
a pe
rikan
an
Peng
emba
ngan
mek
anis
me
pend
anaa
n se
cara
man
diri
(Lem
baga
Mitr
a M
ina
- M
ina
Ven
tura
- A
sura
nsi P
etan
i Ika
n da
n N
elay
an)
Ada
nya
skim
pem
biay
aan
dari
lem
baga
keu
anga
n ya
ng d
apat
m
empe
rcep
at p
emba
ngun
an
perik
anan
, kh
usus
nya
yang
di
arah
kan
pada
pem
bang
unan
in
fras
truk
tur
pend
ukun
gnya
TEK
NO
LOG
ITe
knol
ogi b
udid
aya
(mis
al v
anam
e)
men
ganc
am e
ksis
tens
i tek
nolo
gi
budi
daya
loka
l
DK
P te
lah
mem
iliki
lem
baga
ris
et
perik
anan
yan
g ka
pasi
tasn
ya d
apat
di
anda
lkan
Perlu
nya
peng
uata
n le
mba
ga
riset
di s
ubse
ktor
per
ikan
an,
term
asuk
ris
et m
enge
nai
tekn
olog
i bud
iday
a
KEB
IJAK
AN
PEM
ERIN
TAH
Ada
nya
kebi
jaka
n re
vita
lisas
i, ya
ng
di d
alam
nya
mem
berik
an p
riorit
as
besa
r te
rhad
ap t
iga
kom
odita
s (T
una,
Uda
ng d
an B
udid
aya
Rum
put
Laut
)
Lam
pir
an 2
Pote
nsi
Pen
gem
ban
gan
Ko
mo
dit
as U
ng
gu
lan
Su
bse
kto
r Ta
bam
a d
an P
eter
nak
an
PRO
PIN
SIPa
di
Jag
un
gJe
ruk
Pisa
ng
P.Pe
ng
gem
bal
aan
Bal
i12
9,01
316
,220
16,2
209,
262
Ban
gka
Bel
itu
ng
105,
663
Ban
ten
214,
159
27,6
7727
,677
Ben
gku
lu16
3,84
412
3,79
012
3,79
0 D
I Yo
gya
kart
a10
1,40
28,
283
8,28
3 D
KI J
akar
ta11
,267
7,40
47,
404
Go
ron
talo
82,0
8176
,585
76,5
8592
,799
Jab
ar1,
186,
601
361,
007
361,
007
Jam
bi
428,
716
238,
410
16,8
2823
8,41
0 J
aten
g1,
503,
083
157,
245
157,
245
108,
123
Jat
im1,
567,
708
522,
276
522,
276
438,
082
Kal
bar
493,
373
2,36
9,75
51,
762,
105
2,36
9,75
5 K
alse
l89
3,95
087
2,05
713
9,06
387
2,05
7 K
alte
ng
1,09
6,97
51,
570,
823
2,38
2,72
11,
570,
823
Kal
tim
447,
004
5,35
8,26
252
0,51
55,
358,
262
Lam
pu
ng
628,
329
808,
761
808,
761
Mal
uku
296,
165
140,
695
140,
695
62,9
12 M
alu
ku U
tara
267,
405
114,
945
114,
945
143,
941
NA
D58
0,47
910
2,46
410
2,46
415
1,36
9 N
TB15
3,86
632
6,78
932
6,78
933
1,18
9 N
TT19
9,17
878
2,62
120
3,43
178
2,62
198
5,65
4 P
apu
a9,
550,
816
4,17
6,73
34,
680,
123
28,2
68 R
iau
447,
533
273,
136
273,
136
Su
lsel
1,16
5,77
934
2,99
713
3,93
334
2,99
719
9,30
1 S
ult
eng
539,
499
118,
012
118,
012
73,4
65 S
ult
ra37
1,12
847
9,26
447
9,26
448
1,14
4 S
ulu
t12
1,33
716
,859
16,8
59 S
um
bar
483,
305
151,
728
182,
969
151,
728
Su
mse
l1,
386,
946
1,57
3,25
726
2,79
91,
573,
257
Su
mu
t98
4,37
91,
102,
135
47,0
231,
102,
135
126,
022
JU
MLA
H25
,600
,983
22,2
20,1
905,
651,
387
22,7
23,5
803,
231,
531
Lam
pir
an 3
Lim
a (5
) B
esar
Dae
rah
Pro
du
sen
Ko
mo
dit
as U
ng
gu
lan
Su
bse
kto
r Pe
rkeb
un
an
Kel
apa
Saw
it
2004
Pr
op
insi
Pr
od
uks
i (to
n)
Luas
Are
al (
Ha)
Su
mat
era
Uta
ra
3.1
92.8
30
954
.854
Ri
au
3.1
89.0
87
1
.370
.284
Ja
mbi
790
.781
4
57.4
52
Sum
ater
a Se
lata
n
975
.686
5
15.3
72
Kal
iman
tan
Bara
t
830
.351
4
55.8
13
Kak
ao
2004
Pr
op
insi
Pr
od
uks
i (to
n)
Luas
Are
al (
Ha)
Su
mat
ra U
tara
51.
093
6
4.29
8
Jaw
a Ti
mur
15.
622
3
5.97
5
Sula
wes
i Ten
gah
13
6.77
5
184
.552
Su
law
esi S
elat
an
18
4.47
0
217
.400
Su
law
esi T
engg
ara
11
0.51
7
175
.349
Sum
ber
: Sta
tistik
Ditj
enbu
n 20
05–2
006
Kar
et
2004
Pr
op
insi
Pr
od
uks
i (to
n)
Luas
Are
al (
Ha)
Su
mat
era
Uta
ra
402.
977
456.
782
Sum
ater
a se
lata
n 37
9.31
6 63
0.79
5 Ri
au
261.
507
426.
294
Jam
bi
210.
628
418.
302
Kal
iman
tan
Bara
t 20
0.55
2 36
7.26
7
Teb
u
2004
Pr
op
insi
Pr
od
uks
i (to
n)
Luas
Are
al (
Ha)
Ja
wa
Tim
ur
901.
179
150.
111
Lam
pung
71
0.26
0 96
.260
Ja
wa
Teng
ah
167.
083
37.1
13
Jaw
a Ba
rat
114.
222
21.1
41
Sum
ater
a Se
lata
n 56
.170
11
.657
Sum
ber
: Sta
tistik
Ditj
enbu
n 20
05–2
006
Lam
pir
an 4
Sen
tra
Pro
du
ksi S
ub
sekt
or
Peri
kan
an
Tun
a. C
akal
ang
. To
ng
kol
Pro
du
ksi r
ata-
rata
(to
n/t
ahu
n)
Lo
kasi
(W
ilaya
h P
eng
elo
laan
Per
ikan
an)
Tu
na
Cak
alan
g
Ton
gko
l La
ut C
ina
Sela
tan
64
3.
419
29.2
34
Laut
Jaw
a
0 0
37.0
05
Sela
t M
akas
sar
& la
ut F
lore
s
18.6
91
34.0
04
37.7
14
Laut
Ban
da
15.6
48
27.9
43
4.15
9 La
ut S
eram
. Lau
t H
alm
aher
a da
n Te
luk
Tom
ini
44.4
27
77.1
22
30.2
29
Laut
Sul
awes
i Sam
uder
a Pa
sifik
17
.482
29
.280
8.
632
Laut
Ara
fura
2.
179
6.02
7 2.
606
Sam
uder
a H
indi
a
55.1
15
44.4
98
98.8
72
Ud
ang
W
ilaya
h
Rata
-Rat
a 19
99-2
003
Peri
kan
an T
ang
kap
Su
mat
era
Uta
ra
34.
808
Ri
au
41.
769
Ja
mbi
1
8.06
9
Jaw
a Ti
mur
1
0.58
4
Kal
iman
tan
Bara
t
16.
595
K
alim
anta
n Se
lata
n 32
.005
Kal
iman
tan
Tim
ur
15.
223
Pa
pua
1
5.35
1
Lain
nya
5
8.93
5
Tota
l 24
3.33
8 Pe
rika
nan
Bu
did
aya
Sum
ater
a U
tara
1
9.81
7
Sum
ater
a Se
lata
n
10.
249
La
mpu
ng
21.
802
Ja
wa
Bara
t
19.
651
Ja
wa
Teng
ah
11.
391
Ja
wa
Tim
ur
19
.180
K
alim
anta
n Ti
mur
9
.698
Su
law
esi S
elat
an
19.
301
La
inny
a
26.
124
To
tal
157
.213
TO
TAL
4
00.5
51
Sum
ber
: Dire
ktor
at J
ende
ral P
erik
anan
Tan
gkap
(200
1 –
2005
); D
irekt
orat
Jen
dera
l Per
ikan
an B
udid
aya
(200
1 –
2005
)
Ru
mp
ut
Lau
t
Po
ten
si P
rod
uks
i
Ind
ust
ri
Loka
si
E. C
ott
on
ii
Loka
si
Pen
go
lah
an
(t
on
/tah
un
)
(t
on
/tah
un
) N
AD
10
4.10
0 N
usa
Teng
gara
Tim
ur
1.00
0 Su
mse
l 2
.000
Su
law
esi U
tara
10
.500
D
KI
1.8
00
Sula
wes
i Ten
gah
10
6.30
0 Ja
bar
dan
Bant
en
2.40
0 Su
law
esi S
elat
an
26.5
00
Jaw
a Te
ngah
5
.200
Su
law
esi T
engg
ara
83.0
00
Jaw
a Ti
mur
29
.500
M
aluk
u
206.
600
Bali
18.
100
Papu
a
501.
900
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
12
.000
Su
mbe
r: P
usat
Ris
et P
engo
laha
n Pr
oduk
dan
Sos
ial E
kono
mi K
elau
tan
dan
Perik
anan
, 200
4