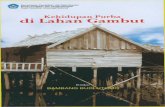UPDATING PETA PENUTUPAN LAHAN KABUPATEN PEMALANG
Transcript of UPDATING PETA PENUTUPAN LAHAN KABUPATEN PEMALANG
1
UPDATING PETA PENUTUPAN LAHAN KABUPATENPEMALANG
LAPORAN KERJA PRAKTEKBALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN XI WILAYAH JAWA-
MADURA
OLEH:
Dwi Puji Astuti11/315480/DGE/0904
PROGRAM DIPLOMA
2
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASIGEOGRAFIS
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufiq, dan
hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan kerja praktek
(magang) dan penyusunan laporan kerja praktik ini tepat
waktu tanpa banyak kendala yang berarti. Selama
melaksanakan kerja praktek di kantor Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura ini saya banyak
mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru mengenai GIS
dan pemetaan khususnya Kawasan Hutan yang ada di wilayah
Jawa-Madura.
Oleh karena pengalaman dan ilmu yang saya dapat itu,
saya mengucapkan banyak terima kasih pihak-pihak yang
ikut terlibat dalam kerja praktik ini, diantaranya:
1. Bapak Ir.Heryadi M.M selaku kepala balai yang
telah mengizinkan saya untuk kerja praktik di
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-
Madura.
2. Bapak Pandam Sulistya, S.S sekalu pembimbing kerja
praktek yang telah memberikan pengarahan serta
bimbingan selama kerja praktek.
3
3. Seluruh pegawai BPKH Wilayah XI Jawa-Madura yang
telah memberikan ilmu, berbagi pengalaman serta
membantu selama kerja praktek.
4. Anisa Nurma Sari, Diah Fitriyani Witanti, Amanda
Meyer dan Safirah Fakhria selaku patner yang telah
bekerja sama saat mendapatkan dan menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan selama kerja praktek.
Setiap manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan
kekurangan, oleh karena itu saya meminta maaf apa bila
ada kesalahan yang saya perbuat dan banyak kekurangan
selama saya kerja praktek di Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XI Jawa-Madura. Dan semoga laporan kerja
praktek ini dapat bermanfaat dikemudian hari.
Hormat Saya
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
4
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan (menurut Undang Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan).
Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan
yang relatif cepat dari tahun ketahun membuat lahan
hutan semakin berkurang. Jumlah penduduk yang kian
bertambah membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai
tempat tinggal. Namun kenyataanya kapasitas lahan
yang terbatas membuat masyarakat membuka lahan hutan
untuk digunakan sebagai lahan permukiman.
Aktifitas manusia juga berdampak pada semakin
perkurangnya lahan kawasan hutan, dimana lahan hutan
digunakan oleh masyarakan untuk lahan pertanian,
lahan permukiman, pariwisata atau fasilitas lain
yang menunjang hidup masyarakat. Sering kali
masyarakat merubah fungsi lahan kawasan hutan
menjadi non hutan tampa mempertimbangkan dampak yang
dapat terjadi akibat semakin berkurangnya lahan
hutan. Lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan
non hutan dapat mengakibatkan degradasi lahan yang
dapat menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan
dan longsor. Lahan hutan yang semakin sedikit juga
dapat perdampak pada kondisi udara dimuka bumi.
Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul
akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktifitas
manusia yang berdampak dengan berkurangnya lahan
5
kawasan hutan dimuka bumi maka perlu diadakanya
monitoring terhadap perubahan penggunaan lahan hutan
guna mengantisipasi masalah-masalah yang timbul,
serta menentukan tindakan apa yang harus
diambil/dilakukan guna menanggulangi masalah-masalah
tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
Sumber daya hayati di Indonesia paling banyak
dieksploitasi pemanfaatannya adalah sumber daya
hutan, akibatnya pemanfaatan yang tidak selaras
dengan alam akan menimbulkan ketidaksesuaian dalam
siklus alam. Hal tersebut menjadi salah satu
permasalahan yang mampu merubah fungsi Kawasan Hutan
sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan sumber
oksigen. Sehingga penggunaan Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi Geografi di bidang Kehutanan
diharapkan mampu menyelesaikan dan meminimalisir
kerusakan Kawasan Hutan dapat teramati perubahan
penutupan lahannya.
1.3. Tujuan
Mengetahui perubahan penutupan lahan terdapat
dikabupaten pemalang, serta menyajikan penutupan
lahan Kabupaten Pemalang dalam bentuk peta.
1.4. Manfaat
6
Kegiatan ini bermanfaat untuk menambah
pemahaman, pengetahuan dan informasi mengenai
penutup lahan yang ada di Kabupaten Pemalang.
1.5. Waktu Dan Tempat
Kerja Praktek (Magang) tahun 2013 dilaksanakan
pada :
1.Waktu
Kerja Praktek (Magang) dilaksanakan selama 2
bulan, yakni dimulai pada 03 Februari - 03 April
2014
2.Tempat
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Xi Jawa-
Madura Jl. Ngeksigondo No.53
BAB II
DASAR TEORI
2.1. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan (land use) adalah setiap
bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap
lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik
material maupun spiritual (Vink, 1975). Penggunaan
lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok
besar yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2)
7
penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan
secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada
lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan
lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang
dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat
yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti
tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan
menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi.
Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi,
khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi
industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi
(Suparmoko, 1995).
2.2. Perubahan Pengunaan Lahan
Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya
suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke
penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya
tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke
waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan
pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto et al.,
2001). Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan
pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan
tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya
keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang
makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan
8
meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih
baik.
Kenampakan penggunaan lahan berubah
berdasarkan waktu, yakni keadaan kenampakan
penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun
waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat
terjadi secara sistematik dan non-sistematik.
Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh
fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan
penggunaan lahan pada lokasi yang sama.
Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan
dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat
dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan
penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-
sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan
yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap.
Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena
kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan
maupun lokasinya (Murcharke, 1990).
2.3. Klasifikasi Penggunaan Lahan
Sistem klasifikasi penggunaan lahan yang
digunakan juga ikut menentukan ketelitiaan dalam
identifikasi penggunaan lahan. Beberapa masalah
yang terkait dengan sistem klasifikasi penggunaan
lahan adalah : (a) pemberian batasan istilah /
9
katagori pengunaan lahan yang tidak seragam, (b)
kesesuaian dengan tujuan pemetaan yang dilakukan,
dan (c) kesulitan dalam penyusunan sistem
klasifikasi secara hirarkhis, yaitu bertingkat dari
skala tinjau sampai dengan skala besar.
2.4. Klasifikasi Hutan
Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 837/Kpts/Um/11/1980 untuk menetapkan
perlunya hutan lindung dalam suatu wilayah, maka
nilai dari sejumlah parameter dijumlahkan setelah
masing-masing dikalikan dengan nilai timbang sesuai
dengan besarnya pengaruh relatif terhadap erosi.
Nilai timbangan adalah 20 untuk lereng lapangan, 15
untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan.
Menurut surat keputusan tersebut penetapan hutan
lindung haruslah memiliki kriteria kemiringan lereng
≥ 40% atau memiliki nilai total ≥ 175 dari hasil
penjumlahan tiap parameter yang telah dikalikan
dengan nilai timbangan.
2.5. Penginderaan Jauh
Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk
memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah,
atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh
10
dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan
obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji.
Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai suatu
proses membaca (Lillesand & Kiefer, 1990). Sutanto
(1979) menjelaskan bahwa penginderaan jauh atau
remote sensing merupakan cara memperoleh informasi
atau pengukuran dari pada obyek atau gejala, dengan
menggunakan sensor dan tanpa ada hubungan langsung
dengan obyek atau gejala tersebut. Karena tanpa
kontak langsung, maka diperlukan media supaya obyek
atau gejala tersebut dapat diamati dan didekati oleh
si penafsir. Media ini berupa citra (images atau
gambar).
Citra penginderaan jauh merupakan gambaran muka
bumi beserta obyek - obyek yang ada atau nampak
padanya dan pembuatan gambarannya dilakukan dengan
sensor (alat pengindera) buatan yang dipasang pada
balon, pesawat terbang, satelit, dan sebagainya.
Interpretasi setidak-tidaknya akan meliputi tiga
pekerjaan mental yang dapat dilaksanakan secara
bersamaan maupun tidak, yakni:
a. Deteksi obyek pada citra
b. Identifikasi obyek pada citra
c. Penggunaan yang tepat dari informasi yang
diperoleh untuk memecahkan masalah yang
sedang dihadapi
11
Identifikasi merupakan pengejaan ciri-ciri
obyek yang dikaji. Tiap obyek mempunyai ciri-ciri
atau karakteristik tersendiri dimana karakteristik
ini dapat dilacak pada citra (Sutanto, 1979).
Citra penginderaan jauh terbagi menjadi dua
jenis citra, yaitu citra foto dan citra non foto.
Pembeda dari kedua jenis citra tersebut adalah jenis
sensor, jenis detektor, dan proses perekamannya.
Citra foto udara biasanya dicetak dalam skala besar,
sedangkan citra non foto biasanya dicetak dalam
skala kecil. Untuk dapat memahami prinsip
penginderaan jauh, terdapat 5 komponen yang terdapat
pada sistem penginderaan jauh meliputi :
a. Matahari sebagai sumber energi utama
karena temperaturnya tinggi 5
b. Atmosfer sebagai medium yang bersikap
menyerap, memantulkan, menghamburkan
(scatter) dan melewatkan radiasi
elektromagnetik
c. Obyek atau target di muka bumi yang
diterima atau memancarkan spektrum
elektromagnetik dari dalam obyek tersebut
d. Radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan
e. Alat pengindera (sensor), yaitu alat untuk
menerima dan merekam radiasi atau emisi
12
spektrum elektromagnetik yang datang dari
obyek.
2.6. Interpretasi Citra
Interpretasi citra (image interpretation) merupakan
proses untuk memperoleh informasi dengan citra
sebagai sumber atau sebagai perantaranya (Sutanto,
1979). Untuk dapat melakukan interpretasi, penafsir
memerlukan unsurunsur pengenal pada obyek atau
gejala yang terekam pada citra. Unsur-unsur pengenal
ini secara individual maupun secara kolektif mampu
membimbing penafsir ke arah pengenalan yang benar.
Unsur-unsur ini disebut unsur-unsur interpretasi dan
meliputi 8 hal, yaitu:
a. Rona (tone) mengacu ke kecerahan relatif
obyek pada citra. Rona biasanya dinyatakan
dalam derajat keabuan (gray scale), misalnya
hitam/sangat gelap, agak gelap, cerah, sangat
cerah/putih. Apabila citra yang digunakan itu
berwarna, maka unsur interpretasi yang
digunakan ialah warna, meskipun penyebutannya
masih terkombinasi dengan rona; misalnya
merah, hijau, biru, coklat kekuningan, biru
kehijauan agak gelap, dan sebagainya.
b. Bentuk (shape) sebagai unsur interpretasi
mengacu ke bentuk secara umum, konfigurasi,
13
atau garis besar wujud obyek secara
individual. Bentuk beberapa obyek kadang-
kadang begitu berbeda dari yang lain,
sehingga obyek tersebut dapat dikenali
semata-mata dari unsur bentuknya saja.
c. Ukuran (size) obyek pada foto harus
dipertimbangkan dalam konteks skala yang ada.
Penyebutan ukuran juga tidak selalu dapat
dilakukan untuk semua jenis obyek.
d. Pola (pattern) terkait dengan susunan
keruangan obyek. Pola biasanya terkait pula
dengan adanya pengulangan bentuk umum atau
sekelompok obyek dalam 6 ruang. Istilah-
istilah yang digunakan untuk menyatakan pola
misalnya adalah teratur, tidak teratur,
kurang teratur; namun kadang-kadang pula
perlu digunakan istilah yang lebih ekspresif,
misalnya melingkar, memanjang terputus-putus,
konsentris, dan sebagainya.
e. Bayangan (shadows) sangat penting bagi
penafsir, karena dapat memberikan dua macam
efek yang berlawanan. Pertama, bayangan mampu
menegaskan bentuk obyek pada citra karena
outline obyek menjadi lebih tajam/jelas;
begitu pula kesan ketinggiannya. Kedua,
14
bayangan justru kurang memberikan pantulan
obyek ke sensor, sehingga obyek yang diamati
menjadi tidak jelas.
f. Tekstur (texture) merupakan ukuran frekuensi
perubahan rona pada gambar obyek. Tekstur
dapat dihasilkan oleh pengelompokan suatu
kenampakan yang terlalu kecil untuk dapat
dibedakan secara individual, misalnya
dedaunan pada pohon dan bayangannya,
serombongan satwa liar di gurun, ataupun
bebatuan yang terserak di atas permukaan
tanah. Kesan tekstur juga bersifat relatif,
tergantung pada skala dan resolusi citra yang
digunakan.
g. Situs (site) atau letak merupakan penjelasan
tentang lokasi obyek relatif terhadap obyek
atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk
dikenali dan dipandang dapat dijadikan dasar
untuk identifikasi obyek yang dikaji. Obyek
dengan rona cerah, berbentuk silinder, ada
bayangannya, dan tersusun dalam pola teratur
dapat dikenali sebagai kilang minyak, apabila
terletak di dekat perairan pantai.
h. Asosiasi (association) merupakan unsur yang
memperlihatkan keterkaitan antara suatu obyek
15
atau fenomena dengan obyek atau fenomena
lain, yang digunakan sebagai dasar untuk
mengenali obyek yang dikaji. Misalnya pada
foto udara skala besar dapat terlihat adanya
bangunan berukuran lebih besar daripada
rumah, mempunyai halaman terbuka, terletak di
tepi jalan besar, dan terdapat kenampakan
menyerupai tiang bendera (terlihat dengan
adanya bayangan tiang) pada halaman tersebut.
Bangunan ini dapat ditafsirkan sebagai
bangunan kantor, berdasarkan asosiasi tiang
bendera dengan kantor (terutama kantor
pemerintahan).
2.7. Sistem Informasi Geografis
Sistem Informasi Geografi merupakan suatu
sistem hasil pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga
fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sitem
berbasis komputer. Sistem informasi ini semua data
yang ditampilkan bereferensi spasial (berkaitan
dengan ruang/tempat/posisi absolut) demikian pula
dengan data atributnya, karena yang membedakan
sistem ini dengan sistem informasi lainnya terletak
di aspek spasialnya (kaitan dengan ruang), semua
data dapat dirujuk lokasinya di atas peta yang
menjadi peta dasarnya. Ketelitian lokasi data
16
ditentukan oleh sumber petanya dengan segala
aspeknya antara lain kedar/skala, proyeksi, tahun
pembuatan, saat pengambilan (untuk citra satelit),
koreksi geometris dan lain sebagainya. Menurut
Prahasta (2001) Sistem Informasi Geografis merupakan
sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk
menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi
geografi khussunya data spasial.
Komponen SIG terdiri atas : komponen perangkat
keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi,
dan manajemen data, sedangkan sebagai sistem SIG
terdiri atas subsistem : data input, data output, data
management dan data manipulation serta analysis, sehingga
pada dasarnya dapat dikatakan bahwa peranan data
sangat vital dalam menjalankan proyek-proyek SIG.
Pengorganisasian data perlu dibentuk sistem basis
data/data base yang bertujuan memudahkan dalam
kegiatan pengembangan selajutnya ataupun manipulasi
ulang.
SIG merupakan suatu sistem informasi yang
berbasis spasial, maka untuk dapat memberikan
informasi yang akurat diperlukan data yang akurat,
tepat waktu, berkesinambungan dan sesuai kebutuhan.
Usaha untuk mendukung hal tersebut diperlukan peta
dasar berupa peta terbaru, peta digital dan citra
satelit sedangkan data atribut (berupa teks, tabel
17
dan grafis), harus selalu diperbaharui sesuai dengan
perubahan kondisi dan dikumpulkan dari sumber-sumber
yang berkompeten.
Salah satu unggulan pertama SIG adalah terletak
pada kemampuannya untuk mendapatkan informasi-
informasi yang tidak terprediksi sebelumnya.
Penggunaan SIG terutama untuk pengelolaan sumberdaya
alam, yang meyangkut perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
(Prahasta, 2001).
Secara umum SIG terdiri dari sub sistem
(Prahasta,2001), yaitu :
1. Data masukan (Input Data) : Subsistem ini
bertugas untuk mengumpulkan dan
mempersiapkan data spasial dan atribut dari
berbagai sumber. Sub sistem ini pula yang
bertanggung jawab dalam mengkonversikan
atau mentransformasikan format-format data
aslinya ke dalam format yang dapat
digunakan oleh SIG.
2. Data Keluaran (Output Data) : Subsistem
ini menampilkan atau menghasilkan keluaran
seluruh atau sebagian data baik dalam
bentuk softcopy maupun dalam hardcopy seperti
tabel, grafik, dan peta.
18
3. Data Manajemen : Subsitem ini
mengorganisasikan baik data spasial maupun
atribut ke dalam sebuah basis data
sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil,
diupdate, dan diedit.
4. Data Manipulasi dan Analisis : Subsistem
ini menentukan informasi-informasi yang
dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu,
subsistem ini juga melakukan manipulasi dan
pemodelan data untuk menghasilkan informasi
yang diharapkan.
Subsistem masukan data dimaksudkan sebagai
upaya mengumpulkan dan mengolah data spasial dari
sumber (peta, data penginderaan jauh, dan basis data
lain). Subsistem penyimpanan dan pemanggilan kembali
dilakukan untuk mengorganisasi data dalam bentuk
yang mudah dan cepat dapat diambil kembali, dan
memungkinkan pemutakhiran serta koreksi cepat dan
akurat. Sistem manipulasi data dan analisis data
dilaksanakan untuk mengubah data sesuai permintaan
pengguna, atau menghasilkan parameter dan hambatan
bagi berbagai optimasi atau pemodelan menurut ruang
dan waktu. Subsistem keluaran mampu menayangkan
sebagian atau seluruh basis data asli maupun data
yang telah dimanipulasi, serta keluaran dari model
spasial dalam bentuk tabel dan peta.Sistem Informasi
19
Geografis (SIG) bukan sekedar alat pembuat peta, dan
walaupun produk SIG lebih sering disajikan dalam
bentuk peta, namun kekuatan SIG yang sebenarnya
terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis.
SIG dapat mengolah data dengan volume yang besar.
Dengan demikian, pengetahuan mengenai bagaimana
mengekstrak data tersebut dan bagaimana
menggunakannya merupakan fungsi analisis dalam SIG
(Prahasta, 2001).
Informasi keruangan (data spasial) diperlukan
untuk berbagai kajian sumberdaya lahan, memecahkan
berbagai masalah keruaangan, seperti analisis
bencana alam, kebakaran hutan, banjir, konversi
lahan, studi kualitas permukiman, dan perencanan
tata ruang. Informasinya dapat diperoleh dan
dianalisis melalui teknologi Sistem Informasi
Geografis (SIG).Pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis secara terpadu dalam pengolahan citra
digital adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi.
Dengan demikian, peranan teknologi Sistem Informasi
Geografis dapat diterapkan pada operasionalisasi
penginderaan jauh satelit. Mengingat sumber data
sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh
baik satelit maupun terestrial terdigitasi, maka
teknologi Sistem Informasi geografis erat kaitannya
dengan teknologi penginderaan jauh. Namun demikian,
20
penginderaan jauh bukan merupakan satu-satunya ilmu
pendukung bagi sistem ini. Sumber data lain berasal
dari hasil survey terestrial atau uji lapangan dan
data-data sekunder lainnya seperti sensus, catatan,
dan laporan yang terpercaya. Data spasial dari
penginderaan jauh dan survey terestrial tersimpan
dalam basis data yang memanfaatkan teknologi
komputer digital untuk pengelolaan dan pengambilan
keputusan.
Perkembangan perangkat lunak SIG saat ini sudah
sangat pesat, saat ini sudah ada berbagai jenis
software antara lain : Arc/info, Arcview, Mapinfo,
Ermapper, Erdas, SpansGIS, MGE, Ilwis, PCI GEOMATICS
dan lain-lain, yang pada umumnya dapat kompatibel
satu dengan lainya termasuk dengan penggunaan basis
data yang ada (langsung dapat diaplikasikan atau
melalui proses konversi terlebih dahulu).
21
BAB III
DESKRIPSI PEKERJAAN
3.1. Tanggal 3 – 28 Februari
3.1.1 Minggu Pertama
Minggu pertama ini saya memulainya dengan
melakukan adaptasi lingkungan bersama dengan teman-
teman kerja praktek saya. Pertama saya dan teman-
teman diberitahu tentang tata tertib yang ada
dikantor BPKH seperti jam kerja yakni mulai pukul
07.30 - 16.00 WIB untuk hari senin hingga kamis,
sedangkan hari jumat mulai pukul 07.30-16.30 WIB.
Waktu istirahat untuk hari senin hingga kamis pukul
12.00 – 13.00 WIB, sedangkan hari jumat mulai pukul
11.30 – 13.00 WIB. Tata terbib lainya seperti aturan
berkaian yakni untuk hari senin dan selasa
menggunakan pakaian hitam-putih sedangkan hari rabu
hingga jumat menggunakan pakaian bebas tetapi sopan.
Selain itu, hal lain yang diberi tahu yakni tentang
22
kebiasaan kantor BPKH yang melakukan upacara/apel
pagi setiap hari senin yang dilakukan tepat pukul
07.30 WIB.
Minggu pertama ini saya dan teman-teman belum
mendapat tugas dari kantor BPKH. Kegiatan yang kami
lakukan hanya sekitar membaca buku-buku yang ada
dikantor dan pembagian sistem kerja magang yang akan
saya dan teman-teman jalani yakni untuk satu bulan
pertama magang dilakukan pada seksi PKH (Pemolaan
Kawasan Hutan) dan satu bulan terakhir pada seksi
ISDH (Informasi Sumber Daya Hutan). Selain itu juga
diberitahu sedikit tentang tugas-tugas atau kegiatan
yang dilakukan oleh seksi PKH dan ISDH. Tugas seksi
PKH ini salah satunya yaitu untuk memetakan batas
kawasan hutan yang ada di jawa dan madura, sedangkan
tugas seksi ISDH diantaranya melaksanakan pengamatan
dan pengolahan data pertumbuhan kondisi hutan serta
penyajian informasi sumberdaya hutan.
3.1.2 Minggu Ke Dua
Minggu kedua ini saya dan teman-teman mulai
mandapat tugas dari seksi PKH yakni untuk menscan
beberapa peta tata batas kawasan hutan AB yang ada
dikabupaten Gunungkidul. Peta yang telah saya dan
teman-teman saya scan kemudian digeorefencing.
23
Georeferencing merupakan proses penempatan objek
berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan
sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan
proyeksi tertentu. Software yang digunakan adalah
arcGIS 10.1. Dalam melakukan proses georeferencing ini
saya dan teman-teman bagi tugas yakni satu anak
mendapat tugas melakukan georefencing 2-3 peta yang
telah discan.
Proses georefencing ini dilakukan dengan
menggunakan nemu toolbar Georefencing yang ada pada
software arcgis 10.1. Dalam melakukan georeferencing
memerlukan minimal 4 titik kontrol dimana titik
kontrol tersebut ditentukan berdasarkan koordinat X
dan Y. Setelah menentukan 4 titik konrol maka hasil
koreksi kita di update dengan cara pilih Update
Georefencing pada toolbar Georefencing. Proses
selanjudnya yaitu menampalkan peta dengan shapfile
jalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah
georeferencing yang telah dilakukan tepat atau tidak,
bila posisi jalan yang ada di peta telah sesuai
dengan yang ada di shapfile maka georeferncing sudah
benar. Namun jika posisi jalan belum tepat maka
perlu dilakukan koreksi ulang yakni dengan cara
menarik jalan pada peta tepat pada shapfile. Setelah
posisi jalan yang ada pada peta bertampalan dengan
24
jalan yang ada di shapfile maka dilakukan proses
rectyfi.
Kesulitan yang saya alami saat melakukan proses
georeferncing ini yaitu ketika memasukkan koordinat X
dan Y. Karena pada beberapa peta menggunakan
koordinat geografis yang nilai koordinatnya
menggunakan koordinat jakarta sebagai acuanya.
Selain itu kesulian yang saya alami ketika
menentukan titik kontrol karena tidak semua peta
menampilkan garis grid pada muka peta.
Setelah proses georefencing peta-peta tata batas
kawasan hutan AB langkah selanjudnya yaitu melakukan
digitasi batas kawasan hutan AB. Sebelum melakukan
digitasi, langkah pertama yang saya lakukan yaitu
membangun database dimana feature class yang dibuat
ada 2 yaitu nomor pal dengan tipe point dan batas
hutan dengan tipe polygon. Feature class nomor pal diisi
dengan mendigitasi nomor pal yang ada di peta secara
berurutan kemudian mengisi atributnya sesuai dengan
nomor pal yang tertera pada peta. Sedangkan untuk
batas hutan berisi luas hutan yang didapat dari
perhitungan menggunakan claculate geometri.
3.1.3 Minggu Ke Tiga
Tugas yang harus saya dan teman-teman kerjakan
di minggu ketiga ini yaitu membuat peta kerja untuk
25
tata batas kawasan hutan AB yang ada didesa sebagian
kabupaten Gunungkidul. Saat membuat peta kerja ini
saya dan teman-teman mendapat tantangan dimana kami
harus membuat layout sedemikian rupa supaya peta
kerja yang kami buat manjadi mudah dimengerti dan
informatif.
Selain membuat peta kerja saya dan teman-teman
juga diperintahkan untuk melakukan scanning peta-
peta Belanda wilayah Jawa Timur dan Taman Nasiaonal
Merubetiri. Peta Belanda yang telah kami scan
kemudian dilakukan proses Scaling guna memposisikan
peta sesuai dengan jarak yang ada di lapangan.
3.1.4 Minggu Ke Empat
Minggu keempat ini saya dan teman-teman
mendapat tugas untuk ikut survei penetapan batas
kawasan hutan AB yang ada di sebagian Kabupaten
Gunungkidul. Untuk survei ini kami mendapat giliran
satu per satu. Saya dan patner saya mendapat giliran
terakhir yakni pada hari Kamis tanggal 27 Februari
2014.
Survei kali ini menggunakan GPS Trimble GeoXT.
Karena sebelumnya saya belum pernah menggunakan GPS
tersebut maka sebelum terjun kelapangan untuk
pemetaan batas kawasan hutan AB yang belum ditata
batas, saya diajari terlebih dahulu bagaimana cara
26
menggunakan GPS tersebut. Kesulitan yang saya alami
saat survei batas kawasan hutan AB ini yaitu medan
yang sulit karena harus melewati bukit-bukit yang
ada di Kabupaten Gunungkidul, akses jalan menuju
lokasi yang sulit serta kesulitan saat menentukan
batas kawasah hutan AB di lapangan karena saat di
lapangan tidak ada batas yang jelas yang menandakan
suatu kawasan hutan AB.
3.2. Tanggal 1 maret – 3 april
Setelah selesai mengerjakan tugas yang
diberikan oleh seksi PKH, saya dan teman-teman
giliran mendapat tugas dari seksi ISDH. Dari seksi
ISDH ini kami diberi tugas untuk melakukan updet
hasil penafsiran penggunaan lahan. Di tugas ini kami
harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang
ada pada Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Resolusi
Sedang Untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan Tahun
2013.
Sebelum melakukan koreksi hasil penafsiran,
kami harus menyiapkan citra yang akan digunakan. Di
sini saya ditugaskan untuk mengkompositkan citra
landsat yang akan digunakan. Komposit yang biasanya
digunakan oleh seksi ISDH yakni komposit 654.
Setelah citra dikompositkan kemudian citra dipotong
berdasarkan batas administrasi setiap kabupatennya.
27
Seksi ISDH memberi 11 kabupaten dan saya mendapatkan
2 kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten
Kuningan.
Setelah citra dikomposit kemudian citra
dipotong dengan menggunakan tool yang bernama Clip.
Untuk melakukan penafsiran saya harus membuat
database terlebih dahulu. Pembuatan database juga
harus sesuai dengan yang ada pada petunjuk teknis
penafsiran citra. Dalam membangun database juga
dilakukan topology guna menghilangkan adanya batas
polygon yang Gaps/bercelah atau polypon yang Overlap.
Sistem klasifikasi yang digunakan untuk koreksi
hasil penafsiran ini menggunkan Sistem Klasifikasi
Penutupan Lahan (23 klas) disertai kode layer dan
kode topomini yang ada pada petunjuk teknis
penafsiran penutupan lahan.
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Deskripsi Daerah Penelitian
4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
4.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Admisnistrasi
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu
kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
Dengan Luas wilayah sebesar 111.530 Ha,
sebagian besar wilayah merupakan tanah kering
28
seluas 72.836 Ha (65,30%) dan lainnya tanah
persawahan seluas 38.694 Ha (34,7%). Adapun
Batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang, sebagai
berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan
Kabupaten Banyumas
Sebelah Barat : Kabupaten Tegal
4.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Pemalang terletak pada 1090 17’
30’– 1090 40’ 30’ Bujur Timur (BT) dan 8052’
30’ – 7o20’ 11’ Lintang Selatan (LS)
4.1.1.3. Topografi
Secara topografis, wilayah Kabupaten
Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat
dikelompokkan menjadi empat (4) kategori, yaitu
sebagai berikut :
1. Daerah dataran pantai: daerah ini memiliki
ketinggian rata-rata antara 1-5 meter
diatas permukaan air laut (DPL); meliputi
17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di
bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
2. Daerah dataran rendah: daerah ini memiliki
ketinggian rata-rata antara 6-15 meter DPL
29
yang meliputi 94 desa dan 4 kelurahan di
bagian selatan dari wilayah pantai.
3. Daerah dataran tinggi: daerah ini memiliki
ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter
DPL yang meliputi 35 desa, terletak di
bagian tengah dan selatan.
4. Daerah pegunungan: terbagi menjadi dua,
yaitu:
5. Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924
meter diatas permukaan laut, meliputi 55
desa yang terletak dibagian selatan.
6. Daerah berketinggian 925 meter diatas
permukaan laut yang terletak di bagian
selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan
berbatasan langsung dengan Kabupaten
Purbalingga.
4.1.1.4. Geologi
Jenis tanah di Kabupaten Pemalang dibagi
menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut
:
a. Tanah alluvial : terutama terdapat
di dataran rendah
b. Tanah regosol : terdiri dari batu-
batuan pasir dan intermedier
didaerah bukit sampai gunung.
30
c. Tanah latosol : terdiri dari batu bekuan
pasir dan intermedier di
daerah perbukitan sampai
gunung.
4.1.1.5. Hidrologi
Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang
terbagi atas :
1. Air Permukaan
Kabupaten Pemalang dialiri sungai yaitu
Sungai Waluh yang terletak kurang lebih 4 km
dari pusat kota dan sungai comal yang terletak
kurang lebih 14 km dari pusat kota.
2. Mata air
Kabupaten Pemalang memiliki potensi
berupa mata air antara lain :
a. Mata air Gung Agung yang terletak di Desa
Kebongede Kecamatan Bantarbolang, dengan
debet air kurang lebih 10 liter/detik,
terletak pada ketinggian kurang lebih 70
meter diatas permukaan air laut.
b. Mata air Telaga Gede yang terletak di
Desa Sikasur Kecamatan Belik.
c. Mata air Asem yang terletak di Desa
Bulakan, dengan debet air kurang lebih 160
meter/detik;
d. Mata air yang lain.
31
3. Air Tanah
Kabupaten Pemalang terbagi menjadi dua
wilayah air tanah sebagai berikut :
a. Daerah dataran rendah
Tanah terdiri dari endapan-endapan lepas
yang mempunyai sifat lulus air. Pada daerah
ini kandungan air tanahnya cukup besar hanya
saja karena dekat pantai maka terjadi
intrusi air laut.
b. Daerah Perbukitan tua dan Perbukitan muda
Daerah perbukitan tua : ditempati batu-
batuan dari formasi mioson dan floosen yang
mempunyai sifat kelulusan air yang sangat
kecil, terutama serpih dan Nepal. Adapun
yang berukuran kasar seperti pasir mempunyai
sifat kelulusan air, namun karena kelerengan
yang cukup terjal maka air tanahnya belum
terbentuk. Daerah perbukitan muda: ditempati
batuan tafaan hasil gunung berapi,
litologinya bersifat lulus air, tetapi
morphologinya berupa perbukitan dengan
lereng yang cukup terjal dimungkinkan air
tanahnya baru mulai terbentuk. Pada satuan
tafaan litologinya bersifat lulus air, maka
kemungkinan sudah mengandung air tanah.
32
Kabupaten Pemalang memiliki beberapa bagian
wilayah hutan, terdiri dari hutan lindung
dengan luas 1.858,60 ha, hutan suaka alam
dan wisata luas 24,10 ha, hutan produksi
tetap sebesar 26.757,60 ha, hutan produksi
terbatas sebesar 3.980,70 ha, hutan bakau
dengan luas 1.672,50 ha, dan hutan rakyat
seluas 22.874,78 ha. Luas hutan
dibandingkan dengan luas wilayah sebesar
49,57%. Gambaran ini menunjukkan keadaan
yang cukup baik terkait dengan kemampuan
wilayah untuk menyimpan air tanah (catchment
area).
4.1.1.6. Klimatologi
Temperatur Kabupaten Pemalng tidak banyak
mengalami perubahan pada musim kemarau maupun
penghujan, berkisar antara 300C dengan rata-
rata curah hujan selama 1 tahun sebesar 302 mm.
Curah hujan tertinggi berada pada Bulan Januari
yaitu 739 mm, sedangkan curah hujan terendah
berada di Bulan Juli, yaitu sebesar 47 mm.
4.1.2. Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang,
berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010
adalah 1.262.013 orang, yang terdiri dari 625.642
33
laki-laki dan 636.371 perempuan. Dari data
tersebut 3 kecamatan menempati urutan teratas
jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Pemalang
sebesar 173.217 orang, Kecamatan Taman sebesar
157.298 orang serta Kecamatan Petarukan sebesar
143.816 orang.
Kecamatan Warungpring, Bodeh dan Pulosari
adalah 3 kecamatan urutan terbawah dengan jumlah
penduduk paling sedikit masing-masing berjumlah
37.839 orang, 53.040 orang dan 54.295 orang.
Sedangkan Kecamatan Belik dan Kecamatan
Randudongkal merupakan kecamatan yang paling
banyak penduduknya untuk wilayah punggung (bagian
selatan) dengan jumlah penduduk masing-masing
sebanyak 102.386 orang dan 95.598 orang.
Dengan luas wilayah Kabupaten Pemalang
sekitar 1.115,30 kilometer persegi yang didiami
oleh 1.262.013 orang maka rata-rata tingkat
kepadatan penduduk Kabupaten Pemalang adalah
sebanyak 1.132 orang per kilometer persegi.
Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan
penduduknya adalah Kecamatan Comal yakni sebanyak
3.240 orang per kilometer persegi, sedangkan yang
paling rendah adalah Kecamatan Warungpring dengan
kepadatan sebanyak 492 orang per kilometer
persegi.
34
4.1.3. Kondisi Ekonomi
4.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2010**
(angka sementara) atas dasar harga berlaku
sebesar Rp. 8.066.313,66 juta sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan sebesar Rp.
3.455.736,95 juta. Kontribusi sektoral
terbesar penyumbang PDRB pada tahun 2010
adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
28,42%, sektor pertanian 25,42% dan industri
pengolahan sebesar 22,59%.
4.1.3.2 Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pemalang
pada tahun 2010 menunjukkan gambaran yang
terus meningkat, hal ini ditunjukkan dengan
PDRB Kabupaten Pemalang atas dasar harga
berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.
8.066.313,66 juta, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan sebesar Rp. 3.455.736,95 juta.
PDRB per kapita menurut harga berlaku yaitu
6,329 juta rupiah dan laju pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2010 sebesar 4,94 persen.
4.1.3.3 Pendapatan Per kapita
Pendaptan per kapita Kabupaten Pemalang
pada tahun 2010 atas dasar harga konstan
35
sebesar Rp.2.738.000,00 per orang** (angka
sangat sementara). Angka tersebut meningkat
secara nominal daripada tahun 2009 sebesar Rp.
2.373.358,00, Tahun 2008 sebesar Rp.
2.255.100,00 per orang dan tahun 2007 yaitu
sebesar Rp. 2.166.279,00.
4.1.3.4 Laju Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang
pada Tahun 2010 ** (angka sangat sementara)
diperkirakan sebesar 7,38%. Kondisi ini
menurun apabila dibandingkan dengan laju
inflasi pada Tahun 2009 yang sebesar 8,71%.
Kondisi tersebut mengindikasikan terjadi
stabilisasi perekonomian daerah, meskipun
demikian secara makro kondisi tersebut perlu
dijaga agar nilai inflasi juga tidak terlalu
rendah.
4.1.3.5 Potensi Unggulan Daerah
Beberapa potensi yang bisa dijadikan
komoditas unggulan dalam rangka mendukung
pengembangan Kabupaten Pemalang meliputi :
industri tekstil, tenun dan konveksi, kawasan
agropolitan, hasil pertanian dan perkebunan,
obyek wisata, dan perikanan tangkap dan
budidaya.
36
4.2 Alat Dan Bahan
4.2.1 Alat
1. Seperangkat komputer
2. Software GIS : Arcgis 10.1
4.2.2 Bahan
1. Citra satelit landsat tahun 2013 Jawa-Madura
2. Data shapefile penutupan lahan Kabupaten
Pemalang
3. Data shapefile wilayah administrasi Kabupaten
Pemalang
4.3. LANGKAH KERJA
4.3.1. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data merupakan tahap
dalam mengumpulkan alat dan bahan penelitian,
serta pemilihan metode penelitian yang akan
digunakan. Penggunaan data untuk penelitian
merupakan data sekunder yang di dapat dari
Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Jawa-Madura. Dimana data tersebut terdiri dari
data citra satelit landsat tahun 2013 Jawa-
Madura, data shapefile penutupan lahan Jawa-
Madura tahun 2012, data shapefile wilayah
administrasi Jawa-Madura
37
4.3.2. Tahap Analisis Data
Komposit Band
1. Membuka software ArcGIS 10.1
2. Add citra yang akan di gunkan dengan band 4,5
dan 6
3. Mengkompositkan citra agar tampilan citra
menjadi berwarna. Komposit citra dapat
dilakukan dengan menggunakan Data Management
Tools Raster Raster Processing Composite
Bands pada ArctoolBox. Komposit citra yang
digunakan adalah komposit 654
38
Hasil citra yang telah dikompositkan
4. Add data shapefile batas administrasi
kabupaten Pemalang.
5. Memotong citra yg telah dikomposit dengan
menggunakan clip (data managemen). Pemotongan
citra ini berdasarkan batas administrasi
Kabupaten Pemalang.
6. Hasil citra yang telah dipotong sesuai dengan
batas administrasi kabupaten Pemalang.
Membangun Database
1. Membuat folder dengan nama Penafsiran 2013
39
2. Klik kanan kemudian pilih New File
Geodatabase
3. Merubah nama file Geodatabase menjadi
bpkhxi_penutupanlahan dengan cara klik kanan
pada file geodatabase kemudian pilih rename
4. Setelah merubah nama file geodatabase menjadi
bpkhxi_penutupan lahan, klik kanan kemudian
pilih Feature Dataset. Membuat feature dataset
dengan nama Kab_Pemalang Geographic koordinate
system pilih WGS 1984 Vertical Coordinate System
pilih WGS 1984 Finish
40
5. Melakukan import data penggunaan lahan tahun
2012 dengan cara klik kanan pada Feature Dataset
Kab_Pemalang Import Feature Class (Single).
Pada jendela Feature Class to Feature Class masukkan
input Feature pl2012 dengan Output Feature Class
pl12. Pastikan pada Field Map (optional)
PL12_ID(Long).
6. Melakukan topology guna menghilangkan adanya
polygon yang Gaps ataupun Overlap. Topology
dilakukan dengan cara klik kanan pada
Kab_Pemalang kemudian pilih New Topology.
41
7. Pada tampilan pertama New Topology klik Next
setelah itu masukkan nama topology
“Kab_Pemalang_Topology” Next. Select pl12
kemudian klik Next. Add Rule pilih Features of
feature class pl12 dengan Rule Must Not Overlap
OK. Add Rule lagi namun kali ini pilih Rule Must
Not Have Gaps OK. Jika Rule Overlap dan Gaps
telah terbentuk maka klik Next Finish
42
8. Menunggu hingga proses topology selasai
berjalan masukkan hasil topologi dalam layer
9. Untuk melakukan topology maka perlu dilakukan
Start Editing kemudian klik tool Error Inspector
10. Pilih target pl12 – Must Not Overlap untuk
menghilangkan polygon yang overlap Search Now.
Tidak ada polygon yang Overlap
43
11. Memilih target Must Not Have Gaps Search
Now. Untuk menghilangkan polygon yang Gaps
maka klik kanan pada Must Not Have Gaps kemudian
pilih Mask as Expretions
12. Melakukan Import data penggunaan lahan
yang telah ditopology dengan cara klik kanan
Import Feature Class (Single)
13. Memasukkan Input Feature pl12 output
Feature Class lp13. Tunggu hingga proses Import
selesai
44
14. Tampilan pada jendela arcMap
Digitasi
1. Membuka atribut pl13 dengan cara klik kanan
pada pl13 Open Attributs Table
2. Menambahkan atribut baru dengan nama cara Add
Field. Buat field dengan nama pl13_ID type
Long Integer
45
3. Klik kanan pada kolom pl13_ID yang telah
dibuat sebelumnya kemudian pilih Field Calculator
klik 2 kali pada field pl12_ID OK
4. Memulai melakukan digitasi penutup lahan.
Digitasi dilakukan berdasarkan polygon yang
telah ada sebelumnya. Digitasi dilakukan
pada kenampakan pada citra yang mengalami
perubahan. Penentuan penutupan lahan
46
dilakukan dengan menggunakan klasifikasi
penutupan lahan 23 kelas
5. Setelah selesai makakukan digitasi perubahan
penutupan lahan, simpan hasil digitasi dengan
cara Save Editing Stop Editing.
47
4.4. Diagram Alir Penelitian
Citra satelit
Landsat liputan
Komposit
Band 654
Clip
Management
Data Penutupan
Lahan tahun
Import Data
kedalan Database
Topology
Error
Import data kedalam
Database dengan
nama penutupan
Data shapefile
wilayah
administrasi
Citra Satelit
Landsat Kabupaten
Pemalang
Digita
Peta Tentatif Penutupan Lahan Tahun 2013
Kabupaten Pemalang
Layout
48
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil
Peta Tentatif Penutupan Lahan Tahun 2013 Kabupaten
Pemalang Skala 1:200.000 (Terlampir)
5.2. Pembahasan
Perubahan penutupan lahan terjadi dalam kurun
waktu yang relatif cepat khusunya penutupan lahan
kawasan hutan. Adanya perubahan penutupan lahan
inilah yang membuat perlunya dilakukan
identifikasi/monitoring perubahan yang terjadi guna
mengetahuai pergerakan perubahanya serta dapat
menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil
49
untuk mengatasi perubahan penutupan lahan hutan
menjadi non hutan. Perubahan penutupan lahan ini
terjadi disetiap wilayah diindonesia. Untuk kali ini
identifikasi perubahan penutupan lahan dilakukan
pada kabupaten Pemalang.
Identifikasi penutupan lahan Kabupaten Pemalang
ini menggunakan citra satelit skala sedang yakni
citra satelit Landsat. Klasifikasi yang digunakan
untuk identifikasi penutupan lahan Kabupaten
Pemalang ini menggunakan klasifikasi penutup lahan
23 klasifikasi. Komposit citra yang digunakan yakni
komposit 654 sehingga pada citra kenampakannya
seperti kenampakan aslinya. Misalnya untuk vegetasi
akan berwarna hijau dan obyek yang mengandung air
seperti tambak/tubuh air akan berwarna gelap.
Komposit citra ini akan memudahkan dalam
mengenali/identifikasi jenis penutupan lahan apa
saja yang ada di Kabupaten Pemalang ini. Untuk
membedakan setiap penutupan lahan yang tampak pada
citra dapat ditentukan dengan memperhatikan
rona/warna, tekstur serta polanya.
Kabupaten Pemalang sendiri memiliki penutupan
lahan yang beragam. Berdasarkan hasil identifikasi,
penutupan lahan yang ada di Kabupaten Pemalang
berupa Hutan Lahan Kering Sekunder/bekas Tebangan,
Hutan Tanaman, Semak Belukar, Perkebunan/Kebun,
50
Permukiman/Lahan Terbangun, Semak Belukar, Pertanian
Lahan Kering Campur, Semak/Kebun Campur, Sawah,
Tambak, Tubuh Air, serta Pertanian Lahan Kering.
Penutupan lahan Hutan Tanaman dapat diidentikasi
dari citra dengan kenampakan memiliki rona cerah
dengan warna hijau tua, bertektur kasar dengan pola
yang mengelompok. Tutupan lahan ini banyak terdapat
pada daerah tinggi.
Selain penutupan lahan Hutan Tanaman, tutupan
lahan lain yang tampak jelas pada citra yakni
tutupan lahan sawah. Tutpan lahan sawah ini, rona
terlihat gelap, berwarna magenta, bertekstur halus
berbentuk kotak-kotak dengan pola yang teratur.
Penutupan lahan sawah ini bnyak terdapat pada bagian
utara Kabupaten Pemalang dengan topografi yang
cenderung datar dan berada pada dataran rendah.
Untuk tutpan lahan Permukiman/lahan terbangun tampak
berwarna magenta dengan rona cerah, lebih cerah dari
tutupan lahan sawah. Tekstur penutupan lahan sawah
terlihat sekikit kasar dengan bercak-bercak, berpola
mengelompok berasosiasikan olah jalan dan banyak
berada pada daerah rendah/dataran rendah. Penutupan
lahan sawah dan permukiman ini hampir sama. Hal yang
terlihat jelas unuk membedakan penutupan lahan ini
yakni pada rona atau warnanya. Penutupan lahan sawah
terlihat lebih gelap karena sawah mengandung air
51
dimana komposit citra yang digunakan adalah komposit
654 dimana band biru diberi band infrared yang
membuat air akan tampak berwarna gelap/hitam.
Penutupan lahan yang berhasil diidentifikasi
berupa pertanian lahan kering dimana pada citra akan
tampak berwarna hijau magenta dengan kestur sedikit
halus dan berpola tidak teratur. Pertanian lahan
kering ini terdapat hampir diseluruh wilayah
Kabupaten Pemalang, terutama pada daerah yang
bergelombang. Bila dilihat dari citra penutupan
lahan ini tampak seperti penutupan lahan sawah,
namun terdapat perbedaan pada teksturnya yang
sedikit lebih kasar dengan rona yang cerah.
Bedanya penutupan lahan pertanian lahan kering
dengan pertanian lahan kering campur semak/kebun
campur terlihat jelas pada warna, teksturnya.
Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur
berwarna hijau tua dengan tekstur kasar dan terdapat
pada daerah yang tinggi tepatnya pada bagian selatan
Kabupaten Pemalang.
Penutupan lahan yang berhasil diidentifikasi
selanjudnya yaitu tambak. Pernutupan lahan ini
terdapat pada bagian utara Kabupaten Pemalang dan
letaknya dipinggir pantai/dekat laut. Tambak pada
citra berwarna gelap kerena mengandung air dimana
52
pada komposit citra yang digunakan air akan berwarna
gelap dengan tekstur yang halus.
Perubahan penutupan lahan yang ada di Kabupaten
Pemalang tahun 2013 ini tidak selalu penutupan lahan
tersebut memang mengalami perubahan. Namun bisa jadi
adanya kesalahan saat identifikasi penutupan lahan
sebelum atau tahun 2012. Hal ini dikarenakan
identifikasi perubahan penutupan lahan tahun 2013
ini didasarkan pada hasil identifikasi perubahan
penutupan lahan tahun sebelumnya.
Dalam melakukan identifikasi perubahan
penutupan lahan ini menggunakan panduan petunjuk
teknis citra resolusi sedang yang didalamnya berisi
aturan serta tata cara ketika akan melakukan
identifikasi penggunaan lahan.
Identifikasi perubahan penutupan lahan ini
sangat bergantung pada kemampuan interpreter dalam
menentukan jenis penutupan lahan. Selain itu
kualitas citra juga sangat mempengaruhi hasil
identifikasi karena kejelasan kenampakan penutupan
lahan pada citra sangat membantu interpreter dalam
mengidentifikasi penutupan lahan tertentu.
Pengetahuan interpreter tentang lokasi/wilayah yang
diidentifikasi juga sangat membantu dan memudahkan
53
untuk mentukan jenis penutupan lahan yang tampak
pada citra.
Kelemahan/kesulitan yang dialami saat melakukan
identifikasi perubahan penutupan lahan ini yakni
kesulitan saat menentukan jenis perubahan yang
terjadi. Hai ini dikarenakan citra yang digunakan
merupakan citra skala sedang dengan tingkat
kedetailan obyek sedang. Selain itu citra skala
sedang ini cenderung terdapat tutupan awan sehingga
tidak dapat ditentukan penutupan lahan apa yang ada
pada lokasi yang tertutup oleh awan tersebut.
54
BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
1. Perubahan penutupan lahan yang terjadi tidak luput
dari aktifitas manusia itu sendiri
2. Penutupan lahan yang mengalami peruhan di
Kabupaten Pemalang meliputi hutan tanaman,
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering
bercampur semak/belukar, sawah dan
permukiman/lahan terbangun
55
3. Perubahan yang terjadi pada penutupan lahan di
Kabupaten Pemalang ini tidak luput dari aktifitas
penutupan lahan lain disekitarnya.
4. Ketepatan hasil indentifikasi perubahan penutupan
lahan tergantung pada kemampuan interpreter,
pengalaman interpreter dalam identifikasi suatu
kenampakan citra, pengetahuan interpreter terhadap
lokasi penelitian serta kualias citra yang
digunakan
6.2. Saran
1. Identifikasi perubahan penutupan lahan sebaiknya
dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh
ketelitian guna mendapatkan hasil identifikasi
yang tepat dan baik.
2. Hasil identifikasi akan lebih baik jika
menggunakan data-cata atau citra dengan kualitas
yang bagus dan dilakukan oleh interpreter yang
sudah ahli dibidangnya
DAFTAR PUSTAKA
56
Khakim, Nurul. 1999. Petunjuk Praktikum Penggunaan Peta.
Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada,
Prahasta, Eddy. 2001. Konsep – Konsep Dasar Sistem Informasi
Geografi. Informatika. Bandung.
Sudaryatno. Drs. MSi. 2002. Pedoman Praktikum Kartografi
Tematik. Fakultas Geografi. Universitas Gadjah
Mada. Yogyakarta,
Sutanto. 1979. Penginderaan Jauh Jilid 1. Gadjah Mada
University Press.Yogyakarta
2
PROFIL INSTANSI
Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (disingkat
BPKH) adalah unit
pelaksana teknis di
bawah Direktorat
Jenderal Planologi.
Kehutanan Kementerian
Kehutanan Indonesia. Lembaga ini memiliki 3 tugas pokok
yaitu melaksanaan pemantapan kawasan hutan, penilaian
perubahan status dan fungsi hutan, dan penyajian data
dan informasi sumberdaya hutan. Selain ketiga tugas
tersebut BPHK juga memiliki fungsi tertentu, yakni :
1. Pelaksanaan identifikasi lokasi dan
potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk
2. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan
kawasan hutan konservasi
3. Pelaksanaan identifikasi fungsi dan
penggunaan dalam rangka penagunaan kawasan
hutan
3
4. Penilaian hasil tata batas dalam rangka
penatagunaan kawasan hutan
5. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian
perubahan status dan fungsi kawasan hutan
6. Pelaksanaan identifikasi pembentukan
unit pengelolaan hutan konservasi serta lindung
dan hutan produksi lintas administrasi
pemerintahan
7. Penyusunan dan penyajian data informasi
sumberdaya hutan serta neraca sumberdaya hutan
8. Pengelolaan sistem informasi geografis
dan perpetaan kehutanan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai 1 (satu)
Sub Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) seksi yaitu Seksi
Informasi Sumber Daya Hutan, Seksi Pemolahan Kawasan
Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas
masing-masin seksi adalah sebagal berikut :
a) Sub Bagian Tata Usaha :
Melaksanakan urusan kepegawaian
Melaksanakan urusan keuangan
4
Melaksanakan urusan tata persuratan
Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah
tangga.
b) Seksi Informasi Sumberdaya Hutan :
Melaksanakan penyusunan program, anggaran dan
evaluasi
Melaksanakan penginderaan jauh
Melaksanakan pengelolaan sistem informasi
geografis
Melaksanakan perpetaan dan pemasangan jaringan
titik kontrol
Melaksanakan penyusunan neraca sumberdaya hutan
Melaksanakan pengamatan danpengolahan data
pertumbuhan kondisi hutan serta penyajian
informasi sumberdaya hutan.
c) Seksi Pemolaan Kawasan Hutan :
Melaksanakan identifikasi lokasi dan potensi
kawasan hutan yang akan ditunjuk
Melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan
hutan konservasi
Melaksanakan identifikasi fungsi dan penggunaan
dalam rangka penatagunaan kawasan hutan
Melaksanakan penilaian hasil tata batas dalam
rangka penetapan kawasan Hutan lindung dan hutan
produksi
5
Melaksanakan identifikasi dan penilaian
perubahan status dan fungsi kawasan hutan
Melaksanakan identifikasi pembentukan unit
pengelolaan hutan konservasi, serta hutan
lindung dan hutan produksi lintas administrasi
pemerintah
KEPALA BPKH WILAYAH XI JAWA DAN MADURA(Ir.HERYADI,MM)
6
SBTU(SUB BAGIAN TATA USAHA)
1. POKJA PERSYARATAN DANPELAPORAN
2. POKJA KEPEGAWAIAN3. POKJA ANGGARAN, STATISTIK4. POKJA KEUANGAN5. POKJA KOORDINATOR
PENYUSUNAN PERENCENAANPROGRAM ANGGARAN, EVLUASILAPANGAN DAN PELAPORAN
SEKSI ISDH1. POKJA PENGELOAAN SISTEM INFORMASI
GEOGRAFI DAN PERPETAAN KEHUTANAN2. POKJA INVENTARISASI, PENYAJIAN NERACA
SUMBERDAYA HUTAN DAN INFORMASISUMBERDAYA HUTAN
3. POKJA PENILAIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTANDAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN
SEKSI PKH1. POKJA KPH (KESATUAN PENGELOLAAN
KAWASAN HUTAN)2. POKJA PENATAGUNAAN WILAYAH
PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN3. POKJA PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Kelompok JabatanFungsional
8
No Kelas
Kode
layer/
toponimi
Keterangan
1 Hutan lahan
kering
primer
Hp /
2001
Seluruh kenampakan hutan
dataran rendah, perbukitan
dan pegunungan (dataran
tinggi dan subalpin) yang
belum menampakkan bekas
penebangan, termasuk hutan
kerdil, hutan kerangas,
hutan diatas batuan kapur,
hutan di atas batuan ultra
basa, hutan daun jarum,
hutan luruh daun dan hutan
lumut.2 Hutan lahan
kering
sekunder /
bekas
tebangan
Hs /
2002
Seluruh kenampakan hutan
dataran rendah, perbukitan
dan pegunungan yang telah
menampakkan bekas penebangan
(kenampakan alur dan bercak
bekas tebang), termasuk
hutan kerdil,
hutan kerangas, hutan di
atas batuan kapur, hutan di
atas batuan ultra basa,
hutan daun jarum, hutan
9
luruh daun dan hutan lumut.
Daerah berhutan bekas tebas
bakar yang ditinggalkan,
bekas kebakaran atau yang
tumbuh kembali dari bekas
tanah terdegradasi juga
dimasukkan dalam kelas ini.
Bekas tebangan parah bukan
areal HTI, perkebunan atau
pertanian dimasukkan sav
anna, semak belukar atau
lahan terbuka3 Hutan rawa
primer
Hrp /
2005
Seluruh kenampakan hutan di
daerah berawa, termasuk rawa
payau dan rawa gambut y ang
belum menampakkan bekas
penebangan, termasuk hutan
sagu.4 Hutan rawa
sekunder /
bekas
tebangan
Hrs /
20051
Seluruh kenampakan hutan di
daerah berawa, termasuk rawa
payau dan rawa gambut y ang
telah menampakkan bekas
penebangan, termasuk hutan
sagu dan hutan rawa bekas
terbakar. Bekas tebangan
parah jika tidak
10
memperlihatkan tanda
genangan (liputan air)
digolongkan tanah terbuka,
sedangkan jika
memperlihatkan bekas
genangan atau tergenang
digolongkan tubuh air (rawa)5 Hutan
mangrove
primer
Hmp /
2004
Hutan bakau, nipah dan
nibung yang berada di
sekitar pantai yang belum
menampakkan bekas
penebangan. Pada beberapa
lokasi, hutan mangrove
berada lebih ke pedalaman6 Hutan
mangrove
sekunder /
bekas
tebangan
Hms /
20041
Hutan bakau, nipah dan
nibung yang berada di
sekitar pantai yang telah
memperlihatkan bekas
penebangan dengan pola alur,
bercak, dan genangan atau
bekas terbakar. Khusus untuk
bekas tebangan yang telah
berubah fungsi menjadi
tambak/sawah digolongkan
menjadi tambak/sawah,
sedangkan yang tidak
11
memperlihatkan pola dan
masih tergenang digolongkan
tubuh air (rawa).7 Hutan
tanaman
Ht /
2006
Seluruh kawasan hutan
tanaman yang sudah ditanami,
termasuk hutan tanaman untuk
reboasasi. Identifikasi
lokasi dapat diperoleh
dengan Peta Persebaran Hutan
Tanaman. Catatan: Lokasi
hutan tanaman yang
didalamnya adalah tanah
terbuka dan atau semak-
belukar maka didelineasi
sesuai dengan kondisi
tersebut dan diberi kode
sesuai dengan kondisi
tersebut misalnya tanah
terbuka (2014) dan
semakbelukar
(2007).8 Perkebunan
/ Kebun
Pk /
2010
Seluruh kawasan perkebunan,
yang sudah ditanami. Identif
ikasi lokasi dapat diperoleh
dengan Peta Persebaran
Perkebunan. Perkebunan
12
rakyat yang biasanya
berukuran kecil akan sulit
diidentif ikasikan dari
citra maupun peta
persebaran, sehingga
memerlukan informasi lain,
termasuk data lapangan.
Catatan: Lokasi
perkebunan/kebun yang
didalamnya adalah tanah
terbuka dan atau semak-
belukar maka didelineasi
sesuai dengan kondisi
tersebut dan diberi kode
sesuai dengan kondisi
tersebut misalnya tanah
terbuka (2014) dan
semakbelukar (2007)9 Semak
belukar
B / 2007 Kawasan bekas hutan lahan
kering yang telah tumbuh
kembali atau kawasan dengan
liputan pohon jarang (alami)
atau kawasan dengan dominasi
vegetasi rendah (alami).
Kawasan ini biasanya tidak
menampakkan lagi
13
bekas/bercak tebangan10 Semak
belukar
rawa
Br /
20071
Kawasan bekas hutan rawa /
mangrove yang telah tumbuh
kembali atau kawasan dengan
liputan pohon jarang (alami)
atau kawasan dengan dominasi
vegetasi rendah (alami).
Kawasan ini biasanya tidak
menampakkan lagi bekas /
bercak tebangan11 Savanna/
Padang
rumput
S / 3000 Kenampakan non hutan alami
berupa padang rumput,
kadang-kadang dengan sedikit
semak atau pohon. Kenampakan
ini merupakan kenampakan
alami di sebagian Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara
Timur dan bagian Selatan
Papua. Kenampakan ini dapat
terjadi pada lahan kering
ataupun rawa (rumput rawa).12 Pertanian
lahan
kering
Pt /
20091
Semua aktiv itas pertanian
di lahan kering seperti
tegalan, kebun campuran dan
ladang13 Pertanian Pc / Semua jenis pertanian lahan
14
lahan
kering
campur
semak
/kebun
campur
20092 kering y ang berselang-
seling dengan semak, belukar
dan hutan bekas tebangan.
Sering muncul pada areal
perladangan berpindah, dan
rotasi tanam lahan karst.
Kelas ini juga memasukkan
kelas kebun campuran14 Sawah Sw /
20093
Semua aktivitas pertanian
lahan basah yang dicirikan
oleh pola pematang. Yang
perlu diperhatikan oleh
penafsir adalah fase rotasi
tanam yang terdiri atas fase
penggenangan, fase tanaman
muda, fase tanaman tua dan
fase bera. Kelas ini juga
memasukkan sawah musiman,
sawah tadah hujan, sawah
irigasi. Khusus untuk sawah
musiman di daerah rawa
membutuhkan inf ormasi
tambahan dari
lapangan15 Tambak Tambak Aktiv itas perikanan darat
(ikan / udang) atau
15
penggaraman yang tampak
dengan pola pematang
(biasanya) di sekitar panta16 Permukiman
/
Lahan
terbangun
Pm /
2012
Kawasan permukiman, baik
perkotaan, perdesaan,
industri dll. Yang
memperlihatkan pola alur
rapat.17 Transmigras
i
Tr /
20122
Kawasan permukiman
transmigrasi beserta
pekarangan di sekitarnya.
Kawasan pertanian atau
perkebunan di sekitarnya
yang teridentif ikasi jelas
sebaiknya dikelaskan menurut
pertanian atau perkebunan.
Kawasan transmigrasi yang
telah berkembang sehingga
polanya menjadi kurang
teratur dikelaskan menjadi
permukiman perdesaan.18 Lahan
terbuka
T / 2014 Seluruh kenampakan lahan
terbuka tanpa vegetasi
(singkapan batuan puncak
gunung, puncak bersalju,
kawah v ulkan, gosong pasir,
16
pasir pantai, endapan
sungai), dan lahan terbuka
bekas kebakaran.
Kenampakan lahan terbuka
untuk pertambangan
dikelaskan pertambangan,
sedangkan lahan terbuka
bekas pembersihan lahanland
clearing dimasukkan kelas lahan
terbuka. Lahan terbuka dalam
kerangka rotasi tanam
sawah / tambak tetap
dikelaskan sawah / tambak19 Pertambanga
n
Tb /
20141
Open pit (spt.: batubara,
timah, tembaga dll.), serta
lahan pertambangan tertutup
skala besar y ang dapat
diidentif ikasikan dari
citra berdasar asosiasi
kenampakan objeknya,
termasuk tailing ground
(penimbunan limbah
penambangan). Lahan
pertambangan tertutup skala
kecil atau yang tidak
teridentifikasi dikelaskan
17
menurut kenampakan
Permukaannya20 Tubuh air A / 5001 Semua kenampakan perairan,
terasuk laut, sungai, danau,
waduk, terumbu karang,
padang lamun dll. Kenampakan
tambak, sawah dan rawa-rawa
telah digolongkan tersendiri21 Rawa Rw /
50011
Kenampakan lahan rawa yang
sudah tidak berhutan22 Awan Aw /
2500
Kenampakan awan yang
menutupi lahan suatu kawasan
dengan ukuran lebih dari 4
cm2 pada skala penyajian.
Jika liputan awan tipis
masih memperlihatkan
kenampakan di bawahnya dan
memungkinkan ditafsir tetap
didelineasi.23 Bandara /
Pelabuhan
Bdr/
Plb /
20121
Kenampakan bandara dan
pelabuhan yang berukuran
besar dan memungkinkan untuk
didelineasi tersendiri.