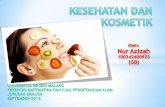KB sektor Kesehatan
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KB sektor Kesehatan
1
Peranan Sektor Kesehatan dalam Pembangunan Keluarga Berencana
dalam rangka
Kajian lanjut hasil Background Study untuk penyusunan RPJMN 2015-2019
2
Daftar Isi
Daftar Isi ........................................................................................................................................................ 2
Daftar Singkatan ............................................................................................................................................ 3
Bab 1. Pendahuluan ...................................................................................................................................... 5
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................... 5
1.2. Tujuan ........................................................................................................................................... 7
1.3. Metodologi .................................................................................................................................... 7
Bab 2. Analisis situasi .................................................................................................................................... 8
2.1. Sejarah perkembangan Keluarga Berencana ..................................................................................... 8
2.2. Kependudukan ................................................................................................................................. 10
2.3. Derajad kesehatan ibu ..................................................................................................................... 13
2.4. Situasi program KB di Sektor Kesehatan .......................................................................................... 20
2.4.1. Pelayanan KB di tingkat Masyarakat ......................................................................................... 20
2.4.2. Pelayanan KB di Puskesmas ...................................................................................................... 20
2.4.3. Pelayanan KB di Rumah Sakit .................................................................................................... 21
Bab 3. Pembangunan KB oleh Sektor Kesehatan ........................................................................................ 23
3.1. Program KB dalam upaya peningkatan kesehatan ibu .................................................................... 23
3.2. Peran institusi terkait dalam pelayanan kesehatan Ibu ................................................................... 23
Bab 4. Teknologi Program KB (dari sisi demand dan supply) ...................................................................... 30
4.1. Kualitas pelayanan KB ...................................................................................................................... 30
4.2. Pengembangan sumber daya manusia ............................................................................................ 30
4.3. Keamanan ber-KB............................................................................................................................. 31
4.4. Manajemen pelayanan KB ............................................................................................................... 32
4.5. Behavior change communication (BCC)/promotion counseling...................................................... 32
Bab 5. Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan .................................................................................... 34
Bab 6. KB dan BPJS ...................................................................................................................................... 36
Bab 7. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan KB 2015-2019 ................................................................. 38
Rujukan ....................................................................................................................................................... 41
3
Daftar Singkatan
AKI : Angka Kematian Ibu
ANC : Antenatal Care
ASFR : Age Specific Fertility Rate
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
BCC : Behavior Change Communication
BKIA : Bagian Kesehatan Ibu dan Anak
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CPR : Contraceptive Prevalence Rate
GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara
IMT : Indeks Massa Tubuh
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Atas
IUD : Intrauterine Device
JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
KB : Keluarga Berencana
KEK : Kurang Energi Kronis
KEMENKES : Kementerian Kesehatan
KH : Kelahiran Hidup
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIE : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
LILA : Lingkar Lengan Atas
LKBN : Lembaga Keluarga Berencana Nasional
MDG : Millenium Developemnt Goals
MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP : Metode Opersai Pria
MOW : Metode Operasi Wanita
NTB : Nusa Tenggara Barat
NTT : Nusa Tenggara Timur
P4K : Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PELITA : Pembangunan Lima Tahun
PKBI : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKBRS : Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit
PKRT : Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu
PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PTT : Pegawai Tidak Tetap
PUS : Pasanagan Usia Subur
PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat
RI : Republik Indonesia
4
RIFASKES Riset Fasilitas Kesehatan
RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar
RPJMN : Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional
RS : Rumah Sakit
RSAB : Rumah Sakit Anak dan Bersalin
SDKI : Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM : Sumber Daya Manusia
SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKN : Sistem Kesehatan Nasional
SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional
TB : Tuberculosis
TFR : Total Fertility Rate
UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
UNDP : United Nations Development Program
UU : Undang Undang
WHO : World Health Organization
WUS : Wanita Usia Subur
5
Bab 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Secara nasional, Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang baik pada satu dekade
terakhir. Pendapatan per kapita meningkat dari sekitar Rp 6 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar
Rp.32 juta rupiah pada tahun 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam golongan negara
berpendapatan menengah serta menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia
Tenggara. Perkembangan ekonomi tersebut diikuti dengan peningkatan proporsi penduduk kelas
menengah. Proporsi penduduk dengan tingkat pengeluaran antara dua sampai 20 dolar Amerika
per hari dalam sepuluh tahun terakhir meningkat dari sekitar 37 persen menjadi 56,7 persen pada
2013. Proporsi penduduk miskin juga terus menurun dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi
11,25 pada Maret tahun 2014 (BPS, 2014). Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga meningkat dari 0,540 pada tahun 2000 menjadi
0,684 pada tahun 2013 (UNDP, 2014).
Perkembangan ekonomi dan kesejahteraan tersebut, akan lebih baik jika issue kependudukan
dan keluarga berencana juga menunjang, artinya pertambahan penduduk yang disebabkan oleh
tidak berubahnya pengguna kontrasepsi satu dekade terakhir, tetap akan menjadi beban negara.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 juga memperlihatkan proporsi pengguna alat
kontrasepsi masih sekitar 60-an persen, bervariasi dari yang tidak ada yang ber-KB cara modern
(0.0%) di kabupaten Nduga (Provinsi Papua) sampai tertinggi (82,5%) di kabupaten Ogan
Komering Ilir Timur (Provinsi Sumatera Selatan).
Melihat variasi yang luar biasa dari pengguna kontrasepsi modern tersebut, sangat penting bagi
Indonesia untuk segera mengambil langkah kebijakan strategis agar pertumbuhan penduduk
dapat dikendalikan. Kita ketahui, berdasarkan hasil sensus 2010, penduduk Indonesia berjumlah
238.518.800 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah tersebut
diperkirakan akan mencapai 255,46 juta jiwa tahun 2015, dan akan menjadi 305,65 juta jiwa pada
tahun 2035 (BPS, 2013).
Analisis perlu dilakukan untuk menilai setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk masa yang akan
datang menghadapi variasi kependudukan yang akan berdampak pada semua masalah
kesehatan. Diketahui bahwa jumlah penduduk jika menggunakan estimasi tahun 2013 yaitu
sejumlah 248.484.191 yang berkisar dari 6637 jiwa (kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat)
sampai dengan 5.192.754 jiwa (kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat).
Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk untuk kabupaten/kota pada 6 region: Sumatera,
Jawa-bali, NTB-NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku–Papua dengan kisaran <200.000;
200.000-500.000, 500.000-1.000.000, dan >1.000.000. Jumlah kabupaten/kota masih
menggunakan posisi tahun 2013, yaitu sejumlah 497 dari 33 provinsi1, ketika Riskesdas 2013
dilakukan.
1 Jumlah Provinsi di Indonesia menjadi 34, setelah Kalimantan Timur terbagi dua pada tahun 2012, menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; jumlah kabupaten menjadi 410, dan kota 98.
6
Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Jumlah Penduduk dan Region, Indonesia 2013
Region
Klasifikasi Kabupaten/Kota menurut jumlah penduduk
<200.000 200.000-500.000
500.000 -1.000.000
>1.000.000 Total
Sumatera 58 64 24 5 151
Jawa-Bali 10 15 39 63 127
NTB-NTT 10 18 2 1 31
Kalimantan 23 24 8 0 55
Sulawesi 34 36 2 1 73
Maluku-Papua 50 10 0 0 60
Indonesia 185 167 75 70 497
Sumber: Analisis SP 2010, dan Proyeksi Penduduk 2013.
Seperti pada kondisi tahun 2013, dimana jumlah kabupaten dengan penduduk terbanyak
masih terpusat di Jawa, maka diperkirakan pada tahun 2035, kondisi ini masih akan
sama. Peningkatan jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan berbagai masalah
kesehatan.
Kecenderungan peningkatan urbanisasi juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan
penduduk. Wilayah perkotaan mulai menjadi pilihan bagi penduduk untuk bermukim,
tercermin dari proporsi penduduk yang tinggal di kota meningkat dari 17,4 persen tahun
1971 menjadi 50,2 persen tahun 2010, dan akan menjadi 67 persen tahun 2035.
Gambar 1. Kecenderungan Urbanisasi 1971-2035.
Sisi positif, dari urbanisasi adalah dapat meningkatkan akses seseorang terhadap pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Sisi negatif, terkadang urbanisasi tersebut cenderung tidak diikuti
dengan persiapan yang matang sehingga mereka tinggal di daerah kumuh. Daerah kumuh
perkotaan identik dengan masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya akan
berpengaruh ke status kesehatan masyarakat.
17.4
67.0
82.6
50.2
33.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
1971 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035
%
Kota Desa
7
1.2. Tujuan
Kajian berikut ini bertujuan untuk melengkapi background study yang sebelumnya telah dilakukan
agar terjadi pemahaman yang komprehensif mengenai keluarga berencana di Indonesia, dan
mengidentifikasi strategi dan program untuk mengurangi hambatan terkait peningkatan
penggunaan alat KB dari sektor kesehatan. Secara khusus, penggunaan alat kontrasepsi
merupakan indikator kependudukan dipilih acuan target akhir. Selain mencerminkan kondisi
pertumbuhan penduduk, pengguna alat kontrasepsi juga merupakan indikator strategis untuk
mengukur pembangunan kesehatan di masa depan.
Secara lebih spesifik, kajian ini melakukan:
– Peninjauan sejarah program Keluarga Berencana
– Analisis kondisi kependudukan di Indonesia dan derajat kesehatan ibu;
– Analisis situasi perkembangan program KB di sektor kesehatan;
– Tinjauan teknologi program KB dalam upaya peningkatan kesehatan ibu;
– Peran sektor kesehatn and sektor terkait dalam penyusunan berbagai rencana nasional
yang ditujukan untuk mencapai target,
– Identifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dan
program kependudukan dilihat dari sektor kesehatan, serta gap dalam kebijakan/program
yang telah dilaksanakan;
– Penyusunan saran mengenai kebijakan dan program, serta langkah-langkah yang penting
untuk program KB, termasuk kerjasama antarlembaga.
Penyusunan kajian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada upaya keluargar
berencana dalam menangani isu kependudukan dan kesehatan. Selain itu, hasil kajian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan bagi intansi terkait dalam menyusun strategi dan memfasilitasi
Pemerintah.
1.3. Metodologi
Penyusunan tinjauan strategis keluarga berencana sektor kesehatan ini dilakukan melalui empat
tahapan analisis, yaitu:
(i) analisis situasi yang dilakukan berdasarkan sejarah KB serta permalasahan yang
dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi,
(ii) analisis kebijakan dan program apa saja yang sudah/sedang dilakukan untuk mengatasi
masalah tersebut; bagaimana hasil atau efektivitasnya? Instansi apa saja yang terlibat
dan apa peran dan tanggung jawab mereka? Bagaimana kapasitas mereka dalam
menangani masalah keluarga berencana terkait dengan masalah kependudukan dan
kesehatan ?
(iii) analisis kesenjangan dalam kebijakan dan program untuk memahami kelemahan atau
kekurangn dalam kebijakan atau program yang telah dilakukan selama ini? serta
(iv) penyusunan rekomendasi untuk perbaikan program keluarga berencana sektor
kesehatan 2015-2019.
Adapun mekanisme penulisan dilakukan berdasarkan analisis kecenderungan dari data
Riskesdas, Rifaskes, SDKI, SP 2010, tinjauan pustaka, konsultasi, serta rapat-rapat dengan
pihak terkait.
8
Bab 2. Analisis situasi
2.1. Sejarah perkembangan Keluarga Berencana
Upaya membatasi kelahiran secara tradisional sudah dilakukan oleh masyarakat
Indonesia sejak tahun 1950-an ketika angka kematian bayi dan ibu melahirkan cukup
tinggi. Upaya mengatur kelahiran pada saat itu hanya terjadi dikalangan kelompok
tertentu saja, terutama dikalangan dokter. Pada waktu itu, para ahli kandungan berusaha
mencegah angka kematian dengan membentuk Bagian Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
Pada tahun 1957, dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – PKBI yang
melakukan pelayanan yang masih sangat terbatas. Baru pada tahun 1967 PKBI diakui
sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Pada tahun yang sama Kongres
Nasional I – PKBI dilakukan, yang salah satu keputusan adalah mengembangkan dan
memperluas usaha keluarga berencana dan bekerjasama dengan instansi pemerintah.
Pada tahun yang sama, Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani Deklarasi
Kependudukan Dunia yang berisi tentang pentingnya merencanakan jumlah anak, dan
menjarangkan kelahiran dalam berkeluarga.
Selanjutnya dikeluarkan instruksi Presiden pada tahun 1968 (Inpres No. 6, 1968) kepada
Menteri Kesejahteraan Rakyat yang isinya antara lain: i) membimbing, mengkoordinir
serta mengawasi segala aspirasi yang ada dalam masyarakat dibidang Keluarga
Berencana; ii) membentuk suatu Badan yang dapat menghimpun segala kegiatan di
bidang keluarga berencana yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan Inpres tersebut, Menkesra mengeluarkan Surat Keputusan tentang
pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan untuk membentuk Lembaga
Keluarga Berencana. Tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana
Nasional (LKBN).
Memasuki periode Pelita I (1969-1974) mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga
Berencana (BKKBN) berdasarkan Keppres No.8. tahun 1970, kemudian disempurnakan
melalui Keppres no. 33 tahun 1972, dimana status BKKBN berubah menjadi lembaga
pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Pada
periode Pelita I, program KB di masyarakat dikembangkan dengan pendekatan klinik,
karena masih banyak tantangan terhadap ide KB, sehingga pendekatan melalui
kesehatan.
Pelita II (1974-1979), pada periode ini pelaksanaan program KB nasional merubah
pendekatan yang semula berorientasi pada kesehatan, mulai melakukan integrasi
dengan sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan pendekatan integratif. Pada
Pelita III (1979-1984), dilakukan pendekatan kemasyarakatan yang mendorong peran
dan tanggung jawab masyarakat untuk mempertahankan peserta KB yang sudah ada
9
serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada periode Pelita III dikembangkan pula
strategi operasional yang bertujuan mempercepat penurunan fertilitas, dikenal dengan
sebutan Panca Karya dan Catur Bhava Utama. Selain itu pada periode yang sama
dilakukan strategi KIE yang diintegrasikan dengan pelayanan kontrasepsi dalaan Bm
bentuk ‘Mass Campaign’ yang dikenal denga nama ‘Safari KB Senyum Terpadu’.
Pada Pelita IV (periode 1983-1988) dikembangkan pendekaakn tan baru melalui
koordinasi aktif. Program KB dilakukan dengan strategi pembagian wilayah untuk
mengantisipasi laju kecepatan program, dicanangkan KB Mandiri, dipopulerkan
kampanye lingkaran biru KB. Gerakan KB diteruskan pada periode Pelita V (1988-1993)
yang berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia untuk
memberikan pelayanan KB. Strategi baru dilakukan, yaitu kampanye lingkaran emas,
dengan menawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi. Pada Lingkaran biru jenis
kontrasepsi masih sangat terbatas, pada lingkaran emas sampai 16 jenis.
Pada Pelita V ditetapkan UU No. 10 1992 tentang Perkembanagan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan pada GBHN 1993 difokuskan strategi gerakan
KB nasional untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dengan menunda usia
perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan
kesejahteraan keluarga.
Memasuki Pelita VI (1993-1998) BKKBN ditetapkan setingkat dengan kementerian,
dengan fokus kegiatan diarahkan pada pelayanan KB dan pembangunan keluarga
sejahtera yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluaga untuk
meningkatkan kualitas keluarga. Kegiatan yang dikembangkan diarahkan pada tiga
gerakan: Gerakan Reproduksi Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera, dan
Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Program KB mulai memudar memasuki periode reformasi, terjadi beberapa kali pimpinan,
sampai dengan diterbitkan UU No.52 tahun 2009 yang mengganti BKKBN dari Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional. Tindak lanjut dari UU no 52 tahun 2009 BKKBN direstrukrisasi
menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi.
Program KB selain dilakukan oleh BKKBN dan sektor kesehatan secara terintegrasi
menjadi bagian dari program KB nasional. Di sektor kesehatan, program KB menjadi
salah satu kegiatan dari program kesehatan ibu dan anak (KIA), dimana implementasi
kegiatannya antara lain memberikan penerangan dan motivasi keluarga berencana yang
seluas-luasnya kepada masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat.
Pelaksanaan program KB di sektor kesehatan menjadi tanggung jawab Puskesmas yang
masuk pada kegiatan perawatan dalam pelayanan KIA dan KB. Kegiatan perawatan ini
10
dilakukan sepenuhnya oleh dokter, bidan atau perawat yang sekaligus melaksanakan
kegiatan pemeriksaan, penyuntikan, pelayanan KB, pengobatan dan lain-lain.
Dari Pelita I sampai dengan Pelita VI pelaksanaan program KB sektor kesehatan tidak
terpisahkan dengan BKKBN. Masalah muncul setelah Pelita VI berakhir, dan dimulainya
periode reformasi, dan berubahnya sistem perencanaan pembangunan jangka panjang
dan mulainya sistem desentralisasi.
2.2. Kependudukan
Maju tidaknya suatu negara, dinilai melalui indeks pembangunan manusia/IPM (human
development index/HDI). Konsep pembangunan manusia ini meletakkan manusia
sebagai pelaku pembangunan yang harusnya berkualitas. IPM diukur melalui tiga
indikator penting yang sangat mendasar dan bersifat universal yaitu umur harapan hidup,
income per capita, dan pendidikan. Jika kebutuhan mendasar ini terpenuhi diharapkan
manusia dapat hidup lebih panjang, sehat wal’afiat, dan sejahtera (wealthy and healthy).
Program keluarga berencana yang membatasi kelahiran dan menjarangkan kelahiran
dari pasangan usia subur, sangat berhubungan erat karena mempunyai dampak untuk
kemajuan ketiga indikator IPM ini.
Untuk menilai keberhasilan program keluarga berencana pada umumnya dilihat dari
angka fertilitas, penggunaan alat/cara KB, dan unmet need. Dampaknya akan terlihat
pada laju pertumbuhan penduduk, yang diharapkan terjadi kecenderungan menurun
yang artinya jumlah penduduk akan stabil atau tidak terjadi ledakan pertambahan
penduduk.
Indonesia sudah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2.32 pada
periode 1971-1980 menjadi 1.97 pada periode 1980 – 1990, dan 1.45 pada periode 1990-
2000, akan tetapi terjadi kecenderungan meningkat menjadi 1.49 untuk periode 2000-
2010. (BPS, 2013). Kecenderungan angka fertilitas bisa diikuti dari SDKI, seperti yang
disajikan pada gambar 2. Terlihat ada kecenderungan penurunan yang cukup berarti dari
periode tahun 1981-1983, dari 4.3 menjadi 2.6 di periode tahun 1998-2002 dan stabil di
posisi 2.6 sampai periode 2003-2012. Dengan angka fertilitas yang stabil pada 2.6
selama 10 tahun terakhir menyebabkan jumlah kelahiran akan tetap meningkat terus dan
ini berdampak pada pertambahan penduduk. (SDKI, 2012).
Pada tabel 2 dapat dilihat kelompok umur 0-4 cenderung meningkat dari tahun 2010
sampai tahun 2014, kemudian mulai terjadi kecenderungan menurun pada tahun 2015.
Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk perempuan, dan yang harus menjadi fokus
perhatian program keluarga berencana adalah perempuan usia 10-14 sampai dengan
usia 50-54 tahun, yang jumlahnya akan menjadi 87 juta atau 34 persen dari total
penduduk pada tahun 2015. Biasanya yang menjadi perhatian untuk perempuan usia
reproduksi adalah 15-49 tahun yang berjumlah 69 juta atau 27 persen dari total
11
penduduk. Akan tetapi di Indonesia kelahiran sudah terjadi lebih dini yaitu pada usia 10-
14 tahun dan juga sampai dengan usia 50 54 tahun. (BPS, 2013).
Gambar 2. TFR Indonesia 1981-2012
Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur 2010-2015
Umur Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-4 23,454.40 23,680.90 23,852.70 23,994.20 24,086.80 24,065.50
5-9 22,518.00 22,632.40 22,767.30 22,931.90 23,109.50 23,330.40
10-14 22,165.60 22,230.10 22,280.90 22,309.80 22,360.20 22,461.50
15-19 21,558.10 21,678.30 21,812.10 21,931.20 22,024.70 22,095.40
20-24 20,939.40 21,039.00 21,148.70 21,250.70 21,352.40 21,447.90
25-29 20,589.90 20,636.60 20,646.60 20,663.80 20,716.30 20,810.40
30-34 19,987.20 20,105.90 20,240.50 20,348.10 20,430.90 20,448.30
35-39 18,514.10 18,829.00 19,104.30 19,365.90 19,587.10 19,816.10
40-44 16,564.30 16,958.40 17,332.80 17,683.20 18,004.70 18,295.10
45-49 14,165.30 14,585.10 15,015.20 15,447.00 15,867.40 16,266.50
50-54 11,479.50 11,980.00 12,440.60 12,877.20 13,313.70 13,766.50
55-59 8,546.30 9,015.20 9,515.70 10,026.00 10,518.10 10,972.70
60-64 6,156.70 6,432.50 6,753.40 7,116.80 7,518.80 7,955.30
65-69 4,651.20 4,775.60 4,908.50 5,062.80 5,253.40 5,489.60
70-74 3,375.50 3,469.40 3,565.30 3,661.70 3,757.00 3,852.00
75+ 3,853.30 3,942.30 4,040.60 4,147.80 4,263.80 4,388.50
Total 238,518.80 241,990.70 245,425.20 248,818.10 252,164.80 255,461.70
Sumber: BPS, 2013
4.3
3.33.0
2.9 2.8 2.6 2.6 2.6
3.7
2.82.6
2.3 2.4 2.4 2.32.4
4.5
3.6
3.23.2
3.02.7 2.8 2.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1981-1983 1984-1987 1988-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012
TF
R
Tahun rujukan
Kota+Desa
Kota
Desa
12
Tabel 3. Jumlah penduduk perempuan 2010-2015
Umur Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-4 11,405.70 11,538.80 11,636.80 11,726.10 11,785.40 11,792.10
5-9 10,975.80 11,026.20 11,093.80 11,166.80 11,252.20 11,356.00
10-14 10,832.00 10,850.40 10,872.00 10,888.50 10,911.90 10,954.30
15-19 10,657.60 10,695.70 10,733.60 10,763.60 10,786.90 10,806.40
20-24 10,404.50 10,446.90 10,498.70 10,542.00 10,583.90 10,618.60
25-29 10,340.10 10,346.50 10,328.00 10,315.20 10,318.10 10,354.90
30-34 9,998.20 10,080.70 10,167.60 10,238.00 10,280.70 10,279.20
35-39 9,196.00 9,358.90 9,505.60 9,648.20 9,784.50 9,922.20
40-44 8,242.30 8,433.30 8,616.00 8,789.00 8,950.50 9,099.70
45-49 7,067.60 7,284.80 7,500.50 7,712.80 7,918.20 8,114.40
50-54 5,646.60 5,928.60 6,186.70 6,427.70 6,663.10 6,900.80
55-59 4,167.60 4,389.80 4,649.20 4,927.10 5,198.50 5,445.60
60-64 3,127.50 3,251.10 3,382.10 3,531.60 3,714.10 3,937.80
65-69 2,462.40 2,519.20 2,587.90 2,666.80 2,753.20 2,846.00
70-74 1,856.20 1,904.20 1,949.90 1,995.10 2,042.00 2,092.80
75+ 2,286.00 2,333.20 2,385.80 2,443.60 2,506.40 2,574.20
Total 118,666.10 120,388.30 122,094.20 123,782.10 125,449.60 127,095.00
Sumber: BPS, 2013
Bukti ini dapat dilihat pada gambar 3, hasil Riskesdas 2010 dan 2013 yang menunjukkan
kejadian kehamilan pada usia 10-14 tahun dan 50-54 tahun.
Gambar 3. Persentase perempuan 10-54 tahun menurut status kehamilan,
Riskesdas 2010 dan 2013
Sumber: Riskesdas 2010, 2013
0.0
1
1.9
0
6.0
4
6.0
4
4.8
0
3.0
0
1.1
1
0.6
3
0.5
9
0.0
2
1.9
7
5.7
5
6.4
6
4.6
2
2.4
8
0.7
3
0.0
9
0.0
3
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
2010 2013
13
Jika tidak diantisipasi oleh program keluarga berencana, kejadian kehamilan akan
meningkat terus utamanya pada kelompok muda 10-14 tahun dan 15-19 tahun, mereka
akan menjadi penyumbang angka kelahiran yang tinggi, dengan kurun waktu reproduksi
yang lebih panjang.
Seperti terlihat pada gambar 4, sebenarnya perkawinan muda umur 10-14 tahun pada
penduduk sudah terjadi pada tahun 2000-an. Dan dari SDKI 2012, kejadian kelahiran
pada perempuan usia 15-19 tahun di perkotaan adalah 32 per 1000 perempuan, dan di
perdesaan lebih tinggi lagi yaitu 69 per 1000, atau secara nasional adalah 48 per 1000.
Gambar 4.
Presentase penduduk status kawin usia 10-35 tahun, Susenas 2004, 2010, 2012
Sumber: Atmarita, Analisis dari Susenas 2004, 2010, 2012
2.3. Derajad kesehatan ibu
Mewujudkan derajad kesehatan ibu yang setinggi-tingginya adalah satah satu agenda
pembangunan yang tercakup dalam tujuan pembangunan millennium (MDG’s 1990-
2015) yang akan berakhir dan dilanjutkan ke Sustainable Development Goals (SDG
2016-2030). Tahun 2014 adalah tahun terakhir fase pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN) 2010-2014, yang akan dilanjutkan ke fase berikutnya RPJMN 2015-
2019.
Indikator yang disepakati pada MDG’s untuk menilai meningkatnya kesehatan ibu, yaitu
target 5a. mengurangi 75 persen angka kematian ibu dalam kurun waktu 1990-2015, dan
target 5b adalah tercapainya akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi: 1)
CPR/kesertaan keluarga berencana aktif; 2) tingkat kelahiran remaja/ASFR 15-19; 3)
cakupan ANC; dan 4) unmet need, sepertinya masih jauh dari target yang ditetapkan.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2004 2010 2012
14
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2012 maupun Riskesdas 2013 posisi terakhir indikator dimaksud diatas dapat dilihat pada tabel 4. Pada saat ini berbagai estimasi menunjukkan masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Pertama, estimasi dari SDKI yang menunjukkan angka 359 (berkisar dari 239 – 478) per 100.000 kelahiran hidup. (SDKI, 2012). Kedua, adalah dari sensus penduduk 2010 yang memberi estimasi antara 316-366 per 100.000 kelahiran hidup (sesudah adjustment). (BPS, 2014). Sementara WHO mengeluarkan estimasi terbaru tahun 2013 adalah sebesar 190 (120-300) per 100.000 kelahiran hidup. Namun, apapun sumber yang kita pakai, mereka memberikan satu informasi yang sama bahwa AKI di Indonesia masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain, berada di kisaran 200 – 400 per 100.000 kelahiran hidup. (WHO, 2014).
Tabel 4
Target dan Pencapaian Kesehatan Ibu
Indikator Tahun 1990 Target RPJMN
Tahun 2014
Target MDGs
Tahun 2015 Pencapaian Tahun 2012/2013
AKI (per 100,000 kelahiran hidup)
390 118 102 359 (239-478) - (SDKI 2012);
346 (316-366) - (SP 2010)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
40,7% 90% 90% 78,7% - (SDKI 2012);
87,1% - (Riskesdas 2013)
CPR pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, saat ini, semua cara
49,7% 66% 61,9% (SDKI 2012);
59,7% (Riskesdas 2113)
CPR pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, saat ini, cara modern
47,0% 60,1% 65% 57,9% (SDKI 2012);
59,3% (Riskesdas 2013)
ASFR* usia 15-19 tahun (per 1000 remaja perempuan usia 15-19 tahun)
67 30 30 48 - (SDKI 2012)
Cakupan pelayanan antenatal
1 kunjungan 75% 95% 95% 95,7% - (SDKI 2012);
95,4% (Riskesdas 2013)
4 kunjungan (ANC1-1-2) 56 % 90% 90% 73,5% - (SDKI 2012);
70,4% (Riskesdas 2013)
Unmet need 12,7% 6,5% 5% 11.4% - (SDKI 2012)
Keterangan:
* ASFR = Age Specific Fertility Rate
Sumber: 1) Riskesdas 2007, 2010, 2013, 2) SDKI, 2012
AKI adalah indikator dampak dari berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan
derajad kesehatan ibu. Kematian ibu bisa dicegah jika dari awal ibu sudah sehat dan
sudah dapat dilakukan persiapan, terutama pada saat kehamilan bahkan sebelum
kehamilan. Pencegahan kehamilan, dapat dilakukan dengan mengurangi kehamilan,
kejadian empat terlalu misalnya bisa dihindari (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak
15
anak, terlalu sering) dengan menggunakan kontrasepsi. Dalam hal ini peran program
keluarga berencana menjadi sangat penting, yang ditunjukkan dari indikator pada tabel
4 di atas, yaitu CPR, ASFR, dan unmet need yang masih jauh dari yang diharapkan.
Kesertaan KB, walaupun CPR sudah hampir 60 persen (gambar 5), yang perlu
dikuatirkan adalah kesertaan KB menurut kelompok umur, yang menurut Riskesdas 2013
adalah seperti yang terlihat pada gambar 6. (Kemenkes, 2013).
Gambar 5
Proporsi penggunaan KB WUS kawin menurut Provinsi, Riskesdas 2013
Gambar 6
Proporsi penggunaan KB WUS kawin menurut kelompok umur, Riskesdas 2013
Tampak umur berisiko tinggi untuk kematian penggunaan KB lebih rendah, tidak sampai
50 persen (15-19 tahun, 45-49 tahun). Sedangkan tabel 5 menunjukkan penggunaan
55.8
59.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Papu
a
Ma
luku
NT
T
Paba
r
Kep.R
iau
Sum
ut
Ma
lut
Ace
h
Sulb
ar
Suls
el
Sultra
Sum
bar
DK
I
DIY
Ria
u
Kaltim
NT
B
Sulteng
IND
ON
ES
IA
Bante
n
Jatim
Jate
ng
Bali
Jaba
r
Babe
l
Goro
nta
lo
Sulu
t
Kals
el
Sum
sel
Beng
ku
lu
Kalteng
Jam
bi
Kalb
ar
La
mpu
ng
2010 2013
46.059.8 63.0 65.3 66.1 58.9
40.4
14.0
15.820.8 22.4 22.3
27.6
42.3
40.024.4
16.2 12.3 13.5 13.5 17.3
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Sekarang pakai Pernah KB Tidak Pernah
16
MKJP/Metode Kontrasepsi Jangka Panjang menurut karakteristik yang juga sangat
rendah, yaitu hanya 10,2 persen. (Kemenkes, 2013).
Tabel 5
Proporsi Penggunaan MKJP menurut karakteristik, Riskesdas 2013
Karakteristik MKJP
Kel. Umur
15-19 3.2
20-24 5.4
25-29 6.8
30-34 9.8
35-39 12.8
40-44 13.9
45-49 12.4
Tempat tinggal
Kota 11.2
Desa 9.2
Tingkat pendidikan
Tidak Sekolah 7.2
Tidak Tamat SD 8.7
Tamat SMP 9.1
Tamat SMP 8.7
Tamat SMA 11.8
D1-D3+ 18.1
Kuintil indeks kepemilikan
Terbawah 7.7
Menengah bawah 8.9
Menengah 9.5
Menengah atas 9.9
Teratas 14.0
Cakupan pelayanan antenatal, walaupun sudah hampir sesuai target, yang masih perlu
dipertanyakan adalah kualitas yang diberikan oleh para tenaga kesehatan, apakah ketika
mereka menemukan kasus-kasus kehamilan seperti anemia, hipertensi, oedema, dll
langsung dilakukan intervensi. Apalagi jika kasus-kasus kehamilan tersebut datang
melakukan pemeriksaan kehamilan tidak pada awal trimester. Pada tabel 4 di atas
cakupan pelayanan antenatal untuk 4 kunjungan, dengan asumsi-asumsi 1 kali pada
trimester I, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester ke 3, itu hanya 73,5 persen,
artinya ada 26,5 persen ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan ANC 1-1-2. (Kemenkes,
2013).
Perkawinan muda dan kurang gizi dapat menyebabkan tingginya kejadian kematian ibu,
dan risiko tingginya kematian neonatal. Mereka tidak siap untuk hamil, pertama karena
17
secara biologis memang belum siap, kedua adalah faktor lain yang memperberat seperti
kurang gizi atau penyakit infeksi yang menyertai, seperti TB-paru, pneumonia, atau diare
yang cenderung masih cukup dominan.
Tabel 6. Proporsi KEK perempuan 15-49 tahun,
Riskesdas 2007-2013
Umur (tahun) Hamil Tidak Hamil
2007 2013 2007 2013
15-19 31.3 38.5 30.9 46.6
20-24 23.8 30.1 18.2 30.6
25-29 16.1 20.9 13.1 19.3
30-34 12.7 21.4 10.2 13.6
35-39 12.6 17.3 8.9 11.3
40-44 10.3 17.6 7.9 10.7
45-49 5.6 20.7 8.1 11.8
Pada tabel 6 di atas menunjukkan proporsi perempuan umur 15-49 tahun (hamil atau
tidak hamil) yang kurang energi kronis (KEK) berdasarkan hasil pengukuran lingkar
lengan atas (Lila) < 23,5 cm. Ada kecenderungan meningkat cukup tinggi untuk semua
kelompok umur dari tahun 2007 ke tahun 2013. (Kemenkes, 2008; Kemenkes 2013)
Masalah gizi lainnya seperti anemia, juga bisa menjadi faktor penyebab tidak langsung
kematian ibu, dan juga jika ibu pendek (tinggi badan<145 cm), maka risiko untuk
melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), selain risikonya juga tinggi
untuk meninggal, jika disertai dengan komplikasi penyakit menular maupun tidak
menular.
Riskesdas 2013 memperlihatkan prevalensi anemia untuk ibu hamil adalah 37,1 persen,
tidak ada perbedaan prevalensi anemia ibu hamil di perkotaan (36,4%), dengan
perdesaan (37,8%). Sementara, proporsi wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun dengan
tinggi badan rata-rata <145 cm adalah 8,1 persen (ibu hamil), dan 8,3 persen (ibu tidak
hamil).Variasi antar provinsi dapat dilihat pada gambar 7 berikut, yang menunjukkan
variasi yang sangat lebar antar provinsi, mulai dari <10 persen, sampai yang tertinggi
hampir mencapai 30 persen. (Kemenkes, 2013).
18
Gambar 7. Proporsi WUS 15 49 tahun pendek (<145 cm) menurut provinsi, 2013
Sumber: Atmarita, analisis Riskesdas 2013
Riskesdas 2013 mengumpulkan data yang bisa mewakili sampai tingkat kabupaten,
masalah gizi lainnya yang juga dapat menjadi penyebab tidak langsung untuk kematian
ibu, adalah kurus. Kurus didefinisikan sebagai ibu mempunyai indeks massa tubuh (IMT)
<18,5. Disebut kurus kemungkinan intake makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak
mencukupi, atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika kondisi ini terjadi pada kehamilan
maka kehamilan mempunyai risiko tinggi pada janin atau ibu hamil.
Gambar 8 menunjukkan besaran masalah WUS 15-49 tahun yang kurus menurut provinsi
dan variasinya antar kabupaten/kota.
Gambar 8
Proporsi WUS 15-49 tahun kurus (IMT<18,5) menurut variasi kabupaten di 33 provinsi, 2013
Sumber: Atmarita, Analisis Riskesdas 2013.
8.1 8.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Su
msel
Ba
li
Ke
p.
Ria
u
Ma
luku
Lam
pun
g
DK
I
Ba
nte
n
Ka
ltim
Su
ltra
Su
lte
ng
NT
B
Ka
lba
r
DIY
Ma
lut
Su
lut
Pa
pu
a
Indo
nesia
Aceh
Jate
ng
Su
mb
ar
Su
lse
l
Ria
u
Ke
p.B
ab
el
Su
mu
t
Su
lba
r
Pa
ba
r
NT
T
Jab
ar
Ka
lte
ng
Jatim
Jam
bi
Be
ng
kulu
Go
ronta
lo
Ka
lse
l
Hamil Tidak Hamil
19
Provinsi Nusa tenggara timur menunjukkan prevalensi kurus yang sangat tinggi (>20%),
dan variasi antar kabupaten yang juga cukup lebar antar 12,5-35 persen, berikut adalah
Maluku (15%), dengan varasi antar kabupaten antara 10-25 persen. Provinsi dengan
besaran masalah kurus antar kabupaten, yang cukup lebar adalah Nusa Tenggara Barat,
dan Sulawesi Barat. (Kemenkes, 2013)
Perempuan memasuki usia untuk dapat mulai bereproduksi ditandai dengan mulainya
haid pertama, untuk perempuan di Indonesia menurut Riskesdas 2010, umur haid
pertama adalah 9-10 tahun (1,5%), 11-12 tahun (20,9%), dan 13-14 tahun (37,5%).
Dengan adanya 0,1-0,2 persen perempuan sudah menikah pada usia 10-14 tahun, maka
masalah kesehatan menjadi sangat penting. Diare dan ISPA atau kombinsi penyakit
infeksi ini (diare, ISPA, pneumonia, TB-paru dan batuk) adalah penyakit infeksi yang
mungkin menjadi kontribusi tidak langsung untuk kesehatan ibu menjadi tidak optimal
ketika konsepsi, disertai masalah anemia, dan kurang gizi lainnya.
Pada tabel 7 berikut mempresentasikan hasil riskesdas 2007 dan 2013 untuk perempuan
10-18 tahun yang sakit diare dan ISPA, dan juga kombinasi sakit diare, ISPA, pneumonia,
batuk, dan TB-paru, dan juga pendek untuk tahun 2013.
Tabel 7
Proporsi perempuan 10-18 tahun yang sakit tahun 2007 dan 2013
Umur (tahun)
Diare ISPA Sakit Pendek
2007 2013 2007 2013 2013 2013 10 8.3 5.6 28.3 26.3 35.0 33.7 11 8.8 6.2 25.9 25.2 34.1 35.8 12 8.5 5.9 24.0 24.3 33.3 34.9 13 7.7 5.2 23.4 23.4 31.4 34.1 14 7.4 6.2 22.1 20.5 29.7 32.8 15 7.4 6.8 21.0 21.3 30.5 29.7 16 7.5 5.9 21.1 21.9 30.9 26.0 17 7.6 7.1 20.8 22.3 31.6 23.3 18 8.8 6.8 20.3 20.7 30.3 26.2
Sumber: Atmarita, Analisis Riskesdas 2007 dan 2013.
Dari uraian di atas masalah kesehatan ibu masih sangat memprihatinkan, perlu upaya-
terintegrasi dan komprehensif untuk meningkatkan kesehatan ibu di Indonesia. Program
KB sangat diperlukan untuk ikut berpartisipasi dalam hal menunda kelahiran atau
menjarangkan kelahiran, agar generasi berikutnya tidak bermasalah dan kesehatan ibu
menjadi lebih baik.
20
2.4. Situasi program KB di Sektor Kesehatan
Pada Sektor Kesehatan, program KB menjadi bagian dari upaya prioritas penurunan AKI
bersamaan dengan:
i) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal,
ii) peningkatan pelayanan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,
iii) peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kehamilan/kebidanan;
iv) pelayanan KB berkualitas,
v) peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, responsif gender;
vi) kegiatan manajemen program kesehatan ibu.
Program KB di sektor Kesehatan dilaksanakan melalui sistem pelayanan kesehatan
komprehensif yang telah ada, mulai dari tingkat masyarakat, Puskesmas dan yang sederajat
dalam pelayanan kesehatan dasar sampai dengan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan
rujukan.
2.4.1. Pelayanan KB di tingkat Masyarakat
Pelayanan KB di tingkat masyarakat dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) melalui jejaring pelayanan dibawah supervisi Puskesmas seperti Posyandu,
Polindes, Poskesdes, Pos KB Desa, Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K), kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti PKK,
Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA), dll.
Jenis pelayanan KB ditingkat masyarakat mencakup penyuluhan KB, pelayanan kontrasepsi
sederhana seperti pil ulang dan kondom oleh kader, pos KB Desa; pil dan suntikan di Posyadu
meja-5, di Polindes, Poskesdes; pada P4K dilakukan penyuluhan KB dan identifikasi penggunaan
KB pasca salin, serta mengupayakan agar masyarakat memilih metode KB jangka panjang
(MKJP).
Tenaga pelayanan KB di tingkat masyarakat terdiri dari Bidan, Perawat, untuk pelayanan
kontrasepsi dan KIE medis, dan oleh Kader untuk penyuluhan KB. Monitoring pelaksanaan
program KB di tingkat masyarakat dilakukan oleh puskesmas terintegrasi dengan kegiatan
kesehatan ibu dan anak.
Kendala yang dirasakan dalam pelayanan KB di tingkat masyarakat ini adalah kurangnya tenaga
PLKB yang dapat membantu bidan dalam pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya KB.
2.4.2. Pelayanan KB di Puskesmas
Pelaksanan pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan di Puskesmas menjadi bagian dari
program pelayanan Kesehatan Ibu yang meliputi: 1) pelayanan pemasangan alat kontrasepsi, 2)
penanganan komplikasi kontrasepsi, dan 3) konsultasi keluarga berencana dengan pelayanan
KIE medis KB. Secara nasional menurut Riset fasilitas kesehatan (Rifaskes) 2011 yang dilakukan
Badan Litbang Kesehatan, 61,3 persen Puskesmas melakukan ketiga pelayanan KB tersebut
secara lengkap, 34,8 persen tidak lengkap, dan 3,9 persen tidak ada informasi.(Kemenkes 2012)
Secara rinci, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dilakukan di 88 persen Puskesmas, yaitu
pemasangan pelayanan alat kontrasepsi mantap (IUD, Susuk, Vasektomi). Untuk pelayanan
penanganan komplikasi kontrasepsi dilakukan di 64,5 persen Puskesmas, dan untuk pelayanan
21
konsultasi KB dilakukan di 95,8 persen Puskesmas. Masing-masing kegiatan pelayanan KB di
Puskesmas tersebut bervariasi untuk masing-masing provinsi (Rifaskes, 2011).
Selain informasi kegiatan pelayanan KB yang dilakukan Puskesmas, dikumpulkan pula informasi
pelatihan tenaga kesehatan terkait dengan pelayanan program KB. Rifaskes 2011 mencatat
persentase Puskesmas yang tenaganya mendapat pelatihan yang dilakukan pada tahun 2009
dan 2010, adalah sebagai berikut:
i) Pelatihan program pelayanan KB dilakukan di 45,4 persen Puskesmas, dengan variasi
antar provinsi dari yang terendah di Maluku (23,0%), dan yang tertinggi di Gorontalo
(92,3%).
ii) Pelatihan pemasangan alat kontrasepsi dilakukan di 50,8 persen Puskesmas, dengan
variasi antar provinsi yang terendah di Maluku (21,7%), dan yang tertinggi di Riau
(70,3%)
iii) Pelatihan penanganan kompliksi kontrasepsi dilakukan di 24,6 persen Puskesmas,
dengan variasi antar provinsi dari yang terendah di Maluku (7,5%) , dan yang tertinggi
di Nusa Tenggara Barat (38,9%).
iv) Pelatihan lengkap ketiganya adalah di 22,1 persen Puskesmas, yang bervariasi antara
5,6 persen (Provinsi Maluku) sampai 36,2 persen (Provinsi Nusa Tenggara Barat).
Selanjutnya, Rifaskes 2011 juga mengumpulkan informasi tentang keberadaan pedoman
program keluarga berencana yang meliputi 1) panduan praktis pelayanan kontrasepsi; 2)
panduan audit medik pelayanan KB; 3) panduan baku klinis KB; 4) pedoman pelayanan
kesehatan reproduksi terpadu; 5) panduan kontrasepsi darurat; dan 6) panduan penanggulangan
efek samping/kompliasi kontrasepsi. Sekitar 62 persen memiliki panduan praktis pelayanan
kontrasepsi, kemudian berturut-turut panduan Baku Klinis KB (40,2%), dan Panduan
penanggulangan efek samping/komplikasi kontrasepsi (36,9%). Hanya 22,0 persen Puskesmas
yang memiliki lengkap ke 6 jenis pedoman/panduan pelayanan KB tersebut.
Dilaporkan pula dari Rifaskes 2011 tentang Puskesmas yang menerima pengawasan, evaluasi
dan bimbingan secara lengkap untuk pelayanan KB terkait dengan ketiga kegiatan pokok tersebut
di atas, yaitu hanya 36,5 persen, dengan variasi terendah di Maluku (2,2%) dan tertinggi di Jawa
timur (67,5%).
2.4.3. Pelayanan KB di Rumah Sakit
Upaya kesehatan dalam mendukung program KB di Rumah Sakit adalah berkaitan dengan upaya
untuk mendukung pelayanan KB paska persalinan dan pasca keguguran. Pelayanan ini
mencakup semua jenis alat/obat kontrasepsi baik jangka panjang maupun jangka pendek,
penanganan efek samping, komplikasi, dan penanganan masalah kesehatan reproduksi.
Sasaran pelayanan KB di RS adalah pasangan usia subur, klien yang mengalami kegagalan dan
komplikasi kontrasepsi, klien pasca persalinan dan pasca keguguran, serta pasangan yang
mengalami masalah kesehatan reproduksi.
Pelayanan KB terbagi menjadi tiga yaitu pelayanan KB lengkap, pelayanan KB sempurna, dan
pelayanan KB paripurna. Pelayanan KB lengkap adalah pelayanan KB yang meliputi pelayanan
kontrasepsi kondom, pil KB, suntik KB, AKDR/IUD, pemasangan atau pencabutan implant, MOP,
serta penanganan efek samping dan komplikasi pada tingkat tertentu. Palayanan KB Sempurna
adalah pelayanan KB yang meliputi pelayanan KB lengkap dengan MOW, penanganan
22
kegagalan dan pelayanan rujukan. Pelayanan KB paripurna adalah pelayanan KB yang meliputi
pelayanan kontrasepsi sempurna ditambah penanganan masalah kesehatan reproduksi dan
sebagai pusat rujukan.
Adapun jumlah RS yang ada saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Kategori Kepemilikan RS Umum RS Khusus Total
RS Publik Pemerintah 772 94 866 Swasta, non profit 539 201 740 RS Privat Swasta 473 251 724 BUMN 59 7 66
Total 1843 553 2396 Sumber: Dirjen BUK, Kemenkes, online, 20 November 2014
Jumlah RS di atas perlu dievalauasi lagi untuk ketersediaannya dalam memberikan pelayanan
KB di RS, khususnya terkait dengan Pasca Persalinan dan pasca keguguran yang tidak segera
menggunakan kontrasepsi. Karena biasanya, jika keluar RS dengan kondisi tidak menggunakan
kontrasepsi, maka mereka memberikan kontribusi cukup besar terhadap tingginya unmet need,
dan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Pelayanan KB di RS sangat potensial
memberikan sumbangan pencapaian target program KB nasional, dan menurunkan AKI.
23
Bab 3. Pembangunan KB oleh Sektor Kesehatan
3.1. Program KB dalam upaya peningkatan kesehatan ibu
Target nasional berkaitan dengan Pelayanan KB dalam rangka pelayanan kesehatan ibu
pada RPJMN 2015-2019, yang merupakan kelanjutan RPJMN 2010-2014 berdasarkan
pertimbangan kondisi tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Target Nasional yang Berkaitan dengan Pelayanan Keluarga Berencana
Indikator dampak dan luaran
Pelayanan KB
Kondisi
Tahun 2010 2014
Target RPJMN
Tahun 2015-2019
AKI (per 100.000 KH) 346 306
TFR 2,6 2,3
ASFR usia 15-19 tahun (per 1000 remaja
perempuan usia 15-19 tahun) 48 30
CPR cara modern 59.3% 65%
Kehamilan yang tidak diinginkan 17% <10%
Unmet need 11.4% 8%
Target di atas memerlukan kerja keras dari kementerian lembaga terkait. Untuk AKI
diharapkan menjadi 306 pada tahun 2019 dari kondisi tahun 2010-2014 yang masih
diestimasikan 346 per 100.000 KH. Untuk TFR diambil berdasarkan proyeksi dari posisi
2,6 tahun 2010, yang diperkirakan akan menjadi 2,3 pada tahun 2019.Target ASFR usia
15-19 tahun pada tahun 2019, menggunakan target MDG’s 2015. Demikian halnya untuk
CPR pada tahun 2019, menggunakan target MDG’s 2015, yaitu 65 persen. Kehamilan
yang tidak diinginkan diantara PUS (perkosaan, kurangnya pengetahuan tentang
kontrasepsi, terlalu banyak anak, alasan kesehatan janin, usia ibu masih terlalu muda,
atau masalah ekonomi) cenderung meningkat (SDKI 2007 menunjukkan 17%),
diharapkan pada akhir tahun 2019 menjadi kurang dari 10 persen. Untuk unmet need
dengan posisi 11,4 persen pada tahun 2012, diharapkan bisa menjadi 8 persen pada
tahun 2019.
3.2. Peran institusi terkait dalam pelayanan kesehatan Ibu
Dari uraian analisis situasi, diketahui masalah kesehatan ibu demikian kompleks, mulai
dari remaja, bahkan anak. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ibu adalah
semua upaya terkait untuk meningkatkan kesehatan ibu berikut dengan faktor-faktor yang
berpengaruh, seperti pelayanan keluarga berencana dalam upaya pengaturan dan
penjarangan kehamilan dan kelahiran, peningkatan pendidikan dan pengetahun
perempuan, perbaikan status kesehatan dan gizi perempuan.
24
Berdasarkan Undang-Undang RI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bagian
ketujuh: Keluarga Berencana, pasal 78 menyebutkan bahwa:
(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan
kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang
sehat dan cerdas.
(2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas
pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana
yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangundangan.
UU 52 tahun 2009 yang mengamanatkan tentang perkembangan kependudukan dan
permbangunan keluarga dengan pertimbangan sebagai berikut:
i) Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan
termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur
ii) Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi
titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang
besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat
tercapainya kondisi yang ideal
iii) Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala
aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan
berdampingan dengan bangsa lain
iv) Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga
berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka
kematian, pengarahan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan
pengaturan perkawinan serta kehamilan.
UU 52 tahun 2009 tersebut, menjadi panduan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2010-2014 yang dituangkan ke dalam visi Kementerian Kesehatan
adalah menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mewujudkan
visi terebut ditetapkanlah misi Kementerian Kesehatan untuk (1) meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan
masyarakat madani; (2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; (3)
menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; dan (4) menciptakan
tata kelola kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian
Kesehatan mengembangkan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan
25
preventif. 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk
mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata
dan bermutu. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat
kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.
Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, program KB menjadi bagian dari program-program
dalam bidang bina kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan setempat. Bidang ini
mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan program promosi kesehatan dan
UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat), peningkatan gizi masyarakat, serta
kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Konsep program pelayanan di bidang bina kesehatan
masyarakat sebenarnya cukup komprehensif, jika implementasinya dilakukan secara
terintegasi. Pada pelayanan kesehatan ibu, misalnya pelayanan kesehatan dilakukan
mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan maternal dengan pencegahan
komplikasi, perlindungan kesehatan reproduksi, dan Keluarga berencana.
Implementasi program dari Bidang Bina Kesehatan ini dilakukan melalui Pusat
Kesehatan Masyarakat [Puskesmas] sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang
tersedia di setiap kecamatan di Indonesia (Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat). Implementasi dari strategi Kementerian Kesehatan dillakukan melalui 6
Upaya Kesehatan Wajib Puskesmas yang meliputi: i) Upaya Promosi Kesehatan, ii)
Upaya Kesehatan Lingkungan, iii) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga
Berencana, iv) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, dan vi) Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Menular dan Upaya Pengobatan.
Pelayanan KB yang termasuk upaya kesehatan wajib di Puskesmas ini terkait dengan
strategi percepatan penurunan AKI. Kementerian Kesehatan menetapkan 9 provinsi
dengan populasi terbanyak sebagai fokus program, yaitu Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kesembilan provinsi ini juga merupakan bagian dari
10 provinsi penyangga utama dalam intensifikasi penggarapan pembangunan KB yang
ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN]. Satu
provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur. Bentuk implementasi program,
sebenarnya sama dengan apa yang sudah diuraikan sebelumnya, hanya dilakukan lebih
intensif dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat.
Penyelenggaraan Pelayanan KB merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional
26
[SKN]. SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen
program kementerian secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan kesehatan yang dimaksud
dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah
dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.
Sebagai bagian dari SKN maka Pelayanan KB juga diselenggarakan secara berjenjang
di berbagai tingkat administratif. Sebagaimana dinyatakan dalam SKN, Pelayanan KB
juga ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat,
profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif
tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.
Dua institusi Kementerian Kesehatan dan BKKBN adalah pelaku utama untuk
meningkatkan pelayanan KB dalam konteksi pelayanan kesehatan ibu, disamping
kementerian lainnya seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk
meningkatkan pendidikan perempuan dalam upaya menunda perkawinan muda,
Kementerian sosial untuk perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
Kementerian agama, maupun Kementerian Dalam Negeri. Pembagian peran
kementerian lembaga terkait ini perlu dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian
keuangan untuk pengaturan efisiensi penganggaran, supaya tidak terjadi tumpang tindih.
Disamping kementerian lembaga di atas upaya untuk peningkatan kesehatan ibu perlu
juga melibatkan badan-badan organisasi non-pemerintah di tingkat pusat maupun
daerah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan juga lembaga-lembaga mantra
pembangunan internasional, nasional, maupun lokal di tingkat provinsi dan
kebupaten/kota.
a. Peran Kementerian Kesehatan
Pelayanan KB adalah bagian dari implementasi pendekatan life cycle yang menggunakan
prinsip continuum of care dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu. Peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan dimulai sejak masa pra-hamil, kehamilan,
persalinan dan nifas, bayi, balita, hingga remaja dan wanita usia subur. Untuk masa pra-
hamil, program ditujukan pada pemahaman PUS untuk merencanakan kehamilan
dengan baik dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga disarankan
untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan penggunaan
kontrasepsi non-hormonal. Untuk PUS juga diperlukan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Terpadu (PKRT) di Puskesmas. Pelayanan KB kepada ibu hamil diberikan terintegrasi
dengan pelayanan antenatal, antara lain melalui Kelas Ibu Hamil, penggunaan buku KIA,
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), dan konseling KB
pasca-persalinan pada saat kunjungan antenatal. Segera sesudah bersalin, pelayanan
KB diberikan dalam bentuk konseling dan pelayanan KB pasca persalinan.
27
b. Peran BKKBN
Pelayanan KB berperan sangat strategis dalam upaya komprehensif untuk menurunkan
AKI, dan pengaturan kependudukan terkait dengan tingkat fertilitas. Dengan program
pelayanan KB yang komprehensif berarti ada upaya mengatur kelarhiran anak, jarak dan
usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi dan perlindungan sesuai
dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Pelayanan KB tidak
saja ditujukan untuk ibu tapi keluarga, terutama peran suami juga harus mempunyai
kedudukan yang sama dengan istri dalam melaksanakan KB untuk menentukan cara KB
yang diminati bersama.
c. Peran kementertian pendidikan dan kebudayaan
Integrasi yang dilakukan adalah upaya yang berorientasi pada perubahan sikap, perilaku
keluarga dan masyarakat. Anak dan generasi muda adalah target utama yang diharapkan
ke depan memiliki nilai Perilaku Hidup Berwawasn Kependudukan sebagai wujud
manusia Indonesia yang resional, cerdas, dan bertanggungjawab. Dengan demikian
sinergisitas program Keluarga Berencana dengan Pendidikan adalah memasukak
kurikulum tentang kependudukan dan keluarga berencana untuk mendidik generasi
muda agar paham sehingga terjadi perubahan pola pikir generasi muda mengenai
pentingnaya keluarga berencana, antara lain upaya terkait dengan penundaan usia
perkawinan, pengetahuan tentang penjarangan kehamilan, serta keluarga kecil bahagia
dan sejahtera.
d. Peran Kementerian Agama
Keterlibatan Kementerian Agama dalam program Keluarga Berencana bertujuan sama
yaitu dalam rangka mwwujudkan kelaurga kecil dan sejahtera. Kementerian Agama
melalui pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha and Konghucu dapat
melakukan pembinaan masyarakat termasuk diantaranya penyuluhan program keluarga
sakinah, keluarga berencana bagi calon pengantin.
e. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada semua aspek kehidupan menuju
kelaurga yang mandiri, sehat, dan sejahtera. Kementerian pemberdayaan perempuan
perlu melakukan upaya-upaya terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan
(pendidikan, kesehatan, ekonomi) dan perlindungan terhadap perempuan, antara lain:
i) upaya peningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-
laki ber KB;
ii) upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja dalam
pendewasaan usia perkawinan berbasis gender;
iii) upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di berbagai bidang kehidupan
(sosial budaya ekonomi dan pendidikan)
28
iv) upaya peningkatan partidipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana
v) upaya peningkatan kesejateraan dan perlindungan anak
vi) upaya menghaspus berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
f. Peran Kementerian Sosial
Kementerian Sosial menetapkan visinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yang
dapat diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
sosial selutuh warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Dalam hal ini Kementerian Sosial
berkepentingan untuk mensukseskan program keluarga berencana dalam mewujudkan
keluarga mandiri, sehat, dan sejahtera. Integrasi program kementerian sosial dengan
program keluarga berencana bisa dalam bentuk, antara lain:
i) Upaya peningkatan aksesibiltas perlindungan sosial untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dalam Program Keluarga Harapan,
yang memfokuskan pada keluarga miskin
ii) Upaya pengembangan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi
masyarakat
iii) Upaya perlindungan masyarakat dari segala risiko sosial, perlakuan salah,
tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial
g. Peran Kementerian Dalam Negeri
Dalam menuju Keluarga Sejahtera, Kementerian Dalam Negeri sangat berperan melalui
pelaksanaan 10 program PKK. Gerakan PKK sebagai wadah aktivitas sosial
kemasyarakatan bagi keluarga sangat perlu untuk mengembangkan potensi keluarga
sebagai wahana utama dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Program keluarga berencana sangat membutuhkan peran aktif PKK di lapangan melalui
bantuan kader serta jajaran pemerintah di desa yang didukung pemerintahan kecamata,
kabupaten, dan provinsi.
h. Peran institusi non-pemerintah
Lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
dan keluarga berencana seyogyanya memberikan dukungan teknis pelayanan keluarga
berencana dan kesehatan reporduksi, yang belum dilakukan secara optimal oleh
lembaga pemerintah. Bentuk kegiatanya antara lain:
i) penyelanggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan keseharan reproduksi
ii) operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB dalam upaya peningkatan
partisipasi pria
iii) penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hdiup
ibu, bayi dan anak
29
iv) membantu pemerintah dalam penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi, termasuk unmet need
v) membantu pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
untuk institusi terkait.
vi) melakukan penyuluhan pentingnya keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi
vii) melakukan dukungan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
viii) membantu pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan
keluarga berencana.
30
Bab 4. Teknologi Program KB (dari sisi demand dan supply)
4.1. Kualitas pelayanan KB
Kementerian Kesehatan bersama dengan BKKBN harus dapat memberikan pelayanan
KB kepada PUS dengan akses dan kualitas pelayanan yang baik. Artinya pelayanan KB
tersedia pada semua level administrasi dengan standar prosedur pelayanan yang sama.
Untuk menyediakan pelayanan yang standar tersebut maka dibutuhkan pelatihan untuk
semua petugas yang terlibat mulai dari petugas di tingkat masyarakat (Polindes,
Poskesdes), sampai ke tingkat Provinsi, baik di RS maupun di Dinas Kesehatan.
Program pelayanan Keluarga Berencana perlu meyakinkan bahwa setiap individu atau
PUS mempunyai pengetahuan yang cukup dan benar untuk memilih semua cara KB.
Perlu dipertimbangkan tentang kepuasan pengguna KB, dan dievaluasi terus menerus
untuk PUS yang tidak ber-KB (discontinue). Dari SDKI 2012, misalnya diketahui
discontinuation rate untuk semua alasan adalah 27.1 persen, tertinggi untuk penggunaan
PIL (40,7%), diukuti kondom laki-laki (31,2%), dan injeksi (24,7%). Sementara ada 13
persen yang juga mengganti cara ber-KB.
Metode Kontrasepi Jangka Panjang (MKJP) dan/atau kontrasepsi non-hormonal yang
masih rendah perlu dipertimbangkan juga untuk ditingkatkan. Program pelayanan KB
perlu memperhatikan keberadaan supply untuk kebutuhan (demand) masyarakat yang
sudah mau memilih cara sterilisasi misalnya, apakah pelayanan tersebut sudah tersedia
dari RS ketika mereka mau memilih cara tersebut.
Antisipasi peningkatan kualtias pelayanan KB dapat dilakukan dengan melakukan:
i) Menyediakan pelayanan KB sesuai standard di setiap tingkat administrasi
ii) Mengembangkan database yang dapat dimonitor terus menerus untuk
ketersedian SDM yang terlatih di semua tingkat administrasi
iii) Menyediakan logistik yang cukup sesuai demand masyarakat
iv) Mengembangkan rencana aksi untuk mengurangi unmet need
v) Melatih petugas secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB
4.2. Pengembangan sumber daya manusia
Kualitas sumber daya sebagai pelaku dalam pemberian pelayanan KB kepada
masyarakat sangat diperlukan. Sistem pelayanan yang terstandar perlu dilakukan oleh
tenaga terlatih untuk kepentingan melakukan identifikasi alat KB yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Pengembangan sumber daya diutamakan mulai dari tenaga yang
memberikan pelayanan langsung untuk masyarakat. Untuk pelaksanaan pelayanan
31
kesehatan dan KB diperlukan SDM yang mencukupi dalam jumlah dan jenis, dan
kualitasnya, serta terdistribusi merata.
Sebelum masuk periode reformasi terdapat tenaga PLKB di tingkat desa yang dapat
bekerja sama dengan tenaga kesehatan, utamanya bidan dan perawat melalui
Posyandu, atau pelayanan Puskesmas lainnya. Hal ini perlu diaplikasikan kembali,
ketersediaan PLKB akan membantu tenaga kesehatan yang sudah banyak dengan
berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, minimal membantu dalam memberikan
penyuluhan agar masyarakat ber-KB, menjarangkan/menunda kehamilan, dll. Pada
masa sebelum reformasi, setiap 1 orang PLKB ditetapkan dapat bertugas di 2 desa.
Dengan jumlah desa yang sudah 80.000-an maka dibutuhkan sekurangnya 40.000
PLKB, dan ini akan membantu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
Untuk tenaga kesehatan, khususnya bidan yang fungsinya memberikkan pelayanan
kesehatan termasuk KB kepada seluruh masyarakat. Menurut IBI pada tahun 2013
diketahui ada sejumlah lebih dari 175.000 bidan, dengan distribusi berdasarkan
keanggotaan IBI sebagai berikut:
i) bekerja di RS: 11.632;
ii) bekerja di RS, RSAB, RS Swasta: 17.133;
iii) bekerja di Puskesmas: 57.489;
iv) bekerja di Desa/Poskesdes 10.793;
v) bidan PTT biasa: 23.137;
vi) bidan PTT terpencil: 10.808;
vii) praktik mandiri: 35.333;
viii) institusi lain: 1.549;
ix) Pendidikan: 7.250.
Lebih lanjut dari IBI menyatakan baru sekitar 11.000-an bidan delima, yang artinya sudah
lulus kualifikasi bidan. Tidak dijelaskan kemampuan bidan di desa dalam memberikan
pertolongan persalinan dan pelayanan KB sesuai standar atau belum, karena terkendala
dengan sarana tempat tinggal yang bergabung menjadi Poskesdes.
Jika PLKB dan bidan berkualitas ini tersedia, maka diharapkan mereka bisa bekerja sama
dalam memberikan pelayanan kesehatan dan KB pada masyarakat.
4.3. Keamanan ber-KB
Keamanan ber-KB adalah suatu kondisi dimana masyarakat memilih alat/cara KB dan
merasa nyaman menggunakannya. Jika masyarakat tahu dan merasa aman, maka
tujuan program KB yang sebenarnya untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk bisa
tercapai. Target atau CPR yang tidak tercapai pada saat ini, diasumsikan bahwa masih
ada masyarakat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, kemungkinan mereka tidak
32
tahu, atau alatnya tidak tersedia, atau mereka tidak mampu untuk membeli, selain
kemungkinan ada faktor budaya, atau merasa tidak aman.
Untuk itu diperlukan edukasi, advoksai dan promosi tentang KB kepada masyarakat.
Edukasi tentang KB itu sangat penting dan mendesak, diharapkan dapat disampaikan
kepada masyarakat sedini mungkin melalui kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah-
sekolah, misalnya. Advokasi dan promosi KB juga harus menyesuaikan dengan budaya
setempat. Pada daerah terpencil mungkin bisa dijangkau dalam bentuk leaflet, poster,
dan lain sebagainya, sedangkan untuk daerah tidak terpencil, atau perkotaan dapat
menggungkan terknologi komunikasi yang ada saat ini, seperti televise, radio, sms, atau
bentuk media online lainnya.
Kajian perlu terus dilakukan untuk mengetahui mengapa masyarakat tidak ber-KB agar
ditemukan cara atau teknologi terbaru, misalnya dalam menghambat kehamilan yang
aman.
4.4. Manajemen pelayanan KB
UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran
anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi,
perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga
berkualitas.
Untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan alat kontrasepsi yang sampai pada
masyarakat sesuai sasaran dan tepat waktu. Antisipasi pokok persoalan perlu segera
dilakukan mulai dari tersedianya alat kontrasepsi di masyarakat sampai kompetennya
tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat tesebut. Dengan demikian keterbatasan
akses dan kualitas pelayanan KB dapat diatasi.
Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah:
i) Penyediaan alat, obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS sampai desa.
ii) Menyediakan tenaga dan meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan
penyuluhan/konseling KB
iii) Melakkan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pelayanan KB
iv) Melakukan standarisasi dan sertifikasi kepada tenaga pelayanan KB
4.5. Behavior change communication (BCC)/promotion counseling
Untuk memberikan kesadaran atau meningkatkan pengetahuan seluruh masyarakat,
tentang pentingnya kesehatan reproduksi sehingga mereka mau ber-KB sangat
diperlukan. Masyarakat disini adalah semua kelompok umur dari laki-laki maupun
33
perempuan, atau keluarga secara utuh. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya
ber-KB selain untuk pengaturan dan penjarangan kehamilan, dan pencegahan beberapa
penyakit infeksi yang berhubungan dengan penyakit kelamin masih sangat terbatas. BCC
yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi AKI. Seyogyanya diperlukan
suatu keterkaitan antar pendekatan pelayanan KB dan kegiatan BCC di semua
komponen kesehatan reproduksi. BCC sebagai salah satu komponen strategi komunikasi
sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan KB. BCC ini seyogyanya dilakukan
dengan pertimbangan sosial dan budaya masyarakat.
Adapun pendekatan BCC yang dapat dilakukan untuk perubahan perilaku masyarakat
antara lain:
i) Menyampaikan informasi yang bertujuan untuk merubah tingkat kesadaran
masyarakat dengan cara kampanye yang bersifat nasional tentang pentingnya
keluarga berencana. Kampanye ini tentunya melibatkan seluruh institusi yang
berkepentingan untuk suksesnya KB.
ii) Memperkuat penyampaian informasi yang diperlukan untuk meningkatkan
pengetahuan pada masyarakat tentang KB, bisa didukung dengan peraturan
pemerintah setempat
iii) Berupaya untuk merubah kebiasaan/budaya/persepsi yang salah dari
masyarakat ke pengetahuan dan perilaku yang positif tentang KB.
iv) Menciptakan suasana lingkungan yang bertujuan merubah kebiasaan negatif
menjadi pengetahuan dan kesadaran positif
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terlaksananya BCC seperti diatas mungkin bisa
dilakukan melalui:
i) Advokasi yang merupakan bagian dari mobilisasi sosial untuk para perencana
program, pembuat kebijakan di seluruh intitusi terkait
ii) Capacity building untuk pengembangan media penyampaian pesan melalui
radio, televisi, atau poster, brosur, leaflet, dll
Sebagai bagian dari semua kegiatan BCC, ada hal penting untuk kondisi Indonesia yang
akan datang yaitu penundaan usia perkawinan, hal ini tentunya ditargetkan pada remaja
perempuan. Kegiatan terkait dengan tujuan ini bisa dilakukan bersamaan dengan
kegiatan BCC yang sudah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi perlu advokasi yang
ditujukan pada pemuka agama, politikus, dan para ketua LSM dalam rangka menurunkan
proporsi perkawinan dini. Adapun pelaku dari BCC ini di lapangan adalah tenaga
kesehatan, utamanya dokter bidan dan perawat, yang dibantu oleh PLKB.
34
Bab 5. Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan
Hasil analisis situasi menunjukkan adanya beberapa masalah strategik, seperti masih
tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun,
dan masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya unmet
need dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi, yang ditandai dengen CPR
yang tidak bisa mencapai sesuai yang ditargetkan. Dampaknya adalah AKI yang
cenderung meningkat, dan TFR yang cenderung stabil di posisi 2.6 dalam 10 tahun
terakhir.
Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah
dan non-pemerintah dalam penyelenggaraann pelayanan KB. Rendahnya pengguna
MKJP menunjukkan masih rendahnya permintaan atas pelayanan KB, atau belum
optimalnya ketersediaan, keterjangakauan, dan kualitas pelayanan KB, termasuk
pelayanan KIE dan konseling pada masyarakat.
Strategi pelaksanaan Program Keluarga Berencana mengikuti sistem desentralisasi,
dengan memprioritaskan lokasi-lokasi kebupaten dimana ketersediaan sumber daya
untuk pelayanan KB sangat terbatas. Pada saat ini terdapat fasilitas pelayanan
kesehatan primer sebanyak kurang lebih 9.510 Puskesmas, diantaranya adalah
Puskesmas perawatan, dan 23.059 Pustu, yang didukung upaya kesehatan bersumber
masyarakat yang meliputi 51.996 Poskesdes dan Polindes. Fasilitas pelayanan
kesehatan sekunder dan tersier yang tersedia meliputi 833 Rumah Sakit Pemerintah,67
Rumah Sakit BUMN, 721 Rumah Sakit Swasta non-profit, dan 548 Rumah Sakit Swasta.
Ketersediaan tenaga kesehatan sebagai pemberi Pelayanan KB semakin membaik,
walaupun belum mencapai target yang diinginkan dan belum merata di seluruh wilayah
Indonesia. Target yang diinginkan adalah tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk.
Saat ini baru tersedia 49,5 bidan per 100.000 penduduk. Provinsi Aceh dan Bengkulu
memiliki rasio yang terbaik, yaitu masing-masing 193,4 dan 142,3 bidan per 100.000
penduduk. Rasio terendah ditemukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, masing-masing
21,5 dan 23,5 bidan per 100.000 penduduk. Target ketersediaan dokter umum yang
diinginkan adalah 40 per 100.000 penduduk. Saat ini di tingkat nasional baru tersedia
13,6 dokter umum per 100.000 penduduk. Rasio terbaik terdapat di Sulawesi Utara dan
Yogyakarta, yaitu masing-masing 38,7 dan 35,5 dokter umum per 100.000 penduduk.
Sementara rasio terendah terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu masing-masing
6,4 dan 7,4 dokter umum per 100.000 penduduk.
Adapun isu strategis yang sudah dicanangkan pada peringatan Hari Keluarga Nasional
tahun 2014 ini, yang pada intinya mengingatkan kembali peran keluarga untuk
memantapkan kembali program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan
kesehatan di Indonesia. Program-program terdahulu yang diarahkan pada pengendalian
jumlah penduduk dan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kualitas penduduk hingga
35
peningkatan pembinaan keluarga meliputi Balita, Anak, Remaja dan lansia. Diharapkan,
kondisi saat ini, dimana desentralisasi/otonomi daerah sudah diberlakukan selama
hampir 15 tahun, maka pemerintah daerah kedepan lebih mendukung prioritas program
kependudukan, kesehatan, dan keluarga berencana dengan lebih memperhatikan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Momentum pemantapan program kependudukan dan Keluarga Berencana sangat erat kaitannya dengan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Keberhasilan KB, akan berpengaruh terhadap penurunan peluang kehamilan atau pengaturan kehamilan guna menghindari faktor resiko penyulit kehamilan dan persalinan, seperti 4 Terlalu dan 3 Terlambat. Faktor resiko 4 terlalu, seperti: terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat merupakan kondisi yang sebisa mungkin dihindari ketika hamil, oleh karena itu pengaturan kehamilan sangatlah perlu dilakukan dengan pemantapan program Keluarga Berencana. Hasil analisis pada uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa dalam kondisi keberlebihan tenaga bidan di Puskesmas, yang belum terdistribusi merata di seluruh desa, dan minimnya jumlah PLKB hampir di seluruh Provinsi di Indonesia perlu diantisipasi. Dilain pihak, pemilihan cara KB pada masyarakat juga perlu ditingkatkan, yang saat ini menjadi kendala yang cukup berarti (MKJP masih rendah), yang akan memberikan potensi terjadinya kehamilan dengan kondisi berisiko tinggi, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada peningkatan AKI. Selain itu upaya konseling KB harus dilakukan secara terus-menerus tidak saja hanya pada perempuan, tapi juga pada kelompok pria atau seluruh anggota keluarga, dengan memperhatikan isu sosial budaya setempat. Beberapa isu strategis yang harus dilakukan adalah mengatasi beberapa hal terkait dengan:
1) Pencapaian target dan indikator yang belum optimal 2) Meningkatkan akses dan lualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum optimal 3) Mencegah kelahiran yang terjadi pada remaja 4) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia
kesehatan 5) Meningkatkan ketersedian, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi
serta alat kesehatan 6) Penyediaan kecukupan alokok di fasilitas kesehatan yang memberi pelayanan
KB 7) Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 8) Mensinergiskan tujuan nasional dalam rencana pembangunan daerah 9) Desentralisasi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah 10) Komitment stakeholder (legistlatif dan eksekutif) di setiap tingkatan 11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat 12) Penguatan manejemen data dan sistem informaso 13) Pengembangan pembiayaan kesehtana dalam JKN 14) Monitoring dan evaluasi di setiap level.
36
Bab 6. KB dan BPJS
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang implementasinya secara nasional per 1 Januari
2014. Program ini ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang
komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan keluarga berencana
hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik
institusi pelayanan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk
program tersebut selama mereka menandatangni sebuah kontrak kerja sama dengan
pemerintah.
Masalah kependudukan dan keluarga berencana masih menjadi perhatian pemerintah,
apalagi di era JKN. Permenkes No.71 tahun 2013 yang menjamin bahwa pelayanan
kontrasepsi adalah termasuk pelayanan dasar sehingga mendapat porsi pembiayaan
yang cukup. Kerja sama antara BKKBN dengan (BPJS) kesehatan ini diperlukan sebagai
upaya peningkatan pelayanan KB. Bentuk pelayanan KB melalui BPJS meliputi
konseling, kontrasepsi dasar, kontrasepsi jangka panjang (vasektomi dan tubektomi),
dan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatan. Yang akan
ditanggung dalam BPJS kesehatan adalah untuk jasa layanannya di fasilitas kesehatan
dasar maupun lanjutan (RS) yang masuk dalam sistem JKN. Termasuk pemasangan
maupun pelepasan alat kontrasepsi seperti metode operasi wanita (MOW) dan metode
operasi pria (MOP).
BKKBN ditugaskan untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi peserta BPJS Kesehatan,
khusus penerima bantuan iuran (PBI), yaitu 86,4 juta jiwa. Keberadaan program JKN
adalah peluang bagi program KB, selain itu kepastian cakupan kepesertaan KB lebih
besar lagi bagi masyarakat miskin. BKKBN bertugas menggerakkan secara berjenjang
mulai dari perwakilan BKKBN provinsi dan Satuan Kerja sama dan koordinasi dengan
Dinas Kesehatan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dan Puskesmas di wilayah
kerjanya dalam pelaksanaan program KB melalui pertemuan berkala, bimbingan teknis
dan surpevisi terpadu.
Adapun tugas lain dari BKKBN dalam BPJS kesehatan adalah menyediakan dan
mendistribusikan materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk penggerakan
pelayanan KB dan kesehatan reprodusi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi serta
menjamin kersediaan alat dan obat kontrasepsi seusia dengan kebutuhan pelayanan KB
ke seluruh fasilitas pelayanan yang terintegrasi dan bekerja sama dengan BPJS
kesehatan.
Dalam pelaksanaanya masih disadari masih belum sempurna, proses penyempurnaan
program terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga
berencana yang lebih baik ke masyarakat. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah
37
melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta RS membuka berbagai
saluran pengaduan dan permintaan inforrmasi dari masyarakat sebagai langkah untuk
terus menyempurnakan program ini.
Pelayanan KB yang masuk dalam JKN menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) ini akan berdampak kepada kualitas penduduk yang semakin baik.
Masyarakat Indonesia sehat, pelayanan KB lebih terjamin, dan diharapkan SDM juga
semakin baik.
.
38
Bab 7. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan KB 2015-2019
Berdasarkan indikator pelayanan kesehatan ibu yang masih belum banyak berubah,
maka strategi program Pelayanan Keluarga Berencana tahun 2015-2019 perlu dilakukan
lebih komprehensif lagi. Memperhatikan permasalahan yang sudah diuraikan pada
analisis situasi, maka pertimbangan strategi kedepan, khususnya untuk RPJMN 2015-
2019 seyogyanya berupaya untuk:
i) Menekan angka kelahiran remaja dengan cara meningkatkan partisipasi
sekolah minimal sampai tamat SMA, sehingga dapat terjadi penundaan
perkawinan yang terjadi diusia remaja. Peran ini dilakukan oleh sektor
pendidikan.
ii) Meningkatkan status gizi anak dan remaja agar pada saat konsepsi mereka
pada kondisi kesehatan optimal, tidak anemia, sakit-sakitan, atau kurang gizi
lainnya. Peran ini dilakukan oleh berbagai sektor, utamanya sektor kesehatan
untuk hal-hal yang terkait dengan program spesifik kesehatan, dan sektor
lainnya yang berkaitan dengan program sensitif, seperti ansipasi kemiskinan,
dan pemberdayaan keluarga atau masyarakat, dan juga peningkatan
pendidikan.
iii) Menekan kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy), dengan
tujuan mengurangi “4 terlalu”: terlalu muda (<20 tahun), terlalu tua (>35 tahun),
terlalu banyak (.4 anak), dan terlalu dekat (<2 tahun). Strategi ini dapat
dilakukan oleh kesehatan yang akan berperan dalam memberikan promosi
kesehatan terkait meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi. Dapat
juga sektor lain, seperti Pendidikan, BKKBN, dan Pemberdayaan perempuan
terlibat untuk upaya ini.
iv) Mencegah komplikasi kehamilan, dengan mengupayakan peningkatan kualitas
pelayanan antenatal. Strategi ini dilakukan oleh Kesehatan dengan
mengutamakan pada peningkatan kompetensi bidan agar pelayanan yang
diberikan dapat lebih berkualitas.
v) Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Upaya ini mutlak dilakukan
oleh sektor kesehatan dengan membenahi fasilitas kesehatan yang ada,
memperbaiki sistem rujukan, dan peningkatan kompetensi bidan maupun
dokter.
vi) Mempromosikan penggunaan MKJP dan/atau non-hormonal sesuai dengan
kelompok usia PUS. Upaya ini dapat dilakukan oleh BKKBN, Kesehatan,
Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, atau LSM swasta untuk menjelaskan
berbagai pilihan alat/cara kontrasepsi yang sesuai.
vii) Memperhatikan keterjangkauan pelayanan KB pada daerah-daerah sulit,
kepulauan, terisolir, terpencil, dan perbatasan. Upaya ini dilakukan secara
terintegrasi antara Kesehatan, BKKBN, serta LSM swasta.
viii) Memberikan pelayanan KB yang berkualitas, terhindar dari komplikasi,
ketidakberlangsungan, dan kegagalan kontrasepsi. Upaya ini dilakukan secara
terintegrasi antara Kesehatan, BKKBN, serta LSM swasta.
39
ix) Meningkatkan kompetensi tenaga yang memberikan pelayanan KB dengan
melakukan pelatihan secara periodik. Upaya ini sangat diperlukan dalam
rangka memberikan pelayanan kesehatan dan KB yang berkualitas. Institusi
kesehatan berkepentingan untuk melakukan upaya ini dan bekerja sama
dengan institusi pendidikan
x) Meningkatkan sarana dan prasarana, alat dan obat kontrasepsi, ketersediaan
pedoman pelayanan dalam upaya untuk menjaga mutu. Upaya ini dilakukan
secara terintegrasi antara kesehatan dan BKKBN.
xi) Melakukan advokasi terus menerus kepada seluruh pimpinan pada institusi
terkait tentang kependudukan, KB dan ketahanan keluarga, serta
KIE/penyuluhan melalui mass media, poster, dll ke seluruh lapisan masyarakat
yang dapat dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan, Posyandu,
dasawisma, dll. Upaya ini dilakukan oleh seluruh sektor terkait.
Usulan strategi kedepan tersebut di atas dapat dijabarkan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi institusi terkait kedalam perencanaan program 2015-2019. Berbagai bentuk
implementasi program ditujukan untuk mencegah kematian ibu, dan ledakan penduduk,
yang ditandai dengan indikator yang sudah disepakati bersama, seperti AKI dan TFR.
Untuk sektor kesehatan, implementasi program KB dilaksanakan melalui system
pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi mulai dari tingkat masyarakat,
Puskesmas dan yang sederajat sampai dengan tingkat Rumah Sakit sebagi dukungan
rujukan, dengan prinsip pelaksanaan Continuum of Care dalam upaya peningkatan
kesehatan ibu, mulai dari remaja dan pasangan usia subur (PUS). Adapun upaya konkrit
untuk sektor kesehatan antara lain:
Di tingkat Masyarakat:
1. Penguatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), melalui posyandu,
Polindes, Poskesdes
2. Penguatan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K) dan penguatan peran Kepala Desa, Camat
3. Penguatan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti PKK dengan
Dasa wismanya, Kelompok Peminat KIA (KP-KIA), dll
Di tingkat Puskesmas dan yang sederajat: tetap mengacu pada pelayanan kesehatan
wajib di Puskesmas, dimana pelayanan KB menjadi bagian dari pelayanan KIA
1. Meningkatkan keberadaan Puskesmas pada daerah terpencil, terisolir,
perbatasan, dan kepulauan.
2. Menambah jumlah Puskesmas pada daerah padat penduduk.
3. Memperhatikan/memfokuskan keberadaan tenaga kesehatan pada daerah padat,
terpencil, terisolir, perbatasan, dan kepulauan, serta peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dan KB yang
berkualitas dan merata.
40
4. Meningkatkan koordinasi antara puskesmas dengan institusi pelayanan KB
swasta yang sederajat dengan puskesmas
Upaya konkrit di atas dapat dilaksanakan jika jumlah tenaga kesehatan bidan, maupun
dokter ditambah dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang, sehingga pada tahun 2019
dapat mencapai minimal 50.000 dokter umum, dan 300.000 bidan. (Rasio ideal yang
dibutuhkan penduduk untuk pelayanan kesehatan: 1 dokter melayani 5000 penduduk; 1
bidan melayani 850 penduduk). Tenaga kesehatan tersebut harus semuanya profesional,
agar pelayanan dapat dilakukan berkualitas dan merata ke seluruh pelosok Indonesia.
Di tingkat Rumah sakit:
Setiap RS dipastikan tersedia pelayanan PKBRS dengan sarana yang memadai seperti
alat kontrasepsi, konseling, dan sistem monitoringnya. Oleh karena itu diperlukan:
a. Koordinasi BKKBN setempat dengan RS pemberi pelayanan IUD, Post partum
untuk follow up akseptor setelah pulang dari RS
b. Konseling tentang KB sangat penting diberikan kepada ibu-ibu hamil mulai dari
perawatan kehamilan pada waktu ANC/antenatal care dan juga PNC/Postnatal
Care, sehingga setiap ibu pasca persalinan sudah menggunakan kontrasepsi
sebelum pulang dari RS
c. Pelatihan konseling dan medis teknis untuk provider tentang KB PP (Pasca
Persalinan) & KB PK (Pasca keguguran) khususnya Insersi IUD Post Partum.
d. Menyediakan IUD dan IUD KIT di Rumah sakit dan menyediakan materi KIE
tentang KB di RS
41
Rujukan
1. UNDP 2014. Human Development Report, 2014
2. BPS 2014. Laporan Kemiskinan, WEB BPS, online, 2014
3. BPS, 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Bappenas, BPS, UNFPA,
Jakarta 2013.
4. BPS, 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025. Bappenas, BPS, UNFPA,
Jakarta, 2005.
5. Kemenkes 2008. Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta: Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
6. Kemenkes 2010. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta: Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
7. Kemenkes 2012. Laporan Nasional Riset Fasilitas Kesehatan 2011 untuk
Puskesmas.
8. Kemenkes 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
9. Kemenkes 2013. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana 2014-
2015.
10. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Kementerian Kesehatan dan MEASURE DHS, ICF Internasional. 2013.
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Calverton, Maryland, USA: BPS
dan MEASURE DHS, ICF Internasional.
11. UU RI nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.
12. WHO. 2014. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013. Geneva: WHO.
13. Badan Pusat Statistik. Presentasi Kecenderungan AKI, Razali, unpublished, 2014.