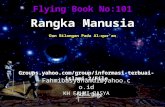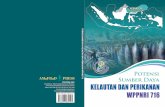PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
-
Upload
ubrawijaya -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
MAKALAH
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN
Disusun guna memenuhi tugas matakuliah hukum dan peraturan
perikanan dan kelautan yang dibimbing oleh bapak Dr. H Rudianto
Disusun oleh;
Catur A. Pamungkas 125080600111052
Septian Bagaskara 125080600111065
Nur Farida Purwanti 12508060011168
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
1
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah
daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi
daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi
oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan
perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih
dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti
sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan
manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz, 1972;
Soegiarto, 1976;Beatly, 1994 dalam Direktorat Jenderal Pesisir
dan Pulau Kecil 2003).
Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan
wilayah peralihan (Interface) antara ekosistem darat dan laut,
serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan
yang sangat kaya Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri
bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan
mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.
(Clark, 1996).
2
Masyarakat merupakan pelaku utama bagi pembangunan, maka
diperlukan kualitas sumber daya manusia yang berpotensial,
sehingga masyarakat dapat bergerak pada arah pembangunan untuk
menuju cita-cita rakyat Indonesia, yaitu bangsa yang makmur dan
berkepribadian yang luhur, terlebih lagi pada zaman yang semakin
hari bertambah tuntutan yang harus dipenuhi diera modern ini
maupun yang akan datang, masyarakat dituntut untuk mempunyai
ketrampilan atau kompetensi dalam dirinya supaya dirinya menjadi
manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi bangsa dan
Negara, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh manusia maka
diperlukan adanya pendidikan. Dunia pendidikan memang dunia yang
tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Karena selama manusia
itu ada, perbincangan tentang pendidikan akan tetap ada di dunia,
sehingga mustahil manusia hidup tanpa pendidikan di dalamnya,
kerena itu ada sebuah tanggung jawab untuk mengetengahkan apa dan
bagaimana pendidikan itu yang harus kita bagun dan konstruksi
kalau kita masih ingin dianggap sebagai manusia(Oktama,2013).
Sumber daya alam yang melimpah belum tentu merupakan jaminan
bahwa suatu Negara atau wilayah itu akan makmur, bila pendidikan
sumber daya manusianya kurang mendapat perhatian. Upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas bersama
dan berjangka waktu yang panjang karena menyangkut pendidikan
bangsa disepanjang daerah pesisir mata pencaharian penduduk
umumnya nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih
karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara
sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang
3
mempunyai nilai ekonomi. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi
masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain menjadi
nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. masyarakat
nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda
dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Karakteristik
yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah
memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja
tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal,
kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap
keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekpresif,
solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks
(laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum
perempuan), dan berperilaku konsumtif(Kusnadi, 2009:39).
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang di bahas dalam makalah ini adalah;
Apa pengertian dari nelayan?
Bagaimana kondisi nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya
laut?
Solusi apa yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya
laut?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah;
Menjelaskan pengertian dari nelayan,
4
Menjelaskan kondisi nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya
laut,
Mendeskripsikan solusi yang diambil oleh Kementrian
Pendidikan Nasional, kementrian kelautan dan perikanan
serta kementrian tenaga kerja dalam meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam pemanfaatan
sumberdaya laut,
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kehidupan Nelayan
Secara umum nelayan yang dimaksud di sini mengacu pada orang
yang secara aktif melakukan usaha penangkapan ikan atau binatang
air di laut atau di perairan umum, seperti penebar dan penarik
pukat, pengemudi perahu layar dan pawang. Secara umum pengertian
perikanan menerangkan telur dan anak-anak ikan, teripang, karang
dan udang-udang.Semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dalam
bidang penangkapan ikan, budidaya ikan, dan usaha orang-orang di
pesisir pantai yang berhubungan dengan laut atau istilahnya
nelayan. Nelayan adalah orang yang melakukan aktivitas
penangkapan ikan di laut atau air tawar.(Sarjulis, 2011)
Kondisi nelayan saat ini sangat dilematis, dengan sumber
daya alam laut yang luar biasa, nasib nelayan seakan berjalan
ditempat. Adalah hal yang rasional apabila nelayan hidup dalam
kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar nelayan
masih merupakan masyarakat tertinggal dibanding komunitas
5
masyarakat lain. Nelayan sering disebut sebagai masyarakat
termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the
poor). Itu disebabkan salah satunya karena tingkat pendidikan
mereka masih rendah. Masa depan kelestarian pengelolaan potensi
kelautan kita membutuhkan kearifan dan sumberdaya manusia yang
memiliki kompetensi untuk mengelola dan memanfaatkannya. Kondisi
bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat
kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak
melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber
Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan
berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam
pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas
tangkapan tidak mengalami perbaikan.
Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat
kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup.
Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika
dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun
kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat
penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik,
melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada
lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi. Deskripsi
diatas merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat
nelayan umumnya di Indonesia.
Terdapat 5 (lima) masalah pokok terkait penyebab kemiskinan
masyarakat nelayan, diantaranya:
6
1. Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan kemiskinan
masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup
dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian
dalam menjalankan usahanya.
2. Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya
belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya
manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga
sangat rendah.
3. Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi
masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat
penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik,
melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
4. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir
memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para
nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada
tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
5. Program pemerintah yang belum memihak nelayan, kebijakan
pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan
terkait penanggulangan kemiskinan yang selalu menjadikan
masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro
nelayan mutlak diperlukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang
akan mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan.
Berdasarkan pada sejumlah variables yang mempengaruhi
pendapatan nelayan tersebut, sedikitnya ada sembilam permasalahan
teknis yang membuat sebagian besar nelayan masih miskin.
7
Pertama, pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir (seperti
mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuari) yang semakin
dahsyat, dan perubahan iklim global ditenggarai menurunkan stok
(populasi) SDI.
Ketiga, sebagian besar nelayan menangani (handling) ikan hasil
tangkapan selama di kapal sampai di tempat pendaratan ikan
(pelabuhan perikanan) belum mengikuti cara-cara penanganan yang
baik (Best Handling Practices). Akibatnya, mutu ikan begitu sampai di
tempat pendaratan sudah menurun atau bahkan busuk, sehingga harga
jualnya murah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kapal ikan
tidak dilengkapi dengan palkah pendingin atau wadah (container)
yang diberi es untuk menyimpan ikan agar tetap segar. Selain
itu, banyak nelayan tardisional yang beranggapan bahwa membawa es
berarti menambah biaya melaut, apalagi kalau tidak dapat ikan
atau hasil tangkapnnya sedikit, atau esnya mencair sebelum
mendapatkan ikan, maka rugi besar.
Keempat, hampir semua nelayan tradisional mendaratkan ikan hasil
tangkapannya di pemukiman nelayan, tempat pendaratan ikan (TPI),
atau pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang tidak dilengkapi
dengan pabrik es atau cold storagedan tidak memenuhi persyaratan
standar sanitasi dan higienis. Sehingga, semakin memperburuk
mutu ikan yang berimplikasi terhadap harga jual ikan. Hampir
semua nelayan tradisional tidak bisa mendaratkan ikannya di
pelabuhan perikanan samudera (PPS) atau pelabuhan perikanan
nusantara (PPN) yang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan
8
sanitasi dan higienis, karena mereka harus membayar biaya tambat-
labuh yang mahal (tidak terjangkau).
Kelima, di masa paceklik dan kondisi laut sedang berombak besar
atau angin kencang (badai), antara 2 sampai 4 bulan dalam
setahun, nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Bagi
nelayan dan anggota keluarganya yang tidak memiliki usaha lain,
saat-saat paceklik seperti ini praktis tidak adaincome, sehingga
mereka terpaksa pinjam uang dari para rentenir yang biasanya
mematok bunga yang luar biasa tinggi, rata-rata 5 persen per
bulan. Di sinilah, awal nelayan mulai terjebak dalam ‘lingkaran
setan kemiskinan’, karena pendapatan yang ia peroleh di musim banyak
ikan, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari juga
dikeluarkan untuk bayar utang sekaligus bunganya.
Keenam, pada musim paceklik, harga jual ikan di lokasi pendaratan
ikan biasanya tinggi (mahal), tetapi begitu musim ikan (peak
season) tiba, harga jual mendadak turun drastis. Lebih dari itu,
nelayan pada umumnya menjual ikan kepada padagang perantara
(middle-man), tidak bisa langsung kepada konsumen terakhir.
Sehingga, harga jual ikan yang mereka peroleh jauh lebih murah
dari pada harga ikan yang sama di tangan konsumen terakhir.
Padahal, jumlah pedagang perantara itu umumnya lebih dari dua
tingkatan.
Ketujuh, kebanyakan nelayan membeli jaring, alat tangkap lain,
BBM, beras, dan bahan perbekalan lainnya untuk melaut juga dari
pedagang perantara yang jumlahnya bisa lebih dari dua tingkatan,
tidak langsung dari pabrik atau produsen pertama. Sehingga,9
nelayan membeli semua sarana produksi perikanan tersebut dengan
harga yang lebih mahal ketimbang harga sebenarnya di tingkat
pabrik. Kondisi ini tentu membuat biaya melaut lebih besar dari
pada yang semestinya.
Kedelapan, harga BBM dan sarana produksi untuk melaut lainnya
terus naik, sementara harga jual ikan relatif sama dari tahun ke
tahun, atau kalaupun naik relatif lamban. Hal ini tentu dapat
mengurangi pendapatan nelayan.
Kesembilan, sistem bagi hasil antara pemilik kapal ikan, nahkoda
kapal, fishing master, dan ABK ditenggarai jauh lebih
menguntungkan pemilik kapal. Dan, yang paling dirugikan adalah
ABK. Karena itu, pada umumnya pemilik kapal modern (diatas 30
GT) beserta nahkoda kapal dan fishing master sudah sejahtera,
bahkan kaya. Sementara, ABK nya masih banyak yang miskin.
Kesepuluh, pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara
tetangga, di antaranya Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.
Dengan lemahnya tindakan pemerintah terhadap penyelesaian batas
perairan terkait Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara tetangga
yang tidak tuntas selama puluhan tahun menyebabkan gerbang
terdepan itu menjadi lahan empuk pencurian.
Konstalasi sumberdaya pesisir dan laut selalu berdampak
terhadap komunitas nelayan kecil hampir di seluruh wilayah
nusantara ini. Eksistensi nelayan tradisional hampir selalu tidak
pernah diperhitungkan. Posisi tawar mereka sangat kecil
dibandingkan dengan keberadaan nelayan besar atau para pengusaha
10
perikanan skala besar. Bahkan anggapan terburuk yang telah di
labelkan terhadap para nelayan kecil ini adalah sebagai perusak
lingkungan. Disisi lain hal ini tak dapat dipungkiri, aktifitas
illegal fishing (bom ikan) oleh nelayan tradisional masih terus
berlanjut, walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mengurangi kegiatan illegal ini, namun tingkat kriminal
terhadap lingkungan ini masih cukup tinggi. Kondisi ini
diperparah dengan lemahnya pengawasan dan model pengelolaan
sumberdaya pesisir-laut yang tidak ramah lingkungan.
Nasib nelayan tradisional di perbatasan sangat miskin
dibanding nelayan asing yang kehidupannya gemerlap. Dari segi
peralatan dan kapal pun, nelayan Indonesia yang tinggal di
perbatasan sangat jauh berbeda dari nelayan asing.
2.2 Permasalahan Pendidikan Dalam Masyarakat Nelayan
Masyarakat nelayan sering dinilai lebih terbelakang daripada
masyarakat perkotaan dalam hal derap pembangunan, dalam arti
seluas-luasnya. Padahal mereka dapat mencukupi hidup keseharian
jika bisa memenejnya dengan baik. Namun semua itu hanya bersifat
memenuhi kebutuhan primer saja. Kemiskinan yang terjadi pada
masyarakat nelayan disebabkan karena kebijakan yang terlalu
terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat. Sedangkan
pembangunan sektor kelautan kurang mendapatkan perhatian serius
dari pemerintah dan sering terpinggirkan dan juga Masyarakat
pantai masih belum banyak dikaji oleh para sejarawan. Padahal
11
nelayan yang usahanya menangkap ikan telah memberikan kontribusi
bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah setempat(Sarjulis, 2011)
Pada keluarga nelayan yang kebanyakan berada di
daerah pesisir, pada umumnya tingkat pendidikannya rendah
yaitu lulusan SD dan juga lulusan SMP dan bahkan ada
juga yang tidak pernah sekolah. Tanpa menutup kemungkinan
ada yang sekolah sampai tingkat menengah keatas bagi
mereka yang tergolong mampu. Pada keluarga yang mampu
dalam kondisi ekonominya biasanya termotivasi untuk
menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tinggi ataupun
setidaknya lebih tinggi daripada pendidikan orang tuanya.
kurang perhatiannya orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya
dan karena masalah ekonomi yang kurang, kesulitan-kesulitan
ekonomi tidak memberikan kesempatan bagi rumah tangga
nelayan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka.
Di samping itu, kemudahan akses untuk bekerja di sektor
perikanan tangkap, tuntutan ekonomi keluarga dan kesulitan
dalam mencari peluang kerja lainnya sebagai akibat
kegagalan pembangunan pedesaan, telah memperkuat barisan nelayan
dengan tingkat kualitas sumber daya yang rendah. Dalam benak
pikiran mereka, yang terpenting adalah bisa bekerja
(menangkap ikan), dapat penghasilan dan bisa makan setiap
hari (Kusnadi, 2003:85)
Nelayan masih tetap berada dalam taraf sosial ekonomi yang
sederhana seperti nelayan yang turun ke laut masih mengandalkan
12
alat penagkapan yang masih tradisonal. Nelayan tradisonal masih
mengandalkan perahu dayung. Walaupun sudah ada sebagian nelayan
yang memiliki perahu yang digerakkan dengan mesin tempel, tetapi
alat tangkap yang digunakan masih berupa pancing, jaring, jala,
dan pukat. Karena itu hasil yang diperoleh sangat terbatas dan
tidak mampu bersaing dengan daerah lain.Selain itu adanya
keterbatasan pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta
teknologi
yang dipunyai, membuat mereka kurang mampu menghadapi tantangan
alam. Karena hasil tangkapan tidak menentu, yang bergantung pada
musim dan cuaca.(Sarjulis, 2011)
Kondisi kehidupan sosial ekonomi nelayan dengan penghasilan
yang tidak menentu dan tidak mampu menhadapi tantangan alam yang
buruk dengan peralatan yang sederhana meskipun sudah ada
peralatan yang di gerak oleh mesin namun semua itu belum mampu
membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi garis
kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan Mereka
tidak berdaya dalam mengikuti perkembangan teknologi penagkapan
ikan. Bahkan kadang-kadang mereka menghadapi resiko yang sangat
besar dari laut. Mereka sering di timpa gelombang pasang sehingga
menghancurkan komplek pemukiman dan peralatan dalam menagkap ikan
(Sarjulis, 2011)
Umumnya, nelayan bisa bertahan hanya dan hanya jika didorong
semangat hidup yang kuat dengan motto kerja keras agar kehidupan
mereka menjadi lebih baik. Nelayan tradisional berjuang keras
13
melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat pada saat pasang naik
untuk mendapatkan ikan. Dengan hanya mengandalkan kemampuan mesin
tempel misalnya, nelayan dapat berada pada radius 500 M dari
pinggir pantai dan dengan cara seperti ini nelayan akan
mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan bila menangkap ikan
di bibir (tepi pantai) pada radius 200 M, yang ikannya sudah
langka.(Kompas Com, 26 Maret 2009)
Bagi para nelayan pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan
turun temurun tanpa pernah belajar sebagai nelayan yang
modern.Sehingga pada usia meningkat remaja anak nelayan mulai
diajak berlayar dan ikut melaut oleh orang tuanya atau pamannya,
sehingga diantara mereka putus sekolah. Kini harus dipahami bahwa
kehidupan nelayan memerlukan perhatian yang multi dimensi.
Tantangan yang terbesar adalah bagaimana membangun kehidupan
nelayan menjadi meningkat pendidikan dan kesejahterannya.
Asumsi yang ditegakkan, kesejahteraan akan dapat ditingkatkan
jika tingkat pendidikan anak nelayan ditingkatkan. Karena
berbekal ilmu pengetahuan yang cukup akan mengangkat harkat dan
martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya
yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir. “Usaha ke
arah ini haruslah bermuara pada peningkatan kemakmuran nelayan,
terutama nelayan kecil dan petani ikan” (Indrawadi, 2009).
Kondisi masyarakat nelayan di wilayah Indonesia yang
identik dengan kemiskinan dan pendidikan yang rendah, hal
ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan
14
yang dimiliki anak mereka. Masalah ketersediaan biaya
untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi
sosial dan ekonomi orang tua. masih kurang perhatiannya
orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak
mereka. Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja setelah
tamat dari SD dan SMP, baik itu menjadi buruh atau membantu
orang tua melaut dan lain sebagainya. Hal ini juga tidak
lepas dari pendapatan orang tua dan jenis pekerjaan pada
lingkungan masyarakat tersebut.(Oktama,2013)
kondisi kehidupan nelayan yang tidak memungkinkan anak
nelayan memasuki sekolah formal karena keberadaan anak nelayan
dimaksudkan untuk membantu ayahnya mencari ikan ke laut.secara
empirik anak nelayan pada usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Mengah Pertama (SMP) angka putus sekolahnya cenderung tinggi,
anak putus sekolah akan berpotensi untuk bekerja menjadi buruh
atau pekerja kasar di mana mereka berada.Terdapat dua faktor yang
mempengaruhi anak untuk bersekolah, yaitu faktor internal (dalam
diri) dan faktor eksternal (luar diri) siswa. Aspek internal
meliputi kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap,
ekspektasi (harapan), dan persepsi siswa tentang sekolah. Pada
aspek eksternal meliputi latar belakang ekonomi orang tua,
persepsi orangtua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah,
hubungan guru-murid, usaha yang dilakukan pemerintah (meliputi
pemberian bantuan dan pengadaan sarana dan prasarana). Banyaknya
siswa-siswa yang tidak berhasil dalam belajar, termasuk banyaknya
15
anak-anak putus sekolah bisa dilihat dari kedua aspek tersebut
(Hasanuddin, 2000).
Pendidikan yang dimiliki anak nelayan di wilayah Indonesia
umumnya masih tergolong sangat rendah, hal ini tergambar
dari data pada tahun 2006 dalam HSNI (Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia) hanya ada 1-1,3% anak nelayan yang lulus
jalur sarjana, 3% lulus SMA, 6% lulus SMP dan sisanya 85%
hanya lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan yang
dimiliki anak nelayan ini tentunya dipengaruhi dari
rendahnya pendidikan dan rendahnya persepsi orang tua
mereka terhadap pendidikan, semakin tinggi tingkat
pendidikan orang tua maka akan semakin baik persepsi
mereka tentang pendidikan anaknya, sebaliknya semakin rendah
tingkat pendidikan orang tua maka akan semakin rendah pula
persepsi mereka tentang pendidikan anaknya. Orang tua dalam hal
ini mempunyai tanggung jawab penuh didalam pendidikan anaknya,
akan tetapi tidak sedikit dari orang tua yang dalam hal
ini bermata pancaharian sebagai nelayan kurang
memperhatikan pendidikan anaknya, waktu mereka hanya
dihabiskan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup
mereka, rendahnya perekonomian keluarga juga turut
memberikan pengaruh bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya.
( Oktama,2003)
Alasan petani-nelayan berusahatani-melaut adalah : untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan sumber daya yang ada,
16
meneruskan pekerjaan orang tua. Disamping itu, alasan lain adalah
karena sulitnya mencari pekerjaan, adanya keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan, tidak membutuhkan pendidikan yang
tinggi dan tidak ada pekerjaan lain. Petani-nelayan yang berlatar
pendidikan rendah menyadari bahwa Indonesia adalah negara agraris
dan petani-nelayan adalah tulang punggung perekonomian negara
(Azahari, A. 2002).
Dalam kehidupan nelayan, orang tua beranggapan bahwa anak
laki-lakinyalah yang nanti akan membantu melunaskan utang pada
tengkulak. Di lain pihak, anak-anak muda nelayan juga cukup
memahami kesulitan hidup orang tuanya sehingga keinginan untuk
membantu orang tuanya pun cukup besar. Di samping itu, sebagian
besar anak nelayan pun masih ingin bekerja di bidang kenelayanan
untuk menambah pendapatan keluarga (Mulyadi. 2005).
2.3 Rendahnya Pemanfaatan Sumberdaya Laut oleh Nelayan.
Kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia terkenal dengan
kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber
alam yang dapat pulih (Renewable) maupun yang tidak dapat pulih
(Un-renewable). Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan
dengan sumber daya manusia yang handal serta di dukung dengan
iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan
pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi
pembangunan nasional (Anggoro, 2000).
17
Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya alam dan
sumber daya manusianya yang potensial untuk di tumbuhkembangkan
pendayagunaannya. Sumber daya alam pulau-pulau kecil mempunyai
arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi
lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan lain yang
terkait.(Mardijono 2014)
Seiring dengan banyaknya peluang usaha muncul permasalahan-
permasalahan pembangunan terutama berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam yang over eksploitasi dan tidak bertanggung
jawab. Permasalahan-permasalahan yang muncul secara umum
disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu akibat perubahan alam dan
adanya aktifitas manusia. Akan tetapi permasalahan yang terbesar
pada kenyataannya disebabkan oleh adanya aktifitas yang dilakukan
manusia seperti kerusakan ekosistem yang banyak terjadi di
wilayah-wilayah pesisir.Akibat adanya ekploitasi yang berlebihan
dan aktifitas manusia lainnya, menyebabkan penurunan kuantitas
maupun kualitas sumberdaya alam termasuk berbagai jenis flora dan
fauna. Selain itu ditemukan konflik antar stakeholder yang masih
sering terjadi akibat tumpang tindih kepentingan dalam
pemanfaatan ruang pesisir. Hal ini disebabkan adanya banyak
perbedaan persepsi diantara para pelaku pembangunan (stakeholders)
dalam hal pengelolaan kawasan yang berhubungan dengan pengambilan
kebijakan menyeluruh terhadap penataan ruang dan pengelolaan
kawasan yang berimbang. Konflik masalah penentuan batas antar
wilayah secara spasial maupun pengelolaan kawasan serta
pemanfaatan sumberdaya alam yang makin marak juga merupakan
18
permasalahan tersendiri.Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi
telah menyebabkan terjadinya tekanan ekologis terhadap sumberdaya
poesisir dan laut. Setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas dan
daya dukung ekosistem pasisir dan laut terutama akibat dari
penambangan pasir laut, reklamasi pantai, konversi lahan pesisir
serta penangkapan ikan secara destruktif.
Komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan
homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim
di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat.
Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan
terpencil biasanya mengunakan alat-alat tangkap ikan yang
sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu,
kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan
menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.
Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat
dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan
nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi
penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan
tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena
penggunaan motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga
besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat
eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan
modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh
pada kemampuan jelajah operasional mereka. Pada masyarakat
nelayan Pekerjaan menangkap ikan dikerjakan oleh lelaki
karena merupakan pekerjaan yang penuh resiko, sehingga
19
keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh.
Kalaupun nelayan pekerja memiliki alat produksi sendiri ternyata
alat tangkap ikan yang dimiliki tersebut belum dilengkapi
dengan alat teknologi tangkap ikan, dan modal usaha, sehingga
penghasilannya tidak seperti bila mereka menggunakan alat
teknologi tangkap ikan yang baik. Bagi para nelayan memang
tidak ada pilihan lain, karena pekerjaan yang berhadapan
dengan ancaman gelombang laut, ombak, cuaca, dan
kemungkinan terjadi karam saat akan melaut ke tengah lautan
untuk menangkap ikan adalah pekerjaan turun temurun tanpa
pernah belajar sebagai nelayan yang modern(Badiran.2009)
2.4 Solusi Menanggulangi Kemiskinan Nelayan
Rekomendasi yang harus dilakukan dalam menanggulangi
kemiskinan nelayan yang erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia
adalah:
1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Dalam
hal ini konteksnya adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga,
dan nelayan sebagai seperangkat keluarga. Nelayan yang buta huruf
minimal bisa membaca atau lulus dalam paket A atau B. Anak
nelayan diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan tingkat
menengah. Sehingga kedepan akses perkembangan tekhnologi
kebaharian, peningkatan ekonomi lebih mudah
dilakukan. Pendidikan untuk nelayan pada hakekatnya merupakan
human investmen dan social capital, baik untuk kepentingan
pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pendidikan merata
20
dan bermutu baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah
akan berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan nelayan.
Demikian pula halnya dengan pendidikan memadai, paling tidak
dapat dijadikan modal untuk mencari dan menciptakan peluang-
peluang kerja yang dapat menjadi sumber kehidupan dan peningkatan
kesejahteraan. Dalam banyak hal, terjadinya kemiskinan nelayan
bukan semata-mata karena masalah ekonomi akan tetapi salah satu
penyebabnya ialah pendidikan yang rendah.
Dilihat dari sumberdaya manusia nelayan paling tinggi hanya
80 % tamat sekolah dasar, bahkan banyak yang tidak tamat atau
tidak sekolah sama sekali. Fakta tersebut menyiratkan kemampuan
nelayan mengelola sumberdaya alam pesisir sangat terbatas. Ini
disebabkan karena mereka identik dengan berbagai prilaku sosial
yang tidak menguntungkan selama ini, misalnya budaya konsumtif,
menyebabkan mereka terjebak pada lingkaran utang dan kemiskinan.
Hal itu tentu jauh dari harapan untuk mengelola potensi
sumberdaya kelautan yang tidak terbatas secara berkelanjutan,
maka diperlukan regenerasi nelayan yang memiliki kemandiran,
kompetensi dan kapasitas yang memadai pula.
2. Perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Hal ini terkait
dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus
dirubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat paceklik.
Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat
rentenir. Selain itu perlu membangun diverifikasi mata pekerjaan
khusus dipersiapkan menghadapi masa paceklik, seperti pengolahan
ikan menjadi makanan, pengelolaan wialyah pantai dengan
21
pariwisata dan bentuk penguatan ekonomi lain, sehingga bisa
meningkatkan harga jual ikan, selain hanya mengandalakan ikan
mentah.
3. Peningkatan kualitas perlengkapan nelayan dan fasilitas
pemasaran. Perlunya dukungan kelengkapan tekhnologi perahu maupun
alat tangkap, agar kemampuan nelayan Indonesia bisa sepadan
dengan nelayan bangsa lain. Begitupula fasilitas pengolahan dan
penjualan ikan, sehingga harga jual ikan bisa ditingkatkan.
4. Perlunya sebuah kebijakan sosial dari pemerintah yang
berisikan program yang memihak nelayan, Kebijakan pemerintah
terkait penanggulangan kemiskinan harus sesuai dengan kondisi,
karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan. Kebijakan yang
lahir berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat
nelayan, bukan lagi menjadikan nelayan sebagai objek program,
melainkan sebagai subjek. Selain itu penguatan dalam hal hukum
terkait zona tangkap, penguatan armada patroli laut, dan
pengaturan alat tangkap yang tidak mengeksploitasi kekayaan laut
dan ramah lingkungan.
2.5 Solusi yang diambil Pemerintah Melalui Kementerian.
2.5.1 Kemenerian Pendidikan Nasional
Pemberdayaan anak nelayan ternyata tidak bisa diseragamkan,
tetapi harus disesuaikan dengan kondisi aktual masyarakat
22
setempat. Misalnya saja pendidikan manajemen keuangan yang
diharapkan memungkinkan mereka terbebas dari jeratan tengkulak,
memasuki lapangan
kerja dengan kualitas pengetahuan yang terbatas, dan tekanan
kebutuhan yang terus bervariasi dan meningkat. Kondisi aktual ini
harus diberikan solusi dengan memerhatikan budaya dan kondisi
psikologis mereka. Jika kondisi nyata kehidupan nelayan ini tidak
diperhatikan, dipastikan program pemberdayaan pendidikan akan
gagal karena pemberdayaan pendidikan anak nelayan tidak terlepas
dari pemberdayaan masyarakat pesisir. Program pendidikan anak
nelayan yang disediakan oleh pemerintah terutama dilakukan
melalui jalur sekolah. Hal ini sama dengan anak Indonesia
lainnya, karena itu fungsi pendidikan di sekolah adalah
mengembangkan kemampuan peserta didik seoptimal mungkin(Badiran,
2009).
Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden
No. 15 tahun 1974 memberikan kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggung jawab menyeluruh mengenai bidang pendidikan
dan latihan baik pemerintah maupun swasta, termasuk menyusun
program pendidikan. Dalam prakteknya pemerintah hanya
melaksanakan pengendalian secara terbatas tidak melaksanakannya
secara optimal terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta yang
lebih dari separuh jumlah sekolah lanjutan. Kemudian SKB sebagai
penyelenggara pendidikan non formal tidak banyak yang berbasis di
daerah nelayan, sehingga programnya tidak banyak menyentuh anak
nelayan. Persoalan lain yang tidak kalah penting yang dihadapi
23
adalah, sebagian masyarakat pesisir masih beranggapan bahwa
pendidikan itu tidak penting. Karena untuk keterampilan yang
digunakan oleh nelayan sudah diterima secara turun temurun dan
tidak diperlukan melalui proses pendidikan di sekolah(Badiran,
2009).
Dengan menerapkan prinsip tentang fungsi sekolah khususnya
pada tingkat wajib belajar, maka menurut Soedijarto (1997:237)
sistem pendidikan di Indonesia harus mengakomodasikan peserta
didik yang demikian heterogen baik dipandang dari segi sosial
ekonomi, sosial kultural, maupun kemampuan dasar kognitifnya.
Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar
yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan
peserta didik untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh
karena itu sentuhan pendidikan bagi anak nelayan dan masyarakat
lainnya dalam bentuk pendidikan formal sudah disediakan oleh
pemerintah maupun yayasan swasta dalam bentuk pendidikan formal
seperti Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah
Mengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTsN). Melalui
pendidikan formal ini peserta didik memiliki sikap dan kemampuan
serta pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk
hidup dalam masyarakat. Sedangkan bagi anak yang putus sekolah
atau kesulitan ekonomi disediakan pemerintah pendidikan formal
melalui wadah SMP Terbuka dengan sistem belajar pamong yang
disediakan di rumah warga atau tempat lain yang disepakati.
Sebagai tanda lulus ujian mereka para peserta didik pada SMP
24
terbuka memperoleh ijazah SMP yang sama dengan siswa SMP lainnya.
Disamping program SMP Terbuka pemerintah juga menyediakan layanan
pendidikan melalui lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) anak-
anak putus sekolah atau yang kurang mampu secara ekonomi melalui
jalur pendidikan non formal yang dibina di tempat warga atau
tempat lain yang disepakati, para peserta didik setelah lulus
ujian berhak mendapat ijazah paket A untuk memberikan kesempatan
pada warga memperoleh kesempatan mengikuti sekolah dasar (SD),
atau paket B yang
dikembangkan sebagai alternatif pendidikan jenjang setara SMP.
Sejak krisis ekonomi berdampak pada tingginya biaya
operasional melaut dan diperparah hancurnya laut akibat rusaknya
terumbu karang oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab
membuat ikan yang diperoleh semakin sedikit. Sementara biaya yang
dikeluarkan nelayan sangat besar sehingga mereka menjadi
terkatung-katung dalam kemiskinan. Pada tahun 2001 program
pesisir dikenal dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
(PEMP). Program ini bertujuan untuk nelayan. Pemerintah membuat
program khusus untuk para nelayan guna mendorong perkembangan
sosial ekonomi dan budaya Adanya bantuan yang diberikan oleh
Dinas Perikanan dan Kelautan para nelayan berhasil mendirikan
Bank Perkeriditan Rakyat (BPR), pembenahan Tempat Pelelang Ikan
(TPI), dan pembagunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
khusus untuk nelayan.Selain itu Pemerintah Daerah dan Dinas
Kelautan dan Perikan juga ikut memberikan bantuan berupa
25
peralatan penangkap ikan, seperti jaring udang atau nangkalong
dan pembangunan rumah tempat tinggal nelayan(Sarjulis, 2011).
Pada tahun 2001 program pesisir dikenal dengan Pemerdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) guna mendorong perkembangan
sosial dan budaya kesejahteraan masyarakat nelayan namun program
yang telah dilaksanakan ini tidak mampu seepenuhnya merubah pola
kehidupan nelayan. Disamping itu terlihat dari pendapatan ikan
yang berkurang sehingga hasil tangkapan nelayan sedikit.
Berkurangnya jumlah ikan ini juga merupakan akibat dari para
pengusaha yang memiliki alat tangkapan yang telah mempergunakan
kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi alat tangkapan dan
persaingan bebas dalam dunia usaha telah menggilas para nelayan
skala kecil(Sarjulis, 2011).
2.5.2 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus
memberikan perhatian dan dukungan anggaran baik melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)
untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Diantaranya Provinsi Bengkulu, pada tahun 2014 KKP telah
mengalokasikan kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 23,3 Milyar.
Bengkulu merupakan wilayah pesisir yang berhadapan langsung
dengan Samudera Hindia, dimana gelombang lautnya cukup tinggi dan
rawan akan bencana gempa. Sehingga nelayan nya harus terus kita
perhatikan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan,
26
Sharif C. Sutardjo, pada kunjungan kerja di PPP Pulau Baai,
Provinsi Bengkulu.
Adapun tujuan dan manfaat dari program bantuan untuk wilayah
pesisir di barat sumatera ini diantaranya, untuk meningkatkan
produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan
menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. Kedua,
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta dapat
meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil
dari ikan hasil tangkapan. Program ini secara langsung juga untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (dalam
hal ini adalah masyarakat nelayan) dan untuk menjamin
keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil (nelayan
tradisional).diharapkan, seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi
anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Bengkulu dan
Pulau Baai khususnya, dapat dimanfaatkan dan dioperasionalkan
secara maksimal agar memberikan kontribusi nyata dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan tujuan agar
kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber
pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha(KKP, 2014).
2.5.3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program
padat karya menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.264
orang pada 2012. Pelaksanaan program padat karya ini bertujuan
menyerap pengangguran di daerah pesisir, meningkatkan daya beli
27
dan membantu pertumbuhan ekonomi pesisir di Indonesia, Sasaran
utama dari Program padat karya itu adalah kawasan pesisir yang
tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki tingkat pengangguran
yang cukup tinggi.
Program padat karya terbagi menjadi dua kegiatan yaitu padat
karya produktif dengan target penyerapan 8.184 orang dan padat
karya infrastruktur dengan target sebanyak 3.080 orang.
Menakertrans menyebut dengan adanya program padat karya itu maka
akan tercipta pekerjaan sementara yang dapat menambah penghasilan
masyarakat sekaligus terbangunnya sarana, prasarana dan usaha
produktif masyarakat pesisir.
Pada dasarnya pemerintah hanya membantu memfasilitasi
pelaksanaan padat karya ini. Semua berdasarkan usulan dan
pertimbangan masyarakat setempat dengan memperhatikan potensi
sumber daya alam yang tersedia. Program padat karya itu
berorientasi pada prinsip "Dari, oleh dan untuk Masyarakat,"
dengan mengutamakan semangat gotong royong dan rasa solidaritas
dari masyarakat di pesisir yang berada di wilayah kabupaten/kota
dan provinsi di Indonesia.
Program padat karya infrastruktur akan difokuskan pada
pembuatan dan rehabilitasi fisik seperti gpembangunan dan
pengerasan jalan di desa, pembangunan jembatan dan saluran air di
pesisir. Sedangkan padat karya produktif lebih diutamakan pada
pemberdayaan usaha seperti budidaya ikan, udang dan rumputlaut.
28
Tidak hanya itu, ternak sapi, kambing dan ayam dan kerajinan
tangan anyaman juga akan di galakkan.
Dalam pelaksanaannya, program padat karya itu didampingi oleh
petugas lapangan padat karya (PLPK) yang bertugas merencanakan,
mengkoordinasikan dan mengawasi. Pelaksanaan program padat karya
ini dapat mengurangi angka pengangguran di pesisir dan
memperluasan kesempatan kerja baru sehingga mampu menambah
lapangan kerja bagi tenaga kerja baru(Antaranews, 2012).
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Secara umum nelayan yang dimaksud di sini mengacu pada orang
yang secara aktif melakukan usaha penangkapan ikan atau binatang
air di laut atau di perairan umum, seperti penebar dan penarik
pukat, pengemudi perahu layar dan pawing.
Kondisi nelayan saat ini sangat dilematis, dengan sumber
daya alam laut yang luar biasa, nasib nelayan seakan berjalan
ditempat. Adalah hal yang rasional apabila nelayan hidup dalam
kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar nelayan
masih merupakan masyarakat tertinggal dibanding komunitas
masyarakat lain. Kondisi lain yang turut berkontribusi
memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai
29
kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan
nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang
selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup
konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung
untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk
membeli kebutuhan sekunder.
Rekomendasi yang harus dilakukan dalam menanggulangi
kemiskinan nelayan yang erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia
adalah Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan,
Perlunya merubah pola kehidupan nelayan, Peningkatan kualitas
perlengkapan nelayan dan fasilitas pemasaran dan pemerintah wajib
turut serta menanggulangi kemiskinan nelayan melalui kementerian
pendidikan, kemenerian perikanan dan kelautan sera melalui
kemenerian tenaga kerja dan transmigrasi.
Daftar Pustaka
Antaranews, 2012. Program padat karya serap 11.264 tenaga kerja.
http://www.antaranews.com. Di akses pada 9 maret 2014.
30
Antaranews.2014. dalam http://www.antaranews.com. Diakses pada
tanggal 8 Maret 2014 Pukul 15.17
Bangazul.2014.dalam http://bangazul.com. Diakses pada tanggal 8
Maret 2014 Pukul 14.00
Clark, J.R.1996. Coastal Zone Management Handbook. Lewis
Publisher, Boca Raton, FL.
Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. Pedoman Penetapan
Kawasan Konservasi Laut Daerah. Direktorat Konservasi
dan Taman laut Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Jakarta.
Indrawadi, 2009. Nasib Nelayan dan Potensi Kelautan.
http://www.geocities.com/minangbahari/artikel/nasibnelay
an.html
KKP, 2014. Ekonomi Pesisir Barat Sumatera Jadi Perhatian KKP.
http://www.kkp.go.id. Di akses pada 9 maret 2014.
Kompas.
2014.dalamhttp://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/06/2
5/nasib-pelaut-indonesia-467049.html diakses pada
tanggal 8 Maret 2014 pukul 15.15
Kompas.Com, 2009. Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan
Lindungi Laut
Kusnadi, 2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi
Pesisir.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
31
Mardijono.2014.Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap
Pengelolaan Kawasan Konservasi laut Kota
Batam(tesis) .Universitas dipenogoro. Semarang
Oktama, 2013. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat
Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Kelurahan Sugihwaras
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Universitas
negeri semarang, 2013.
Sarjulis 2011.Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam(1970 – 2009).UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG
Slideshare.2014.dalam http://www.slideshare.net. Diakses pada
tanggal 8 Maret 2014 Pukul 14.12
Soedijarto, H. 1997. Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan
Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki
Abad Ke 21. Jakarta: Depdikbud
32