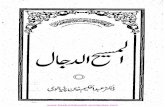FENOMENA AMBIGUITAS PUTUSAN HAKIM SARPIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF BAHASA MANUSIA DALAM FLSAFAT...
Transcript of FENOMENA AMBIGUITAS PUTUSAN HAKIM SARPIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF BAHASA MANUSIA DALAM FLSAFAT...
FENOMENA AMBIGUITAS PUTUSAN HAKIM SARPIN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF BAHASA MANUSIA DALAM FLSAFAT MANUSIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum. Doktrin ini secara literer
dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan
hajat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Itu sebabnya
mengapa kita sering mendengar para pakar hukum yang
membahasakan bahwa ‘di mana ada masyarakat di situ ada
hukum, dan di mana ada hukum di situ ada masyarakat.’
Lantas, hukum menjadi bagian vital dalam dinamika masyarakat
Indonesia, secara khusus proses penegakaan hukum di
Indonesia.
Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia sedang
diterpa berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling
krusial adalah tentang persoalan pemberantasan korupsi. Di
tengah maraknya penangkapan aparat negara penegak hukum yang
terlibat kasus korupsi, berakibat pada munculnya gelombang
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan
institusi penegak hukum. Hal ini kemudian bercampur dengan
kentalnya unsur politik dalam upaya penegakan hukum yang
akhirnya berdampak pada kondisi psikologis masyarakat. Sebut
saja kisruh yang tengah berlangsung antara KPK vs POLRI,
sudah barang tentu sangat menyita perhatian masyarakat.
Carut marutnya informasi terkait posisi hukum dan politik
dua lembaga ini, ditambah dengan pemberitaan media yang1
bertumpu pada sensasionalisme berita, menggiring masyarakat
pada sebuah keadaan yang membingungkan.
Kasus yang paling hangat dan aktual adalah putusan
praperadilan terhadap Komjen. (Pol.) Budi Gunawan. Budi
Gunawan dijerat KPK dengan dugaan gratifikasi sewaktu
menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber
Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di
kepolisian.1 Titik ketegangan semakin mencuat manakala pada
saat yang bersamaan Budi Gunawan ditetapkan Presiden sebagai
calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral (Purn.) Sutarman
yang sudah memasuki masa purnabaktinya. Lantas, publik yang
tidak ingin calon pemimpinnya “tidak bersih” ramai-ramai
menggalang dukungan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan.
Upaya publik pun berhasil dengan respon Presiden Jokowi yang
menunda pelantikan Budi Gunawan dengan dalih penyelesaian
penyelidikan dari KPK. Namun, pihak Budi Gunawan mengajukan
perkaranya ke pra-peradilan, yang tidak dinyana-nyana
memutus-bebaskan Budi Gunawan dari status tersangka. Putusan
kontroversial dari Hakim Sarpin tersebut mengundang pelbagai
respon, yang mayoritas menyatakan putusan Hakim Sapin tidak
sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Salah satu
contohnya adalah putusan atas status tersangka yang dalam
KUHAP Pasal 77 tentang domain hukum pra-peradilan telah
gamblang dinyatakan bahwa domain hukum praperadilan tidak
1 SARAS ADICIPTA, “Kronologi kasus Budi Gunawan dan ketegangan KPK-Polri” disadur dari http://www.bbc.co.id diakses pada 15 Mei 2015 Pk.18.23 WIB.
2
mencakup pembebasan status tersangka.2 Bukan hanya perihal
domain hukum, penafsiran yang kontroversial dan ambigu juga
terjadi pada penetapan Budi Gunawan bukan sebagai aparat
penegak hukum oleh Hakim Sarpin. Pasalnya, saat melakukan
dugaan tindak gratifikasi Budi menjabat sebagai Kepala Biro
atau setingkat sekretaris dan dinyatakan oleh Sarpin bukan
sebagai aparat penegak hukum.
Ambiguitas penafsiran hukum Hakim Sarpin inilah yang
menarik perhatian penulis untuk menelaah lebih jauh putusan
Hakim Sarpin bila dipandang dalam kacamata bahasa manusia
dalam kajian filsafat manusia. Sejatinya, bahasa manusia -
yang adalah sarana berkomunikasi dan menghubungkan
intersujektif/ manusia satu dengan yang lain- sangat vital
dan berperan dalam kehidupan manusia. Namun, di sisi lain,
salah penafsiran, multitafsir bahasa, bahkan ambiguitas
kerap terjadi dalam dinamika penggunaan bahasa tersebut.
Lantas, kajian penulis tidak berfokus pada telaah literer
bahasa hukum, namun lebih kepada bahasa manusia secara umum
(general) secara khusus dalam putusan Hakim Sarpin bila
ditelaah dalam perspektif filsafat manusia.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merumuskan
masalah yang akan terjawab pada bagian pembahasan, yaitu :
2 BAMBANG SUNO, “Saksi Ahli: Hakim Sarpin Keliru Menafsirkan KeteranganSaya”, www.Tempo.co.id diakses pada 17 Februari 2015 Pk.19.47 WIB.
3
1. Bagaimana ambiguitas bahasa dalam Kasus Putusan Hakim
Sarpin bila ditelaah dari sudut pandang Filsafat
Manusia?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Karya Tulis
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk :
1. Menelaah secara lebih mendalam putusan kontroversial
Hakim Sarpin dan mengetahui titik ambiguitas bahasa
manusia dalam hasil putusannya.
2. Setelah mengetahui titik ambiguitas dan kemungkinan
penyebabnya diharapkan dapat menjadi poin pertimbangan
penegakan hukum selanjutnya di Indonesia agar setiap
putusan dapat lebih adil.
D. Metode Penulisan
Metode penulisan merupakan pengetahuan tentang ilmu-
ilmu dan cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi
ilmu-ilmu yang bersangkutan. Metode penulisan merupakan
jalan yang mengarahkan peneliti agar dapat mencapai tujuan
untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu
pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode
penelitian harus memberikan garis-garis dengan cermat dan
mengajukan syarat-syarat yang ketat agar pengetahuan yang
dicapai dari suatu penelitian dapat memiliki nilai-nilai
ilmiah yang objektif. Dalam karya tulis ini penulis
menggunakan metode pustaka (literer). Alasan penulis
menggunakan metode pustaka agar penulisan dan pengkajian
4
masalah dapat komprehensif (mendalam) secara teoritis dan
kedekatan akan sumber valid yang ada.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Ambiguitas
Ambiguitas (nomina) dari ambigu (adjektiva) ; 1. sifat
atau hal yang berarti dua: kemungkinan yang mempunyai dua
pengertian; taksa; 2. ketidaktentuan; ketidakjelasan;
3.kemungkinan adanya makna yang lebih dari satu atas suatu
karya sastra; 4.kemungkinan adanya makna lebih dari satu di
sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat).3 Ambiguitas
berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti
suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu
arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan.4 Ketaksaan
dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu
makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Tidak dapat
dipungkiri keambiguan yang mengakibatkan terjadinya lebih
dari satu makna ini dapat terjadi saat pembicaraan lisan
ataupun dalam keadaan tertulis. Namun, lebih dalam daripada
itu ambiguitas dapat terjadi oleh karena ketidaksepahaman
antara manusia sebagai subjek bahasa yang mencoba memahami
suatu bahasa tertentu dengan bahasa literer itu sendiri.
B. Pengertian Filsafat Manusia
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.III, Gramedia, Jakarta,1990, 27.4 Lorens Bagus, Kamus Filsafat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, 43.
5
Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang
membahas mengenai makna menjadi manusia.5 Filsafat manusia
menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu
filsafat ini manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai
diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus
berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan
misteri Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan
pengalaman manusia, serta dunia yang melingkupinya. Filsafat
manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan
dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu
secara mendalam.
C. Pengertian Bahasa Manusia
Bahasa Manusia berarti suatu sistem rangkaian kata
dalam bentuk unit terceil dari suatu bahasa yang memiliki
suatu makna.6 Adapun kata-kata yang terangkai dalam bahasa
memuatu makna, ide, konsep, atau gagasan dari sesuatu yang
dengan disampaikan dari subjek satu ke subjek yang lain
(intersubjektif). Kaidah atau tata bahasa manusia membuat
manusia terhubung dan dapat saling berkomunikasi –memahami
maksud dari lawan bicara baik melalui bahasa lisan/verbal
maupun bahasa tulis/non-verbal atau bahkan bahasa-bahasa
lain (isyarat,simbol,dll).
BAB III
5 LOUIS LEAHY, Manusia sebuah Misteri, Gramedia, Jakarta, 1984, 1.6 LOUIS LEAHY, Siapakah Manusia? Sintensis Filososfis tentang Manusia, Kanisius,Yogyakarta, 2001, 37.
6
PEMBAHASAN
A. Deskripsi Singkat Kasus Putusan Hakim Sarpin
Nama hakim Sarpin kian melambung pasca merilis
keputusannya yang kontroversial. Pasalnya ia membebaskan
Budi Gunawan, petinggi polri yang terlilit kasus rekening
gendut dari status tersangka. Padahal pada posisi ini,
Sarpin hanya bertugas sebagai hakim praperadilan yang
sejatinya secara yuridiksi tidak memiliki kekuatan dan
wilayah hukum dalam hal menghilangkan status tersangka. Hal
itu didasarkan pada Pasal 77 KUHAP yang memberikan
kewenangan secara terbatas mengenai wewenang praperadilan.7
Bagai boomerang yang berbalik ke arah tuannya, dengan
cepat usulan mutasi dan pengajuan sanksi Sarpin ke MA
(Mahkamah Agung) kian merebak. Seluruh aktivis dan penggiat
hukum berusaha meminta klarifikasi darinya, tidak terkecuali
saksi ahli yang menganggap keputusan arpin ini tidak
mempunyai dasar penafsiran hukum yang kuat. Sarpin sendiri
mengambil keputusan demikian berdasarkan penafsirannya bahwa
Budi Gunawan bukan termasuk penegak hukum (hanya pegawai
administrasi Polri pada saat itu, sehingga tidak bisa
dikenakan hukum pidana.
Senin, 16 Februari 2015, Hakim praperadilan kasus
penetapan tersangka BG, Hakim Sarpin membuat putusan
kontroversial. Adapun isi putusan hakim Sarpin adalah7 SARI SOEDARSSONO, “Kabulkan Budi Gunawan, Hakim Terancam Sanksi MA”,www.Tempo.co.id diakses pada 17 Februari 2015 Pk.19.47 WIB.
7
sebagai berikut:8
1.Menyatakan sprindik penetapan tersangka atas BG tidak sah
dan tidak memiliki
kekuatan hukum.
2.Menyatakan penyidikan KPK atas kasus BG tidak berdasar
hukum dan tidak memiliki
kekuatan hukum.
3.Menyatakan penetapan tersangka atas BG yang dilakukan KPK
tidak sah.
4.Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang
dikeluarkan lebih lanjut
oleh KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka
terhadap BG.
Putusan di atas yang membuat publik dan kalangan akademisi
hukum maupun disiplin ilmu yang lain turut bersuara
menyikapi putusan kontroversial ini. Banyak yang menyasar
terhadap logika penafsiran hukum Hakim Sarpin. Namun juga
tidak sedikit yang menyasar pada rekam jejak Hakim Sarpin
dalam putusan-putusan sebelumnya.
B. Analisis Kasus dalam Perspektif Bahasa Manusia
Manusia hidup dengan berbahasa.9 Bagi manusia, bahasa
mengungkapkan dirinya. Lewat bahasa, manusia
8 BUDIARTO SHAMBAZY, "Moral Hakim Merosot", KOMPAS, 12 April 2015. Budiarto Shambazy adalah penulis sekaligus redaktur senior Koran Kompas yang telah lama berkutat pada persoalan politik dan hukum di Indonesia secara khusus ketegangan antara Polri dan KPK.9 EMANUEL PRASETYONO, Dunia Manusia – Manusia Mendunia, Zifatama, Sidoarjo, 2013,53.
8
mengkomunikasikan dirinya, pemikirannya, keinginannya,
kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Lewat bahasa, manusia memaknai
kehidupannya. Dengan berbahasa, manusia memaknai
kehidupannya, mengkomunikasikan eksistensinya. Karena bahasa
berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk
mengkomuinikasikan dirinya, bahasa mencakup pelbagai
kemampuan berkaitan dengan intelektualitas, kesadaran diri
maupun motivasi subjek (manusia) sebagai sang pengguna dan
penafsir bahasa. Bahasa juga dikatakan sebagai sarana
ekspresi diri manusia, karena melaluinya seseorang dapat
dianggap berjasa dapat juga dianggap bersalah karena
“mengkhianati” arti sebuah bahasa itu sendiri. Dengan kata
lain manusia –dengan kebebasannya- mampu menafsirkan dan/
atau mengartikan sebuah bahasa (kata-kata) dengan motif dan
kehendak pribadinya sendiri.
B.1 Kata dan Makna
Unit dasar dari setiap bahasa adalah kata. Kata (baik
lisan maupun tertulis) adalah tanda atau symbol inderawi
yang merepresentasikan konsep atau ide, dan secara langsung
juga inner feeling, keinginan dan kehendak terdalam yanbg keluar
dari batin si pembicara.10 Kata dalam bahasa tulis dapat
dilihat sebagai kekuatan symbol linguistik yang dapat
dilihat dan dipahami maknanya. Makna terinternalisasi dalam
“kendaraan” kata yang memuat representasi suatu ide/konsep
tertentu. Kata yang berbentuk simbolis tersebut memiliki
makna karena memang simbol itu bukan ada dari dirinya10 Ibid., 55.
9
sendiri atau untuk dirinya sendiri. Sebagai simbol, kata
terbentuk dan “lahir” dari ucapan-ucapan yang bermakna.
Karena itulah, kata bersifat linguistik (sebagaimana arti
kata aslinya, lingua, yang berarti lida; ucapan yang bermakna,
sebagau produksi dari kombinasi antara gesekan dan desis
udara dari mulut kita).
Kata dalam bahasa manusia selalu mengusung makna sebab
pada hakikatnya kata “berdiri” di atas suatu ide atau konsep
tertentu yang mengacu pada objek tertentu yang mau dikatakan
atau direpresentasikan itu. Jadi suatu kata
merepresentasikan suatu idea tau konsep tertentu mengacu
pada objek tertentu yang mau dikatakan. Suatu kata “berdiri”
di atas suatu makna.11 Makna, ide, atau konsep tertentu
itulah yang disebut dengan signification bagi kata. Dengan
signification dimaksudkan makna atau konsep tertentu berada di
balik suatu simbol. Signification membuat kata menjadi
bermakna, karena pada gilirannya kata bisa menjalankan
fungsinya untuk menyampaikan sesuatu (communicable).
B..2 Makna dan Bahasa
Manusia mengkomunikasikan eksistensi dirinya (ide /
pemikiran) melalui eksplorasi ide dalam bahasa (argumentasi,
retorika, dll). Lantas bahasa bisa selalu dipastikan memuat
makna, dan mengandung suatu maksud dan tujuan dari sang
penyampai. Bahasa pertama-tama ingin bertujuan untuk
mengkomuniasikan diri (eksistensi) manusia melalui11 FRANSISKUS BORGIAS. 2013. Manusia Pengembara : Refleksi Filosofis tentang Manusia,Jalasutra, Yogyakarta, 25.
10
penyampaian maksud dan kehendak kepada yang lain. Lantas,
dalam bahasa manusia mengasosiasikan pengalaman-pengalaman
inderawinya, menyusunnya untuk memperoleh makna dan maksud,
dan kemudian menyajikannya kepada lawan bicara dalam bentuk
bahasa lisan maupun tulisan. Dalam bahasa pula, pikiran,
imajinasi, keinginan dan kehendakn manusiawi yang merupakan
makna itu sendiri dikomunikasikan.12 Atau dengan kata lain,
dalam filsafat manusia, bahasa adalah “tempat” makna
memijakan dirinya dan berada di dunia. Kendati bahasa
terbatas sebagai “jembatan” makna antar manusia secara
simbolis, sistematis, dan terstruktur.
Dengan kata lain, bagi manusia bahasa berfungsi secara
fundamental untuk mengkomunikasikan makna yang ingin
disampaikannya kepada orang lain. Bahas menunjukan pula
tingkat kesadaran diri, tanggung jawab (dalam level
tertentu), dan kebebasan manusia. Maka bahasa adalag hal
yang paling manusiawi, mendasar/fundamental, dan
eksistensial dalam kehidupan manusia.
B.3 Ambiguitas Makna dalam Kasus Sarpin
Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa
ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang
berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari
satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan Tidak
dapat dipungkiri keambiguan yang mengakibatkan terjadinya
lebih dari satu makna ini dapat terjadi saat pembicaraan
lisan ataupun dalam keadaan tertulis. Ambiguitas dapat12 LOUIS LEAHY, Op.Cit., 76.
11
terjadi oleh karena ketidaksepahaman antara manusia sebagai
subjek bahasa yang mencoba memahami suatu bahasa tertentu
dengan bahasa literer itu sendiri.
Ambiguitas bahasa manusia dalam filsafat manusia dapat
pula diartikan sebagai ketidakmadainya bahasa sebagai sebuah
simbol dalam mengusung dan mengkomunikasikan realitas dan
hidup manusia. Telah dikatakan penulis sebelumnya bahwa
bahasa manusia adalah sebuah simbol linguistik yang memuat
makna dalam rangkaian kata. Lantas, sebagai sebuah simbol,
bahasa tentu tidak mungkin memuat segala dinamika kehidupan
dan makna yang dimaksud manusia di dalamnya. Artinya bahasa
bersifat sangat terbatas dalam mengkomunikasikan makna.
Kendati simbol-lingustik adalah cara yang paling tepat bagi
proses intelektual manusia untuk menyampaikan atau
mengkomunikasikan realitas, toh walau bersifat tidak sempurna
namun untuk saat ini paling memadai (adequate) bagi tingkat
intelektualitas manusia.
Proses ambiguitas dalam bahasa manusia terjadi ketika
manusia hendak mengkomunikasikan maksudnya sebagai contoh
melalui retorika dan pelbagai bentuk argumentasi. Di mana di
dalamnya, manusia mengeksplorasi, memodifikasi, bahkan
“memanipulasi” pelbagai bentuk ekspresi dari pikiran dan
dunia ide yang berseliweran dalam benaknya. Alhasil kerapkali
manusia mengabaikan tata bahasa maupun bahasa yang tidak
mampu memuat keseluruhan maksud manusia tersebut.
Kesalahpahaman pun terjadi baik karena multitafsir, maupun
karena ketidakutuhan melihat konteks yang ada. Alhasil,
bahasa manusia mengandung pluralitas makna karena manusia12
mencoba untuk menutupi kelemahan dan/ atau kekurangannya.
Sebagai contoh, adanya ambiguitas bahasa karena faktor
tulisan kata yang sama, seperti “apel” yang bisa berarti
buah maupun berbaris sejajar. Adapun juga homofon, yaitu
kesamaan bunyi suatu kata namun berbeda makna, seperti
“bank” dengan “bang”. Namun yang patut diperhatikan adalah
bahwa bahasa kerap menimbulkan ambiguitas karena berupaya
mengekspresikan gagasan / ide yang universal-abstrak-
konseptual dengan realitas objektif-inderawi secara
simbolis-linguistik. Makna yang seringkali abstrak dan
implisit berusaha dibahasakan dengan simbol-linguistik yang
implisit yang tidak mencakup keseluruhan makna yang hendak
disampaikan. Artinya, makna dan pengalaman manusia terlalu
luas dan dalam untuk diungkapkan dalam ekspresi kata-kata
atau bahasa.
Salah satu contoh ambiguitas putusan Hakim Sarpin
adalah perihal sah atau tidaknya penyidikan atau sah atau
tidaknya penetapan tersangka, menurut penulis, berdasarkan
hukum yang berlaku saat ini, bukanlah merupakan objek
praperadilan. Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini tentang:
a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan;
b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang
13
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan
atau penuntutan”13
Dalam bahasa hukum tertulis yang dinyatakan dalam KUHAP
Pasal 77, secara gamblang mengatur domain hukum dari pra-
peradilan, yaitu menyatakan sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, dan seterusnya serta perihal ganti kerugian serta
rehabilitasi bagi tersangka. Namun, Hakim Sarpin dalam
putusannya memasukan domain penetapan status tersangka.
Dalil yang dijadikan poin argumentasi Sarpin adalah wewenang
hakim dalam menafsirkan Pasal 77 KUHAP ini. Sarpin berdalih
bahwa keputusannya membebaskan Budi Gunawan dari status
tersangka berpedoman pada pasal 77 KUHAP yang mengatur “sah
atau tidaknya penangkapan”.14 Sarpin berargumen bahwa kata
“sah atau tidaknya penangkapan” juga berarti memuat wewenang
untuk memutuskan status tersangka dalam suatu proses
perkara. Menurutnya, penangkapan sama dengan penetapan
bersalah seseorang. Seseorang bersalah, oleh karena itu ia
ditangkap. Lantas, bila Hakim Sarpin mempunyai wewenang
untuk menolak keabsahan penangkapan Budi Gunawan, berarti ia
juga mempunyai wewenang untuk memutusbebaskan Budi Gunawan
dari status tersangka.
Tampak dalam proses penafsiran hukum tertulis secara
khusus KUHAP Pasal 77, Hakim Sarpin berusaha untuk
menyamakan setiap kata yang padahal mempunyai distingsi dan
domain yang berbeda. Domain “penangkapan” tentu berada dalam
wilayah sebelum penetapan tersangka, dan tidak bisa13 KUHAP Pra-peradilan, dikutip dari KEMENKUMHAM.go.id diakses pada 12 Mei 2015 Pk.14.52 WIB.14 BUDIARTO SHAMBAZY, Op.Cit., 3.
14
disamakan. Begitu pula dengan distingsi kata “penangkapan”
yang berbeda dengan penetapan status tersangka. Penangkapan
bmemuat kemungkinan seseorang belum tentu bersalah. Namun,
status tersangka memuat probabilitas yang lebih besar bahwa
seseorang bersalah berdasarkan bukti dan saksi yang valid
untuk kemudian diangkat dalam proses peradilan yang lebih
tinggi. Dalam dinamika kasus ini terlihat sekali bagaimana
Hakim Sarpin sebagai subjek penafsir hukum kebingungan dan
dalam proses berpikirnya menyamaratakan setiap term sehingga
ambiguitas bahasa pun terjadi.
Pokok yang tidak boleh dilupakan adalah pembebasan
status tersangka Budi Gunawan karena Budi Gunawan tidak
dinyatakan sebagai aparat hukum oleh Hakim Sarpin. Memang
pada saat kasus gratifikasi terjadi, Budi Gunawan sedang
menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber
Daya Manusia Polri periode 2003-2006, yang mempunyai tugas
yang lebih administratif. Lantas, term “administratif” ini
ditafsirkan oleh Hakim Sarpin sebagai wilayah pekerjaan di
luar penegak hukum.15 Baginya, aparat penegak hukum adalah
mereka yang bekerja menegakkan hukum dari perundang-undangan
yang berlaku dan bukan pegawai administratif, dalam konteks
ini pengurus sekolah Polri. Lantas, dalil inilah yang
mendorong Hakim Sarpin untuk berani menetapkan Budi Gunawan
bukan sebagai aparat hukum. Padahal secara jelas, tertera
dalam kartu identitasnya bahwa ia adalah seorang polisi, dan
sudah terang bahwa polisi adalah aparat penegak hukum. Tentu
penafsiran yang asal-asalan ini memang tidak serta merta15 Ibid.
15
karena ambiguitas hukum. Tapi juga karena faktor subjek yang
kurang holistik (utuh) melihat kasus yang ada dan terkesan
“menutup mata” dari beberapa fakta yang jelas.
Bila kita telisik lebih dalam dan tinjau secara kritis,
sejatinya ada yang janggal dari proses penafsiran hukum
tertulis oleh Hakim Sarpin. Tampak adanya unsur kepentingan
di balik putusannya. Hal ini dilandasi secara kuat karena
ini bukan kali pertama Sarpin membuat putusan kontroversial.
Tahun 2010 ketika ia bertugas di Pengadilan Negeri (PN)
Bangkinang propinsi dan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.
Ia pun “memotong” setengah tuntuntan Jaksa kepada terdakwa
kasus narkoba dengan alasan yang kurang jelas. Kendati
hingga saat ini, penyelidikan mendalam belum membuktikan
dirinya bersalah.
Ada pula kesan memaksakan putusan yang terang sangat jelas
bertentangan dengan UU, domain dan logika hukum (bahasa).
Lantas, dikhawatirkan dengan dikabulkannya putusan pra
peradilan ini berpotensi membuka pintu upaya hukum yang luas
bagi para tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK sehingga
marwah KPK yang sebelumnya ditakuti oleh para koruptor
namanya kini luntur dengan kejadian pra peradilan BG.
Beberapa nama yang mungkin akan mengikuti jejak BG adalah
Hadi Purnomo, Jero Wacik, Surya Dharma Ali dan Sutan
Batoegana. Dalam praktik hukum, maka ke depan akan banyak
sekali langkah-langkah hukum melalui pra peradilan yang akan
mengakibatkan praktik peradilan sesungguhnya tidak
terlaksana.
16
BAB IV
Simpulan dan Saran
Alhasil dapat disimpulkan bahwa bahasa manusia memuat
makna dalam rangkaian kata-kata. Bahasa manusia yang
mengeksplisitkan makna manusia dalam bentuk simbol
linguistik baik secara verbal maupun non-verbal ternyata
sangat terbatas dan tidak memadai. Ketidakmampuan bahasa
dalam menampung ekspresi makna manusia bisa disebabkan
karena makna manusia yang sangat abstrak-konseptual,
sedang bahasa sangat simbolik-dan konkret. Lantas,
ketidakmampuan bahasa dalam menampung makna inilah yang
kerapkali menyebabkan subjek (manusia) salah dalam
mengartikan suatu makna yang terkandung dalam bahasa.
Ketidakselarasan antara makna dalam bahasa dengan
interpretasi manusia inilah yang disebut ambiguitas.
Namun bila ditinjau secara lebih kritis, secara khsus
dalam kasus putusan Hakim sarpin, ambiguitas yang terjadi
bukan hanya sebatas karena bahasa yang tidak mampu
menampung makna abstrak-konseptual dari manusia secara
tertulis. Tapi juga faktor manusia menjadi penentu
interpretasi sebuah bahasa. Faktor manusia yang penulis
maksud adalah faktor motivasi, tujuan manusia dalam
menggali makna dalam suatu bahasa, yang juga merujuk pada
faktor kepentingan karena memiliki wewenang dan kehendak
untuk memutuskan. Dalam kasus putusan Hakim Sarpin, pokok
kedua yaitu menolak penetapan Budi Gunawan sebagai aparat
penegak hukum tentu sangat janggal dan tidak mempunyai
dasar hukum maupun logika yang valid. Lantas, hal ini pula17
yang patut diantisipasi oleh lembaga penegak hukum di
Indonesia. Masalah batasan kewewenangan seorang hakim
dalam memutuskan suatu perkara dan menafsirkan bahasa
hukum secara tegas harus diatur. Selama ini, Komisi
Yudisial (KY) masih terlihat anteng dalam menindak para
hakim atau jaksanya yang terkesan keluar dari logika dan
bahasa hukum dalam memproses suatu perkara. Dengan kasus
dan analisis ini, penulis berharap lembaga peradilan
negara dalam hal ini KY dapat memproses dan menyelidiki
secara tegas dan tanpa pandang bulu para penegak hukum
dalam peradilan yang berusaha menafsirkan hukum di luar
domain perundang-undangannya dan memperketat pengawasan
demi terciptanya lembaga peradilan yang bersih
kepentingan, adil, dan membawa kesetaraan hak dalam segala
dinamika penegakan hukum di Indonesia.
18
DAFTAR PUSTAKA
Bagus, Lorens. Kamus Filsafat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2000.
Borgias Fransiskus. Manusia Pengembara : Refleksi Filosofis tentang
Manusia, Jalasutra, Yogyakarta, 2013.
KEMENDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.Revisi 2, Gramedia.
Jakarta, 2012.
Leahy, Louis, Siapakah Manusia? Sintensis Filososfis tentang Manusia,
Kanisius,
Yogyakarta, 2001.19
Prasetyono, Emanuel, Dunia Manusia – Manusia Mendunia, Zifatama,
Sidoarjo, 2013.
.
SUMBER KORAN:
Shambazy, Budiarto, "Moral Hakim Merosot", KOMPAS, 12 April 2015.
SUMBER INTERNET :
Adicipta, Saras, “Kronologi kasus Budi Gunawan dan
ketegangan KPK-Polri” disadur dari
http://www.bbc.co.id diakses pada 15 Mei 2015
Pk.18.23 WIB.
Bambang Suno, “Saksi Ahli: Hakim Sarpin Keliru Menafsirkan
Keterangan Saya”,
www.Tempo.co.id diakses pada 17 Februari 2015 Pk.19.47
WIB.
Sari Soedarsono, “Kabulkan Budi Gunawan, Hakim Terancam
Sanksi MA”,
www.Tempo.co.id diakses pada 17 Februari 2015 Pk.19.47
WIB.
20