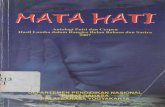Mata Kuliah Kualitatif Desentralisasi Dengan Hati: Studi tentang Pemikiran
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Mata Kuliah Kualitatif Desentralisasi Dengan Hati: Studi tentang Pemikiran
Mata Kuliah Kualitatif
Desentralisasi Dengan Hati: Studi tentang Pemikiran
Josef Riwu Kaho
Ardiansyah Bahrul A. 11/317992/SP/24872
Deasy Kumalasari Dewi 11/317981/SP/24862
Dias Prasongko 11/312395/SP/24543
Hidayatul Mashuroh 11/312490/SP/24558
Muhammad Gufron Rum 08/267564/sp/22971
Permadi Tunggul Surya W. 11/311843/SP/24442
Satria Triputra W. 11/317852/SP/24739
Sholeh Tri Harjoko 09/283809/SP/23679
Sukma Jati Setya W. 11/317943/SP/24825
Yuda Pamungkas 11/312511/SP/24564
Jurusan Politik Pemerintahan
Universitas Gadjah Mada
2013
Abstraksi
Tulisan ini akan mengangkat pemikiran Josef Riwu Kaho terhadap desentralisasi
pasca tahun 1999. Josef Riwu Kaho dikenal sebagai ilmuwan politik di dalam bidang
desentralisasi dan otonomi daerah. Beliau paham betul sejarah bangsa Indonesia secara
detail dan terperinci. Beliau juga menjadi saksi hidup dinamika Indonesia pasca
kemerdekaan tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan biografi
kepada Josef Riwu Kaho untuk melihat bagaimana pemikiran beliau tentang desentralisasi
pasca 1999? Dan juga penelitian ini menyertai dalil pemikiran-pemikiran tersebut hingga
sampai muncul ke permukaan sampai menjadi produk pemikiran beliau.
Keyword: desentralisasi, pemikiran, Josef Riwu Kaho, biografi
Pendahuluan
Berbicara tentang desentralisasi di Indonesia, barangkali pendekatan yang akan
sering digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan ini
menterjemahkan proses desentralisasi yang dilakukan oleh setiap rezim dalam sebuah
negara. Desentralisasi sendiri bisa diartikan sebagai penyerahan kewenangan oleh
pemerintahan pusat kepada pemerintahan di daerah untuk mengurusi rumah tangganya
masing-masing di dalam bidang-bidang tertentu. Menurut Litvack & Seddon (1992),
desentralisasi diartikan sebagai : “The transfer of authority for public from the central
government to subordinate or quasi-independent government organization, or the private
sector.” Sementara Rondinelli (1981) menekankan desentralisasi pada aspek transfer of
political power.
Perjalanan prospek desentralisasi di Indonesia dapat dikatakan penuh liku-liku.
Semenjak masa penjajahan oleh Belanda, hingga pascareformasi, desentralisasi diketahui
dalam konteks Indonesia, digunakan sebagai alat pemersatu keberagaman, dan
membangun semangat nasionalisme. Indonesia memilih menggunakan desentralisasi,
karena pilihan sentralisasi dianggap akan memperburuk proses-proses tersebut, ketika
setiap daerah diperlakukan sama.
Secara historis, latar belakang kelahiran desentralisasi diawali dengan kemerdekaan
bangsa Indonesia. Tarik ulur kepentingan yang terjadi menyebabkan munculnya tiga versi
negara Indonesia. Pertama, Indonesia itu nusantara, yakni wilayah Indonesia sampai ke
Filipina dan Malaysia. Hal ini ditolak sebab akan menimbulkan perkara baru. Kedua, hanya
Jawa saja, versi ini pun ditolak karena setiap wilayah di sekitar Jawa pun ikut bergerak
melawan penjajahan dan memiliki nasib yang sama. Kemudian, ketiga (yang dipilih hingga
sekarang) adalah Indonesia itu adalah wilayah jajahan kolonial Hindia-Belanda.
Negara Indonesia pun muncul, logika dasar yang digunakan adalah for the good of
mankind. Karena setiap konsep seharusnya memiliki tujuan untuk kebaikan manusia.
Berdasarkan hal itu, para pendiri bangsa kemudian menggunakan desentralisasi untuk
mengakomodir daerah-daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan
budaya.
Beranjak kepada konteks rezim Soeharto, kita melihat bahwa pada rezim ini,
pemerintah menggunakan pendekatan sentralistik di dalam menjalankan kepemimpinanya.
Meskipun pada saat itu kita temukan amanat konstitusi untuk mendelegasikan kekuasaan
pemerintahan kepada daerah. Konstirusi tersebut yakni UU No.5 tahun 1974 yang mengatur
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini hadir sebagai pengganti dari UU No.18 tahun
1965. Namun pada kenyataannya, kita hanya melihat beberapa proses desentralisasi semu,
yakni proses administratif kemudian dipolitisasi untuk pemenangan partai penguasa.
Desentralisasi yang terjadi di Indonesia difokuskan pada pendistribusian beberapa
wewenang. Dalam kaitannya dengan kekuasaan, desentralisasi ini biasanya berada pada
level-level administratif pemerintahan. Salah satu hasil dari proses reformasi tahun 1998
yakni sumber-sumber kekuasaan didistribusikan ulang secara merata agar tidak terjadi lagi
keadaan too strong government pada roda pemerintahan.
Di era sebelum reformasi, kita melihat rezim yang ada merupakan rezim yang
memusatkan segala aktivitas pemerintahannya di pusat. Sementara di daerah, hanyalah
kepanjangan dari apa yang menjadi keputusan para teknokrat birokrat yang ada di Jakarta.
Proses ini bukanlah sebuah peristiwa kebetulan, melainkan sebuah sistem yang digunakan
oleh rezim dalam kerangka melakukan kontrol penuh agar terciptanya konsolidasi politik
dan ekonomi sehingga menciptakan negara yang kondusif dari sisi iklim politik.
Namun yang dikorbankan dari rezim otoriter adalah keleluasaan daerah.
Kemandirian daerah untuk berkembang menjadi mandeg. Daerah kiranya telah kehilangan
gairah untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Daerah pada kala itu hanya sebagai
sampiran untuk memenangkan partai Golkar ketika tahun-tahun politik tiba. Hingga muncul
adagium “Siapa yang memilih Golkar, maka daerah tersebut akan mendapat
pembangunan.”.
Tahun 1998 merupakan titik balik proses desentralisasi yang selama rezim
sebelumnya hanyalah bersifat normatif. Seiring munculnya proses demokratisasi, wacana
akan desentralisasi yang implementatif pun mulai digencarkan untuk menghadang
kehadiran rezim traumatik yang pernah ada.
Penelitian biografi juga dipandang menarik ketika digunakan untuk menarik
kerangka historis bagaimana proses tarik ulur desentralisasi yang menjadi bagian dari proses
demokratisasi di Indonesia. Dan juga, melihat bagaimana pemetaan desentralisasi pasca
tahun 1999. Tak luput pula, dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana perjalanan seorang
Josef Riwu Kaho menjadi seorang ilmuwan politik Indonesia yang ahli terhadap
desentralisasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang coba ingin dijawab dalam tulisan kali
ini ialah Bagaimana pemikiran politik Josef Riwu Kaho terhadap desentralisasi Indonesia
pasca 1999?
Memahami Desentralisasi
Desentralisasi merupakan istilah yang dapat dipakai dalam berbagai lintas disiplin
ilmu. Oleh karena itu tidak ada satu definisi pasti tentang istilah desentralisasi itu sendiri.
Dalam berbagai disiplin ilmu seperti Ilmu Administrasi Negara, dan Ilmu Politik, cakupan
pembahasan tentang teori desentralisasi tentu saja akan menghasilkan fokus kajian yang
berbeda. Desentralisasi dalam frame politik akan lebih banyak mengarahkan titik
pembahasan pada bagaimana konsep penyebaran dan distribusi kekuasaan diantara
kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam hal ini, desentralisasi bisa dimaknai ketika kita
dihadapkan pada kenyatakaan adanya dua kutub kekuatan politik yakni antara “pusat” dan
“daerah”. Sedangkan di bidang Ilmu Administrasi Negara, pembahasannya lebih banyak
tersita untuk menjawab pertanyaan berkaitan manajemen atau tata kelola governance
dalam menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dilihat dari sisi etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang terdiri
dari dua kosa kata “de” dan ‘’centrum”. “De” berarti lepas sedangkan “centrum” berarti
pusat, keduanya membentuk kata desentralisasi yang bila diartikan menjadi melepaskan diri
dari pusat. Dari sudut ilmu politik dan ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan
kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membentuk tata kelola
pemerintahan yang berdiri secara otonom. Secara umum, ada dua perspektif utama dalam
melihat desentralisasi. Yang pertama adalah cara pandang administratif dan yang kedua
adalah cara pandang demokratik. Cara pandang demokratik didasarkan pada persepsi
bahwa kekuatan lokal sebagai positive purposive untuk mencapai tujuan bersama,
sedangkan cara pandang administrasi cenderung mengedepankan kepentingan “pusat”
[Ratnawati, 2003).
Tujuan dari kebijakan desentralisasi biasanya berkaitan dengan pengambilan
keputusan yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah agar sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi daerah. Langkah tersebut sebagai respon terhadap sentralisasi kekuasaan yang
cenderung mengabaikan berbagai kepentingan di tingkat lokal. Atau dengan kata lain,
pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan di tingkat pusat.
Disamping itu, ada beberapa alasan yang biasanya menjadi latar belakang
diterapakannya kebijakan desentralisasi (Smith, 1986). Mengapa desentralisasi dianggap
perlu diantaranya adalah; untuk pendidikan politik, latihan kepemimpinan politik, menjaga
stabiltas politik baik di pusat maupun daerah, mencegah konsentrasi kekuasaan berada di
pusat, memperkuat akuntabilitas publik, dan meningkatkan sensifitas elit terhadap
kepentingan publik.
Selanjutnya, pada tataran operasional, kebijakan desentralisasi berimplikasi pada
pola distribusi kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kerangka
undang-undang yang ada. Namun, tidak semua kekuasaan didistribusikan ke daerah, ada
beberapa bidang yang menyangkut kepentingan nasional seperti politik luar negeri,
pertahanan dan keamanan, kekuasaan kehakiman, serta kebijakan moneter yang mutlak
menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, distribusi kekuasaan dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu distribusi kekuasaan berdasarkan wilayah atau distribusi kekuasaan
berdasarkan fungsi-fungsi tertentu pemerintahan. Hal ini menurut Samuel Humes dapat
dikategorikan sebagai berikut :
“the power to govern locally is distributed two ways : areally and functionally. On an
area [also called teriteritorial) basis, the power to manage local public affairs is distributes
among a number of general purpose regional and local governments. On a functional basis,
the power to manage local public services is distributed among number of specialized
ministries and other agencies concerned with the operation of one or more related activities.
Thus the way power is distributed affects which central agencies exert control over which
loal institutions” (Humes, 1991)
Dengan demikian kekuasaan pemerintah lokal mempunyai dua jenis kekuasaanyaitu
kekuasaan desentralisasi atau otonomi dan kekuasaan tugas pembantuan (medelbewind).
Menurut Constantijn Kortman dan Paul Bovend’Ert kekuasaan otonomi adalah kekuasaan :
“to regulate and administer their own affairs.”
Selanjutnya dinyatakan bahwa :
“… in areas where it has autonomous powers, the decentralized authority conducts
its own polices, deciding for it self its aim and means.” (Costantijn & Eert, 2000)
Sedangkan kekuasaan tugas pembantuan merupakan :
“…cooperates in the implementation of policy which has been decided by other
government institutions.” (Costantijn & Eert, 2000)
G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rodinelli [1983) menyatakan bahwa ada empat
bentuk utama dari desentralisasi. Keempat bentuk tersebut adalah dekonsentrasi, delegasi,
devolusi dan privatisasi atau debirokratisasi. Sejalan dengan bentuk-bentuk desentralisasi
tersebut, Brian C. Smith mengemukakan bahwa dalam sistem politik negara kesatuan,
devolusi dan dekonsentrasi merupakan bentuk yang fisibel untuk diterapkan. Bentuk
devolusi sendiri adalah upaya pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab
administrasi di internal kementerian atau jawatan. Dari pengertian tersebut, tidak ada
transfer kewenangan yang nyata karena pihak yang diberikan kewenangan menjalankan
tugas atas nama atasan dan bertanggungjawab kepadanya. Sedangkan pengertian devolusi
sendiri merupakan pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat
lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada
bidang-bidang tertentu saja [Smith, 1986)
Desentralisasi dalam Negara Kesatuan
Terdapat rentang sejarah yang panjang berkaitan dengan pengalaman Indonesia
dalam membentuk diri sebagai sebuah negara bangsa. Setelah sengitnya perjuangan
merebut kemerdekaan dan berproses menuju kesepakatan atas identitas bersama yang
kemudian dilegitimasi menjadi ‘Indonesia’ itu ternyata belum cukup. Masih banyak energi
lain yang harus tercurahkan, revolusi telah berakhir dan saatnya kini membangun Indonesia
menuju kesejahteraan, demikian kata Bung Hatta di masa awal pemerintahan Indonesia
berdaulat. Pergolakan dan pemberontakan di daerah seperti PRRI/Permesta, Andi Aziz, serta
gejolak lain di Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan merupakan sekelumit persoalan
yang menggambarkan betapa keragaman saat itu tidak mampu tertampung dan disatukan
dalam bejana yang bernama NKRI. Elit politik begitu heroik mengobarkan nilai nasionalisme
namun senyatanya mereka dangkal dalam memahami realitas sosial politik di daerah-
daerah. Mereka sibuk melakukan konsolidasi nasional namun abai terhadap kepentingan
aspirasi di daerah, yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara daerah dengan
pemerintah pusat yang baru seumur jagung itu.
Bisa dikatakan, masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sudah ada sejak awal negara ini terbentuk. Demikian pula ketika terjadi suksesi
kepemimpinan di pucuk pemerintahan ketika Soeharto menggantikan Soekarno di tahun
1966. Tidak banyak perubahahan berarti di bidang tata pemerintahan pusat-daerah di masa
pemerintahan Orde Baru. Dibutuhkan waktu yang lama hingga lahirnya UU N0.5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kemudian di susul dengan diundang-
undangkannya UU No.5 Tahun 1979. Keduannya sarat kepentingan dominatif dan represif
oleh pusat kepada daerah (Lay, 2003). Analoginya, di masa itu Jakarta makin seenaknya
mengatakan ‘akulah Indonesia’, padahal Indonesia terdiri dari banyak kepingan puzzle yang
tersebar dari Aceh hingga Papua. Kondisi tersebut berlanjut hingga penghujung millennium
kedua ketika rezim pemerintahan Soeharto digoyang demonstrasi yang menjadi titik balik
bagi gerakan reformis yang menuntut pergantian kepemimpinan di pemerintahan. Di
tengah hingar bingar nyanyian reformasi tersebut, seolah semua orang alergi terhadap
segala bentuk represi dan otoritarianisme yang sudah demikian melekat pada pemerintahan
Soeharto. Pun demikian, pendulum sentralisasi pemerintahan kemudian bergeser ke arah
berlawanan, desentralisasi.
Sadar akan hal itu, Habibie sebagai pewaris mandat dari mentor politiknya tidak bisa
tidak mengakomodasi tuntutan para reformis. Di tengah gejolak dalam negeri yang diwarnai
dengan krisis ekonomi dan memburuknya situasi keamanan, Habibie mengambil langkah
cepat dengan melahirkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sampai pada titik ini format
hubungan pusat-daerah seperti memperoleh angin segar, eksperimen pun dimulai.
Reformasi menghadirkan euphoria optimistis melihat masa depan Indonesia. Sayangnya,
perubahan yang liberal dalam skema hubungan pusat-daerah tersebut justru menghadirkan
masalah baru. Negara justru gagap dalam menjalankan desentralisasi ketika dihadapkan
pada realitas munculnya raja-raja kecil mengatasnamakan otonomi daerah. Kebijakan
desentralisasi pada awalnya menghadirkan ekspektasi, namun realitasnya tidak sama
seperti yang diharapkan. Desentralisasi yang digadang-gadang menjadikan tata kelola
pemerintahan di daerah menjadi lebih demokratis, mempercepat pencapaian kesejahteraan
rakyat, serta perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik senyatanya hanya
fatamorgana. To much to soon, demikian istilah yang mungkin tepat untuk menggambarkan
kebijakan desentralisasi di masa awal reformasi (Hidayat, 2007).
Pada akhirnya UU No.22 Tahun 1999 kemudian direvisi setelah DPR mengesahkan
draft RUU Pemerintahan Daerah yang baru. UU 32 Tahun 2004 menjadi kerangka baru bagi
implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih tertata. Otonomi daerah dan
desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. istilah otonomi lebih
cenderung berada dalam aspek politik-kekuasaan Negara (political aspect), sedangkan
desentralisasi lebih cenderung berada dalam apsek administrasi Negara [administration
aspect). Sebaliknya jika dilihat dari sharing of power kedua istilah tersebut mempunyai
keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi
daerah, tentu akan menyangkut pula pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah,
demikian pula sebaliknya (Surianingrat, 1981)
Secara umum, otonomi daerah berangkat dari hal tersebut maka inti pelaksanaan
otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power)
untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar mengembangkan dan
memajukan daerahnya (Widjaja, 1998). Di sini masyarakat tidak saja dapat menentukan
nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah
berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Konsep desentralisasi dan otonomi daerah
akan terus mengalami pasang surut. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan
terkait karakteristik hubungan antara pusat dan daerah, desentralisasi bisa menjadi titik
penting kajian yang akan terus berkembang di Indonesia. Mengingat kondisi Indonesia yang
sangat beragam, akomodasi terhadapnya tidak bisa dilakukan dengan parsial. Keberagaman
tersebut mencakup sebaran geografis, demografis dan sebaran ekonomi (Dardias, 2012).
Di sisi yang lain, kesepakatan untuk memilih bentuk Negara kesatuan adalah
konsekuensi bersama yang tentu akan berpengaruh bagi masa depan kebijakan hubungan
pusat-daerah. Desentralisasi merupakan konsep yang mengkerangakai relasi antara
pemerintah pusat dengan daerah. Dalam Negara kesatuan, seluruh urusan dan kepentingan
Negara dikelola oleh pemerintah pusat. Mengingat kondisi keterbatasan pemerintah pusat
dalam mengelola segala urusan serta luasnya wilayah Negara, maka beberapa urusan
pemerintahan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi
tersebut tentu berbeda bila dibandingkan dengan konsep negara federal. Tarik ulur
kepentingan politik dan ekonomi antara pusat dan daerah adalah sebuaha keniscayaan yang
tidak bisa dihindari. Implikasinya, mungkin saja otonomi khusus kelak tidak hanya akan
diberlakukan di Aceh, Papua dan D.I.Y saja. Jika sudah demikian, menarik untuk disimak
apakah negara ini akan mampu menemukan bentuk desentralisasi yang tepat. Jadi,
desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di
dalam pola relasi tersebut mengatur hubungan yang berkaitan dengan kewenangan,
kelembagaan, keuangan dan kontrol. Ilmuwan desentralisasi Indonesia senior membagi
desentralisasi menjadi tiga hal: kewenangan, keuangan dan kontrol (Riwu Kaho, 2012).
Mengenal Josef Riwu Kaho
Josep Riwu Kaho, Drs., M.P.A lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur, 22 Maret
1938. Beliau adalah anak ke 3 dari 7 bersaudara yang tinggal dalam sebuah rumah
sederhana bersama kedua orang tuanya. Pada pertengahan akhir tahun 1946 saat peralihan
setelah kemerdekaan, beliau masuk sekolah SD yang didirikan untuk pertama kalinya.
Semenjak kecil beliau dididik untuk disiplin dan hidup sederhana. Setiap hari, setelah
bangun tidur sampai sepulang sekolah, beliau dan saudara-saudaranya mempunyai tugas
masing-masing untuk bekerja dan membantu orang tuanya. Ada sesuatu yang tidak biasa
dari ayahanda yaitu mengambil anak-anak terlantar dipasar atau jalanan untuk dipungut
kerumahnya dan diperlakukan seperti anaknya sendiri, bisa sampai sekitar 50 an orang.
Pada tahun 1951 beliau melanjutkan sekolahnya di Kupang, karena di Atambua
sendiri tidak ada sekolah SMP. Disana beliau berhasil menembus ujian masuk dari seleksi 22
orang dan yang diterima hanya 2 orang yang salah satunya adalah beliau sendiri. Tamat dari
SMP, pada tahun 1955 beliau tetap ingin melanjutkan sekolah SMAnya yang terletak tidak
jauh dari yang sebelumnya di Kupang. Selama 6 tahun beliau hidup mandiri dan bertempat
tinggal di Kupang yang berjarak sekitar 287 km dari Atambua. Jarak itu ditempuh dalam
waktu 2 hari namun jika musim hujan bisa sampai 10 hari dengan menggunakan kendaraan
truk yang hanya dijumpai dalam satu minggu sekali.
Setelah lulus dari bangku SMA, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan tinggi di
Kota Jogja. Mengingat keadaan di NTT sana, dimana keberadaan perguruan tinggi yang tidak
ada, kemudian hal inilah yang memutuskan beliau untuk melanjutkan pendidikan tinggi di
pulau Jawa. Dan setelah melalui proses yang panjang dari Atambua hingga duduk dibangku
kuliah Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FIsipol), Universitas
Gadjah Mada (UGM) , ternyata ada hal yang menarik dibalik semua cerita tersebut.
Awalnya, pada 14 Juli 1958 Pak Josef memutuskan untuk merantau ke Jawa demi
melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih layak. Perjalanan 14 hari ditempuh dengan
menggunakan kapal pengangkut hewan dari Atambua ke Surabaya. Di Surabaya, yang
merupakan tujuan utama beliau mendaftar perguruan tinggi, maka mendaftarlah Pak Josef
sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sembari menunggu
pengumuman, kali ini Pak Josef berangkat menuju Jogja untuk mencoba peruntungannya
mendaftar sebagai mahasiswa di UUGM, tempat dimana kakaknya menempuh pendidikan
terlebih dahulu. Di UGM beliau mendaftar ke empat fakultas sekaligus ; Fakultas Ekonomi,
Pertanian, Hukum, dan terakhir Fisipol yang hanya kebetulan karena diajak menemani
temannya mendaftar.
Selang beberapa waktu menunggu, akhirnya pengumuman pendaftaran pun
diumumkan. Dari kelima tempat Pak Josef mendaftar, Fakultas Fisipol-lah yang pertama kali
mengumumkan bahwa beliau diterima disana. Uang kuliah sejumlah Rp. 240,- yang harus
dibayarkan tanda diterimanya sebagai mahasiswa Fisipol pun dibayarkan. Walaupun
terpaksa dan tak ada pilihan lain, akhirnya beliau bersedia menjadi mahasiswa Fisipol UGM
dengan cara yang tidak sengaja tersebut. Pada akhirnya seluruh tempat dimana beliau
mendaftar menyatakan bahwa Pak Josef diterima sebagai mahasiswa baru. Tapi apadaya,
uang saku sejumlah Rp. 500,- yang diberikan oleh orang tua, dikurangi biaya kuliah Rp. 240,-
yang dibayarkannya di Fisipol UGM, dan sisanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-
harinya, sekaligus menutup pilihan beliau untuk menjadi mahasiswa baru ditempat yang
diinginkan.
Menarik memang bila kita mendengar cerita Pak Josef mengenai pengalamannya
kuliah di Jogja, khususnya di Fisipol UGM, tempat dimana beliau meniti kesuksesannya
hingga kini. Dan ketika kami menanyakan “apakah ada penyesalan dari bapak sebelumnya
karena berkuliah di Fisipol UGM, yang notabene bukan pilihan utama dan pribadi Pak Josef
?”, beliau menjawab, “ya, bagaimanapun harus saya jalani, karena ini takdir Tuhan kepada
saya.” Berkaca pada sikap itulah yang hingga akhirnya mengantarkan beliau ke jalan
kesuksesan, sebab beliau yakin bahwa Fisipol UGM-lah takdir Tuhan yang dikirimkan
kepadanya untuk menjadi jembatan menuju kesuksesan.
1 Agustus 1960 adalah awal permulaan bagi Pak Josef berkuliah di Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fisipol UGM. Selama duduk dibangku kuliah, Pak Josef memegang teguh
semangat untuk mencapai target lulus cepat dengan hasil yang memuaskan. Sebab beliau
berkeyakinan sekali bila ia dapat lulus cepat dengan hasil yang memuaskan, maka untuk
mencari pekerjaan pun akan mudah. Pada saat itu Pak Josef memikirkan sekali bagaimana
caranya agar dirinya tidak lagi membebani orang tua, dan satu-satunya cara ialah mencari
pekerjaan. Sebab bila kita ketahui bersama bahwasannya Pak Josef adalah seorang anak
petani sederhana di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Kehidupan yang sederhana sudah
biasa baginya, bahkan hingga beliau bersekolah di Jogja.
Oleh karena itu, untuk merubah nasibnya beliau sangat bersungguh-sungguh dan
bekerja keras dalam menempuh pendidikan di Fisipol UGM. Lima hingga enam jam perhari
waktunya dihabiskan untuk belajar, displin tinggi dalam mengejarkan tugas kuliah, dan
bersunguh-sungguh dalam memperhatikan dosen mengajar dikelas adalah jurus jitu Pak
Josef dalam berkuliah. Tak mengherankan bila Pak Josef dulu semasa kuliah selalu
memperoleh hasil yang memuaskan dan nilai terbaik. Keberhasilan tersebut tak terlepas
dari peran teman dan senior Pak Josef dulu semasa kuliah. Teman yang sangat
dibanggakanya tersebut adalah Pak Mariun dan The Liang Gie. Mereka berdua adalah orang
yang membentuk mental dan sikap displin Pak Josef hingga berhasil seperti saat ini.
Semasa kuliah Pak Josef selalu berpegang teguh pada motto “bila orang lain bisa,
kenapa saya tidak”. Hal tersebut dipikirkan beliau berkaca pada senior-seniornya yang
terlebih dahulu sukses. Hal inilah yang selalu menjadi api semangat Pak Josef dalam
menjalankan studinya di Fisipol UGM. Hingga akhirnya beliau dapat lulus cepat menjadi
sarjana muda, yaitu tiga tahun enam bulan, dengan nilai yang terbaik. Tak lama berselang
beliau diangkat menjadi asisten dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Orang
yang telah berjasa dalam membuka jalan awal karirnya tersebut adalah Prof. Sudjiono
Wachid. Hingga prestasinya kini beliau mampu menjabat sebagai Dekan Fisipol sebanyak
dua kali, Sekretaris Jurusan dua kali, Ketua Jurusan selama 19 tahun, dan Dosen Jurusan
Ilmu Pemerintahan dari 1966 hingga kini.
Menikah ditahun 1964 saat usia beliau menginjak 26 tahun dan memperoleh empat
orang anak adalah bagian dari target dan perencanaan hidup dari bapak Josef Riwo Kaho.
Beliau selalu berkata kepada kami, “bahwa hidup itu harus direncanakan, sebab yang
menentukan keberhasilan kita adalah rencana kita sendiri, bukan orang lain”. Bahkan hingga
beliau bersekolah S2 di College Public Administration, University of the Philippines tahun
1977 dan lulus Master tahun 1979, adalah merupakan sebagian dari agenda yang
direncanakan oleh Pak Josef. Menjadi PNS dan pensiun ditahun 1989 dengan golongan
tertinggi 4E, juga merupakan perencanaan dan target yang berhasil dicapai oleh Pak Josef.
Keberhasilan dan kesuksesan yang digapai Pak Josef hingga kini merupakan hasil dari
kerja kerasnya dulu, dimana sikap disiplin dan bersungguh-sungguh serta target dan
perencanaan matang selalu dijunjung tinggi oleh Pak Josef. Peran orang-orang disekitar juga
tidak lepas dalam mengantarkan Pak Josef menjadi orang yang sukses dan berhasil. Orang
tua dan kampung halaman Atambua adalah pengobar semangat penuntun kesuksesan Pak
Josef, yang menjadi harapan untuk merubah situasi disana. Setidaknya konsep desentralisasi
yang telah dipikirkan Pak Josef sejak dari dulu adalah salah satu bentuk yang dapat
digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat lewat pemerintahan daerah. Begitulah
harapan Pak Josef untuk kampung halamannya disana, yang mengalami kesenjangan sangat
jauh dengan daerah-daerah lainnya, terutama daerah di pulau Jawa. Konsep desentralisasi
dan pemerintahan daerah adalah konsep yang telah dipikirkan oleh Pak Josef sejak
berkuliah di JIP Fisipol UGM dulu. Sejak duduk jadi mahasiswa maupun dosen beliau sangat
konsen terhadap hal tersebut, terbukti dengan skripsi, tesis, serta buku-buku yang
dibuatnya mayoritas bertemakan politik lokal dan desentralisasi.
Kemunculan Desentralisasi
Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia berkaitan dengan pemilihan bentuk
negara yakni negara kesatuan. Hal ini juga berkaitan dengan pilihan dalam pembagian
kekuasaan yakni pemilihan antara sentralisasi atau otonomi daerah. Sejak Indonesia
merdeka tahun 1945, sudah dipastikan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan dan
menggunakan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal itu
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 19545), Pasal 1 ayat 1 UUD
194545, dan Pasal 18 UUD 194545. Pemilihan otonomi daerah memiliki konsekuensi
diberlakukannya desentralisasi oleh pemerintah pusat.
Josef (1988) dalam bukunya “Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”
sendiri mengatakan cenderung mengikuti pendapat Mariun yang mengatakan bahwa alasan
dianutnya desentralisasi adalah:
1. Demi tercapainya efektivitas pemerintahan;
2. Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (grassroots democracy).
Pelaksanaan desentralisasi dinilai akan membawa efektivitas dalam pemerintahan
karena pihak negara terdiri dari berbagai daerah yang memiliki sifat-sifat khusus. Misalnya
faktor-faktor geografis (letak, iklim, sumber daya), ekonomi, budaya, pendidikan, dan
lainnya. Selain itu, dengan melaksanakan desentralisasi dikatakan akan membawa
pemerintahan yang lebih demokatis. Alasanya karena negara seharusnya memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk ikut serta dalam
pemerintahan. Untuk itu realisasi dari semboyan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat juga dilaksanakan di daerah.
Josef juga memaparkan keuntungan yang diperoleh dengan diberlakukannya sistem
desentralisasi, antara lain:
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan
cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi pemerintah pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan
dapat segera dilaksanakan.
4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang
berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi territorial, dapat
lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan
khusus daerah.
5. Dengan adanya desentralisasi territorial, daerah otonom dapat merupakan
semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan,
yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat
diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik, dapat
dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah
untuk ditiadakan.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi
daerah-daerah karena difatnya yang lebih langsung.
Selain sisi kebaikan dari desentralisasi, beliau juga memaparkan kelemahan dari
desentralisasi antara lain:
1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan
bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah
dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi territorial, dapat mendorong timbulnya apa yang
disebut daerahisme atau provinsialisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan
perundingan yang bertele-tele.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebuh banyak dan
sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformitas dan kesederhanaan.
Pelaksanaan desentralisasi menimbulkan akibat timbulnya daerah-daerah otonom.
Dalam perjalanan dan perkembangannya, daerah otonom menjadi daerah yang berhak dan
berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.
Esensi Desentralisasi Josef Riwu Kaho
Setiap konsep yang dihasilkan oleh buah pikir manusia pasti memiliki inti. Inti
pemikiran inilah yang kemudian dikembangkan menjadi argumentasi-argumentasi yang
saling berkaitan satu sama lain. Demikian juga dengan pemikiran desentralisasi milik Josef
Riwu Kaho. Dihadapkan dengan pluralisme negeri ini, Josef mulai memikirkan suatu bentuk
pemerintahan yang sesuai dengan kondisi Indonesia tersebut. Keanekaragaman Indonesia
lah yang kemudian mendorong beliau menemukan konsep desentralisasi dalam pikirannya.
Pak Josef, demikian kami biasa memanggilnya, mengingat dengan detail luas
bentang daratan dan lautan Indonesia. Beliau juga hafal jumlah pulau milik Indonesia yang
ribuan jumlahnya. Suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta berbagai macam
bahasa yang mereka gunakan juga beliau sebutkan jumlahnya. “Kita ini negara yang luar
biasa,” demikian yang beliau katakan ketika memulai kisah panjang desentralisasi Indonesia.
Beliau dengan senang hati membagi ilmunya kepada mahasiswa Jurusan Politik dan
Pemerintahan yang butuh banyak bimbingan. Seringkali Pak Josef menyampaikan ilmunya
dalam bentuk kisah pengalaman yang dahulu beliau alami.
Pak Josef menyebut Kabupaten Alor sebagai daerah asalnya. Daerah itu, bersama
dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya didiami oleh banyak suku yang masing-masing
berkumpul untuk membentuk perkampungan. Hal yang luar biasa adalah setiap kampung
menggunakan bahasa yang berbeda dari kampung lain. Hal ini dikarenakan sering terjadi
peperangan antarkampung. Perbedaan bahasa ini digunakan sebagai tindakan pengamanan
agar musuh tidak mengetahui strategi yang digunakan oleh lawan.
Jangankan di pulau-pulau kecil yang jauh dari perkotaan, tengok saja pulau Jawa.
Meski dinamai pulau Jawa, tidak hanya bahasa Jawa yang digunakan di pulau ini. Di samping
bahasa Jawa, tentunya bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan bahkan bahasa lokal Suku Badui
pun masih digunakan. Orang Jawa pun tidak seiya sekata dalam menggunakan bahasa Jawa.
Bahasa Jawa yang digunakan di daerah Jogja tidak sama dengan yang digunakan di Solo,
bahkan Banyumas memiliki kekhasan dalam bahasa Jawa yang dipergunakan, yakni ngapak.
Berangkat dari hal ini, perbincangan kami dengan Pak Josef mulai masuk lebih dalam ke
dalam pemikiran beliau.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara berkarakteristik plural.
Tidak hanya bahasa dan adat istiadat, bahan makanan serta kondisi alam daerahnya pun
berbeda-beda. Dengan keanekaragaman yang begitu luar biasa, tentu saja pola
pemerintahan yang sentralistik tidak dapat bekerja dengan baik. Sebagai ilustrasi sederhana,
pada Orde Baru pemerintah pusat mendeklarasikan bahwa makanan pokok orang Indonesia
adalah beras. Deklarasi ini tentu saja bersifat Jawa-sentris dan mengabaikan penduduk
Indonesia timur, sebagai contoh, yang biasa makan sagu. Penduduk Indonesia bagian timur
dipaksa menjadi orang Jawa dengan makan nasi, padahal kondisi alam tidak memungkinkan
untuk ditanami padi. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai pemerintahan yang
sentralistik, terfokus pada penyeragaman.
Sebuah penolakan dari Josef ditujukan kepada sentralisasi. Masyarakat yang
beraneka ragam tidak dapat diseragamkan oleh pemerintahan yang sentralistik begitu saja.
Oleh karena itu, desentralisasi sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang berbentuk negara
kesatuan. Dengan desentralisasi, keragaman Indonesia tidak dimusnahkan, justru
desentralisasi memfasilitasi pengembangan potensi masing-masing daerah Indonesia.
Akomodasi keanekaragaman, inilah pandangan Josef mengenai desentralisasi, ‘Sedangkan
desentralisasi itu lebih akomodatif terhadap keanekaragaman’. Desentralisasi dipandang
sebagai penyelamat keanekaragaman Indonesia.
Paska reformasi hubungan pusat dan daerah mengalami perubahan yang signifikan,
daerah mendapatkan hak otonom atas daerahnya yang sering disebut dengan
desentralisasi. Josef Riwu Kaho menerangkan beberapa hal penting dalam buku analisis
hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu dalam tahap awal reformasi
hubungan pusat dan daerah adalah memberikan dasar filosofi yaitu bahwa Indonesia
memiliki keanekaragaman dalam kesatuan, bukan lagi keseragaman yang menjadi dasar
filosofi orde baru. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22 tahun
1999. Hal ini merupakan kebijakan pertama yang mengubah wajah hubungan pemerintah
pusat dan daerah dalam masa reformasi. Daerah bukan lagi menjadi mesin pemerintah
pusat baik secara politis maupun penyelenggaraan kebijakan. Pada orde baru, daerah
dijadikan alat politik oleh pusat, selain itu hasil sumber daya alam daerah dibawa kepusat.
Daerah hanya menjadi “sapi peras” pusat saja. Akan tetapi dengan adanya reformasi ini
daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur daerahnya sendiri dengan
tujuanmemberikan kesejahteraan yang merata di daerah.
Dengan kemajuan informasi dan adanya evaluasi dalam implementasi UU No. 22
Tahun 1999 ternyata semakin tidak lagi komperhensif dan ada celah masalah. Kurangnya
pengetahuan dalam menjalankan dan mendefinisikan asas desentralisasi yang dimaksud
dam peraturan ini justru membalikan kembali masalah lama serta timbulnya masalah baru.
Kemudian UU No.22 tahun 1999 ini dievaluasi dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU
No. 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menurut Josef pada dasarnya memiliki misi
utama menyediakan pelayanan dasar (Basic Service) dan mengembangkan sektor unggul
(Core Competence) dengan cara-cara yang demokratis. Dalam UU No. 32 tahun 2004 ini
lebih komperhensif dan rinci serta mendetail, hubungan pusat dan daerah serta daerah
berjenjang (Provinsi-Kabupaten/Kota) dapat terbagi dengan jelas fungsi dan tugas pokoknya
masing-masing. Perselisihan antara daerah dan pusat berkurang, karena sudah jelas mana
yang menjadi tugas pusat dan mana tugas daerah.
Tantangan Bagi Desentralisasi di Indonesia
Tak ada gading yang tak retak inilah peribahasa yang tepat bagi peraturan
pemerintah yang diungkapkan Josef Riwu Kaho. Tujuan peraturan tersebut terkadang tidak
selalu sesuai dengan apa yang direncanakan. Pemberian otonomi serta urusan kewenangan
pada pemerintah daerah bisa menjadi boomerang ketika penggunaan otonomi yang
diberikan ini tidak sesuai dengan semestinya. Evaluasi yang dilakukan kemudian menyingkap
tabir persoalan yang lebih serius lagi: meluasnya korupsi dan nepotisme di ranah politik
lokal. Data awal tahun 2013 dari Depertemen Dalam Negeri menunjukan hampir 300
gubnernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sedang
dihadapkan pada persoalan hukum terkait korupsi. Dari data tersebut mengungkapkan
bahwa semakin merebaknya praktek ‘politik keluarga atau dinasti’ di ranah lokal yang makin
menjauhkan desentralisasi dan otonomi daerah dari demokrasi. Menurut Dirjen Otonomi
Daerah, memberitakan semakin meluasnya dinasti di daerah-daerah. Diindikasikan, setidak-
tidaknya terdapat 57 kepala daerah yang membangun dinasti ditingkat lokal1 (Lay, 2013).
Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak
selalu menghasilan kebaikan tapi juga penyimpangan sosial yang dilakukan aktor yang
mengimplementasikannya.
Josef yang memiliki fokus pada desentralisasi dan otonomi daerah ini mengatakan
bahwa ada beberapa masalah terkait desentralisasi yang tidak memenuhi harapan. Bagi
beliau yang menjadi faktor utama dalam permasalahan ini adalah manusia. Manusia
merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau gagalnya desentralisasi .
Perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi selalu terkait dengan manusia, karena
manusialah yang menciptakan, menerapkan dan mengontrol semua itu. Dari banyak
manusia yang menjalankan desentralisasi, sebagian besar tidak memiliki cinta pada negara.
Josef menekankan regulasi dan kebijakan pada dasarnya membantu implementasi menjadi
lebih baik, namun apabila manusianya merupakan orang-orang yang tidak mengerti
mengapa mereka diciptakan didunia ini. Manusia bagi Josef Riwu Kaho merupakan makhluk
Tuhan yang diciptakan untuk membantu sesamanya di dunia, karena ketidakpahaman
manusia itulah kini desentralisasi menjadi tidak seperti yang kita inginkan.
Manusia oleh Josef diibaratkan sebagai inti dari kehidupan manusia, termasuk
masalah desentralisasi. Tidak semua memang tapi sebagian besar dari manusia yang
menempatkan diri pada posisi strategis melakukan kecurangan dan kerusakan. Niat setiap
manusia tidak selalu benar, oleh sebab itu manusia sering melakukan korupsi, nepotisme
dan lain-lain yang merugikan semua manusia. Manusia dianggap begitu penting karena
semua pemikiran adalah hasil dari manusia, termasuk desentralisasi juga merupakan bagian
dari pemikiran manusia. Desentralisasi pada dasarnya digunakan untuk menjalankan tugas
yang tuhan berikan yaitu menolong sesama manusia. Desentralisasi diciptakan untuk
1 Dalam catatan Kompas, 6 Maret 2013, fenomena paling menonjol adalah di Banten dimana jaringan kekerabatan Ratu Atut Chosifah, Gubernur Banten menguasai politik di kawasan ini: Atut adalah kakak kandung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kakak tiri walikota Serang, Tb Hairul Jaman; kakak ipar walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany; dan sekaligus anak tiri wakil bupati Pandeglang, Heryani. Gejala serupa ditemui di Sulsel, Sulut, Sumbar, Lampung, Jateng, Jatim, dan masih banyak daerah lainnya.
manusia, yang melaksanakan manusia, pelaksanaanya tentu harus baik, orientasi
pemikirannya juga harus baik apalagi niat individu itu harus lebih baik. Dari semua itu
manusia-lah yang bertanggung jawab berjalan atau tidak berjalannya hasil pemikirannya itu
(desentralisasi).
Faktor selanjutnya yang mengurangi optimalisasi berjalannya desentralisasi adalah
keseragaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Semenjak reformasi lewat UU No.32
Tahun 2004 pola hubungan pusat dan daerah dianggap dan dijadikan sama atau seragam.
Padahal kita bisa melihat Indonesia itu tidak seragam dari banyak hal, bahasa, adat istiadat
dan lain sebagainya. Singkatnya Indonesia ini menjadi ladang keberagaman.
Kesalahan tersebut dapat dilihat, pada kasus di KabupatenSleman. Sebagai daerah
kabupaten, Sleman diberikan tugas yang sebenarnya tidak mereka miliki potensi dan
sumber dayanya yakni perikanan dan kelautan. Jelas keseragaman seperti ini tidak bisa
ditolelir, selain salah sasaran dalam memberikan tugas pada daerah negara juga akan
mengalami defisit pembiayaan yang begitu tinggi. Banyak daerah tidak berkembang justru
karena dipaksakan untuk seragam. Contohnya adalah NTT yang bukan merupakan wilayah
tepat untuk menanam karet, tetapi diciptakan daerah untuk penanaman karet rakyat.
Kesimpulanya kita tidak bisa menyeragamkan daerah satu dengan daerah lainnya
karena potensi sumber daya alam dan manusia yang memang berbeda. Karena itu kita
terlebih dahulu harus dapat membandingkan infrastruktur serta pendidikan yang berbeda
antara daerah satu dengan daerah yang lain.
Jadi memberikan urusan rumah tangga dan otonomi itu didasarkan pada
kemampuan, keadaan dan kebutuhan yang nyata. Kemampuan daerah pastilah berbeda
karena sumberdaya yang juga berbeda, urusan setiap daerah perlu disesuaikan dengan hal
tersebut. Bagi Josef Riwu Kaho otonomi bukan merupakan hal yang statis, seharusnya
dinamis, daerah dituntut berkembang sehingga urusan diberikan bertahap, jika kemampuan
daerah bertambah urusannya pun ditambah dan jika daerah tidak bisa menjalankan
urusannya bisa diserahkan kembali pada pusat agar pusat bisa membantu, bukan dengan
carapukul rata semua daerah.
Kesimpulan
Dari semua penjelasan di atas ada beberapa yang kemudian harus digaris bawahi
terkait pemikiran seorang Josef Riwu Kaho mengenai desentralisasi. Pertama, desentralisasi
menurut beliau dianggap sebagai cara atau media untuk mengakomodasi keberagaman
yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sistem desentralisasi dipilih karena menuruh Josef
memang merupakan sistem yang paling kuat dan bagus daripada dengan sistem
federalisme. Beliau mengandaikan bahwa sistem hanya sebagai ‘wadah’, sedangkan yang
lebih penting adalah isinya. Jika isinya sudah pas dan benar maka, permasalahan wadah
kemudian menjadi tidak berarti lagi secara signifikan. Kedua, ada dua faktor yang menurut
beliau menjadi penentu keberhasilan dari penerapan sistem desentralisasi di dalam
masyarakat, yakni faktor manusia dan faktor sumber daya. Faktor manusia merupakan
faktor yang paling dominan dan berpengaruh terhadap keberhasilan tidak hanya sistem
desentralisasi tetapi juga sistem-sistem yang lain. Beliau percaya bahwa, manusia yang baik
tentu juga akan membawa pengaruh yang baik juga terhadap sistem yang ada. Kemudian
terkait sumber daya. Josef menekankan bahwa jika ingin mengunakan sistem ini harus
melakukan takaran yang pas terkait pemberian kewenangan kepada daerah dari pemerintah
pusat. Hal itu dilakukan karena perbedaan potensi dan kemampuan daerah dalam
mengelola keleluasaan untuk menguasai dan mengatur daerahnya sendiri.
Dari hasil pemikiran beliau dapat ditarik dua kemungkinan mengapa dirinya tertarik
dan setuju dengan menggunakan konsep desentralisasi. Pertama, terkait masalalu beliau
yang tinggal di luar Pulau Jawa. Keadaan pada waktu itu ada terjadi perbedaa yang kentara
antara Jawa dengan tempat tinggalnya, dalam hal ini perbedaam infrastruktur. Memori
masa kecil yang kemudian turut membentuk pemikiran beliau mengenai desentralisasi. atau
juga bisa dikatakan sebagai rasa traumatik akibat dari pola-pola pemberlakukan yang tidak
seimbang antara daerah satu dengan daerah yang lain akibat proses pemerintahan yang
sentralistik. Kemudian faktor kedua yang mendukung yakni terkait konteks era pada saat itu.
Keadaan pada waktu itu ialah telah muncul rasa-rasa ketidaksukaan pada Orde Baru yang
menerapkan sentralisasi bagi pemerintahan di Indonesia yang menyebabkan tidak
meratanya pembangunan.
Pada perjalanannya, desentralisasi mengalami dinamika yang begitu kompleks.
Kemunculannya dihadapkan pada harapan dan tantangan yang hadir seiring dengan lahirnya
desentralisasi. Michael S. Malley mengatakan bahwa desentralisasi yang demokratis di
Indonesia telah menghasilkan perubahan baru dalam pengaturan pemerintahan lokal, tapi
masih tetap berhadapan dengan struktur lama yang menghambat demokrasi dan
desentralisasi. Adanya bukti perubahan dengan hadirnya desentralisasi didukung dengan
hadirnya era transisi yang terjadi di Indonesia. Adanya transisi ini menimbulkan
ketidakpastian dengan dihadapkannya berbagai harapan, idealisme, perubahan,
pembahasan dan kemajuan yang harus berbenturan dengan kegelisahan, pragmatisme,
ketidakpastian, kesulitan, hambatan dan konservatisme (Eko, 2005 : 416).
Secara teoretis, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan bisa mempromosikan
demokrasi lokal, membawa negara lebih dekat kepada masyarakat, menghargai identitas
lokal yang beragam, memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan dengan kebutuhan
lokal, membangkitkan potensi dan prakarsa lokal dan memperkuat partisipasi masyarakat
lokal (Eko, 2005 : 416). Namun mimpi-mimpi ideal ini sangat jauh dari harapan. Bahkan
dapat dikatakan bahwa desentralisasi ini disalahartikan. Desentralisasi yang dimaknai
dengan penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri sesuai
dengan potensi daerah yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan rakyat nyatanya
hanya dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan untuk menggugat negara. Hal ini sangat
nyata dalam pandangan Josef Riwu Kaho dengan adanya Dewan Penguatan Daerah (DPD)
untuk dijadikan sama kewenangannya dengan DPR, menurut Josef Riwu Kaho, akan
berpotensi seperti menjadi negara bagian. Padahal ide desentralisasi itu sendiri lahir karena
negara ini menganut negara kesatuan.
Hadirnya desentralisasi tidak hanya menimbulkan dampak konseptual yang luas
dalam tataran negara, namun juga berdampak pada praktek-praktek tidak mendidik elit-elit
lokal daerah. Desentralisasi hanya dimaknai sebagai jalan untuk melanggengkan
kepentingan pribadi, utamanya pribadi-pribadi yang memiliki modal. Beliau mengatakan
bahwa dominasi elit lokal ada dalam arena pengembangan industri kecil di era
desentralisasi. Jalan yang paling sering ditempuh adalah dengan pemekaran daerah.
Pemekaran yang pada awalnya dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan publik
kepada masyarakat digunakan sebagai dalih untuk melindungi kepentingan pribadi yang
kemudian dengan permainan politiknya berhasil menempati pucuk pimpinan untuk
membuat regulasi yang melindungi kepentingannya. Tidak hanya kepentingan modal
pribadi, namun juga melindungi modal-modal kroni dan golongannya.
Pemekaran daerah merupakan salah satu manifestasi cara yang ditempuh untuk
mencapai desentralisasi. Massifnya pemekaran daerah yang terjadi di negara ini membawa
kembali pertanyaan fondasional lahirnya pemekaran daerah. Apakah benar pemekaran ini
bertujuan untuk kesejahteraan rakyat ataukah hanya permainan elit lokal untuk melindungi
kepentingannya? Josef Riwu Kaho pun heran dengan adanya fenomena ini. Dengan adanya
fakta bahwa 90% daerah pemekaran gagal dan hanya sekitar 10% yang berhasil
memunculkan keraguan dengan munculnya fenomena ini. Josef memberikan prasyarat dan
mekanisme tertentu suatu daerah dapat dilakukan pemekaran. Suatu daerah dapat
dikatakan dimekarkan apabila dalam waktu sepuluh tahun sejak daerah itu berdiri sudah
dapat mandiri dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun apabila
dalam kurun waktu tersebut daerah yang dimekarkan tidak dapat berdiri secara mandiri
maka sudah selayaknya daerah itu kembali kepada daerah induknya.
Selain kepada aspek kemampuan daerah, yang perlu dipertimbangkan adalah adanya
spesifikasi dan standar kualifikasi pejabat yang akan mengisi jabatan di daerah tersebut.
Karena sudah barang tentu sebuah daerah yang baru memerlukan pejabat-pejabat yang
memiliki tingkat dedikasi tinggi disertai kapabilitas yang memadai untuk membangun
pondasi awal mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tataran pemerintahan
dan pelayanan publik yang baik. Terlebih seringkali di daerah baru mudah dijumpai adanya
not the right man in the right place. Akibatnya pembangunan di daerah tersebut tidak
berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya. Konsepsi inilah yang nantinya akan
memulai babak baru pemekaran daerah supaya sesuai dengan tujuan awal dari hadirnya
pemekaran daerah tersebut.
Fenomena lain yang terjadi dalam era desentralisasi ini adalah adanya heavy
legislatif. Josef Riwu Kaho mengatakan bahwa legislatif dalam hal ini adalah DPRD yang
memiliki kekuasaan bermacam-macam cenderung menggunakannya untuk menjatuhkan
eksekutif. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sudah tumbang pada
tataran proses perumusan kebijakan, ketika DPRD tidak menghendaki suatu kebijakan maka
secara otomatis kebijakan ini tidak akan pernah berjalan di daerahnya. Hal inilah yang
menurut Josef Riwu Kaho menjadi celah korupsi, karena akan ada banyak anggaran yang
tidak terserap dan terjadi proses-proses lobi yang kecenderungan korupsinya sangat tinggi.
Maka dengan hal ini, adanya fakta-fakta di atas yang terjadi kiranya perlu untuk
memahami kembali hadirnya desentralisasi di negara ini. Desentralisasi hadir untuk
memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi daerah
yang dimilikinya. Perencanaan pembangunan betul-betul harus mencakup semua aspek di
daerah dan semua kepentingan rakyat berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya.
Kesempatan bagi tiap daerah untuk berkembang akan memunculkan adanya pemerataan
pembangunan di setiap daerah yang ada, dengan hal inilah ketimpangan pembangunan
antar daerah akan minim ditemui. Pembangunan di daerah tidak hanya mencakup kepada
kesiapan sumber daya potensial yang ada di daerah namun juga perlu didukung oleh
hadirnya pemimpin daerah yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi membangun
daerahnya. Pemimpin daerah ini juga harus cerdas dalam bernegosiasi dengan DPRD demi
merealisasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk daerahnya. Sehingga dengan
kombinasi-kombinasi yang mendukung dari semua lini pembangunan di daerah akan
mampu mewujudkan desentralisasi daerah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama
filosofis desentralisasi.
Daftar Pustaka
Dardias, Bayu. 2012. Desain Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Makalah pada
seminar LAN Jatinangor 26 November 2012
Fisipol UGM.
Gunawan, Jamil dkk. (Ed). 2005. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal.
Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia.
Kaho, J.R. 2012. Analisa Hubungan Pusat an Daerah di Indonesia. Yogyakara : PolGov
JPP Fisipol UGM.
Kaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,
Jakarta: Rajawali Pers.
Lay, Cornelis, 2013. Desentralisasi Asimetris: Sebuah Model Bagi Indonesia?, dari
bahan Mata Kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah, tanggal 5 Juni 2013, Jurusan Politik
dan Pemerintahan. Fisipol Universitas Gadjah Mada.
Lay, Cornelis. 2009. Pengembangan Assymetrical Decentralization Sebagai Model
Pengelolaan Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia. Yogyakarta : Jurusan Politik dan
Pemerintahan
Pratikno, dkk. 2010. Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi.
Yogyakarta : Penelitian Jurusan Politik Pemerintahan, Fisipol UGM.
Sumber Online
Kompas, 6 Maret 2013