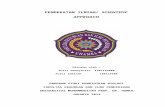LAPORAN PRAKTIKUM UJI KUALITATIF PROTEIN METODE PENGENDAPAN ALKOHOL
Lima Pendekatan Kualitatif Penyelidikan
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Lima Pendekatan Kualitatif Penyelidikan
PENYELIDIKAN KUALITATIF DAN DISAIN PENELITIAN
Memilih di Antara Lima Pendekatan.
Oleh:
©John W. Creswell
Universitas Nebraska, Lincoln.
Alih bahasa oleh:
W. Saputro
Palembang
2015
Untuk kalangan terbatas
1
Kata kunci:
Narasi, Fenomenologi, Etnografi, Grounded Theory, dan Studi Kasus
Creswell, John W.
Judul asli :
Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches/
John W. Creswell.--2nd ed.
Copyright © 2007 by Sage Publication, Inc.
Printed in the United States of America
Saputro, W
Judul terjemah:
Penyelidikan Kualitatif dan Disain Penelitian: Memilih di Antara Lima Pendekatan
Alih bahasa oleh :
W. Saputro
Palembang, 26 Mei 2015 M/ 7 Sya'ban 1436 H
2
Bab 4
Lima Pendekatan Kualitatif Penyelidikan
alam bab ini, kita mulai eksplorasi rinci kita tentang penelitian narasi, fenomenologi,
grounded theory (teori dasar), etnografi dan studi kasus. Untuk masing-masing
pendekatan, penulis menempatkan definisi, menelusuri secara gamblang tentang
sejarahnya, memeriksa jenis- jenis studi, memperkenalkan prosedur yang dilibatkan
dalam pelaksanaan studi, dan menunjukkan tantangan-tantangan potensial dalam penggunaan
pendekatan. Penulis juga meninjau sejumlah kesamaan dan perbedaan di antara kelima pendekatan,
dengan demikian para peneliti kualitatif dapat memutuskan pendekatan manakah yang terbaik untuk
digunakan dalam studi khusus mereka.
Pertanyaan untuk Diskusi
• Apakah yang dimaksud studi narasi, fenomenologi, grounded theory (teori dasar), etnografi dan
studi kasus?
• Prosedur dan tantangan apa yang digunakan untuk menggunakan masing-masing pendekatan
penelitian kualitatif?
• Apa kesamaan dan perbedaan di antara kelima pendekatan?
Penelitian Narasi
Definisi dan Latar Belakang
Penelitian narasi memiliki banyak bentuk, menggunakan ragam praktik-praktik analitis dan
mengakar dalam masyarakat yang berbeda dan disiplin ilmu kemanusiaan (Datute dan Lightfoot,
2004). Narasi mungkin sebuah istilah yang diperuntukkan untuk semua teks atau wacana, atau ia
mungkin berupa teks dalam konteks sebuah mode penyelidikan dalam penelitian kualitatif (Chase,
2005), dengan fokus khusus pada sejarah yang diceritakan oleh individu (Polkinghorne, 1995).
Seperti saran Pinnegar dan Daynes (2006), narasi dapat berbentuk dua hal, yaitu metode dan
3
D
fenomena studi. Seperti halnya metode, ia mulai dengan pengalaman-pengalaman yang
terekspresikan dalam hidup dan pengisahan sejarah individu. Para penulis telah menyediakan pola-
pola untuk menganalisa dan memahami kehidupan dan pengisahan. Penulis akan
mendefinisikannya di sini sebagai jenis disain kualitatif yang mana narasi difahami sebagai
pembicaraan atau teks tulisan yang memberikan sekumpulan peristiwa/tindakan atau rangkaian
peristiwa/ tindakan, yang secara kronologis memiliki keterhubungan (Czarniawska,2004, hlm.17).
Prosedur untuk penerapan penelitian ini terdiri dari pemokusan pada studi terhadap satu atau dua
individu, pengumpulan data melalui pengumpulan kisah-kisah mereka, pelaporan pengalaman-
pengalaman individual dan penataan secara kronologis (atau menggunakan tahapan wacana
kehidupan) makna-makna pengalaman tersebut.
Meskipun penelitian narasi aslinya berasal dari kajian literatur, sejarah, antropologi,
sosiologi, sosiolinguistik, dan pendidikan, sejumlah disiplin studi tertentu telah menggunakan
pendekatan tersebut (kelompok penelitian narasi) tersebut (Chase,2005). Penulis menemukan gejala
ini dalam sebuah karya para posmodern yang berorientasi keorganisasian di dalam karya
Czarniawska (2004); juga dalam tulisan perspektif pengembangan kemanusiaan dalam karya Daiute
dan Lightfoot (2004); Pendekatan psikologi di Lieblich karya Tuval-Mashiach dan Zilber (1998);
pendekatan sosiologis dalam Cortazzi (1993), Riessman (1993); dan kuantitatif (misalnya, sejarah
statistik dalam pemodelan sejarah peristiwa) dan pendekatan kualitatif dalam karya Elliot (2005).
Sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan pada penelitian narasi juga telah didukung oleh
seri tahunan studi narasi kehidupan yang mulai pada tahun 1993 (lihat misalnya, Josselson dan
Lieblich, 1993), dan jurnal penyelidikan narasi dengan banyaknya jumlah buku yang ditulis akhir-
akhir ini dalam penelitian narasi, hal ini tentunya merupakan sebuah field in making (Chase,2005,
hlm.651). Dalam diskusi tentang prosedur narasi dimana penulis mendasarkan pada sebuah buku
yang mudah diperoleh yang ditulis untuk para pelaku ilmu sosial yang disebut penyelidikan narasi
(Clandinin dan Conelly, 2000) yang bertema Apa yang dilakukan oleh peneliti narasi? (hlm. 48).
4
Jenis Studi-Studi Narasi
Sebuah pendekatan terhadap penelitian narasi adalah untuk membedakan jenis-jenis penelitian
narasi oleh strategi analisis yang digunakan oleh para pengarang. Polkinghorne (1995)
menggunakan pendekatan ini dan membedakan antara analisis tentang narasi (hlm. 12),
menggunakan paradigma berfikir untuk membuat deskripsi tema apa yang dipakai ke arah cerita
atau pembagian jenis ceritanya, dan analisis narasi dimana para peneliti mengumpulkan sejumlah
deskripsi peristiwa atau kejadian dan mengkonfigurasinya ke dalam sebuah cerita menggunakan
sebuah alur panduan. Polkinghorne (1995) terus menekankan pada bentuk kedua dalam tulisannya.
Akhir-akhir ini, Chase (2005) menyajikan sebuah pendekatan yang secara khusus beraliansi dengan
analisis tentang narasinya Polkinghorne. Chase menyarankan bahwa para peneliti dapat
menggunakan alasan paradigmatik untuk sebuah studi narasi, seperti bagaimana seorang individu
mampu dan dipaksa oleh sumber-sumber sosial, yang secara sosial disituasikan dalam penampilan
yang saling interaksi dan bagaimana para pelaku narasi mengembangkan penafsiran.
Pendekatan kedua adalah untuk menekankan ragam bentuk dalam praktik penelitian narasi
(lihat misalnya, Casey, 1996/1996). Sebuah studi biografi adalah merupakan sebuah bentuk studi
narasi dimana para peneliti menulis dan mencatat pengalaman-pengalaman hidup orang lain.
Autobiografi adalah tulisan dan catatan oleh individu-individu yang merupakan subjek studi (Ellis,
2004). Sebuah sejarah hidup membawa sebuah keseluruhan hidup individu, ketika cerita
pengalaman individu seseorang adalah berupa studi narasi dari sebuah pengalaman pribadi
seseorang dijumpai dalam episode tunggal atau ganda, stuasi khusus atau cerita rakyat milik
komunitas tertentu (Denzin, 1989a). Sebuah cerita lisan terdiri dari pengumpulan refleksi individu
atau peristiwa dan sebab musababnya dari seorang individu atau sejumlah individu (Plummer,
1983). Studi narasi dapat memiliki sebuah fokus kontekstual khusus seperti guru dan siswa dalam
sebuah ruangan kelas (Ollerenshaw dan Creswell, 2002) atau sejarah yang menceritakan tentang
sebuah organisasi (Czarniawska, 2004). Narasi mungkin saja dipandu oleh sebuah lensa (sudut
5
pandang) atau perspektif. Lensa tersebut mungkin digunakan untuk membela warga Amerika Latin
melalui penggunaan testimoni (kesaksian) (Beverly, 2005), atau mungkin berupa sebuah lensa
feminis yang digunakan untuk melaporkan sejarah wanita (lihat misalnya, Kelompok Narasi
Pribadi, 1989) adalah sebuah lensa yang menunjukkan suara wanita yang diubah, beragam dan
bertentangan (Chase, 2005).
Prosedur Pelaksanaan Penelitian Narasi
Dengan menggunakan pendekatan yang diambil oleh Clandinin dan Conelly (2000) sebagai
panduan prosedural umum, metode pelaksanaan sebuah studi narasi tidak mengikuti sebuah
pendekatan kaku, akan tetapi tentunya menyajikan sebuah kumpulan tidak resmi mengenai topik.
- Menentukan jika pertanyaan atau permasalahan penelitian terbaik untuk penelitian narasi.
Penelitian narasi sangat baik untuk menangkap rincian sejarah atau pengalaman hidup dari
kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah kecil para individu.
- Memilih satu atau lebih para individu yang memiliki kisah atau pengalaman hidup melalui ragam
jenis informasi. Clandinin dan Conelly (2000) merujuk kisah-kisah tersebut sebagai “teks-teks
lapangan”. Partisipan penelitian dapat mencatat kisah mereka dalam buku diari atau jurnal, atau
para peneliti dapat mengamati individu dan mencatat kutipan-kutipan lapangan. Para peneliti juga
dapat mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan oleh para individu, mengumpulkan kisah tentang
individu yang berasal dari anggota keluarga, mengumpulkan dokumen-dokumen seperti memo atau
surat-menyurat kantor tentang individu atau mengumpulkan foto-foto, kotak memori (koleksi dari
artikel yang memicu memori) dan artefak sosial-keluarga-individu lainnya. Setelah memeriksa
sumber-sumber ini, para peneliti mencatat pengalaman-pengalaman hidup individu.
- Mengumpulkan informasi tentang konteks dari kisah-kisah ini. Para peneliti narasi meletakkan
kisah individu dalam konteks pengalaman pribadi partisipan (pekerjaan dan rumah mereka), budaya
mereka (ras atau suku) dan konteks sejarah mereka (waktu dan tempat).
6
- Menganalisa kisah para partisipan dan kemudian menceritakannya kembali ke dalam sebuah
kerangka kerja yang dapat membuat pemahaman. Penceritaan kembali adalah proses pemahaman
kisah ke dalam sejumlah jenis umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini dapat terdiri dari
pengumpulan kisah, menganalisanya bagi elemen-elemen kunci dari kisah (misalnya, waktu,
tempat, alur dan sekenario) dan kemudian menuliskan kembali kisah untuk menempatkannya dalam
sebuah urutan kronologis (Ollerenshaw dan Creswell, 2000). Seringkali ketika para individu
menceritakan kembali kisah mereka, mereka tidak menyajikannya dalam sebuah urutan kronologis.
Selama proses penceritaan, para peneliti menyiapkan sebuah hubungan penyebab di antara gagasan-
gagasan. Cortazzi (1993) menyarankan bahwa kronologi penelitian narasi, dengan menekankan
pada urutan, mengatur bagian-bagian narasi dari aliran penelitian lain. Sebuah aspek dari kronologi
adalah bahwa kisah memiliki sebuah awal-tengah dan akhir. Sama halnya dengan elemen utama
yang ditemukan dalam karya novel yang baik, aspek-aspek ini meliputi keadaan berbahaya, konflik
atau perjuangan, pelaku utama atau karakter utama dan sebuah urutan dengan akibat yang
dikandungnya (misalnya sebuah plot) dimana keadaan berbahaya tersebut dapat diselesaikan dalam
sejumlah cara (Carter, 1993). Sebuah kronologi lebih jauh dapat terdiri dari gagasan masa lalu,
sekarang dan yang akan datang (Clandinin dan Conelly, 2000) berdasarkan pada asumsi bahwa
waktu memiliki sebuah arah yang tidak lurus (Polkinghorne, 1995). Dalam sebuah pengertian yang
lebih umum, sebuah kisah dapat memuat jenis elemen lain yang ditemukan dalam sebuah novel,
seperti waktu, tempat, dan cerita (Conelly dan Clandinin, 1990). Alur, garis cerita dapat pula
memuat tiga dimensi ruang penyelidikan narasi, yaitu individu dan sosial (interaksi), masa lalu,
sekarang dan akan datang (kesinambungan) dan tempat (situasi). Garis cerita ini mungkin memuat
informasi tentang seting atau konteks dari pengalaman partisipan. Di depan kronologi, para peneliti
dapat merinci tema yang mencuat dari kisah untuk menyediakan sebuah diskusi yang lebih rinci
tentang makna arti dari kisah tersebut (Huber dan Whelan, 1999). Kemudian analisis data kualitatif
mungkin berupa sebuah deskripsi kedua kisah dan tema yang timbul darinya. Seorang penulis
7
beraliran posmodernis seperti Czarniawska (2004) akan menambahkan elemen lain untuk analisis,
sebuah penghancuran kisah, sebuah penghilangan dari kisah-kisah tersebut seperti strategi analisis,
menyingkap dikotomi, memeriksa kebungkaman dan menghadirkan gangguan dan kesakitan.
- Bekerjasama dengan partisipan secara aktif, melibatkan mereka dalam penelitian (Clandinin dan
Conelly, 2000). Sebagai peneliti yang mengumpulkan kisah-kisah, mereka menegosiasikan
hubungan, perpindahan yang sopan, dan menyediakan cara yang bermanfaat bagi para partisipan.
Dalam penelitian narasi, tema kunci sedang mengarah kepada hubungan antara para peneliti dan
yang diteliti dimana kedua fihak akan belajar dan berubah dalam sebuah pertemuan (Pinnegar dan
Daynes, 2006). Dalam proses ini, masing-masing fihak menegosiasikan makna kisah,
menambahkan sebuah pemeriksaan validasi untuk analisis (Creswell dan Miller, 2000). Dalam
kisah milik partisipan dapat juga terdapat kisah yang terjalin dari para peneliti yang ditambahkan ke
dalam kehidupannya (partisipan) (lihat Huber dan Whelan, 1999). Juga, dalam kisah terdapat
epipani atau poin pengarah dimana garis cerita yang merubah arah secara dramatis. Dan di akhir,
studi narasi akan menceritakan kisah individu yang terbuka dalam sebuah kronologi dari
pengalaman mereka, yang tertata dalam hidup pribadi dan sosial mereka dan konteks sejarah dan
memuat tema penting dalam pengalaman hidup tersebut. “Penyelidikan Narasi merupakan kisah
hidup dan cerita,” demikian dikatakan Clandinin dan Conolly (2000, hlm. 20).
Tantangan
Setelah diberikan karakteristik dan prosedur penelitian narasi ini, penelitian narasi merupakan
sebuah pendekatan menantang (bagi peneliti) untuk diterapkan. Para peneliti perlu mengumpulkan
informasi mendalam tentang para partisipan dan perlu memiliki pemahaman yang jelas akan
konteks kehidupan seseorang individu. Hal tersebut membutuhkan pandangan yang tajam untuk
mengenali sumber materi yang mengumpulkan kisah khusus yang menangkap pengalaman
individu. Seperti komentar Edel (1984) merupakan hal penting untuk mengungkap sosok di bawah
8
karpet (tersembunyi) yang menjelaskan ragam latar konteks sebuah kehidupan. Aktif bekerjasama
dengan para partisipan adalah perlu dan para peneliti perlu membicarakan kisah para partisipan juga
yang merefleksikan tentang latar belakang politik dan pribadi mereka yang membentuk bagaimana
mereka mengisahkan kembali sejumlah bagian-bagian kehidupan mereka. Beragam persoalan
mencuat ketika proses pengumpulan, analisa dan penceritaan kisah individu. Pinnegar dan Daynes
(2006) memunculkan pertanyaan penting berikut ini: Siapa pemilik kisah? Siapa yang dapat
menceritakannya? Siapa yang dapat mengubahnya? Versi siapa yang meyakinkan? Apa yang terjadi
ketika narasi-narasi itu bersaing? Sebagai sebuah komunitas, kisah apa yang terjadi di antara kita?
Penelitian Fenomenologi
Pengertian dan Latar Belakang
Ketika sebuah studi narasi melaporkan sebuah kehidupan dari seorang individu tunggal, studi
fenomenologi mendeskripsikan makna bagi sejumlah individu mengenai pengalaman hidup mereka
mengenai sebuah konsep atau sebuah gejala. Para peneliti fenomenologi fokus pada penggambaran
apa yang dimiliki oleh semua partisipan secara umum seperti yang mereka alami mengenai sebuah
gejala (misalnya, kegagalan adalah pengalaman universal). Tujuan utama fenomenologi adalah
untuk mengkhususkan pengalaman individu dengan sebuah gejala untuk sebuah gambaran inti yang
universal (sebuah pemahaman mengenai sangat alaminya sesuatu, Van Manen, 1990, hlm. 177).
Untuk tiba pada batas akhir ini, para peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah gejala (sebuah objek
pengalaman manusia, Van Manen, 1990, hlm. 163). Pengalaman manusia ini mungkin saja gejala
seperti insomnia, tersisihkan, kemarahan, kesedihan, mengalami pembedahan langsung arteri
koroner (Moustakas, 1994). Para penyelidik kemudian mengumpulkan data dari pribadi-pribadi
yang mengalami gejala tersebut dan mengembangkan sebuah deskripsi campuran mengenai inti
pengalaman bagi semua individu. Deskripsi ini terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana
mereka mengalaminya (Moustakas, 1994).
9
Di depan semua prosedur ini, fenomenologi memiliki sebuah komponen filosofi yang kokoh
mengenainya. Ia menggambarkan dengan kental dalam sebuah tulisan tentang ahli matematika
berkebangsaan Jerman bernama Edmund Husserl (1859-1938) dan siapa yang ikut memengaruhi
pandangannya, seperti Heidegger, Sartre dan Merleau-Ponty (Spiegelberg, 1982). Fenomenologi
populer di bidang ilmu sosial dan kesehatan, khususnya dalam sosiologi (Borgatta dan Borgatta,
1992; Swingewood, 1991), Psikologi (Giorgi, 1995; Polkinghorne, 1989), keperawatan dan ilmu
kesehatan (Nieswiadomy, 1993; Oiler, 1986), dan pendidikan (Tesch, 1988; Van Mannen, 1990).
Gagasan Husserl adalah abstrak dan seperti pada tahun 1945, Merleau-Ponty (1962) masih
memunculkan pertanyaan seputar, Apa itu fenomenologi?. Faktanya, Husserl telah dikenal
menangani semua proyek baru-baru ini dibawah model fenomenologi (Natanson, 1973).
Para penulis fenomenologi mengikuti langkah-langkah Husserl juga kelihatannya untuk
menunjukkan perbedaan argumen filosofis untuk penggunaan fenomenologi saat ini (bandingkan,
sebagai contoh, dasar filosofis yang dinyatakan dalam karya Moutakas, 1994; dalam karya Stewart
dan Mickunas, 1990; dan dalam karya Van Mannen, 1990). Melihat ke arah semua perspektif ini,
bagaimanapun, kita dapat mengerti bahwa asumsi-asumsi filosofis bersandar pada sejumlah
landasan/ dasar umum: studi mengenai pengalaman seseorang, memandang bahwa semua
pengalaman ini merupakan sebuah kesadaran (Van Mannen, 1990), dan sebuah pengembangan
deskripsi tentang inti pengalaman-pengalaman ini, tidak menjelaskan atau menganalisa (Moustakas,
1994). Pada batasan paling luas, Stewart dan Mickunas (1990) menekankan empat perspektif
filosofis dalam fenomenologi:
-Kembali ke tugas tradisional filosofi. Pada akhir abad ke 19, filosofi telah menjadi terbatas untuk
menunjukkan sebuah dunia dengan arti empiris, yang disebut Saintisme. Kembali pada tugas-tugas
lama filosofi yang telah ada sebelumnya menjadi memikat bersama ilmu empiris yang merupakan
kembalinya ke konsepsi Yunani mengenai filosofi sebagai sebuah usaha pencarian kebebasan.
-Filosofi tanpa presupposisi. Pendekatan fenomenologi adalah untuk menyingkirkan semua
10
penilaian mengenai apa yang nyata- atribut alami- hingga mereka menjumpai dalam sebuah dasar
yang lebih khusus. Suspensi ini disebut epos oleh Husserl.
-Dalamnya kesadaran. Gagasan ini adalah bahwa kesadaran selalu mengarah kepada sebuah objek.
Realitas sebuah objek, kemudian adalah kemampuan eksternal terkait kesadaran seseorang
mengenainya. Kemudian, realitas menurut Husserl, tidak terbagi ke dalam subjek dan objek, tetapi
ke dalam dual alam Cartesian mengenai subjek dan objek, seperti kehadirannya dalam kesadaran.
-Penolakan dikotomi subjek-objek. Tema ini mengalir secara alami dari dalamnya kesadaran.
Realitas sebuah objek adalah hanya difahami dalam pengertian pengalaman dari seseorang individu.
Sebuah penulisan individu tentang fenomenologi akan diizinkan untuk tidak memuat sejumlah
diskusi tentang presupposisi filosofis fenomenologi sepanjang metode-metode yang digunakan
masih dalam bentuk penyelidikan ini. Moustakas (1994) telah menyediakan lebih dari seratus
halaman untuk asumsi-asumsi filosofis sebelum ia kembali ke arah penjelasan mengenai metode-
metode.
Jenis-Jenis Fenomenologi
Dua pendekatan terhadap fenomenologi menyoroti diskusi di bawah ini:
Fenomenologi Hermenetik (Van Mannen, 1990) dan empirik, transendental, atau fenomenologi
psikologi (Moustakas, 1994). Van Mannen (1990), karyanya sering dikutip secara luas dalam
literatur kesehatan (Morse dan Field, 1995). Selaku pendidik, Van Mannen telah menulis sebuah
buku pengajaran dalam fenomenologi hermenetik dimana ia mendeskripsikan penelitian sebagai
orientasi ke arah pengalaman hidup (fenomenologi) dan menafsirkan teks kehidupan (hermenetik)
(Van Mannen, 1990, hlm. 4). Meskipun Van Mannen tidak mendekati fenomenologi dengan
sekumpulan aturan atau metode, ia mendiskusikan penelitian fenomenologi sebagai sebuah
dinamika kegiatan internal di antara kelima kegiatan penelitian. Pertama kali para peneliti harus
mengarah kepada sebuah fenomena (gejala), sebuah konsentrasi yang berkesinambungan (hlm. 31),
11
yang secara serius menarik minat mereka (misalnya, membaca, berlari, mengemudi, dan
pengasuhan). Dalam prosesnya, mereka merefleksi pada tema penting apa yang mengangkat
kealamiahan pengalaman hidup ini. Mereka menulis sebuah deskripsi mengenai fenomena,
memperbaiki hubungan yang kokoh terkait topik penyelidikan dan mengimbangi bagian-bagian dari
penulisan keseluruhannya. Fenomenologi bukan hanya sekedar deskripsi, tetapi juga sebagai sebuah
proses penafsiran di mana para peneliti membuat sebuah penafsiran (misalnya para peneliti
memediasi antara perbedaan makna; Van Mannen, 1990, hlm. 26) makna pengalaman hidup.
Fenomenologi transendental atau transendental karya Moustakas (1994) kurang fokus dalam
penefsiran-penafsiran para peneliti dan lebih fokus pada deskripsi pengalaman partisipan. Sebagai
tambahan, Moustakas fokus pada satu konsep milik Husserl, yaitu epos (atau pengurungan/
pengucilan), dimana para investigator meletakkannya di samping pengalaman mereka sebanyak
mungkin untuk mengambil perspektif yang segar ke arah gejala yang berada dalam pengawasan.
Sebab itu, transendental berarti dimana segala sesuatu dipersepsikan secara segar (asli) seperti
ketika ia hadir untuk pertamakalinya (Moustakas, 1994, hlm. 34). Moustakas membiarkan bahwa
tahap ini jarang diperoleh secara sempurna. Bagaimanapun, penulis melihat para peneliti yang
menggunakan gagasan ini ketika mereka memulai sebuah proyek dengan menggambarkan
pengalaman milik mereka sendiri tentang sebuah gejala dan menghadirkan pandangan-pandangan
mereka sebelum melanjutkan dengan pengalaman-pengalaman lainnya.
Disamping pengisolasian, empirik, fenomenologi transendental tergambar dalam Dusquesne
Studies in Phenomenology Psychology (misalnya, Giorgi, 1985) dan prosedur analisis data karya
Van Kaam (1966) dan Colaizzi (1978). Prosedur-prosedur tersebut digambarkan oleh Moutakas
(1994) terdiri dari pengidentifikasian sebuah fenomenologi terhadap studi, menghadirkan
pengalaman seseorang dan mengumpulkan data dari sejumlah individu yang mengalami gejala-
gejala tersebut. Para peneliti kemudian menganalisa data dengan mengurangi informasi terhadap
pernyataan-pernyataan penting atau mengutip dan menggabungkan pernyataan-pernyataan tersebut
12
ke dalam tema-tema. Menindaklanjuti hal tersebut, para peneliti mengembangkan sebuah deskripsi
tekstural mengenai pengalaman pribadi tersebut (apa yang dialami partisipan), dan juga sebuah
deskripsi struktural pengalaman mereka (bagaimana mereka mengalaminya dalam istilah kondisi,
situasi atau konteks) dan sebuah gabungan deskripsi tekstural dan struktural untuk membawa
sebuah inti keseluruhan dari pengalaman.
Prosedur-Prosedur Pelaksanaan Penelitian Fenomenologi
Penulis menggunakan pendekatan psikologis karya Moustakas (1994) karena memiliki langkah-
langkah yang sistematis dalam prosedur analisis data dan memberikan panduan-panduan untuk
mengumpulkan deskripsi tekstual dan struktural. Pelaksanaan fenomenologi psikologis telah
terwujud dalam sejumlah penulisan, termasuk dalam karya Dukes (1984), Tesch (1990), Giorgi
(1985, 1994), Polkinghorne (1989) dan belakangan dalam karya Moustakas (1994). Langkah-
langkah prosedur utama dalam proses akan digambarkan sebagai berikut:
-Para peneliti menentukan jika permasalahan penelitian diuji dengan cara terbaik dengan
menggunakan sebuah pendekatan fenomenologi. Jenis permasalahan baiknya disesuaikan untuk
bentuk penelitian ini yang merupakan sebuah hal dimana ia penting untuk memahami sejumlah
pengalaman umum individu atau pengalaman berbagi mengenai sebuah gejala. Hal tersebut akan
menjadi penting untuk memahami pengalaman umum ini agar dapat mengembangkan praktik-
praktik atau kebijakan, atau untuk mengembangkan sebuah pengalaman terdalam tentang fitur-fitur
fenomenologi.
-Sebuah gejala kepentingan studi seperti rasa marah, profesionalisme, apakah sesuatu yang
dilakukan itu berarti menjadi ringan atau apakah artinya menjadi sesosok pegulat merupakan
sesuatu yang harus diketahui. Moustakas (1994) menyediakan sejumlah contoh mengenai fenomena
yang sedang distudi.
-Para peneliti menyadari dan mengkhususkan asumsi filosofis luas dari fenomenologi. Sebagai
13
contoh, seseorang dapat menulis tentang gabungan realitas objek dan pengalaman individu.
Pengalaman-pengalaman hidup ini lebih jauh merupakan ‘kesadaran’ dan mengarah pada sebuah
objek. Untuk secara penuh menggambarkan bagaimana partisipan melihat sebuah fenomena, para
peneliti harus menampilkannya sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman milik mereka.
-Data dikumpulkan dari para individu yang memiliki pengalaman mengenai gejala. Seringkali
pengumpulan data dalam studi fenomenologi terdiri dari wawancara mendalam dan wawancara
ganda dengan para partisipan. Polkinghorne (1989) menyarankan bahwa para peneliti meneliti dari
5 sampai 25 individu yang memiliki semua penbgalaman-pengalaman tentang sebuah fenomena
tertentu. Bentuk-bentuk lain dari data mungkin dapat dikumpulkan seperti observasi, jurnal, seni,
puisi, musik dan bentuk lain dari seni. Van Mannen (1990) menyebutkan rekaman percakapan,
tulisan resmi, sejumlah pengalaman yang dialami oleh orang lain dalam drama, film, puisi dan
novel.
-Para partisipan ditanya tentang dua hal umum yaitu pertanyaan umum (Moustakas, 1994): Apa
yang telah anda alami dalam istilah yang terkait dengan sebuah fenomenologi? Konteks atau situasi
apa yang secara khas berpengaruh atau berdampak pada pengalaman anda mengenai sebuah gejala
fenomena? Pertanyaan-pertanyaan buka tutup lainnya dapat juga ditanyakan, akan tetapi yang
kedua secara khusus fokus pada perhatian dalam pengumpulan data yang membimbing dan
puncaknya menyediakan sebuah pemahaman pengalaman-pengalaman umum dari para partisipan.
-Langkah-langkah analisis data fenomenologi umumnya serupa bagi semua pakar fenomenologi
psikologis yang mendiskusikan metode-metode (Moustakas, 1994; Polkinghorne, 1989).
Berdasarkan data dari pertanyaan penelitian pertama dan kedua, analisis data berjalan melewati
data-data (misalnya transkrip wawancara) dan menyoroti pernyataan-pernyataan penting, kalimat-
kalimat atau kutipan-kutipan yang menyediakan sebuah pemahaman tentang bagaimana partisipan
mengalami gejala-gejala tersebut. Moutakas (1994) menyebut langkah ini dengan horisontalisasi.
Selanjutnya, para peneliti mengembangkan kelompok makna dari pernyatan-pernyataan penting ini
14
ke dalam tema-tema.
-Pernyataan-pernyataan dan tema penting ini kemudian digunakan untuk menulis sebuah deskripsi
dari apa yang dialami oleh para partisipan (tekstual deskripsi). Mereka juga menggunakannya untuk
menulis tentang pengalaman mereka sendiri. Penulis lebih suka menyingkat prosedur milik
Moustakas dan merefleksikan pernyataan pribadi ini pada awal pembahasan fenomenologi atau
menyertakannya dalam sebuah diskusi metode dari peran para peneliti (Marshall dan Rossman,
2006)
-Dari deskripsi tekstural dan struktural, para peneliti kemudian menulis sebuah deskripsi gabungan
yang menyajikan inti dari sebuah gejala yang biasa disebut esensial, struktur invarian (atau inti).
Utamanya, tinjauan ini fokus pada pengalaman-pengalaman umum dari para partisipan. Sebagai
contoh, itu dapat berarti bahwa semua pengalaman memiliki sebuah struktur yang dikedepankan
(pengalaman adalah sama ketika mencintai seekor anjing, burung betet atau seorang anak). Ia
adalah sebuah pesan yang bersifat deskripsi, sebuah atau dua paragraf panjang, dan para pembaca
harus menjauh dari (penelitian) fenomenologi dengan ungkapan perasaan “Saya memahami lebih
baik apa yang disukai seseorang untuk dialami,” (Polkinghorne, 1989, hlm. 46)
Tantangan-Tantangan
Sebuah penelitian fenomenologi menyediakan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai
sebuah gejala sebagai pengalaman oleh sejumlah individu. Mengetahui sejumlah pengalaman
umum dapat menjadi berharga bagi sebuah kelompok seperti para pemberi terapi, para guru,
personel kesehatan dan pembuat kebijakan. Fenomenologi dapat melibatkan sebuah bentuk garis
haluan pengumpulan data dengan menyertakan hanya wawancara ganda atau tunggal dengan para
partisipan. Dengan menggunakan pendekatan Moustakas (1994) uuntuk menganalisis data
membantu menhyediakan sebuah pendekatan terstruktur bagi para peneliti pemula. Dengan istilah
lain, penyelidikan fenomenologi sekurang-kurangnya adalah sejumlah pemahaman terkait asumsi-
15
asumsi filosofis yang luas dan ini harus diidentifikasi oleh para peneliti. Para partisipan yang
terlibat dalam studi perlu berhati-hati untuk memilih peran individu yang memiliki semua
pengalaman tentang sebuah fenomena yang diajukan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian,
dengan demikian para peneliti pada akhirnya dapat menempa sebuah pemahaman umum.
Pengisolasian pengalaman pribadi mungkin sulit bagi para peneliti ketika dalam tahap
implementasi. Sebuah pendekatan penafsiran terhadap fenomenologi akan menunjukkan hal ini
sebagai hal yang mustahil (Van Mannen, 1990)- bagi para peneliti menjadi bagian yang terpisah
dari teks. Mungkin kita perlu sebuah definisi baru epos atau pengisolasian, seperti menggantungkan
pemahaman kita dalam sebuah gerak refleksi yang memperkuat keingintahuan (LeVasseur, 2003).
Kemudian, para peneliti perlu menentukan bagaimana dan dengan cara apa pemahaman individunya
akan mengantarnya ke dalam studi.
Penelitian Teori Dasar
Meskipun sebuah fenomenologi menekankan makna sebuah pengalaman bagi sejumlah individu,
maksud dari sebuah studi teori dasar adalah untuk bergerak melampaui deskripsi dan untuk
melakukan jeneralisir atau mengungkap sebuah teori, sebuah analitis abstrak yang
menggambarkan sebuah proses (atau tindakan atau interaksi, Strauss dan Corbin, 1998). Seluruh
partisipan dalam studi semuanya akan mengalami proses, dan pengembangan teori yang mungkin
ikut membantu menjelaskan praktik atau menyediakan sebuah kerangka kerja untuk penelitian
selanjutnya. Gagasan utamanya adalah bahwa pengembangan teori ini tidak datang dengan
sendirinya, tetapi lebih merupakan jeneralisir atau dasar/landasan dalam data dari para partisipan
yang memiliki pengalaman proses (Strauss dan Corbin, 1998). Kemudian, teori dasar adalah sebuah
disain penelitian kualitatif dimana para penyelidik menjeneralisir sebuah penjelasan umum (sebuah
teori) dari sebuah proses, tindakan atau interaksi yang terbentuk oleh pandangan-pandangan
terhadap sejumlah besar partisipan (Strauss dan Corbin, 1998).
16
Disain kualitatif telah dikembangkan pada tahun 1967 oleh dua peneliti, yaitu Barney Glaser
dan Anselm Strauss, sosok yang merasakan bahwa teori-teori yang digunakan dalam penelitian
seringkali tidak memadai dan kurang sesuai untuk partisipan dalam sebuah studi. Mereka
memperluas gagasan mereka melalui sejumlah buku yang ditulis (Glasser, 1978; Glaser dan Strauss,
1967; Strauss dan Corbin, 1990, 1998). Hal ini berlawanan dengan orientasi a priori (berdasar teori
daripada kenyataan yang sebenarnya), orientasi teoritis dalam sosiologi, teori dasar berpegangan
bahwa teori harus berlandas pada data yang berasal dari lapangan, khususnya dalam tindakan-
tindakan, hubungan atau proses melalui antarhubungan kelompok-kelompok informasi berdasarkan
data yang dikumpulkan dari para individu.
Walaupun kolaborasi awal antara Strauss dan Glaser yang menghasilkan sejumlah kerja
seperti dalam karya Awareness of Dying (kesadaran akan kematian) (Glaser dan Strauss, 1965) dan
Time for Dying (Glaser dan Strauss, 1968), dua pengarang pada puncaknya tidak sepakat tentang
pemaknaan dan prosedur teori dasar. Glaser telah mengkritik pendekatan Strauss terhadap teori
dasar sebagai terlalu kaku dan terstruktur (Glaser, 1992). Dan lebih baru lagi, karya Charmaz (2006)
yang telah membela para kontruktifis teori dasar, kemudian memperkenalkan perspektif lain ke
dalam pembicaraan tentang prosedur. Melalui penafsiran-penafsiran yang berbeda ini, teori dasar
telah memeroleh popularitas dalam sejumlah bidang seperti sosiologi, keperawatan, pendidikan dan
psikologi, sama baik dengan bidang ilmu sosial lainnya.
Perspektif teori dasar lainnya yaitu yang berasal dari Clarke (2005) yang, sama lamanya
dengan Charmaz, mencari cara untuk menegaskan kembali teori dasar dari pondasi positifismenya
(hlm. xxiii). Clarke bagaimanapun juga melangkah lebih jauh dibanding Charmaz yang
menyarankan bahwa situasi sosial harus berasal dari unit analisis kita dalam teori dasar dan bahwa
tiga mode sosiologi dapat bermanfaat dalam penganalisaan situasi ini, dunia/arena sosial, dan peta
kartograpi posisional untuk pengumpulan dan penganalisaan data kualitatif. Ia lebih jauh
memperluas teori dasar dalam after the postmodern turn (setelah giliran posmodern) (hlm. xxiv)
17
dan berdasarkan perspektif posmodern (misalnya, lingkungan politis peneliti dan para penafsir,
merefleksikan sisi tertentu peneliti, memahami permasalahan penyajian ulang informasi, pertanyaan
legitimasi dan otoritas dan memosisikan kembali para peneliti jauh dari kesan Mengetahui semua
analis kepada posisi mengakui posisi partisipan) (hlm, xxvii, xxviii). Clarke dengan sering
mengarahkan pada penulis posmodern dan posstruktural yaitu Michael Foucalt (1972) untuk
membantu mengarahkan wacana teori dasar.
Jenis Studi Teori Dasar
Terdapat dua pendekatan populer terhadap teori dasar yaitu prosedur sistematisnya Strauss dan
Corbin (1990, 1998) dan pendekatan kontruktifisnya Charmaz (2005, 2006). Dalam keadaan yang
lebih sistematis lagi, adalah prosedur analitisnya Strauss dan Corbin (1990, 1998), para investigator
mencari secara sistematis cara untuk mengembangkan sebuah teori yang menjelaskan proses,
tindakan atau interaksi pada sebuah topik (misalnya, proses pengembangan sebuah kurikulum,
keuntungan tarapetik dari berbagi hasil tes psikologi dengan klien).
Para peneliti secara khusus melaksanakan 20 hingga 30 wawancara berdasarkan pada
sejumlah kunjungan ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data wawancara untuk
menjenuhkan pengelompokkan (atau untuk menemukan informasi yang dapat melanjutkan
penambahan informasi kepada mereka hingga tidak ada lagi yang dapat ditemukan). Sebuah
pengelompokkan menyajikan sebuah unit informasi yang berisi peristiwa, kejadian, dan sejumlah
peristiwa (Strauss dan Corbin, 1990). Para peneliti juga mengumpulkan dan menganalisa
pengamatan dan dokumen, tetapi bentuk data ini seringkali tidak digunakan. Ketika para peneliti
mengumpulkan data, ia mulai menganalisa. Kesan penulis mengenai pengumpulan data dalam studi
teori dasar adalah sebuah proses zigzag, keluar lapangan penelitian untuk mengumpulkan data, terus
ke kantor untuk menganalisa data, kembali lagi ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi
data, ke kantor lagi untuk melakukan analisa dan demikian seterusnya. Para partisipan yang
18
diwawancarai secara teoritis dipilih (disebut dengan istilah sampling teoritis) untuk membantu para
peneliti bagi menemukan sebentuk teori. Seberapa banyak lintasan yang dibuat seseorang
bergantung pada kategori apakah informasi menjadi jenuh dan apakah sebuah teori dielaborasi
dengan semua kerumitannya. Proses ini mengambil informasi yang berasal dari pengumpulan dan
pembandingan datanya untuk memunculkan kategori yang disebut data constant comparative/
perbandingan tetap analisis data.
Para peneliti mulai dengan membuka kode, pengkodean data kategori informasi utama. Dari
pengkodean ini, pengkodean poros memunculkan dimana para peneliti mengidentifikasi sebuah
kategori pengkodean terbuka untuk fokus pada (disebut Inti fenomena) dan kemudian kembali ke
data dan membuat kategori sekitar fenomena inti ini. Strauss dan Corbin (1990) mensyaratkan jenis
kategori harus mengidentifikasi sekitar fenomena inti. Ia terdiri dari kondisi penyebab (faktor-faktor
apa yang menimbulkan fenomena inti), strategi (tindakan yang diambil dalam merespon fenomena
inti), kontekstual dan kondisi campurtangan (faktor situasional khusus dan luas yang memengaruhi
strategi) dan konsekensi (hasil dari penggunaan strategi). Kategori ini terkait dan mengitari
fenomena inti dalam sebuah model visual yang disebut paradigma pengkodean secara poros.
Langkah akhir, kemudian adalah pengkodean selektif, dimana para peneliti mengambil model dan
mengembangkan proposisi (atau hipotesa) yang menghubungkan kategori dalam sebuah model atau
mengumpulkan sebuah kisah yang mengambarkan kedekatan kategori dalam sebuah model. Teori
ini, dikembangkan oleh para peneliti kemudian diartikulasikan ke arah akhir sebuah studi dan dapat
mengasumsikan sejumlah bentuk seperti sebuah pernyataan narasi (Strauss dan Corbin, 1990),
sebuah gambar visual (Morrow dan Smith, 1995) atau sebuah rangkaian hipotesa atau proposisi
(Creswell dan Brown, 1992).
Dalam diskusi mereka mengenai teori dasar, Strauss dan Corbin (1998) menggunakan
sebuah model yang selangkah lebih maju untuk mengembangkan sebuah matriks kondisional.
Mereka mengembangkan matrik kondisional sebagai sebuah saluran pengkodean untuk membantu
19
para peneliti membuat hubungan antara kondisi makro dan kondisi mikro yang memengaruhi
fenomena. Matriks ini adalah sebuah serangkaian lingkaran pusat pengembangan dengan label yang
dibangun sisi luar dari individu, kelompok dan organisasi terhadap komunitas, wilayah, negara dan
dunia global. Dalam pengalaman penulis, matrik ini jarang digunakan dalam penelitian teori dasar
dan para peneliti secara khusus mengakhiri studi mereka dengan sebuah pengembangan teori dalam
pengkodean selektif, sebuah teori yang mungkin dilihat sebagai sebuah substansi, teori tingkat
rendah dibanding sebuah abstrak, teori dasar (misalnya, lihat Creswell dan Brown, 1992). Meskipun
membuat hubungan antara teori subtantif dan implikasinya yang luas bagi sebuah komunitas,
negara, dan dunia dalam matriks kondisional adalah hal penting (misalnya, sebuah model alur kerja
di sebuah rumah sakit, kekurangan sarung tangan dan garis panduan nasional dalam kasus AIDS
mungkin seluruhnya terkait; lihat contoh ini seperti yang disediakan oleh Strauss dan Corbin, 1998).
Para pakar teori dasar jarang memiliki data, waktu atau sumber untuk disertakan dalam matrik
kondisional.
Sebuah varian kedua dari teori dasar ditemukan dalam sebuah tulisan pakar kontruktifis,
Charmaz (lihat Charmaz, 2005, 2006). Daripada mengambil sebuah studi dari sebuah proses
tunggal atau kategori inti seperti dalam pendekatan Strauss dan Corbin (1998), Charmaz
mendukung sebuah perspektif kontruktifis sosial yang menyertakan penekanan ragam dunia lokal,
realitas ganda dan kompleksitas dunia khusus, pandangan dan tindakan. Teori dasar kontruktifis
menurut pandangan Charmaz (2006) menggariskan secara jujur dalam pendekatan interpretif
terhadap penelitian dengan garis panduan yang fleksibel, fokus pada pengembangan teori yang
bergantung pada pandangan peneliti, mempelajari tentang pengalaman yang dilekatkan di dalam,
jaringan tersembunyi, situasi dan hubungan dan membuat hirarki yang dapat dilihat terhadap
kekuasaan, komunikasi dan kesempatan. Charmaz menempatkan lebih banyak penekanan pada
pandangan, nilai, keyakinan, perasaan, asumsi dan ideokogi individu dibanding pada metode
penelitian, meskipun ia tidak menggambarkan praktik-praktik pengumpulan data yang banyak,
20
pengkodean data, proses memo dan penggunaan sampel teoritis (Charmaz, 2006). Ia menyarankan
bahwa jargon atau istilah yang rumit, diagram, pemetaan konsep, dan pendekatan sistematik (seperti
Strauss dan Corbin, 1990) dikurangi dari teori dasar dan mewakili sebuah usaha untuk memeroleh
kekuatan dalam penggunaannya. Ia juga mendukung penggunaan kode aktif seperti frasa kalimat
berbasis gerund seperti recasting life. Selain itu bagi Charmaz sebuah prosedur teori dasar tidak
mengurangi peran seorang peneliti dalam sebuah proses. Para peneliti membuat keputusan
mengenai kategori melalui proses, membawa pertanyaan-pertanyaa yang diajukan terhadap data dan
mengembangkan nilai-nilai individu, pengalaman dan prioritas. Sejumlah kesimpulan yang
dibangun oleh ahli teori dasar menurut Charmaz (2005) antara lain sugesti, ketidaksempurnaan dan
tidak meyakinkan.
Prosedur Pelaksanaan Penelitian Teori Dasar
Meski pendekatan interpretif Charmaz memiliki banyak elemen menarik (misalnya reflektifitas,
menjadi fleksibel dalam struktur, seperti didiskusikan dalam bab 2), penulis menyandarkan pada
pandangan Strauss dan Corbin (1990, 1998) untuk menggambarkan prosedur teori dasar karena
pendekatan sistematik mereka membantu para individu mempelajari tentang dan menerapkan
penelitian teori dasar.
-Para peneliti perlu memulai dengan menentukan jika teori dasar adalah sangat cocok untuk studi
permasalahan penelitiannya. Teori dasar merupakan sebuah disain bagus untuk digunakan ketika
sebuah teori tidak tersedia untuk menjelaskan sebuah proses. Literatur mungkin memiliki
ketersediaan model tetapi ia dibangun dan diuji pada populasi dan sampel lain daripada hal tersebut
merupakan kecendrungan terhadap peneliti kualitatif. Juga teori tersebut mungkin wujud namun ia
tidak sempurna karena ia tidak diarahkan secara potensial memiliki variabel bernilai kecendrungan
untuk para peneliti. Pada sisi praktis, sebuah teori mungkin perlu dijelaskan bagaimana orang
mengalami sebuah fenomena/gejala dan teori dasar dibangun oleh para peneliti yang akan
21
menyediakan sejumlah kerangka kerja umum.
-Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan penyelidik terhadap partisipan akan fokus dalam
memahami bagaimana individu mengalami proses dan mengidentifiikasi langkah-langkah dalam
proses (apa itu proses? Bagaimana hal itu terungkap?) setelah awalnya mengemukakan
permasalahan-permasalahan ini, para peneliti kemudian kembali kepada partisipan dan mengajukan
pertanyaan lebih rinci yang membantu untuk membentuk fase pengkodean poros, pertanyaan
seperti: apa titik pusat proses? (fenomena inti). Pengaruh dan dampak apa yang terjadi pada
fenomena ini? (kondisi penyebab); strategi apa yang disertakan selama proses berlangsung?
(strategi); apa efek yang terjadi? (konsekuensi)
-Pertanyaan-pertanyaan ini secara khusus diajukan dalam wawancara meskipun bentuk data lain
juga dikumpulkan seperti pengamatan, dokumentasi dan bahan-bahan audiovisual. Titik poinya
adalah mengumpulkan informasi yang cukup untuk secara penuh membangun (kejenuhan) sebuah
model. Hal ini mungkin mencakup 20 hingga 30 wawancara atau 50 hingga 60 wawancara.
-Analisis data berlangsung dalam tahapan-tahapan. Dalam pengkodean terbuka, para peneliti
membentuk kategori informasi mengenai fenomena yang sedang dipelajari oleh segmentasi
informasi. Dalam setiap kategori, para investigator menemukan sejumlah properti (sifat) atau
subkategori dan mencari data untuk mengukur atau menunjukkan kemungkinan-kemungkinan
ekstrim dalam sebuah kesinambungan properti (sifat).
-Dalam pengkodean poros, para investigator mengumpulkan dalam banyak cara setelah pengkodean
terbuka. Penyajian ini menggunakan sebuah paradigma pengkodean atau diagram logis (misalnya,
model visual) dimana para peneliti mengidentifikasi sebuah fenomena pusat (misalnya kategori
pusat mengenai fenomena), menyelidiki kondisi-kondisi penyebab (misalnya pengelompokan
kondisi-kondisi yang memengaruhi fenomena), strategi khusus (misalnya tindakan atau interaksi
yang merupakan hasil dari fenomena pusat) mengenali konteks dan mengintervensi kondisi-kondisi
(misalnya, kondisi luas dan sempit yang memengaruhi strategi itu) dan menjelaskan konsekuensi-
22
konsekuensi (misalnya hasil dari strategi) untuk fenomena ini.
-Dalam pengkodean selektif, para peneliti mungkin menulis sebuah garis cerita yang
menghubungkan kategori-kategori. Secara pilihan, proposisi atau hipotesis secara khusus
menyatakan prediksi keterkaitan
-Akhirnya, para peneliti mungkin mengembangkan dan melukiskan secara visual sebuah matrik
kondisi yang menguraikan aspek sosial, sejarah dan kondisi yang memengaruhi fenomena pusat. Ia
merupakan sebuah langkah pilihan dan sebuah hal dimana penyelidik kualitatif berfikir tentang
model dari perspektif terkecil sampai terluas.
-Hasil dari proses pengumpulan data da analisis ini adalah sebuah teori, teori tingkat subtansi,
diitulis oleh para peneliti dekat dengansebuah permaslahan khusus atau populasi masyarakat. Teori
muncul dengan bantuan dari proses pememoan, sebuah proses dimana para peneliti menulis
gagasan tentang pengembangan teori melalui sebuah proses terbuka, poros dan pengkodean selektif.
Teori tingkat subtansi mungkin diuji mengikuti verifikasi empiriknya dengan data kuantitatif untuk
membatasi jika ia dapat diterapkan ke populasi dan sampel (lihat prosedur disain metode campuran,
Creswell dan Plano Clark, 2007), secara alternatif, studi mungkin berakhir pada poin ini dengan
penerapan sebuah teori sebagai tujuan penelitian.
Tantangan-Tantangan
Sebuah studi teori dasar menantang para peneliti untuk menyertakan alasan-alasan. Para
investigator perlu mengatur kesamping, sebanyak mungkin, gagasan-gagasan teoritis atau pikiran
dengan demikian analitis teori subtantif dapat muncul. Meskipun mengembang, sifat alami induksi
dari bentuk penyelidikan kualitatif ini, para peneliti harus menyadari bahwa ini adalah sebuah
pendekatan sistematis terhadapa penelitian dengan langkah-langkah khusus dalam analisis data, bila
dilihat dari perspektif pendekatan dari Strauss dan Corbin (1990). Para peneliti menghadapi
kesulitan penentuan ketika kategori-kategori mengalami kejenuhan atau ketika sebuah teori telah
23
rinci secara memadai. Sebuah strategi yang mungkin dapat digunakan untuk bergerak ke arah
kejenuhan adalah menggunakan sampel diskriminasi, dimana para peneliti mengumpulkan
informasi tambahan dari para individu, mirip dengan orang yang awalnya diwawancarai untuk
menentukan jika sebuah teori memegang kebenaran bagi para partispan ini. Para peneliti perlu
menyadari bahwa hasil utama dari studi ini adalah sebuah teori dengan komponen khusus; sebuah
fenomena pusat, kondisi penyebab, strategi, kondisi, konteks dan konsekuensi. Semua ini
memastikan kategori informasi dalam teori, dengan demikian pendekatan Strauss dan Corbin (1990,
1998) mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang diingini sejumlah peneliti kualitatif. Dalam kasus
ini, pendekatan Charmaz (2006), yang kurang terstruktur dan lebih mudah diadaptasi mungkin
dapat digunakan.
Penelitian Etnografi
Definisi dan Latar Belakang
Meski para peneliti teori dasar membangun sebuah teori dari pengujian banyak individu yang
berbagi dalam proses tindakan atau interaksi yang sama, studi partisipasi sepertinya tidak dapat
ditempatkan pada tempat yang sama atau berinteraksi dengan begitu sering sebagai landasan yang
mereka bangun, berbagi pola perilaku, keyakinan dan bahasa. Seorang etnograper tertarik dalam
pemeriksaan pola berbagi ini dan sebuah unit analisis yang lebih besar dari 20 para individu yang
dilibatkan dalam sebuah studi teori dasar. Etnografi berfokus pada sebuah kelompok budaya
sepenuhnya, diakui meski terkadang kelompok budaya ini mungkin sebuah komunitas (sejumlah
guru, secuil pekerja sosial) tetapi secara khusus adalah luas dan melibatkan banyak orang yang
saling berinteraksi sepanjang waktu (guru dalam sebuah sekolah secara keseluruhan, atau sebuah
komunitas kelompok kerja sosial). Etnografi merupakan sebuah disain kualitatif dimana para
peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola-pola berbagi dan mempelajari bentuk nilai-nilai,
perilaku, keyakinan dan bahasa darii sebuah kelompok budaya berbagi (Harris, 1968). Sebagai dua
24
bentuk dari proses dan hasil penelitian (Agar, 1980), etnografi merupakan sebuah cara mempelajari
sebuah kelompok budaya berbagi juga pada akhirnya yang akan menulis produk dari penelitian
tersebut. Sebagai proses, egtnografi melibatkan pengamatan mendalam terhadap kelompok, paling
sering melalui pengamatan partisipan, dimana para peneliti membenamkan diri dari waktu ke waktu
tinggal bersama masyarakat, mengamati dan mewawancarai kelompok partisipan. Para pelaku
etnografi mempelajari makna perilaku, bahasa dan interaksi di antara anggota kelompok budaya
berbagi.
Etnografi dimulai dalam studi perbandingan antropologi budaya yang dilakukan pada awal
abad 20 seperti Boas, Malinowski, Radcliffe-Brown dan Mead. Walaupun para peneliti ini pada
awalnya mengambil disiplin ilmu alam sebagai model untuk penelitian, mereka membedakan dari
penggunaan pendekatan saintifik tradisional melalui pengumpulan (data) dari tangan pertama
(pelaku langsung) yang tertuju pada budaya primitif yang ada (Atkinson dan Hammersley, 1994).
Pada tahun 1920 an dan 1930 an, ahli sosiologi seperti Park, Dewey dan Mead di Universitas
Chicago mengadaptasi metodologi di bidang antropologi terhadap studi kelompok budaya di
Amerika Serikat (Bogdan dan Biklen, 1992). Belakangan ini, pendekatan saintifik terhadap
etnografi telah meluas meliputi mazhab atau subtipe etnografi dengan tujuan dan orientasi teoritis
yang berbeda, seperti fungsionalisme struktural, interaksionalisme simbolis, antropologi kognitif
dan budaya, feminisme, Marsisme, etnometodologi, teori kritis, studi budaya dan posmodernisme
(Atkinson dan Hammersley, 1994). Hal ini telah mengarahkan pada pengurangan sifat ortodok
dalam etnografi dan memiliki hasil dalam pendekatan pluralistik. Banyak buku-buku istimewa yang
tersedia terkait etnografi, termasuk karya Van Mannen (1988) ‘Ragam Wajah Etnografi; Wolcott
(1999) dalam karya Cara Memahami Etnografi; LeCompte dan Schensul (1999) dalam Prosedur
Etnografi yang disajikan dalam bentuk buku ringkasan; Atkinson, Coffey dan Dealmont (2003)
dalam Praktik Etnografi; dan Madison (2005) dalan Etnografi Kritis.
25
Jenis Etnografi
Terdapat ragam bentuk etnografi, seperti etnografi konfessional, sejarah hidup, autobiografi,
etnografi feminis, novel etnografi dan etnografi visual yang dijumpai dalam fotografi dan video dan
media elektronik (Denzin, 1998a; LeCompte, Millroy dan Preissle, 1992; Pink, 2001; Van Mannen,
1988). Dua bentuk populer etnografi yang akan ditekankan di sini adalah etnografi realis dan
etnografi kritis.
Etnografi realis merupakan pendekatan tradisional yang digunakan oleh para antropologi
budaya. Etnografi realis dicirikan oleh Van Mannen (1988), ia merefleksikan sebuah perkembangan
khusus yang dibawa oleh para peneliti ke arah individu yang sedang distudi. Etnografi realis
merupakan sekumpulan objek situasi, secara khusus ditulis dalam titik orang ketiga mengenai
pandangan dan pelaporan secara objektif terkait dengan informasi yang dipelajari dari partisipan
dalam sebuah lapangan penelitian. Dalam pendekatan etnografi ini, para etnografi realis
menceritakan studi dalam bentuk orang ketiga dengan pengungkapan yang tidak memihak dan
melaporkan mengenai apa yang diamati atau didengar dari partisipan. Para peneliti etnografi tinggal
dalam latarbelakang selaku pelapor yang serbatahu tentang fakta-fakta. Para penganut realis juga
melaporkan data objek dalam sebuah moodel yang terukur yang tidak tercemari oleh persangkaan,
tujuan dan pendapat pribadi. Para peneliti mungkin menyediakan rincian biasa mengenai kehidupan
sehari-hari di antara orang-orang yang distudi. Para penganut etnografi juga menggunakan kategori
standar untuk deskripsi budaya (misalnya, kehidupan keluarga, jaringan komunikasi, kehidupan
kerja, jaringan sosial, sistem status). Para penganut etnografi memproduksi pandangan-pendangan
partisipan melalui ungkapan-ungkapan terpilih secara akrab dan memiliki kata pamungkas dalam
hal bagaimana sebuah budaya ditafsirkan dan disajikan.
Bagi kebanyakan peneliti, para penganut etnografi saat ini menggunakan pendekatan kritis
(Carspecken dan Apple, 1992; Madison, 2005; Thomas, 1993) dengan menyertakan dalam
penelitian sebuah perspektif advokasi. Pendekatan ini merupakan sebuah respon terhadap
26
masyarakat saat ini, dimana sistem kekuasaan, martabat, kepemilikan hak istimewa dan para
penguasa melayani dengan maksud memarjinalkan (meminggirkan) orang yang berbeda kelas, ras
dan gender. Etnografi kritis merupakan sebuah jenis penelitian etnografi dimana para pengarang
membela terhadap emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat (Thomas, 1993).
Secara khusus para peneliti kritis merupakan para individu yang berpikiran politis, yang mencari
melalui penelitian mereka untuk menyuarakan keadaan dominasi dan ketidaksetaraan (Carspecken
dan Apple, 1992). Sebagai contoh, etnografi mungkin memelajari institusi sekolah yang berpotensi
menyediakan sebuah hak istimewa bagi tipe siswa tertentu atau praktik bimbingan yang melayani
pemberian kebutuhan kelompok–kelompok yang terabaikan. Komponen utama sebuah etnografi
kritis meliputi sebuah orientasi yang memuat nilai-nilai khusus, pemberdayaan masyarakat dengan
memberikan mereka wewenang lebih, menentang keadaan statis dan mengarahkan perhatian
tentang kontrol dan kekuasaan. Para peneliti etnografi akan mempelajari persoalan-persoalan
kekuasaan, pemberdayaan, ketidakmerataan, ketidakadilan, dominasi, ketertekanan, hegemoni dan
pembohongan-pengorbanan.
Prosedur Pelaksanaan Etnografi
Sama halnya dengan penyelidikan kualitatif, tidak ada metode tunggal untuk melaksanakan
penelitian di bidang etnografi. Meski tulisan-tulisan saat ini menyediakan lebih banyak panduan
terhadap pendekatan ini dari yang pernah ada (sebagai contoh, lihat tinjauan istimewa yang
ditemukan dalam karya Wolcott, 1999), yang mengambil pendekatan dengan cara menyertakan
elemen dari kedua pendekatan kritis dan etnografinya penganut aliran realis. Langkah-langkah yang
akan digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian etnografi yaitu sebagai berikut:
-Menentukan jika etnografi merupakan disain yang paling tepat yang digunakan untuk studi
permasalahan penelitian. Pendekatan etnografi dikatakan tepat digunakan bila kebutuhan untuk
mendeskripsikan bagaimana sebuah aktivitas/kerja kelompok budaya dan menyelidiki keyakinan,
27
bahasa, perilaku dan sejumlah persoalan seperti kekuasaan, perlawanan dan dominasi. Sebuah
literatur mungkin tidak memadai secara tepat mengetahui bagaimana sebuah kelompok bekerja
karena sebuah kelompok bukanlah sebuah arus utama, masyarakat mungkin tidak akrab dengan
kelompok tertentu, atau caranya demikian jauh berbeda yang (dengan demikian) para pembaca
mungkin saja tidak mengenali kelompok tersebut.
-Mengenali dan menentukan sebuah kelompok budaya berbagi terhadap studi. Secara khas,
kelompok ini merupakan sebuah kelompok yang tinggal bersama untuk jangka waktu yang lama,
dengan demikian mereka berbagi bahasa, pola perilaku, dan sikap yang melebur dalam sebuah pola
yang cerdas. Kelompok ini mungkin juga sebuah komunitas yang sedang mengalami proses
peminggiran oleh masyarakat. Karena para peneliti etnografi menghabiskan waktu berbincang
dengan dan mengamati kelompok ini, mungkin perlu sebuah akses menemukan satu atau lebih
individu dalam sebuah kelompok orang yang akan mengizinkan para peneliti (masuk dalam
kelompok tersebut, apakah ia seorang juru kunci, informan utama atau seorang partisipan).
-Memilih permasalahan atau tema budaya untuk memelajari tentang keadaan sebuah kelompok
tertentu. Kegiatan ini meliputi analisis kelompok budaya berbagi. Tema-tema tersebut mungkin
menyertakan sejumlah topik seperti enkultrasi, sosialisasi, pembelajaran, pengertian, dominasi,
ketidaksamaan atau perkembangan anak atau dewasa (LeCompte, Millroy dan Preissle, 1992).
Seperti didiskusikan oleh Hammersley dan Atkinson (1995), Wolcott (1987, 1994b), dan Fetterman
(1998), para peneliti etnografi memulai studi dengan menyelidiki masyarakat dalam interaksi pada
latar normal dengan berusaha melihat pola-pola yang dapat ditembus seperti daur kehidupan,
peristiwa, dan tema budaya. Budaya merupakan sebuah istilah yang tidak berbentuk, bukan sesuatu
hal tentang kebohongan (Wolcott, 1987, hlm. 41), tetapi merupakan sesuatu perlengkapan khusus
para peneliti terhadap kelompok ketika mencari pola dunia sosial mereka. Hak tersebut disimpulkan
dari ucapan dan tindakan anggota-anggota kelompok, dan itu ditujukan kepada kelompok ini oleh
para peneliti. Ia terdiri dari apa yang dilakukan oleh masyarakat (perilaku), apa yang mereka
28
katakan (bahasa), tegangan potensial antara apa yang mereka lakukan dengan apa yang seharusnya
mereka lakukan, apa yang mereka pakai dan gunakan seperti sejumlah perkakas (Spradley, 1980).
Sejumlah tema yang bermacam-macam seperti yang digambarkan dalam kamus Konsep dalam
Antropologi Budaya karya Winthrop (1991). Fatterman (1998) membicarakan bagaimana para
peneliti etnografi menggambarkan sebuah perspektif yang menyeluruh tentang sejarah kelompok,
agama, politik, ekonomi dan lingkungan. Dalam deskripsi ini, konsep budaya seperti pertalian
keluarga, struktur politik dan hubungan sosial atau fungsi di antara anggota kelompok mungkin
dapat digambarkan.
-Untuk memelajari konsep budaya, menentukan jenis etnografi yang mana untuk digunakan.
Mungkin tentang bagaimana sebuah kelompok bekerja perlu digambarkan, atau etnografi kritis
mungkin perlu menyingkap permasalahan seperti kekuasaan, hegemoni, dan pembelaan terhadap
sebuah kelompok tertentu. Seorang etnografi kritis, sebagai contoh, mungkin memerhatikan sebuah
ketimpangan dalam masyarakat atau sejumlah bagiannya, menggunakan penelitian untuk
melakukan pembelaan dan melakukan perubahan, dan khusus menyingkap sebuah permasalahan,
seperti ketimpangan, dominasi, tekanan atau ketakberdayaan.
-Mengumpulkan informasi dimana sebuah kelompok bekerja dan tinggal. Ini disebut kerja
lapangan (Wolcott, 1999). Pengumpulan tipe informasi secara khas diperlukan dalam sebuah
etnografi terkait dengan lokasi penelitian, menghargai kehidupan sehari-hari para individu di lokasi
dan mengumpulkan ragam materi yang luas. Permasalahan lapangan mengenai rasa menghormati,
hal timbal balik, memutuskan siapa pemilik data, dan orang lain yang menjadi pusat etnografi. Para
peneliti etnografi membawa sebuah kepekaan terhadap permasalahan pekerjaan lapangan
(Hammersley dan Atkinson, 1995), seperti menghadiri bagaimana memeroleh akses, memberikan
umpan balik atau timbal balik terhadap para partisipan dan menjadi lebih santun dalam semua aspek
penelitian seperti dalam menampilkan diri mereka sendiri dan studi. LeCompte dan Schensul (1999)
mengelola tipe data etnografi ke dalam observasi, tes dan pengukuran, survey, wawancara, analisis
29
isi, metode pemunculan, metode audiovisual, pemetaan ruang dan jaringan penelitian. Dari banyak
sumber data yang dikumpulkan, para etnografi menganalisis data untuk menggambarkan kelompok
budaya berbagi, tema yang muncul dari kelompok dan keseluruhan penafsiran (Wolcott, 1994b).
Para peneliti memulai dengan mengumpulkan sebuah gambaran rinci kelompok budaya berbagi,
fokus pada kejadian tunggal atau sejumlah aktivitas atau berada dalam kelompok dalam periode
waktu yang cukup lama. Para etnografi bergerak kepada analisis tema pola atau topik yang
memberitahukan bagaimana kehidupan dan pekerjaan kelompok budaya.
-Menempa serangkaian kegiatan atau pola-pola sebagai produk akhir analisis ini. Produk akhir
bersifat keseluruhan potret budaya dari kelompok yang tergabung dalam pandangan para partisipan
(emik) serupa dengan pandangan para peneliti (etis). Hal tersebut mungkin saja mendukung
kepentingan kelompok atau menyarankan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk
mengarahkan kepentingan kelompok. Sebagai hasilnya para peneliti memelajari tentang kelompok
budaya berbagi dari kedua belah pihak baik para partisipan maupun penafsiran para peneliti. Hasil-
hasil lain mungkin lebih berbentuk kinerja/ penampilan, seperti produksi teater, permainan atau
puisi.
Tantangan
Penelitian menantang penggunaan alasan-alasan lebih lanjut. Para peneliti perlu memiliki sebuah
landasan dalam antropologi budaya dan pemaknaan sebuah sistem sosial budaya juga konsep-
konsep yang secara khusus diselidiki oleh para peneliti. Waktu yang digunakan untuk
mengumpulkan data bersifat luas, meliputi perpanjangan waktu tinggal di lapangan. Dalam banyak
kasus penelitian etnografi, para peneliti narasi biasanya menulis dalam sebuah bentuk literatur,
hampir-hampir menyerupai pendekatan penuturan sejarah, sebuah pendekatan yang mungkin
membatasi ruang para pendengar untuk sebuah pekerjaan dan mungkin saja menantang para
pengarang yang telah terbiasa dengan pendekatan tradisional dalam menulis penelitian ilmu-ilmu
30
sosial dan kemanusiaan. Terdapat sejumlah kemungkinan untuk para peneliti, untuk lebih menjadi
alami lagi dan menjadi tidak mungkin melengkapi studi atau bersepakat dalam studi. Akan tetapi
sebuah isu dalam sebuah aturan yang rumit dari sejumlah persoalan-persoalan kerja lapangan
menghadapkan para peneliti etnografi yang berusaha masuk ke dalam sebuah kelompok budaya
atau sistem yang belum akrab. Sikap peka terhadap kebutuhan individu yang distudi adalah hal
khusus yang penting dan para peneliti perlu menyatakan dampaknya pada masyarakat dan tempat
yang sedang distudi.
Penelitian Studi Kasus
Definisi dan Latar Belakang
Keseluruhan kelompok budaya berbagi dalam etnografi mungkin dapat dipertimbangkan sebagai
sebuah kasus, tetapi yang dimaksudkan etnografi adalah untuk menentukan bagaimana sebuah
budaya, dibanding memahami sebuah permasalahan atau persoalan menggunakan kasus tertentu
sebagai sebuah gambaran khusus. Kemudian, penelitian studi kasus mencakup studi mengenai
sebuah persoalan yang diselidiki melalui satu atau lebih kasus dalam sebuah sistem yang berbatas
(misalnya, sebuah latar, sebuah konteks). Meskipun Stake (2005) menyatakan bahwa penelitian
studi kasus bukanlah sebuah metodologi akan tetapi sebuah pilihan mengenai apa yang sedang
distudi (misalnya, sebuah kasus dalam sebuah sistem yang berbatas), sementara pakar teori lain
menyajikan studi kasus sebagai sebuah strategi penyelidikan, sebuah metodologi atau sebuah
strategi penelitian yang komprehensif (Denzin dan Lincoln, 2005, Merriam, 1998, Yin, 2003).
Penulis lebih memilih melihat studi kasus sebagai sebuah metodologi, sebuah jenis rancangan
dalam penelitian kualitatif, atau sebuah objek studi, sama seperti sebuah hasil penyelidikan.
Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang mana para peneliti memeriksa sebuah
sistem yang berbatas (sebuah kasus) atau sistem ganda berbatas (banyak kasus) secara rinci, dalam
pengumpulan data yang mendalam meliputi sumber informasi ganda (misalnya, pengamatan,
31
wawancara, materi audiovisual, dokumen dan laporan) dan melaporkan sebuah deskripsi kasus dan
sebuah kasus berbasis tema, sebagai contoh, sejumlah program-program (sebuah studi multi situs/
lapangan) atau sebuah program tunggal (studi di lapangan) mungkin dapat dipilih sebagai studi.
Pendekatan studi kasus telah akrab bagi para ilmuan sosial karena kepopularitasannya di bidang
psikologi (Freud), kesehatan (analisis kasus sebuah masalah), hukum, dan ilmu-ilmu politik
(laporan kasus). Penelitian studi kasus memiliki sejarah panjang dan khusus ke sejunlah disiplin
ilmu. Hamel, Dufour dan Fortin (1993) melacak asal muasal studi kasus ilmu-ilmu sosial modern
melalui sosiologi dan antropologi. Mereka mengutip karya antropologi milik Malinowski tentang
Pulau-pulau Trobriand, karya sosiologis pengarang Perancis tentang studi keluarga, studi kasus
Departemen Sosiologi Universitas Chicago dari tahun 1920 an dan 1930 an dan tahun 1950 an
(misalnya, Thomas dan Znanieck, 1958 studi mengenai Petani Sopan di Amerika dan Eopa) sebagai
pengantar penelitian studi kasus. Saat ini, penulis studi kasus memiliki sebuah aturan teks dan
pendekatan luas yang dapat dipilih. Yin (2003), sebagai contoh kedua penelitian baik pendekatan
kuantitatif maupun kualitatif pengembangan studi kasus dan membicarakan eksplanatori,
eksploratori dan studi kasus kualitatif deskriptif. Merriam (1998) mendukung pendekatan umum
terhadap studi kasus kualitatif dalam bidang pendidikan. Stake (1995) secara sistematis menyusun
sejumlah prosedur untuk penelitian studi kasus dan mengutipnya secara ekstensif dalam contoh
karyanya Harper School. Buku karya Stake yang terakhir ini menyajikan sebuah analisis studi kasus
ganda sebuah pendekatan langkah demi langkah dan menyediakan gambaran yang memadai tentang
studi kasus ganda di Ukraina, Slovakia, dan Rumania (Stake, 2006).
Karakteristik Studi Kasus
Karakteristik studi kasus kualitatif ditentukan oleh ukuran kasus yang berbatas, seperti apakah
sebuah kasus mencakup individu tunggal, beberapa individu, sekelompok, program, atau sebuah
32
aktivitas. Diamping itu dikhususkan juga dalam istilah-istilah yang diarahkan dalam analisis kasus.
Terdapat tiga varian yangg ada dalam istilah-istilah yang diarahkan: studi kasus instrumen tunggal,
studi kasus ganda atau gabungan dan studi kasus intrinsik (hakiki). Dalam studi kasus instrumental
tunggal (Stake, 1995), para peneliti fokus pada sebuah masalah atau perhatian sekali lagi dipilih,
tetapi para peneliti memilih studi kasus ganda untuk menggambarkan sebuah permasalahan. Para
peneliti mungkin memilih untuk studi sejumlah program yang berasal dari sejumlah situs (lokasi)
penelitian atau program rangkap dalam sebuah situs (lokasi) tunggal. Seringkali para penyelidik,
dengan maksud tertentu memilih kasus rangkap untuk menunjukkan perspektif yang berbeda dalam
sebuah permasalahan. Yin (2003) menyarankan bahwa disain studi kasus rangkap digunakan dalam
aspek logis peniruan, dimana para penyelidik meniru prosedur untuk masing-masing kasus. Sebagai
aturan umum, para peneliti kualitatif enggan untuk melakukan jeneralisasi dari satu kasus ke kasus
lain karena konteks kasus yang berbeda. Untuk jeneralisasi terbaik, bagaimanapun, para peneliti
perlu memilih kasus yang representatif untuk masuk dalam studi kualitatif. Kekhususan terakhir
disain studi kasus adalah sebuah studi kasus yang hakiki dimana fokusnya pada kasus itu sendiri
(misalnya, evaluasi program atau studi tentang siswa yang memiliki kesulitan belajar, lihat Stake,
1995) karena sebuah kasus menyajikan sebuah situasi yang tidak biasa/ asing dan unik. Ini
menyerupai fokus pada penelitian narasi, tetapi prosedur analisis studi kasus mengenai deskripsi
rinci kasus berada dalam konteksnya atau sekelilingnya masih tetap berlaku.
Prosedur Pelaksanaan Studi Kasus
Sejumlah prosedur juga tersedia untuk pelaksanaan studi kasus (lihat Merriam, 1998, Stake, 1995,
Yin, 2003). Diskusi ini akan disandarkan secara khusus berdasar pada pendekatan pelaksanaan studi
kasus karya Stake (1995).
-Pertama, para peneliti menentukan terlebih dahulu jika pendekatan studi kasus merupakan
pendekatan yang paling tepat diterapkan dalam permasalahan penelitian. Sebuah studi kasus sebuah
33
pendekatan yang baik ketika para penyelidik secara jelas dapat mengenali kasus-kasus dengan
batasan-batasannya dan menyiapkan sebuah pemahaman yang mendalam terhadap kasus atau
sebuah perbandingan sejumlah kasus.
-Lebih jauh, para peneliti perlu mengenali kasus atau sejumlah kasus mereka. Kasus-kasus ini
mungkin meliputi seorang individu, sejumlah individu, sebuah program, sebuah peristiwa, atau
sebuah kegiatan. Dalam pelaksanaan penelitian studi kasus, penulis (Creswell) merekomendasikan
bahwa penyelidik pertamakali mempertimbangkan apa hal khusus dari sebuah studi kasus yang
paling menjanjikan dan bermanfaat. Sebuah kasus dapat berbentuk tunggal atau gabungan, bersitus
rangkap atau bersitus hakiki, fokus pada sebuah atau permasalahan (hakiki, isntrumental) (Stake,
1995, Yin, 2003). Dalam hal pemilihan kasus mana terhadap studi, sebuah aturan kemungkinan
untuk tersedianya sampel purposif sudah tersedia. Penulis lebih suka memilih kasus-kasus yang
menunjukkan perspektif beragam pada sebuah permasalahan, proses atau peristiwa yang ingin
dipotret penulis (disebut sampel maksimal purposif, Creswell, 2005), tetapi penulis juga mungkin
memilih kasus-kasus umum, kasus-kasus yang dapat diakses, atau kasus-kasus yang tidak biasa.
-Pengumpulan data dalam peneltian studi kasus secara khusus bersifat mendalam, menggambarkan
sumber informasi yang rangkap, seperti pengamatan, wawancara, dokumentasi dan materi
audiovisual. Sebagai contoh, Yin (2003) merekomendasikan enam (6) jenis informasi untuk
dikumpulkan; dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan partisipan
dan perlengkapan fisik.
-Jenis analisis data ini dapat berupa sebuah analisis menyeluruh terhadap keseluruhan kasus, atau
sebuah analisis yang disertakan terhadap aspek khusus dari kasus (Yin, 2003). Melalui
pengumpulan data ini, deskripsi yang rinci terhadap kasus (Stake, 1995) muncul ketika para peneliti
merinci sejumlah aspek sejarah sebuah kasus, kronologi (urutan) peristiwa, atau kejadian rutin yang
turut berkontribusi pada kegiatan-kegiatan sebuah kasus. (Studi kasus pria bersenjata dalam
lampiran F meliputi penelusuran respon kampus terhadap seorang pria bersenjata selama dua
34
minggu secara langsung mengikuti ke arah tragedi dalam kampus.). Setelah mendeskripsikan hal ini
(secara relatif merupakan data yang tak dapat dipertandingkan, Stake, 1995, hlm. 123), para peneliti
dapat fokus pada sejumlah kecil permasalahan (atau analisis tema), bukan untuk melakukan
jeneralisir melampaui kasus, tetapi untuk memahami kerumitan sebuah kasus. Sebuah strategi
analitis akan digunakan untuk mengenali permasalahan dalam setiap kasus dan kemudian mencari
tema umum yang menjernihkan kasus tersebut (Yin, 2003). Analisis ini kaya akan konteks kasus
atau latar dimana sebuah kasus menampilkan dirinya sendiri (Merriam, 1998). Ketika kasus rangkap
dipilih, sebuah bentuk khas pertamakali menyediakan sebuah gambaran rinci mengenai kasus dan
tema dalam kasus yang disebut analisis kasus secara internal dan diikuti sebuah analisis tematik ke
arah kasus yang disebut analisis kasus secara silang, sama halnya seperti pernyataan yang tegas atau
sebuah penafsiran terhadap makna kasus.
-Pada fase akhir penafsiran, para peneliti melaporkan makna kasus, apakah makna tersebut berasal
dari pembelajaran tentang permasalahan-permasalahan dari sebuah kasus (sebuah kasus pelengkap)
atau pembelajaran mengenai sebuah situasi yang asing/ tidak biasa (sebuah kasus hakiki). Seperti
yang disebutkan oleh Lincoln dan Guba (1985), fase ini merupakan pengalaman pembelajaran dari
sebuah kasus.
Tantangan
Sebuah tantangan yang muncul dari dalam pengembangan studi kasus kualitatif adalah bahwa para
peneliti harus mengenali kasusnya sendiri. Penulis tidak dapat mengajukan sebuah solusi yang
terang terhadap tantangan ini. Peneliti studi kasus harus memutuskan sistem batasan mana yang
perlu distudi, memahami bahwa sejumlah aspek berkemungkinan menjadi calon untuk pilihan ini
dan menerapkan salah satu dari dua kasus itu sendiri atau dari sebuah permasalahan, dimana sebuah
kasus atau sejumlah kasus dipilih untuk menggambarkan apa yang layak untuk distudi. Para peneliti
harus mempertimbangkan apakah akan melakukan studi tunggal atau banyak kasus. Studi lebih dari
35
satu kasus mengurangi keseluruhan analisis, banyak kasus studi individu kurang mendalam dalam
kasus tunggal manapun. Ketika seorang peneliti memilih banyak kasus, permasalahan menjadi
berapa banyak kasus? Tidak ada istilah serangkaian kasus. Secara khusus bagaimanapun seorang
peneliti memilih tidak lebih dari empat atau lima kasus. Apa yang memotivasi para peneliti untuk
mempertimbangkan sejumlah besar kasus merupakan sebuah gagasan tentang daya jeneralisir,
sebuah istilah yang menggunakan sedikit pemaknaan bagi kebanyakan peneliti kualitatif (Glesne
dan Peshkin, 1992). Memilih sebuah penyelidikan sebuah kasus berarti bahwa para peneliti
membangun sebuah argumen untuk menggunakan strategi purposif sampelnya untuk memilih
sebuah kasus dan mengumpulkan informasi tentang sebuah kasus. Memiliki informasi yang
memadai untuk menyajikan sebuah potret mendalam sebuah kasus membatasi nilai sejumlah studi
kasus. Dalam perencanaan studi kasus, penulis dibantu sejumlah orang yang mengembangkan
sebuah matrik pengumpulan data dimana mereka mengkhususkan sejumlah informasi yang
sepertinya layak mereka kumpulkan terkait sebuah kasus. Mempertimbangkan batasan-batasan
sebuah kasus, bagaimanapun hal tersebut mungkin dibatasi dalam penyebutan waktu, peristiwa dan
proses merupakan sebuah tantangan. Sejumlah studi kasus mungkin saja tidak memiliki poin awal
dan akhir yang jelas dan peneliti akan perlu mengatur sejumlah batasan yang secara memadai
meliputi sebuah kasus.
Perbandingan Kelima Pendekatan
Kelima pendekatan secara umum memiliki proses lazim mengenai penelitian yang mulai dengan
sebuah permasalahan penelitian dan kemajuan terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian, data,
analisis data dan laporan penelitian. Mereka juga menggunakan proses pengumpulan data yang
sama, penyertaan, dalam tingkatan yang bervariasi, wawancara, pengamatan, dukumen, dan bahan
audiovisual. Juga, sepasang kesamaan potensial di antara rancangan harus dicatat. Penelitian
narasi, etnografi dan penelitian studi kasus mungkin terlihat mirip ketika unit analisis merupakan
36
sosok individu tunggal. Benar, seorang peneliti mungkin saja dapat mendekati studi tentang sosok
individu tunggal dengan menggunakan satu dari ketiga pendekatan ini, bagaimanapun jenis-jenis
data sosok tersebut akan dikumpulkan dan dianalisa akan dipertimbangan secara berbeda. Dalam
penelitian narasi, para penyelidik fokus pada sejarah yang dikisahkan dari seorang individu dan
menata kisah ini dalam aturan kronologis. Dalam etnografi, fokusnya pada latar sejarah individu
dalam sebuah konteks budaya dan kelompok budaya berbagi mereka. Dalam penelitian studi kasus,
kasus tunggal secara khusus dipilih untuk menggambarkan sebuah permasalahan dan peneliti
mengumpulkan deskripsi rinci mengenai latar untuk sebuah kasus. Seperti komentar Yin (2003),
Anda akan menggunakan metode studi kasus karena anda dengan sengaja ingin mengungkap
kondisi kontekstual- keyakinan dimana mereka mungkin sangat berhubungan dengan fenomena
studi anda (hlm. 13). Pendekatan penulis yang disarankan adalah jika para peneliti mengingini studi
sosok individu tunggal, pendekatan narasi atau studi kasus tunggal mungkin dapat dipertimbangkan
karena etnografi merupakan sebuah bingkai budaya yang sangat luas. Kemudian ketika
membandingkan studi narasi dengan studi kasus tunggal, penulis merasa pendekatan narasi terlihat
lebih akademis karena studi narasi ditujukan fokus pada individu tunggal, sedangkan studi kasus
seringkali melibatkan lebih dari sebuah kasus.
Dari gambaran ringkas kelima pendekatan ini, penulis dapat mengenali perbedaan mendasar
dari antara jenis penelitian kualitatif ini. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1, penulis
menyajikan sejumlah dimensi untuk membedakan di antara kelima pendekatan. Pada tingkat yang
paling bawah, kelimanya berbeda dalam hal mengenai apa yang sedang mereka lengkapi pada fokus
mereka atau objek utama dari studi. Penyelidikan sebuah kehidupan merupakan hal yang berbeda
dari proses generalisir sebuah teori atau penggambaran perilaku sebuah kelompok budaya. Selain
itu, meski adanya tumpang tindih dalam menentukan dari mana asal disiplin ilmunya, sejumlah
pendekatan memiliki tradisi disiplin ilmu sendiri (misalnya teori dasar berasal dari sosiologi,
etnografi mengakar pada antropologi atau sosiologi) dan yang lainnya memiliki latarbelakang
37
interdisiplin ilmu yang luas (misalnya, narasi dan studi kasus). Pengumpulan data memiliki
keragaman dalam hal penggunaan istilah dalam titik tekannya (misalnya, lebih banyak pengamatan
dalam etnografi, lebih banyak wawancara dalam teori dasar) dan kesinambungan pengumpulan data
(misalnya, hanya wawancara dalam fenomenologi, bentuk rangkap pengumpulan data dalam
penelitian studi kasus untuk menyajikan potret kasus yang mendalam). Pada tahap analisis data,
perbedaan-perbedaan tersebut sangat nampak. Tidak hanya menyangkut satu perbedaan khusus
mengenai sebuah analisis (misalnya teori dasar sangat bersifat unik, penelitian narasi kurang
terumus dengan baik), tetapi sejumlah langkah yang diambil juga bervariasi (misalnya, langkah
yang luas dalam fenomenologi, sejumlah kecil langkah-langkah dalam etnografi). Hasil dari setiap
pendekatan berupa laporan tertulis mengambil bentuk semua proses-proses sebelumnya. Narasi
tentang kehidupan seseorang membentuk penelitian narasi. Penggambaran sebuah inti pengalaman
fenomena menjadi sebuah fenomenologi. Sebuah teori seringkali tergambar dalam sebuah model
visual, menekankan pada teori dasar dan sebuah pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana
kelompok budaya berbagi beraktifitas dihadirkan dalam etnografi. Sebuah studi mendalam
mengenai sebuah sistem atau kasus yang terbatas (atau sejumlah kasus) menjadi sebuah studi kasus.
Terkait dengan dimensi tabel 4.1. terhadap disain penelitian dalam kelima pendekatan akan menjadi
fokus bab selanjutnya. Para peneliti mendapatinya begitu membantu untuk memahami poin ini
secara umum menggambarkan secara keseluruhan struktur dari kelima pendekatan. Mari periksa
pada tabel 4.2. tentang struktur masing-masing pendekatan.
Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Kelima Pendekatan KualitatifKarakteristik Narasi Fenomenologi Teori Dasar Etnografi Studi KasusFokus Menyelidiki
kehidupan seorang individu
Memahami inti pengalaman
Mengembangkan sebuah teori dasar dalam data yang berasal dari lapangan penelitian
Menggambarkan dan menafsirkan sebuah kelompok budaya berbagi
Mengembangkan sebuah gambaran dan analisis mendalam sebuah kasus tunggal atau kasus ganda
Jenis Permasalahan yang paling sesuai untuk disain
Keperluan untuk mencerikan pengalaman individu
Keperluan untuk menggambarkan inti sebuah fenomena kehidupan
Mendasarkan sebuah teori dalam sudut pandang partisipan
Menggambarkan dan menafsirkan pola berbagi budaya sebuah kelompok
Menyediakan sebuah pemahaman mendalam mengenai sebuah atau banyak kasus
Latar belakang Penggambaran Penggambaran dari Penggambaran dari Penggambaran dari Penggambaran dari
38
disiplin ilmu dari ilmu kemanusiaan meliputi antropologi, leteratur, sejarah, psikologi, dan sosiologi
ilmu psikologi dan pendidikan
ilmu sosiologi ilmu sosiologi ilmu psikologi, hukum, ilmu politik dan kesehatan
Unit Analisis Mempelajari satu atau lebih individu
Mempelajari beberapa individu yang berbagi sebuah pengalaman
Mempelajari proses, tindakan atau interaksi yang meliputi banyak individu
Mempelajari sebuah kelompok yang berbagi budaya yang sama
Mempelajari sebuah peristiwa, sebuah program, sebuah aktivitas dan melibatkan banyak individu
Bentuk pengumpulan data
Mengutamakan penggunaan wawancara dan dokumen
Mengutamakan penggunaan wawancara dengan individu meskipun dokumen, observasi, dan seni mungkin pula dapat dipertimbangkan
Mengutamakan penggunaan wawancara dengan 20-60 individu
Mengutamakan penggunaan pengamatan dan wawancara, tetapi mungkin pengumpulan sumber data lain selama waktu perpanjangan di lapangan penelitian
Menggunakan banyak sumber, seperti wawancara, pengamatan, dokumen dan alat perlengkapan sehari-hari
Strategi analisa data
Menganalisa data untuk sejarah, pengisahan kembali kisah/sejarah, pengembangan tema, sering menggunakan sebuah rentetan kronologi
Menganalisa data untuk pernyataan penting, pemaknaan unit, tekstural dan deskripsi struktural, deskripsi tentang sebuah esensi
Menganalisa data melalui pengkodean terbuka, pengkodean poros, dan pengkodean seleksi
Menganalisa data melalui deskripsi kelompok budaya berbagi, tema-tema tentang kelompok.
Menganalisa data melalui deskripsi kasus dan tema kasus sama seperti tema-tema lintas kasus
Penulisan laporan Mengembangkan sebuah nrasi tentang kisah kehidupan seseorang
Mendeskripsikan isi pengalaman
Penerapan sebuah teori yang digambarkan dalam sebuah bingkai
Mendeskripsikan bagaimana sebuah aktivitas kelompok budaya berbagi
Mengembangkan sebuah analisa rinci mengenai sebuah atau lebih banyak kasus
Tabel 4.2 Struktur Pelaporan Masing-Masing Pendekatan Pendekatan pelaporan
Narasi Fenomenologi Teori Dasar Etnografi Studi Kasus
Struktur umum studi
Pendahuluan (masalah, pertanyaan)
Pendahuluan (masalah, pertanyaan)
Pendahuluan (masalah, pertanyaan)
Pendahuluan (masalah, pertanyaan)
Memasukkan peredupanPendahuluan (masalah, pertanyaan, studi kasus, pengumpulan data, hasil analisis)prosedur penelitian
(sebuah narasi, pentingnya individu, pengumpulan data, hasil analisis)
prosedur penelitian(sebuah asumsi fenomenologi dan filosofis, pengumpulan data dan analisis)
Prosedur penelitian (teori dasar, pengumpulan data, hasil analisis)
Prosedur penelitian (etnografi, pengumpulan data, hasil analisis)
Pelaporan kisah/sejarah
Pernyataan-pernyataan penting
Pengkodean terbuka Deskripsi budaya Deskripsi kasus/kasus-kasus dan isinya
Para individu menteorisasikan tentang kehidupan mereka
Makna pernyataan-pernyataan
Pengkodean poros Analisis tema budaya Pengembangan permasalahan
Mengenali segmentasi narasi
Tema-tema pemaknaan Pengkodean selektif, model dan proposisi teoritis
Penafsiran, pengalaman pembelajaran,
Rincian tentang masalah terpilih
Pernyataan yang
39
pertanyaan yang timbul
tegasBentuk-bentuk pengenalan makna (peristiwa, proses, epipanis, tema)
Deskripsi yang mendalam mengenai fenomena
Diskusi mengenai teori dan mempertentangkan dengan literatur yang sudah ada
Ringkasan Penutupan /penyorotan
Diadaptasi dari karya Denzin, 1989a, 1989b
Diadaptasi dari karya Moustakas, 1994
Diadaptasi dari karya Strauss dan Corbin, 1990
Diadaptasi dari karya Wolcott
Diadaptasi dari karya Stake, 1995)
Garis panduan dalam tabel 4.2. dapat digunakan dalam perancangan sebuah artikel jurnal dari
sebuah penelitian yang panjang, bagaimanapun dikarenakan sejumlah langkah dalam setiap
pendekatan tersebut, rancangan-rancangan itu juga memiliki kemampuan terapan seperti bab-bab
dari sebuah disertasi atau sebuah buku kerja yang tebal. Penulis memperkenalkannya karena
pembaca dengan sebuah bekal pengetahuan sebagai pengantar dari masing-masing pendekatan,
sekarang dapat mengurai secara umum rancang bangun sebuah studi. Tentu saja, rancang bangun ini
akan memunculkan dan dapat membentuk secara khusus dengan cara penyimpulan studi, tetapi ia
menyediakan sebuah kerangka kerja untuk sebuah disain persoalan untuk ditindaklanjuti. Penulis
menganjurkan garis panduan ini sebagai rambu-rambu umum saat ini. Pada bab lima, kita akan
memeriksa artikel-artikel jurnal yang diterbitkan dari kelima pendekatan tersebut, dimana masing-
masing studi menggambarkan sebuah dari kelima pendekatan dan menyelidiki struktur tulisan dari
setiap kelima pendekatan tersebut.
Ringkasan
Dalam bab ini, penulis menggambarkan masing-masing kelima pendekatan terhadap pendekatan
penelitian, -penelitian narasi, fenomenologi, grounded theory (teori dasar), etnografi dan studi
kasus. Penulis menyediakan sebuah definisi (pengertian), sejumlah sejarah pengembangan
pendekatan mengenai pendekatan, dan bentuk-bentuk utama yang dipahami daripadanya dan
penulis merinci prosedur utama untuk pelaksanaan sebuah studi kualitatif. Penulis juga
mendiskusikan sejumlah tantangan utama dalam pelaksanaan setiap pendekatan. Untuk menyoroti
40
sejumlah perbedaan di antara pendekatan tersebut, penulis menyediakan sebuah tabel ulasan yang
memperbandingkan karakteristik fokusnya, jenis permasalahan penelitian yang ditujukan padanya,
latar belakang disiplin ilmu yang mendasarinya, unit analisis, bentuk pengumpulan data, strategi
analisis data dan tentunya tahap akhir yang lumrah yaitu penulisan laporan. Penulis juga
menyediakan garis panduan mengenai struktur setiap pendekatan yang mungkin berguna dalam
perancangan sebuah studi pada masing-masing kelima jenis. Pada bab selanjutnya, kita akan
memeriksa kelima studi yang menggambarkan seriap pendekatan dan melihat lebih dekat struktur
campuran dari setiap jenis pendekatan.
Bacaan Pengaya
Terdapat sejumlah bacaan yang dapat memperluas ulasan singkat dari masing-masing kelima
pendekatan penyelidikan ini. Pada bab 1, penulis telah menyajikan buku-buku utama yang akan
digunakan untuk memahami diskusi tentang setiap pendekatan. Di sini penulis menyediakan daftar
yang lebih melimpah terkait rujukan yang juga menyertakan kegiatan-kegiatan-kegiatan utama.
Dalam penelitian narasi, penulis akan mendasarkan pada karya Denzin (1989a, 1989b),
Czarniawska (2004), dan khususnya karya Clandinin dan Conelly (2000). Penulis juga
menambahkan dalam daftar buku ini tentang sejarah hidup (angrosino, 1989a), metode-metode
humanistik (Plummer, 1983), dan sebuah buku pegangan yang komprehensif dalam penelitian
narasi (Clandinin, 2006).
Angrosino, M.F. (1989a). Documents of interaction: Biography, and life history in social science perspective. Gainesville: university of Florida Press
Clandinin, D,J., dan Conelly (Ed). (2006). Handbook of narrative inquiry; Mapping a methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.
Clandinin, D,J., dan Conelly, F.M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Fransisco: Josey-Bass
Czarniawska, B. (2004). Narrative in social science research, London: Sage
Denzin, N.K. (1989a). Interpretive biography. Newburry Park, CA: Sage
41
Denzin, N.K. (1989b). Interpretive interactionism. Newburry Park, CA: Sage
Elliot, J. (2005). Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches. London: Sage
Plummer, K. (1983). Documents of life: An introduction to the problems and litarature of a humanistic method. London: George Allen & Unwin
Untuk fenomenologi, buku-buku mengenai metode penelitian fenomenologi oleh Moustakas (1994)
dan sebuah pendekatan hermenetik oleh Van Mannen (1990) akan menyediakan sebuah landasan
bab-bab selanjutnya. Panduan prosedural lain untuk penyelidikan meliputi Giorgi (1985),
Polkinghorne (1989), Van Kaam (1966), Colaizzi (1978), Spiegelberg (1982), Dukes (1984), Oiler
(1986) dan Tesch (1990). Untuk perbedaan-perbedaan mendasar antar hermenetik dan empiris atau
fenomenologi transendental, lihat Lopez dan Willis (2004) dan untuk sebuah diskusi tentang
permasalahan lebih spesifik dan mendalam, lihat LeVasseur (2003). Sebagai tambahan, untuk
mengkaji lebih mendalam landasan yang kuat dalam (memahami bahwa) asumsi filosofis itu
penting dan seseorang mungkin akan memeriksa karya Husserl (1931, 1970), Marleau-Ponty
(1962), Natanson (1973), dan Stewart dan Mickunas (1990) untuk latar belakang ini.
Colaizzi, P.F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. Vaile & M. King (Eds), Existential phenomenological alternatives for psychology (pp. 48-71). New York: Oxford University Press.
Dukes, S. (1984). Phenomenological methodology in the human sciences, Journal of Religion and Health, 23, 197-203.
Giorgi, A. (Ed). (1985). Phenomenology and psychological research. Pitsburgh, PA: Duquesne University Press.
Husserl, E. (1931). Ideas: General introduction to pure phenomenology (D. Carr, Trans). Evanston, IL: Northwestern University Press
Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D. Carr, Trans). Evanston, IL: Northwestern University Press
LeVasseur, J.J. (2003). The problem with bracketing in phenomenology. Qualitative Health Reaserch, 31 (2), 408-420
42
Lopez, K. A, & Willis, D. G. (2004). Descriptive versus interpretive phenomenology: Their contribution to nursing knowledge. Qualitative Health Research, 14 (5), 726-735.
Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception (C. Smith, Trans). London: Routledge & Kegan Paul.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, AC: Sage.
Natanson, M. (Wd). (1973). Phenomenology and the social sciences. Evanston, IL: Northewstern University Press
Oiler, C. J. (1986). Phenomenology: The method. In P. L. Munhall & C. J. Oiler (Eds)., Nursing reaserch: A qualitative perspective (pp. 69-82). Norwalk, CT: Appleton-Cemtury-Crofts.
Polkinghorne, D.E. (1989). Phenomenological research methods. In R. S. Valle & S. Halling (Eds.), Existential-phenomenological perspectives in psychology )pp. 41-60). New York: Plenum.
Spiegelberg, H. (1982). The phenomenological movement (3rd ed). The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff
Stewart, D., & Mickunas, A. (1990). Exploring phenomenology: A guide to the field and its literature (2nd wd). Athens: Ohio University Press
Tesch, R. (1990). Qualitative research: Analysis types and software tools. Bristol, PA: Falmer PressVan Kaam, M. (1966). Existential foundations of psychology. Pitsburgh, PA: Dusquesne University Press
Van Mannen, M. (1990). Researching lived experiences: Human sciences for an action sensitive pedagogy. Albany: State University of New York Press.
Dalam penelitian teori dasar, periksa buku karya Strauss dan Corbin (1990) yang sangat dianjurkan
sebelum meninjau karyanya yang lain Glaser dan Strauss (1967), Glaser (1978), Strauss (1978),
Glaser (1992), atau edisi terbaru karya Strauss dan Corbin (1998). Apa yang tersedia pada buku
karya Strauss dan Corbin (1998) yang penulis yakin (memiliki) sebuah panduan prosedural terbaik
daripada buku karya mereka yang diterbitkan pada tahun 1998. Untuk ulasan metodologi yang
gamblang mengenai teori dasar, periksa karya Charmaz (1983), Strauss dan Corbin (1994) dan
Chenitz dan Swanson (1986). Khususnya karya yang sangat membantu, yaitu buku-buku Charmaz
(2006) mengenai penelitian teori dasar ditinjau dari perspektif kontruksionis dan perspektif
postmodern dalam karya Clarke’s (2005).
43
Charmaz,K. (1983). The grounded theory method: An explication and interpretation. In R. Emerson (Ed), Contemporary field research (hlm. 109-126). Boston: Little, Brown
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. London: Sage.
Chenitz, W. C, & Swanson, J. M. (1986). From practice to grounded theory: Qualitative research in nursing. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
Clarke, A. E. (2005). Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn. Thousand Oaks, CA: Sage
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity. Mill Valley, CA: Sosiology Press
Glaser, B.G. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sosiology Press
Glaser, B.G., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.
Strauss, A. (1987). Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge University Press
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage
Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative research (hlm. 273-285). Thousand Oaks, CA: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage
Sejumlah buku-buku terkini yang membahas tentang etnografi akan menyediakan landasan bagi
bab-bab berikutnya: Atkinson, Coffey dan Delamont (2003); volume pertama dalam rangkaian
sarana para etnografi, Disain dan Pelaksanaan Penelitian Etnografi, sama baiknya dengan enam
volume lainnya dalam rangkaian karya LeCompte dan Schensul (1999); dan Wolcott (1994b, 1999).
Sumber lain tentang etnografi termasuk Spradley (1979, 1980), Fetterman (1998), dan Madison
(2005).
Atkinson, P., Coffey, A., & Delamont, S. (2003). Key themes in qualitative research: Continuities and changes. Walnut Creek, CA: Alta Mira
Fetterman, D. M. (1998). Ethnography: step by step (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
LeCompte, M. D., & Schensul, J.J. (1999). Designing and conducting ethnographic research (Ethnographer’s toolkit, Vol. 1). Walnut Creek, CA: Alta Mira
44
Madison, D. S. (2005). Critical ethnography: Method, ethics, and performance. Thousand Oaks, CA: Sage.
Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. New York: Holt, Rinchart & Winston.
Wolcott, H. F. (1994b). Transforming qualitative data: Description, analysis an interpretations. Thousand Oaks, CA: Sage
Wolcott, H. F. (1999). Ethnography: A way of seeing. Walnut Creek, CA: Alta Mira
Dan akhirnya, untuk penelitian studi kasus, silahkan merujuk pada karya Stake (1995) atau buku-
buku terkini seperti karya Lincoln dan Guba (1985), Merriam (1988), dan Yin (2003).
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Merriam, S. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. San Fransisco: Jossey- Bass
Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage
Yin, R. K. (2003). Case study Research: design and method (3rd ed). Thousand Oaks, CA. Sage.
Latihan
1. Pilih satu di antara kelima pendekatan untuk sebuah studi yang diajukan. Tulis sebuah
deskripsi yang jelas mengenai pendekatannya, meliputi definisi, sejarah, dan prosedur yang
terkait dengan pendekatan tersebut, termasuk referensi literatur.
2. Buatlah sebuah pengajuan studi kualitatif yang akan dilakukan. Mulai dengan
menyajikannya sebagai sebuah studi narasi, kemudian bentuk ke dalam sebuah
fenomenologi, grounded theory (teori dasar), etnografi dan akhirnya studi kasus. Diskusikan
untuk masing-masingnya; jenis studi, fokus dari studinya, jenis pengumpulan dan analisis
data dan penulisan laporan akhir
45