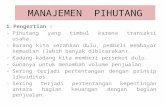Manajemen Kerbau dan Sapi Perah
Transcript of Manajemen Kerbau dan Sapi Perah
BAB IPENDAHULUAN
Latar Belakang
Ternak sapi perah dan kerbau memegang peranan
penting dalam penyediaan gizi bagi masyarakat. Produk
utama yang dihasilkan dari ternak sapi perah adalah
susu dan Kerbau (Bubalus bubalis) adalah ternak ruminansia
besar yang mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan
daging. Susu merupakan cairan bukan kolostrum yang
dihasilkan dari proses pemerahan ternak perah, baik
sapi, kambing maupun kerbau secara kontinyu dan tidak
merubah komponennya sebagai bahan pangan yang sehat.
Susu sapi merupakan susu yang sebagian besar dikonsumsi
oleh manusia, karena kandungan zat gizinya dapat
diserap sempurna oleh tubuh.
Pertumbuhan populasi sapi perah dari tahun -
ketahun rata-rata meningkat, akan tetapi peningkatannya
tidak setinggi pada ternak unggas. Saat ini dibutuhkan
suatu metode yang tepat dalam membangun subsektor
peternakan khususnya mengenai komoditas sapi perah.
Karena sebagian besar susu dihasilkan dari Pulau Jawa,
sehingga pengembangan didaerah luar Jawa sangat
potensial untuk dikembangkan.
Pengembangan sapi perah dapat dilakukan dengan
cara meningkatkan produktivitas sapi perah baik dari
segi teknis maupun dari segi ekonomis. Produktivitas
ternak sapi perah harus dipacu untuk dapat
ditingkatkan, diantaranya manajemen reproduksi dan
manajemen pakan. Hal tersebut dikarenakan besarnya
produksi susu ditentukan oleh keberhasilan program-
program reproduksi dan manajemen pakan yangbalance
(seimbang) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Di samping itu, ternak kerbau dapat dijadikan
sebagai salah satu ternak potong yang dapat
menghasilkan daging untuk memenuhi kebutuhan daging
masyarakat. Oleh karena ternak kerbau dan sapi perah
yang ada di Indonesia perlu dilestarikan dan
dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayah masing-
masing.
BAB IIPEMBAHASAN
MANAJEMEN SAPI PERAH
A. Pengembangan Sapi Perah di Indonesia
Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang
penting sebagai sumber protein hewani, selain kambing,
domba dan ayam. Sapi menghasilkan sekitar 50% (45-55%)
kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85%
kebutuhan kulit (Menteri Negara Riset dan Teknologi,
2005). Sapi berasal dari famili Bovidae. seperti halnya
bison, banteng, kerbau (Bubalus), kerbau Afrika
(Syncherus), dan anoa. Pemeliharaan sapi secara
intensif mulai dilakukan sekitar 400 tahun SM. Sapi
diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian
menyebar ke Eropa, Afrika dan seluruh wilayah Asia.
Menjelang akhir abad ke-19, sapi Ongole dari India
dimasukkan ke pulau Sumba dan sejak saat itu pulau
tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi Ongole murni.
Pada tahun 1957 telah dilakukan perbaikan mutu genetik
sapi Madura dengan jalan menyilangkannya dengan sapi
Red Deen. Persilangan lain yaitu antara sapi lokal
(peranakan Ongole) dengan sapi perah Frisian Holstein
di Grati guna diperoleh sapi perah jenis baru yang
sesuai dengan iklim dan kondisi di Indonesia (Menteri
Negara Riset dan Teknologi, 2005).
Secara garis besar, bangsa-bangsa sapi (Bos) yang
terdapat di dunia ada dua, yaitu (1) kelompok yang
berasal dari sapi Zebu (Bos indicus) atau jenis sapi
yang berpunuk, yang berasal dan tersebar di daerah
tropis serta (2) kelompok dari Bos primigenius, yang
tersebar di daerah sub tropis atau lebih dikenal dengan
Bos Taurus. Di Indonesia, manajemen pemeliharaan
biasanya terbagi atas pemeliharaan sapi perah dan sapi
potong. Jenis sapi perah yang unggul dan paling banyak
dipelihara adalah sapi Shorhorn (dari Inggris),
Friesian Holstein (dari Belanda), Yersey (dari selat
Channel antara Inggris dan Perancis), Brown Swiss (dari
Switzerland), Red Danish (dari Denmark) dan
Droughtmaster (dari Australia). Hasil survei
menunjukkan bahwa jenis sapi perah yang paling cocok
dan menguntungkan untuk dibudidayakan di Indonesia
adalah Frisien Holstein.
Pengembangan usaha peternakan sapi perah di Indonesia
(on farm) beserta industri pengolahannya (off farm)
mengalami kemajuan pesat pada tahun 1980 sampai dengan
1990 namun pada tahun 1990 sampai dengan 1999 produksi
susu segar relatif tetap. Jumlah susu segar yang
diproduksi pertahunnya mencapai kurang lebih 330.000
ton. Produksi tersebut terbagi atas 49% berasal dari
Jawa Timur, 36% dari Jawa Barat dan sisanya 15% dari
Jawa Tengah. (1999). Dari segi perkembangan populasi
sapi perah pada tahun 1970 sekitar 3000 ekor menjadi
193.000 ekor pada tahun 1985, dan menjadi 369.000 ekor
pada tahun 1991. Kenaikan ini terjadi karena adanya
impor sapi perah asal Australia dan New Zealand
( Achjadi, 2001). Pada tahun 1999 industri persusuan
nasional hanya memproduksi ± 20% terhadap total
kebutuhan industri pengolahan, sehingga sisanya masih
sangat bergantung kepada bahan baku impor. Kondisi ini
tidak bisa dibiarkan berlangsung lama tanpa adanya
upaya perbaikan pengelolaan sapi perah. Untuk
memperbaiki keadaan ini dibutuhkan usaha yang keras
dari segala komponen yang terkait, mulai dari peternak
sampai dengan pemerintah.
Sistem peternakan sapi perah yang ada di Indonesia
masih merupakan jenis peternakan rakyat yang hanya
berskala kecil dan masih merujuk pada sistem
pemeliharaan yang konvensional. Banyak permasalahan
yang timbul seperti permasalahan pakan, reproduksi dan
kasus klinik. Agar permasalahan tersebut dapat
ditangani dengan baik, diperlukan adanya perubahan
pendekatan dari pengobatan menjadi bentuk pencegahan
dan dari pelayanan individu menjadi bentuk pelayanan
kelompok. Keberhasilan usaha peternakan sapi perah
sangat tergantung dari keterpaduan langkah terutama di
bidang pembibitan (Breeding), pakan, (feeding), dan
tata laksana (management). Ketiga bidang tersebut
kelihatannya belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal
ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan
peternak serta masih melekatnya budaya pola berfikir
jangka pendek tanpa memperhatikan kelangsungan usaha
sapi perah jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan
peningkatan pengetahuan dan pemahaman peternak tentang
manajemen sapi perah yang baik sehingga akan berdampak
pada peningkatan produksi dan ekonomi.
B. Manajemen Pemeliharaan
Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pola
pemeliharaan sapi potong harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Penyiapan sarana dan peralatan tertutama
perkandangan
2. Pembibitan dan pemeliharaan bakalan/bibit
3. Kesehatan dan sanitasi
4. Manajemen pemberian makan
5. Administrasi serta perhitungan ekonomi
Penyiapan Sarana dan Peralatan
Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau
tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki.
Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan
pada satu baris atau satu jajaran, sementara kandang
yang bertipe ganda penempatannya dilakukan pada dua
jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak
belakang. Diantara kedua jajaran tersebut biasanya
dibuat jalur untuk jalan.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjaga agar ternak nyaman sehingga dapat mencapai
produksi yang optimal, yaitu :
Persyaratan secara umum :
a. Ada sumber air atau sumur
b. Ada gudang makanan atau rumput atau hijauan
c. Jauh dari daerah hunian masyarakat
d. Terdapat lahan untuk bangunan dengan luas yang
memadai dan berventilasi
Persyaratan secara khusus :
a. Ukuran kandang yang dibuat untuk seekor sapi
jantan dewasa adalah 1,5 x 2 m atau 2,5 x 2 m,
sedangkan untuk sapi betina dewasa adalah 1,8 x 2 m
dan untuk anak sapi cukup 1,5 x 1 m per ekor, dengan
tinggi atas ± 2-2,5 m dari tanah.
b. Ukuran bak pakan : panjang x lebar = bersih 60 x 50
cm
c. Ukuran bak minum : panjang x lebar = bersih 40 x 50
cm
d. Tinggi bak pakan dan minum bagian dalam 40 cm
(tidak melebihi tinggi persendian siku sapi) dan
bagian luar 80 cm
e. Tinggi penghalang kepala sapi 100 cm dari lantai
kandang
f. Lantai jangan terlalu licin dan terlalu kasar
serta dibuat miring (bedakan ± 3 cm). Lantai kandang
harus diusahakan tetap bersih guna mencegah
timbulnya berbagai penyakit. Lantai terbuat dari
tanah padat atau semen, dan mudah dibersihkan dari
kotoran sapi. Lantai tanah dialasi dengan jerami
kering sebagai alas kandang yang hangat.
g. Selokan bagian dalam kandang untuk pembuangan
kotoran, air kencing dan air bekas mandi sapi :
Lebar (L) x Dalam selokan (D) = 35 x 15 cm
h. Selokan bagian luar kandang untuk pembuangan bekas
air cucian bak pakan dan minum : L x D = 10 x 15 cm
i. Tinggi tiang kandang sekurang-kurangnya 200 cm
dari lantai kandang
j. Atap kandang dibuat dari genteng
k. Letak kandang diusahakan lebih rendah dari sumber
air dan lebih tinggi dari lokasi tanaman rumput.
(Hasanudin, 1988). Lokasi pemeliharaan dapat
dilakukan pada dataran rendah (100-500 m) hingga
dataran tinggi (> 500 m). Temperatur di sekitar
kandang 25-40 derajat C (rata-rata 33 derajat C) dan
kelembaban 75%.
Seluruh bagian kandang dan peralatan yang pernah
dipakai harus disuci hamakan terlebih dahulu dengan
desinfektan, seperti creolin, lysol, dan bahan-bahan
lainnya.
Pembibitan dan Pemeliharaan Bakalan/Bibit
Sapi perah yang cocok dipelihara di Indonesia
adalah sapi Shorthorn (dari Inggris), Friesian Holstein
(dari Belanda) dan Yersey (dari selat Channel antara
Inggris dan Perancis). Agar dapat memperoleh bibit sapi
perah yang baik diperlukan adanya seleksi baik
berdasarkan silsilah, bentuk luar atau antomis maupun
berdasarkan jumlah produksi.
Ciri-ciri sapi perah betina yang baik:
1. Kepala panjang , sempit, halus, sedikit kurus dan
tidak banyak berotot
2. Leher panjang dan lebarnya sedang, besarnya
gelambir sedadang dan lipatan-lipatan kulit leher
halus
3. Pinggang pendek dan lebar
4. Gumba, punggung dan pinggang merupakan garis lurus
yang panjang
5. Kaki kuat, tidak pincang dan jarak antara paha
lebar
6. Badan berbentuk segitiga, tidak terlalu gemuk dan
tulang-tulang agak menonjol (BCS umumnya 2)
7. Dada lebar dan tulang -tulang rusuk panjang serta
luas
8. Ambing besar, luas, memanjang kedepan kearah perut
dan melebar sampai diantara paha. Kondisi ambing
lunak, elastis dan diantara keempat kuartir terdapat
jeda yang cukup lebar. Dan saat sehabis diperah
ambing akan terlimpat dan kempis, sedangkam sebelum
diperah gembung dan besar.
9. Produksi susu tinggi,
10.Umur 3,5-4,5 tahun dan sudah pernah beranak,
11. Berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai
keturunan produksi susu tinggi,
12. Tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit
menular, dan
13. Tiap tahun beranak.
Kesehatan
Gangguan dan penyakit dapat mengenai ternak
sehingga untuk membatasi kerugian ekonomi diperlukan
control untuk menjaga kesehatan sapi menjadi sangat
penting. Manjememen kesehatan yang baik sangat
mempengaruhi kesehatan sapi perah. Gangguan kesahatan
pada sapi perah terutama berupa gangguan klinis dan
reproduksi. Gangguan reproduksi dapat berupa
hipofungsi, retensi plasenta,kawin berulang,
endometritis dan mastitis baik kilnis dan subklinis.
Sedangkan gangguan klinis yang sering terjadi adalah
gangguan metabolisme (ketosis, bloot, milk fever dan
hipocalcemia), panaritium, enteritis, displasia
abomasum dan pneumonia. Adanya gangguan penyakit pada
sapi perah yang disertai dengan penurunan produksi
dapat menyebabkan sapi dikeluarkan dari kandang atau
culling. Culling pada suatu peternakan tidak boleh
lebih dari 25, 3%. Salah satu parameter yang dapat
digunakan untuk pemeliharaan sapi dengan melihat body
condition scoring, nilai BCS yang ideal adalah 3,5
(skala 1-5). Jika BCS lebih dari 4 dapat menyebabkan
gangguan setelah melahirkan seperti mastitis, retensi
plasenta, distokia, ketosis dan panaritium. Sedangkan
kondisi tubuh yang kurus menyebabkan produksi
susumenurun dengan kadar lemak yang rendah. Selain itu
faktor-faktor yang perlu diperhatikan didalam kesehatan
sapi perah adalah lingkungan yang baik, pemerahan yang
rutin dan peralatan pemerahan yang baik.
Manajemen Pemberian Pakan
Pakan sapi terdiri dari hijauan sebanyak 60%
(Hijauan yang berupa jerami padi, pucuk daun tebu,
lamtoro, rumput gajah, rumput benggala atau rumput
raja, daun jagung, daun ubi dan daun kacang-kacangan)
dan konsentrat (40%). Umumnya pakan diberikan dua kali
perhari pada pagi dan sore hari. Konsentrat diberikan
sebelum pemerahan sedangkan rumput diberikan setelah
pemerahan. . Hijauan diberikan siang hari setelah
pemerahan sebanyak 30-50 kg/ekor/hari.
Pemberian pakan pada sapi perah dapat dilakukan
dengan tiga cara, yaitu system penggembalaan, system
perkandangan atau intensif dan system kombinasi
keduanya. Pemberian jumlah pakan berdasarkan periode
sapi seperti anak sapi sampai sapi dara, periode
bunting, periode kering kandang dan laktasi. Pada anak
sapi pemberian konsentrat lebih tinggi daripada rumput.
Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan
sebanyak 10% dari bobot badan (BB) dan pakan tambahan
sebanyak 1-2% dari BB. Sapi yang sedang menyusui
(laktasi) memerlukan makanan tambahan sebesar 25%
hijauan dan konsentrat dalam ransumnya. Hijauan yang
berupa rumput segar sebaiknya ditambah dengan jenis
kacang-kacangan (legum).
Sumber karbohidrat berupa dedak halus atau
bekatul, ampas tahu, gaplek, dan bungkil kelapa serta
mineral (sebagai penguat) yang berupa garam dapur,
kapur, dll. Pemberian pakan konsentrat sebaiknya
diberikan pada pagi hari dan sore hari sebelum sapi
diperah sebanyak 1-2 kg/ekor/hari. Selain makanan, sapi
harus diberi air minum sebanyak 10% dari berat badan
perhari.Pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang
cukup dan berkualitas, serta menjaga kebersihan kandang
dan kesehatan ternak yang dipelihara. Pemberian pakan
secara intensif dikombinasikan dengan penggembalaan Di
awal musim kemarau, setiap hari sapi digembalakan. Di
musim hujan sapi dikandangkan dan pakan diberikan
menurut jatah. Penggembalaan bertujuan pula untuk
memberi kesempatan bergerak pada sapi guna memperkuat
kakinya.
Administrasi Serta Perhitungan Ekonomi
Usaha ternak sapi perah di Indonesia masih
konvensional dan belum mencapai usaha yang berorientasi
ekonomi. Rendahnya tingkat produktivitas ternak
tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya modal, serta
pengetahuan/ketrampilan petani yang mencakup aspek
reproduksi, pemberian pakan, pengelolaan hasil
pascapanen, penerapan sistem recording, pemerahan,
sanitasi dan pencegahan penyakit. Sistem recording
meliputi tanggal kelahiran, pencatatan asal usul sapi
(pedigree), pencatatan reproduksi sapi seperti sapi
kapan terakhir dikawinkan, terakhir melahirkan dan sapi
yang terlambat kawin Selain itu pengetahuan petani
mengenai aspek tata niaga harus ditingkatkan sehingga
keuntungan yang diperoleh sebanding dengan
pemeliharaannya.
MANAJEMEN PEMELIHARAAN KERBAU
A. Peternakan Kerbau di Indonesia
Di Indonesia kerbau telah berkembang sejak dahulu.
Dimana telah tersebar di seluruh Indonesia termasuk
Sulawesi. Kerbau yang berasal di Indonesia didominasi
oleh kerbau lumpur dengan jumlah populasi sekitar 2
juta ekor dan kerbau perah terdapat 5 ribu ekor.
Kerbau-kerbau tersebut dipelihara oleh peternak kecil.
Untuk kerbau lumpur dengan pemeliharaan secara
tradisional dengan jumlah kepemilikan 2-3 ekor induk
peternak, sedangkan kerbau perah dipelihara atau
digembalakan secara berkelompok pada areal sekitar para
peternak berdiam. Walaupun demikian pada beberapa
tempat tertentu terdapat kepemilikan dalam jumlah besar
sepeti di pulau Moa (Maluku), Sumba (NTT), dan Sumbawa
(NTB) dimana jumlah kepemilikan kerbau per peternak
sapat mencapai 100 ekor per induk. Dengan majunya
otonomi daerah dan adanya permentan tentang penetapan
SDG (sumber daya genetik) ternak lokal maka beberapa
daerah mengklaim kerbau-kerbau lumpur yang ada di
daerahnya untuk ditetapkan sebagai bangsa atau sub
bangsa kebau di Indonesia kerana kemampuan adaptasinya
pada lingkungan tertentu yang cukup berbeda dengan
kawasan kerbau lainnya di Indonesia seperti kerbau
Sumbawa (NTB), dan kerbau Moa (Maluku) yang diusulkan
oleh daerah masing-masing untuk ditetapkan sebagai
rumpun kerbau yang adaptif pada kondisi daerah spesifik
pada iklim mikro masing-masing. (Rusastra, 2011)
Kerbau memiliki beberapa peranan utama secara
nasional yaitu sebagai penghasil daging yang mendukung
program pemerintah dalam hal swasembada daging selain
daging sapi, sebagai ternak kerja, penghasil susu dan
pupuk. Murtidjo (1992) menjelaskan bahwa potensi kerbau
sebagai ternak potong ternyata cukup tinggi, meskipun
kerbau sebagai ternak potong tidak sepopuler sapi
karena dagingnya berwarna lebih tua dan keras dibanding
daging sapi, seratnya lebih kasar dan lemaknya berwarna
kuning. Ternak kerbau yang digemukkan, umumnya
memiliki kemampuan pertambahan bobot badan rata-rata
per hari lebih tinggi dibanding ternak sapi.
Daging kerbau dan kontribusinya dalam pangan
sumber protein hewani masih dikesampingkan dan
menempati urutan kedua sesudah susu di negara yang
banyak terdapat kerbau tipe sungai atau sesudah kerja
di negara yang banyak terdapat kerbau tipe rawa. Di
Indonesia harga per kilogram daging kerbau barangkali
sangat mahal jika diperoleh dari kerbau belang (Tedong
bonga) di Tanah Toraja, Sulawesi. Daging kerbau (buff)
biasanya diperoleh dari penyembelihan (15-20 tahun)
dengan berat 380 kg setelah masa kerja. Jika sengaja
diternakkan untuk pedaging, maka kerbau dapat dipotong
pada umur 8 bulan (Murti, T.W., 2006).
Selain menurut Murtidjo (1992) manfaat kerbau
sebagai ternak kerja ternyata sangat besar. Hal ini
terbukti dengan digunakannya kerbau sebagai tenaga
kerja oleh 0,25 milyar petani di negara-negara
berkembang. Bahkan sampai tahun 2000 pun, sebagian
besar petani masih sangat tergantung pada ternak kerja.
Ditinjau dari segi teknis dan ekonomis, penggunaan
ternak kerbau sebagai tenaga kerja pengolah tanah di
Indonesia mutlak perlu, karena sekitar 85% rumah tangga
petani Indonesia rata-rata memiliki lahan kurang dari 2
ha. Sedangkan mekanisasi dengan traktor hanya
dimungkinkan untuk petani yang memiliki lahan 5 ha atau
lebih. Bila digunakan pagi hari atau sekali sehari,
kerbau sebagai tenaga kerja pengolah tanah sanggup
bekerja selama 3,5 jam. Jika digunakan pagi dan sore
hari atau dua kali sehari, kerbau sanggup bekerja
sampai 6 jam. Jadi, sepasang kerbau memiliki
kesanggupan menyelesaikan tanah sawah seluas 2,3 ha per
musim bila dipekerjakan sekali sehari dan 3,2 ha per
musim bila dipekerjakan dua kali sehari. Kerbau juga
sanggup mengolah sawah berlumpur dalam.
Di Indonesia, kerbau sebagai ternak perah sudah
cukup lama dikenal oleh masyarakat Aceh, Tapanuli
Utara, Palembang, Sulawesi dan Timor. Bila
dibandingkan dengan susu sapi, susu kerbau hasil
pemerahan, tidak banyak mengandung air tetapi lebih
banyak mengandung bahan padat, lemak, laktosa dan
protein. Kandungan lemak pada susu kerbau adalah 50%,
jadi lebih banyak dibandingka susu sapi. Begitu juga
halnya dengan kandungan protein. Di Indonesia, umumnya
susu kerbau tidak dikonsumsi langsung dalam keadaan
segar, tetapi diolah untuk berbagai keperluan. Di
Aceh, susu kerbau dibuat mentega dan minyak samin,
sedangkan d Sumatera Utara dibuat dadih (Murtidjo,
1992).
Konsumen susu kerbau memang masih terbatas, namun
peluang pengembangbiakan produk olahan dari susu kerbau
cukup besar karena kerbau memiliki kadar lemak tinggi.
Bibit kerbau penghasil susu cukup tersedia dan dapat
diimpor dalam bentuk semen atau embrio, sedang
teknologinya telah dikuasai (Triwulaningsih, 2006)
Manfaat lain dari ternak kerbau menurut Murtidjo
(1992), adalah meski tanpa didukung pengetahuan ilmiah,
sejak dahulu andil keterpaduan usaha pertanian dan
peternakan cukup besar dalam mempertahankan hasil
produksi pertanian. Keterpaduan ini juga tidak terlalu
mengeksploitasi kemampuan tanah. Menggunakan ternak
kerbau untuk mengolah tanah pertanian dan membuang
kotoran kerbau di lahan berarti mengembalikan dan
mempertahankan kesuburan tanah. Hasil akhir pelapukan
bahan-bahan organik, berkat adanya mikroorganisme yang
disebut humus, mempunyai kegunaan antara lain menyerap
air untuk kebutuhan tanaman, serta menjaga kelembaban
dan menyerap zat-zat makanan yang dibutuhan tanaman.
Demikian pula jika kebutuhan berlaku secara
efektif sesuai yang dibutuhkan peternak maka tentu
existensi kerbau akan terus dipertahankan. Tetapi jika
sebaliknya yang terjadi maka tentulah populasi kerbau
akan menurun, karena kebutuhan tentu driveb by market and
farmers need. Populasi kerbau tidak akan menurun jika ada
nilai tambah yang dilakukan dan berdampak nyata secara
ekonomi bagi perbaikan penghasilan para peternak
(Rusastra, 2011).
Ciri petenakan kerbau yang mendominasi keragaman
usaha ternak kerbau di Indonesia, identik dengan
ketergantungan pada pakan serat alami antara lain;
rumput alam, jerami, berbagai tanaman pangan dan
holtikultura serta perkebunan dengan skala usaha antara
2-3 unit ternak. Kerbau ini dapat digembalakan secara
terus menerus maupun hanya digembalakan pada siang hari
(Talib 2010) dan dikandangka. Kuswandi (2011) dan
Prawiradigdo et, al (2010) mengatakan bahwa pakan
seperti ini umumnya rendah kualitasnya sehingga
membutuhkan teknologi pengkayaan nutrisi untuk
meningkatkan kualitas nilai gizinya, apalagi kalau
ditambah dengan masalah pemberian pakan dalam jumlah
yang tidak mencukupi, maka produktivitas kerbau akan
sangat sulit diperoleh.
Sepuluh provinsi di Indonesia dengan jumlah kerbau
terbanyak
ProvinsiTahun
2004 2005 2006 2007 2008Nanggro 409,071 338,272 371,143 390,334 280,66
Aceh
Darussalam 2Sumatera
Utara 263,435 259,672 261,794 189,167
155,34
1Sumatera
Barat 322,692 201,421 211,531 192,148
196,85
4Sumatera
Selatan 86,528 90,300 86,777 90,160 77,271
Banten 139,707 135,041 146,453 144,944153,00
4
Jawa Barat 149,960 148,003 149,444 149,030145,84
7Jawa
Tengah122,482 123,815 112,963 109,004
102,59
1
NTB 156,792 154,919 155,166 153,822161,45
0
NTT 136,966 139,592 142,257 144,981148,77
2SulawesiSelatan 161,504 124,760 129,565 120,003 130,10
9Sumber :http;www.ditjennak.go.id/basisdataproses.asp?yhn1=2004&thn2=2008&jt=kerbau&button=submit&rep=2&ket=populasi+nasional+%28per+provinsi%29+
B. Produktivitas Kerbau
Murti (2006) menyatakan bahwa reproduksi yang
jelek dari kerbau rawa dan sungai adalah faktor utama
yang membatasi kinerja kerbau dan pencapaian perbaikan.
Kerbau (rawa dan sungai) mempunyai umur beranak
pertamakali sangat tinggi dan interval kelahiran yang
panjang akibat perkawinan yang tergantung pada musim.
Kadangkala siklus estrus yang tidak tampak juga
menyulitkan dokter hewan dan ahli ternak di pedesaan
dalam upaya pengaturan reproduksinya. Kerbau jantan
akan mengalami dewasa kelamin pada umur 2 tahun,
sedangkan kerbau dara mulai mengalami estrus pada umur
2 - 2,5 tahun.
C. Masalah Pengembangan Kerbau di Indonesia
Faktor penyebab menurunnya populasi kerbau di
indonesia tidak berbeda jauh dengan di negara-negara
asia lainnya. Penurunan produktivitas kerbau
sdesebabkan faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor internal
Faktor internal ditentukan oleh sifat atau
karakteristik dari suatu jenis ternak. Pada kerbau
sifat internal yang berpengaruh terhadap kendala
peningkatan populasi adalah:
Masak Lambat
Kerbau termasuk hewan yang lambat dalam mencapai
dewasa kelamin (Subiyanto, 2010). Pada umumnya kerbau
mencapai pubertas pada usia yang lebih tua, sehingga
kerbau mencapai dewasa kelamin pada usia minimal 3
tahun. 2-3 tahun (Lendhanie, 2005).
Lama Bunting
Kerbau akan mengandung anaknya selama 10,5 bulan,
sedangkan sapi hanya 9 bulan. Menurut Keman (2006) lama
bunting pada kerbau bervariasi dari 300-344 hari (rata-
rata 310 hari) atau secara kasar 10 bulan 10 hari.
Dikemukakan pula oleh Hill (1998) bahw lama bunting
pada kerbau lebih lama dan lebih bervariasi. Untuk
kerbau kerja, lama buntuing kerbau mesir bervarisi 325-
330 hari. Hasil penelitian Landhanie (2005) di Desa
Sapala, kecamatan Danau Panggang lama bunting kerbau
rawa mencapai 1 tahun.
Berahi Tenang
Tanda-tanda berahi pada kerbau, umumnya tidak
tampak jelas (Subiyanto, 2010). Sifat ini menyulitkan
paa pengamatan berahi untuk program inseminasi buatan.
Meskipun fenomena ini bisa diatasi dengan menggunakan
jantan, namun kelangkaan jantan dan sistem pemeliharaan
yang terkurung memungkinkan perkawinan tidak terjadi.
Waktu Berahi
Umumnya berahi pada kerbau terjada pada saat
menjelang malam sampai agak malam den menjelang pagi
atau subuh atau lebih pagi (Toilehere, 2001). Menurut
Hill (1988) tanda-tanda berahi da kativitas perkawinan
pada jkerbau mesir pada umumnya terjadi pada malam
hari. Pada saat seperti ini umumnya kerbau-kerbau
betina di Indonesian sedang berada dalam kandang yang
tertutup yang tidak memungkinkan terjadinya perkawinan.
Jarak Beranak yang Panjang
Jarak beranak yang panjang merupakan implikasi
dari sifat-sifat reproduksi lainnya. Pada kerbau
keerja jarak beranak bervariasi dari 350-800 haru
dengan rata-rata 553 hari (Keman, 2006). Menurut Hill
(1988) jarak beranak pada kerbau bervariasi dari 334-
650 hari. Tyergantung pada manajemen yang dilakukan.
Menurut Ladhanie (2005) jaerak beranaka pada kerbau
rawa antara 18-24 bulan.
Beranak pertama
Panjang sifat-sifat produksi lain akan berpengaruh
langsung terhadap beranak pertama pada kerbau. Hasil
survei di Indonesia terutama si NAD< Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa timur, NTB dan Dulaweisi Selatan, umur
pertama kali beranak masing-masing 45,0; 49,6; 47,7;
49,1; 45,6 dan 49,2 bulan denga rata-rata 47,7 bulan
(Keman, 2006), sementara itu di Brebes, Pemalang,
semarang dan Pati rata-rata umur pertama kali8 beranak,
berturut-turut adalah 44, 40, 44, dan 42 (Keman 2006).
Faktor Eksternal
Diantar faktor eksternal, ada yang berpengaruh
langsung terhadap performa reproduksi dan ada yang
tidak berpengaruh langsung. Reproduksi adalah suatu
proses yang rumit pada semua spesies hewan. Rumit
karena reproduksi tergantung Pada fungsi yang sempurna
proses-proses biokimia dari sebagian besar alat tubuh.
Uvilasi, berahi, kebuntingan, kelahiran dan laktasi,
itu semua tergntung dari fungsi yang sempurna dari
berbagai hormon dan alat tubuh. Setiap abnormalitas
dalam anatomi dan fisiologi dari alat reproduksi
berakibat fertilitas menurun atau dapat menyebabkan
sterilitas. (Anggorodi, 1979).
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang berpengaruh langsung
terhadap performa reproduksi adalah :
Pakan
Menurut Murtidjo (1991), makanan ternak kerbau
dapat dibagi dalam beberapa golongan menurut kebutuhan,
usia, dan manfaat ternak kerbau, yaitu makanan
pengganti untuk anak kerbau (gudel), makanan kerbau
dara, makanan kerbau dewasa, makanan kerbau laktasi,
dan makanan kerbau kering kandang. Bahan baku makanan
ternak kerbau digolongkan menjadi 8 kelas, yakni
hijauan kering, hijauan segar, silase, makanan sumber
energi, makanan sumber protein, makanan sumber mineral,
makanan sumber vitamin, dan makanan tambahan.
Kontribusi pakan sangat kuat pengaruhnya terhadap
performa reproduksi. Makanan berperan penting dalam
perkembangan umum dari tubuh dan reproduktif (Tillman,
et al., 1983).
Peternak kerrbau di negara kita pada dasarnya
merupakan peternak tradisional dan merupakan kegiatan
yang turun menurun sehingga pemberian pakan umumnya
didapat pada saat digembalakan. Rumput yang tumbuh di
lapangan, di pematang sawahn atau pinggir-pinggir jalan
adalah pakan yang tersedia pada saat digembalakan.
Pakan yang diberikan di kandang pada umumnya jerami
kering yang kadang-kadang disiram larutan garam dapur.
Pada musim kemarau ketersediaan rumpur alam akan sangat
menurun jumlahnya dan secara langsung akan berpengaruh
langsung terhadap asupan pakan pada ternak. Pakan
dengan kualitas dan kuantitas seperti ini akan
berpengaruh tidak baik terhadap performa reproduksi.
Diperparah lagi oleh tugan yang harus dilakukan pada
saat musim mengolah sawah. Meskipun salah satu
keunggulan kerbau adalah mampu memamfaatkan pakan
dengan kualitas rendah, namun untuk mendapatkan
performa reproduksi yang baik memerlukan makanan yang
cukup, baik kualitas maupun kuantitas.
Manajemen Pemeliharaan
Menurut Setyawan (2010) menyatakan bahwa manajemen
pemeliharaan dalam upaya pengembangan kerbau di
kabupaten Brebes system pemeliharaannya masih sangat
tradisional karena belum ada sentuhan teknologi terpadu
baik untuk peningkatan populasi ternak, pengelolaan
pakan dan pengetahuan pengelolaan hasil produksi
sehingga menyebabkan peningkatan populasi juga tidak
berkembang.
Sosial Budaya
Beberapa di daerah di Indonesia yang secara sosial
budaya berkaitan dengan kerbau menunjukkan populasi
kerbau yang tingg. Keterkaitannya bis a berupa dalam
adat istiadat atau kebutuhan tenaga kerja. NTB,
Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan
keterkaitannya lebih pada adat istiadat yang turun
temurun. Di Sumatera Barat, kerbau mempunyai arti
sosial yang sangat khas.
Rumah adat dan perkantoran pemerintah mempunyai
bentuk atap yang melengkung yang melambangkan bentuk
tanduk kerbau. Diduga kata “minangkabau” berasal dari
“menang kerbau” (Hardjosubroto, 2006). Pada masyarakat
Batak dikenal upacara kematian sepeti saur matua dan
mangokal hili. Bagian dari rangkaian upacara tersebut
biasanya dilaksanakan pesta syukuran adat yang disertai
pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau juga dilakukan
pada saat upacara perkawinan, horha bius (acara
penghormatan terhadap leluhur, dan pendiri rumah adat
(Susilowati, 2008). Bagi etnis toraja, khususnya toraja
sa`dan, kerbau adalah binatang paling penting dalam
kehidupan sosial mereka (Nooy-Palm, 2003 yang dikutip
Stepanus, 2008) selain sabagai hewan yang memenuhi
kehidupan sosial, ritual maupun kepercayaan
tradisional, kerbau juga menjadi lata takaran, status
sosial dan alat transaksi. Dari sisi sosial, kerbau
merupakan harta yang bernilai tinggi bagi pemiliknya
(Issudarsono, 1979 yang dikutip Stepanus, 2008). Kerbau
juga merupakan hewan domestik yang sering dikaitkan
dengan kehidupan masyarakat yang bermata pencaharian
dibidang pertanian.
Di Banten, kerbau selain digunakan sebagai hewan
kerja juga masyarakat sangat fanatik terhadap daging
kerbau. Menurut Patheram dan Liem (1982) selera
masyarakat banten terhadap daging kerbau cukup tinggi
dibandingkan dengan daging sapi. Di Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur lebih pada kebutuhan tenaga
kerja. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat
sangat berperan terhadap perkembangan populasi kerbau.
Populasi kerbau di Indonesia terdapat di seluruh
provinsi, karena kerbau mempunyai daya adapatasi yang
sangat tinggi. Kerbau bisa berkembang mulai dari daerah
kering di NTT dan NTB, lahan pertanian yang subur di
Jawa hingga lahan rawa di Sulawesi Selatan, Kalimantan
dan daerah pantai Sumatera (Asahan sampai Palembang).
Selain itu pengembangannya tidak akan menghadapi
hambatan selera, budaya da agama (Triwulanningsih).
D. Usaha-Usaha Mempercepat Peningkatan Populasi Dan
Kualitas Kerbau Melalui Efisiensi Reproduksi
Banyak faktor yang harus dilakukan dalam rangka
meningkatkan populasi dan kualitas kerbau diantaranya
adalah:
1. Mengupayakan terbentuknya village breeding
system (VBC) yang secara khusus mengupayakan
pengembangan kerbau.
2. Mengadakan upaya recording serta seleksi kerbau
berdasarkan performa dan asal usul ternak dengan
cara penjaringan ternak yang baik berdasarkan
standarisasi.
3. Penerapan teknologi, khusunya untuk mengolah
limbah pertanian (jerami padi, pucuk tebbu, jerami
jagung, jerami kedelai).
4. Komitmen yang berkelanjutan. Penurunan populasi
kerbau di daerah-daerah tertentu sudah lama
terjadi, namun sampai sejauh ini dorongan
pemerintah, terutama pemerintah daerah belum nyata
mendorong perkembangan populasi di daerahnya
masing-masing. Tidak sedikit peternak kerbau
berlokasi jauh dari pusat pemerintah sehingga
banyak yang tidak tersentuh oleh laju pembangunan.
Fasilitas untuk peningkatan populasi baik software
maupun hardware belum sampai ketangan peternak
kerbau. Peternak kerbau seolah berjalan sendiri
tanpa tahu kemana tujuanya.
5. Pembentukan kelompok ternak. Memungkinkan dapat
mendorong peningkatan populasi. Dalam kelompok para
peternak bisa merencanakan usaha yang akan
dilakukan sehubungan dengan peningkatan populasi,
termaksud terbentuknya kandang kelompok. Kandang
kelompok bila dikelola dengan baik dengan kesadaran
yang tinggi dapat memecahkan masalah ketiadaan
jantan dan keterlambatan perkawinan.
6. Melakukan seleksi, baik pada kerbau betina
maupaun pada kerbau jantan, terutama pada kerbau
jantan. Mengingat satu ekor jantan dalam 1 tahun
mampu mengawini 50 ekor betina dan bila semua
berhasil bunting maka akan lahir anak kerbau yang
genetikanya baik. Pada saat ini justru kerbau
betina atau jantan yang tampilanya lebih besar
adalah yang paling cepat masuk rumah potong. Peran
pemerintah disini melakukan penjaringan agar
fenomena yang sudah lama terjadi ini akan
dihentikan minimal dikurangi.
7. Peternak yang memiliki kerbau yang baik dan
memenuhi standar bibit perlu mendapat penghargaan
dengan memberikan sertifikat. Hal ini bisa
merangsang prestasi selanjutnya dan akan
berpengaruh positif terhadap lingkungan.
8. Mengembangkan program inseminasi buatan pada
daerah-daerah yang padat populasi kerbaunya.
Penerapan inseminasi buatan (IB) pada kerbau adalah
salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya
pejantan unggul sepanjang secara sosial ekonomi
dapat dipertanggungjawabkan (SUBIYANTO, 2010) peran
pemerintah harus mengangtifkan kembali produksi
mani beku kerbau di balai-balai inseminasi buatan.
Dengan inseminasi buatan juga dapat mencegah
terjadinya kawin silang dalam.
9. Peningkatan pendidikan inseminator. Inseminator
buatan pada ternak bukan pekerjaan mudah untuk itu
diperlukan pengetahuan dan keterampilan, lebih-
lebih pada kerbau yang saat berahinya sulit
diamati. Meskipun demikian kita bila kita mau kita
bisa. Pengalaman telah menunjukkan bahwa beberapa
tahun yang lalu pada sapi potong, yang pada saat
itu sulit melakukan inseminasi buatan pada sapi
potong karena sapi potong terutama sapi lokal juga
memperlihatkan berahi tenang. Pada saat ini
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para
inseminator inseminasi buatan pada sapi potong
sudah bisa dilakukan dengan prestasi yang baik.
10. Lokasi peternak kerbau yang umumnya masih
berjauhan, akan menyulitkan pelaksanaan inseminasi
buatan. Seorang inseminator mungkin saja melayani
peternak yang jaraknya dari pos bisa belasan
kilometer. Dalam rangka mempercepat peningkatan
populasi maka program sinkronisasi birahi waktu
pelaksanaan dan jumlah yang akan diinseminasi bisa
diatur dan fasilitas inseminasi bisa lebih efisien.
Penggunaan teknik sinkronisasi birahi akan mampu
meningkatkan efisiensi produksi dan reproduksi
kelompok ternak, disamping juga mengoptimalisasi
pelaksanaan inseminasi butan dan meningkatkan
fertilitas .
11. Untuk meningkatkan mutu genetic kerbau di suatu
wilayah, bisa dilakukan dengan membeli pejantan
unggul hasil seleksi dari wilayah lain atau
menggunakan pejantan IB persilang dengan tipe perah
juga bisa dilakukan dengan harapan keturunanya bisa
menghasilkan susu yang lebih banyak, minimal bisa
memberi susu keturunanya dalam jumlah yang
mencukupi.
BAB IIIPENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa :
1. Sapi menghasilkan sekitar 50% (45-55%) kebutuhan
daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85%
kebutuhan kulit
2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pola
pemeliharaan sapi potong harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Penyiapan sarana dan peralatan tertutama
perkandangan
b. Pembibitan dan pemeliharaan bakalan/bibi
c. Kesehatan dan sanitasi
d. Manajemen pemberian makan
e. Administrasi serta perhitungan ekonomi
3. Permasalahan pengembangan peningkatan populasi
kerbau di Indonesia di sebabkan oleh factor internal
dan eksternal, hal ini menyebabkan pengembangan
usaha ternak kerbau di Indonesia kurang berkwmbang
dibandingkan dengan ternak sapi.
4. Peningkatkan populasi kerbau di Indonesia yaitu
dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti
membentuk village breeding system, Komitmen yang
berkelanjutan, Pembentukan upaya recording ternak,
penerapan teknologi khusunya , kelompok ternak,
Melakukan seleksi, Peternak yang memiliki kerbau
yang baik dan memenuhi standar bibit perlu mendapat
penghargaan, Mengembangkan program inseminasi buatan
pada daerah-daerah yang padat populasi kerbaunya,
Peningkatan pendidikan inseminator, Penggunaan
teknik sinkronisasi birahi,dan persilangan.
DAFTAR PUSTAKA
Ditjennak, 2004.http;www.ditjennak.go.id/basisdataproses.asp?yhn1=2004&thn2=2008&jt=kerbau&button=submit&rep=2&ket=populasi+nasional+%28per+provinsi%29+ .
Dirjen Bina Produksi Ternak. 2004. Statistik PeternakanIndonesia. Dirjen Bina Produksi Peternakan, Jakarta.
Gunawan, dkk. 2010. Kebijakan Pengembangan PembibitanKerbau Mendukung swasembada Daging Sapi/Kerbau.Seminar Lokakarya Nasional Kerbau 2010.Pustlitbang Peternakan, Bogor.
Halim. 2012. Pengembangan Kerbau di Indonesia.http://fapethalim.blogspot.com/
Nugroho, Adi. 2009. Produksi Susu, Pemeliharaan Sapi Perah, danReproduksi, Manajemen Kerbau Perah.http://felicitasdian.blogspot.com/2009/11/sapi-perah_25.html
Triwulanngsih E., 2006. Kerbau Sumber Daging dan Susu. BalaiPenelitian Ternak Bogor, Indonesia. http://www.balitnak.bogor.kerbau.sumber.daging.dan.susu.mungkinkah.
Yahya, Harun. 2008. Manajemen Sapi Perah PadaPeternakan Rakyathttp://wah1d.wordpress.com/beternak-sapi-tanpa-rumput-naskah-ini-disalin-sesuai-aslinya-untuk-kemudahan-navigasi/manajemen-sapi-perah-pada-peternakan-rakyat/