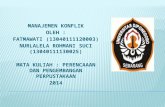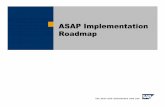konflik kepentingan hak dan kewajiban asasi - Repository ...
Konflik dari Cerobong Asap
Transcript of Konflik dari Cerobong Asap
Konflik dari Cerobong Asap
(Studi kasus pada daerah industri pengasapan ikan di kelurahan
Bandarharjo, Kota Semarang)
Alfisyahr Izzati / 3401412012
Jurusan Sosiologi dan Antropologi
Universitas Negeri Semarang
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Industri pada dasarnya berarti usaha pengolahan barang
mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui
serentetan proses yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan.
Menurut UU Perindustrian No 5 Tahun 1984, industri adalah
kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku,
barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk
kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.
. Penggolongan jenis-jenis industri dapat dilakukan dengan
melihat kuantitas pekerjanya. Industri dalam skala kecil
memiliki jumlah tenaga kerja antara lima hingga sembilan belas
orang. Menurut undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Perkembangan
industri kecil yang bersifat informal merupakan bagian dari
perkembangan industri dan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Industri kecil mempunyai peranan yang strategis dalam hal
pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan
daerah, pemerataan kesempatan kerja, menunjang ekspor non migas
serta melestarikan seni budaya bangsa.
Sebagai Negara maritim dengan kekayaan laut yang luar
biasa, sebagian besar dari angkatan kerja dan kekuatan ekonomi
nasional Indonesia berasal dari sektor kelautan. Di sepanjang
garis pantai utara Pulau Jawa, masyarakat yang bermukim di
daerah-daerah tepi pantai tersebut kebanyakan berprofesi
sebagai nelayan, baik nelayan besar maupun nelayan kecil.
Penghasilan utama mereka adalah apa yang mereka mampu dapatkan
dari dalam laut. Nelayan besar biasanya merupakan mereka yang
memiliki perahu-perahu besar dengan peralatan lengkap. Hasil
tangkapan nelayan besar ini berupa ikan-ikan besar dari tengah
laut. Nelayan kecil ialah mereka yang hanya memiliki perahu
kecil (bercadik maupun tanpa cadik) dengan hasil tangkapan
seperti udang dan ikan-ikan kecil dari tempat yang tak jauh
dari bibir pantai.
Hasil tangkapan nelayan-nelayan besar biasanya langsung
diangkut oleh penampung ikan tangkapan nelayan untuk dibawa
menuju TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ataupun langsung diantarkan
menuju industri pengolahan ikan. Beberapa industri pengolahan
ikan yang ada di Kota Semarang, yaitu industri pengasinan ikan,
pemindangan ikan, pengasapan ikan, dan pembuatan terasi.
Nelayan-nelayan kecil lebih memilih untuk menjual langsung
hasil tangkapannya di tempat pelelangan atau di pasar ikan
maupun di kios-kios kecil pinggir jalan.
Penulis mengambil fokus kajian pengamatan pada kawasan
industri pengasapan ikan di Kelurahan Bandarharjo, karena
kawasan industri tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis
dan ingin mengetahui permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah
asap dari industri pengasapan ikan.
Rumusan Permasalahan
Industri pengasapan ikan di kelurahan Bandarharjo
memproduksi limbah asap yang berasal dari tungku-tungku
pemanggangan yang disalurkan melalui cerobong-cerobong asap
menuju ke luar bangunan industry. Adakah konflik yang
ditimbulkan oleh asap tersebut? Mengapa timbul konflik dalam
masyarakat sekitar industry? Bagaimana cara yang digunakan
masyarakat dalam menyelesaikan konflik dari limbah asap
industry pengasapan ikan?
Tujuan Penelitian
Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti-
peneliti dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda
dalam mengkaji industri pengasapan ikan di sentra pengasapan
ikan kelurahan Bandarharjo, Kota Semarang. Penelitian-
penelitian sebelumnya kebanyakan membahas mengenai
produktifitas industri pengasapan ikan dalam bidang ekonomi,
penerapan bahan bakar tempurung kelapa terhadap kualitas ikan,
pengelolaan lingkungan pada industri pengasapan ikan, lokasi
industri, peranan industry pengasapan ikan dalam peningkatan
pendapatan masyarakat dan beberapa penelitian lain yang
mengambil objek yang sama, yaitu industri pengasapan ikan.
Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan, penulis
berusaha mencari permasalahan yang bisa diangkat dari kawasan
industri tersebut yang lebih relevan dengan bidang keilmuan
penulis. Harapannya, dengan adanya artikel hasil penelitian
singkat yang penulis lakukan secara intensif dalam kurun waktu
kurang lebih dua minggu dan melakukan enam kali observasi
lapangan, dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi para pembaca.
Tinjauan Pustaka
Industrialisasi sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat yang
lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata
lain, pembangunan industri itu merupakan suatu fungsi dari
tujuan pokok kesejahteraan rakyat. Industrialisasi juga tidak
terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam
dan sumber daya lainya. Hal ini berarti pula sebagai suatu
usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia dalam
usia kerja (usia produktif).
Menurut UU Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984, industri
adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk
kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.
Sebenarnya, industri memiliki pengertian yang sangat luas,
yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi
yang sifatnya produktif dan komersial. Disebabkan kegiatan
ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda
untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat
perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin
banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat
kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau
pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada
dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria
yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar,
modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-
faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu
negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara
tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang
harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.
Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-
masing (Siahaan, 1996), adalah sebagai berikut :
1. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja.
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri
dapat dibedakan menjadi :
a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan
tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini
memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal
dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri
biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota
keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri
kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan
ringan.
b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya
berjumlah sekitar relatif kecil, tenaga kerjanya berasal
dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara.
Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan
industri pengolahan rotan.
c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga
kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang
adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja
memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan
memiliki kemapuan manajerial.
d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja
lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki
modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk
pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan
khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji
kemampuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya:
industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan
industri pesawat terbang.
Pengasapan ikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan
untuk mengawetkan dan memberi warna, aroma dan cita rasa yang
khas. Proses pengasapan bisa menghentikan aktivitas mikroba
pembusuk dan enzim perusak dalam daging ikan sehingga proses
pembusukan dapat dicegah. Teknik pengasapan sendiri pada
prinsipnya merupakan proses penarikan air oleh berbagai senyawa
yang berasal dari asap. Adapun bahan bakar yang digunakan
biasanya berupa kayu atau tempurung kelapa (Mashitoh, 2008)
Beberapa hal penting dalam pengasapan ikan adalah :
a. Pemilihan bahan baku
Bahan baku yang digunakan biasanya ikan segar jenis cucut,
pari, tengiri dan tongkol. Untuk ikan jenis besar ini
biasanya dipotong-potong dulu, tidak dalam bentuk utuh
b. Penirisan
Hal ini dilakukan setelah ikan dicuci atau direndam dalam
larutan garam untuk memberikan rasa gurih dan awet
c. Pembentukan warna dan rasa
Rasa, bau dan warna yang khas pada ikan asap/panggang
berasal dari asap dan bara api. Agar warna menarik pada
saat pemanggangan diusahakan agar asap merata.
d. Proses pengasapan
Pengasapan merupakan suatu cara pengawetan dengan
memanfaatkan panas yang berasal dari bara kayu atau bahan
bakar lain. Suhu dalam pengasapan cukup tinggi sehingga
ikan matang. Daya tahan ikan berasal dari pemanasan dan
asap yang menempel selama proses pemanggangan. Mutu Hasil
Pengasapan/Pemanggangan yang baik terlihat dari :
Warna : bersih, cemerlang, coklat, megkilap
Aroma : enak, sedap tanpa aroma lain
Tekstur ikan : padat, tidak berair, empuk, tidak hancur
(jawa : gempi)
Rasa : rasa khas, tidak pahit (Dinas Perikanan, 1995)
Selain memproduksi ikan yang telah diasap, industri
pengasapan ikan tentu saja memproduksi limbah sebagai hasil
dari aktivitas produksinya. Limbah tersebut ialah limbah asap
hasil pembakaran tempurung kelapa. Limbah asap ini dinilai
sebagai penyumbang pencemaran udara di Kota Semarang. Limbah
asap yang dihasilkan industri pengasapan ikan berdampak
langsung pada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan sentra
industri tersebut. Masyarakat yang terkena imbas langsung ialah
masyarakat yang berada di seberang kali yaitu masyarakat di
kelurahan Kuningan yang berhadapan langsung dengan sentra
industri. Mereka yang bermukim di RT delapan, Sembilan dan
sepuluh ialah yang paling merasakan dampaknya, terutama
masyarakat RT Sembilan. Limbah asap ini dapat menimbulkan
gejolak-gejolak di dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan
konflik. Konflik merupakan reaksi terhadap suatu aksi yang
dinilai mengganggu hajat hidup individu maupun kelompok.
Konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan
seorang individu maupun kelompok terhadap tindakan individu
lain atau kelompok masyarakat lain yang ada di sekitarnya.
Konflik muncul selalu berbarengan dengan penyebab-
penyebabnya. Tidak mungkin ada asap tanpa ada apinya, begitu
kata pepatah. Namun demikian, konflik yang muncul juga akan
dibarengi dengan cara-cara penyelesaiannya.
Georg Simmel mengatakan ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu sebagai berikut;
1. Kemenangan di salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. Kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai,
sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada
pihak yang merasa kalah.
3. Rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini akan
mengembalikan suasana persahabatan dan saling percaya di antara
pihak-pihak yang bertikai tersebut.
4. Saling memaafkan atau salah satu pihak memaafkan pihak yang
lain.
5. Kesepakatan untuk tidak berkonflik.
PEMBAHASAN
Indonesia terkenal memiliki wilayah perairan yang sangat
luas dengan potensi kelautan yang dimilikinya, oleh sebab itu
Indonesia disebut sebagai Negara maritim. Tak ayal warga Negara
Indonesia banyak yang bertumpu pada sub sektor perikanan
sebagai sumber mata pencaharian.
Kota Semarang memiliki garis pantai sepanjang 21 km yang
memanjang dari arah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Kendal sampai ke timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Demak. Secara umum, garis pantai Kota Semarang terdiri dari
tiga karakteristik kawasan :
a. Wilayah barat sebagai kawasan yang lebih berorientasi
pada sektor primer untuk pengembangan pariwisata, konservasi,
pertambakan
b. Wilayah tengah merupakan Kawasan Pengembangan
Fungsional Perkotaan yaitu dari pantai PRPP/Marina hingga
kawasan pelabuhan, sebagai pengembangan pelabuhan, industri,
permukiman, pariwisata dan konservasi
c. Wilayah timur mulai dari batas pelabuhan Tanjung Emas
sampai perbatasan Wilayah Kabupaten Demak sebagai pengembangan
kegiatan pertambakan, Pusat Pendaratan Ikan, industri dan
konservasi (Masithoh, 2008).
Tak semua nelayan di Kota Semarang mampu menjadi nelayan
besar. Hanya mereka yang memiliki modal untuk membuat perahu
besar dan mereka yang mempunyai tekad serta keseriusan yang
kuat lah yang menjadi nelayan besar. Sementara mereka yang
tidak terlalu serius menjadi nelayan dan tidak mempunyai modal
banyak untuk membeli perahu dan peralatan nelayan selengkap
nelayan besar akan menjadi nelayan kecil denga perahu-perahu
kecil. Tentu akan ada perbedaan hasil tangkapan diantara
keduanya. Nelayan besar mampu berlayar mencari ikan hingga jauh
ke tengah laut, maka ia akan menghasilkan ikan-ikan tangkapan
yang besar-besar dan lebih banyak. Sementara nelayan kecil
hanya menjangkau wilayah perairan dangkal yang dekat dengan
tepi pantai dengan hasil tangkapan berupa udang, cumi kecil,
dan ikan-ikan kecil. Pangsa pasar keduanya juga berbeda.
Nelayan besar biasanya sudah memiliki penampung ikan-ikan hasil
tangkapannya untuk dijual di tempat pelelangan ikan maupun di
pasar-pasar besar di Kota Semarang. Ada juga ikan-ikan yang
ditampung oleh penampung dan dikirimkan ke industri-industri
pengolahan ikan. Sementara nelayan-nelayan kecil dengan hasil
yang tak seberapa menjual ikan-ikan tangkapan mereka hanya
sampai di tempat pelelangan ikan ataupun di kios-kios kecil
yang mereka dirikan di pinggir jalan besar. Penulis menemukan
kios-kios penjual ikan yang juga berprofesi sebagai nelayan
kecil di tepi jalan arteri PRPP - Pelabuhan Tanjung Emas.
Adapun unsur yang tak kalah penting dari perputaran roda
perekonomian dalam sub sektor perikanan ialah adanya industri
pengolahan ikan. Produksi ikan asap merupakan salah satu dari
hasil usaha pengawetan ikan dengan pengolahan di Kota Semarang.
Industri pengasapan ikan sebagai usaha produksi pengolahan
hasil perikanan terbesar di Kota Semarang, akan tetapi hanya
sebagian kecil bahan baku yang berasal dari daerah sendiri
karena sebagian besar berasal dari daerah lain. Bahan baku yang
digunakan dalam produksi ikan asap ialah ikan Manyung, ikan
Barakuda dan ikan Pari.
Bahan bakar yang digunakan dalam proses pengasapan ikan
adalah tempurung kelapa yang diperoleh dari pengepul yang
menerima setoran dari pasar-pasar dan penjual kelapa parut.
Pengepul menjual tempurung kelapa kering itu dalam karung-
karung goni atau karung beras seharga Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) per karung. Bahan bakar tempurung kelapa ini dipilih
karena menghasilkan panas yang cukup tinggi, merata dan tahan
lama. Setelah tempurung kelapa ini menjadi arang, arangnya pun
dapat dijual di pasar.
Seluruh bagian ikan dapat dimanfaatkan, kecuali jeroan
atau isi perut ikan. Dahulu, jeroan atau isi perut ikan yang
tidak terpakai dibuang begitu saja di sepanjang kali yang
mengalir membelah antara kelurahan Bandarharjo dengan kelurahan
Kuningan. Kali tersebut bernama Kaliasin. Akibat pembuangan isi
perut ikan sembarangan, aroma di sekitar kawasan Kaliasin
sangat tidak sedap. Hal ini menimbulkan polusi udara dan
dampaknya adalah udara menjadi tidak sehat dan tidak segar.
Pada awal tumbuhnya industri pengasapan ikan ini, proses
pengolahan ikan asap masih dilakukan di dalam rumah-rumah
warga. Saat itu belum ada cerobong-cerobong asap, sehingga tiap
kali mengasap ikan,rumah warga akan dipenuhi asap. Mengetahui
hal itu, pemerintah dan dinas kesehatan Kota Semarang
memberikan lahan khusus kepada pemilik usaha pengasapan ikan
untuk membangun sentra industri pengasapan ikan lengkap dengan
cerobong asapnya.
Pada industri pengasapan ikan ini tidak ada perbedaan
mencolok antara pemilik industri dengan para pekerjanya.
Pemilik maupun pekerja senantiasa bekerjasama selama proses
pengasapan ikan berlangsung. Industri pengasapan ikan di
kelurahan Bandarharjo termasuk industri berskala kecil karena
pekerjanya berjumlah tak sampai dua puluh orang. Penulis
mengamati cara kerja pada salah satu rumah produksi, yaitu
industri pengasapan ikan milik Pak Sa’ad. Dalam memproduksi
ikan asap, Pak Sa’ad hanya mempekerjakan lima belas orang yang
kesemuanya masih ada hubungan kerabat dan tetangga, bahkan
anaknya Pak Sa’ad pun turut membantu. Dalam industri ini
mengenal system pembagian tugas antara para lelaki (pemuda dan
bapak-bapak) dan juga ibu-ibu.
Di pagi hari, ikan segar datang dari pengepul sekitar
pukul setengah enam, beberapa pemuda dan bapak-bapak mengangkat
ikan-ikan yang diletakkan di dalam kotak-kotak gabus kemudian
diturunkan dari dalam motor tossa ke pelataran rumah produksi.
Di pelataran rumah produksi itulah para lelaki ini bekerja
memenggal kepala ikan, membelah kepala ikan tersebut menjadi
dua bagian, membersihkan sisik-sisik ikan dan juga membersihkan
isi perut ikan. Keenam orang lelaki tersebut berbagi pekerjaan,
ada yang bagian menyisik kulit ikan dan memenggal kepala,
membelah kepala, dan membersihkan isi perut ikan. Mereka
bekerja sangat cepat dengan pisau daging yang besar dan tajam.
Pada pukul delapan pagi, ibu-ibu datang ke rumah produksi dan
mengambil alih pekerjaan.
Ikan-ikan yang telah dipisahkan dari kepalanya dan sudah
bersih dari sisik dan isi perutnya itu kemudian ditumpuk di
tanah teras rumah produksi. Sembilan orang ibu-ibu yang bekerja
pada rumah industri Pak Sa’ad mulai bekerja sesuai dengan
pembagian kerjanya masing-masing. Ada yang bekerja di bagian
pembelahan ikan menjadi dua bagian, kemudian memotong-motong
daging ikan tersebut menjadi beberapa bagian kecil. Dalam
bidang potong-memotong ini hanya diperlukan dua tenaga ahli
yang sangat cekatan dan hasil potongannya konsisten. Setelah
daging ikan dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil,
daging ikan dimasukkan dalam keranjang berukuran sedang. Satu
persatu daging ikan dalam keranjang tadi segera ditusuki lidi
oleh dua orang ibu yang ahli menyisipi tusuk lidi ke tengah-
tengah daging. Tusukannya sangat rapi karena tusuk lidi
tersebut benar-benar tidak tampak dari luar daging ikan, seolah
tidak ada lidinya. Tusuk lidi ini berfungsi untuk memperkokoh
daging ikan, sehingga saat dibolak-balik tidak mudah hancur.
Setelah ditusuki lidi, masing-masing ibu yang bekerja pada
bidang pengasapan mengambil daging ikan yang siap diasap. Pada
bagian pengasapan, jumlah pekerja menyesuaikan dengan jumlah
tungku yang tersedia. Biasanya terdapat tiga tungku untuk satu
pekerja pengasap ikan. Di rumah industri pengasapan ikan milik
Pak Sa’ad sendiri mempekerjakan lima orang ibu-ibu pada bidang
pengasapan ikan. Pak Sa’ad memiliki tiga pintu rumah industri
dengan empat cerobong asap, oleh sebab itu ia memiliki lebih
banyak pekerja. Meskipun Pak Sa’ad merupakan pemilik dari
industri pengasapan ikan ini, namun tidak ada pembeda atau
eksklusifitas yang ditunjukkannya. Baik pekerja maupun pemilik
industri bekerja sama pada tempat yang sama sesuai bidangnya
masing-masing. Pemilik industri sendiri selalu berada di rumah
industri bersama-sama para pekerjanya. Dalam pembagian tugas,
Pak Sa’ad selaku pemilik industri bekerja sebagai pemantau para
pekerja sehingga ia paham kesulitan yang dihadapi para
karyawannya itu. Ia pun turut bekerja di bagian perendaman ikan
ke dalam drum-drum plastik yang berisi air tawas. Air tawas
dalam pengolahan ikan ini berfungsi untuk menjaga kekuatan
daging ikan yang nantinya akan dipotong-potong menjadi bagian
kecil sehingga tidak mudah hancur. Selain itu, Pak Sa’ad juga
berperan dalam bidang penjualan hasil produksinya.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para
pekerja di industri pengasapan ikan, ditemukan bahwa tidak ada
konflik yang terjadi antara seorang pekerja dengan sesama
pekerja industri. Mereka mengaku bahwa komunikasi antar
pekerja selalu baik-baik saja, karena mereka bekerja pada
bidang yang sama dan mereka semua terhitung kerabat dan
tetangga rumah. Para pekerja pengasapan ikan terintegrasi
karena faktor lingkungan pekerjaan dan lingkungan tempat
tinggal mereka. Demikian halnya yang terjadi dalam hubungan
antara pekerja pengasap ikan dengan pemilik industri pengasapan
ikan. Tidak ada konflik-konflik besar yang terjadi.
Para pekerja pengasap ikan duduk berjam-jam mulai pukul
delapan pagi hingga pukul setengah enam sore (menjelang
maghrib) bersama-sama. Mereka bercakap-cakap dan bersenda
gurau. Minimnya konflik antar pekerja ini dinilai memiliki
hubungan dengan faktor usia para pekerja yang seluruhnya sudah
dewasa. Sehingga tidak ada lagi yang mudah marah atau sensitif
terhadap gurauan-gurauan teman seprofesinya. Adapun hal lainnya
yang membuat para pekerja tetap kompak dan akur ialah karena
mereka telah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Karyawan
terbaru saja sudah bekerja selama dua tahun lebih, sementara
karyawan lama ada yang masa kerjanya sudah mencapai tujuh belas
tahunan.
Konflik justru pernah terjadi dengan masyarakat yang
berada di seberang lokasi industri mereka. Sekitar tahun 2006,
masyarakat RT delapan, Sembilan dan sepuluh kelurahan Kuningan
pernah melakukan demo di lokasi industri pengasapan ikan
tersebut. Wakil ketua RT sepuluh kelurahan Kuningan, Pak Utomo,
menyebutkan bahwa demo yang mereka lakukan dulu itu bukanlah
demo besar-besaran, namun hanya sebatas menyampaikan keluhan
mereka mengenai limbah asap yang dihasilkan oleh industri
pengasapan ikan. Permasalahan ini juga sempat disampaikan
kepada para wakil rakyat yang menjabat di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Semarang. Bahkan, permasalahan limbah asap ini
pun pernah sampai ke balaikota. Setelah pegawai pemerintahan
datang ke lokasi industri, tidak ada penyelesaian yang berarti
bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari limbah asap
industri tersebut. Pada akhirnya, para ketua RT dan pemilik
industri pengasapan ikan dipertemukan dalam satu meja, kemudian
berdiskusi tentang pemecahan masalah yang baik dan adil bagi
mereka.
Permasalahan utama yang mereka kedepankan adalah limbah
asap yang menjadi output sekunder hasil dari pembakaran
tempurung kelapa tersebut menimbulkan penyakit dan
ketidaknyamanan bagi masyarakat RT delapan, sembilan dan
sepuluh. Penyakit yang ditimbulkan ialah saluran infeksi pada
pernapasan.
Saat itu pemerintah hanya mampu membantuan proses
penyelesaian permasalahan dengan memberikan dana sebesar Rp
1.500.000,- kepada setiap pemilik industri pengasapan ikan.
Dana dari pemerintah ini pada awalnya diharapkan agar digunakan
untuk meinggikan cerobong asap yang terdapat pada rumah
industri miliknya. Namun dalam praktiknya, masih banyak pemilik
usaha yang belum meninggikan cerobong asapnya. Hal ini terjadi
karena setelah pencairan dana, pemerintah tidak lagi
menindaklanjuti kasus limbah asap yang dapat mengganggu
kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat di sekitar areal
industri. Dengan kata lain, pemerintah tidak melakukan
pemantauan lanjutan setelah dana dicairkan. Jadi jika ada
penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk meninggikan
cerobong namun tidak dipakai untuk itu, tentu tidak ketahuan.
Pada masa pemerintahan Pak Sukawi Sutarip (menjabat
sebagai walikota Semarang sejak 19 Januari 2000 hingga 2010),
ada rencana untuk pemindahan lokasi (relokasi) industri
pengasapan ikan dari Bandarharjo menuju bagian utara jembatan
arteri. Namun itu hanya wacana belaka. Justru sekarang daerah
utara jembatan jalan arteri tersebut dibangun kolam retensi
untuk mengatasi banjir rob.
Setelah berupaya menyampaikan aspirasi mereka melalui demo
kecil-kecilan tersebut, namun gagal, masyarakat mencari jalan
keluar lain. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari
limbah asap industri sudah berusaha menanam pohon waru di
sepanjang pinggir Kaliasin. Namun, ketika pohon-pohon waru yang
ditanam oleh warga mulai tumbuh besar dan sudah lumayan terasa
manfaatnya, justru harus ditebang akibat pembangunan kolam
retensi yang dilakukan pemerintah. Masyarakat sekitar tidak
berdaya menggugat pemerintah. Mereka cukup tahu bahwa menggugat
pemerintah tidak ada gunanya, karena pembangunan kolam retensi
dan penanaman pancang merupakan proyek pemerintah.
“waktu itu sebelum ada proyek peninggian tanggul-tanggul banjir ini, kita
tanam pohon-pohon yang banyak di sepanjang pinggir kali, paling nggak
ya untuk mengurangi dampak asap ini kan. Saya nanam pohon itu
jaraknya dekat-dekat, sekitar hanya lima meter itu. Ya walaupun hanya
pohon waru, tapi kalau sudah besar kan lumayan, antara daun dengan
daun sudah bisa bertemu. Tapi setelah adanya proyek peninggian tanggul
dan pembuatan kolam arteri, otomatis pohon-pohon yang kita tanam tadi
harus ditebang semua, mbak… Kita yang terkena dampak sampai
sekarang belum dapat ganti rugi. Kita nanam ini (maksudnya pohon waru
tadi) memang seharusnya dapat uang ganti rugi mbak, tapi ya sudah
nggak ada manfaatnya lagi. Waktu ada pohonnya sudah lumayan bisa
nyaring asap dari pabrik itu. Saya terus berhubungan dengan HK-nya,
karena saya kan yang dipercaya warga sebagai wakil dari mereka.”
“gini mbak ya, ini kan proyek pemerintah ya mbak, jadi kalau kita ngotot
pun tetap artinya kita salah. Pemerintah kan modelnya sekarang kalau
sudah nggak bisa diatasi langsung naik ke pengadilan. Kalau saya lihat,
kalau sudah kontingensi itu kita sudah nggak bisa apa-apa. Ditawari ganti
rugi kalau nggak selesai, nggak deal, pemerintah langsung masuk ke
pengadilan, kontingensi. Kalau kontingensi, mau nggak mau ya kita
dapatnya yang dipengadilan itu dapat berapa. Beda dengan kalau bukan
proyek pemerintah, kita bisa ngotot mintanya berapa, kayak
pembangunan apartemen atau hotel, kan kita bisa minta sesuka hati kita.
Kalau pemerintah, kita gak bisa. Kalau kita ngotot pun akhirnya ya kita
tetap kalah. Sebenarnya ya kita sempat eman-eman ya mbak, sudah
nanam pohon begitu. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, proyek ini kita juga
yang bakal menikmati fasilitasnya. Mungkin juga perumahan disini bisa
keliatan bersih, bagus gitu ya mbak.”
Meskipun hingga kini warga RT delapan, sembilan dan
sepuluh kelurahan Kuningan masih merasa sangat terganggu dengan
limbah asap dari industri pengasapan ikan yang berada
diseberang rumahnya, namun warga lebih memilih diam. Mereka
sudah malas heboh-heboh mengadukan permasalahan yang sama
seperti tahun-tahun lalu, karena mereka merasa mereka yang
menjadi korban tetapi justru industri lah yang mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Sebenarnya tidak masalah jika memang
cara itu yang terbaik, cuma mereka mengesalkan mengapa ada
oknum-oknum tertentu yang tidak melaksanakan amanat dari
pemerintah untuk meninggikan cerobong asapnya. Pernah ada
rombongan dari dinas kesehatan Kota semarang datang ke
kelurahan mereka untuk memeriksa penyakit anak-anak di kawasan
tersebut, itu pun karena ketua RT dari tiga RT setempat
mengadukan permasalahan kesehatan di tempat mereka. Ternyata
setelah diperiksakan, anak-anak di kawasan sekitar industri
mengidap penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan aku
akibat terlalu sering diterpa limbah asap. Saat itu memang ada
pengobatan gratis, namun hanya satu kali itu. Program
pemerintah tidak benar-benar serius dalam menangani
permasalahan yang ada di dalam masyarakatnya. Tak heran jika
ada proyek-proyek yang gagal akibat tidak adanya keberlanjutan
dalam menjalankan program pemerintah sebelumnya.
Faktor lain yang memaksa mereka untuk memaklumi keadaan
adalah karena angin yang bertiup membawa serta asap limbah
industri. Puncak operasi industri pengasapan ikan terjadi pada
pukul sebelas siang hingga pukul empat sore. Saat itu seluruh
rumah industri sedang aktif, sehingga hampir setiap cerobong
asap mengeluarkan limbah asapnya ke udara.
Menurut Pak Utomo, narasumber penulis yang menjabat
sebagai wakil ketua RT sepuluh, konflik yang terjadi hanya
sebatas itu saja. Tidak sampai mengganggu hubungan sosial dalam
masyarakat. Meskipun tempat tinggal mereka dibatasi oleh
sungai, mereka masih tetap berkomunikasi dengan baik.
Masyarakat kedua belah pihak cenderung saling memahami dan mau
mengalah demi adanya integrasi sosial. Kalau soal asap,
masyarakat kelurahan Kuningan hanya sebatas bicara sambil
bercanda, “eh… asapmu itu loh, bikin bajuku bau asap”, tetapi
tidak ada permusuhan diantara keduanya.
Sudah menjadi rahasia umum, sentra industri pengasapan
ikan yang pada awalnya dibangun oleh pemerintah di kelurahan
Bandarharjo ini merupakan proyek pemerintah yang gagal (failed
project) diantara proyek-proyek pemerintah yang terdapat di
daerah Tambak Lorok dan Tawang Terasi. Itu pun TPI (Tempat
Pelelangan Ikan) yang terdapat di Tambak Lorok sudah tidak
berfungsi lagi.
Jadi masyarakat yang berada di seberang kawasan industri
pengasapan ikan sudah terbiasa dengan asap yang menerpa mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perikanan. 1995. Teknik Pengolahan Hasil Perikanan
Masithoh. 2008. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA SENTRA INDUSTRI RUMAH
TANGGA PENGASAPAN IKAN BANDARHARJO KOTA SEMARANG. Tesis Program
Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Semarang
Undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
UU Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984