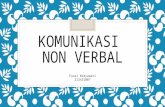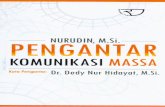komunikasi lintas budaya
-
Upload
universitasnegeripadang -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of komunikasi lintas budaya
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
“ Komunikasi Lintas Budaya”
Oleh:
Winda Dwi Gusti/ 1201590
Sesi:
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang
heterogen dalam berbagai aspek seperti keberagaman
suku, agama, bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
Sementara itu, perkembangan dunia yang semakin pesat
menuntut manusia harus berinteraksi dengan pihak
lain yang menuju kearah global, sehingga tidak
memiliki lagi batas-batas, sebagai akibat dari
perkembangan teknologi.
Oleh karena itu, masyarakat harus siap untuk
menghadapi situasi-situasi baru dengan keberagaman
kebudayaan atau lainnya. Antara komunikasi dan
interaksi harus berjalan antara satu dengan yang
lainnya.
Dalam berkomunikasi dengan konteks keberagaman
kebudayaan sering kali menemui masalah atau
hambatan-hambatan bahkan dapat memicu terjadnya
konflik, misalnya saja dalam penggunaan bahasa,
lambang-lambang, nilai atau norma-norma masyarakat
dan lain sebagainya. Pada hal syarat untuk
terjalinya hubungan itu tentu saja harus ada saling
pengertian dan pertukaran informasi atau makna
antara satu dengan lainnya.
Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal
balik. Budaya menjadi bagian dari prilaku komunikasi
dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan
memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.
Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme
untuk mensosialisasikan norma-norma budaya
masyarakat, baik secara horizontal dari suatu
masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara
vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau
nilai-nilai yang dianggap sesuai untuk kelompok
tertentu.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas maka dapat
dirumuskan masalah, sebagai berikut:
1. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi?
2. Apakah yang dmaksud dengan budaya?
3. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi lintas
budaya?
4. Aspek apa saja yang mempengaruhi komunikasi
lintas budaya?
5. Bagaimana bentuk komunikasi lintas budaya di
indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah
untuk mengetahui tentang komunikasi lintas budaya
diindonesia dan pengaplikasiannya dalam kehidupan
sehari-hari serta untuk pemenuhan tugas mata kuliah
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Komunikasi
1. Pengertian Komunikasi
Secara etimologis atau menurut asal katanya,
istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin
communication dan perkataan ini bersumber pada kata
communis. Arti communis disini adalah sama, dalam
arti kata sama makna, yaitu sama makna menganai satu
hal
Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang
menguntungkan pengirim maupun penerima,
menguntungkan dalam artian sama-sama berbagi makna
dan memahami makna secara bersama sehingga melakukan
proses selanjutnya juga bersama dalam kesamaan makna
atau dengan kata lain komunikasi efektif
Menurut Leeuwis (dalam Satriani dan Muljono,
2005:90) komunikasi merupakan sebuah proses penting
yang digunakan oleh manusia dalam pertukaran
pengalaman dan ide, dan hal itu menjadi pemicu
penting bagi penyampaian pengetahuan dan persepsi
dari berbagai jenis (misalkan pembelajaran). Oleh
karena itu, komunikasi merupakan unsur inti dalam
perubahan strategi untuk mendorong perubahan.
sedangkan menurut Soekartawi (1988) komunikasi
adalah suatu pernyataan manusia, baik secara
perorangan maupun berkelompok, yang bersifat umum
dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti,
maka tampak bahwa dengan perkembangan objek tertentu
akan memerlukan komunikasi yang lebih spesifik.
Misalnya, komunikasi pembangunan, komunikasi
politik, komunikasi antar budaya, dan sebagainya.
Lain halnya dengan Ahmad Sihabudin (2011:28)
menyatakan bahwa bentuk paling nyata dalam
komunikasi adalah bahasa. Secara sederhana bahasa
dapat diartikan sebagai suatu system lambang yang
teroganisasi, disepakati secara umum, dan merupakan
hasil belajar, yang digunakan untuk menyajikan
penglaman-pengalaman dalam suatu komunitas geografis
atau budaya. Bahasa merupakan alat utama yang
digunakan budaya untuk menyalurkan kepercayaan,
nilai dan norma. Bahasa merupakan alat bagi orang-
orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga
sebagai alat untuk berpikir.
Dalam berkomunikasi diharapkan seseorang dapat
menerima pesan yang disampaikan oleh sipemberi
informasi. Edy Sudaryanto (1997:9) mengungkapkan ada
beberapa tugas pokok komunikasi dalam suatu
perubahan sosial dalam rangka pembangunan yaitu:
a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang
pentingnya perubahan.
b. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk
mengambil bagian secara aktif
c. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan dalam
pembangun.
Dalam proses komunikasi terdapat beberapa elemen
yaitu source, message, channel, reciver, dan effect.
Bagi source sebelum menyempaikan pesan terlebih
dahulu menyendi (incode) message (pesan) ke dalam
suatu pengertian. Dalam hal ini penentu kebijakan
(komunikator) dalam menyampaikan arahannya harus
dapat mempertimbangkan kondisi penerima kebijakan.
Dengan demikian diharapkan materi-materi arahannya
disesuaikan dengan tingkat akal pengetahuan
sipenerima kebijakan (komunikan) agar lebih mudah
dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Di
samping itu juga penerima kebijakan menyandi kembali
terhadap materi-materi yang disampaikan oleh penentu
kebijakan. Dengan demikian akan terjadi efek atau
umpan balik yang diinginkan oleh pemerintah.
Selain itu, Everest M. Rogers (dalam Mulyana,
2001:62) mengatakan bahwa komunikasi merupakan
proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada
suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk
mengubah tingkah laku mereka.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi
merupakan proses penyampaian suatu informasi kepada
penerima pesan sehingga penerima pesan dapat
mengerti maksud dari pengirim pesan.
2. Tujuan Komunikasi
Adapun beberapa tujuan sari komunikasi menurut
Levis ( dalam Satriani dan Muljono, 2005:90) antara
lain:
a. Informasi untuk memberikan informasi yang
menggunakan pendekatan dan pemikiran
b. Persuasif untuk menggugah perasaan penerima
c. Mengubah perilaku (sikap, pengetahuan dan
keterampilan) perubahan sikap terhadap pelaku
pembangunan
d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usaha
secara efisien dibidang usaha yang dapat meberi
manfaat dalam batas waktu yang tidak tertentu
e. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan.
Dengan informasi yang dihasilkan oleh adanya
komunikasi berguna untuk memberikan dan memperoleh
pengetahuan serta wawasan global dalam perubahan
lingkungan sosial, budaya serta perkembangan
kehidupan manusia kearah yang lebih baik atau menuju
kemajuan dan kemudahan serta dapat memberikan
manfaat yang menyeluruh bagi masyarakat baik dari
kalangan rendah maupun kalangan tinggi.
3. Unsur-unsur Komunikasi
adapun unsur-unsur dari komunikasi antara lain:
a. Sumber
Merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk
berkomunikasi, yakni keinginan untuk membagi
keadaan internal sendiri, baik yang bersifat
emosional maupun informasional dengan orng lain.
Kebutuhan ini bisa berupa keinginan untuk
memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan
untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang
lain.
b. Meng-encode
Karena keadaan internal tidak bisa dibagi bersama
secara langsung, maka diperlukan simbol-simbol
yang mewakili. Encoding adalah suatu aktifvitas
internal pada sumber dalam menciptakan pesan
melalui pemilihan pada simbol-simbol verbal dan
non verbal, yang disusun berdasarkan aturanaturan
tata bahasa dan sintaksis yang berlaku pada bahasa
yang digunakan.
c. Pesan
Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat
simbol-simbol verbal atau non verbal yang mewakili
keadaan khusus sumber pada satu dan tempat
tertentu
d. Saluran
Merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari
sumber ke penerima atau yang menghubungkan orang
ke orang lain secara umum.
e. Penerima
Adalah orang -orang yang menerima pesan dan dengan
demikian terhubungkan dengan sumber pesan.
Penerima bisa orang yang dimaksud oleh sumber atau
orang lain yang kebetulan mendapatkan kontak juga
dengan pesan yang dilepaskan oleh sumber dan
memasuki saluran
f. Men-decode
Decoding merupakan kegiatan internal dari
penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan
macam-macam data dalam bentuk “mentah”, yang harus
diubah kedalam pengalaman-pengalaman yang
mengandung makna.
g. Respon penerima
Yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima
untuk dilakukan terhadap pesan.Respons dapat
bervariasi sepanjang dimensi minimum sampai
maksimum.
h. Balikan (Feedback)
Merupakan informasi bagi sumber sehingga ia dapat
menilai efektifitas komunikasi untuk selanjutnya
menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.
i. Gangguan (Noise)
Gangguan beraneka ragam, untuk itu harus
didefinisikan dan dianalisis. Noise dapat masuk
kedalam sistem komunikasi manapun yang merupakan
apa saja yang mengganggu atau membuat kacau
penyampaian pesan, termasuk yang bersifat fisik
atau phisikis
j. Bidang pengalaman
Komunikasi dapat terjadi sejauh para pelaku
memiliki pengalamanpengalaman yangsama. Perbedaan
dapat mengakibatkan komunikasi menjadi sulit,
tetapi walaupun perbedaan tidak dapat dihilangkan
bukan berarti komunikasi tidak ada harapan untuk
terjadi
k. Konteks komunikasi
Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks
tertentu paling tidak ada tiga dimensi:
Dimensi fisik
Merupakan lingkungan konkrit dan nyata tempat
terjadinya komunikasi, seperti ruangan,
halaman dan jalanan.
Dimensi sosial
Misalnya adat istiadat, situasi rumah dll
Dimensi norma
Misalnya mencakup kesemua kehidupaan
masyarakat.
4. Tipe Kominikasi
Tipe komunikasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu
komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Komunikasi verbal
Menurut Fajar (2009:109-110) komunikasi verbal
merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata
secara lisan dengan secara sadar dilakukan oleh
manusia untuk berhubungandengan manusia lain.
Dasar komunikasi verbal adalah interkasi antara
manusia. Dan menjadi salah satu cara bagi manusia
berkomunikasi secara lisan atau bertatapan dengan
manusia lain, sebagai sarana utama menyatukan
pikiran, perasaan dan maksud.
b. Komunikasi Nonverbal
Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter
(2010), komunikasi nonverbal mencakup semua
rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu
setting komunikasi oleh individu dan penggunaan
lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai
pesan potensial bagi pengirim atau penerima.
Adapun bentuk-bentuk komunikasi nonverbal antara
lain:
1) Kinesics
Suatu nama teknis bagi studi mengenai
gerakan tubuh digunakan dalam komunikasi.
Gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi
wajah, gerak-isyarat, postur atau perawakan,
dan sentuhan.
2) Paralanguage
Paralanguage atau vocalics adalah “suara”
nonverbal apa yang kita dengar bagaimana
sesuatu dikatakan. Ada empat karakteristik
vokal yang meliputi paralanguage dan kemudian
membicarakan bagaimana kesimpulan-kesimpulan
vokal dapat mengganggu arus pesan.
3) Gangguan-gangguan vokal
Dalam budaya Indonesia gangguan dalam pidato
atau berbicara seperti “ehm”, “aaa”, “eee”,
“baik”
4) Penggunaan ruang
Menggunakan ruang yang dimiliki dengan
caramenggunakan objek dan mendekorasi ruang
tersebut
Bentuk komunikasi
Komunikasi
verbal
Komunikasi
vokal
Komunikasi
nonvokal
Bahasa lisan Bahasa tertulis
Komunikasi
nonverbal
Nada suara,
desah, jeritan,
kualitas vokal
Isyarat,
gerakan,
penampilan,
ekspresi wajah
Sementara itu, menurut Lihapsari (1997:3) teknik-
teknik dalam berkomunikasi antara lain:
a. Teknik komunikasi informatif
Teknik Komunikasi Informatif adalah suatu
ketrampilan berkomunikasi dengan menyampaikan
berbagai tanda informasi baik yang bersifat
verbal, non-verbal maupun paralinguistik.
Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang
perubahan sosial, agar masyarakat dapat:
memusatkan perhatian akan kebutuhan perubahan,
cara mengadakan perubahan, dan dapat menyiapkan
sarana-sarana perubahan. Melalui informasi
masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengambil
bagian secara aktif dan memperoleh pengetahuanyang
diperlukan dalam menghadapi perubahan. Tanpa
informasi sangatlah sulit untuk dapat mengakses
secara cepat dan tepat segala sesuatu yang
bermanfaat dari adanya perubahan sosial.
b. Teknik komunikasi persuasif
Teknik komunikasi persuasif adalah cara
menyampaikan pesan pada orang lain dengan
memperhatikan aspek psikologis, cara ini
menadasrakan pada kesadaran pribadi dan menjauhi
adanya paksaan. Menyampaikan pesan seperti ini
merupakan hal yang mendasarkan pada kesesuaian
kondisi atau latar belakang yang dihadapi. Yang
penting untuk dipahami bahwa komunikasi persuasif
yang dilakukan memperoleh hasil yang diinginkan
sesuai dengan pengalaman yang ada. Komunikasi
persuasif akan terjadi umpan balik tanya jawab
mengenai persoalan perubahan sosial. Dengan
demikian masyarakat akan memperoleh gambaran yang
utuh atau menyeluruh mengenai arti pentingnya
perubahan sosial dalam kehidupan manusia.
c. Teknik komunikasi pervasif
Teknik komunikasi pervasive adalah cara
menyampaikan pesan pada orang lain dengan
berulang-ulang, sehingga sedikit demi sedikit akan
merember pada bawh sadar yang pada akhirnya akan
membentuk sikap dan kepribadiannya. Melalui teknik
ini seseorang akan memperoleh pemahaman tentang
perubahan sosial dimaknakan sebagai pemahaman yang
akurat, karena diinformasikannya secara berulng-
ulang.
d. Teknik komunikasi koersif
Teknik komunikasi koersif adalah teknik komunikasi
yang berlawanan dengan teknik komunikasi peruasif
yaitu penyampaikan pesan komunikasi pada orang
lain dengan cara memaksa orang untuk berbuat
sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan rasa
tunduk serta patuh. Dengan cara ini manusia
dipaksa untuk siapsiap menerima adanya perubahan
yang membawa efek positif dan negatif. Seiring itu
masyarakat dipaksa untuk memeaham dan
mempersiapkan diri dengan beka ilmu pengetahuan
sehingga perubahan social tetap membawa perubahan
yang baik bagi kehidupan umat manusia.
e. Teknik komunikasi instruktif
Teknik komunikasi instruktif adalah penyampaian
pesan komunikasi dikemas sedemikian rupa sehingga
pesan itu dipahami sebagai perintah yang harus
dilaksanakan. Teknik ini agar dilaksanakan oleh
audien terlebih dahulu dikondisikan agar segala
sesuatu itu diperlukan. Komunikasi jenis ini
diterapkan karena sifatnya sseegera mungkin harus
dilaksanakan dan manakala tidak segera dilakukan
akan membawa efek buruk bagi kehidupan. Manakala
manusia ingin mengalami kejauan maka dengan segera
mengikuti dan mentaati adanya perubahan social
pembangunan
f. Teknik hubungan manusiawi
Yang dimaksud dengan teknik komunikasi hubungan
manusiawi adalah kemasan informasi yang
disampaikan dengan mendasarkan aspek psikologis
secara tatap muka utnuk merubah sikap dan perilaku
dan kehidupan sehingga menimbulkan rasa kepuasan
kepada berbagai pihak. Jenis teknik ini bila
dikaitkan dengan perubahan sosial tertama
melakukan pendekatan para tokoh sehingga
menimbulkan pemaman yang mendukung pada adanya
perubahan tersebut. Kemudian diharapkan para tokoh
itu dapat mensosialisasikan pada orang lain atau
para pengikutny dengan caranya sendiri.
B. Budaya
1. Pengertian Budaya
Kata “budaya” berasal dari bahasa sansekerta
buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata
buddhi, yang berarti “budi” atau “kaal”. Kebudayaan
itu sendiri diartikan sebagai “ hal-hal yang
berkaitan dengan budi atau akal”.
Istilah culture, yang merupakan istilah bahasa asing
yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari
kata “colere” yang artinya adalah “mengolah atau
mengerjakan”, yaitu dimaksudkan kepada keahlian
mengolah dan mengerjakan tanah atau bertani. Kata
colere yang kemudian berubah menjadi ulture diartikan
sebagai “segala daya dan kegiatan manusia untuk
mengolah dan mengubah alam”.
Seorang Antropolog yang bernama E.B. Taylor
(1871), memberikan defenisi mengenai kebudayaan
yaitu “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum,
adat istiada, lain kemampuankemampuan dan kebiasaan-
kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai
anggota masyarakat”.
Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen,
menurut ahli antropologi (dalam Mulyana dan
Jalaluddin Rakhmat, 2005) yaitu:
a. Kebudayaan material
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan
masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam
kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang
dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi:
mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan
seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup
barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang,
stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit,
dan mesin cuci.
b. Kebudayaan nonmaterial
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan
abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi,
misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu
atau tarian tradisional.
c. Lembaga sosial
Lembaga social dan pendidikan memberikan peran
yang banyak dalam kontek berhubungan dan
berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem social
yang terbantuk dalam suatu Negara akan menjadi
dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan social
masyarakat.
d. Sistem kepercayaan
Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun
system kepercayaan atau keyakinan terhadap
sesuatu, hal ini akan mempengaruhi system
penilaian yang ada dalam masyarakat. Sistem
keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan,
bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara
mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana
berkomunikasi.
e. Estetika
Berhubungan dengan seni dan kesenian, music,
cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari–tarian,
yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
Seperti di Indonesia setiap masyarakatnya memiliki
nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu
dipahami dalam segala peran, agar pesan yang akan
kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif.
disetiap daerah berbeda.
f. Bahasa
Bahasa merupakan alat pengatar dalam
berkomunikasi, bahasa untuk setiap walayah, bagian
dan Negara memiliki perbedaan yang sangat komplek.
Dalam ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen
komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki
sifat unik dan kompleks, yang hanya dapat
dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi
keunikan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami
agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan
memperoleh nilai empati dan simpati dari orang
lain.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan
adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat
pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan
yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam
kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat
abstrak.
2. Tujuan Mempelajari Budaya
Adapun tujuan mempelajari budaya antara lain:
a. Menyadari bias budaya sendiri
b. Lebih peka secara budaya
c. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat
dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan
hubungan yang langgeng dan memuaskan orang
tersebut.
d. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya
sendiri
e. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang
f. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat
seseorang mampu menerima gaya dan isi
komunikasinya sendiri.
g. Membantu memahami budaya sebagai hal yang
menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan
makna bagi para anggotanya
h. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai
suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya
sendiri: asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-
kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.
i. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan
aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya.
j. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang
berbeda dapat dipelajari secara sistematis,
dibandingkan, dan dipahami.
3. Cakupan kebudayaan
Dalam praktik komunikasi lintas budaya, peran
pemahaman berbudaya tidak dapat dilepaskan. Budaya
mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:
a. Istilah budaya merujuk pada keragaman pool of
knowledge, realitas-realitas yanng dipertukarkan,
dan norma-norma yang dikelompokkan yang membentuk
sistem sistem makna yang dipelajari dalam
masyarakat Partikular
b. sistem-sistem makna yang dipelajari tersebut
dipertukarkan dan ditransmisikan melalui interaksi
sehari-hari di antara para anggota kelompok budaya
dan dari satu generasi ke generasi berikutnya
c. budaya memfasilitasi kapasitas para anggota untuk
bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan
eksternal lainnya
4. Dimensi Ragam Budaya
Telah dikenal ribuan anekdot mengenai
kesalahpahaman akibat komunikasi antarbudaya antara
orang-orang dari budaya yang berbeda-beda. Karena
besarnya jumlah pasangan budaya, dan karena
kemungkinan kesalahpahaman berdasarkan bentuk verbal
maupun perilaku nonverbal antara tiap pasangan
budaya sama besarnya, maka terdapat banyak anekdot
mengenai hal-hal tentang antarbudaya yang mungkin
dibuat. Yang diperlukan adalah cara untuk mengatur
dan memahami banyaknya masalah yang mungkin timbul
dalam komunikasi antarbudaya. Sebagian besar
perbedaan dalam komunikasi antarbudaya merupakan
hasil dari keragaman dalam dimensi-dimensi berikut
ini:
a. Keakraban dan Kebebasan Mengungkapkan Perasaan
Tindakan keakraban merupakan tindakan yang secara
simultan mengungkapkan kehangatan, kedekatan, dan
kesiapan untuk berkomunikasi. Tindakan-tindakan itu
lebih menandai pendekatan daripada penghindaran dan
kedekatan daripada jarak. Contoh tindakan keakraban
misalnya senyuman, sentuhan, kontak mata, jarak yang
dekat, dan animasi suara. Budaya yang menunjukkan
kedekatan atau spontanitas antarpersonal yang besar
dinamakan “budaya kontak” karena orang-orang dalam
negara-negara ini biasa berdiri berdekatan dan
sering bersentuhan. Orang-orang dalam budaya kontak
yang rendah cenderung berdiri berjauhan dan jarang
bersentuhan.
Sangat menarik bahwa budaya kontak tinggi biasanya
terdapat di negara-negara hangat dan budaya kontak
rendah terdapat di negara-negara beriklim sejuk.
Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa yang
termasuk mempunyai budaya kontak adalah negara-
negara Arab, Perancis, Yunani, Itali, Eropa Timur,
Rusia, dan Indonesia. Negara-negara dengan budaya
kontak rendah misalnya Jerman, Inggris, Jepang, dan
Korea (Samovar, Larry A., Richard E. Porter and Lisa
A. Stefani, 1998). Jelas bahwa budaya di iklim
dingin cenderung berorientasi hubungan
antarpersonalnya ‘dingin’, sedangkan budaya di iklim
hangat cenderung berorientasi antarpersonal dan
‘hangat’. Bahkan, orang-orang di daerah hangat
cenderung menunjukkan kontak fisik lebih banyak
daripada orang-orang yang tinggal di daerah dingin.
b. Individualisme dan Kolektivisme
Salah satu dimensi paling fundamental yang
membedakan budaya adalah tingkat individualisme dan
kolektivisme. Dimensi ini menentukan bagaimana orang
hidup bersama, dan nilai-nilai mereka, dan bagaimana
mereka berkomunikasi. Kajiannya tentang
individualisme dalam lima puluh tiga negara, negara
yang paling individualistik secara berurutan adalah
Amerika, Australia, Inggris, Kanada, dan Belanda
yang semuanya negara Barat atau Eropa. Negara yang
paling rendah tingkat individualismenya adalah
Venezuela, Kolombia, Pakistan, Peru, dan Taiwan yang
semuanya budaya Timur atau Amerika Selatan. Korea
berurutan ke-43 dan Indonesia berurutan ke-47. Ting-
kat yang menentukan suatu budaya itu individualistik
atau kolektivistik mempunyai dampak pada perilaku
nonverbal budaya tersebut dalam berbagai cara.
Orang-orang dari budaya individualistik relatif ku-
rang bersahabat dan membentuk jarak yang jauh dengan
orang lain. Budaya-budaya kolektivistik saling
tergantung, dan akibatnya mereka bekerja, bermain,
tidur, dan tinggal berdekatan dalam keluarga besar
atau suku. Masyarakat industri perkotaan kembali ke
norma individualisme, keluarga inti, dan kurang
dekat dengan tetangga, teman, dan rekan kerja mereka
(Hofstede, Geert, 1980).
Orang-orang dalam budaya individualistik juga
lebih sering tersenyum daripada orang-orang dalam
budaya yang cenderung ketimuran. Keadaan ini mungkin
dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa para
individualis bertanggungjawab atas hubungan mereka
dengan orang lain dan kebahagiaan mereka sendiri,
sedangkan orang-orang yang berorientasi kolektif
menganggap kepatuhan pada norma-norma sebagai nilai
utama dan kebahagiaan pribadi atau antarpersonal
sebagai nilai kedua. Secara serupa, orang-orang
dalam budaya kolektif dapat menekan penunjukan emosi
baik yang positif maupun yang negatif yang
bertentangan dengan keadaan dalam kelompok karena
menjaga keutuhan kelompok merupakan nilai utama.
Orang-orang dalam budaya individualistik didorong
untuk mengungkapkan emosi karena kebebasan pribadi
dihargai paling tinggi. Penelitian mengenai hal
tersebut mengungkapkan bahwa orang-orang dalam
budaya individualistik lebih akrab secara nonverbal
daripada orang-orang dalam budaya kolektif.
c. Feminin dan Maskulin
Maskulinitas adalah dimensi budaya yang sering
terlupakan. Ciri-ciri khas maskulin biasanya
disangkutpautkan dengan kekuatan, ketegasan,
persaingan, dan ambisi, sedangkan ciri-ciri khas
feminin dihubungkan dengan kasih sayang, pengasuhan,
dan emosi. Penelitian antarbudaya menunjukkan bahwa
anak perempuan diharapkan lebih dapat mengasuh
daripada anak laki-laki walaupun ada variasi yang
cukup banyak dari negara yang satu dengan yang lain
(Hall, Edward T., 1976).
Budaya maskulin menganggap penting kompetisi dan
ketegasan, sedangkan budaya feminin lebih
mementingkan pengasuhan dan perasaan. Tidak heran,
maskulinitas suatu budaya dihubungkan secara negatif
dengan persentase wanita dalam pekerjaan teknis dan
profesional serta dihubungkan secara positif dengan
pemisahan kedua jenis kelamin dalam pendidikan
tinggi. Negara dengan maskulinitas tertinggi adalah
Jepang, Austria, Venezuela, Itali, dan Swiss.
Kecuali Jepang, negara-negara ini semuanya terletak
di Eropa Tengah dan Karibia. Negara dengan nilai
maskulinitas terendah adalah Swedia, Norwegia,
Belanda, Denmark, dan Finlandia yang semuanya negara
Skandinavia atau Amerika Selatan kecuali Thailand.
Indonesia ditempatkan di urutan ke-30 dan Korea di
urutan ke-41.
d. Kesenjangan Kekuasaan
Dimensi fundamental keempat dalam komunikasi
antarbudaya adalah kesenjangan kekuasaan.
Kesenjangan kekuasaan telah diukur dalam banyak
budaya menggunakan Indeks Kesenjangan Kekuasaan
(IKK). Budaya dengan nilai IKK tinggi mempunyai
kekuasaan dan pengaruh yang lebih terpusat dalam
tangan sedikit orang daripada terbagi dengan cukup
merata di seluruh penduduk. IKK sangat berkaitan
dengan otoritarianisme. Negara dengan IKK tertinggi
adalah Filipina, Meksiko, Venezuela, India, dan
Singapura. Negara-negara tersebut semuanya negara-
negara Asia Selatan atau Karibia, kecuali Perancis.
Negara dengan IKK terendah (mulai dari yang paling
rendah) adalah Austria, Israel, Denmark, Selandia
Baru, dan Irlandia. Dalam hal ini, Indonesia
terletak di tingkat ke-8 yang sangat tinggi dan
Korea berurutan ke-27. Sistem sosial dengan
perbedaan kekuasaan juga menghasilkan perilaku
kinesik yang berbeda. Dalam keadaan beda kekuasaan,
bawahan sering tersenyum dalam usaha untuk tampak
sopan dan menenangkan atasan. Hofstede (1980)
menyatakan bahwa garis lintang dan iklim merupakan
kekuatan utama dalam membentuk budaya. Dia
menekankan bahwa kunci yang mempengaruhi variabel
yaitu bahwa teknologi diperlukan bagi pertahanan
hidup di iklim yang lebih dingin. Kebutuhan ini
menimbulkan rangkaian kejadian di mana anak-anak
tidak terlalu tergantung pada penguasa dan lebih ba-
nyak belajar dari orang lain daripada tokoh-tokoh
penguasa.
Kebudayaan yang sangat menjunjung tinggi
kesenjangan kekuatan besar selalu menekankan nilai
ketidakseimbangan atas status-status individu (Alo
Liliweri, 2001). Senyum yang terus menerus yang
dilakukan orang-orang Timur mungkin merupakan usaha
untuk menenangkan atasan atau menghasilkan hubungan
sosial yang lebih mulus mungkin berhasil dinaikkan
jabatannya dalam budaya ber-IKK tinggi.
e. Konteks Tinggi dan Rendah
Dimensi penting terakhir dari komunikasi
antarbudaya adalah konteks. Hall (1976:91)
menggambarkan budaya konteks tinggi dan rendah yang
cukup mendetil. Komunikasi atau pesan konteks tinggi
(KT) adalah suatu komunikasi di mana sebagian besar
informasinya dalam konteks fisik atau ditanamkan
dalam seseorang, sedangkan sangat sedikit informasi
dalam bagian-bagian pesan yang “diatur, eksplisit,
dan disampaikan”. Teman yang sudah lama saling kenal
sering menggunakan KT atau pesan-pesan implisit yang
hampir tidak mungkin untuk dimengerti oleh orang
luar. Situasi, senyuman, atau lirikan memberikan
arti implisit yang tidak perlu diucapkan. Dalam
situasi atau budaya KT, informasi merupakan gabungan
dari lingkungan, konteks, situasi, dan dari petunjuk
nonverbal yang memberikan arti pada pesan itu yang
tidak bisa didapatkan dalam ucapan verbal eksplisit.
Pesan konteks rendah (KR) hanyalah merupakan
kebalikan dari pesan KT, sebagian besar informasi
disampaikan dalam bentuk kode eksplisit. Pesan-pesan
KR harus diatur, dikomunikasikan dengan jelas, dan
sangat spesifik. Tidak seperti hubungan pribadi,
yang relatif termasuk sistem pesan KT, institusi
seperti pengadilan dan sistem formal seperti
matematika atau bahasa komputer menuntut sistem KR
yang eksplisit karena tidak ada yang bisa diterima
begitu saja.
Budaya konteks yang ditemukan di Timur, Cina,
Jepang, dan Korea merupakan budaya-budaya berkonteks
sangat tinggi. Bahasa merupakan sebagian dari sistem
komunikasi yang paling eksplisit, namun bahasa Cina
merupakan sistem konteks tinggi yang implisit.
Orang-orang dari Amerika sering mengeluh bahwa orang
Jepang tidak pernah bicara langsung ke pokok
permasalahan, mereka gagal dalam memahami bahwa
budaya KT harus memberikan konteks dan latar dan
membiarkan pokok masalah itu berkembang (Hall,
Edward T., 1984).
Komunikasi jelas sangat berbeda dalam budaya KT
dan KR. Pertama, bentuk komunikasi eksplisit seperti
kode-kode verbal lebih tampak dalam budaya KR
seperti Amerika dan Eropa Utara. Orang-orang dari
budaya KR sering dianggap terlalu cerewet,
mengulang-ulang hal yang sudah jelas, dan berlebih-
lebihan. Orang-orang dari budaya KT mungkin dianggap
tidak terus terang, tidak terbuka, dan misterius.
Kedua, budaya KT tidak menghargai komunikasi verbal
seperti budaya KR. Orang-orang yang lebih banyak
bicara dianggap lebih menarik oleh orang Amerika,
tetapi orang yang kurang banyak bicara dianggap
lebih menarik di Korea seperti suatu budaya
berkonteks tinggi. Ketiga, budaya KT lebih banyak
menggunakan komunikasi nonverbal dari pada budaya-
budaya KR. Budaya KR, dan khususnya kaum pria dalam
budaya KR, tidak dapat merasakan komunikasi
nonverbal sebaik anggota budaya KT. Komunikasi
nonverbal memberikan konteks untuk semua komunikasi,
tetapi orang-orang dari budaya KT sangat dipengaruhi
isyarat-isyarat kontekstual. Dengan demikian,
ekspresi wajah, ketegangan, tindakan, kecepatan
interaksi, tempat interaksi, dan pernak-pernik
perilaku nonverbal lainnya dapat dirasakan dan
mempunyai lebih banyak makna bagi orang-orang dari
budaya konteks tinggi. Terakhir, orang-orang dari
budaya KT mengharapkan lebih banyak komunikasi
nonverbal dibandingkan pelaku interaksi dari budaya
KR. Orang-orang dari budaya KT mengharapkan para
komunikator untuk memahami perasaan yang tidak
diungkapkan, isyarat-isyarat yang halus, dan
isyarat-isyarat lingkungan yang tidak dihiraukan
oleh orang-orang dari budaya KR.
C. Komunikasi Lintas Budaya
1. Pengertian komunikasi Lintas Budaya
Berbicara mengenai komunikasi antar budaya, maka kita
harus melihat dulu beberapa defenisi yang dikutip oleh
Ilya Sunarwinadi (1993:7-8) berdasarkan pendapat para
ahli antara lain :
a. Sitaram (1970)
Seni untuk memahami dan saling pengertian antara
khalayak yang berbeda kebudayaan.
b. Samovar dan Poter (1972)
Komunikasi antar budaya terjadi manakalah bagian
yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut
membawa serta latar belakang budaya pengalaman
yang berbeda yang mencerminkan nilai yang dianut
oleh kelompoknya berupa pengalaman, pengetahuan,
dan nilai.
c. Rich (1974)
Komunikasi lintas budaya terjadi ketika orang-
orang berbeda kebudayaan.
d. Stewart(1974)
Komunikasi antara budaya yang mana terjadi dibawah
suatu kondisi kebudayaan yang berbeda bahasa,
norma-norma, adat istiada dan kebiasaan
e. Carley H. Dood (1982)
Komunikasi antar budaya adalah pengiriman dan
penerimaan pesan-pesan dalam konteks perbedaan
kebudayaan yang menghasilkan efek-efek yang
berbeda.
f. Young Yun Kim (1984)
Komunikasi antar budaya adalah suatu peristiwa
yang merujuk dimana orang – orang yang terlibat di
dalamnya baik secara langsung maupun tak tidak
langsung memiliki latar belakang budaya yang
berbeda.
Seluruh defenisi diatas dengan jelas menerangkan
bahwa ada penekanan pada perbedaan kebudayaan sebagai
faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses
komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya
memang mengakui dan mengurusi permasalahan mengenai
persamaan dan perbedaan dalam karakteristik
kebudayaan antar pelaku-pelaku komunikasi, tetapi
titik perhatian utamanya tetap terhadap proses
komunikasi individu individu atau kelompokkelompok
yang berbeda kebudayaan dan mencoba untuk melakukan
interaksi.
Menurut Liliweri (2004:9) Komunikasi antar budaya
terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu
budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari
budaya yang lain. Jadi komunikasi antar budaya adalah
pertukaran makna yang berbentuk simbol yang dilakukan
dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Lain
halnya dengan Devito (dalam Maulista, 2013:3)
Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi yang
terjadi di antara orang- orang dari kultur yang
berbeda, yakni antara orang-orang yang memiliki
kepercayaan, nilai dan cara berperilaku kultural yang
berbeda.
Komunikasi Antarbudaya melibatkan berbagai tingkat
perbe-daan keanggotaan kelompok budaya. Komunikasi
Antarbudaya melibatkan penyandian simultan dan
menerjemahkan pesan verbal dan nonverbal dalam proses
pertukaran makna. Banyak komunikasi antarbudaya
melibatkan pertemuan makna yang berbeda atau bertolak
belakang. Komunikasi Antarbudaya selalu terjadi dalam
konteks. Komunikasi Antarbudaya selalu terjadi dalam
sistem yang tertanam secara dalam.
2. Fungsi faktor budaya dalam berkomunikasi
a. Fungsi pribadi
Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi
yang ditunjukkan melalui komunikasi yang bersumber
dari seorang individu, antara lain untuk :
1) Menyatakan identitas social. Dalam
komunikasi,budaya dapat menunjukkan beberapa
perilaku komunikan yang digunakan untuk menyatakan
identitas diri maupun identitas sosial.
2) Menyatakan integrasi social Inti konsep integrasi
sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan
antar pribadi dan, antar kelompok namun tetap
menghargai perbedaanperbedaan yang dimiliki oleh
setiap unsur . perlu dipahami bahwa salah satu
tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang
sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan
komunikan.
3) Menambah pengetahuan Sering kali komunikasia
antar bribadi maupun antar budaya dapat menambah
pengetahuan bersama ,dan adanya saling mempelajari
kubudayaan masing masing antara komunikator dan
komunikan.
4) Melepaskan diri / jalan keluar Hal yang sering
kita lakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain
adalah untuk melepaskan diri atau mencari jalan
keluar atas masalah yang sedang kita hadapi.
b. Fungsi sosial
Fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang
bersumber dari faktor budaya yang ditunjukkan
melalui prilaku komunikasi yang bersumber dari
interaksi sosial,diantaranya berfunsi sebagai
berikut :
1) Pengawasan
Praktek komunikasi antar budaya di antara
komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan
berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses
komunikasi antar budaya fungsi ini bermanfaat
untuk menginformasikan “ perkembangan “ tentang
lingkungan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh
media massa yang menyebarluaskan secara rutin
perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar
kita meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah
konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya adalah
kita turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa
dan berusaha mawas diri seandainya peristiwa itu
terjadi pula dalam lingkungan kita.
2) Menjembatani
Dalam proses komunikasi antar pribadi, termasuk
komunikasi antar budaya ,maka fungsi komunikasi
yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya
itu merupakan jembatan atas perbedaan diantara
mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol
melalui pesan-pesan yang mereka
pertukarkan.,keduanya saling menjelaskan perbedaan
tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan
makna yang sama.
3) Sosialisasi nilai
Fungsi sosialisasi merupkan fungsi untuk
mengajarkan dan memperkenalkan nilai nilai
kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat lain .
Dalam komunikasi antar budaya seringkali tampil
perilaku non verbal yang kurang dipahami namun
yang lebih penting daripadanya adalah bagaimana
kita menangkap nilai yang terkandung dalam gerakan
tubuh ,gerakan imaginer dari tarian tarian
tersebut.
4) Menghibur
Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses
komunikasi antar budaya . American fun yang sering
ditampilkan TVRI memberikan gambaran tentang
bagaimana orang orang sibuk memanfaatkan waktu
luang untuk mengunjungi teater dan menikmati suatu
pertunjukan humor. Menonton Qosidah yang
ditampilkan oleh anak anak sebuah pesantren
mungkin kurang disukai oleh mereka yang suka music
klasik , namun kalau anda menonton dengan mental
menikmati maka tampilan qosidah tidak mengganggu
anda.
3. Dimensi Komunikasi Antar Budaya
Ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan dalam
komunikasi lintas budaya antara lain:
a. Tingkat keorganisasian kelompok budaya
Istilah kebudayaan telah digunakan untuk menunjuk
pada macam-macam tingkat lingkungan dan
kompleksitas dari organisasi sosial. Umumnya
istilah kebudayaan mencakup :
1) Kawasan – kawasan di dunia, seperti : budaya
timur/barat.
2) Sub kawasan-kawasan di dunia, seperti : budaya
Amerika Utara/Asia Tenggara.
3) Nasional/Negara, seperti, : Budaya
Indonesia/Perancis/Jepang
4) Kelompok-kelompok etnik-ras dalam negara
seperti : budaya orang Amerika Hutam, budaya
Amerika Asia, budya Cina Indonesia
5) Macam-macam subkelompok sosiologis berdasarkan
kategorisasi jenis kelamin kelas sosial.
Countercultures (budaya Happie, budaya orang
dipenjara, budaya gelandangan, budaya
kemiskinan).
b. Konteks Sosil
Macam komunikasi antar budaya dapat lagi
diklasifikasi berdasarkan konteks sosial dari
terjadinya. Yang biasanya termasuk dalam studi
komunikasi antar budaya:
1) Bisnis
2) Organisasi
3) Pendidikan
4) Akulturasi imigran
5) Politik
6) Penyesuain perlancong/pendatang sementara
7) Perkembangan aalih teknologi/ pembangunan/
difusi inovasi
8) Konsultasi terapis
Komunikasi dalam semua konteks merupakan persamaa
dalam hal unsur-unsur dasar dan proses komunikasi
manusia (transmitting, receiving, processing).Tetapi
adanya pengaruh kebudayaan yang tercakup dalam latar
belakang pengalaman individu membentuk pola-pola
persepsi pemikiran. Penggunaan pesan-pesan
verbal/nonverbal serta hubungan-hubungan antaranya.
Maka variasi kontekstual, merupakan dimensi tambahan
yang mempengaruhi prose-proses komunikasi antar
budaya.
c. Saluran komunikasi
Saluran komunikasi dapat dbagi menjadi:
1) Antar pribadi/interpersonal/person-person
2) Media masa
4. Istilah yang berkaitan dengan komunikasi lintas
budaya
Kadang – kadang beberapa istilah yang menunjukkan
adanya perbedaan kebudayaan dalam komunikasi di
perguruan tinggi secara interchangeable (dapat
ditukar-tukar secara berganti-gantian), tetapi
sebenarnya masing-masing mempunyai pengertian yang
berbeda-beda. Beberapa ahli telah mencoba membuat
klasifikasi dan penekanan perbedaan pengertian
sebagai berikut :
Sitaram (1970) menegaskan perbedaan intercultural
Communication (lihat defenisi sebelumnya) dengan
International Communication yang diartikannya sebagai
interaksi antara struktur-struktur politik atau
negara-negara, yang sering dilakukan oleh wakil-
wakil dari negara-negara, atau bangsa-bangsa
tersebut (“interaction between structures or
nations, often carried on by representatives of
those nations”). Ia juga mengemukakan tentang
Intracultural Communications yang terjadi antara individu-
individu dari kebudayaan yang sama dan bukan antara
individu-individu dari kebudayaan-kebudayaan yang
berbeda (“takes place among individuals of different
cultures”). Sedangkan Minority Communication adalah
komunikasi antara anggota-anggota suatu subbudaya
minoritas dengan anggotaanggota budaya mayoritas
yang dominan (“Communications between the people of
a minority sub-culture and those of the majority
dominant culture”).
Arthur Smith (1971) mengemukakan tentang Transcracial
Communication, sebagai pengertian yang dicapai oleh
orang-orang dari latar belakang etnik atau ras yang
berbeda dalam suatu situasi interaksi verbal (“the
understanding that persons from different ethnic or
racial backgrounds can achieve in a situation of
verbal interaction”); dalam pengertian ini tercakup
dalamnya baik dimensi rasial maupun etnik (“it
includes both rasial and ethnic dimensions”); hal
mana untuk membedakan komunikasi transrasial dari
komunikasi internrasial, yang biasanya menunjukkan
perbedaan hanya dalam artiras (“….to differentiate
transracial communication from the much-used term
interracial. Which usually denotes differences in
race only”).
Gerhard Malezke, seperti halnya Sitaram, juga
membedakan pengertian Intercultural Communication (lihat
defenisi sebelumnya) dari International Communication
yang dirumuskannya sebagai Proses komunikasi antara
negaranegara atau bangsa-bangsa yang melampaui
batas-batas negara (“is the communication process
between different countries or nations across
frontiers”). Dari kedua defenisi tersebut dapat
ditarik pengertian bahwa keduanya bisa berarti sama,
tetapi tidak selalu harus demikian. Seringkali
komunikasi internasional terjadi antara orang-orang
dari kebudayaan yang sama, tetapi terpisahkan oleh
batas internasional atau negara. Sebaliknya bisa
saja komunikasi antar budaya terjadi antar orang-
orang dalam batas negara yang sama, tetapi dengan
asak kebudayaan yang berlainan, seringkali dengan
bahasa-bahasa yang berlainan seperti kelompok-
kelompok minoritas. Karenanya, orang cenderung untuk
memakai kata ‘internasional’ jika berbicara tentang
komunikasi pada tingkat murni politik yang dilakukan
wakil- wakil negara, sedangkan konsep antar budaya
(intercultural) lebih ditujukan untuk penggambaran
realita sosiologis dan anthropologis. Kadang –kadang
dipakai juga istilah Supranational atau bahkan
Comparative Communication. Walaupun dalam hal
penggunaan istilah ini tidak ada konsensus yang
mutlak, tetap malapetaka telah membuat satu
garispemisah yang lebih jelas. Penelitian dalam
bidang-bidang komunikasi internasional maupun antar
budaya tidak dapat disamakan dengan penelitian dalam
bidang komunikasi komparatif (perbandingan). Yang
menjadi titik pokok dari semua penelitian tentang
proses-proses komunikasi antar budaya ialah:
hubungan atau kontak-kontak antara orang-orang dari
negara yang berlainan. Sedangkan Penelitian dalam
bidang komunikasi perbandingan, mempelajari dan
membandingkan sistem-sistem komunikasi dari
bermacam-macam kebudayaan dan negara untuk kemudian
menarik perbandingan dari perbedaan-perbedaannya
atau persamaan-persamaanya.
Dodd (1982) membagi situasi perbedaan antar
budaya, khususnya yang biasa dimasukkan ke dalam
pengertian komunikasi subbudaya (Subcultural
Communications) ke dalam:
a. Interethnic communication
Yaitu komunikasi antara dua atau lebih orang dari
luar latar belakang etnik yang berbeda )”….
Communications between two or more persons from
different ethnic backgrounds”). Kelompok etnik
adalah kumpulan orang yang dapat dikenal secara
unik dari warisan tradisi kebudayaan yang sama,
yang seringkali asalnya bersifat nasional.
Contohnya di AS : Italian American, Polish
American. Mexican American, Puerto Rican American.
Di Indonesia, tentunya yang dimaksud dengan
kelompok etnik ialah berbagai suku bangsa yang
ada dalam wilayah negara Indonesia, seperti : Suku
Jawa, Sunda, Batak, Minang, dll, yang bisa
melampaui batas subwilayah secara geografik.
b. Interracian communication
Yakni komunikasi antara dua atau lebih orang dari
latar belakang ras yang berbeda (“communication
between two or more persons of differing racial
background”). Sedangkan ras yang diartikannya
sebagai ciri-ciri penampilan fisik yang diturunkan
dan diwariskan secara genetik. Pokok perhatian
yang penting disini adalah bahwa perbedaan-
perbedaanras menyebabkan perbedaan-perbedaan
perseptual yang menghambat berlangsungnya
komunikasi, bahkan sebelum ada sama sekali usaha
untuk berkomunikasi.
c. Countercultural communication
Melibatkan orang-orang dari budaya asal atau pokok
yang berkomunikasi dengan orang-orang dari
subbudaya yang terdapat dalam budaya pokok tadi
(“….involves persons from a parent culture
communication with persons from subcultures within
the parent culture”). Dengan mengutip perumusan
Prosser tentang Countercultural Communication
(lihat di depan), Dodd pada pokoknya menekankan
sifat dari subbudaya pada situasi khusus antar
budaya di sini yang menolak nilai-nilai yang sudah
diakui masyarakat luas (‘establisment values’)saat
ini.
d. Social class communication
Beberapa perbedaan antara orang-orang adalah
berdasarkan atas status yang ditentukan oleh
pendapatan, pekerjaan dan pendidikan. Perbedaan
ini menciptakan kelas-kelas sosial dalam
masyarakat. Menyertai perbedaan ini adalah
perbedaan dalam hal pandangan, adat kebiasaan dan
lain sebagainya. Walaupun dalam beberapa hal
tertentu kelas-kelas sosial ini memiliki bersama
aspek-aspek kebudayaan pokoknya.
e. Group membership
Merupakan unit-unit subbudaya yang cukup menonjol.
Berdasarkan homogenitas dalam karakteristik –
karakteristik ideologik, ditambah dengan loyalits
kelompok, banyak perbedaan-perbedaan antar
kelompok yang meletus menjadi konflik serius.
Misalnya perang antara kaum protestan dan katolik
di Irlandia Utara atau perang antara penganut
agama Islam dan Kriten di Libanon. Juga faktor –
faktor jenis kelamin, tempat tinggal (seperti
daerah rural atau urban) dan umur dapat menentukan
perbedaan – perbedaan kelompok (group) ini.
5. Prinsip-prinsip Komunikasi yang berkaitan dengan
kebudayaan
Setelah melihat secara umum peta situasi dalam
bidang ilmu komunikasi saat ini, kiranya perlu
ditinjau secara lebih rinci apa hakekat pokok
komunikasi. Tinjauan bisa dilihat dengan suatu
asumsi dasar bahwa komunikasi ada hubungannya dengan
prilaaku manusia dan pemenuhan kebutuhan untuk
berinteraksi dengan makhluk lainnya (communication
hunger) . Hampir setiap orang butuh untuk mengadakan
kontak sosial dengan orang lain. Kebutuhan ini
dipenuhi melalui saling pertukaran pesan yang dapat
menjembatani individu-individu agar tidak terisolir.
Pesan-pesan diwujudkan melalui prilaku manusia.
Dalam hal demikian maka ada dua persyaratan yang
harus dipenuhi:
a. Perilaku apapun harus diamati oleh orang lain
b. Perilaku tersebut harus menimbulkan makna bagi
orang lain. Implikasi dari pernyataan ini adalah:
Kata “apapun” mengandung arti bahwa baik
perilaku komunikasi verbal maupun nonverbal
dapat berfungsi sebagai pesan. Pesan-pesan
verbal terdiri dari kata-kata terucapkan
maupun tertulis, sedangkan pesan-pesan non
verbal merupakan keseluruhan perilaku-
perilaku sisanya,yang tidak termasuk verbal,
tetapi juga dapat dilekatkan makna padanya.
Perilaku dapat terjadi baik secara sadar
maupun tidak sadar. Prilaku tidak sadar
terutama pada non verbal
Seringkali prilaku juga terjadi tanpa ada
maksud tertentu dari pelakunya, tetapi
dipersepsikan dan diberikan makna oleh orang lain
Dengan pengertian lain makna komunikasi dapat
dirumuskan secara umum sebagai : “…sesuatu yang
terjadi bilaman makna dilekatkan pada prilaku atau
pada hasil/akibat dari prilaku tersebut”. Ini
berarti bahwa setiap saat seseorang memperhatikan
prilaku atau akibat dari prilaku kita serta
memberikan makna padanya, maka komunikasi telah
terjadi, tanpa harus dibatasi apakah prilaku itu
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja,
dengan maksud atau tanpa maksud. Jika hal ini kita
renungkan lebih dalam lagi, maka nampaknya tidak
mungkin bagi kita untuk bertingkah laku. Dan jika
tingkah laku memiliki kemampuan komunikasi,
tentunya tidak mungkin pula bagi kita untuk
berkomunikasi (“We cannot not communicate”).
6. Dimensi Komunikasi Lintas Budaya
Dalam suatu kebudayaan yang ada, pasti memiliki
ciri-ciri kebudayaan yang satu berbeda dengan
ciri-ciri budaya di daerah lain. Ciri-ciri budaya
antara lain:
a. budaya bukan bawaan tetapi dapat dipelajari
b. budaya dapat disampaikan dari orang ke orang,
kelompok ke kelompok dan dari generasi ke
generasi.
c. budaya berdasarkan symbol
d. budaya bersifat dinamis, suatu system yang
terus berubah sepanjang waktu
e. budaya bersifat selektif, mereprentasikan pola-
pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya
terbatas
f. berbagai unsur budaya saling berkaitan
g. etnosentrisme
7. asumsi dalam komunikasi lintas budaya
a. During intercultural communication,the message sent is usually
not the message received. Selama komunikasi
antarbudaya pesan terkirim biasanya bukan pesan
yang diterima. Setiap kali orang-orang dari
budaya yang berbeda datang bersama-sama dan
terjadi pertukaran pesan, mereka membawa budaya
berupa berbagai macam pemikiran, nilai-nilai,
emosi, dan perilaku yang mengakar dan
dibudidayakan.
b. Intercultural communication is primarily anonverbal act
between people. Komunikasi Antarbudaya pada
dasarnya merupakan suatu tindakan nonverbal
antara orang-orang. Dibalik komunikasi verbal,
komunikasi non verbal menjadi penguat
komunikasi
c. Intercultural communication necessarily involves a clash of
communicator style. Komunikasi Antarbudaya harus
melibatkan pertemuan berbagai gaya komunikator.
Di Amerika Serikat, kepandaian berbicara adalah
komoditas yang sangat dihargai. Orang-orang
rutin dievaluasi dari pidato mereka. Namun
diam-yaitu, mengetahui kapan tidak berbicara-
adalah prasyarat mendasar untuk linguistik dan
kompetensi suatu budaya.
d. Intercultural communication is a group phenomenon
experienced by individuals. Komunikasi Antarbudaya
adalah fenomena kelompok yang dialami oleh
individu. Setiap kali berinteraksi dengan orang
dari budaya yang berbeda yang dibawa adalah
asumsi dan penampilan dari orang lain.
Interaksi spesifik berupa lisan dan pesan
nonverbal yang dipertukarkan biasanya
disesuaikan berdasarkan asumsi-asumsi dan
penampilan tersebut.
e. Intercultural communication is a cycle of stress and adaptation.
Komunikasi Antarbudaya adalah siklus stres dan
adaptasi. Ketika seseorang datang bersama-sama
dengan orang dari budaya yang berbeda, akan
muncul perasaan tidak pasti, khawatir, dan
cemas. Perasaan seperti itu mengakibatkan
stres. Oleh karena itu komunikasi antarbudaya,
kadang-kadang mendatangkan stres.
Komunikasi antarbudaya dalam prakteknya, tidak
hanya mendatangkan stres, ketidakpastian, juga
menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik. Fred
Jandt & Dolores Tanno dalan Iben Jensen
membenarkan hal tersebut menurutnya komunikasi
Antarbudaya biasanya berhubungan dengan
kesalahpahaman dan konflik - meskipun sebagian
besar dari semua komunikasi antarbudaya adalah
tanpa masalah.
8. kaitan antara Komunikasi dan Kebudayaan
Dari berbagai definisi tentang KAB seperti yang
telah dibahas sebelumnya, dampak bahwa unsur pokok
yang mrndasari proses KAB ialah konsep-konsep
tentang “Kebudayaan” dan “Komunikasi”. Hal ini pun
digarisbawahi oleh Sarbaugh (1979:2) dengan
pendapatnya bahwa pengertian tentang komunikasi
antar budaya memerlukan suatu pemahaman tentang
konsep-konsep komunikaasi dan kebudayaan serta
saling ketergantungan antara keduanya. Saling
ketergantungan ini terbukti, menurut Serbaugh,
apabila disadari bahwa:
a. Pola-pola komunikasi yang khas dapat berkembang
atau berubah dalam suatu kelompok kebudayaan
khusus tertentu.
b. Kesamaan tingkah laku antara satu generasi
dengan generasi berikutnya hanya dimungkinkan
berkat digunakannya sarana-sarana komunikasi.
Sementara Smith (1966) menerangkan hubungan
yang tidak terpisahkan antara komunikasi dan
kebudayaan yang kurang lebih sebagai berikut:
Kebudayaan merupakan suatu kode atau kumpulan
peraturan yang dipelajari dan dimiliki bersama;
untuk mempelajari dan memiliki bersama diperlukan
komunikasi, sedangkan komunikasi memerlukan kode-
kode dan lambang-lambang yang harus dipelajari dan
dimiliki bersama.
Hubungan antara individu dan kebudayaan saling
mempengaruhi dan saling menentukan. Kebudayaan
diciptakan dan dipertahankan melalui aktifitas
komunikasi para individu anggotanya. Secara
kolektif prilaku mereka secara bersama-sama
menciptakan realita (kebudayaan) yang mengikat dan
harus dipatuhi oleh individu agar dapat menjadi
bagian dari unit. Maka jelas bahwa antara
komunikasi dan kebudayaan terjadi hubungan yang
sangat erat:
a. Disatu pihak, jika bukan karena kemampuan
manusia untuk menciptakan bahasa simbolik,
tidak dapat dikembangkan pengetahuan, makna,
simbol-simbol, nilai-nilai, aturan-aturan dan
tata, yang memberi batasan dan bentuk pada
hubungan-hubungan , organisasi-organisasi dan
masyarakat yang terus berlangsung. Demikian
pula, tanpa komunikasi tidak mungkin untuk
mewariskan unsur-unsur kebudayaan dari satu
generasi kegenerasi berikutnya, serta dari satu
tempat ke tempat lainnya. Komunikasi juga
merupakan sarana yang dapat menjadikan individu
sadar dan menyesuaikan diri dengan subbudaya-
subbudaya dan kebudayaan-kebudayaan asing yang
dihadapinya. Tepat kiranya jika dikatakan bahwa
kebudayaan dirumuskan, dibentuk, ditransmisikan
daan dipelajari melalui komunikasi.
b. Sebaliknya, pola-pola berpikir, berprilaku,
kerangka acuan dari individu-individu
sebahagian terbesar merupakan hasil penyesuaina
diri dengan cara-cara khusus yang diatur dan
dituntut oleh sistem sosial dimana mereka
berada. Kebudayaan tidak saja menentukan siapa
dapat berbicara dengan siapa, mengenai apa dan
bagaimana komunikasi sebagainya berlangsung,
tetapi juga menentukan cara mengkode atau
menyandi pesan atau makna yang dilekatkan pada
pesan dan dalam kondisi bagaimana macam-macam
pesan dapat dikirimkan dan ditafsirkan.
Singkatnya, keseluruhan prilaku komunikasi
individu terutama tergantung pada kebudayaanya.
Dengan kata lain, kebudayaan merupakan pondasi
atau landasan bagi komunikasi. Kebudayaan yang
berbeda akan menghasilkan praktek-praktek
komunikasi yang berbeda pula.
1. Hambatan dalam komunikasi lintas budaya
Dalam bukunya Intercultural Business Communication,
Chaney dan Martin (2004) mengungkapkan bahwa:
“hambatan komunikasi atau communication barrier
adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang
untuk terjadinya komunikasi yang efektif.
Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu
faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya,
karenanya hambatan tersebut juga sering disebut
sebagai hambatan komunikasi antar budaya, sebagai
hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi
karena adanya perbedaan budaya antara komunikator
dan komunikan. Adapun faktor hambatan komunikasi
antar budaya yang sering terjadi antara lain:
fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman,
emosi, bahasa (verbal), nonverbal, kompetisi.”
Dalam komunikasi antarbudaya, reaksi negatif dan
evaluatif individu terhadap sebuah budaya dapat
menciptakan hambatan komunikasi. Evaluasi yang
bersifat negatif menyebabkan adanya ketidaksukaan
dan penghindaran. Hal ini terjadi karena budaya
„asing‟ dipandang „menyimpang‟ atau „berbeda‟ dari
norma yang kita anut. Hambatan komunikasi tersebut
terjadi di antara dua budaya dan bersifat satu
arah, yang mana hal ini mencerminkan adanya
ketidakmampuan untuk memahami norma dari budaya
yang berbeda (budaya asing). Hambatan ini juga
tidak selalu bersifat timbal balik. Sebuah
perbedaan budaya (bersifat tunggal) dapat pula
menjadi hambatan bila melanggar salah satu nilai
inti komunikator.
Tracy Novinger (dalam malista, 2013)
mengemukakan bahwa hambatan komunikasi antarbudaya
dapat dibagi dalam tiga jenis, yakni hambatan
persepsi, hambatan verbal dan hambatan nonverbal.
Beberapa jenis hambatan persepsi yang dikemukakan
oleh Tracy Novinger adalah wajah (face), nilai
(values), dan pandangan dunia (worldview). Wajah (face)
merupakan nilai atau pertahanan seseorang terhadap
pandangan di depan orang lain. Hal ini menyangkut
bagaimana seseorang ingin orang lain melihat
terhadap dirinya, yang dipengaruhi dari interaksi
sosial, dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa
diperoleh atau bisa hilang.
Adanya perbedaan nilai juga salah satu yang
memengaruhi munculnya hambatan persepsi dalam
komunikasi antarbudaya. Nilai agama ermanisfestasi
tidak hanya pada dogma, tetapi juga pada pola
kehidupan dan pandangan hidup. Ferraro juga
mengungkapkan bahwa pengaruh agama dapat dilihat
dari jalinan semua budaya, karena hal ini bersifat
dasar. Nilai agama ini juga berpengaruh pada cara
pandang (worldview) seseorang .Cara pandang (worldview)
meliputi bagaimana orientasi budaya terhadap
Tuhan, alam, kehidupan, kematian dan alam semesta,
arti kehidupan dan keberadaan.
Sikap (attitude) juga salah satu bagian yang
termasuk dalam mempengaruhi persepsi. Sikap
merupakan ranah psikologis yang secara jelas
memengaruhi perilaku dan menyimpangkan persepsi.
Sikap akan
menyebabkan interpretasi dari kejadian, yang mana
hal ini bersifat mempengaruhi persepsi. Sikap
mencakup aspek kognitif dan afektif. Aspek
kognitif merujuk pada keinginan untuk menahan
pendapat yang bersifat etnosentris dan kesiapan
untuk mempelajari mengenai isu perbedaan lintas
budaya dengan pandangan terbuka. Sedangkan aspek
afektif merujuk pada komitmen emosional untuk
terlibat dalam partisipasi
perspektif kultural, dan pengembangan rasa empati
dalam memahami perbedaan kelompok kultural.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang diatas, maka dapat kita
simpulkan kenapa kita harus belajar Komunikasi Lintas
Budaya.
1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami
keanekaragaman budaya sangat diperlukan
2. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman
anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-
nilainya berbeda.
3. Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai
masyarakat lainnya.
4. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan
nilai-nilainya sendiri.
5. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun
ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar
yang berlaku.
6. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri
merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan
memahami nilai-nilai budaya lain.
7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk
berhubungan dengan orang lain kita memperoleh
pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan,
aspirasi, perasaan dan masalah manusia.
8. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan
antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan
keberanian dan kepekaan. Semakin mengancam
pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia
kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari
dia, tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya.
9. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang
diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari
pandangan yang monokultural terhadap
interaksimanusia ke pandangan multikultural.
10. Perbedaan-perbedaan budaya menandakan
kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi, namun
perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer
tidaklah menyusahkan atau memudahkan.
11. Situasi-situasi komunikasi antar budaya
tidaklah statik dan bukan pula stereotip. Karena
itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk
mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan,
pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya
siap untuk berperan serta dalam menciptakan
lingkungan komunikasi yang efektif dan saling
memuaskan.
Daftar Pustaka
Ahmad Sihabudin. 2011. Komunikasi Antar Budaya.
Jakarta: Bumi Aksara
Alvin Sanjaya. 2013. Hambatan Komunikasi Antar Budaya
Antara Staf Marketing Dengan Penghuni
Berkewarganegaraan Australia Dan Korea Selatan Di
Apartemen X Di Surabaya. Jurnal E Komunikasi, VOL
1< No 3
Christy, Malista Paulne. 2013. Hambatan Komunikasi
Antar Budaya Antara Dosen Native China Dengan
Mahasiswa Indonesia Program Studi Sastra Tionghoa
Universitas Kristen Petra, Jurnal E Komunikasi,
VOL 1, No. 2
Edy Sudaryanto. 1997. Relevansi Fungsi Dan Peranan
Komunikasi Dalam Pembangunan. Bandung: Pps UNPAD
Fajar, Mahaerni. 2009. Ilmu Komunikasi dan Praktek.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Lihapsari, prihartini, dkk. 1997. Teknik Komunikasi
Tepat Guna Dalam Mengatasi Segala Bentuk
Perubahan. Bandung: Pps UNPAD
Liliweri, Alo. 2004. Dasar-dasar Komunikasi Antar
Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mulyana, Dedi. 2001. Ilmu Komunkasi Suatu Pengantar.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Dedi dan Rachmat Jalaluddin. 2002. Panduan
berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda-beda.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Natalia, Imanuel V.O. 2007. Model Komunikasi Antar
BudayaEkspatriat Guangdong Machiney exp. Imp.Ltd
China (GMC) dengan Orang Indonesia Dalam Rangka
Menjalin Kerja Sama dengn Orang Indonesia di
Surabaya, jurnal Ilmiah Scriptura, ISSN 1978-385X
VOL 1, No. 1
Philep M. Regar, dkk. 2014. Pola Komunikasi Antar
Budaya dan Identitas Etnik SANGIE-TALAUD-SITARO
(studi pada masyarakat etnik SANGIE-TALAUD_SITARO
di Kota Manado tahun ke 1 dari rencana 3 tahun).
Jurnal Acta Diurna, VOL 3, No. 4
Samovar, Larry A, Dkk. 2010. Komunikasi Lintas Budaya.
Jakarta: Salemba Humaniora
Satriani Dan Muljono. 2005. Komunikasi Partispatif
Pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga. Jurnal
Masyarakat Dan Kebudayaan Politik, No. 2 Hal
89_95
Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian.
Jakarta: Universitas Indonesia Press
Sunarwinadi, Ilya. Komunikasi Antar Budaya Pusat Antar
Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Universitas
Indonesia Press