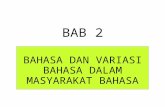kosmologi sejarah dalam filsafat sejarah: makna,teori, dan ...
BAHASA, KEKUASAAN, DAN SEJARAH. - Institutional ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of BAHASA, KEKUASAAN, DAN SEJARAH. - Institutional ...
BAHASA, KEKUASAAN, DAN SEJARAH. Historiografi Islam Marshall G.S. Hodgson
dalam Perspektif Kajian Poststrukturalisme Michel Foucault
D I S E R T A S I
(Promosi)
O l e h:
Gregorius Soetomo
3115.12.0000.0004
Pembimbing:
Prof. Dr. Azyumardi Azra MA
Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor MA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga Disertasi S-3 dengan judul “Bahasa, Kekuasaan, dan Sejarah. Historiografi Islam Marshall G.S. Hodgson dalam Perspektif Kajian Michel Foucault.” menjadi paripurna. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor dengan bidang konsentrasi Pemikiran Islam di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebuah proses penulisan yang benih-benihnya sudah dimulai ketika penulis menekuni studi Masteral (S-2) di Sekolah yang sama (2013 – 2015).
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya, kepada : 1. Pater Provinsial RB Riyo Mursanto SJ (2013) yang mengutus saya studi di
Sekolah tersebut, dan kemudian diteguhkan oleh Pater Provinsial P Sunu Hardiyanta SJ (2014). Atas visi mereka berdua saya, seorang Imam Yesuit dalam Gereja Katolik boleh menikmati kehangatan, persahabatan, dan kedalaman studi Islam di Sekolah ini.
2. YB Heru Prakosa SJ, A. Sudiarja SJ, A. Nugroho Widiyono SJ, Franz Magnis-Suseno SJ, J. Sudarminta SJ, dan M. Sastrapratedja SJ, lewat sumbangan dan dukungan dengan caranya masing-masing, mereka ikut andil dan memberi kesempatan saya untuk merefleksikan kajian Islam sebagai bagian kehidupan iman Kristiani dan imam dalam Gereja Katolik.
3. Para Pimpinan di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra MA, Prof. Dr. Suwito MA, dan Dr Yusuf Rahman MA, yang menerima saya sebagai bagian dan kemudian berproses dalam komunitas akademis ini (2013 – 2015). Sebuah proses yang dilanjutkan (sejak 2015) di bawah pimpinan Prof Dr Masykuri Abdillah MA, Prof. Dr. Didin Saepuddin MA, dan Dr JM Muslimin MA di Sekolah ini.
4. Prof. Dr. Azyumardi Azra MA dan Prof. Dr. Iik Arifin M, pembimbing Disertasi, kepada siapa saya datang berkonsultasi, berdiskusi, dan berbincang-bincang. Mereka berdua selalu ramah, penuh senyum, bersedia menerima saya setiap saat. Terima kasih Pak Azra dan Pak Iik! Perlu saya sebutkan juga nama-nama yang ikut menyumbangkan gagasan, baik lewat bincang-bincang, proses verifikasi, ujian, dan lainnya: Prof Dr Masykuri Abdillah MA, Prof. Dr. Didin Saepuddin MA, Prof. Dr. Sukron Kamil MA, Prof Dr. Zainun Kamaladdin MA, Dr. M. Arief Mufraini, LC, MSi, Prof. Dr. Budi Sulistiono, Prof. Dr. Amany B. Umar Lubis, MA, Suparto, M.Ed, Ph.D, Dr Ali Munhanif MA, Ismatu Ropi’ Ph.D, dan Prof. Dr. M. Sastrapratedja.
ii
5. Sejak 2013, teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Sekolah ini telah menerima saya ‘yang lain dan berbeda’ ini dan menjadikannya sebagai bagian secara alamiah dalam komunitas ini. Mereka datang dan pergi selama saya studi di Sekolah ini. Berbagai kisah, interaksi dan peristiwa dengan mereka telah memperkaya hidup saya, bukan saja kekayaan pengetahuan, tetapi juga kekayaan iman dan spiritual. Saya berterima kasih kepada mereka. Saya bersyukur untuk persahabatan dan persaudaraan ini. Tidak mudah bagi saya untuk menyebutkan mereka satu per satu.
6. Komunitas Skolastik SJ Wisma Dewanto di Jalan Kramat VII/25, Jakarta Pusat tempat saya tinggal, membaca-menulis, dan menikmati apa artinya hidup, bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dalam periode 2015 – 2017, saya ingin menyebut ‘nama panggilan’ mereka yang ikut ambil bagian secara informal, emosional, tetapi memberi sumbangan mendalam juga: Romo Adi, ‘mbak Iin, Harry, Awan, Sakda, Matthew, Daryanto, Bosco, Francis, Erwin, Oat, Barry, Robert.
7. Terima kasih untuk komunitas Gereja Katolik dan Non-Katolik yang di sana sini saya jumpai. Mereka menyapa dan bertanya, “Bagaimana perkembangan studi di UIN?”. Beberapa hanya sekedar basa-basi. Tetapi, beberapa lainnya sungguh serius dengan penuh minat mengajukan pertanyaan yang mengundang diskusi, kemudian benar-benar ingin mendengarkan tanggapan saya, dan membuat saya berpikir untuk mendalami hal-hal mendasar dari studi ini. Terima kasih.
Sebuah karya selalu lahir dan hadir lewat sebuah konteks ruang dan waktu yang
kompleks. Kepada semua pihak yang belum tersapa tetapi telah membantu proses penulisan tesis ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada banyak kisah dan peristiwa yang saya jumpai, duka dan suka, yang telah ikut memoles disertasi ini, saya pantas bersyukur karenanya.
Kramat VII/25, Mei 2017
Greg Soetomo Penulis
ix
A B S T R A K Para ilmuwan sejarah selama ini memegang kesatuan dan kontinuitas
historis sebagai kebenaran. Ada anggapan bahwa sejarah memiliki ‘konstanta’. Disertasi ini menjelaskan dan membuktikan sebaliknya. Tulisan ini melihat perjalanan sejarah pada kenyataannya diisi dengan berbagai keterpatahan, perbedaan dan penyimpangan. Ketidakpastian ini berlangsung ketika ‘bahasa’ menjadi fokus kajian ilmu sejarah.
Michel Foucault (1926 – 1984), khususnya dalam L'archéologie du savoir (1969), menolak prakonsepsi mengenai kesatuan dan kontinuitas sejarah yang selama ini justru dijadikan pegangan kebenaran para sejarawan. Ia melihat perjalanan sejarah pada kenyataannya diisi dengan berbagai keterpatahan, perbedaan dan penyimpangan yang menjadi ciri-ciri ketidakpastian dalam ilmu sejarah sekarang ini. Pembalikan ini berlangsung karena pembalikan fokus studinya pada bahasa dalam ilmu sejarah. Foucault menyebut ini sebagai metode Arkeologi Pengetahuan.
Permasalahan yang hendak dijawab dalam disertasi ini bisa dirumuskan demikian: “Bagaimana Michel Foucault, khususnya dalam L'archéologie du savoir, yang bertumpu pada analisa bahasa menjelaskan keanekaragaman dalam sejarah Islam Marshall G.S. Hodgson?” Pertanyaan mayor ini diuraikan ke dalam tiga pertanyaan minor.
Tiga pertanyaan ini masing-masing mencerminkan tiga dimensi ‘keanekaragaman’ pemikiran Arkeologi Pengetahuan Foucault (strukturalisme-poststrukturalisme, postmodernisme, dan filsafat sejarah).
Pertama, bagaimana Hodgson, dalam posisi strukturalis, menulis sejarah Islam dengan membangun sistem diskursus untuk menjelaskan sebuah makna; tetapi pada saat yang sama, ia dalam posisi poststrukturalis memperlihatkan inkoherensi dalam sistem diskursus yang ditandai dengan pluralitas makna? Kedua, bagaimana menjelaskan bahwa struktur sosial dalam sejarah Islam tidak pernah bisa lepas dari rantai kekuasaan yang adalah dimensi konstitutif dalam diskursus? Ketiga, bagaimana membuktikan bahwa setiap era dalam sejarah Islam memiliki epistemenya masing-masing yang khas dan keanekaragaman cara berpikir yang mengkerangkakan terbentuknya pernyataan dan diskursus?
Kesimpulan besar dan temuan Disertasi: Analisa bahasa Michel Foucault menyingkapkan adanya keanekaragaman dalam struktur pemikiran, ideologi, dan kerangka berpikir sejarah Islam Marshall G.S. Hodgson (1922 – 1968).
Metodologi penelitian ini pada prinsipnya menjelaskan tiga perspektif pemikiran filsafat Foucault. Pada saat yang sama tiga pendekatan Hodgson dalam menulis sejarah Islam juga juga diuraikan. Keduanya, secara metodologis dan substantif, memiliki titik temu dan titik pisah, yang menjadi bahasan seluruh kajian disertasi ini.
Kata Kunci:Bahasa, Diskursus, Pengetahuan, Sejarah, Historiografi, Islam
xi
A B S T R A K
Historians have been preserving historical unity and continuity as truth.
There is an assumption that history has a ‘constant’. This dissertation explains and proves otherwise. This writing understands history is in fact filled with various ruptures, differences, and deviations. This uncertainty has taken place when ‘language’ turns into the focus of the study of history.
In his L’Archeologie du savoir (1969), Michel Foucault (1926-1984) rejected the preconception of history as unity and continuity that has been kept by historians as truth. He perceived the true history has been painted with various ruptures, differences, and irregularities that reveal uncertainty in the field of history. This reversal has taken place because of the turnaround of language as the focus’ study in historical knowledge. Foucault calls this method the Archaeology of Knowledge.
A question addressed in this dissertation is formulated as follows: “How does Michel Foucault’s Archaeology of Knowledge, which is based on the analysis of language, elucidate the diversity within Marshall G.S. Hodgson’s history of Islam?” This major question is divided into three minor questions.
These three questions respectively reflect a three-fold dimension of the diversity of thoughts in Foucault’s L’Archeologie du savoir (poststructuralism-structuralism, postmodernism, and philosophy of history).
First, how does Hodgson, as a structuralist, writes the history of Islam by way of building a system of discourses to expose meaning; at the same time, as a poststructuralist, he reveals incoherence of discourses and its plurality of meanings? Second, how to explain that the social structure in the history of Islam cannot avoid the elements of power as a constitutive dimension of discourse? Third, how to prove, that in every period, the history of Islam has its distinctive episteme and diversity of thoughts that pillars the formation of statements and discourses?
The main conclusion and finding of this research: by way of linguistic analysis of Michel Foucault’s L’Archeologie du savoir, it reveals the diversity in the structure of thoughts, ideologies, and the frames of thought in Marshall G.S. Hodgson’s history of Islam.
This research methodology is essentially to explain the three perspectives of Foucault’s philosophy. At the same time, the three approaches in Hodgson’s writing on the history of Islam are also explored. Both, methodologically and substantively, have points of convergence and of divergence, which is to be the whole study of this dissertation.
Keywords: Language, Discourse, Knowledge, History, Historiography, Islam
xvii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR --- i PERNYATAAN --- iii PERSETUJUAN TIM PENGUJI --- v ABSTRAK --- ix PEDOMAN TRANSLITERASI --- xv DAFTAR ISI --- xvii BAB I. PENDAHULUAN --- 1
A. Latar Belakang Masalah --- 2 B. Permasalahan --- 11
1. Identifikasi Masalah --- 11 2. Perumusan Masalah ---- 12 3. Pembatasan Masalah: Marshall G.S. Hodgson dan Michel Foucault –13
C. Tujuan Penelitian --- 13 D. Penelitian Terdahulu yang Relevan --- 14
1. Mengambil Inspirasi Hodgson --- 14 2. Membandingkan Hodgson dengan Sejarawan lain ---16 3. Hodgson dan Kajian Sejarah Islam Global --- 18 4. Memanfaatkan Teori Hodgson ‘Islam sebagai Penghubung’ --- 19 5. Memperdebatkan Hodgson --- 21 6. Kajian Michel Foucault dan Islam --- 22
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian --- 23 F. Metodologi Penelitian --- 24 G. Sistematika Penulisan --- 26
BAB II. SEJARAH ISLAM: HISTORIOGRAFI DALAM PERDEBATAN – 29
A. Struktur Diskursus dalam Sejarah Islam --- 30 1. Periode Klasik --- 31 2. Periode Pertengahan --- 35 3. Periode Moderen --- 37
B. ‘Kekuasaan dan Pengetahuan’ dalam Sejarah Islam --- 42 1. Periode Klasik --- 43 2. Periode Pertengahan --- 48 3. Periode Moderen --- 51
C. Nalar Berpikir dalam Sejarah Islam --- 56 1. Periode Klasik --- 57 2. Periode Pertengahan --- 61 3. Periode Moderen --- 65
xix
BAB III. ARKEOLOGI PENGETAHUAN DAN PEMIKIRAN SEJARAH MICHEL FOUCAULT --- 73
A. Michel Foucault dalam Silang-Lintasan Para Pemikir Kontemporer -- 73 1. Kancah Sosial-Politik Pemikiran Foucault --- 74 2. “L'archéologie” dalam Panorama Karya-Karya Foucault ---78 3. Pengaruh dan Pararelitas dengan Para Pemikir lain --- 80 4. Michel Foucault dan Revolusi Iran --- 82
B. Strukturalisme dan Poststrukturalisme Michel Foucault --- 83 1. Mengenai Strukturalisme- Poststrukturalisme --- 85 2. Diskursus (‘Le Discours’) dan Arsip (L’archive) dalam Arkeologi
Pengetahuan --- 87 3. Sejarah dan Analisa Diskursus --- 89
C. Unsur-unsur Postmodernisme Pemikiran Michel Foucault --- 90 1. Arkeologi Pengetahuan, Kekuasaan, dan Postmodernisme --- 91 2. Kekuasaan sebagai Tema Penting --- 94
D. Konsep dan Pemikiran Sejarah Michel Foucault --- 96 1. Problematika Kontinuitas-Diskontinuitas dalam Metode Arkeologi ---
97 2. Arkeologi dan Epistemologi --- 100 3. Kritik terhadap Sejarah Pemikiran --- 103
E. Beberapa Kritik untuk Michel Foucault --- 104 BAB IV. SEJARAH ISLAM MARSHALL G.S. HODGSON --- 107
A. Genealogi Pemikiran Sejarah Marshall G.S. Hodgson --- 108 1. Cuaca Intelektual di University of Chicago --- 109 2. Pengaruh dari luar University of Chicago --- 112 3. The Venture of Islam: Posthumous--- 115
B. Sejarah Islam Hodgson dalam Logika Struktur dan Poststruktur --- 118 1. Merumuskan Pernyataan dan Menggali Dokumen dalam Sejarah Islam
--- 119 2. Peradaban dalam Perdebatan Diskursus --- 124 3. Beberapa Diskursus Penting: Sharia, Sufisme, Relasi Islam-Barat ---
127 C. Sejarah Islam Hodgson, Bahasa, dan Kekuasaan --- 128
1. Kekuasaan dalam Diskursus Sejarah --- 129 2. Kekuasaan di balik Wacana Modernitas --- 132 3. Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Metodologi Penulisan --- 134
D. Sejarah Islam Hodgson sebagai Rantai Keragaman Kerangka Berpikir - 137 1. Periodisasi Sejarah: Kesatuan dan Keragaman --- 138 2. Mengenai Tahapan-Tahapan dalam Sejarah Islam --- 141 3. Lahirnya Episteme Baru --- 149
xix
4. Keutuhan yang Retak --- 151
BAB V. KERAGAMAN DALAM HISTORIOGRAFI ISLAM: SINTESA DAN ANALISA --- 153
A. Keragaman Diskursus dalam Sejarah Islam --- 154
1. Problematika ‘Status Ilmiah’ dalam Sejarah Islam --- 154 2. Bahasa dan Diskursus Bertransformasi dalam Sejarah Islam --- 156 3. Menelusuri Arsip dan Berbagai Aturan dalam Menulis Sejarah --- 160 4. Keragaman Diskursus Sejarah Islam non-Hodgson --- 163
B. Kekuasaan dan Ideologi yang Menyebar lewat Pengetahuan --- 165 1. Postmodernisme Sejarah Islam Hodgson --- 165 2. Bahasa dan Kekuasaan dalam Sejarah Islam --- 169 3. Kekuasaan dan Ideologi dalam Sejarah Islam non-Hodgson --- 171
C. Keragaman Episteme dalam Sejarah Islam --- 173 1. Konstruksi dan Dekonstruksi dalam Sejarah Islam ---173 2. Diskursus Sejarah Islam Dibangun dalam Keragaman Episteme --- 177 3. Keragaman Episteme dalam Sejarah Islam non-Hodgson --- 182
D. Hodgson dan Foucault: Titik Kritis dan Titik Pisah --- 185 1. Epistemologi dan Arkeologi: Dua Kerangka Filosofis yang Terpisah? --
- 186 2. Kejelasan ‘Dekonstruksionisme’ ada dalam ‘Rekonstruksionisme’ dan
‘Konstruksionisme’ --- 187 3. Dialektika ‘Postmodernis’ Foucault dan Sejarah Hodgson --- 189
BAB VI. KESIMPULAN DAN TANTANGAN-REKOMENDASI --- 193
A. Kesimpulan --- 193 B. Tantangan dan Rekomendasi:
Perubahan Sosial-Intelektual Masyarakat Muslim dan Historiografi Baru --- 194 1. Sejarah Islam, Bahasa, dan Ide tentang Kemajuan --- 194 2. Sejarah oleh ‘Yang Tak Berkuasa’ --- 197 3. Sejarah ‘Diskontinu’ dan Islam di Asia Pasifik --- 200
DAFTAR PUSTAKA --- 203 GLOSARIUM --- 217 INDEKS NAMA --- 225 INDEKS SUBYEK --- 229 LAMPIRAN: ISI BUKU --- 233 CURRICULUM VITAE PENULIS --- 237
1
B A B I
PENDAHULUAN
Metodologi dan pendekatan penulisan sejarah dunia sudah hampir setengah abad mendapatkan tantangan serius. Dengan berlangsungnya globalisasi yang semakin intensif dan canggih, sejarawan memiliki paradigma baru dalam penulisan sejarah global. Dimulailah sebuah periode di mana konsep-konsep baru digunakan sebagai alat untuk menjelaskan sejarah manusia. Salah seorang yang merealisasikan konsep ini adalah Marshall G.S. Hodgson (1922 – 1968).1
Pencarian dan pemetaan pola-pola sejarah dunia membawa Hodgson menjadi salah seorang dari generasi paling awal yang kritis terhadap kebekuan dan kebuntuan metodologi kerja para orientalis.2 Ia yakin ada kebutuhan reorientasi mendasar terhadap cara pandang historis dan geografis para orientalis. Berbagai data dan fakta digunakan sebagai basis untuk mempertanyakan keistimewaan dan superioritas Barat. Hodgson menjadi salah seorang yang pertama kali menjelaskan teori peradaban menyeluruh dalam kajian sejarah. Teori ini telah membuka kemungkinan Islam dijelaskan dalam relasinya dengan berbagai kebudayaan yang lain.3
1 Dengan rentang umurnya yang relatif pendek, Marshall Goodwin Simms
Hodgson (1922 –1968), sebenarnya belum bisa disebut penulis yang prolific. Meski demikian, tidak perlu diragukan lagi, ia adalah adalah salah seorang sejarawan Islam terpenting dari kawasan Amerika Utara berkat tiga volume (enam buku) karyanya The Venture of Islam; Conscience and History in a World Civilization (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974). Volume Pertama dari keseluruhan karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mulyadhi Kartanegara dengan judul The Venture of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Islam, “Buku Pertama Lahirnya sebuah Tatanan Baru” (Jakarta: Paramadina, 2002). Karya ini dianggap sebagai sebuah terobosan dalam merekonfigurasi studi mengenai peradaban Islam. Dia berpendapat bahwa orang tidak akan bisa memahami sejarah dunia, terutama sejarah modern ini, kalau tidak mengetahui sejarah Islam. Sedemikian menarik gagasan-gagasan Hodgson, hingga Nurcholish Madjid (1939 – 2005) dalam seluruh tulisannya mengutip sejarawan ini hingga sekitar 30 kali. (Greg Soetomo, “Indonesian Pluralism and Global Islamic History. Marshall Hodgson’s Thoughts in Nurcholish Madjid’s Writings”, Paper International Conference. Southeast Asian Islam: Promoting Moderate Understanding of Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 8 – 9 October 2015)..
2 Akhir-akhir ini ada keberatan dengan sebutan ‘orientalis’. ‘Islamisis’ dianggap istilah yang lebih tepat. (Is·la·mi·cist: A specialist in the study of Islam.). Hodgson juga menjelaskan terminologi Islamicist ini. (Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 56 - 57). Dalam konteks diskusi mengenai Hodgson ini, pada umumnya akan digunakan ‘orientalis dan orientalisme’, sebagai frase umum yang menjadi sasaran kritik Hodgson.
3 Hodgson menciptakan terminologi Islamicate dan Islamdom dalam The Venture of Islam melalui “Introduction to the Study of Islamic Civilization”. Dalam pengantar ini ia menyibukkan diri dengan menjelaskan definisi-definisi. Diantaranya ia menerangkan
2
Bab Pendahuluan ini berturut-turut akan menjelaskan Latar Belakang Masalah dari seluruh riset ini. Dalam Permasalahan, akan diidentifikasi, dirumuskan, dan dibatasi pokok permasalahannya. Tujuan Penelitian dirumuskan berdasarkan rumusan permasalahan. Pembahasan mengenai Penelitian Terdahulu yang Relevan menegaskan bahwa riset dalam Disertasi ini berbeda dan unik dari berbagai penelitian sebelumnya. Dan akhirnya, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan diuraikan.
A. Latar Belakang Masalah Hodgson melihat bahwa sejarah Islam menyimpan kekuatan strategis untuk
mengeritik diskursus peradaban Barat.4 Peradaban Islam, yang berakar dalam religi dan kebudayaan Irano-Semitic,5 kawin silang dengan dinasti Asia Barat. Peradaban Islam, dengan demikian, adalah saudara sepupu kebudayaan Barat. Islam adalah ‘Yang Lain’ untuk Barat. Sekaligus, ia menjadi sebuah peradaban yang kaya dan sukses yang karenanya Barat mampu menjelaskan dirinya dengan lebih baik.
Tulisan awal Hodgson, “Hemispheric Interregional History as an Approach to World History”6 memuat tema-tema sentral yang dikembangkan lebih jauh dalam tulisan-tulisan kemudian. Kritik Hodgson terhadap sejarah dunia yang ditulis oleh para orientalis berpusat pada persoalan perspektif. Ia menyebutkan bahwa Eropa sebenarnya hanyalah area pinggiran saja dalam zone agrarianate citied life (‘kehidupan agraris yang berpusat di kota-kota’; 4 milenium BCE – abad 17/18 CE)7 dalam konstelasi peradaban Afro-Eroasia.8 Artikel ini menjadi basis untuk
beberapa neologisms, seperti Islamic selalu mengacu pada Islam sebagai agama; Islamicate mengacu pada fenomena sosial-kultural yang secara historis memiliki keterkaitan dengan Islam dan masyarakat Muslim, meski ditemui juga dalam masyarakat yang tidak beragama Islam; Islamdom mengacu pada masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya di mana Islam dan ajarannya tampil dominan. (Hodgson, The Venture of Islam , Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 57 – 60.
4 Burke berpendapat bahwa kritik Hodgson menjadi kurang menggigit karena posisi epistemologinya yang meletakkan peradaban sebagai sebuah unit analisis. (Edmund Burke III, “Introduction: Marshall G.S. Hodgson and World History”, dalam Marshall G. S. Hodgson dan Edmund Burke, Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History (Cambridge – New York : Cambridge University Press, 1993), xv)
5 Hodgson, The Venture of Islam , Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 60 – 62.
6 Marshall Hodgson, “Hemispheric Interregional History as an Approach to World History”, Journal of World History I, 3 (1954): 715-23; Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History”, 307.
7 Hodgson, The Venture of Islam , Vol 1, One:I, “The World before Islam”, 110. 8 Hodgson menjelaskan rentetan dan rangkaian masyarakat agraris berbasis kota
(agrarian citied societies) yang membentang di seluruh kawasan Afro-Eroasia (Afro-Eurasian), dari Tiongkok ke Eropa Barat. Semua jalur itu pada dasarnya memiliki karakter Asia. Oleh pakar sejarah bentangan kawasan ini disebut Oikoumene (Toynbee) atau Ecumene (McNeill). Bagi Hodgson, pendekatan historis interregional semacam itu lebih kuat argumentasinya, dari pada melulu menggunakan Barat sebagai pusat sejarah. Eropa Barat harus menunggu hingga abad 15, yang sebenarnya merupakan puncak perkembangan
3
tulisan lain dari Hodgson "Introduction to the Study of Islamic Civilization” yang menjadi pembuka untuk Volume Pertama The Venture of Islam.9
Di bawah ini akan dibuat uraian ringkas dua hal sebagai berikut: ‘kerangka metodologi sejarah Marshall G.S. Hodgson’ dan ‘kerangka teori sejarah Michel Foucault’. Dan sebagai penutup dari ‘Latar Belakang Masalah’ ini akan ditegaskan pernyataan singkat atas pertanyaan ‘Mengapa Topik Riset ini Penting?’
Kerangka kerja metodologi apakah yang sebenarnya digunakan oleh Hodgson dalam menulis sejarah dunia? Sejarah dunia hanya dapat dijelaskan secara memadai bila dimulai dengan proposisi bahwa sejarah manusia beradab ‘baca-tulis’ adalah sejarah Asia. Eropa tidak memiliki peran istimewa dalam hal ini. Dengan demikian, ‘sejarah dunia’ hanya pantas disebut sejarah dunia jika menjelaskan secara intensif ketergantungan dan interaksi satu sama lain dalam perkembangan lintas-regional. Maka sejarah yang ia tulis melukiskan persimpangan dan persilangan seni Helenistik, perkembangan matematika, corak-corak monastik India, dan perkembangan kerajaan Mongol.10 Dalam interkoneksi antar berbagai peradaban, Hodgson memberi makna dan nilai universal. Yaitu, bahwa semua manusia adalah saudara. Islam adalah satu bagian dari seluruh komunitas sejagad dalam sejarah. 11
Posisi moral Hodgson ini nampak jelas dalam tulisan, “The Islamic Heritage and the Modern Conscience.” Di dalamnya, ia menyampaikan keyakinannya akan kesatuan moral umat manusia di zaman moderen ini. Lebih lanjut, ia bertanya, “Apa yang bisa diambil dari warisan Islam bagi manusia yang hidup di zaman modern ini?”. Seluruh umat manusia berada dalam satu bahtera yang sama. Kesadaran ini menjadi urgen ketika berbagai moralitas di dunia moderen terpecah-pecah dan berserakan. Maka, ia berharap bahwa komunitas Islam mampu menjadi rumah bagi individu-individu dengan berbagai latar belakang kepercayaan dan agama di bawah nilai-nilai humanitas.12
Ada tiga pendekatan dan perspektif dalam sejarah Islam Hodson yang membuka peluang untuk menjelaskan historiografinya.
a. Memahami sejarah Islam dalam Logika Struktur dan Poststruktur. Strukturalisme memberi tekanan pada bahasa. Oleh karena itu, ia tidak
bermaksud untuk menjelaskan realitas, melainkan sistem makna. Poststrukturalisme
peradaban Afro-Eroasia. (Edmund Burke III, “Introduction: Marshall G.S. Hodgson and World History”, xvi)
9 Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 3 – 69.
10 Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History”, dalam Marshall G. S. Hodgson dan Edmund Burke, Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History (Cambridge – New York : Cambridge University Press, 1993), 309.
11 Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 30 - 34..
12 Greg Soetomo, “Sejarah Hubungan Islam dan Barat Menurut Marshall G.S. Hodgson. Interpretasinya untuk Ideologi Neoliberalisme”, Paper Akhir Mata Kuliah Contemporary Islamic World, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 (tidak diterbitkan)
4
masih menggunakan prinsip-prinsip dalam strukturalisme.13 Poststrukturalisme hendak memperlihatkan inkoherensi dalam sistem diskursus, sehingga pluralitas makna menjadi nyata. Poststrukturalis, dengan kecenderungan selalu melihat apa yang membuat berbeda, telah meninggalkan upaya untuk mencari ‘kebenaran universal’. Di sini humanisme tunduk pada struktur bahasa dan diskursus.
Kajian bahasa itulah yang akan digunakan untuk mendeteksi sejarah Islam Hodgson. Di dalam sejarah Islam, bahasa menjadi penentu manusia dalam mengungkapkan ide-ide mereka. Sejarah tidak ditentukan oleh satu peristiwa besar (perang, bencana) atau oleh keputusan mengagumkan dari raja, dinasti, pemimpin besar. Sejarah tidak digerakkan oleh subyek individual, melainkan oleh diskursus. Jadi, diskursus inilah yang justru membentuk subyek.
Unsur-unsur strukturalisme dan postrukturalisme ini nampak dalam beberapa ciri dan fenomena berikut. Pertama, sejarah Islam Hodgson yang dihasilkan lewat penggalian dokumen. Hodgson ia berlelah-lelah memulai karya besarnya itu dengan catatan metodologis puluhan halaman “Introduction to the Study of Islamic Civilization,” yang menjadi semacam syllabus of errors.14Arah besar The Venture of Islam adalah memperlihatkan kemungkinan cara baru menulis sejarah Islam. Klarifikasi yang dibuat oleh Hodgson sangat mengandalkan klarifikasi bahasa dan penjelasan diskursus. Di bawah judul “On making sense of Islamicate words, names, and dates”,15 misalnya, Hodgson melukiskan bagaimana kebudayaan Islamicate diungkapkan dalam berbagai bahasa tetapi terminologi dan praktiknya adalah sama.
Kedua, sejarah dalam perdebatan diskursus. Hodgson menempatkan Islam ‘di dalam’ (bukan ‘di luar’) konstelasi sejarah dunia pada umumnya. Beberapa pakar akan menganggap metodologi penulisan semacam ini berisiko. Penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat Islam tertelan dalam sejarah umum.16 Menjawab keraguan ini, Hodgson mulai dengan asumsi bahwa
13 Poststrukturalisme berbeda dari strukturalisme. Strukturalisme cenderung
menjelaskan koherensi sehingga makna bisa dijelaskan. Ia membedah bagaimana sebuah sistem membangun batas-batas agar bisa dipikirkan, bisa dikatakan, bisa dimaknai. Konsekuensinya, cara berpikir ini tidak jarang mereduksi perkara kompleks menjadi beberapa unsur. Upaya ini digunakan untuk menjelaskan kebenaran universal. Strukturalisme bersifat ‘anti-humanis’, karena struktur kerap mensistemkan cara berpikir dan cara pandang-dunia yang dimiliki manusia. (Clayton J. Whisnant, “Differences between the Structuralism and Poststructuralism”, A Handout for HIS, 389, http:// webs. wofford.edu/whisnantcj/his389/differences_struct_poststruct.pdf, (diunduh 6 Oktober 2013))
14 Prolegomena “Introduction to the Study of Islamic Civilization” dianggap sebagai tulisan yang pararel dengan karya Muqaddimah Ibn Khaldūn. Sebagaimana Ibn Khaldūn, langkah demi langkah, Hodgson memeriksa prinsip dan praktik yang menjadi framing dalam studi-studi sejarah sebelumnya. Tidak hanya kritis, ia menawarkan sebuah paradigma baru dalam merekonstruksi sejarah Islam. (Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 3 – 69.)
15 Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 3.
16 Albert Hourani (1915 – 1993), seorang sejarawan Islam raksasa di Oxford University, dalam ulasan yang luas membandingkan Hodgson dengan Ibn Khaldun. (Albert
5
Islam itu besar dan luas, dengan pengaruh yang mendalam. Ia menganggap Islam dengan ajaran dan ritualnya bukan hanya milik masyarakat Muslim saja. Penjelasanya mengenai Islamicate membuat para pakar harus merumuskan kembali secara lebih akurat apa itu yang disebut Islam dan Muslim.
Ketiga, peradaban sebagai diskursus. The Venture of Islam adalah sebuah karya intelektual yang dikerjakan dengan basis sejarah dunia. Penulisnya dengan sadar menenggelamkan dirinya dan berenang-renang di atas lautan peradaban Islam klasik. Ia meninggalkan ratusan halaman coretan-coretan sejarah dunia yang belum diselesaikan ketika ia wafat. Menurut Burke, The Venture of Islam pada dasarnya adalah textbook yang bertujuan untuk memperlihatkan prestasi manusia yang diraih dalam peradaban Islam. Di sana terungkap peradaban Islam sebagai bagian warisan manusia dan menjelaskan signifikansinya dalam sejarah dunia.17
b. Sejarah Islam Hodgson, Bahasa, dan Kekuasaan Bahasa menjadi alat penentu manusia dalam mengungkapkan ide-ide mereka
mengenai hidup dan pengalamannya. Menurut Foucault, karena bahasa selalu bersifat sosial, maka ia juga merupakan alat manusia untuk menyebarkan kekuasaan dan ikut membentuk struktur sosial. Definisi dan makna dari kata-kata dan konsep selalu memiliki pertautan dengan ‘fungsi kekuasaan’ dalam masyarakat. Bahasa, dengan demikian, selalu ideologis.
Setidaknya tiga konsep ada dalam cara pandang Hodgson yang menyentuh isu ini. Pertama, lahirnya kekuasaan dalam diskursus. Satu konsep yang paling penting yang dibuat oleh Hodgson dalam The Venture of Islam adalah penjelasannya yang panjang lebar mengenai Periode Pertengahan (Middle Periods). Dengan menggunakan frase Periode Pertengahan, Hodgson mengoreksi frase konvensional Abad Pertengahan (Middle Ages). Konsep yang terakhir ini adalah rekonstruksi sejarah Eropa-sentrisme yang menempatkan sejarah Islam di penggiran, bahkan di luar sejarah Eropa. Abad Pertengahan tidak menganggap sejarah Islam sebagai faktor penting sejarah kawasan ini. Periode Pertengahan ini membentang sejak pudarnya kejayaan kalifah Abbasiyah yang sangat sentralistik ini (945 CE) hingga lahirnya kerajaan ‘bubuk mesiu’ pada abad 16.18
Kedua, kekuasaan sebagai faktor penting dalam menalar sejarah. Fokus penulisan sejarah dunia Hodgson adalah menengok dan memeriksa kembali persyaratan sejarah Barat dalam konteks global. Ia mempertanyakan, dan kemudian membongkar ‘teleologi’ Eropa-sentris. Hodgson, dengan reputasi moral yang tinggi, menyampaikan sebuah tesis besar sejarah dunia demikian: “Sejarah Islam selama
Hourani, “Review: The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization by Marshall G. S. Hodgson.” Journal of Near Eastern Studies 37 (1) 1978: 53 – 62, dalam Steve Tamari, “The Venture of Marshall Hodgson”, 83.)
17 Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History”, 302. 18 Hodgson membahas panjang lebar Periode Pertengahan dalam Volume 2, “The
Expansion of Islam in the Middle Periods” dalam The Venture of Islam. Uraian sepanjang lebih dari enam ratus halaman dalam Volume 2 dibagi ke dalam Book Three (“The Establishment of an International Civilization”) dan Book Four (“Crisis and Renewal: The Age of Mongol Prestige”).
6
ini dipahami keliru, dan dianggap mengalami keterpurukan. Kedua pemahaman ini secara epistemologis dan emosional, disebabkan oleh karena dominasi Eropa-sentris dalam menulis sejarah dunia”.19 Proyek besar sejarah dunia dikerjakan Hodgson dengan menulis sejarah Islam sebagai latar belakang, dan memasukan ke dalamnya seluruh dokumentasi sejarah masyarakat universal.
Ketiga, kekuasaan di balik wacana modernitas. Satu sumbangan terpenting yang diberikan oleh Hodgson adalah penjelasannya mengenai periode sejarah modernitas dan tempat Eropa secara baru. Penjelasan kreatif ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan intelektualnya dalam mempelajari sejarah Islam. Ia menghapus (setidaknya, sebagian) posisi Barat ‘yang serba istimewa’ dalam teori modernitas. Kreativitas ini diungkapkan dalam penjelasannya mengenai “The Great Western Transmutation”,20 di mana ia menguraikan dimensi global dari proses perubahan kompleks sejak abad 18. Revisinya terhadap konsep akar-akar modernitas masih terus menjadi bahan diskusi hingga sekarang ini.
c. Sejarah Islam sebagai Rangkaian Keragaman Kerangka Berpikir Sejarah dekonstruksionis berpandangan bahwa sejarah adalah sistem
kompleks produk bahasa. Hodgson menulis dokumen dengan memilah dan memilih kata demi kata secara cermat dan dengan penuh kesadaran. Setiap era dalam sejarah memiliki episteme yang khas. Episteme atau struktur epistemologis ini mengkerangkakan cara berpikir sejarawan. Hal ini berimplikasi pada bagaimana pernyataan-pernyataan dirumuskan dan berbagai diskursus dibentuk. Sejarah Islam Hodgson memperlihatkan adanya tertib struktural, dengan segala perbedaan dan diskontinuitasnya.
Beberapa aspek pemikiran sejarah Hodgson menunjukkan konsep di atas. Pertama, kesatuan dan keragaman dalam diskursus peradaban. Hodgson menghadapi kesulitan melihat kenyataan betapa besar dan luas yang disebut ‘peradaban Islam’ itu. Bagaimana mungkin menjelaskan secara tepat sebuah peradaban ekumene Afro-Erosia yang membentang dari Maroko hingga Tiongkok, yang mengisi periode waktu hampir satu setengah milenium sejak abad tujuh hingga dewasa ini?21 Sebuah entitas kultural, menurut Hodgson, tidak bisa dijelaskan secara konklusif dalam hubungannya dengan sebuah peradaban. Sebagai contoh, hingga batas-batas tertentu, Islam memiliki kontinuitas relasional dengan tradisi Irano-Semitis. Tetapi, di lain pihak, diskontinuitas juga berlangsung di sana.22
19 Dibawah judul kecil “Islamicate Civilization as Human Heritage” Hodgson
memberikan posisi keyakinan itu. (Hodgson, The Venture of Islam, Vol. 1, “General Prologue: The Islamic Vision in Religion and in Civilization”, 95 – 99).
20 Esai ini pertama kali diterbitkan Chicago Today (1967): 40-50. Tulisan ini juga muncul dalam Rethinking World History (Bab 4) dan The Venture of Islam (Vol 3, Six, I: “The Impact of the Great Western Transmutation: The Generation of 1789”).
21 Satu tulisan Hodgson mendiskusikan persoalan ‘kesatuan’ ini, “The Unity of Later Islamic History”, dalam Marshall G. S. Hodgson dan Edmund Burke, Rethinking World History”, 171 – 206.
22 Sebagai satu ilustrasi, Hodgson menjelaskan bahwa dalam Periode Pertengahan, sosio-religius merupakan produk konteks dan kehidupan Irano-Semitis. Nilai-nilai Islam mendorong perpaduan dengan cita-cita kehidupan sosial. Di sini, Islam tidak hanya
7
Kedua, peradaban dan intelektualisme. Sejarah Hodgson tidak menggunakan filsafat politik dengan konsep waktu linear. Ia membawa pembaca ke dalam dunia di mana pola-pola historis dinyanyikan dengan tempo penuh kejutan. Hodgson membedakan dan menunjukkan adanya tiga tradisi intelektual yang beroperasi di zaman post-Axial23: Monoteisme Profetis, Tradisi Kebangsawanan Persia, serta Filsafat Yunani dan Ilmu Alam. Dengan kehadiran Islam, dalam perjalanan bersama, tiga tradisi ini membentuk sebuah formulasi baru.24
Ketiga, keutuhan yang retak. Bagi Hodgson keutuhan sejarah Islam harus diutamakan. Konsistensi ini digunakan untuk menjelaskan dialog terus-menerus antara komunitas Muslim dengan peradaban besar yang lain. Ada kelemahan akademis dan argumentatif dalam Buku 6.25 Hadirnya periode moderen, segera diikuti dan menjadi titik balik lenyapnya masa keemasan peradaban Islam. Dialog kultural berkelanjutan yang menjadi basis konsep Hodgson dalam menjelaskan argumentasinya mengalami kegoyahan dengan menyusupnya berbagai bahasa dan tradisi dalam wilayah ekumene. Sejak 1800, komunikasi di antara komunitas Muslim dan interaksi kebudayaan lintas-bangsa mengalami kesulitan.
Disertasi ini mencakup wilayah kajian historiografi dan filsafat sejarah
Islam. Sejarah Islam yang ditulis Hodgson akan dikaji dengan menggunakan teori L'Archéologie du savoir (1969; Arkeologi Pengetahuan) Michel Foucault (1926 - 1984). Marshall G.S. Hodgson (1922 - 1968) dan Michel Foucault (1926 - 1984)
beradaptasi, tetapi juga ikut mempengaruhi kebudayaan setempat. Dengan demikian, Islamicate di kawasan kebudayaan Irano-Semitis berlangsung karena sumbangan moralisme Islam. (Hodgson, The Venture of Islam, Vol 2, Three, VII: “Cultural Patterning in Islamdom and the Occident”, 340.)
23 Zaman Axial (Axial Age, Axis Age), sebuah frase yang diciptakan oleh Karl Jaspers (1883 – 1969) dalam Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949; The Origin and Goal of History), yang menandai periode kuno sekitar 800 – 200 BCE. Dalam rentang waktu ini, menurut Jaspers, lahir berbagai konsep cara berpikir baru filsafat dan agama di Persia, India, Tiongkok dan Yunani-Romawi secara hampir bersamaan, tanpa adanya kesinambungan dengan periode sebelumnya. (Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, One, I, “The World before Islam”, 112 - 113.)
24 Penjelasan Hodgson dalam bentuk grafik dan tabel akan segera memberikan gambaran konteks kultural dan intelektual di sekitar kelahiran Islam: “The Origins of Islamic Culture in Its World Context, 226 – 715” (Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, One, I, “The World before Islam”, 139; Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History”, 321 -322).
25 Ketika Hodgson meninggal pada 1968 (dalam usia 47 tahun), The Venture of Islam baru terdiri dari lima buku pertama. Volume Three, “The Gunpowder Empires and Modern Times”, khususnya “Book Six: The Islamic Heritage in the Modern World” adalah bagian tidak pernah diselesaikan. Tulisan-tulisan tersedia dalam rupa catatan tulisan tangan yang tercecer. Rekan kerjanya yang paling dekat Reuben Smith dengan penuh kesetiaaan mengumpulkan manuskrip yang masih tersisa dan berserakan. Catatan dan tulisan tangannya ini kemudian diterbitkan dalam wujud Buku 6 ini. Reuben Smith bekerja keras selama empat tahun mempersiapkan penerbitan The Venture of Islam (1974). (Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History, 302.)
8
hadir dan hidup dalam era yang hampir sama. Meski demikian, keduanya tidak pernah berkontak langsung. Tahun terbit L'Archéologie du savoir (1969) hampir menandai tahun ketika Hodgson wafat (1968). Keduanya menyandang sebagai pemikir yang serius pada masanya, dengan bacaan yang sangat luas. Meski keduanya bekerja di dua ranah keilmuan yang berbeda, mereka berdua memiliki titik temu (dan, titik pisah) karena hidup dan bergumul dalam zaman yang sama.
Bab awal buku L'Archéologie du savoir (1969) diisi dengan pengantar yang mempertanyakan asumsi bahwa sejarah adalah sejarah yang kontinu. Pertanyaan mendasar yang hendak diklarifikasi Michel Foucault adalah. mengapa penjelasan dan penulisan sejarah selalu berubah? Pertama, karena penjelasan sejarah dengan menggunakan metode empiris itu tidak memadai. Kedua, terkait dengan pertama, terbukti bahwa sejarah adalah bangunan diskursus naratif yang ditulis oleh para sejarawan. Dengan demikian, sejarah ada dan hidup dengan klaim untuk merepresentasikan aktualitas, kenyataan, dan peristiwa. Sejarah, tidak jarang, adalah interpretasi dari interpretasi sejarah lainnya. Sejarah adalah hasil interpretasi banyak sejarawan yang masing-masing mengklaim sejarahnya paling atau lebih akurat dan dekat realitas masa lalu yang dilukiskan. Dengan demikian, sejarah tidak tunggal. Ia berubah-ubah dan menjadi tidak pasti.26
Foucault mengeritik model pengetahuan ini. Ia menganggapnya kurang memperhatikan kompleksitas dalam diskursus. Studi sejarah pemikiran, dari satu periode ke periode lain, menurutnya, tidak bersifat transisional dalam kontinuitas, melainkan ‘keterpatahan’. Menurut Foucault, diskontinuitas adalah komponen integral dalam formasi diskursus. Sebagai pengganti dari sejarah pemikiran, ia mengajukan Arkeologi Pengetahuan.27
Pararel dan sejalan dengan tiga perspektif sejarah Islam Hodgson yang pokok-pokok pikirannya sudah diterangkan di atas, maka karya Foucault L'Archéologie du savoir juga memiliki tiga dimensi: strukturalisme-poststrukturalisme, postmodernisme, dan filsafat sejarah.
a. Strukturalisme-Poststrukturalisme. Karya-karya Foucault dianggap merupakan cerminan transisi dari filsafat strukturalisme ke poststrukturalisme.28
26 Alun Munslow, Deconstructing History (London-New York:Routledge, 1997) 34
– 35. 27 Pendekatan Foucault ‘sejarah sebagai proses diskontinu’ bisa dibandingkan
dengan gagasan dari Thomas Kuhn (1922 – 1996) tentang ‘paradigma’ atau Imre Lakatos (1922 – 1974) mengenai ‘program riset ilmiah’. Keduanya menganalisa norma-norma yang menggejala dalam berbagai aliran pemikiran, model-model teori masing-masing, serta teknik dan cara merumuskan asumsi-asumsinya. Ini semua adalah pergumulan ontologis dalam ilmu sejarah. (Scott J. Simon, “Paradigms, Presuppositions, and Information: Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions”, http://shell.cas.usf.edu/ ~simon/documents/ Paradigms.pdf (diunduh 28 Desember 2015); Imre Lakatos, “History of Science and Its Rational Reconstructions”, Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1970. (1970): 91-136, file:///C:/Users/gssoetomo/ Downloads/Lakatos%201970.pdf (diunduh 28 Desember 2015))
28 Warna poststrukturalisme terutama dalam metode genealoginya. Foucault menampilkan pendekatan poststrukturalis ketika ia membelokkan dan mengevaluasi kembali bahasa dalam teori pengetahuan.
9
Strukturalisme memberi tekanan pada bahasa. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud untuk menjelaskan realitas, melainkan sistem makna. Poststrukturalisme masih menggunakan prinsip-prinsip dalam strukturalisme.29 Poststrukturalisme hendak memperlihatkan inkoherensi dalam sistem diskursus, sehingga pluralitas makna menjadi nyata. Perbedaan dan keanekaragaman ini kerap menciptakan celah dan keterpatahan yang dapat mengoreksi sistem itu sendiri. Poststrukturalis, dengan kecenderungan selalu melihat apa yang membuat berbeda, telah meninggalkan upaya untuk mencari ‘kebenaran universal’.
Foucault membangun pemahaman baru mengenai sejarah sebagai proses keterpatahan, penyimpangan, dan kontingensi. Diskursus sejarah dalam pemikiran Foucault adalah proses yang tidak memiliki tujuan dan tidak beraturan. Sejarah ditandai dengan perubahan terus menerus dan karena proses reorganisasi diskursus tiada henti. Sejarah tidak ditentukan oleh satu peristiwa besar (perang, bencana) atau oleh keputusan mengagumkan dari raja, dinasti, pemimpin besar. Sejarah tidak digerakkan oleh subyek individual, melainkan oleh diskursus. Diskursus inilah yang membentuk subyek.
b. Postmodernisme. Foucault bisa dikategorikan ke dalam para
pemikir postmodernisme mengingat dua konsepnya: ‘diskursus’ (discours) dan ‘kekuasaan’ (pouvoir). Dua konsep ini menjelaskan karakter fenomena postmodern. Salah satu perspektif dari postmodernisme adalah menolak ‘Pencerahan’ (Enlightenment), yang ditandai dengan kebangkitan sains, rasionalitas, dan penyelidikan ilmu. Semangat Pencerahan kira-kira bisa diwakili dengan ungkapan terkenal dari Francis Bacon (1561 – 1626) Scientia Potentia Est (“Knowledge is Power’)30. Di dalam frase itu tersimpan makna, bahwa ketika orang bisa menjelaskan benda-benda (mengungkapkan fakta-fakta), maka orang mampu
29 Poststrukturalisme berbeda dari strukturalisme. Strukturalisme cenderung
menjelaskan koherensi sehingga makna bisa dijelaskan. Ia membedah bagaimana sebuah sistem membangun batas-batas agar bisa dipikirkan, bisa dikatakan, bisa dimaknai. Konsekuensinya, cara berpikir ini tidak jarang mereduksi perkara kompleks menjadi beberapa unsur. Upaya ini digunakan untuk menjelaskan kebenaran universal. Strukturalisme bersifat ‘anti-humanis’, karena sistem berperanan dalam menstrukturkan cara berpikir dan cara pandang-dunia yang dimiliki manusia. Di sini humanisme tunduk pada struktur bahasa dan diskursus. (Clayton J. Whisnant, “Differences between the Structuralism and Poststructuralism”, A Handout for HIS, 389, http://webs.wofford.edu/ whisnantcj/his389/differences_struct_poststruct.pdf, (diunduh 6 Oktober 2013))
30 Frase scientia potentia est (scientia est potentia, atau scientia potestas est) paling kerap disematkan pada Sir Francis Bacon (1561 – 1626). Meski demikian, rumusan yang ia buat sesungguhnya adalah ipsa scientia potestas est (knowledge itself is power), sebagaimana ditulis dalam Meditationes Sacrae (1597). Sementara frase scientia potentia est (knowledge is power) ditulis dalam Leviathan (1688) oleh Thomas Hobbes (1588 – 1679), yang pada waktu muda adalah sekretaris Bacon. Dokumen yang lebih muda sudah ditulis oleh Imam Ali (599-661 CE), yang tercatat dalam buku yang ditulis abad 10, Nahj Al-Balagha (Peak of Eloquence). Ia menulis, “Pengetahuan adalah kekuasaan dan ia bisa menuntut ketaatan. Orang berilmu mampu membuat orang lain taat. Ia dipuji dan dihormati. Ingatlah, pengetahuan adalah penguasa, sedangkan kesejahteraan adalah subyeknya”.
10
mengerjakan apa pun yang diinginkan dan mampu mengetahui apa yang terbaik. Foucault menolak ini.
Menjungkirbalikkan apa yang pernah dikatakan Bacon, Foucault mengatakan ‘kekuasaan adalah pengetahuan’. Mereka yang memiliki kekuasaan (sosial, politik, ekonomi) selalu mengambil keputusan yang diperhitungkan sebagai pengetahuan. Sejarah Foucault mengambil topik-topik yang terdengar ‘aneh’ (antara lain, penjara, klinik, seksualitas) dengan isi kisah yang berbeda dari apa yang biasanya kita dengarkan. Ia, pararel dengan pemikiran postmodernis, mempertontonkan bagaimana manusia tidak bisa dan tidak pernah bisa lepas dari rantai jerat kekuasaan. Kekuasaan adalah dimensi konstitutif dalam seluruh diskursus. Eksperimen Foucault, dengan mendalami sejarah berbagai perspektif, psikiatri, kedokteran, hukuman, dan kriminologi, serta lahirnya ilmu-ilmu humaniora, menjelaskan relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, yang kemudian menciptakan berbagai bentuk dominasi.31
c. Filsafat Sejarah. Arkeologi merupakan metode riset dan analisa
sejarah yang dikembangkan dan didalami Foucault. Ia menggali fenomena di masa lalu, membongkar jejak-jejak diskursus dalam periode-periode kritis dalam sejarah, dan kemudian merekatkannya kembali dengan cara baru. Foucault memperlihatkan bahwa setiap periode memiliki pola pernyataan terstruktur, yang terungkap dalam sebuah diskursus sistematis.
Setiap era dalam sejarah dan setiap stratum arkeologis, menurut Foucault, memiliki episteme yang khas. Episteme atau struktur epistemologis ini mengkerangkakan cara berpikir sejarawan. Hal ini berimplikasi pada bagaimana pernyataan-pernyataan dirumuskan dan berbagai diskursus dibentuk. Episteme ini seakan sudah terpateri dalam diri pikiran menjadi kesadaran yang tidak pernah dipertanyakan lagi. Arkeologi hendak memperlihatkan tertib struktural, dengan segala perbedaan dan diskontinuitasnya. Dengan kata lain, arkeologi pada dasarnya menarik garis batas perbedaan antara ‘hari ini’ dengan ‘yang lalu’.
Akhirnya, mengapa topik riset ini penting? Karena ia hendak
mengklarifikasi dan mengoreksi penulisan sejarah konvensional. Sejarah itu bukan sesuatu yang begitu saja mengalir, beraturan, kontinu, satu dan utuh, produk sebuah upaya rekonstruktif. Disertasi ini membuktikan, dengan pembalikan ke arah studi bahasa dalam ilmu sejarah, penulisan sejarah kovensional-empirisme ditinjau ulang dan perlu dikritik secara memadai. Karya tulis ini hendak mengambil peranan kritik tersebut. Caranya adalah dengan membuktikan bahwa analisa Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault mampu memperlihatkan dan menjelaskan pluralitas dan keanekaragaman makna dan pemikiran dalam sejarah Islam global sebagaimana ditulis oleh Marshall G.S. Hodgson. Dengan cara inilah penulisan sejarah konvensional perlu ditinjau ulang dan metodologinya diperbaiki.
31 Konsep ini sudah muncul dalam L'Archéologie du savoir (1969) (Foucault,
L'Archéologie, 240 – 243). Topik ini akan lebih kentara dalam dalam tulisan Foucault bertemakan genealogi kemudian
11
B. Permasalahan 1. Identifikasi Masalah Asumsi dan pemikiran dalam disertasi ini berbeda dengan teori dari penulis
lain. Perbedaan dan pertentangan dengan riset dan cara berpikir para pakar lain telah memberi peluang terbukanya berbagai permasalahan.
1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Pandangan Edward Said Marshal G.S. Hodgson (1922 – 1968) dan Edward Said (1935 – 2003),
meski tidak pernah bertemu dan kenal satu sama lain dan tidak pernah bertemu muka, mereka berdua memiliki persamaan dalam memandang peradaban Barat. Peranan strategis karya Edward Said, Orientalism32 (1978), adalah mengevaluasi hubungan sejarah Barat dengan dunia sekitarnya. Orientalisme, bagi Said, adalah perpanjangan hegemoni Eropa atas Timur Tengah, pada khususnya, dan, hegemoni Barat atas non-Barat, pada umumnya. Sebaliknya, meski menyadari adanya kelemahan ini, Hodgson tetap menggunakan pendekatan peradaban untuk menulis sejarah dunia.
Disertasi ini menunjukkan bahwa Hodgson meyakini setiap kritik mengandung apriori epistemologis. Setiap karya adalah produk ‘prakomitmen dari sang penulis’ (author’s precommitments). Prakomitmen ini menjadi ideologi yang mendasari proses memahami fenomena yang hendak disingkapkan. Pada saat yang sama, prakomitmen ini kerap kali menghalangi kemungkinan dan cara lain dalam memahami sebuah realitas.
1.2. Perbedaan dengan Sejarah Islam Ibn Khaldūn Marshall G.S. Hodgson, sebagai seorang sejarawan, memiliki beberapa
padanan sebelumnya, di antaranya adalah Ibn Khaldūn (1332 – 1406). Dalam The Venture of Islam, Hodgson memulai dengan prolegomena sepanjang 66 halaman, “Introduction to the Study of Islamic Civilization.” Pengantar ini kerap dibandingkan dengan Muqaddimah dari Ibnu Khaldun. Penjelasan Hodgson yang distingtif mengenai banyak perkara dalam kajian Islam33 membuat para pakar harus merumuskan kembali secara lebih akurat apa itu yang disebut Islam dan Muslim. Menurut Ibn Khaldūn, sejarah merupakan penjelasan dan pencerminan organisasi sosial dan pola-pola peradaban. Sejalan dengan Khaldūn, Hodgson menempatkan Islam ‘di dalam’ (bukan ‘di luar’) konstelasi sejarah dunia pada umumnya.
Beberapa pakar menganggap metodologi penulisan semacam ini berisiko. Penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan ini akan membuat Islam tertelan dalam sejarah umum. Menjawab keraguan di atas, Hodgson yang hidup lima abad sesudah Khaldūn menggunakan data dan fakta yang baru. Ia mulai dengan asumsi bahwa Islam itu besar dan luas, dengan pengaruh yang mendalam. Ia
32 Edward Said, Orientalism (London: Penguin, 1978). 33 Hodgson dalam Pengantar ini menjelaskan dan membuat klarifikasi di bawah
beberapa subjudul, antara lain, “On making sense of Islamicate words, names, and dates”, “Why transliteration?”, “Historical humanism”, “On defining civilizations”, “Islamics,Islamicist”, “Islamdom, Islamicate”, “Middle East, Nile to Oxus”.
12
menganggap Islam dengan ajaran dan ibadahnya bukan hanya milik masyarakat Muslim saja. Ia menciptakan kosakata Islamicate yang mendeskripsikan bagaimana Islam memberikan getaran sosial dan gerakan kultural dalam rupa tradisi yang sedemikian kuat ke lingkungan sekitarnya.
1.3. Berlawanan dengan Teori Esensialisme Dalam kajian peradaban dikenal terminologi esensialisme. Esensialisme
adalah basis dan sentral untuk kajian-kajian peradaban. Orientalisme memulai teks yang ditulisnya dengan praandaian bahwa peradaban memiliki berbagai esensi. Untuk memudahkan, misal, peradaban Islam dilihatnya sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan tragedi, sementara kebangkitan Barat sebagai sebuah kemenangan. Produk esensialisme tercermin dalam ekspresi Barat sebagai kisah kebebasan dan rasionalitas, sementara kisah Timur hanyalah berupa catatan-catatan kultural yang statis.34
Teori Hodgson dan Foucault, keduanya mengeritik orientalisme dan esensialisme. Dengan demikian, tesis dasar disertasi ini melawan teori esensialisme. Berbagai varian permasalahan bisa timbul dalam kajian ini.
Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa sejarah Islam Hodgson telah menimbulkan banyak kemungkinan permasalahan yang bisa dikaji. Disertasi ini hendak membatasi masalah kajian sebagai berikut.
2. Perumusan Masalah Berdasarkan ‘Pembatasan Masalah’ di atas, satu pertanyaan mayor yang
hendak dijawab dalam disertasi ini dirumuskan demikian: “Bagaimana Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault yang bertumpu pada analisa bahasa menjelaskan keanekaragaman dalam sejarah Islam Marshall G.S. Hodgson?”.
Pertanyaan mayor ini diuraikan ke dalam tiga pertanyaan minor di bawah. Tiga pertanyaan ini masing-masing mencerminkan tiga dimensi pemikiran Arkeologi Pengetahuan Foucault (strukturalisme-poststrukturalisme, postmodernisme, dan filsafat sejarah). Tiga dimensi ini juga pararel dengan tiga wujud ‘keanekaragaman’ yang disebut dalam pertanyaan mayor di atas, yaitu dalam struktur pemikiran, ideologi, dan kerangka berpikir. Tiga pertanyaan ini merupakan tiga alat pendekatan untuk menjelaskan historiografi sejarah Islam Hodgson.
Pertama, bagaimana Hodgson, dalam posisi strukturalis, menulis sejarah Islam dengan membangun sistem diskursus untuk menjelaskan sebuah makna;
34 Lihat antara lain, Afsin Matin-asgari, “Islamic Studies and the Spirit of Max
Weber: A Critique of Cultural Essentialism,” Critique: Critical Middle Eastern Studies, 13 (3) (Fall 2004): 293 – 312, http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/ 1066992042000300666?journalCode= ccri19 (diunduh, 15 Maret 2016); Tariq Modood, “Anti-Essentialism, Multiculturalism, and the ‘Recognition’ of Religious Groups”, The Journal of Political Philosophy: Volume 6, Number 4, 1998: 378 - 399 http://www.tariqmodood.com/ uploads/ 1/2/3/9/12392325/anti-essentialism.pdf (diunduh 24 Desember 2015); Anne Phillips, “What’s wrong with essentialism?”, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 11 (1), 2010: 47-60 (LSE Research Online: April 2012; https://core.ac.uk/download/files/67/216427.pdf, (diunduh, 29 Maret 2016)
13
tetapi pada saat yang sama, ia dalam posisi poststrukutralis memperlihatkan inkoherensi dalam sistem diskursus yang ditandai dengan pluralitas makna?
Kedua, bagaimana menjelaskan bahwa struktur sosial dalam sejarah Islam tidak pernah bisa lepas dari rantai kekuasaan yang adalah dimensi konstitutif dalam diskursus?
Ketiga, bagaimana membuktikan bahwa setiap era dalam sejarah Islam memiliki epistemenya masing-masing yang khas dan keanekaragaman cara berpikir yang mengkerangkakan terbentuknya pernyataan dan diskursus?
3. Pembatasan Masalah: Marshall G.S. Hodgson dan Michel Foucault Dalam disertasi ini, sejarah Islam sebagaimana dilukiskan Marshall G.S.
Hodgson hendak didalami dengan menggunakan pendasaran teoretis filsafat Michel Foucault. Marshall G.S. Hodgson (1922 - 1968) dan Michel Foucault (1926 - 1984) hadir dan hidup dalam era yang hampir sama. Meski demikian, keduanya tidak pernah berkontak langsung. Tahun terbit L'Archéologie du savoir (1969) hampir menandai tahun ketika Hodgson wafat (1968). Keduanya menyandang sebagai pemikir yang serius pada masanya, dengan bacaan yang sangat luas. Meski keduanya bekerja di dua ranah keilmuan yang berbeda, mereka berdua memiliki titik temu (dan, titik pisah) karena hidup dan bergumul dalam zaman yang sama.
Pernyataan ‘titik temu’ dan ‘titik pisah’ inilah yang hendak dibuktikan dalam disertasi ini. Permasalahan dan pertanyaan besar yang hendak dianalisa adalah sejauh mana analisa Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault mampu menjelaskan struktur pemikiran, ideologi, dan keanekaragaman kerangka berpikir dalam sejarah Islam global menurut Marshall G.S. Hodgson.
Penelitian ini membatasi tiga area permasalahan yang ‘hipotesis’ menjadi titik singgung antara sejarah Islam menurut Hodgson dan Arkeologi Pengetahuan Foucault. Tiga titik singgung terletak dalam dalam tiga dimensi pemikiran arkeologi Foucault, yaitu strukturalisme-poststrukturalisme, postmodernisme, dan filsafat sejarah.
Berdasarkan pembatasan masalah ini maka dirumuskan permasalahan yang digarap dalam disertasi ini. Perumusan masalah di bawah ini terdiri dari satu pertanyaan besar (mayor) dan tiga pertanyaan kecil (minor). Kesimpulan disertasi pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dibedakan
antara tujuan umum yang hendak menjawab pertanyaan utama, dan tiga tujuan khusus yang merupakan respon terhadap tiga pertanyaan penjelas.
1. Tujuan Umum Disertasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa analisa Arkeologi
Pengetahuan Michel Foucault memperlihatkan dan menjelaskan struktur pemikiran, ideologi, dan keanekaragaman kerangka berpikir dalam sejarah Islam global sebagaimana ditulis oleh Marshall G.S. Hodgson.
2. Tujuan Khusus
14
a. Mengeksplorasi komplekstitas sejarah Islam. Di satu sisi, dalam posisi strukturalis, sejarah Islam membangun sistem diskursus yang ketat untuk menjelaskan ‘makna’ dalam sejarah Islam; tetapi di sisi lain, dalam posisi poststrukutralis, kajian ini hendak memperlihatkan inkoherensi sistem diskursus yang berimplikasi adanya pluralitas struktur pemikiran.
b. Membongkar pendapat lama yang mengatakan bahwa ‘pengetahuan adalah pembawa kekuasaan’. Sebaliknya di sini hendak dianalisa bagaimana struktur sosial, sebagaimana tersusun dalam sejarah Islam, tidak pernah bisa lepas dari rantai jerat kekuasaan yang adalah pembentuk pengetahuan.
c. Menunjukkan realita pada level transedental, bahwa setiap era dalam sejarah Islam memiliki epistemenya masing-masing yang khas. Dengan demikian, pada setiap periode terdapat keanekaragaman cara berpikir dalam merumuskan pernyataan dan membangun diskursus.
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan Topik dan kajian disertasi ini menggali beberapa unsur dan aspek. Ia
mencakup, setidaknya, tiga kemungkinan sudut pandang berikut: sejarah Islam menurut Hodgson, relasi sejarah Islam dan sejarah dunia, dan historiografi sejarah Islam. Berbagai penelitian terdahulu yang relevan yang hendak dipaparkan di sini mengikuti unsur-unsur tadi.
1. Mengambil Inspirasi Hodgson Ira Lapidus (l. 1937), sejarawan Amerika, berhutang secara intelektual pada
pemikiran Hodgson. Ia mereproduksi beberapa peta dari The Venture of Islam. Karyanya A History of Islamic Societies (1988), mencerminkan banyak perspektif yang dibuat Hodgson. Lapidus membuat tiga teleskop untuk meneropong sejarah Islam: Pertama, kelahiran Islam dan munculnya masyarakat Islam; Kedua, periode panjang proses pertemuan Islam dengan berbagai kelompok lain, termasuk di dalamnya perkembangan dinasti-dinasti besar Islam; Ketiga, periode dominasi Eropa, menurunnya kekuatan ekonomi, dan nasionalisme pasca-kolonialis.35
A History of Islamic Societies, karya Ira Lapidus kerap dibandingkan dengan magnum opus dari Marshall G.S. Hodgson (1922 – 1968), The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization (1974). Keduanya menulis sejarah Islam dengan pendekatan ‘totalitas’.36 Hodgson dalam karyanya menjelaskan evolusi Islam dengan banyak membuat penekanan pada Islamdom dan
35 Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge University
Press, 2002), http://books.google.co.id/books?id= I3mVUEzm8xMC&pg =PR7&hl =id&source= gbs_selected_pages&cad= 3#v=onepage&q&f=false (diunduh 20 Pebruari 2014).
36 Azyumardi Azra, “Sejarah Islam Totalitas” dalam Historiografi Islam Kontemporer. Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 68 – 70.
15
Islamicate.37 Lapidus menulis dengan metodologi pendekatan yang berbeda. Ia menulis sejarah Islam ‘dialogis’. Sang penulis menggali interaksi simbol-simbol religius dengan realitas sehari-hari. Dari realitas inilah mengalir pertanyaan filsafat dan teologis mendasar: Apakah itu Islam? Bagaimana Islam bisa menyatukan masyarakatnya yang hidup di pelbagai belahan bumi dengan latar belakang yang beranekaragam tersebut?38 Tulisan Lapidus memiliki keunikan dalam metodologi penulisan sejarah. Terobosan penulisan sejarahnya terletak dalam pendekatannya untuk masuk ke dalam struktur sosial masyarakat, keluarga dan komunitas, tarekat dan kongregasi. Ia juga memeriksanya dari perspektif politik. Sudut pandang penulisan Lapidus berbeda dengan sejarawan lain yang melulu berbicara sejarah Islam sebagai sejarah kelompok elit dan berkuasa. Tidak hanya membeberkan mengenai dinasti, kerajaan, perang, ekspansi oleh satu rejim berkuasa terhadap sebuah bangsa, Lapidus melukiskan peradaban Islam lewat detil-detil pemikiran hukum, filsafat dan teologi, penjelasan bahasa, dan bahkan lewat keindahan berbagai karya seni.39
Dengan demikian pendekatan Ira Lapidus mencoba mengoreksi paradigma sejarah yang pada umumnya Middle-Eastern oriented, Islam yang identik dengan Arab. Pengamat mengatakan, Ira berhasil menggantinya dengan sejarah Islam dengan perspektif mondial. Bahkan, sejarah yang ditulis oleh Lapidus menjadi indikasi dan bukti luruhnya batas-batas antara Islam pusat dan Islam periferi.40
Selain Ira Lapidus, sejarawan lain, Francis Robinson (l. 1944),41 dari Inggris, menggunakan karya Hodgson sebagai sumber referensi untuk menyusun Atlas of the Islamic World since 1500 (1982). Karya yang disertai dengan disain menarik dengan gambar mewah memberi sketsa sejarah politik, ekonomi, dan religius dalam dunia Islam sejak periode moderen (dimulai tahun 1500), dalam relasinya dengan Barat. Meski menggunakan sumber Hodgson yang memiliki asumsi bahwa Islam adalah entitas yang berperan penting dalam mendefinisikan Barat, karya Robinson dianggap masih meletakkan Islam ‘di luar’ Barat.
Robinson dan Lapidus adalah contoh dua sejarawan yang terkesan dengan Hodgson tanpa harus lekat dan bergantung padanya. Keduanya meriset sejarah
37 Edmund Burke III, ’There is No Orient’: Hodgson and Said”, Presented to
American Historical Association Annual Meetings January 2008. Panel on Marshall Hodgson’s The Venture of Islam, https://escholarship.org/uc/item/8hg7g677#page-2 (diunduh 18 Oktober 2014)
38 Azra, “Sejarah Sosial Dialogis” dalam Azra, Historiografi Islam Kontemporer., 65 - 67.
39 Greg Soetomo, “Sejarah Politik Islam menurut Ira Lapidus: Kritik Historiografis”, Indo-Islamika, Vol. 4. No. 2 Juli – Desember 2014: 229.
40 Azra, “Revisionisme Historis Sejarah Umat Islam”, dalam Azra, Historiografi Islam Kontemporer, 62 – 64.
41 Riset Robinson, pengajar di Oxford University dan University of Washington, berfokus pada komunitas Muslim di kawasan Asia Selatan. Ia juga mengkaji bagaimana Islam merespon modernitas, perubahan politik. Ia telah menulis sejumlah buku, antara lain Atlas of the Islamic World Since 1500 (1982), Islam and Muslim History in South Asia (2000), The Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia (2001), The Mughal Emperors (2007), dan Islam, South Asia, and the West (2007).
16
Islam dunia. Disertasi ini tidak menulis sejarah Islam dengan versi atau paradigma lain dari apa yang sudah ditulis Hodgson. Ia menganalisa tulisan Hodgson itu sendiri. Analisa ini dilakukan dengan menggali diskursus atau wacana dalam tulisannya. Demikian pula, cara berpikir dan kerangka berpikir Hodgson dijelaskan.
2. Membandingkan Hodgson dengan Sejarawan lain Beberapa penelitian terdahulu mencoba membandingkan Hodgson dengan
Khaldun. Azyumardi Azra menjelaskan arti ‘totalitas’ dalam sejarah Islam, dengan membandingkan karya Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, dengan magnum opus dari Ibn Khaldūn, Kitābu l-ʻibar wa Diwānu l-Mubtada' wa l-Ħabar fī tarikhi l-ʻarab wa l-Barbar wa man ʻĀsarahum min Đawī Ash-Sha'n l-Akbār (Book of Lessons, Record of Beginnings and Events in the history of the Arabs and Berbers and their Powerful Contemporaries).42
Azra menjelaskan bahwa keduanya menulis dengan basis argumen sejarah Islam dan masyarakat Muslim dalam ‘totalitas’ peradaban manusia. Menurutnya, keduanya menulis sejarah Islam (kontemporer dan klasik) dengan menggunakan pendekatan general dan total history. Ibn Khaldūn, misalnya, menunjukkan pendekatan totalitas ketika ia menguraikan sejarah Islam dari segala perspektif: geografi, klimatologi, sosiologi, antropologi, etnologi, pedagogi, filosofi, astronomi – untuk menyebut beberapa saja.
Ibn Khaldūn (1332 – 1406), hampir tak terbantahkan, adalah sejarawan paling besar Muslim di era Klasik. Ribuan karya tulis, seminar, konferensi, kuliah terkait dengan tokoh dan isi pemikiran orang ini sudah diselenggarakan di berbagai belahan dunia. Magnum opus-nya yang diberi judul Muqqadimah (‘Pendahuluan’, Prolegomena), adalah karya raksasa yang berisi diskursus sejarah (Islam) universal yang tersusun dalam 6 (enam) bab.43
The Venture of Islam, dimulai dengan prolegomena sepanjang 66 halaman, “Introduction to the Study of Islamic Civilization.” Pengantar ini bisa dibandingkan dengan Muqaddimah dari Ibn Khaldun.44 Sebagaimana Ibnu Khaldūn, di abad 14, di Afrika Utara, Hodgson di abad 20 dengan latar belakang tradisi keilmuan Barat juga melakukan kritik terhadap tradisi intelektual yang sedang berlangsung. Hodgson, lapis demi lapis, menguliti kerangka kajian sejarah para Orientalis, dan memberikan paradigma alternatif untuk merekonstruksi sejarah Islam. Sebagaimana Muqaddimah, Hodgson menulis “Introduction” sebagai manifesto untuk meninjau kembali tidak saja pondasi sejarah Islam, tetapi sejarah dunia secara umum.
42 Azyumardi Azra, “Sejarah Islam Totalitas” dalam Azyumardi Azra,
Historiografi Islam Kontemporer. Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 68 – 70.
43 Topik dan isi dari enam Bab ini adalah sebagai berikut. Bab I: Geografi Fisik dan Manusia; Bab II:Kkehidupan Urban dan Pedesaan; Bab III: Negara dan Pengelolaannya; Bab IV: Kota-kota, Kejayaan dan Kehancurannya; Bab V: Ekonomi Masyarakat; Bab VI: Ilmu Pengetahuan, Klasifikasi dan Perkembangannya.
44 Steve Tamari, “The Venture of Marshall Hodgson: Visionary Historian of Islam and the World”, New Global Studies 2015; 9(1): 73–87 (76) (http://econpapers.repec.org/ article/bpjnglost/ v_3a9_3ay_3a2015_3ai_3a1_3ap_3a73-87_3an_3a7.htm, diunduh 23 Pebruari 2016)
17
Sambil menjelaskan kehidupan sosial berbagai bangsa dan komunitas, disertai dengan seribu satu aspek kehidupan manusia, Khaldūn memeriksa berbagai tulisan dan sumber sejarah yang tersedia pada zamannya. Ia mengeritik sumber-sumber sejarah yang tidak didasarkan pada fakta dan data. Dengan demikian, ia memberikan dimensi ilmiah baru untuk ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu ekonomi, pemikirannya yang lahir pada abad 14 ini dianggap melampaui zamannya. Buruh sebagai sumber kemakmuran, pembedaan antara sumber pendapatan langsung (pertanian, perdagangan, industri) dan tidak langsung (pekerja sipil dan swasta), adalah beberapa gagasan ekonominya.45 Historiografi universal Ibnu Khaldūn dianggap oleh beberapa pakar menjadi pondasi paling dasar metode dan riset sejarah.46
Edmund Burke III menyebut nama William McNeill dalam perbandingan dengan Hodgson.47 Lewat tulisannya The Rise of the West (1963)48, McNeill membuat inovasi dalam pelukisan sejarah. Tulisannya menyimpang dari pakem yang pada umumnya Eropa-sentris. Eksperimennya dikerjakan dengan mengoreksi penulisan sejarah tradisi Marxis, yang menggunakan abad 16 sebagai awal sejarah, yaitu menandai berlangsungnya kapitalisme. Tradisi Marxis menulis paradigma sejarah sebagai rangkaian peristiwa interaksi sosial-ekonomi manusia dan masyarakat. Ia melupakan pertukaran kultural dalam peradaban manusia. Para ilmuwan yang bisa dikategorikan menggunakan paradigma Marxis dalam penulisan sejarah adalah, antara lain, Immanuel Wallerstein (The Modern World System), Eric Hobsbawm (The Age of Revolution, 1789 - 1848), Eric Wolf (Europe and the People Without History), Andre Gunder Frank (World Accumulation, 1492 – 1789), dan Samir Amin (Unequal Development).
Menyimpang dari paradigma Marxis tersebut, McNeill meletakkan modernitas dalam konteks panjang sejarah manusia. Dalam tulisannya, ia memperlihatkan bahwa tempat dan posisi Eropa dalam sejarah selalu menyimpan problematika. Dalam tantangan dilematis inilah sumbangan Marshall G.S. Hodgson menjadi relevan. “On Doing World History” adalah sebuah ringkasan gagasan Hodgson mengenai bagaimana sejarah dunia ditulis. Paper ini juga merupakan kritik terhadap buku William McNeill The Rise of the West.49
45 Salah Zaimeche, “A Review on Early Muslim Historians”, Muslim Historians,
November 2001: 7-8. 46 Antara lain dikatakan oleh J. de Somogy, “The Development of Arab
Historiography” dalam The Journal of Semitic Studies, Vol 3: 373 – 387; R.S. Humphreys, Muslim Historiography. Dictionary of the Middle Ages, New York: Charles Scribners and Sons, Vol. 6: 250-255.
47 Edmund Burke III, “ Introduction: Marshall G.S. Hodgson and World History”, ix – x.
48 William McNeill, The Rise of the West: A History of the Human Community (Chicago: The University of Chicago Press, 1963)
49 Tulisan ini sebenarnya sebuah ekstrak dari suratnya yang ditujukan pada John O. Voll (University of New Hampshire, 16 Desember 1966). Hodgson adalah seorang dengan kebiasaan menulis surat yang panjang. Tidak sedikit gagasan-gagasan penting muncul dari suratnya, antara lain gagasan yang tertuang dalam “The Unity of World History”, yang semula tertulis dalam sebuah surat pada 1941.
18
Disertasi ini hendak meneliti topik yang lain. Ia tidak membandingkan Hodgson dengan sejarawan lain. Meski Foucault, bisa dianggap sebagai sejarawan, peranan pemikirannya bukanlah pembanding. Filsafat sejarah Foucault di sini digunakan memberikan ‘kerangka teori’ untuk menjelaskan dan menggali problematika tulisan sejarah Islam Hodgson.
3. Hodgson dan Kajian Sejarah Islam Global John Obert Voll (l. 1936), dalam “Islam as a Special World-System”
(1994), dua puluh tahun setelah terbitnya The Venture of Islam (1974), menjelaskan kembali secara lebih moderen posisi Islam dalam dunia global dengan menggunakan teori sistem-dunia (world-system).50
Voll memulai eksplorasi gagasannya dengan mengidentifikasi ‘Islam’. Ia mendata bahwa ‘Islam’ kerap dipertukarkan dengan berbagai identitas, sebagai ‘agama’, ‘peradaban’, ‘jalan hidup’, dan beberapa lainnya. Gejala ini, menurut Voll, disebabkan karena para islamisis menggunakan terminologi ini untuk berbagai fenomena. Sambil mengutip Hodgson, Voll mengatakan bahwa Islam, Islamic, Islamdom, dan Islamicate kerap digunakan dan dipertukarkan untuk menyebut agama, masyarakat, dan kebudayaan secara longgar, dalam kaitan dengan sejarah.51 Kebingungan ini nampak ketika Islam sebagai ‘agama’ ternyata digunakan pada saat yang sama untuk ‘peradaban Islam’.
Memperhitungkan segala kerancuan di atas, Voll mengajukan satu usulan. Dengan berlangsungnya perubahan sosial dalam skala global, maka berlangsung pula penjelasan baru terhadap peradaban. Peradaban Islam di bawah dunia global kontemporer dan di bawah penjelasan konsep sistem-dunia (world-system) menjadi larut di dalamnya. Teori sistem-dunia yang diperkenalkan Immanuel Wallerstein (l. 1930), digunakan oleh Voll untuk menjelaskan entitas Islam global. Konsep ini sudah dikembangkan oleh beberapa pemikir sebagai basis dan perspektif untuk menjelaskan berbagai realitas.52
Pengalaman dan kesaksian Ibn Baṭūṭah (1304 – 1368/69) mewakili satu dimensi yang disebut sistem-dunia. Ia tidak paham dengan bahasa-bahasa lokal dari tempat-tempat yang ia singgahi. Meski demikian, ia tetap bisa memahami bahasa kultural berbagai komunitas Muslim yang ia masuki. Untuk itulah ia merasa kerasan di setiap titik perhentiannya sebagai seorang musafir dunia. Sistem-dunia di sini selalu didasarkan pada sebuah diskursus. Jadi pergerakan Ibn Baṭūṭah adalah perjalanan di bawah komunitas diskursus global.53
50 John Obert Voll, “Islam as a Special World-System”, Journal of World History,
vol. 5, no. 2 (1994): 213 – 226 (http://www.uhpress.hawaii.edu/ journals/jwh/ jwh052p213.pdf, diunduh 4 Januari 2016)
51 Hodgson, The Venture of Islam, Vol 1, “Introduction to the Study of Islamic Civilization”, 57 - 60.
52 Samir Amin, “The Ancient World-Systems versus the Modern Capitalist World-System,” Review 14 (1991): 349–85; Andre Gunder Frank, “A Theoretical Introduction to 5,000 Years of World System History,” Review 13 (1990): 155–248; Immanuel Wallerstein, “World-Systems Analysis: The Second Phase,” Review 13 (1990): 287–93.
53 Voll, “Islam as a Special World-System”, 224 – 225.
19
Fenomena yang sama dapat dilihat ketika umat Muslim berziarah ke Makkah. Mereka berbondong-bondong dan mengekspresikan iman mereka. Ini merupakan entitas universal yang melampaui peradaban partikular dari mana mereka berasal. Di Makkah, selama ibadah haji, umat Muslim yang berkumpul merasakan ‘kesamaan diskursus’. Pengalaman yang mirip dengan Ibn Baṭūṭah ketika ia berkelana ke pelbagai belahan dunia Muslim di abad 14.
Islam sebagai sistem-dunia mempertontonkan kekuatannya ketika di zaman kapitalisme mulai menggurita di abad 16. Pada saat itu para pedagang, guru dan ulama Sufi mampu menarik orang-orang di Afrika dan Asia Tenggara untuk memeluk Islam. Kekuatan kultural-religius mereka, dalam kasus di Kepulauan Nusantara, mampu melampui kekuatan ekonomi politik Pemerintahan Belanda.54
Tekanan tulisan Voll, mengikuti konsep sistem-dunia Wallerstein, adalah menjelaskan pengaruh praktik kapitalisme. Meski demikian, ia mencoba untuk melampaui paradigma kapitalisme ini dengan menggunakan gagasan diskursus dalam sistem dunia. Komunitas Muslim sejagat tidak hanya berinteraksi lewat pertukaran barang-barang ekonomis, tetapi juga lewat pertemuan diskursus kebudayaan dan agama. Dengan demikian, meski sistem-dunia Islam sangat dipengaruhi oleh kapitalisme, namun yang pertama tidak pernah bisa hanyut oleh yang kedua.
Voll menggunakan kosakata kunci yang sama dengan Foucault, yaitu ‘diskursus’. Meski demikian, keduanya menggunakan dan memahami kata yang sama ini dengan cara dan makna yang berbeda. Disertasi ini mencurahkan makna diskursus dalam Arkeologi Pengetahuan, yang memiliki penjelasan yang berbeda dengan diskursus sebagaimana dijelaskan oleh Voll.
4. Memanfaatkan Teori Hodgson ‘Islam sebagai Penghubung’ Edmund Burke III mengeksplorasi topik “Islam at the Center:
Technological Complexes and the Roots of Modernity”.55 Dengan asumsi bahwa peradaban Islam adalah pewaris peradaban-peradaban Timur Tengah, maka peradaban Islam memiliki peranan ‘pembawa’ pengetahuan-pengetahuan kuno ke alam pemikiran Barat. Demikian, Burke meringkaskan gagasan “Islam at the Center”.
Dalam penelitiannya, Burke memeriksa bagaimana dan mengapa benih-benih teknologi pada dasarnya disebar dan menjadi jelas wujudnya pada periode 1000 – 1500 C.E. Penemuan dan penciptaan ini merupakan proses berkesinambungan sangat panjang, sejak 3000 BCE hingga 1750 CE. Perjalanan lima milenia ini disebut ‘sejarah dinasti agraria’. Dalam periode ini berlangsung perkembangan dari teknologi praktis individual, kemudian berakumulasi semakin canggih menjadi teknologi komunal, lokal dan regional. Akhirnya, sejak abad 7,
54 Voll, “Islam as a Special World-System”, 225. 55 Edmund Burke III, “Islam at the Center: Technological Complexes and the Roots
of Modernity”, University of California, Santa Cruz, Journal of World History, June 2009: 165 – 186, http://classroom.ldisd.net /users/0011/ Islam%20at%20the%20Center%20 Technology%20Complexes%20and%20Modernity.pdf (diunduh, 11 Januari 2016)
20
fenomena ini menyatu dalam Islam dan kemudian tersebar ke pelbagai penjuru dunia.56
Para sejarawan dunia Islam, terutama Marshall Hodgson, dalam The Venture of Islam, menyampaikan seruannya bahwa Islam adalah sentral untuk menjelaskan kebangkitan modernitas. Mengutip pernyataan Hodgson, Burke menulis, “Islam adalah pewaris kebudayaan antik di kawasan Indo-Mediterania”.57 Islam menjadi titik temu dan titik simpang gagasan dan kebudayaan (termasuk, teknologi) dengan segala bentuknya. Di tengah-tengah titik pertemuan Asia, Afrika, dan Mediterania, Islam tetap memiliki kekayaan kultural dan institusional yang khas. Ia juga memberikan sumbangan yang khas terbentuknya teknologi dan pengetahuan baru.
Pada masa pra-Islam, wilayah ‘Nil-ke-Oxus’ adalah palungan timbul tenggelamnnya kerajaan, dinasti, dan agama-agama. Hodgson mencatat bahwa agama-agama monoteistik Asia Barat (Judaisme, Kristianitas, Zoroaster) kerap memainkan peranan sebagai benteng moral pengeritik kekuasaan dan militer. Gejala yang mirip juga berlangsung di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Islam dibangun dalam konteks seperti itu.58
Beberapa abad setelah lahir di Arab, Islam menjadi agama untuk masyarakat agraris dan komunitas gembala di pusat Eroasia. Islam memainkan peranan penyambung jalur sutra di Asia. Ia menghubungkan kawasan Mediterania dengan Tiongkok dan India, dan juga wilayah Lautan India. Pada abad 10, Islam melakukan penetrasi ke Afrika Barat lewat jalur karavan Gurun Sahara. Ringkasnya, geografi Islam ada di sentral yang memerankan ekspansi interkomunikasi lintas Afro-Eroasia.
Tidak terhindarkan, disertasi yang membahas Hodgson ini juga memberi tekanan Islam pada posisi ‘sentral’ dan penghubung.59 Tetapi karya tulis ini tidak
56 Nurcholish Madjid, mengutip Hodgson, menyebutkan beberapa kata Arab dalam
dunia Teknologi yang menjadi petunjuk bahwa dunia Muslim sudah sejak lama ikut berperanan dan memberi pengaruh di dalamnya. Madjid menyebutkan beberapa kata antara lain, admiral, alchemy, alcohol, azimuth, elixir, henna, nadir, saffron dan sebagainya. (Nurcholish Madjid, “Akar Islam: Beberapa Segi Budaya dan Kemungkinan Pengembangannya bagi Masa Depan Bangsa”, dalam Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2013), 89)
57 Hodgson, The Venture of Islam, Vol. 1, One:I, “The World before Islam”, 125, 130, 137 – 138.
58 Edmund Burke III, “Islam at the Center”, 165 – 166. 59 Dalam konteks lain, ‘Islam sebagai Penghubung’ bisa ditemukan dalam
penelusuran Majid Fakhry, A History Islamic philosophy (2004). Penelusuran sejarah filsafat Islam oleh Majid Fakhry, sejak abad 7 hingga era kontemporer, memperlihatkan adanya kesatuan dan kontinuitas pemikiran Islam sejak sejarah Islam paling awal hingga pemikiran dewasa ini. Ia mengawali penelusuran sejarah filsafat Islamnya dengan mendiskusikan warisan pemikiran Timur Dekat (Alexandria) abad 7. Penulis juga menganalisa pengaruh filsafat Pra-Sokratik dan sesudahnya (Plato dan Aristoteles serta Neo-Palatonis), serta pemikiran Persia dan India. Kemudian, setelah mendiskusikan ratusan halaman nama-nama besar seperti, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Al-Ḥallāj, Ibn Rushd, Al-Suhrawardī, hingga 'Abdul-Wahhab, sang penulis membawa pemikiran-pemikiran awal Islam ini ke pemikiran modern dan kontemporer. Majid Fakhry memperlihatkan kesatuan
21
menjadikan topik tersebut sebagai paradigma. Analisa dalam tulisan ini bukan pada sejarah pemikiran, melainkan pada ‘pemikiran sejarah’. Analisa pemikiran sejarah ini menggunakan analisa diskursus (wacana).
5. Memperdebatkan Hodgson Pada 28 Mei 2013, Sir Christopher Bayly menyampaikan ceramah pada
serial Humanitas Lecture di bidang historiografis, dengan topik “Marshall G S Hodgson, Islam and World History”. Pada saat yang sama diundang pula Faisal Devji sebagai penanggap.60 Christopher Bayly61 dari Cambridge University mengeritik keras Hodgson. Dalam forum ini, ia menganggap bahwa Hodgson, seorang vegetarian dan pacifist, yang mempunyai agenda tersembunyi. Ia menggunakan suara Islam dan Dunia Islam sebagai pengganti dan nama lain untuk Dunia Ketiga. Sebagai seorang sejarawan, Hodgson dianggap memanfaatkan suara komunitas Muslim, mengolah argumen-argumen Islam untuk menopang proyeknya dalam melawan kapitalisme. Bayly mengeritik Hodgson yang sebenarnya sedang mengkampanyekan ide-ide kuasi-sosialisme.
Dalam forum yang sama, Faisal Devji dari University of Oxford menolak pendapat Bayly. Devji membela dan memuji Hodgson yang membuat model alternatif, menyusun peta sejarah baru, dengan menempatkan Islam di antara Eropa dan India. Ia menghargai Hodgson sebagai seorang moralis yang membela kaum pinggiran. Ia berasumsi, monograf yang ditulis Hodgson, The Secret Order of Assassins (1955), adalah karya awal yang menjadi pelatuk dan pemberi arah proyek The Venture of Islam. Meski Devji mengeritik tema-tema yang memberi tekanan dan pujian berlebihan pada Persia di volume tiga dalam buku itu,62 ia tidak setuju dengan ‘serangan murahan’ yang disampaikan oleh Bayly. Ia mendukung perjuangan dan pilihan moral dalam karya Hodgson ini.
dan kesinambungan sejarah panjang filsafat Islam dan aspek-aspek kulturalnya, dengan pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, sekularisme, eksistentialisme, Marxism dan postrnodernism. (Bdk Majid Fakhry, A History Islamic Philosophy (New York: Columbia University Press, 2004)
60 Lihat video “Marshall G S Hodgson, Islam and World History”, University of Oxford, http://podcasts.ox.ac.uk/marshall-g-s-hodgson-islam-and-world-history (diunduh, 28 Desember 2015)
61 Sir Christopher Alan Bayly, FBA, FRSL (l. 1945) adalah sejarawan Inggris dengan spesialisasi kajian dalam topik-topik Imperialisme Inggris, India, dan sejarah dunia global.
62 Volume 3 The Venture of Islam yang terdiri dari Buku Five dan Six ini merupakan teks yang diedit secara besar-besaran setelah penulisnya meninggal. Ketika Hodgson meninggal dalam usia 47 tahun (1968), The Venture of Islam yang sudah dikerjakan lebih dari sepuluh tahun, baru selesai dua pertiganya. Rekan kerjanya yang paling dekat, Reuben W. Smith dengan penuh kesetiaaan mengumpulkan manuskrip yang dicatat dalam tulisan tangan dan kemudian menerbitkannya. “Kata Pengantar” dari Smith dalam The Venture of Islam, memberi kesan bahwa ia sangat (dan terlalu hati-hati) dalam upaya mempertahankan dan menjaga gaya penulisan Hodgson. Beberapa orang menganggap keaslian corak tulisan Hodgson tetap terjaga meski sentuhan Smith ada di sana. (Edmund Burke, III, “Conclusion: Islamic History as World History, 302.)
22
Tulisan ini pertama-tama tidak bermaksud memperdebatkan Hodgson, meski di dalamnya ada analisa dan kritik. Substansi dan isi pemikiran Hodgson bukan subyek kajian utama. Yang menjadi kesibukan disertasi ini adalah analisa wacana. Dalam banyak hal, pusat kajian karya tulis ini adalah nalar dan logika dalam bahasa sebagaimana dijelaskan Foucault.
6. Kajian Michel Foucault dan Islam Satu tulisan oleh Ulrika Mårtensson, “The Power of Subject: Weber,
Foucault and Islam”63, mengeksplorasi hubungan antara Michel Focault (dan Max Weber) dengan Islam.
Mårtensson memulai observasinya dengan merujuk tulisan Afsin Matin-asgari64, “Islamic Studies and the Spirit of Max Weber: A Critique of Cultural Essentialism,” yang mengeksplorasi wacana ‘kulturalisme’. Hipotesa Matin-asgari adalah menanggapi pandangan yang mengatakan diskursus kebudayaan sebagai alasan dan penyebab politis yang mengkonstruk ‘kebudayaan Islam’. Matin-asgari hendak mengoreksi pandangan bahwa kebudayaan Islam itu memiliki karakter anti-modernitas dan bersifat fundamentalis. Berangkat dari teori terakhir ini, para sarjana dan teoretisi kebudayaan menganggap bahwa kebangkitan fundamentalisme Islam adalah produk otomatis sejarah dan kebudayaan Islam.
Dalam upaya kritik terhadap pendekatan kulturalis di atas, Matin-asgari menelusuri jejak-jejak wacana yang dikembangkan sejak Max Weber (w. 1920) mengenai sosiologi interpretatif (verstehende Soziologie) dan ‘tipe Islam’, sejarawan Islam global Marshall G.S. Hodgson (w. 1968), antropolog simbolis Clifford Geertz (w. 2006), hingga pemikir dan antropolog sosial Ernest Gellner (w. 1995).
Matin-asgari mengeritik para kulturalis yang etnik-sentris. Pendekatan ini mencerminkan sebuah paradigma pemahaman bahwa analisa ini mewakili cara berpikir ‘modernitas’. Semua analisa ini bisa digunakan untuk menjelaskan perkembangan yang berlangsung di semua negara Islam. Ia mengeritik cara berpikir ini dan mengembangkannya menjadi kritik kajian Islam secara umum.
Mårtensson, lewat kritik terhadap riset Matin-asgari di atas, hendak melampaui pengandaian-pengandaian epistemeologi ‘kulturalisme’ di atas. Ia menggali lebih dalam hubungan Weber dan Foucault serta problematika etnosentrisme. Dengan menjelaskan konsep hubungan ‘kebenaran’ dan ‘kekuasaan’ dua pemikir ini, ia menerapkan metodologinya untuk kajian Islam. Ia mengembangkan metodologi analisa-diskursus (discourse-analytical methodology) sehingga etno-sentrisme dapat dijelaskan baik lewat subyektivitas dan obyektivitas,
63 Ulrika Mårtensson, “The Power of Subject: Weber, Foucault and Islam”,
Critique: Critical Middle Eastern Studies, Vol. 2 No 2, Summer 2007: 97 – 136, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10669920701378853 (diunduh, 15 Maret 2016)
64 Afsin Matin-asgari, “Islamic Studies and the Spirit of Max Weber: A Critique of Cultural Essentialism,” Critique: Critical Middle Eastern Studies, 13 (3) (Fall 2004): 293 – 312, http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/ 1066992042000300666?journalCode= ccri19 (diunduh, 15 Maret 2016)
23
dan sintesa antara keduanya. Michel Foucault (w. 1984), dalam pandangan Mårtensson, adalah contoh yang paling nyata seorang Weberian yang menggunakan pendekatan kultural.
Meski menggunakan pemikiran analisa diskursus Michel Foucault, disertasi ini berbeda dengan Matin-asgari dan Mårtensson. Disertasi ini menggunakan diskursus dengan cara berbeda. Ia tidak menggunakannya sebagai analisa kultural, melainkan sebagai analisa arkeologi dan bahasa untuk menjelaskan historiografi Islam.
Setelah melewati ziarah penelitian terdahulu atas topik-topik Hodgson di
atas, disertasi ini memiliki posisi yang unik dan berbeda dalam beberapa hal. Pada level abstraksi dan transedental, disertasi ini menunjukkan realita yang selama ini tidak diperhatikan oleh banyak sejarawan. Yaitu, setiap era dalam sejarah Islam memiliki epistemenya masing-masing yang khas, dengan demikian di sana terdapat keanekaragaman cara berpikir dalam merumuskan pernyataan dan membangun diskursus.
Eksplorasi ini akan menjelaskan bahwa, dalam posisi strukturalis, sejarah Islam membangun sistem diskursus yang ketat untuk menjelaskan ‘makna’ dalam sejarah Islam; tetapi pada saat yang sama, dalam posisi poststrukutralis, kajian ini juga hendak memperlihatkan inkoherensi sistem diskursusnya yang berimplikasi adanya pluralitas makna. Selain itu, disertasi ini hendak membongkar pendapat lama yang mengatakan bahwa ‘pengetahuan membawa kekuasaan’, sebaliknya di sini hendak dianalisa bagaimana manusia, sebagaimana tersusun dalam sejarah Islam, tidak pernah bisa lepas dari rantai jerat kekuasaan yang adalah pembentuk pengetahuan.
E. Manfaat dan Signifikansi Penelitian Dengan memperhatikan beberapa perspektif disertasi di atas, dari ‘latar
belakang masalah’ hingga posisi disertasi di tengah-tengah penelitian yang lain, manfaat dan signifikansi penelitian ini adalah:
1. Penelahaan sejarah Islam dengan menggunakan analisa diskursus belum serius dikerjakan. Sementara kajian ini sangat penting untuk memahami sejarah Islam dengan lebih kritis.
2. Kalangan terpelajar akan mendapatkan pengetahuan sejarah Islam global dan total yang ditulis secara kreatif. Sekaligus, memperoleh pemikiran alternatif dalam metodologi dan historiografi penulisan sejarah disampaikan di sini.
3. Para peminat sejarah akan memperoleh sudut pandang baru. Studi peradaban Islam hendak memeriksa kembali sejarah Eropa, membongkar berbagai asumsi keistimewaan yang selama ini ada di dalamnya, dan meletakkan proses tahap demi tahap perkembangannya ke dalam konteks sejarah dunia.
F. Metodologi Penelitian
24
Metodologi penelitian menjelaskan beberapa konsep teoretis yang digunakan dalam riset ini. Kemudian, dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Dengan demikian, metode-metode teknis yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan untuk mendukung dan mengimplementasikan metodologi penelitian yang dijelaskan teoretis.
Metodologi penelitian ini pada prinsipnya menjelaskan tiga pendekatan dan kerangka berpikir Hodgson dalam penulisan sejarah Islam. Pada saat yang sama pemikiran filsafat Foucault juga diuraikan dalam tiga perspektif. Keduanya, secara metodologis dan substantif, memiliki titik temu dan titik pisah, yang menjadi bahasan seluruh kajian disertasi ini. Titik temu tersebut dapat diringkaskan dalam penjelasan atas satu permasalahan: Bagaimana analisa Arkeologi Pengetahuan Michel Foucault menjelaskan struktur pemikiran, ideologi, dan keanekaragaman kerangka berpikir dalam sejarah Islam global Marshall G.S. Hodgson.
Metodologi di atas, sangat dekat dengan metode postpositivisme-rasionalistik, sebagaimana kategori yang dibuat dan dijelaskan Noeng Muhadjir. Ia menguraikan metode ini dengan menunjukkan beberapa elemen sebagai berikut:65
1. Pola berpikir rasionalistik dan logis, 2. Konseptualisasi teoretis, 3. Perumusan grand concepts sebagai landasan penelitian, 4. Penarikan kesimpulan dan pemberian makna. Dengan memanfaatkan metode postpositivisme rasionalistik di atas, titik
temu antara Michel Foucault (Arkeologi Pengetahuan) dan Marshall G.S. Hodgson (sejarah Islam global) diupayakan dalam riset ini. Titik temu yang dirumuskan dalam satu pertanyaan mayor di atas dijabarkan dalam tiga problematika yang spesifik berikut ini. Tiga problematika ini pararel dengan tiga pertanyaan minor yang disebutkan dalam Perumusan Masalah.
Pertama, problematika bagaimana Hodgson dalam posisi strukturalis membangun sistem diskursus yang ketat untuk menjelaskan ‘isi pemikiran’ dalam sejarah Islam, tetapi pada saat yang sama, dalam posisi poststrukutralis, tulisannya juga memperlihatkan inkoherensi sistem diskursusnya yang berimplikasi adanya pluralitas makna. Sejarah ditandai dengan perubahan terus menerus dan karena reorganisasi diskursus tiada henti. Sejarah di sini tidak digerakkan oleh subyek individual, melainkan oleh diskursus yang membentuk subyek.
Kedua, problematika manusia dari perspektif postmodernisme. Stuktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Hodgson dalam sejarah Islam, tidak pernah bisa lepas dari rantai jerat kekuasaan atau ideologi yang adalah dimensi konstitutif dalam diskursus. Kekuasaaan bekerja lewat dan di dalam diskursus. Kekuasaan adalah ‘pengetahuan’. Di sini, postmodernitas mendapatkan batasan-batasannya dalam
65 Karakteristik utama aktivitas riset postpositivistik, menurut Muhadjir, adalah
mencari dan menjelaskan makna di balik data. Ia memiliki empat macam metode: rasionalistik, phenomenologis-interpretatif, postpositivisme teori kritis, dan postpositivisme meta-etik. (Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 79 – 87).
25
‘diskursus’, sementara ‘diskursus’ diintepretasikan lewat ‘kekuasaan’ atau ‘ideologi’.66
Ketiga, problematika bahwa setiap era dalam sejarah Islam memiliki epistemenya masing-masing yang khas. Dengan demikian di sana terdapat keanekaragaman ‘kerangka berpikir’ dalam merumuskan pernyataan dan membangun diskursus. Dalam tulisan sejarahnya, Hodgson membongkar jejak-jejak diskursus dalam periode-periode kritis. Kemudian, ia merekatkannya kembali dengan cara baru. Ia memperlihatkan bahwa setiap periode memiliki pola pernyataan terstruktur, yang terungkap dalam sebuah diskursus sistematis.
Data, informasi dan penjelasan dikumpulkan dengan membaca dan menelaah serta mendalami buku dan karya Michel Foucault dan Marshall G.S. Hodgson. Metode kepustakaan (Library Research) ini digunakan untuk menjawab tiga problematika di atas.
Metode induktif67 digunakan untuk memperoleh gambaran umum (generalisasi) mengenai isi dan metodologi yang dipakai Marshall G.S. Hodgson ketika menjelaskan proses dan perkembangan sejarah Islam. Buku karya Marshall G.S. Hodgson The Venture of Islam menjadi bacaan dan sumber utama. Tulisan ini menyediakan materi perkembangan dan sejarah Islam yang akan diteliti isi dan metodologinya. Karya Michel Foucault L'archéologie du savoir (1969) menjadi basis teori untuk menjelaskan, dan memberikan kritik isi dan metodologi sejarah Hodgson. Corak deskriptif dari sumber primer ini dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder, yaitu komentar-komentar berbagai penulis lain yang mengkaji pemikiran mereka.
Dengan kata lain, studi ini merupakan kajian Meta-Research.68 Metodologi ini adalah nama lain dari ‘riset atas riset’. Ia menggunakan metode riset untuk memeriksa bagaimana sebuah riset dibuat. Dari sini, diajukan alternatif-alternatif perbaikan. Kesimpulan ditarik, yang tahap demi tahapnya bisa dijelaskan sebagai berikut.
Landasan teoretis disertasi ini menggunakan pemikiran filsafat sejarah dan filsafat bahasa Michel Foucault, khususnya lewat karyanya L'archéologie du savoir
66 Salah satu perspektif dari postmodernisme adalah penolakan terhadap
‘Pencerahan’ (Enlightenment), yang ditandai dengan kebangkitan sains, rasionalitas, dan penyelidikan ilmu. Semangat Pencerahan kira-kira bisa diwakili dengan ungkapan terkenal dari Francis Bacon (1561 – 1626) Scientia Potentia Est (“Knowledge is Power’). Foucault menolak ini, sebaliknya mengungkapkan “Power is Knowledge”. Ini akan dijelaskan di BAB III.
67 Penalaran induksi adalah sebuah proses logis di mana berbagai premis ditarik benang merahnya untuk mendapatkan kesimpulan spesifik. Penalaran ini tiada lain merupakan proses generalisasi dari berbagai pendapat orang. (Evan Heit dan Caren M. Rotello, “Relations Between Inductive Reasoning and Deductive Reasoning”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 2010, Vol. 36, No. 3: 805– 812 (805) (http:/ /www.psych.umass.edu/ uploads/sites/ 48/Files/Heit%20 Rotello% 202010.pdf, diakses 13 Desember 2015)
68 John P. A. Ioannidis , dkk, “Meta-research: Evaluation and Improvement of Research Methods and Practices”, Plos Biology, October 2, 2015, http://journals.plos.org/ plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002264, diunduh 19 Agustus 2016).
26
(1969), dengan fokus pada tiga unsur: pemikiran strukturalisme-poststrukturalisme, penjelasan mengenai kekuasaan dan ideologi dalam pengetahuan, dan filsafat sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah studi terhadap isi sejarah Islam sebagaimana ditulis oleh Marshall G.S. Hodgson dengan mempelajari tiga aspek metode penulisan sejarahnya: 1. Sejarah Islam dalam Logika Struktur dan Poststruktur; 2. Sejarah Islam Hodgson, Bahasa, dan Kekuasaan; 3. Sejarah Islam Hodgson sebagai Rantai Keragaman Kerangka Berpikir
Langkah demi langkah teoretis dan konseptual di atas digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, dan menjelaskan maknanya. Langkah pertama adalah membuat survei historiografi Periode Klasik, Periode Pertengahan, dan Periode Modern lewat sistematika tiga problematika dan tiga pertanyaan minor di atas. Langkah ketiga dan keempat, adalah mengeksplorasi tiga elemen Michel Foucault dan Marshall G.S. Hodgson masing-masing berdasarkan tiga problematika di atas. Sintesa dari tiga elemen dan dimensi ini dikerjakan. Bukan hanya sintesa yang memperlihatkan adanya kesesuaian dan integrasi, tetapi juga analisa yang memperlihatkan krisis dan perpisahan di antara Foucault dan Hodgson, juga ditunjukkan.
Dengan demikian, meski pemikiran Foucault dikatakan sebagai landasan teoretis dan partner dialog intelektual, ini tidak berarti bahwa sejarah Islam dari Hodgson yang hendak dikembangkan di sini bergantung padanya. Hodgson memiliki corak-warna dan substansi pemikiran yang tersendiri. Oleh karena itu, di sana tetap ada ruang bebas di mana setiap kompleksitas pemikirannya secara leluasa menjelaskan dirinya. Di sinilah, terbuka berlangsungnya titik pisah antara Hodgson dan Foucault.
G. Sistematika Penulisan Setelah Bab I. Pendahuluan, penjelasan dan perdebatan ‘historiografi Islam
global’ menjadi fokus kajian Bab II. Alur pemikiran Bab II ini dibangun dalam pola dialektis. Di satu pihak, pembagian tiga subbab di bawah adalah mengadaptasi tiga logika dan dimensi pemikiran Michel Foucault. Di lain pihak, uraian dan isi penjelasan di dalamnya tidak begitu saja mengikuti rationale dari Foucault. Dengan demikian demikian, aliran pemikiran dalam Bab ini berlangsung dalam cara kerja tesa dan anti-tesa secara dialektis.
Bab III menjelaskan panjang lebar Arkeologi Pengetahuan dan pemikiran sejarah sebagaimana dikontemplasikan Michel Foucault. Dibuka dengan posisi pemikiran Michel Foucault dalam peta pemikiran kontemporer, khususnya di Eropa, kemudian dilanjutkan dengan tiga perspektif dari pemikiran Foucault mengenai Arkeologi Pengetahuan. Tiga perspektif itu meliputi ‘strukturalisme dan poststrukturalisme’, ‘unsur-unsur postmodernisme’, dan ‘konsep dan pemikiran sejarah’. Tiga elemen ini digunakan menjadi alat untuk menganalisa sejarah Islam global yang ditulis oleh Marshall G.S. Hodgson, sebagaimana dianalisa dalam Bab V.
Inti pemikiran sejarah Islam global Marshall G.S. Hodgson diuraikan dalam Bab IV. Sebelum berbicara substansi, genealogi pemikiran sejarah Marshall G.S. Hodgson ditelusuri. Tiga topik utama metodologi penulisan sejarahnya digali: 1.
27
Sejarah Islam dalam Logika Struktur dan Poststruktur; 2. Sejarah Islam Hodgson, Bahasa, dan Kekuasaan; 3. Sejarah Islam Hodgson sebagai Rantai Keragaman Kerangka Berpikir. Tiga topik ini merupakan pararel dari tiga perspektif Arkeologi Pengetahuan yang dipaparkan dalam Bab III. Pararelitas ini yang memungkinkan proses sintesis dalam Bab V.
Bab V diberi judul ‘Keragaman dalam Historiografi Islam’ yang merupakan sintesa dan analisa disertasi ini. Judul ini juga sudah memberikan isyarat kesimpulan besar yang diungkapkan dalam abstrak. Dengan kata lain, pertanyaan yang diformulasikan dalam ‘Perumusan Masalah’ hendak direspon dan dijawab dalam Bab ini. Dan tiga pertanyaan minor dalam ‘Perumusan Masalah’ masing-masing dijawab dalam uraian 1. Keanekaragaman Struktur Pemikiran Dalam Sejarah Islam; 2. Kekuasaan dan Ideologi yang Menyebar Lewat Pengetahuan; 3. Keanekaragaman Episteme dalam Sejarah Islam. Dalam Bab V ini uraian ‘Hodgson dan Foucault: Titik Kritis dan Titik Pisah’ menjadi satu uraian kritis terhadap terhadap historiografi Islam ini.
Bab VI merupakan kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan dalam ‘Perumusan Masalah’. Kesimpulan merupakan pernyataan padat dan ringkas dari apa yang sudah dijelaskan panjang lebar dalam Bab V. Tantangan Baru dan Rekomendasi untuk melengkapi riset ini diungkapkan dalam Bab ini.